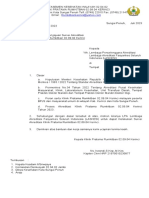Dilema Etik
Diunggah oleh
Ikaa ParamithaDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Dilema Etik
Diunggah oleh
Ikaa ParamithaHak Cipta:
Format Tersedia
Pendahuluan Dalam pembuatan keputusan klinik pada beragam kasus konkrit, seringkali mahasiswa kedokteran atau bahkan dokter
mengalami kesulitan. Apalagi bila kasus yang dihadapinya dalam keadaan dilematis, atau (akan tetap) hidup atau (sebentar lagi) mati. Selain mereka harus berkonsentrasi pada kegawatan pasiennya, mereka harus menenggang ancaman etikolegal yang akan merusak reputasi profesinya. Apalagi dalam situasi akhir-akhir ini yang mengarah ke kedokteran-demipembelaan (defensive medicine) akibat ramainya tuduhan malpraktek semena-mena. Reputasi yang dibina puluhan tahun dapat hancur dalam semenit. Keputusan klinik seperti di atas memang dibangun atas dua pilar utama, yakni : a) keputusan medik atas permasalahan medik pasien dan b) keputusan etis atas isu etis pasien. Yang seharihari ada di kepala (mindset atau paradigma) dokter adalah keputusan medik yang nyata dalam ranah indikasi medik dari sistematika Jonsen & Siegler. Keadaan makin rumit ketika kita mempertimbangkan sistematika etika praktis bagi klinisi (Jonsen & Siegler) yakni 3 komponen lain : pilihan pasien, kualitas hidup dan fitur kontekstual begitu didominasi oleh komponen non medis, yakni struktur budaya masyarakat. Sedangkan struktur masyarakat Indonesia sendiri adalah plural. Mereka terdiri atas beragam suku, adat istiadat, dan latar belakang sosio-budaya dan geografi yang tidak sama. Hal inilah yang membuat pada dokter sejak masa di bangku kuliah kurang tertarik dengan hal-ihwal sosio-antropologi budaya.[1]Salah satunya adalah ketidakpastiannya. Padahal ketika di klinik, mereka terkaget-kaget ketika menghadapi kenyataan bahwa seni (teknik) pengobatan pasien adalah juga sama-sama sebuah ketidak-pastian. Yang agak pasti dalam hal ini adalah keputusan medik karena dibangun oleh ilmu kedokteran yang bermodel biomedik[2]. Pertemuan Nasional III Bioetika & Humaniora Kesehatan Indonesia, FKUI, Jakarta, 30 Nopember 2 Desember 2004. Sedangkan sebaliknya pertimbangan keputusan etis bukan berbasis biomedik, namun lebih tepat menggunakan paradigma infomedik[3]. Isu etik. Isu etik bukanlah isu medik. Ini merupakan titik pijak awal pembahasan permasalahan etika klinis. Kegagalan menemukan isu etik dalam kasus konkrit di klinik seringkali akibat dangkalnya pemahaman tentang etika kedokteran dalam metode deskriptif yang diajarkan sebelumnya. Pengetahuan etika dalam metode deskriptif (apalagi dalam bentuk kuliah searah) kurang menerampilkan logika berpikir dalam menguak aspek etis pasien yang dihadapinya, sehingga seringkali menyebabkan konflik berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan data bahwa klinisi 71% sering terbantu untuk menemukan isu etik relevan oleh konsultan etik atau fatwa komite etik rumah sakit sebagai dasar pengelolaan pasiennya atau untuk metode belajar etika kedokteran.[4] Padahal dengan latihan dialog berbasis pendekatan sistematik pemikiran klinis etis hal itu dapat segera selesai. Isu etik dalam kesejarahannya bersumber dari kaidah dasar moral (disingkat KDM atau moral principle/principle-based ethics atau ethical guidelines) yang merupakan acuan tertinggi moralitas manusia atau acuan generalisasi etik yang menuntun suatu tindakan kemanusiaan.[5] Bertolak dari Childress & Beauchamp yang memaparkan adanya 4 KDM yakni beneficence, nonmaleficence, justice dan autonomy dalam buku sucinya The Principles of Biomedical Ethics (1994). Ke 4 KDM tersebut kemudian ditinjau melalui etika, secara deduktif, apakah masih merupakan maxim (kaidah dasar) yang berlaku normatif ketika dokter menghadapi kasus konkrit di klinik. Hal ini amat mempengaruhi cara pemikiran kritis logis dari etika normatif, salah satu
cabang etika. Beberapa cara meneliti keberlakuan normatif masing-masing KDM tersebut pada galibnya merupakan upaya meneliti pembenaran moral (moral justification) tuntunan tindakan tertentu pada kasus etis konkrit tertentu sehingga tindakan klinisi dipandang sebagai tindakan etis, walaupun dalam suasana ketidak-pastian medik dan penuh wacana moral yang mewarnai praktek medik. KDM memberikan bahasa moral dan lingkup kerja analisis etik ditengah pluralitas manusia seperti perbedaan agama, moral, politik bahkan perspektif filosofis. Inilah kekuatan 4 KDM (principle-based ethics) dalam memberi pegangan pembenaran moral dokter/tenaga kesehatan yang bergerak dalam lapangan biomedik[6]. Tindakan etis disini begitu kuatnya berakar sehingga dalam pandangan etikolegal, tindakan tersebut merupakan lingkup atau rangkaian pola tindakan preskriptif hukum. Tindakan etis sekaligus dasar dari tindakan hukum inilah pada kasus klinis akan mewarnai pilihan konkrit kebebasan profesi yang dapat dibenarkan secara moral dan doktrin hukum dalam bentuk kewajiban etis (moral duty), sehingga dengan sendirinya sulit atau tidak mungkin dokter/rumah sakit dijatuhi sanksi, baik etik, disiplin maupun hukum. Pada kasus klinis konkrit, isu etis seringkali sudah nampak jelas pada saat mahasiswa memahami sekilas namun cukup sistematik (proses insight kasus) karena adanya satu KDM yang dominan atau khas. Insight diperoleh dari pilihan sambil lalu : mana diantara 1 KDM yang paling menonjol tanpa analisis mendalam atau repot-repot yang mewarnai isu etis kasus tersebut.[7] Misalnya adakah isu etis atau masalah otonomi pasien, yang bermanifestasi pada kasus seperti : perlunya informed consent, dipertahankannya rahasia pasien, keputusan terapi yang dibuat oleh remaja yang sakit dll. Dalam konteks kasus tersebut, jelas bahwa isu etisnya diturunkan secara sederhana dari keberlakuan normatif KDM yang paling relevan (hanya satusatunya) yakni : otonomi. Keberlakuan KDM otonomi sebagai isu etis disini adalah absolut atau sebagai kebenaran yang tetap (fixed truth) yang membingkai ethical guidelines[8] pada kasus tersebut. Ketegaran Moral. Pembenaran moral yang diaplikasikan secara deduksi[9] berurutan ke bawah ke yang khusus yakni ke arah kasus konkrit dari 1 KDM sebagaimana asalnya dari yang umum/teoritis akan menggunakan suatu cara berpikir lurus alias logis.[10] Bila pendeduksian itu sendiri merupakan suatu keharusan (absolut, artinya tanpa ragu lagi bahwa tidak ada yang relatif karena konteksnya dan kasusnya begitu khas untuk hanya 1 KDM) yang mengikat KDM tersebut (moral bindingness) maka dari kasus sederhana tadi muncul warna isu etis khas yang mutlak harus dilaksanakan. Disinilah KDM tersebut harus dideduksi hingga ke keputusan klinis-etis karena memiliki moral stringency atau ketegaran moral.[11] Akibat kekakuan rumusan ini, deduksi akan mengawetkan logika berpikir karena metode ini tidak serabutan atau asal-asalan, sepanjang dilakukan secara koheren. Tindakan serabutan yang tidak konsisten dan koheren dengan pembenaran moral akan dengan segera ketahuan. Semisal isu etisnya adalah otonomi. Disini tuntunan tindakan autonomy tersebut mutlak dan mengikat. Artinya dalam kasus konkrit tersebut, secara etis dokter seharusnya akan lebih menghargai keputusan yang dibuat oleh pasien. Bila ditengah tatanan perjalanan klinis tiba-tiba dokterlah tanpa konteks atau dasar situasi tertentu yang justru membuat keputusan sepihak tanpa setahu atau seijin pasien (artinya ia menggunakan KDM beneficence yang paternalistik), hal ini akan serta merta dikenali dari deduksi pembenaran moralnya. Yakni disini bertentangan dengan KDM autonomy, sehingga mudah sekali dicap bahwa tindakan dokter tersebut adalah tidak etis (tidak bisa dibenarkan secara moral).
Namun tak jarang, pada satu kasus klinis terdapat saling pengaruh mempengaruhi lebih dari 1 KDM. Tabrakan antar KDM dalam metode principle-based ethics di satu sisi akan membingungkan para mahasiswa dalam tatanan klinik[12], mana KDM yang harus dimenangkan. Namun di sisi lain bila ada kelompok mahasiswa lain yang menyanggah dengan KDM lain, justru akan memperkaya kemampuan kritis logis karena atas dasar KDM beneficence misalnya, mahasiswa akan serta merta mampu berargumen logis terhadap mahasiswa atau pihak lain (termasuk fasilitator atau nara sumber senior sekalipun) yang mendasarkan diri pada argumen KDM autonomy. Relevannya prima facie. Dalam proses identifikasi KDM mana yang paling relevan atas kasus konkrit tertentu, tabrakan antar KDM tadi demikian kentalnya sehingga tetap sulit diyakinkan mana KDM yang paling dominan. Kasus yang memuat tabrakan antar KDM ini hingga ke tingkat analisis mendalam, yang (tinggal) memunculkan 2 dari 4 KDM yang konteksnya secara nalar terkuat (artinya 2 KDM tersebut memiliki ketegaran moral yang kuat, sedangkan 2 KDM lainnya tereliminasi sementara), inilah yang memunculkan suatu dilema etik. Pada kasus dilema atau simalakama etik ini bila dilakukan suatu upaya diskusi yang kontinu dan makin mendalam, akan makin mengasyikkan karena mahasiswa atau dokter akan berupaya mencari tambahan data baru yang berkaitan dengan 3 konteks kasusnya (misalnya dengan menggali lagi 3 komponen non-medis Jonsen & Siegler tersebut di atas).[13] Maka tak jarang mereka akan lebih teliti dan ingin tahu lagi untuk melakukan anamnesis baru (reanamnesis) pasiennya atau keluarganya, sambil menunggu terkumpulnya data medik baru (indikasi medik baru/yang lebih tepat, bila ada). Alhasil siapa yang mampu mengumpulkan basis bukti data baru terbanyak dan relevan (kontekstual), akan lebih berpeluang memilih satu di antara 2 KDM yang saling bersitegang tersebut. Dialog antar 2 kubu yang saling mempertahankan KDM paling absah disini merupakan proses terpenting permusyawaratan etis yang kelak merupakan prosedur amat penting dalam keputusan klinis. Dengan begitu, jelas sekali disini bahwa dialog antar klinisi bukan hanya berorientasi pada hasil upaya mediknya belaka, tetapi lebih pada proses. Hal ini akan memberi perintah tanpa sadar bagi mahasiswa/dokter untuk mengobservasi sisi non medik (dalam hal ini jadi sisi etis) pasiennya setiap saat ia melakukan asesmen klinis. Pemilihan 1 KDM ter-absah sesuai konteksnya berdasarkan data atau situasi konkrit terabsah inilah yang disebut pemilihan berdasarkan asas prima facie. Dua KDM yang dilematis tadi tetap berlaku, sampai yang paling mutakhir ada novum (bukti/konteks absah terbaru) yang menggeser KDM tersisih, dengan memunculkan KDM yang lebih unggul. Jadi disini, prima facie mirip seperti troef card pada permainan kartu bridge, dimana kartu bernominal kecil, sepanjang telah ditetapkan sebagai troef, senantiasa dimenangkan dibandingkan dengan kartu As warna lain yang bukan troef pada permainan saat itu. Dengan prinsip prima facie, dialog klinisi (yang diperankan mahasiswa) tentang dimensi etik pasiennya lebih mengemuka untuk memecahkan masalah etik klinis ditengah berkecamuknya perspektif moral yang saling bertentangan satu sama lain atau minimal tidak sejalan.[14] Prinsip prima facie secara langsung atau tidak langsung akan merangsang mahasiswa untuk belajar aktif (senantiasa mencari konteks terbaru yang terabsah) dan komprehensif (tidak melulu ilmu kedokteran) khususnya dalam mempermahir penerapan kedokteran sebagai seni kelak setelah ia menghadapi pasien sesungguhnya. Ciri-ciri KDM yang berbasis prima facie. Dalam penanganan pasien di klinik, selain indikasi medik yang memang berpengaruh pada sisi awalnya, namun pengelolaan pasien akan ditentukan pula oleh seni yang berbasis ketegaran
moral KDM terabsah pada kasus konkrit sederhana. Bila pada kasus konkrit yang kompleks yang mengarah ke dilema etik, maka diterapkan prinsip prima facie di antara 4 KDM dalam menerapkan penanganan etikanya. Prinsip prima facie akan mempersyaratkan secara sederhana, adanya konteks baru absah yang ada pada diri pasien atau keluarganya ketika tengah dalam proses perawatan medik (proses bersamaan dengan adanya clinical judgment, yang berasal dari kewenangan clinical privilege yang dipunyai dokter). Oleh karena itu diperlukan ciri-ciri KDM yang demikian khasnya sehingga setiap kali bila itu ditemukan pada diri pasien/keluarganya, secara prima facie hal itu akan menjadi tuntunan umum yang berlaku secara etis. Dari ciri khas tersebut, ketika konteksnya tiba, KDM yang lama ditinggalkan untuk diganti dengan KDM baru yang lebih absah. Untuk kepentingan pendidikan etika, secara sederhana uraian prima facie KDM tersebut adalah nampak pada tabel berikut : Dalam konteks beneficence, pada tabel di atas prinsip prima facienya adalah sesuatu yang (berubah menjadi atau dalam keadaan) g umum. Artinya ketika kondisi pasien merupakan kondisi yang wajar dan berlaku pada banyak pasien lainnya, sehingga dokter akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan pasien. Juga dalam hal ini dokter telah melakukan kalkulasi dimana kebaikan yang akan dialami pasiennya akan lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya. Dalam konteks non maleficence, prinsip prima-facienya adalah ketika pasien (berubah menjadi atau dalam keadaan) gawat darurat dimana diperlukan suatu intervensi medik dalam rangka penyelamatan nyawanya. Dapat pula dalam konteks ketika menghadapi pasien yang rentan, mudah dimarjinalisasikan dan berasal dari kelompok anak-anak atau orang uzur ataupun juga kelompok perempuan (dalam konteks isu jender). Dalam konteks autonomy, nampak prima facie disini muncul (berubah menjadi atau dalam keadaan) pada sosok pasien yang berpendidikan, pencari nafkah, dewasa dan berkepribadian matang. Sementara justice nampak prima facienya pada (berubah menjadi atau dalam keadaan) konteks membahas hak orang lain se lain diri pasien itu sendiri. Hak orang lain ini khususnya mereka yang sama atau setara dalam mengalami gangguan kesehatan. di luar diri pasien, serta membahas hakhak sosial masyarakat atau komunitas sekitar pasien. Kesimpulan. 1. Metode pembelajaran etika kedokteran menggunakan Kaidah Dasar Moral (Principlebased ethics) merupakan metode tangguh dalam mengusung konsep etika normatif karena berperan memunculkan isu etik pasien, sebagai pendamping isu medik dalam penanganan klinik. 2. Pemunculan isu etik pasien secara deduktif logik dari Kaidah Dasar Moral akan memberi dampak cara berpikir kritis rasional bagi mahasiswa karena mereka terbiasa melakukan analisis pembenaran moral sekaligus ketegaran moral. 3. Adanya 4 KDM yang masing-masing saling berebut untuk tampil sebagai acuan dasar isu etik melalui prinsip prima facienya masing-masing sesuai dengan ciri-ciri konteks berubah menjadi atau dalam keadaan) pasien, entah beneficence, entah non maleficence, entah autonomy ataupun justice sebagaimana kasus konkrit di klinik, diharapkan akan lebih menggairahkan cara menalar mahasiswa. 4. Prinsip prima facie praktis diharapkan akan menjadi model berpikir kritis yang dapat diterapkan pada analisis etik pelbagai kasus konkrit lainnya, baik sebagai subyek
penelitian, pasien berdilema etik dalam perawatan yang memerlukan pemecahan etis ataupun penelusuran pelanggaran etik profesi yang mungkin dilakukan oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan.
Kepustakaan
Penulis, pendidikan terakhir doktor filsafat, adalah Sekretaris MKEK Pusat IDI, Sekjen Jaringan Bioetika & Humaniora Kesehatan Indonesia, anggota Komisi Bioetika Nasional, dan konsultan etikolegal beberapa rumah sakit di Jakarta.
[1] Sedikit banyak hal ini akibat stereotip mahasiswa FK yang hampir semuanya berasal dari SMU jurusan IPA yang begitu bangganya atas jurusannya, cenderung memandang sebelah mata IPS, apalagi jurusan Budaya. [2] Agus Purwadianto, Perkosaan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.Landasan Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum. Disertasi. Fak. Ilmu Budaya UI, Jakarta, 2003, hal. 245. Paradigma ini akibat konsep dualisme tubuh-jiwa Cartesian, sehingga manusia dianggap hanya tubuhnya saja ibarat mesin biologis, tanpa jiwa. Tubuh sakit manusia, sebagai organisme biologis multikompleks dalam rangka menghilangkan penyebab penyakit tadi direduksi menjadi unsur faali, seluler, molekular untuk menemukan agen atau faktor penyebab yang juga fisik. Hal ini sejalan dengan status primer pengetahuan yang bertolak dari benda (matter) dan dunia material. Dokter selaku subyek untuk menyembuhkan obyek tubuh sakit pasiennya melalui ilmu kedokteran modern kemudian melakukan intervensi pengobatan secara mekanistik reduksionistik, dengan tindakan kimiawi, elektris, atau pembedahan dengan mengupayakan tindakan netralisasi terhadap agen patogen penyebab sakit, suplementasi terhadap defisiensi faktor atau pengurangan terhadap kelebihan faktor intrinsik penyebab penyakit tersebut, sehingga tercapai kembali kurva atau norma normal dari deviasi terukur parameter biologis tubuh pasien pada proses perjalanan penyakitnya. Lihat pula Laurence Foss & Kenneth Rothenberg. The Second Medical Revolution., Shaftesbury, Boston, 1988, hal 8. [3] Agus Purwadianto, ibid. hal. 283. Sebagai mahluk swa-atur kompleks, manusia mampu mengolah pesan-pesan eksternal yang berasal dari ragam jenjang organisasi dalam ranah fisik, psikologis dan sosial serta lingkungan dengan landasan bahasa ilmu mekanika kuantum dan termodinamika nirpulih serta teori informasi yang bertumpu kepada hukum-hukum infomedik. Disini didalilkan bahwa penyakit manusia dapat diakibatkan oleh hasil interaksi program yang melibatkan informasi dengan faal tubuh (pesan bio-aktif); saling pengaruh sadar atau tidak sadar suatu determinan-sebab-kodeterminan-prevalensi-sebab-hasil; antara fisik dan psikis/faktor sosial (pesan psiko-aktif/sosio-aktif); serta tekanan selektif alam (lingkup kesatuan kawasan tubuh, biosfer) tekanan selektif budaya (lingkup kesatuan kawasan jiwa, noosphere) dalam bentuk pesan tekno-aktif. Lihat pula Laurence Foss, ibid, hal. hal. 298 301
[4] LaPuma J, Stocking CB, Silverstein MD et al. An Ethics Consultation Service in a Teaching Hospital. JAMA 1988; 206 : 808 811, yang dikutip Bernard Lo.Resolving Ethical Dilemmas. A Guide for Clinicians. Williams & Wilkins. Baltimore, USA, 1995, hal. 155. [5] Bernard Lo. Resolving Ethical Dilemmas. A Guide for Clinicians. Williams & Wilkins. Baltimore, USA, 1995, hal. 19 [6] Gillon R. Medical Ethics : Four principles plus attention to scope. British Med. Journal No. 309, 1994, hal. 184-188. [7] Bila dalam kasus berbentuk teks, insight nampak pada kelompokan kasus, judul kasus, atau ekspresi ungkapan yang menjadi simbol isu etis dalam bentuk kalimat langsung atau kalimat yang diberi tanda tekanan khusus. Dalam bentuk tuturan/lisan, insight kasus tersebut nampak pada saat dosen atau tayangan visual secara ekspresif menuturkannya atau mewarnai keseluruhan alur cerita atau yang senantiasa diulang-ulang pengungkapannya (berdasarkan pola sentral berpikir penutur kisah tsb). Bila mahasiswa masih bingung, insight dilanjutkan dengan proses identifikasi KDM mana paling relevan dengan metode asal sebut/itung kancing (rule of thumb) diantara 4 KDM tersebut dalam teks atau tuturan kasus tsb. Yang penting tujuan insight adalah mahasiswa mampu meneliti isu etik, bukan tergelincir atau terjebak ke isu medik belaka. [8] Bernard Lo, loc.cit. hal. 20. [9] James F. Childress. The Normative Principles of Medical Ethics, dalam Robert M. Veatch (ed). Medical Ethics (2nd ed). Jones and Bartlett Publishers Massachusetts. 1997. hal 29 39. Aplikasi adalah salah satu model untuk pembenaran moral, dalam hal ini menggunakan metode deduksi logis. [10] Selain aplikasi, menurut Henry Richardson (1990) hubungan KDM sebagai asas umum etika dengan keputusan klinis-etis sebagai pendapat/putusan partikular etik dapat dilakukan dengan dua model lain yakni : a)Ballancing/Penyeimbangan berupa melakukan petimbangan intuitif mana azas yang saling bertentangan dalam kasus tersebut yang berpotensi menjadi dilemma etik) dan b) Spesifikasi yakni merinci dari asas/KDM ke aturan/rule dalam hal makna, kisaran dan ruang lingkupnya. [11] Dalam kemutlakan pemberlakuan 1 KDM atas 1 kasus konkrit, dikenal istilah ketegaran moral (moral stringency). Dalam 1 kasus sederhana, bukan kasus kompleks, ketegaran moral merupakan satu-satunya tolok ukur etis tidaknya tindakan seorang dokter. Untuk metode pembelajaran pengenalan isu etik, khususnya pada mahasiswa tahun pertama, pemberian penekanan pada 1 KDM yang berciri-ciri khas atau unik yang membedakannya dari KDM lainnya amatlah diperlukan, sehingga secara cepat mereka mampu mengungkapkan isu etik yang berbeda dari isu medik. Moral stringency atas beberapa kasus yang berciri kemutlakan berlakunya 1 KDM, secara satu persatu pada satu session amat diperlukan.
[12] Tata-letak klinik disini adalah situasi yang dijadikan latar belakang pembelajaran adalah suasana klinik (dimana ada hubungan dokter pasien di sarana kesehatan tertentu). Tata-letak klinik dapat pula dan justru harus dilakukan, pada mahasiswa tahun pertama akademik, tanpa harus menunggu tingkat klinik (early clinical exposure method). [13] Hal ini akan sejalan dengan metode PBL (problem based learning) yang kini popular sebagai roh pendidikan kedokteran di dunia. Artinya, pendalaman prinsip prima facie pada principle based ethics, sama seperti metode pembelajaran lainnya apapun, tidak akan berarti apa-apa pada mahasiswa yang pasif dan kurang bernalar. [14] Adanya pemilihan isu etik ini akan sejalan dengan proses open inquiry(pada metode self directed learning) yang amat bagus diterapkan sejak dini pada mahasiswa tingkat premedik atau preklinik. Isu open inquiry ini sama relevannya ketika metode principle-based ethics ini diberlakukan pada mahasiswa tingkat klinik, yakni memperkuat kemampuan problem solvingmereka. Bila pelaksanaan pembelajaran etika kedokteran ini terus menyambung dalam bentuk kontinuum, maka diharapkan mereka akan mahir menyelesaikan kasus etika kedokteran.
Anda mungkin juga menyukai
- Eritroblastosis FetalisDokumen20 halamanEritroblastosis Fetalisattamd100% (1)
- Makalah SipDokumen12 halamanMakalah SipAlie Anwar SutisnaBelum ada peringkat
- PENGGUNAAn ZAT TAMBAHAN MAKANAN YANG AMANDokumen28 halamanPENGGUNAAn ZAT TAMBAHAN MAKANAN YANG AMANdianBelum ada peringkat
- Jadwal Imunisasi DewasaDokumen5 halamanJadwal Imunisasi DewasaLili Uisa RahmasariBelum ada peringkat
- PENELITIAN KOMUNITASDokumen160 halamanPENELITIAN KOMUNITASYusufBelum ada peringkat
- Studi Kualitas Layanan Rumah Sakit Yanti ErawatiDokumen33 halamanStudi Kualitas Layanan Rumah Sakit Yanti ErawatiYanti ErawatiBelum ada peringkat
- Referat Telogen EffluviumDokumen15 halamanReferat Telogen EffluviumRani Dwi HapsariBelum ada peringkat
- MakalahDokumen32 halamanMakalahlenajustifia kilikilyBelum ada peringkat
- Surat Permohonan Survei-1Dokumen1 halamanSurat Permohonan Survei-1Lilis SetyawatiBelum ada peringkat
- SK. Pasien DGN Resiko Tinggi (PAP 3 Dan 3.3)Dokumen9 halamanSK. Pasien DGN Resiko Tinggi (PAP 3 Dan 3.3)nesyBelum ada peringkat
- ReferatDokumen35 halamanReferatkarinagiovanniBelum ada peringkat
- RSUDDokumen6 halamanRSUDyudi albertoBelum ada peringkat
- Surat Pengajuan SurveyDokumen1 halamanSurat Pengajuan SurveyAhmad RandiBelum ada peringkat
- Kewenangan KlinikDokumen4 halamanKewenangan KlinikSetiawati PinemBelum ada peringkat
- 5.4.1 SK Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Mks 1Dokumen13 halaman5.4.1 SK Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Mks 1Syifa Fauzia.Belum ada peringkat
- RKK Apoteker 2Dokumen2 halamanRKK Apoteker 2cendraBelum ada peringkat
- RincianKlinisDokumen2 halamanRincianKlinisNuky ArdiniBelum ada peringkat
- Laporan PBL Skenario 6 Blok 2Dokumen20 halamanLaporan PBL Skenario 6 Blok 2Mohammad TaufikBelum ada peringkat
- Proposal PenelitianDokumen22 halamanProposal PenelitianFarrel JuniorBelum ada peringkat
- SOP Kontrol Infeksi PandegaDokumen13 halamanSOP Kontrol Infeksi Pandegaaas.amdkepBelum ada peringkat
- Ebm - Therapy FixDokumen8 halamanEbm - Therapy FixJovankaBelum ada peringkat
- Surat RujukanDokumen8 halamanSurat Rujukanannisa citra susantiBelum ada peringkat
- Five-star doctors rolesDokumen3 halamanFive-star doctors rolesRatih Puspa WardaniBelum ada peringkat
- Lembar Jawaban UAS Etika Bisnis Dhimas-DikonversiDokumen6 halamanLembar Jawaban UAS Etika Bisnis Dhimas-Dikonversisyahreza andika gunawanBelum ada peringkat
- Dokter Keluarga Adalah Dokter Yang Mengutamakan Penyediaan Pelayanan Komprehensif Bagi Semua Orang Yang Mencari Pelayanan KedokteranDokumen2 halamanDokter Keluarga Adalah Dokter Yang Mengutamakan Penyediaan Pelayanan Komprehensif Bagi Semua Orang Yang Mencari Pelayanan KedokteranCanda ArdityaBelum ada peringkat
- Kedokteran KomunitasDokumen32 halamanKedokteran KomunitasAyutrisna AnnisaBelum ada peringkat
- Pemerintah Kabupaten Parigi MoutongDokumen10 halamanPemerintah Kabupaten Parigi MoutongAyhu PadmiBelum ada peringkat
- Aspek Bioetika Dalam Penanganan Kasus Penyakit Menular Seksual Pada Remaja Di YogyakartaDokumen9 halamanAspek Bioetika Dalam Penanganan Kasus Penyakit Menular Seksual Pada Remaja Di YogyakartaAlfani FajarBelum ada peringkat
- HIPERTENSI DALAM KEHAMILANDokumen28 halamanHIPERTENSI DALAM KEHAMILANEga WirdaBelum ada peringkat
- Uraian Kompetensi Cleaning ServisDokumen7 halamanUraian Kompetensi Cleaning ServisAlma ghaisanyBelum ada peringkat
- Teknik QA: Audit Kualitas, Analisis Proses, Alat Manajemen & Kontrol MutuDokumen1 halamanTeknik QA: Audit Kualitas, Analisis Proses, Alat Manajemen & Kontrol MutuVey ChiBelum ada peringkat
- Teori Hukum-Teori Hukum EkonomiDokumen2 halamanTeori Hukum-Teori Hukum Ekonomiatrinadecy50% (2)
- Mata Kuliah KewirausahaanDokumen1 halamanMata Kuliah KewirausahaanUtari Septiana DewiBelum ada peringkat
- Pedoman Beban Kerja Dosen 2 PDFDokumen11 halamanPedoman Beban Kerja Dosen 2 PDFlilisBelum ada peringkat
- SPO PELEPASAN INFORMASI MEDIS RevDokumen2 halamanSPO PELEPASAN INFORMASI MEDIS RevRSKK100% (1)
- Lembar persetujuan medis untuk pasien RSIA Kumala SiwiDokumen2 halamanLembar persetujuan medis untuk pasien RSIA Kumala SiwiAyoe KhumairohBelum ada peringkat
- Pedoman Pendidikan Pasien Dan KeluargaDokumen4 halamanPedoman Pendidikan Pasien Dan KeluargaJuniarsih JamilBelum ada peringkat
- 7.1.1 SK PendaftaranDokumen3 halaman7.1.1 SK PendaftaranBintang BaskoroBelum ada peringkat
- Quality AssuranceDokumen18 halamanQuality AssurancehimiBelum ada peringkat
- SURVEYDokumen3 halamanSURVEYIhsan KamalBelum ada peringkat
- RS SAYANG IBU DAN BAYIDokumen5 halamanRS SAYANG IBU DAN BAYIDewina Dyani RosariBelum ada peringkat
- Contoh Status Kulit UjianDokumen3 halamanContoh Status Kulit Ujianayuafrilyasari0% (1)
- SOP ABSESDokumen57 halamanSOP ABSESHelmi ZuryaniBelum ada peringkat
- SK Tim Mutu Dan Layanan Klinis Keselamatan PasienDokumen7 halamanSK Tim Mutu Dan Layanan Klinis Keselamatan PasienLin Lin Shoffwatun NidaBelum ada peringkat
- Pedoman Organisasi Tata Laksana Kerja MKEKDokumen40 halamanPedoman Organisasi Tata Laksana Kerja MKEKdrghempik100% (2)
- Kopi KafeinDokumen24 halamanKopi KafeinCeeikeyBelum ada peringkat
- Jadwal Imunisasi Dewasa 2017Dokumen6 halamanJadwal Imunisasi Dewasa 2017Muhammad NurBelum ada peringkat
- SOPDokumen123 halamanSOPdelta mutiaraBelum ada peringkat
- FKU5-Robby Ashar-Anestesiologi Dan Terapi IntensifDokumen3 halamanFKU5-Robby Ashar-Anestesiologi Dan Terapi IntensifRobby AsharBelum ada peringkat
- Komite Dokter Internsip Indonesia Surat Tanda Selesai InternsipDokumen1 halamanKomite Dokter Internsip Indonesia Surat Tanda Selesai InternsipkinausmanBelum ada peringkat
- SK Hak Dan Kewajiban PasienDokumen5 halamanSK Hak Dan Kewajiban PasiensinungwjBelum ada peringkat
- Pengumuman - Rekruitment PARU SURABAYA (1) - 1Dokumen5 halamanPengumuman - Rekruitment PARU SURABAYA (1) - 1Taufik HidayatBelum ada peringkat
- Kurva Pertumbuhan Anak Berkebutuhan KhususDokumen43 halamanKurva Pertumbuhan Anak Berkebutuhan KhususChairidaichaa100% (2)
- Struktur Organisasi Klinik Pratama Mitra Sehat FixDokumen1 halamanStruktur Organisasi Klinik Pratama Mitra Sehat FixkartikaheriyonoBelum ada peringkat
- Pedoman Pelayanan IRJDokumen19 halamanPedoman Pelayanan IRJSholeh AmanahBelum ada peringkat
- Kewenangan Klinis Dr. SPPDDokumen6 halamanKewenangan Klinis Dr. SPPDTwin BamasaqBelum ada peringkat
- RS Ibnu SinaDokumen5 halamanRS Ibnu SinaJaka KurniawanBelum ada peringkat
- MorbiditasDokumen13 halamanMorbiditasFani Rahmat Fauzi BluesshelterBelum ada peringkat
- KONTEKSTUALISASI PRINSIPDokumen7 halamanKONTEKSTUALISASI PRINSIPBramantyo NugrahaBelum ada peringkat
- Prima FacieDokumen17 halamanPrima Facieanjozz100% (1)
- PRIMAFACIEDokumen13 halamanPRIMAFACIEMuhammad Taufiqul HadiBelum ada peringkat
- Asesmen Geriatri - AsliDokumen7 halamanAsesmen Geriatri - AsliIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Metabolisme HemeDokumen8 halamanMetabolisme HemeIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Keuntungan dan Kerugian LAIDokumen2 halamanKeuntungan dan Kerugian LAIIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Latar Belakang EpidDokumen3 halamanLatar Belakang EpidIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Matriks Medikolegal FixDokumen5 halamanMatriks Medikolegal FixAci Dwi LestariBelum ada peringkat
- Pengaruh Pemberian Asi Ekslusif Terhadap Status Gizi Pada Bayi Usia 6 Bulan Di Kecamatan Mampang Prapatan Jacko New Dari Jacko PDFDokumen57 halamanPengaruh Pemberian Asi Ekslusif Terhadap Status Gizi Pada Bayi Usia 6 Bulan Di Kecamatan Mampang Prapatan Jacko New Dari Jacko PDFryan_northemBelum ada peringkat
- DBD Syok FaktorDokumen4 halamanDBD Syok FaktorIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- PPK UsilaDokumen5 halamanPPK UsilaIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- PPK UsilaDokumen5 halamanPPK UsilaIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Mte DemensiaDokumen24 halamanMte DemensiaIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal GadarDokumen2 halamanAnalisis Jurnal GadarIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- DM Tipe 2Dokumen8 halamanDM Tipe 2Ikaa ParamithaBelum ada peringkat
- Mte DemensiaDokumen24 halamanMte DemensiaIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal GadarDokumen2 halamanAnalisis Jurnal GadarIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Dilema EtikDokumen7 halamanDilema EtikIkaa Paramitha0% (1)
- Pengertian Anak AngkatDokumen24 halamanPengertian Anak AngkatVincentsius PuteraBelum ada peringkat
- Tugas PPK Jiwa.Dokumen19 halamanTugas PPK Jiwa.Ikaa ParamithaBelum ada peringkat
- Mte DemensiaDokumen24 halamanMte DemensiaIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- ChecklistRJP FixDokumen1 halamanChecklistRJP FixIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok MedikolegalDokumen4 halamanTugas Kelompok MedikolegalIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Cedera DadaDokumen18 halamanCedera DadaMirsal PicassoBelum ada peringkat
- DM Tipe 2Dokumen8 halamanDM Tipe 2Ikaa ParamithaBelum ada peringkat
- Fistula AniDokumen5 halamanFistula AniIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Tuba Ovrii AbsesDokumen5 halamanTuba Ovrii AbsesIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Trauma ThoraxDokumen21 halamanTrauma Thorax譚惠玲100% (3)
- DiareeeDokumen5 halamanDiareeeIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal GadarDokumen2 halamanAnalisis Jurnal GadarIkaa ParamithaBelum ada peringkat
- PPK GadarDokumen8 halamanPPK GadarIkaa ParamithaBelum ada peringkat