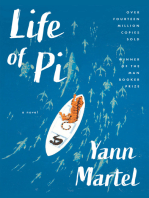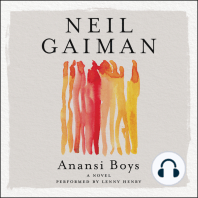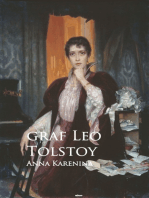Sekolah Tidak Membuat Kaya
Diunggah oleh
Ryeska FajarHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Sekolah Tidak Membuat Kaya
Diunggah oleh
Ryeska FajarHak Cipta:
Format Tersedia
Sekolah Ternyata (Tidak) Selalu Membuat Kaya Suatu siang beberapa tahun yang lalu.
Matahari bersinar terik sekali, seolah-olah sebagian besar air yang tersimpan di dalam kulitku menguap. Bahkan tidak sempat menjadi sebutir keringatpun. Uap air tubuhku melayang-layang tinggi ke langit dan membentuk awan yang kelak akan jatuh di bagian bumi entah yang mana. Begitupun aku sekarang. Berjalanjalan mencari rezeki ke jalan-jalan pinggiran Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelak akan berhenti entah dimana. Akan ku kejar jejak rezeki yang dijanjikan Tuhan untukkuwalaupun jejak itu tidak pernah jelas ku lihat. Asal daganganku nanti habis terjual. Lagi-lagi, aku lupa membawa air minum. Padahal air penting sekali untuk penjual yang mengandalkan suara sebagai alat promosinya. Ah, bibirku telah kering. Tenggorokanku mulai terasa perih akibat habis suaraku sedari pagi berteriak menjajakan gorengan. Jilbabku mulai berbau matahari sedangkan kulitku sudah lama menghitam dan kering karena tiap hari terpapar ganasnya sinar matahari Jakarta. Tak ada lagi sisa-sisa keindahan kulit perempuan yang lembut seperti dahulu. Tak pernah lagi aku oleskan pelembab kulit apalagi tabir surya. Barang itu terlalu mahal buatku. Sudah satu tahun aku jalani kegiatan ini. Tepatnya sejak ayah dipecat dari
pekerjaannya. Aku berkeliling menjual gorengan dan nasi uduk dari pagi sampai siang. Lalu segera menuju kampus untuk mengerjakan proyek skripsiku. Uang hasil jualan lumayan untuk menutupi hutang biaya semester kuliah dan biaya skripsi. Ayah sejak dua semester lalu sebenarnya sudah meminta aku cuti kuliah dulu karena tidak ada dana lagi. Tapi aku tidak mau. Aku harus meneruskan kuliah apapun resikonya. Bukankah kalau aku kelak sudah menyandang gelar sarjana maka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji dengan nominal yang besar? Seperti Pak Deni tetanggaku. Dia sarjana, entah jurusan apa. Tapi yang pasti sekarang dia terlihat perlente dengan mobil Honda Jazz-nya, sering jalan-jalan keluar negeri bersama anak istrinya, dan rumahnya baru saja dibuat tingkat dua, bulan puasa kemarin. Ahhhenaknya menjadi sarjana! Aku bisa membelikan rumah yang lebih layak untuk Ayah dan Ibu, memberangkatkan mereka naik haji serta memboyong mereka liburan tiap tahun
keluar negeri. Ah, nikmatnya!! Suara deru metromini yang mengebut membuyarkan lamunanku. Aku masih
disini rupanya, di pinggiran jalan Jakarta yang kotor dan panas. Kulirik nampan jualanku. Masih ada empat gorengan lagi yang belum terjual. Daganganku harus habis agar genap keuntungan penjualanku menjadi Rp.7.200,Kesempatan buatku menjual sisa jualan. Permisi PakGorengannya Pak? Satunya lima ratus aja, tawarku Mereka cuma melirik sebentar lalu asyik kembali dengan obrolan mereka Paklumayan buat cemilan makan siang Pak, ngabisin aja, aku kembali berpromosi karena tak mau pulang dengan sisa dagangan satupun. Ngabisin? Kalo gitu gua beli semuanya seribu yah!, seorang Bapak supir tertarik untuk membeli. Satunya lima ratus Pak, sisanya ini tinggal empat jadi dua ribu Pak Ahh..kan sisa dek, lihat itu udah gak garing lagi, udah seribu aja, Bapak supir lainnya mencoba membantu temannya Tapi Pak. Mau gak? Kalo gak mau ya udah, kita ga beli!, sahut Bapak supir yang lainnya agak galak. Aku terdiam dan berpikir. Kalau aku tolak, belum tentu nanti akan ada pembeli lagi. Kalau aku iyakan, keuntunganku cuma Rp.6.800,- sedangkan seratus rupiahpun sangat berarti buatku. Gimana? Dikasih ga?, tanya bapak supir pertama sedikit memaksa. Iya paksilahkan., jawabku sambil membungkus gorengan itu untuk mereka. Nah gitu dong!, mereka lalu tertawa bersama..entah apa yang mereka Aku lihat di seberang jalan ada beberapa orang supir taksi yang sedang beristirahat siang.
tertawakan. Mungkin tertawa atas keberhasilan mereka menurunkan harga gorengan dari dua ribu menjadi seribu saja? Begitu sederhananya alasan mereka bahagia. Andai aku juga bisa mudah bahagia seperti itu. Himpitan hidup membuat aku merasa sulit untuk bahagia. Terus terang, aku sedih gorengan jualanku ditawar seperti itu. Keuntungan perbuahnyapun tidak seberapa, hanya dua ratus rupiah. Artinya modal empat gorengan adalah seribu dua ratus rupiah jadi untuk cemilan siang bapak-bapak itu aku rugi dua ratus rupiah. Aku sedih walaupun ikhlas. Tak terasa dalam perjalanan pulang, air mataku beruraian. Aku takkan lupa wajah para bapak itu. Ya Tuhanbegitu sulit mencari sepeser rezekimuuntuk kuliah, untuk masa depanku. Beberapa menit lalu Sudah puluhan berkas lamaran aku kirimkan namun belum ada satu perusahaanpun yang memanggilku untuk mengadakan wawancara. Padahal sudah satu tahun lebih sejak aku menyandang gelar sarjana ekonomi. Bayangan indah kehidupan pasca lulus kuliah belum kunjung menghampiri. Dan sekarang aku masih disini, pinggiran jalan Jakarta. Menjajakan gorengan dan nasi uduk lagi. Dari kantor ke kantor, sekedar menjaga agar perut tetap terisi, sembari menunggu panggilan kerja yang akan datang entah kapan. Kali ini, hari ini, karena begitu marahnya akan kondisi yang kurang mengenakkan ini, aku jadikan fotokopi ijasah sarjana yang sudah dilegalisir sebagai alas gorengan tahu dan bakwan. Aku marah. Entah pada siapa. Entah pada apa. Ayah susah payah menyekolahkan aku sampai pertengahan kuliah dengan satu harapan agar aku menjadi manusia yang lebih baik secara perekonomian dengan gelar sarjana itu. Tapi apa hasilnya? Kamu harus jadi sarjana Nak, tidak seperti Ayah yang cuma lulusan SMA, kerjaannya kasar dan kecil gajinya Aku mengamini dan memegang erat nasihat Ayah malam itu, waktu aku masih kelas 2 SMP. Nasihat yang aku pegang walaupun pada akhirnya Ayah yang duluan menyerah pada nasib dan kemudian memaksaku untuk berhenti kuliah karena ketiadaan biaya dulu. Aku teringat pak Deni yang berhasil sukses secara finansial karena gelar sarjananya dan menjadi karyawan di sebuah perusahaan
bonafid. Ah, Nak! Sudah Ayah bilang kamu sebaiknya berhenti kuliah saja dulu! Buktinya sekarang kamu belum dapat kerja kan?? Tapi Yah, aku mau seperti pak Deni tetangga kitasejak beliau ambil kuliah dan jadi sarjana, kehidupannya membaik Ah, itu cuma luarnya saja!! Kamu gak tau? Dia dikejar-kejar debt-collector karena hutangnya banyak! Dan dua malam lalu dia habis dipukuli sama debtcollector karena hutang kartu kreditnya belum dilunasi! Aku terdiam. Apa ternyata semua cuma fatamorgana? Harapan palsu? Aihh, kenapa aku lupa. Bang Mori juga sarjana tapi dia cuma jadi tukang ojeg di pangkalan ujung. Begitu juga mas Tedi dan mas Herman, mereka cuma jadi supir angkot Bang haji Salman, seorang juragan angkot yang SD-pun tak lulus. Sebaliknya, Bang Kumis tetangga depan rumahku adalah seorang pengusaha ayam bakar yang sukses, warungnya sampai ke Jogja sana, padahal pendidikannya cuma sampai SMP. Pak Saidi sukses dengan usaha kayu gelondongannya padahal cuma sampai SD kelas 5. Banyak lagi contoh lainnya. Kenapa aku lupa? Kenapa aku buta? Salah siapa? Tingginya pendidikan tidak selalu berkorelasi positif dengan kesuksesan finansial. Aku terlalu berharap banyak dari gelar sarjanaku. Aku berharap keuntungan ekonomi dari pendidikan yang tinggi. Aku lupa padahal pendidikan adalah jalan untuk mendapatkan ilmu. Aku menjadi pelaku dari pemerkosaan pendidikan atas nama gaji besar kelak. Aku cuma mencari secarik ijasah untuk dijual ke perusahaan-perusahaan berharap mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Ini ganjaranku. Aku pantas mendapatkannya. Tapi benarkah sepenuhnya salahku? Aku ambil selembar kertas fotokopi ijasah dari bawah gorengan. Walaupun berlumur minyak, aku lipat kembali ijasahku dengan rapi. Bukan salah ijasah, amarahku salah sasaran. Kulirik nampan daganganku. Tersisa gorengan sebanyak lima buah. Dua pisang goreng dan tiga bakwan. Semuanya sudah tidak garing lagi. Siapa yang mau membeli? Kulihat ke arah seberang jalan. Ada empat bapak supir taksi sedang asik bercengkrama. Ternyatamereka adalah para supir taksi
beberapa tahun yang lalu.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]Dari EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3845)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
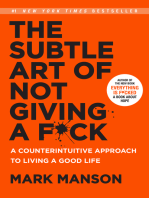
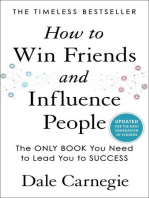






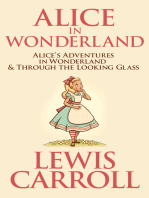






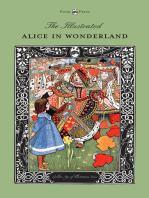
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)