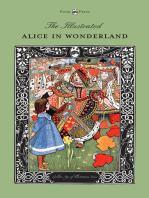Beberapa Catatan Tiga Tahun Desentralisasi Fiskal
Diunggah oleh
Hermawan SuratmanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Beberapa Catatan Tiga Tahun Desentralisasi Fiskal
Diunggah oleh
Hermawan SuratmanHak Cipta:
Format Tersedia
Dimuat dalam Majalah Anggaran, edisi khusus Hari Keuangan, 2003
BEBERAPA CATATAN TIGA TAHUN DESENTRALISASI FISKAL
Suminto, M.Sc. Economist, The Indonesia Economic Intelligence Desentralisasi fiskal telah dimulai dijalankan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini membawa perubahan yang luar biasa dalam tata-pemerintahan Republik Indonesia. Tulisan ini mencoba memberikan beberapa catatan atas tiga tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Beberapa Kharakteristik UU No. 22 dan UU No. 25 Sebagaimana dimaklumi, UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 dilahirkan saat euphoria reformasi tengah mencapai puncaknya. Inti dari UU No. 22 adalah pelimpahan berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah dan setting-up proses-proses politik di daerah, sedangkan inti dari UU No. 25 adalah dukungan terhadap UU No. 22 dengan menjamin ketersediaan sumber-sumber fiskal bagi pemerintah daerah. UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai the big bang decentralization policy (Asanuma dan Brodjonegoro, 2003) mempunyai beberapa kharakteristik sebagai berikut: Pertama, otonomi diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, dan bukannya kepada pemerintah provinsi. Pilihan ini didasarkan pada dua alasan. Alasan pertama adalah, untuk menekan seminimal mungkin potensi kecenderungan separatis dari daerah otonom. Asumsinya, dari segi kekuatan politik maupun ekonomi, potensi sebuah kabupaten/kota untuk melakukan separatisme jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebuah provinsi. Dalam kalimat Asanuma dan Brodjonegoro, Governing the relationship of one vs. 300 was regarded far easier for the center than the one vs. 27. Alasan kedua adalah alasan efisiensi. Pemerintah kabupaten/kota dipandang sebagai lebih dekat dengan publik, sehingga lebih memahami kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan publik. Dengan demikian diasumsikan bahwa otonomi pada level pemerintah
kabupaten/kota akan lebih menjamin pelaksanaan pelayanan publik (public service). Kedua, otonomi daerah diletakkan dalam bingkai negara kesatuan dan menghindari sejauh mungkin nuansa federalisme. Inti dari konsep negara kesatuan adalah, setiap daerah diperlakukan sama (equal treatment), dengan sedikit pengecualian pada Jakarta sebagai ibukota negara yang bersifat istimewa. Karena perkembangan politik, selanjutnya dilahirkan pula undangundang mengenai otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Berdasarkan status otonomi khusus ini, otonomi yang lebih besar justru diberikan kepada pemerintahan provinsi. Ketiga, dengan UU No. 22 Tahun 1999, berbagai fungsi dan kegiatan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Undang-undang ini menentukan bahwa kewenangan pemerintah pusat terbatas pada urusan-urusan pertahanan dan keamanan nasional, agama, peradilan, kebijakan fiscal dan moneter, luar negeri, dan beberapa urusan khusus, seperti perencanaan makroekonomi, system transfer fiscal, administrasi pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan standarisasi nasional. Urusan-urusan selain ini praktis dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dan secara spesifik Undang-undang menyebutkan kewenangan pemerintah daerah mencakup pekerjaan umum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, regulasi atas kegiatan perdagangan dan manufacturing, regulasi atas kegiatan investasi, urusan lingkungan, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Keempat, mengingat pelimpahan kewenangan sebagaimana diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 membutuhkan sumber-sumber fiscal, maka UU No. 25 Tahun 1999 mengatur batas kewenangan pemerintah daerah untuk menarik pajak dan retribusi, serta transfer sumber-sumber fiscal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pajak pemerintah provinsi terutama adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kepemilikan kendaraan bermotor; sedangkan pajak pemerintah kabupaten/kota mencakup pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak bahan-bahan bangunan, pajak atas penggunaan air, pajak hiburan, pajak izin mendirikan bangunan, dan beberapa macam retribusi. Sebagaimana dimaklumi, jenis-jenis pajak pemerintah daerah ini adalah jenis pajak gurem, yang oleh karenanya kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangatlah kecil. Kelima, UU No. 25 Tahun 1999 mengenal konsep tax sharing dan revenues sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini
dilaksanakan bagi hasil atas pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh) perorangan, dan bagi hasil atas eksploitasi sumber daya alam, sepeti minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Keenam, UU No. 25 Tahun 1999 mengintrodusir transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah block grant yang diberikan kepada semua pemerintah kabupaten/kota untuk menutup kesenjangan antara kapasitas fiscal (fiscal capacity) dengan kebutuhan fiscal (fiscal needs). Pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan sekurangkurangnya 25% dari penerimaan domestik netto untuk DAU. Sedangkan DAK didesain untuk tujuan yang spesifik dan dialokasikan untuk pemerintah daerah secara spesifik pula. Ketujuh, UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, atas pinjaman pemerintah daerah ini diterapkan pembatasan-pembatasan dalam konteks manajemen keuangan yang hati-hati. Pinjaman jangka panjang hanya dimungkinkan untuk membangun infrastruktur yang men-generate pendapatan, sementara pinjaman jangka pendek hanya dapat dilakukan untuk operasi perbendaharaan dalam konteks cash-flow management. Outstanding pinjaman jangka panjang tidak boleh melebihi 75% penerimaan umum tahunan, dan outstanding pinjaman jangka pendek tidak boleh melebihi 1/6 total pengeluaran tahunan. Sedangkan pinjaman luar negeri hanya dimungkinkan melalui pemerintah pusat.
DAU dan DAK: Quo Vadis? Dalam UU No. 25 Tahun 1999, besarnya DAU sudah ditetapkan, yaitu 25% terhadap penerimaan domestik netto (penerimaan domestik setelah dikurangi alokasi bagi hasil, baik bagi hasil SDA maupun non SDA) ke daerah. Dari total DAU tersebut, 90% dibagikan kepada kabupaten/kota, sedangkan sisanya kepada tingkat propinsi. Ini berarti 22,5% dari penerimaan dalam negeri netto akan dibagikan kepada semua kabupaten/kota, sedangkan 2,5% dari penerimaan dalam negeri netto akan dibagikan kepada semua propinsi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi untuk melakukan alokasi DAU ini kepada daerah-daerah di Indonesia. Menurut ketentuan yang berlaku pada UU No. 25 Tahun 1999, maka alokasi DAU ini ditentukan dengan menggunakan konsep kesenjangan fiscal (fiscal gap), yaitu mempertimbangkan sisi kebutuhan fiscal (fiscal needs) dan sisi kemampuan
fiscal (fiscal capacity). Untuk memperoleh perkiraan kebutuhan dan kemampuan fiscal, diperlukan suatu kajian empiris. Hal ini diperlukan agar diketahui variabelvariabel apa yang dapat mewakili (proxy) bagi kebutuhan dan kemampuan fiscal, serta bobot dari variable tersebut dalam penentuan alokasi DAU. Menurut ketentuan UU No. 25 Tahun 1999, maka kebutuhan fiscal suatu daerah paling sedikit dicerminkan dari variable jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan rakyat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, untuk potensi ekonomi daerah, antara lain dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi industri, sumber daya lama, sumber daya manusia, dan PDRB. Formula umum DAU adalah sebagai berikut:
DAU daerah i = (bobot daerah i / total bobot daerah diseluruh Indonesia) X total DAU
Meskipun variable-variable kapasitas fiscal maupun kebutuhan fiscal cukup jelas, namun muncul berbagai persoalan dalam implementasinya, misalnya adanya keluhan sebagian daerah bahwa alokasi DAU yang diterimanya terlalu kecil. Mengenai hal ini, hendaknya daerah menyadari bahwa DAU bukanlah satu-satunya dana yang krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masih banyak sumber-sumber penerimaan daerah lainnya yang harus diperhitungkan dalam membiayai urusan didaerah. Untuk itu, kiranya penting untuk dipahami formula suatu keseimbangan keuangan daerah sebagai berikut (Dr. Raksaka Mahi, 2003):
PAD + Bagi Hasil SDA + Bagi Hasil Non SDA + DAK + DAU = Beban Biaya Urusan yang Didaerahkan + Beban Urusan Masa Lalu yang Masih Ditanggung + Beban Biaya Pembangunan Daerah
Dari formula di atas, apabila terjadi kekurangan (defisit), maka berdasarkan ketentuan yang berlaku, akan dapat dibiayai melalui pinjaman daerah (sepanjang memungkinkan) maupun sisa perhitungan tahun yang lalu. Satu catatan kritis untuk implementasi DAU adalah diterapkannya konsep faktor penyeimbang sebagaimana diamanatkan PP No. 104/2000. Dengan konsep faktor penyeimbang ini, DAU yang diterima oleh suatu daerah paling
tidak harus sama dengan yang diterimanya tahun yang lalu; dengan kata lain tidak dimungkinkan adanya penurunan alokasi DAU. Faktor penyeimbang untuk DAU tahun 2001 dengan demikian adalah jumlah alokasi dana rutin daerah (DRD) dan dana pembangunan daerah (DPD) yang umumnya dilakukan alokasi dengan metoda ala INPRES. Menurut catatan Dr. Raksaka Mahi (2003), ternyata untuk tahun 2001, alokasi DAU lebih didasarkan atas jumlah yang diterima masa lalu, sedangkan peranan formula hanya 20% dalam menetapkan alokasi DAU. Ini mengakibatkan terus dibawanya warisan masa lalu; sebagai misal, DKI Jakarta yang relatif sudah kaya menerima alokasi DAU yang besar karena di masa lalu telah menerima bantuan yang besar (dimana pada masa lalu ala INPRES, alokasi bantuan lebih ditentukan oleh jumlah penduduk, yang dengan demikian DKI Jakarta yang besar penduduknya juga menerima alokasi yang besar, meskipun sudah kaya). Dengan demikian, perlu dipikirkan sebuah alternatif untuk mengatasi hal ini di masa depan. Persoalan lain berkenaan dengan formula DAU yang merangsang pembentukan provinsi ataupun kabupaten/kota baru, karena formula DAU menjamin alokasi atas jumlah tertentu (a fixed sum) untuk semua pemerintah daerah, tidak peduli ukuran relatifnya dalam konteks bahwa semua pemerintah daerah membutuhkan biaya administrasi tertentu (certain fixed administration cost). Sebagai illustrasi, jumlah kabupaten/kota telah meningkat dari 300 pada masa sebelum era desentralisasi menjadi sekitar 400 pada saat ini. Berbeda dengan DAU yang merupakan block grant, DAK adalah bantuan khusus yang bersifat specific. DAK pada awalnya hanya berupa DAK untuk kegiatan reboisasi, yang dananya terkait dengan penerimaan dari dana reboisasi dari sektor kehutanan. PP No. 104 Tahun 2000 menggariskan bahwa penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi 40% disediakan kepada daerah penghasil sebagai bagian DAK untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Mulai tahun 2003, alokasi DAK mulai dilakukan untuk sektor-sektor yang lebih luas, terutama adalah sector yang berkaitan dengan infrastruktur (irigasi dan jalan), pendidikan, dan kesehatan. Salah satu catatan kritis mengenai DAK adalah persyaratan dana pendamping. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) PP No. 104 Tahun 2000, atas pembiayaan kebutuhan khusus diperlukan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (fixed rate). Dalam kaitan ini Dr. Raksaka Mahi (2003) mengajukan proposal kiranya dapat diterapkan system dana pendamping variatif (variable matching rate), yakni porsi dana pendamping untuk masing-masing daerah bisa dibedakan berdasarkan kapasitas fiskalnya. Sebagai illustrasi, daerah A yang kapasitas fiskalnya lebih tinggi mampu menyediakan dana
pendamping sebesar 15%, sementara daerah B hanya mampu menyediakan dana pendamping 5%. Dalam kasus demikian, alokasi DAK sebesar 5% untuk daerah A dapat dialihkan sebagai tambahan DAK bagi daerah B. Menurut Dr. Raksa Mahi, metode inipun kiranya tidak melanggar UU No. 25 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dana pendamping yang diperlukan tergantung pada kemampuan daerah.
Pinjaman Daerah: Di Persimpangan Jalan UU No. 25 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah yang melengkapinya, yakni PP No. 107/2000 memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri. Bahkan UU No. 25 menyatakan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah memiliki akses langsung kepada sumber-sumber dana luar negeri. Namun dalam praktiknya hal ini tentu saja sangat sulit untuk dilaksanakan. Praktis semua lembaga internasional tidak berkeinginan untuk membuat berbagai perjanjian (loan agreement) yang terpisah, masing-masing dengan sekitar 400 pemerintah daerah yang ada pada saat ini. Tambahan lagi, mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa dalam system baru yang desentralistik ini, pemerintah pusat pada dasarnya tidak menjamin pinjaman pemerintah daerah, yang dimasa lalu merupakan hal yang otomatis diberikan. Guna mengatasi hal tersebut di atas, diupayakan mencari mekanisme pinjaman yang sesuai dan system perantaraan yang cocok, yang hasilnya tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 35 Tahun 2003. KMK 35 sebagai satu langkah terobosan itu sendiri masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Dr. Robert Simanjuntak, misalnya, dalam laporannya untuk Project for Strengthening Indonesias Framework for Decentralization-Package 14: On Lending Specialist mengidentifikasi adanya beberapa isu krusial dalam KMK 35 yang perlu klarifikasi lebih lanjut, mencakup: (1) klasifikasi dari proyek-proyek yang akan dibiayai hibah dan/atau pinjaman; (2) klasifikasi daerah; (3) evaluasi mengenai porsi hibah dalam pinjaman daerah terkait dengan klasifikasi daerah; (4) terms and conditions dari pinjaman dan hibah, serta kaitannya dengan masalah penggunaan rupiah atau mata uang asing. KMK 35 membuat pembedaan proyek cost recovery/revenue generating dan proyek non cost recovery/non revenue generating, namun demikian tidak terdapat definisi yang jelas mengenai keduanya, sehingga sulit untuk membuat justifikasi mana yang cost recovery/revenue generating dan mana yangnon cost recovery/non revenue generating. KMK 35 hanya memberikan row
definition, bahwa yang kategori proyek pertama adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menghasilkan penerimaan, sedangkan kategori proyek yang kedua adalah proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana yang tidak menghasilkan penerimaan. Persoalannya adalah, apa ukuran dan seberapa besar ukuran penerimaan, sehingga sebuah proyek dimasukkan dalam kategori cost recovery/revenue generating? Dalam praktek, kharakteristik proyek sangatlah bervariasi dan kompleks. Ada proyekproyek yang memang mampu menghasilkan secara penuh (full cost recovery), ada proyek-proyek yang hanya mampu menghasilkan sebagian (partial costrecovery), dan bahkan ada proyek-proyek yang tidak menghasilkan sama sekali (non cost recovery). KMK 35 menggariskan bahwa pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk hibah (on granting) adalah pinjaman untuk proyekproyek non-cost recovery; begitu pula sebaliknya, pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada daerah dalam bentuk pinjaman (on-lending) adalah pinjaman untuk proyek-proyek. KMK tidak jelas posisinya dalam hal ini; cost-recovery yang mana? Yang partial cost recovery atau full cost recovery? Ataukah keduanya? Demikian pula, apakah tidak dimungkinkan on lending proyek atas proyek-proyek non cost recovery bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, dan sebaliknya, apakah tidak dimungkinkan on granting atas proyek-proyek non cost recovery bagi daerah-daerah miskin? Kaitannya dengan on granting, KMK 35 menentukan bahwa porsi hibah akan tergantung pada kapasitas fiskal daerah. Pasal 27 KMK 35 menggariskan bahwa, daerah dengan kapasitas fiskal tinggi mendapatkan porsi hibah 30% dari total nilai proyek, daerah dengan kapasitas fiskal sedang dan rendah masingmasing mendapatkan porsi hibah 60% dan 90%. Kaitannya dengan penentuan kapasitas ini telah diterbitkan KMK No. 538/KMK.07/2003 tanggal 12 Desember 2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal Dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah Dalam Bentuk Hibah. Dalam KMK ini diintrodusir satu formula untuk menentukan kapasitas fiskal, yaitu: KF = (PAD + BH + DAU + PL) BP Jumlah penduduk miskin Dimana: KF = Kapasitas Fiskal PAD = Pendapatan Asli Daerah BH = Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) DAU = Dana Alokasi Umum]
PL BP
= Penerimaan Lain-lain yang sah kecuali DAU, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama dan penerimaan lainnya yang dibatasi penggunaannya = Belanja Pegawai Menengok KMK 538 ini, mungkin pembaca akan cukup kaget melihat
propinsi Maluku Utara, misalnya, ternyata masuk klasifikasi daerah kapasitas tinggi, sedangkan propinsi Jawa Timur masuk klasifikasi daerah kapasitas fiskal rendah. Keterkejutan-keterkejutan demikian tentunya mengindikasikan masih adanya keraguan akan kesahihan formula ini. Kaitannya dengan klasifikasi proyek dan klasifikasi daerah ini, sangat menarik untuk menyimak hasil kajian konsultan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) untuk "Study on Transfer Mecanism for Local Government Borrowing in Indonesia". Kajian ini merekomendasikan, kiranya klasifikasi proyek dibagi menjadi tiga, yakni (1) "financially viable" (full cost recovery; dalam pengertian cash out lebih besar atau sama dengan cash in); (2) "Economically viable" (partial cost recovery; dalam pengertian cash out lebih kecil dari cash in); dan (3) "socially viable" (non cost recovery; dalam pengertian cash in sama dengan 0). Sementara itu, kapasitas fiscal daerah dikatergorikan sebagai tinggi, sedang, dan rendah. Atas proyek-proyek "financially viable" (full cost recovery) dapat diterapkan on-lending murni (pinjaman 100%, hibah 0%), sedangkan terhadap proyek-proyek "socially viable" (non cost recovery) dapat diterapkan on-granting murni (hibah 100%, pinjaman 0%). Adapun terhadap proyek-proyek "Economically viable" (partial cost recovery) dapat diterapkan blending (campuran) dari on lending dan on granting, dimana porsi hibahnya ditentukan oleh kapasitas fiscal daerah. "Pekerjaan rumah" selanjutnya dari KMK 35 adalah belum jelasnya mekanisme penyesuaian antara porsi hibah dan porsi pinjaman dalam penerusan pinjaman dengan porsi pinjaman dalam original loan agreement yang ditentukan oleh lender. Misalnya, suatu daerah mendapatkan penerusan pinjaman dari IBRD dengan porsi hibah 60% dan porsi pinjaman 40%; sementara porsi pinjaman dalam original loan agreement IBRD adalah 20% porsi pendamping dan 80% porsi pinjaman; bagaimana mekanisme matching ini? KMK 35 juga masih menyisakan problem dengan dimungkinkannya penerusan pinjaman kepada daerah dalam bentuk valuta asing. Dalam ini muncul pertanyaan, apakah daerah mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko kurs; demikian halnya apakah daerah mempunyai kapasitas untuk melakukan manajemen risiko kurs. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kapasitas untuk menanggung risiko kurs lebih mungkin ada pada pemerintah pusat,
demikian juga, kemampuan manajemen kurs lebih dipunyai oleh Bank Sentral dan Departemen Keuangan. Dalam konteks ini muncul pertanyaan, apakah tidak lebih bijaksana jika penerusan pinjaman ke daerah dalam bentuk mata uang local saja. Isu lainnya yang sering diangkat berkenaan dengan implementasi KMK 35 adalah tidak diperkenankannya mekanisme rekening khusus dalam penarikan pinjaman. Sebagaimana diketahui, sejauh ini KPKN-KPKN di daerah hanya berwenang melakukan pembayaran atas proyek yang dibiayai dengan utang luar negeri melalui mekanisme rekening khusus. Sedangkan pembayaran non rekening khusus masih tersentralisir di Jakarta, yakni melalui KPKN Khusus VI. Pertanyaannya adalah, mungkinkah orang proyek di daerah-daerah harus bolakbalik daerah yang bersangkutan-Jakarta untuk mengurus penerbitan SPM? Ataukah KMK 35 mengisyaratkan bahwa KPKN-KPKN di daerah nanti dapat menerbitkan SPM atas proyek berbantuan luar negeri non reksus? Atau, mungkinkah ada scenario yang lain? Hal ini masih cukup kabur dalam konteks KMK 35.
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20011)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2565)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6513)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3271)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2306)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)


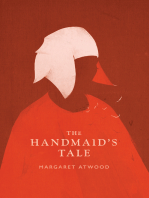



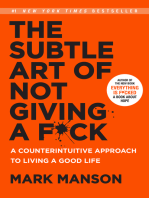


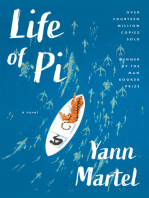




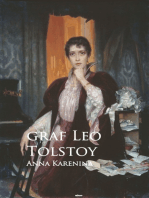





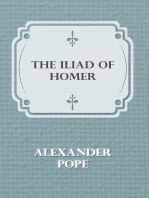





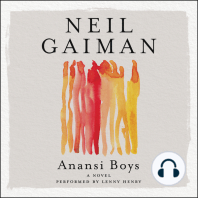
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)