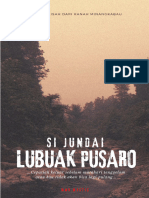Mak Dan Ikan Teri
Diunggah oleh
wahyu sugitoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Mak Dan Ikan Teri
Diunggah oleh
wahyu sugitoHak Cipta:
Format Tersedia
MAK DAN IKAN TERI Cerpen : Santyarini
Sore itu, setelah menyiapkan lauk untuk makan malam, istriku pamit untuk balik ke sekolah tempat ia mengajar. Rini adalah guru sejarah merangkap seni suara pada sebuah SMP Negeri di daerah Kebayoran Lama, 2 km dari tempat kami tinggal. Sudah beberapa hari ini ia bekerja di luar jam dinasnya, memimpin latihan koor murid-muridnya untuk menyambut Hari Kartini. Seperti kebiasaan sepulang kerja, aku mandi, lalu duduk membaca koran sore. Tiga jam lewat. Rini belum juga pulang. Perutku mulai keroncongan. Bau harum balado teri di meja makan menggodaku untuk tidak menunggu lebih lama. Aku ambil piring dan mulai menyantap makanan kesukaanku itu. Istimewa betul masakan Rini malam ini. Nasi dengan lauk teri, lalap ketimun, dan daun kemangi. Sudah lama aku tidak menikmati spesialisasi istriku. Persisnya sejak dua tahun yang lalu, setelah Rini menjadi guru SMP, Iyem, pembantu kami, menggantikan tugasnya di dapur. Akan tetapi seminggu yang lalu Iyem meminta izin untuk pulang kampong. Anak laki satu-satunya akan dikhitankan. Dengan gembira tetapi terburu-buru, Iyem pulang ke Tegal. Anaknya, Bambang ditinggalkan bapaknya sejak berusia enam bulan di kandungan. Jadi semua kewajiban dipikul oleh ibunya. Selama seminggu ini tidak pernah Rini masak seenak ini. Terasa perutku semakin gendut. Bau teri mengundang satu dua lalat. Aku bangkit mencari tudung saji di dekat cucian. Panci dan penggorengan bertumpuk-tumpuk. Kasihan Rini. Sejak Iyem pergi, waktunya habis untuk mengajar dan bekerja di rumah. Ia memang tidak mengeluh. Tetapi kemarin Bi Marti, tetangga sebelah, dimintanya mengerik punggungnya. Jangan-jangan ia terlalu capek. Aku mengangkat tudung saji. Balado teri?.... tiba-tiba aku terhenyak. Badanku terasa lemas dan jantungku berdebar-debar. Mengapa Rini menyiapkan masakan kesukaanku itu hari ini? Tidak biasanya ia pulang selambat ini, lewat magrib. Ia selalu member tahu kalau harus pulang lewat jam makan. Aku mencoba mengingat tindak-tanduk Rini beberapa hari ini. Ia tidak banyak becanda seperti biasanya? Ingatanku melarang ke saat-saat terakhir sebelum Mak, begitu panggilan akrabku untuk nenekku dari pihak Ibu, mengingat dari rumah kami di desa Wringin Kembar di daerah Lamongan yang tandus. Wajtu itu aku berusia sekitar enam tahun. Adikku Ratni tiga tahun
dan Wiji baru enam bulan. Ibu dan Bapakku sedang mengajar di satu-satunya SD Negeri di desa itu. Siang itu aku dan Ratni bermain di bawah pohon sawo di belakang rumah. Mak memanggil kami untuk makan. Di meja tersedia goring teri kesukaanku. Aku dan Ratni berebutan mengambil nasi dan lauk. Mak menggendong Wiji, sambil mengawasi kami makan. Aku ingat Mak berpesan sesuatu, lalu mengatakan bahwa ia harus pergi ke rumah Lik Narsih untuk menempil telur. Ketika Ibu Bapak pulang, Mak belum juga kembali. Baru setelah magrib, mereka menyadari ada yang tidak beres. Bapak pergi ke rumah Lik Narsih dan mendapati Wiji di sana. Kata tetangga kami itu, Mak menitipkannya di sana karena ia perlu pergi ke Mbah Marni untuk minta urut. Bapak bergegas ke rumah Mbah Marni. Mak tidak pernah dating ke sana hari itu. Mak minggat, demikian kata-kata Bapak terngiang-ngiang di kepalaku. Ibu mengurut dada, sambil berkeluh-kesah seperti pada dirinya sendiri. Itu kebiasaannya kalau sedang bingung. Lik Narsih muncul dengan Wiji di gendongannya, Mbah Dukun dan beberapa tetangga lain dating untuk menenangkan Ibu. Bapak member isyarat padaku agar ikut ke luar rumah. Ia mengambil sepeda tuanya, mendudukkan aku di boncengan, lalu mengayuh cepat ke arah rumah Pak Lurah. Pak Lurah menugaskan Lik Dimin; pembantunya untuk menemani ayah mencari Mak. Kami meluncur menelusuri jalan berbatu, pematang sawah, dan akhirnya sepanjang sisi rel kereta api yang melintasi desa kami dari barat ke timur. Beberapa penduduk melihat Mak berjalan ke arah sana. Entah beberapa lama kami bersepeda, ketika Bapak menyerukan sesuatu. Dari kejauhan tampak punggung Mak yang bungkuk, dengan baju kebaya krem kesayangannya, terhunyuk-hunyuk di sepanjang rel. Ia menanting sebuah bungkusan kain di siku kanannya. Aku tak tahu berapakah Mak mendengar panggilan Bapak. Ia berjalan terus tanpa menoleh. Bapak dan Lik Dimin memacu sepeda mereka. Kira-kira sepelempar sirih, keduanya berhenti. Bapak menyerahkan sepedanya ke Lik Dimin, lalu berlari menyusuk Mak. Kami tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Mak berjalan terus tanpa menoleh, Bapak mengikuti di sampingnya, sambil bercakap serius. Entah kenapa aku menangis. Mungkin kakiku kesemutan. Lik Dimin menaruh sepedanya dan menurunkan aku ke tanah. Aku melihat Bapak dan Mak berhenti berjalan. Bapak menunjuk-nunjuk ke arah kami. Rasanya aku ingin lari memeluk Mak, tetapi aku takut pada Bapak, Lagi pula Lik Dimin memegangi tanganku.
Mak menunduk memandang bungkusan yang dipegangi dengan kedua tangannya. Entah berapa lama mereka berbicara seperti itu. Hari sudah mulai gelap. Akhirnya aku lihat Bapak memeluk bahu Mak dan menuntunnya ke arah kami. Mak mengatupkan bibirnya. Kerutan-kerutan wajahnya tampak jelas dari lampu sepeda. Matanya berlinang. Rambutnya yang abu-abu, biasanya tersisir rapi, tampak agak longgar tersanggul. Mak, kataku pelan sambil memeluk kainnya. Mak mengusap kepalaku. Lik Dimin mendudukkan aku di depan sadel sepedanya. Pantatku terasa sakit bersandar pada tiang besi sepeda, tetapi aku diam saja. Bapak membantu Mak duduk diboncengan. Kami bersepeda pulang tanpa bicara. Dalam gelap suara gesekan ban sepeda kami menyelingi dengkungan kodok dan gossip lirih serangga malam. Para wanita ramai menyambut kedatangan kami di rumah dengan puji syukur. Tetapi malam itu aku tidur tanpa dongeng Mak. Ia hanya merapikan selimutku, lalu duduk di balaibalai di sampingku tanpa suara. Ibu menyuruhnya makan. Mak menggeleng. Ikan teri yang disisakan Ibu untuknya tidak disentuhnya. Bajaj menderu-deru di depan rumah. Aku menarik napas lega. Dari jendela aku melirik keluar. Istriku bergegas turun. Aku bergerak ke tempat cucian dan mulai menyabuni piring. Rini membua pintu. Pipinya merah berkeringat, wajahnya cerah walaupun tampak lelah. Maaf aku terlambat, Mas, katanya. Sehabis latihan aku mampir ke took sebentar. Persediaan kertas krep di koperasi sekolah habis. Perlu untuk hiasan perayaan Kamis nanti. Ia melepas sepatu, meletakkan tasnya yang menggebung di kursi tamu lalu berjalan mendekatiku. Aduh, aku sudah lapar sekali. Kau ketinggalan kereta, kataku seloroh. Terimu yang lezat sudah kuhabiskan. Minggir sebentar, Mas, aku mau cuci tangan. Nanti saja cuciannya. Rini minum air segelas, menghilang ke kamar mandi sebentar, dan dalam beberapa detik sudah duduk di meja dalam gaun rumahnya, segar dan cantik, siap melahap balado teri. Sambil makan, gossip-gosip hari itu dilaporkannya padaku aaaaBagaimana mood bossmu hari ini? tanyanya memancing ceritaku. Mood-ku yang jelek sore tadi sebelum kau dating, kataku mengalihkan pembicaraan. Kau sih bikin balado teri, aku jadi ingat pada saat Mak minggat dulu. Rini membelalakkan matanya dan menutup mulutnya yang bersuara seperti tersedak. Ia tertawa terkikik. Ada-ada saja kau ini.
Ia sudah hapal sejarah keluargaku. Tetapi senyum tidak lama bertahan di wajahnya. Sebentar kemudian ia mengetuk-ngetukkan garpu pada piring. Tangannya memang tidak pernah berhenti bergerak kalau ia sedang memikirkan sesuatu. Mas, katanya, Siapa sih dulu yang meminta Mak untuk ikut pindah ke Wringin Kembar? Meninggalkan Mbah Parto di desa Tumbal Waras di Kediri? Entahlah. Mungkin Bapak atau Ibu. Jadi bukan keinginan Mak sendiri. Lalu kenapa Mbah Parto tidak diajak serta? Sejak kecil, kami memang terbiasa memanggil kakek dengan panggilan Mbah Parto, bukan Mbah Kakung seperti lazimnya. Demikian Ibu membasakan ayahnya untuk kami. Anehnya, Ibu memanggil ibunya Mak, dan kami semua menirukannya. Aku berpikir-pikir, sekarang, Ibu tidak pernah dekat dengan kakek. Aku ingat cerita Ibu, bagaimana beratnya ia berjuang melawan kakek ketika ia mengajukan keinginannya untuk melannjutkan pendidikan ke SPG di kota. Kabarnya Ibu termasuk anak yang cerdas di antara teman-temannya. Guru-gurunya suka padanya dan mendorongnya untuk terus belajar, Mbah Parto marah besar. Anak perempuan tempatnya di dapur begitu kira-kira kata-katanya, buat apa belajar susah-susah toh akhirnya nanti kembali ke dapur juga. Ibu minggat ke rumah guru kesayangannya, yang sekarang kami panggil dengan sebutan Mbah Guru. Ia dipungut anak, disekolahkan dan diasramakan di kota. Entah bagaimana cara Mbah Guru menghadapi Mbah Parto yang kabarnya disegani di seluruh desanya. Bertahun-tahun lamanya Ibu berhenti berbicara dengan ayahnya. Mbah Parto kan tidak mungkin meninggalkan sawahnya. Lagi pula ia sakit-sakitan. Pasti berat Mak meninggalkannya? Entah kenapa, aku merasa disudutkan oleh pertanyaan Rini yang bertubi-tubi. Mungkin karena aku sendiri tidak pernah mempertanyakannya. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan kehadiran Mak di tengah keluarga. Mak-lah yang menanak nasi pagi-pagi, menyiapkan sarapan, pergi belanja, masak, menerima tamu kalau Ibu dan Bapak tidak ada di rumah, dan mengasuh anak-anak. Walau Wiji menangis rewel, Mak bahkan membiarkan bayi itu mengisap teteknya yang keriput untuk menenangkannya. Entahlah Rin, kataku. Mungkin keputusan-keputusan yang kau rasa aneh saat ini, pada saat itu terasa wajar saja. Ibu adalah anak Mak satu-satunya. Tentunya Mak juga merasa berat berpisah jauh dengannya. Lagi pula, saat itu Ibu sedang mengandung Wiji, sedangkan aku dan Ranti masih kecil-kecil. Ibu dan Bapak harus mengajar di desa yang terpencil, tanpa
gaji yang cukup untuk mempekerjakan pembantu. Wajar saja kalau mereka minta tolong Mak untuk menemani kami. Hmmm Mungkin Mak mengira kepergiannya tidak lama. Mengapa ia sampai minggat? Barangkali sudah beberapa kali minta diantar pulang. Barangkali ia punya firasat tidak enak. Barangkali ia rindu suaminya, kataku sambil mengerdipkan mataku pada Rini. Istriku tetap saja serius. Mestinya ia pulang mengurus rumah-tangganya sendiri. Kasihan, Mak. Ia hanya bisa menumpahkan semua kekecewaannya kepada suaminya. Sampai saat terakhir ia tidak bisa memaafkan Mbah Parto. Istriku memang sangat saying pada nenekku itu. Padahal keduanya berbicara dalam bahasa yang berbeda. Rini mengerti bahasa Jawa, tetapi tidak pernah memakainya karena ia dibesarkan di Jakarta. Sebaliknya nenek sedikit-sedikit paham bahasa Indonesia, tetapi tidak bisa mengucapkannya. Bagaimanapun, setiap ada kesempatan bertemu, mereka selalu bercakap-cakap dengan akrab, dan merasa dekat. Setiap kali Rini mengunjungi Mak, nenekku selalu mengungkapkan kembali kekecewaan dan rasa sakit hatinya pada kakek. Dua tahun kemudian setelah keluarga kami kembali ke Kediri, ia mendapati Mbah Parto tidak sendiri lagi. Kakekku sudah menikah lagi dengan Mbah Endang, seorang janda, tetangganya, yang membantu merawatnya ketika Mak pergi. Sejak itu Mak tinggal seterusnya bersama keluarga kami. Dalam hal ini hati Mak keras bagaikan batu. Pada saat Mbah Parto sakit keras, dan diboyong Ibu untuk dirawat di kota, di rumah kami, jangankan berbicara, masuk ke kamarnya pun Mak tidak mau. Anehnya, Mak bersedia masak khusus untuk kakek, menyiapkan air mandinya. Kadang-kadang ia duduk saja di bangku luar kamar tempat kakek di rawat. Beberapa kali Mbah Parto mengajaknya bicara, dalam bahasa Jawa. Sudahlah, Mak yang lewat biarlah berlalu. Saya memang salah. Saya minta maafmu. Tetapi Mak tidak pernah menjawabnya. Biarpun dibujuk oleh Ibu atau Bapak agar mengabulkan permintaan Kakek yang terakhir itu, Mak selalu menggeleng dan berdiam diri. Ketika jenazah kakek dibaringkan, dan orang membaca doa, Mak duduk di belakang. Bibirnya ikut bergerak, kedua tangannya terbuka, tetapi ketika orang mengajaknya untuk melihat wajah Kakek terakhir kali sekali lagi ia menggeleng. Kiranya Mak kukuh dalam pendiriannya, walaupun menurut surat Ibu dua tahun yang lalu, kata-kata Mak yang terakhir adalah tentang suaminya Nduk, kata Mak kepada Ibu yang menungguinya, Itu Bapakmu dating.
Padahal sebetulnya Kakek tidak bisa disalahkan, kata Rini pelan. Tidak ada yang bisa disalahkan di sini, Rin. Lagipula kita perlu ingat, betapa besar peranan Mak dalam menunjang kehidupan keluargaku. Sementara karier Bapak Ibu menanjak, mereka pun semakin sibuk. Padahal keluarga membengkak dari tiga anak menjadi delapan. Siapa yang memandikan, menyuapi dan masak untuk seluruh keluarga, jika bukan Mak? Siapa di antara delapan saudaraku, yang tidak pernah merasakan gendongan selendangnya. Tetapi ongkosnya pun sungguh tak terbayar, Rini menghela napas. Ia mengemasi piring mangkok di atas meja, lalu membawanya ke tempat cuci piring. Biasanya suara kelontang piring ditempa kosekan tangan Iyem mengisi keheningan rumah petak kami, malam-malam begini.
NGARAI
Walau kedatangan Nita saat itu tak pernah diharapkan ayahnya, namun tentu saja merupakan kejutan yang menggembirakan. Lagi pula ayahnya tak pernah mengirim surat padanya bahwa ia sakit. Ayahnya merasa, sakitnya hanya demam biasa, terlalu lelah dan butuh istirahat yang cukup. Kau tidak bawa anak-anakmu? Tidak ayah. Saya sendiri. Saya dengar kabar dari Erni, tetangga kita yang sekarang menjadi mahasiswa saya. Katanya Ayah ikut gotong-royong manunggal. Betul?
Sedikit. Asal menampakkan muka saja. Malulah Ayah, kalau mereka tidak melihat wajah ketua RW-nya. Ya, tapi Ayah sudah tua. Belum pensiun hanya karena guru saja. Coba kalau pegawai negeri biasa, Ayah sekarang tentu sudah dianggap manula, pensiunan, begitu. Ayah Nita terdiam sambil menatap dan membaca wajah putrinya yang sekarang mungkin disebut sebagai wanita karir dan tinggal di kota propinsi. Ia bangga, Zurnita cantik, lebih cantik dari mendiang ibunya sewaktu muda, terpelajar, bersuamikan laki-laki yang setara dengan pendidikannya. Tetapi dari goresan pelupuk mata Nita, ayahnya seakan-akan membaca mendung. Nita tahu, ayahnya adalah laki-laki yang sangat arif, karena itu ia gugup dan berusaha berhelah. Putri yang kecil saya titipkan sama tantenya, adik Uda yang tinggal bersama kami di Padang. Umurnya berapa sekarang? Sudah hampir setahun. Tidak menetek lagi Ayah. Kalau Tari tiap pagi diantar papinya ke sekolah sambil berangkat kerja. Pulangnya dijemput sopir kantor papinya. Jadi tidak begitu repot kok. Kamu kembali hari ini kan? Saya harap begitu, Ayah. Tapi ini sudah sore. Mana ada bis ke Padang. Oplet yang akan membawamu ke jalan propinsi saja mungkin sudah usai. Nita terdiam dan mencoba tersenyum. Kemudian meninggalkan kamar itu dan menuju dapur, melihat kakaknya Sarima memasak sambil bercengkerama dengan putra bungsunya yang baru berusia dua tahun. Walaupun bersuamikan petani dan ia sendiri tak tamat SMA, Sarima juga tahu bahwa Nita datang hari itu jauh-jauh ke kampung pasti bukan menjenguk ayahnya yang sakit. Oleh karena itu ia langsung saja menembak Nita. Kamu bertengkar lagi yang Nita? Bertengkar itu kan biasa. Ya tidak biasa, kenapa kau sampai tega meninggalkan bayimu. Dia kan masih bayi dan belum pernah pisah denganmu bukan? Biasanya sering juga saya tinggal seharian kok. Di samping jadi dosen saya kan juga jadi redaksi koran. Wartawan maksudmu? Bukan. Itu, yang mengasuh ruangan konsultasi. Uni tidak pernah baca nama saya di koran?
Di rumah ini aku kan nomor satu repot. Kapan aku dapat membaca koran? Apalagi sejak kacamataku pecah terinjak sepatu ayah tempo hari. Zurnita meninggalkan Sarima di dapur tanpa harus mempertimbangkan Sarima akan kesal karena dibiarkan bicara sendirian. Nita butuh sendiri. Ia masuk ke kamar ibunya yang selalu dipelihara rapi oleh Sarima. Kamar itu sebenarnya kamar yang kembar dengan kamar depan yang sekarang dipakai ayahnya untuk kamar kerja dan sekaligus kamar tidur. Sejak ibu Nita meninggal lima tahun lalu, kamar itu dibiarkan kosong, kecuali kalau Nita pulang dengan keluarganya, atau saudara laki-lakinya yang merantau jauh di seberang lautan itu pulang bersama istrinya yang bukan orang Minang. Tanpa mengganti pakaian, Nita menggolekkan tubuhnya di atas ranjang kuno terbuat dari besi itu. Agak tinggi memang, tetapi itu bekas ranjang pengantin mendiang ibunya. Menurut ceritanya, ibu kawin di usia sangat muda, enam belas tahun dengan ayah yang waktu itu berusia dua puluh satu. Jauh beda dengan Nita yang kawin pada usia dua puluh tujuh tahun, dengan Syafri yang waktu itu berusia enam tahun lebih tua. Bedanya lagi, Nita tidak menikah di kampung, tetapi di kantor Urusan Agama dan pestanya di sebuah gedung pertemuan yang besar, yang semua ongkosnya ditanggung keluarga Syafri, tepatnya Drs. Syafri. Nita tidak menangis walau sebenarnya dia ingin. Bau sprei ranjang ibu mengingatkan Nita sewaktu masih kecil. Bau khas itu entah datang dari kasur atau badan ibu yang harus tak bernama, seperti masa kanak-kanak dulu. Kalau Nita tidak enak badan, ibu akan menidurkannya di ranjang ini. Rasa aman dan nyaman itulah yang membuatnya ingin membayangkan wajah itu kembali dan ia berhasil menetes air mata. Tetapi bayangan wajah ibu hanya sesaat. Cepat saja berganti dengan bayangan ranjangnya di kota yang sebenarnya jauh lebih empuk dan mahal ketimbang ranjang kuno ibu. Tetapi ranjang itu sering membuatnya tidak nyaman bahkan anehnya, sering merasa kepanasan di samping suaminya yang sering tidur lebih awal. Lelaki yang dulu menjadi impiannya siang malam, hampir tujuh tahun lalu, dan kini tiba-tiba berubah menjadi laki-laki tambun yang lebih suka meninggalkan perintah daripada berkata lembut kalaupun tidak merayu-rayu seperti dulu. Padahal sewaktu Nita sedang di Kanada mengikuti program pertukaran pemuda, kepada lelaki itulah yang paling banyak ia menulis surat, bahkan menelpon sebelum berangkat tidur, ke tanah air. Lelaki itu justru yang memberinya semangat, mendukung kariernya sebagai mahasiswa berprestasi tinggi dan aktivitasnya yang menonjol. Nita memang butuh orang yang mengerti cita-citanya. Kedengarannya memang sederhana, tak sekedar ibu rumah tangga. Tetapi sekarang?
Sekarang, anak-anak mesti jadi tanggung jawabmu yang utama. Karier, jelas nomor dua. Sekarang, kau terima tawaran koran picisan itu untuk menjadi redaktur tamu pengaruh apa itu? Konsultasi remaja? Seharusnya kau lebih rasional Nita. Anak jelas tanggung jawab kita berdua. Mengapa aku sendiri? Ingat, sekarang aku pegawai eselon, kepala sebuah bagian penting di Kantor Bergonjong (1) itu. Mestinya kau aktif di Darma Wanita. Jadi contoh istri-istri pejabat yang lain dan menjadikan aku lebih bergengsi karena beristrikan wanita terpelajar, pinter, dan berpengalaman luar negeri lagi. Menjadi anak buah istri bossmu yang tak tamat SMA itu? Lantas gengsimu naik sementara harga diriku diinjak-injak oleh ketua Darma Wanita kantormu yang judes itu? Sok tahu segala itu? Nggak usah ya. Itu justru tidak logis. Aku ini dosen. Aku justru menyiapkan generasi Indonesia masa depan. Pertengkaran seperti itu semakin sering dan membuat Nita merasa tak berharga di rumah tangganya, di mata suaminya. Bagi suaminya, jabatan dan penghasilannya (Nita sendiri tak pernah ingin tahu dari mana uang yang bukan berasal dari gaji itu) sudah pantas disyukuri Nita. Karena itu Nita tak perlu kerja keras. Mengapa harus repot-repot menjajakan ijazah sarjana ke koran-koran segala? Malam itu, sehabis bersoal jawab dengan suaminya, Nita mengetik makalah sampai pagi, sampai tuntas untuk bahan seminar tentang peranan generasi muda dalam memajukan budaya bangsa seminggu lagi. Esok harinya Nita bolos mengajar. Seharian tidur-tiduran dengan Tari putrinya. Nita puas walau capai, karena dengan bertengkar semalam dengan Syafri suaminya, ia berhasil mengambil hikmahnya. Menyiapkan makalah seminar dan tinggal menunggu panitia menjemput naskahnya untuk diperbanyak. Zurnita masih mengingatnya selalu ketika wartawan surat kabar yang
mewawancarainya itu langsung memintanya untuk mengasuh rubrik konsultasi remaja sehabis seminar. Wartawan yang hangat dan berwawasan luas itu bernama Rus. Esoknya wajah Nita terpampang di koran itu dengan sejemput ulasan tentang makalahnya. Tetapi Syafri suaminya malah menanggapinya dengan wajah sinis, jangankan memberikan pujian. Namun Nita sudah menduga dan siap menerimanya. Bagi Nita, orang lain jauh lebih tahu menghargai dirinya. Bagi Nita tawaran untuk menjadi pengasuh rubrik itu bagaikan nafas kehidupan baru setelah tersenggal-senggal dihimpit tangga dan rumah yang dibikinnya berdua dengan Syafri. Sekarang kau hamil Nita. Kumohon kau mengurangi kegiatanmu.
Nita tidak menjawab, menerawang angan untuk mengatur pertemuannya dengan teman-teman di kantor redaksi. Hari ini mestinya dia ke sana untuk beberapa jam menyiapkan bahan-bahan surat yang ditujukan pada oengasuh rubrik itu. Manik-manik keringat membasahi jidat Nita yang tertidur bagaikan bocah di kamar mendiang ibunya. Lambat-lambat ayahnya yang masih sempoyongan itu mengusap keringat Nita dengan handuk kecil. Nita mendengkur kecil, pertanda tidunyra pulas. Ayahnya mencium kening yang sedikit mengerut itu, mungkin sedang bermimpi. Kemudian memandang wajah Nita agak lama, sementara matahari mulai turun, pertanda malam akan segera tiba. Tak biasanya Nita pulang sendirian kalaupun dengan alasan menjenguk ayahnya sakit. Ini mungkin pertengkaran serius, pikir ayahnya yang termangu di depan jendela kamar itu. Tiba-tiba ayahnya tersentak oleh pikirannya sendiri bahwa Nita hari ini genap tiga puluh tiga tahun. Sekali lagi diciumnya kening Nita. Mungkin agak lama, hingga Nita terbangun. Agak terkejut memang, mencari-cari, wajah siapa yang begitu dekat dengan wajahnya. Selamat ulang tahun Nita ucapan itu membuat Nita terlonjak dan langsung merangkul ayahnya. Ayah dan anak itu saling melepaskan perasaannya, dibumbui dengan tetes-tetes aur mata sebagai pelengkap. Sebenarnya dalam tidurnya Nita betul-betul bermimpi. Nita bermimpi bertemu Rus dengan muka penuh luka, tetapi tertawa-tawa seperti tak merasa apa-apa. Nita ingin membasuh luka itu, tetapi Rus mencegahnya hingga Nita kecewa. Jangan, terima kasih atas perhatianmu. Nita mundur dan hampir menangis memikirkannya. Padahal selama ini Rus akrab dengannya. Nita pernah beberapa kali ditelepon Rus, dijemput ke kampus lalu pergi bersama, sekitar pukul sepuluh menyaksikan film yang akan diresensi dan dinilai oleh badan sensor film daerah. Biasanya habis itu berdiskusi, makan siang di kantor redaksi dengan nasi rantangan. Dan dalam setiap diskusi, Rus selalu memuji pikiran-pikirannya. Dan Rus yang punya istri pegawai bank itu sering dijumpai Nita sedang melatih anak bungsunya menggambar di kantor redaksi sehabis jam sekolahnya di sebuah TK. Maksud Rus, agar putrinya itu asyik bekerja dan tidak mengganggu. Diam-diam Nita mengagumi Rus. Karena itu sesekali Nita mengajak Tari ke kantor redaksi, bermain dengan putri Rus. Mereka seperti saudara kembar, akrab sekali menggambar dengan kertas dan spidol warna-warni. Sebenarnya, sebelum berangkat ke kampungnya, Nita hanya bermaksud ke kantor redaksi. Ia ingin jumpa Rus dan berharap Rus akan memberinya surprise sehubungan dengan hari ulang tahunnya. Mungkin karena di rumah, tadi pagi suaminya hanya bilang akan terlambat pulang karena banyak pekerjaan, Nita butuh orang lain yang mengucapkan selamat
ulang tahun. Tapi Rus tidak ada di tempat. Menurut rekannya, Rus ke pusat pemutaran film badan sensor. Nita kecewa, lalu menulis surat pendek dan meletakkannya di bawah kaca alas meja Rus. Rus, aku pulang kampung. Ayahku sakit. Walaupun tidak pakai tanda tangan dan inisial nama, Rus tahu bahwa itu tulisan Nita. Bahkan Rus tahu bahwa sobekan kertas itu berasal dari buku agenda Nita, karena agenda itu hadiah Rus sewaktu hari ulang tahun Nita tahun lalu. Sore itu Syafri dan putrinya Tari datang ke kantor redaksi mencari Nita. Tari langsung saja menemui Rus. Om Rus, mama Tari ada di sini? Oh, tidak Tari. Dengan siapa ke sini? Dengan papi. Tuh, ujar Tari sambil menunjuk ke perut papinya yang kelihatan sesak nafas menaiki tangga lantai dua itu. Maaf mengganggu. Kenalkan, saya suami Nita. Selama ini Rus tidak pernah berjumpa Syafri dan tidak pernah ingin berkenalan. Saat itu Syafri berada di hadapannya sambil berbasa-basi. Tetapi Rus cepat memberi tahu bahwa Nita menitip surat sepeninggalnya sewaktu menyerahkan naskah rubrik konsultasi. Dan tampaknya Syafri cukup lega karena sudah merasa aman kalau Nita pulang ke kampungnya di kaki gunung Singgalang itu. Tari, mamamu pulang kampung. Kakek Tari sakit. Mendadak ngkali. Syafri meyakinkan putrinya dan dirinya. Permisi kami pulang dulu. Besok-besok juga kembali. Atau kalau sampai Sabtu, saya jemput sambil berlibur, ujar Syafri pada Rus. Rus mengangguk sopan dan mengerdip Tari. Karena itu Tari jadi penasaran dan bertanya: Dita tidak diajak ke sini Om? Tidak Tari. Dita di rumah bersama mamanya. Lain kali main ke rumah Om ya? tawar Rus. Tari mengangguk dan pergi meninggalkan ruangan itu bersama papanya. Semakin jelas bagi Rus, bagaimana Nita sering cekcok dengan suaminya. Tetapi pun Rus bercermin pada dirinya yang sudah lama mendapat perlakuan dingin dari istrinya. Bagi istri Rus, siapa yang paling banyak menghasilkan uang, itulah yang berhak menjadi kepala rumah keluarga. Karena itu resikonya, Rus harus membenahi anak-anak yang tiga orang itu di samping membenahi pekerjaannya di kantor redaksi dengan gaji kecil. Dan Rus memilih anjuran istrinya sehingga ketiga anaknya lebih akrab dengannya ketimbang dengan ibunya. Sedangkan istri Rus dari pagi hingga setengah lima sore non stop di kantornya. Kok kamu nekat ke sini Rus? tanya Nita.
Nggak ah. Aku memang punya jadual sejak kemarin untuk meliput keruntuhan Ngarai Sianok. Lalu surat yang kau titipkan di bawah kaca mejaku itu membuat aku ingin jumpa kau di sini. Sambil ke Ngarai Sianok, lihat teman kan? Bareng terjun ke ngarai yuk, kelakar Nita. Yuk, Tetapi kemudian wajah Nita memerah karena sadar percakapan itu mungkin didengar ayahnya di kamar depan ruang tamu itu. Kamu masih juga bercanda. Tari dan papanya kemarin mencarimu ke kantor. Kalau mereka butuh aku dan tahu ayahku sakit, mestinya hari ini kan mereka datang ke sini. Memang, tapi bukan sekarang. Suamimu bilang mungkin Sabtu sekalian libur. Tapi siang ini aku harus kembali. Esok pagi aku ngajar Rus. Kalau begitu, siap saja sekarang. Kita berangkat; oke? Oke! Di perjalanan, di atas jeep Rus yang tua menuju kota Bukittinggi mereka lebih banyak diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Dan mereka betul-betul menuju panorama pinggiran Ngarai Sianok, tapi tidak jadi melompatinya berdua. Sebab Rus sibuk memilih souvenir untuk Nita, sebagai hadian ulang tahun. Selamat ulang tahun, lebih satu hari ya? Oh, terima kasih. Kau tidak lupa Rus? Langkah-langkah yang berasal dari rombongan bersepatu membuat mereka tersentak. Rombongan gubernur sedang memasuki taman pinggir ngarai itu sambil meninjau bagian yang longsor seperti yang diberitakan koran-koran dan radio. Naluri kewartawanan Rus membuatnya cepat-cepat mengambil tustel dari dalam tasnya dan membidik, ciprot, cipret! Sedangkan Nita terlibat pandang memandang dengan Syafri yang berada di dalam rombongan resmi itu tanpa dapat berkata-kata.
Padang, Jan-April, 1991
Anda mungkin juga menyukai
- KejujuranMembawaBerkatDokumen4 halamanKejujuranMembawaBerkatalinny waasBelum ada peringkat
- ManifestasiMimpiDokumen4 halamanManifestasiMimpi477 633 Religia Paramestri100% (1)
- Ayah] Ayah Menjadi Pengemis Tanpa Diketahui RetnoDokumen2 halamanAyah] Ayah Menjadi Pengemis Tanpa Diketahui RetnoAmaliaBelum ada peringkat
- Cerita Malin KundangDokumen2 halamanCerita Malin KundangSilvia AnggrainiBelum ada peringkat
- Kisah Asal Mula Nama Kota CianjurDokumen4 halamanKisah Asal Mula Nama Kota CianjurMoka KasimBelum ada peringkat
- Berlian Yang Hilang - Rachmat Sabit UddinDokumen4 halamanBerlian Yang Hilang - Rachmat Sabit UddinindahBelum ada peringkat
- Z Jfek Ry 7Dokumen16 halamanZ Jfek Ry 7Dinda Kirana0% (1)
- Cila Yang Malang Yang Ku SayangDokumen5 halamanCila Yang Malang Yang Ku SayangEmil FathirBelum ada peringkat
- Si Merah ApiDokumen4 halamanSi Merah ApiAldhila Putri FauzaniBelum ada peringkat
- KISAH DAN MISTERIKU - Selly Rumzatul Inayah - BSA-1ADokumen6 halamanKISAH DAN MISTERIKU - Selly Rumzatul Inayah - BSA-1Aalfi staniyahBelum ada peringkat
- Cerpen 'IKATAN'Dokumen8 halamanCerpen 'IKATAN'Hanif M. ABelum ada peringkat
- Bahan Ajar Kutipan CerpenDokumen6 halamanBahan Ajar Kutipan CerpenLiana RandikaBelum ada peringkat
- CERPEN LATIHAN MTsDokumen4 halamanCERPEN LATIHAN MTsAhmad BadarudinBelum ada peringkat
- Tugas Cerpen Bahasa Indonesia Sang SuryaDokumen5 halamanTugas Cerpen Bahasa Indonesia Sang Suryasaffana ayu azzahraBelum ada peringkat
- Safna Puspita Sari-Bidadari DuniaDokumen4 halamanSafna Puspita Sari-Bidadari DuniaSafna El lasemyBelum ada peringkat
- Cerpen BindoDokumen12 halamanCerpen BindoNURSYAFITRY AZ-ZAHRABelum ada peringkat
- Pulang KampungDokumen2 halamanPulang KampungJonathan ErikBelum ada peringkat
- Aku Terlahir Dari Keluarga Yang SederhanaDokumen4 halamanAku Terlahir Dari Keluarga Yang SederhanaJohan Delarey SihalohoBelum ada peringkat
- LombaCerpen - Siluet Kenyataan - Arya Hasa KuswiratamaDokumen3 halamanLombaCerpen - Siluet Kenyataan - Arya Hasa KuswiratamaAryaHakushoBelum ada peringkat
- Cerita JagaDokumen70 halamanCerita JagaRizky IlhamBelum ada peringkat
- Belanga KeramatDokumen3 halamanBelanga Keramatlitmatch instituteBelum ada peringkat
- Sebuah Lorong Di KotakuDokumen7 halamanSebuah Lorong Di KotakuSuasti Ayu T33% (6)
- DavidDokumen3 halamanDavidMuhammad David Al Fajri.Belum ada peringkat
- Cerpen NadiaDokumen5 halamanCerpen NadiaYudhi AuliaBelum ada peringkat
- HikayatDokumen2 halamanHikayatfarrelfjrsBelum ada peringkat
- Script PodcastDokumen2 halamanScript PodcastJenni FriskaBelum ada peringkat
- Arwah Ke 10Dokumen5 halamanArwah Ke 10Kang RudiBelum ada peringkat
- Mentari kembali bersinarDokumen3 halamanMentari kembali bersinarsintadevi puspitsariBelum ada peringkat
- Cerpen NovitaDokumen4 halamanCerpen Novitazmw3r_anharBelum ada peringkat
- 34 - PART 1 - Si Jundai Lubuak PusaroDokumen41 halaman34 - PART 1 - Si Jundai Lubuak Pusarozd55h2754kBelum ada peringkat
- Saat Ku Mudik Zia RADokumen4 halamanSaat Ku Mudik Zia RARafabian Rauf CannavaroBelum ada peringkat
- Terima Kasih MaDokumen13 halamanTerima Kasih MaMaria HanimBelum ada peringkat
- Sahabat SejatiDokumen86 halamanSahabat Sejatithania luthfyahBelum ada peringkat
- KULIAH BERSAMA NENEKDokumen4 halamanKULIAH BERSAMA NENEKNur HanifahBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa Indonesia 4 HermanDokumen8 halamanTugas Bahasa Indonesia 4 Hermanhermansaripudin11Belum ada peringkat
- MASA LALU YANG MENCERAHKAN MASA DEPANDokumen12 halamanMASA LALU YANG MENCERAHKAN MASA DEPANPrinsca Syantik100% (1)
- IMPIAN YANG TERLUPAKANDokumen6 halamanIMPIAN YANG TERLUPAKANDian Gerimis Kesuma100% (2)
- HOPEDokumen3 halamanHOPEAditiya HafidzBelum ada peringkat
- Cerita Rakyat SumbarDokumen14 halamanCerita Rakyat SumbarjulBelum ada peringkat
- RAWONDokumen11 halamanRAWONMeylia CatherineBelum ada peringkat
- Petuah IbuDokumen5 halamanPetuah Ibughoutsiislahiyah nurrohmahBelum ada peringkat
- RESEPBUKUMASAKANDokumen3 halamanRESEPBUKUMASAKANAlexandra JuliantBelum ada peringkat
- Kebahagiaan KeluargaDokumen2 halamanKebahagiaan KeluargaLee ComputerBelum ada peringkat
- Roda HidupkuDokumen5 halamanRoda HidupkuPatikaBelum ada peringkat
- 36 - Si Jundai Lubuak PusaroDokumen53 halaman36 - Si Jundai Lubuak Pusarozd55h2754kBelum ada peringkat
- Si MC (Main Story)Dokumen82 halamanSi MC (Main Story)Toni ArdiansahBelum ada peringkat
- Cerpen - Silfi Atma Wijayanti - SMAN 1 Badegan - Jawa TimurDokumen5 halamanCerpen - Silfi Atma Wijayanti - SMAN 1 Badegan - Jawa Timursilfasilfi silfasilfiBelum ada peringkat
- Cerpen Detik Terakhir@Dokumen5 halamanCerpen Detik Terakhir@Azam KaitoBelum ada peringkat
- KeluargaAdalahHartayangPalingBerhargaDokumen2 halamanKeluargaAdalahHartayangPalingBerhargaLaedi gurusdn2woncoBelum ada peringkat
- AYAHKUDokumen9 halamanAYAHKUDwiiBelum ada peringkat
- CERPENDokumen8 halamanCERPENJasmine Desnita Amelinda SBelum ada peringkat
- Liburan Ke Rumah NenekDokumen6 halamanLiburan Ke Rumah NenekMyprint BangkinangBelum ada peringkat
- Damardokumen (1) - 2Dokumen56 halamanDamardokumen (1) - 2CharlotteakkiBelum ada peringkat
- Tentangku "Int-WPS OfficeDokumen21 halamanTentangku "Int-WPS Officeemil aidinBelum ada peringkat
- Jawa Timur Gudang Rempah - Docx - TIFANIDokumen4 halamanJawa Timur Gudang Rempah - Docx - TIFANImuhamricahyadiBelum ada peringkat
- Novel Tessa PatikaDokumen16 halamanNovel Tessa PatikaSdnsepuluh Muara EnimBelum ada peringkat
- CINTA_SEBENARDokumen7 halamanCINTA_SEBENARFayadNaufalBelum ada peringkat
- Cerpen Kelompok 5Dokumen5 halamanCerpen Kelompok 5keandrehadian4Belum ada peringkat
- MicroscopeDokumen1 halamanMicroscopewahyu sugitoBelum ada peringkat
- MENGEMBANGKAN BAKATDokumen3 halamanMENGEMBANGKAN BAKATwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Konferensi Meja BundarDokumen6 halamanKonferensi Meja Bundarwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Konferensi Meja BundarDokumen6 halamanKonferensi Meja Bundarwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Fathu MakahDokumen5 halamanFathu Makahwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Kuliner PapuaDokumen8 halamanKuliner Papuawahyu sugitoBelum ada peringkat
- Makalah PernikahanDokumen15 halamanMakalah Pernikahanwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945Dokumen7 halamanUndang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945M TaufikBelum ada peringkat
- Konduktor Dan IsolatorDokumen10 halamanKonduktor Dan Isolatorwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Lima ElangDokumen1 halamanLima Elangwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Makalah Suku NauluDokumen8 halamanMakalah Suku Nauluwahyu sugito100% (2)
- Ceramah Tentang Sunnah RasulDokumen2 halamanCeramah Tentang Sunnah Rasulwahyu sugito50% (2)
- Nuwo SesatDokumen2 halamanNuwo Sesatwahyu sugitoBelum ada peringkat
- BOLABESARDokumen8 halamanBOLABESARwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Makna Pancasila Sila Ke 3Dokumen5 halamanMakna Pancasila Sila Ke 3wahyu sugitoBelum ada peringkat
- Makna Pancasila Sila Ke 3Dokumen5 halamanMakna Pancasila Sila Ke 3wahyu sugitoBelum ada peringkat
- Cerita Rakyat NusantaraDokumen7 halamanCerita Rakyat Nusantarawahyu sugito100% (1)
- Pengertian Macam Macam Topologi Jaringan KomputerDokumen5 halamanPengertian Macam Macam Topologi Jaringan KomputerBangkit Eko PutroBelum ada peringkat
- Anak EmasDokumen3 halamanAnak Emaswahyu sugitoBelum ada peringkat
- Ws. Rendra PuisiDokumen10 halamanWs. Rendra Puisiwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Makalah 3Dokumen13 halamanMakalah 3wahyu sugitoBelum ada peringkat
- Sepatu MerahDokumen11 halamanSepatu Merahwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Akar Ke NDokumen2 halamanAkar Ke Nwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Alat MikroskopDokumen2 halamanAlat Mikroskopwahyu sugitoBelum ada peringkat
- 10 Penyakit Pada Alat Reproduksi Wanita Dan PriaDokumen4 halaman10 Penyakit Pada Alat Reproduksi Wanita Dan Priawahyu sugitoBelum ada peringkat
- Kliping Kerajinan TanganDokumen16 halamanKliping Kerajinan Tanganwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Proposal Bab 3Dokumen16 halamanProposal Bab 3wahyu sugitoBelum ada peringkat
- Kolonial PenjajahDokumen8 halamanKolonial Penjajahwahyu sugitoBelum ada peringkat
- Perangkat KerasDokumen4 halamanPerangkat Keraswahyu sugitoBelum ada peringkat


![Ayah] Ayah Menjadi Pengemis Tanpa Diketahui Retno](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/557594609/149x198/26d7bb90b0/1710543272?v=1)