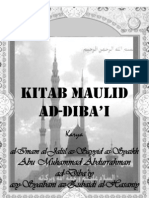Relasi Agama Dan Negara
Diunggah oleh
Candu Naraya LanaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Relasi Agama Dan Negara
Diunggah oleh
Candu Naraya LanaHak Cipta:
Format Tersedia
16
BAB II
RELASI AGAMA DAN NEGARA
A. Konsepsi Islam Tentang Negara
Perbincangan mengenai hubungan agama dan negara merupakan
persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (discourse) yang terus
berkepanjangan di kalangan para ahli.
1
Hal ini disebabkan oleh perbedaan
pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau
negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan, menurut Syafii Maarif
(1935 M.), Prof. Dr. Harun Nasution (1919-1998 M.), seorang ahli teologi
Islam pernah mengatakan, bahwa persoalan yang telah memicu konflik
intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait
dengan masalah hubungan agama dengan negara.
2
Menurut Deliar Noer (1926 M.), Islam setidaknya meliputi dua aspek
pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).
3
Akan tetapi untuk
mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan
suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak
holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah
untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari
1
Dede Rosyada, et al., Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Cet. Ke-1, 2000, hlm.
58.
2
Ahmad Syafii Maarif, Pengantar dalam M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran
Islam Politik, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1999, hlm. ix.
3
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesi 1900-1942, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-8,
1996, hlm.1.
17
mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama
dan negara.
4
Perdebatan dan diskusi mengenai ini sesungguhnya lebih terletak pada
tataran konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya.
5
Dimana
perdebatan ini muncul dilatar belakangi oleh teks-teks agama sendiri yang
pola hubungannya dikotomis. Agama dan negara seringkali dikesankan
sebagai dua wilayah yang berhadapan. Misalnya, hubungan dunia akhirat atau
al dunya wa al-din. Baik al-Quran maupun hadits banyak menyebut dua hal
tersebut. Bahkan sering dijumpai ungkapan al Islam huwa al-din wa al-
daulah.
6
Kesan berhadap-hadapan seperti itulah yang kemudian memunculkan
kontroversi yang tajam dan keras di sekitar konsep hubungan agama dan
negara. Sehingga menurut, Azyumardi Azra (1955 M.), ketegangan perbedaan
hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang agak canggung
antara Islam sebagai agama (din) dan negara (daulah).
7
Dari sini lalu akan
timbul pertanyaan: Apakah Islam mempunyai konsep tentang negara?. Untuk
menjawab tentang pertanyaan ini kiranya sangat perlu kita menengok ke
belakang, perjalanan sejarah pemikiran para ulama dalam konteks ini.
Memang dalam Islam, negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara.
Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi
4
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam
Konstituante, Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 15.
5
Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, Yogyakarta: LKiS, Cet. Ke-1,
hlm. 2000, hlm. 88.
6
Ibid.
7
Dede Rosyada, et al., Op. Cit., hlm. 61.
18
bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, Walaupun
Islam mempunyai konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi al-Quran belum
menjelaskan secara rinci tentang bentuk dan konsepsi tentang negara Islam.
8
Ada sederet teoritisi Islam yang mewakili Zaman klasik yang bisa
disebutkan, antara lain: Ibn Abi Rabi (833-842 M.), hidup pada abad ke-9
dengan karyanya yang bertitel Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik
menekankan pada ketuhanan dan memadukannya dengan teori tentang asal
usul negara; Al-Farabi (257-339 M.) dalam karyanya Ara-Ahl al-Madinah al-
Fadhilah dan Al- Siyasah al-Madaniyyah mengatakan bahwa yang dapat dan
boleh menjadi kepala negara adalah anggota masyarakat atau menusia yang
paling sempurna (al-Insan al-Kamil); Al-Mawardi (975-1058 M.) dengan
karyanya Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Qawwain al-Wuzarah, dan Siyasah al-
Malik, menekankan hubungan yang demikian erat antara Syariah dan
Imamah; Imam al-Ghozali (1058-1111 M.) dengan karyanya Ihya Ulum al-
Din, melihat agama sebagai orde sosio-politik dan penguasa sebagai
pemeliharanya; Ibnu Taimiyyah (1263-1328 M.) dengan karyanya Al-Siyasah
al-Syariyyah fi-Ishlah al-Rai wa al-Raiyyah , ia dipenjarakan karena
mempertahankan pendapatnya tentang Siyasah Syariyah (politik atas dasar
syariat) dan Ibnu Khaldun (1332-1406 M.) dengan karyanya Muqaddimah
yang menyatakan bahwa siyasah berdasarkan al-din adalah berguna untuk
dunia dan akhirat.
9
8
M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Op. Cit., hlm. 1.
9
Ahmad Syafii Maarif, Pengantar dalam M. Rusli Karim, Ibid., hlm. ix-x.
19
Melihat tulisan para teoretisi di atas dapat dipahami bahwa secara
eksplisit maupun implisit menyatakan tujuan dibentuknya suatu negara tidak
semata-mata karena untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusiawi belaka,
melainkan untuk kebutuhan ruhaniyyah dan ukhrawiyah. Untuk kepentingan
ini agama dijadikan landasan dan dijadikan sebagai fondasi dan kehidupan
kenegaraan. Dari sinilah kemudian muncul jargon politik Islam: al-Islam Din
wa Daulah ( Islam adalah agama dan negara ).
10
Dari konsep ini berarti tidak
ada pemisahan antara agama dan negara. Sementara di sisi lain ada yang
bersikap sekuler, yang secara tegas menyatakan pemisahan antara agama dan
negara, dan tidak ada kewajiban untuk membangun sebuah negara Islam di
dunia ini. Bagi yang memegang konsep ini memandang bahwa agama adalah
urusan akhirat, sedangkan negara urusan dunia.
11
Sebetulnya, konsep negara Islam itu sendiri menurut Nurcholis Madjid
(1939 M.) adalah merupakan gejala modern.
12
Sebagaimana ungkapan Amin
Rais (1944 M.), bahwa dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara
Islam ini setelah berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki.
13
Selama
penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslimin tidak sempat berpikir
tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Nurcholis Madjid, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial
Politik Kontemporer, Editor: Edy A. Effendi, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 158.
13
M. Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Editor: Hamid Basyaib,
Bandung: Mizan, Cet. Ke-5, 1994, hlm. 36.
20
pelbagai masalah.
14
Namun kejelasan tentang ada dan tidaknya konsep yang
definitif mengenai masalah ini belum bisa dipastikan begitu saja.
Untuk dapat menjawab persoalan tentang ada dan tidaknya konsepsi
Islam yang rinci sekaligus kewajibannya bagi umat Muslim mendirikan
sebuah negara Islam dengan benar, kita harus lebih dahulu memahami ciri
khusus Islam dari asal kitab sucinya. Kemudian untuk mempermudah
pembahasan selanjutnya, tidaklah lupa kami jelaskan dahulu apakah yang
dimaksud dengan negara itu sediri.
Dr. Bonar sebagaimana dikutip oleh M. Yusuf Musa mendefinisikan
bahwa negara adalah suatu kesatuan hukum yang bersifat langgeng, yang di
dalamnya mencakup hak institusi sosial yang melaksanakan kekuasaan hukum
secara khusus dalam menangani masyarakat yang tinggal dalam wilayah
tertentu, dan negara memiliki hak-hak kedaulatan, baik dengan kehendaknya
sendiri maupun dengan jalan penggunaan kekuatan fisik yang dimilikinya.
15
Dalam buku yang sama, seorang penulis Mesir, yaitu Dr. Wahid Rafat,
mendefinisikan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang
tinggal pada suatu wilayah tertentu di belahan bumi ini yang tunduk pada
suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggungjawab memelihara
eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingannya dan kemaslahatan
umum.
16
Sementara Dr. Abu Hamid Mutawalli
17
, mendefinisikan bahwa
negara adalah suatu institusi abstrak yang terwujudkan dalam sebuah
14
Ibid.
15
M. Yusuf Musa, Nidhamul Hukmi fil Islam, Terj. M. Thalib, Politik dan Negara dalam
Islam, Kairo, Cet. Ke-2, 1963, hlm. 24.
16
Ibid., hlm.25.
17
Ibid.
21
konstitusi untuk suatu masyarakat yang menghuni wilayah tertentu dan
memiliki kekuasaan umum.
Dalam Islam, menurut Javid Iqbal, negara didirikan atas dasar prinsip-
prisip tertentu yang ditetapkan al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad. Prinsip
pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah
karena Ia yang telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum
Islam ditetapkan oleh Allah dalam al-Quran dan Sunah Nabi, sedangkan
sunah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang al-Quran. Ketentuan-
ketentuan ini untuk membimbing umat manusia, diturunkan kepada para Nabi
dari waktu dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Saw.
18
Dalam teori, negara Islam adalah merupakan negara Allah, dan kaum
muslim merupakan partai-Nya (hizbullah).
19
Hal ini, menurut Javid Iqbal,
berdasarkan konsep tentang kebahagiaan (falah), yaitu: (1) harus berusaha
untuk keberhasilan masyarakat muslim di dunia ini serta mempersiapkannya
untuk keberhasilannya di akhirat; (2) untuk menyadari tujuan-tujuan tersebut,
masyarakat muslim (ummah) harus berdasarkan prinsip-prinsip persamaan
hak, solidaritas dan kemerdekaan.
20
Namun yang menjadi permasalahan bagi umat Islam dari zaman klasik
hingga abad modern ini adalah bahwasannya al-Quran tidak menetapkan cara
hidup tertentu untuk masyarakat muslim. Begitu pula tentang masalah poitik,
khususnya hubungan agama dan negara. Semasa empat Al-Khulafa al-
18
Hakim Javid Iqbal, Konsep Negara Menurut Islam dalam Mumtaz Ahmad (ed.),
Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung: Mizan, Cet. Ke-3, 1996, hlm. 57.
19
Ibid., hlm. 58.
20
Ibid.
22
Rosyidin tidak terdapat suatu pola yang baku mengenai cara pengangkatan
khalifah atau kepala negara.
21
Dalam sejarah empat khalifah tersebut, tidak
juga terdapat petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa
jabatan seorang kepala negara. Mereka semua mengakhiri masa tugasnya
karena wafat.
22
Keragaman dalam praktek tersebut mencuatkan pula konsep dan
pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam.
Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman
yang tidak sama terhadap hubungan agama dan negara yang dikaitkan dengan
kedudukan Nabi dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan
polotik dan pemerintahan.
Tentang hubungan agama dan negara ada terdapat tiga kelompok
pemikiran. Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga
kegamaan dan sekaligus lembaga politik. Karena itu kepala negara adalah
pemegang kekusaan dan agama. Kelompok kedua mengatakan bahwa negara
adalah lembaga keagamaan tetapi mempunyai fungsi politik. Karena itu
kepala negara mempunyai kekuasaan negara yang berdimensi politik.
Kelompok ketiga menyatakan bahwa negara adalah lembaga politik yang
sama sekali terpisah dari agama. Kepala negara, kerenanya, hanya mempunyai
kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja.
23
21
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI
Press, Cet. Ke-2, 1990, hlm. 30.
22
Ibid., hlm. 31.
23
J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1995, hlm. xii.
23
Demikian dalam pemahaman dan penafsiran ajaran Islam kaitannya
dengan politik dan pemerintahan juga terdapat tiga golongan. Golongan
pertama menyatakan, di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan,
karena Islam adalah agama yang paripurna. Golongan kedua mengatakan di
dalam Islam tidak ada sistem politik dan pemerintahan, tetapi terdapat
seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara,
24
mengandung ajaran-
ajaran dasar tentang kehidupan masyarakat dan bernegara. Sedangkan
golongan ketiga berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak terkait dengan
politik dan pemerintahan. Ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid dan
pembinaan akhlaq dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan.
25
Opini tentang teori politik Islam seperti di atas kiranya telah dikenal oleh
masyarakat luas, kalangan muslim khususnya. Berkenaan tentang hubungan
agama dan negara tersebut, setidaknya lebih dikenal dengan istilah tiga
paradigmatik pola hubungan agama dan negara, yang diutarakan dan
dipertahankan oleh tokoh inspiratornya masing-masing. Dengan wacana
inilah, akan dijelaskan secara lebih terang mengenai konsepsi Islam tentang
negara. Adapun ketiga paradigma tersebut yaitu; integralistik, simbiostik, dan
sekularistik.
a. Paradigma Integralistik
Paradigma pertama ini mengajukan konsep bersatunya agama
dan neagra. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini tidak bisa
24
Munawir Sjadzali, Op. Cit., hlm. 2.
25
J. Suyuti Pulungan, Loc. Cit.
24
dipisahkan (integrated), wilayah agama juga meliputi politik atau
negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan
lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara
diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi ( devine cofereignty),
karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.
26
Jadi, pandangan ini bersifat teokratis.
27
Konsekuensi lebih lanjut dari pandangan ini adalah bahwa aturan
kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-hukum Tuhan (syariah).
Ayat-ayat al-Quran yang sering dikumandangkan sebagai legitimasi
bagi penerapan hukum Tuhan ini misalnya:
.,, , :, = , ,- , , , '
Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
28
Bagi kelompok ini, syariah selalu dipahami sebagi totalitas yang
par exellent kaffah kamilah bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan
dan kemanusiaan. Sementara negara berfungsi untuk menjalankan
syariah. Karena legitimasi politik negara harus berdasarkan syariah,
maka sistem kenegaraan menurut sistem ini bersifat teokratis.
29
Pandangan ini kebanyakan dianut oleh kelompok Syiah.
30
Paradigma pemikiran politik Syiah memandang bahwa negara (istilah
26
M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam dalam Andito (Abu Zahra) (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia,
Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 45-46.
27
Ahmad Suaedy (ed.), Op. Cit., hlm. 89.
28
QS. Al-Maidah: 44, Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang:
Karya Toha Putra, hlm. 215.
29
Ahmad Suaedy (ed.), Op. Cit., hlm. 90.
30
Ibid.
25
yang relevan dangan hal ini adalah Imamah)
31
atau kepemimpinan
adalah lembaga kenegaraan dan mempunyai fungsi keagamaan.
Menurut Syiah juga, hubungan legitimasi keagamaan berasal dari
Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad,
legitimasi garis berdasarkan pada hukum Allah, dan hal ini hanya
dimiliki oleh para keturunan Nabi.
32
Penyatuan agama dan negara, juga menjadi anutan kelompok
fundamentalis Islam
33
yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai
Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma
fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yakni bahwa Islam
meliputi seluruh aspek kehidupan.
34
Tokoh kelompok ini yang
menonjol adalah, Al-Maududi (1903-1979 M.). Bagi Al-Maududi
syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syariah
adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan
kemasyarakatan. Sehingga menurutnya, Islam harus dibangun di atas
perundang-undangan syariah yang dibawa Nabi dari Tuhan dan harus
diterapkan dalam kondisi apapun.
35
Syariah inilah yang mengatur manusia, perilakunya dan
hubungan-hubungan satu sama lain di dalam segala aspek, baik
31
Imamah adalah gerakan dan prinsip politik kaum Syiah yang mewajibkan penguasa
negaraitu seorang imam dan berkeyakinan bahwa imam itu mashum serta masih keturunan Ali
Ibnu Abi Tholib. Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Palembang: Universitas
Sriwijaya, Cet. Ke-1, 2001, hlm. 435.
32
Andito (Abu Zahra) (ed.), Loc. Cit.
33
Istilah Fundalisme ini oleh golongan tertentu diberikan kepada orang-orang Islam yang
menginginkan memperlakukan semua ajaran syariat Islam didalam perikehidupan. Mochtar
Effendy, Op. Cit., hlm.197.
34
Andito (Abu Zahra) (ed), Op. Cit., hlm. 47.
35
Ahmad Suaedy (ed.), Op. Cit., hlm. 91.
26
bersifat individu, keluarga, masyarakat, serta hubungannya dengan
negara.
36
Karena memandang wajib ditegakkannya hukum Allah, maka
demi tercapainya misi tersebut haruslah ditegakkan negara Islam. Dan
dalam hal ini, menurut Al-Maududi, harus didasarkan pada empat
prinsip dasar, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan, menerima otoritas
Nabi Muhammad, memiliki status wakil Tuhan, dan menerapkan
musyawarah.
37
Menurut Al-Maududi, prinsip dasar Islam adalah bahwa umat
manusia, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus
melepaskan semua hak pertuanan, pembuatan undang-undang dan
pelaksanaan kedaulatan atas orang lain. Kedaulatan dalam Islam
menurut al-Maududi, bukan di tangan manusia, tetapi di tangan
Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan tersebut mencakup semua bidang
kehidupan.
38
Dengan demikian prinsip-prinsip pokok negara Islam menurut
Al-Maududi ialah; kedaulatan penuh ada di tangan Allah, dimana yang
lain adalah hamba-Nya; hukum yang berlaku hanyalah hukum Allah,
dan hanya Dia yang berwenang membuat atau merubahnya; negara
Islam tersebut haruslah dipimpin oleh pemerintah yang benar-benar
36
M. Yusuf Musa, Op. Cit., hlm. 23.
37
Andito (Abu Zahra) (ed.), Op. Cit., hlm. 47.
38
Sudirman Tebba, Islam Menuju Era Reformasi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya,
Cet. Ke-1, 2001, hlm. 6.
27
bersikap patuh dalam kedudukannya sebagi lembaga politik yang
dibentuk untuk memberlakukan hukum-hukum Allah.
39
Kemudian, nama yang lebih tepat untuk negara Islam, menurut
Al-Maududi adalah kerajaan Allah, yang dalam bahasa inggris
disebut theocracy. Akan tetapi, Al-Maududi menambahkan, theocracy
Islam berbeda dengan budaya Barat yang menekan dan memaksa
hukum buatannya atas nama Tuhan. Menurut Maududi, pemerintahan
semacam itu bersifat setani, bukan bersifat Ilahi (satanic rather than
divine).
40
Theocracy dalam Islam diperintah oleh seluruh rakyat
muslim. Dimana seluruh rakyat Islam menjalankan roda kenegaraan
sesuai dengan petunjuk kitab Allah dan contoh praktik Rasul-Nya. Al-
Maududi menamakan sistem pemerintahan ini dengan theo-
democracy
41
-- yakni suatu pemerintahan demokrasi yang berdasarkan
ketuhanan, karena dalam pemerintahan ini rakyat Islam diberi
kedaulatan di bawah wewenang Allah.
Secara teoritis, penguasa sebuah negara Islam ini tidak memiliki
kekuasaan mutlak, demikian juga parlemen ataupun rakyat, karena
kekuasaan mutlak itu hanya milik Allah semata, dan hukum-Nya harus
tetap berkuasa. Memakai istilah kini, konstitusi Islam hanya
mempunyai dua organ penting: eksekutif dan yudikatif. Organ ketiga
39
Abu Ala Maududi Teori Politik Islam dalam Khurshid Ahmad (ed.), Pesan Islam,
Bandung: Pustaka, Cet. Ke-1, 1983, hlm. 193.
40
M. Amin Rais, Pengantar dalam Abu Ala al-Maududi, Al-Khilafah wa Al-Mulk, Terj.
Muhammad Al-Baqir Khilafah dan Kerajaan: Efaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam,
Bandung: Mizan, Cet. Ke-6, 1996, hlm. 22.
41
Khurshid Ahmad (ed.), Loc. Cit.
28
yang memungkinkan -- yaitu, legislatif -- secara konstitusional tidak
diberi batasan, karena undang-undang telah ditetapkan di dalam al-
Quran oleh Allah.
42
Tugas pemerintah adalah untuk
melaksanakannya, bukan merubahnya untuk kepentingan-
kepentingannya sendiri.
Sistem pemerintahan Islam itu sendiri adalah sebuah sistem yang
yang lain sama sekali dengan sistem-pemerintahan yang ada di dunia.
Baik dari aspek yang menjadi landasan berdirinya, standar hukum
yang dipergunakan, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan
wujud negara. Taqiyuddin An Nabhani (1909-1977 M.)
mengemukakan bahwa pemerintahan Islam bukanlah monarki, bukan
republik, bukan kekaisaran dan bukan federasi. Akan tetapi,
menurutTaqiyuddin, sistem pemerintahan Islam ini adalah sistem
khilafah.
43
Menurut Taqiyuddin lebih lanjut, mendirikan khilafah adalah
wajib bagi seluruh muslimin di seluruh dunia. Sedangkan
melaksanakannya seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain,
yang telah difardlukan oleh Allah SWT.
44
Demi tegaknya hukum Allah
dan syariat Islam, kaum muslimin tidak boleh mengabaikannya,
karena ini telah menjadi ketentuan sunah Nabi. Demikian pula
42
Mumtaz Ahmad (ed.), Op. Cit., hlm. 47.
43
Taqiyuddin An-Nabhani, Nidhomul Hukmi fil Islam, Terj. Moh. Maghfur Wahid Sistem
Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik, Bangil: Al Izzah, Cet. Ke-1, 1996,
hlm. 31-35.
44
Ibid.
29
pelaksanaannya dalam pemerintahan nanti haruslah berdasarkankan
kepada al-Quran dan Hadits sebagai pedoman.
45
Demikian kentalnya ragam pemikiran tersebut dengan otoritas
kedaulatan Tuhan, serta menganggap ajaran Rosulullah sebagai agama
yang komprehensif, maka kemudian muncullah istilah al Islam huwa
al-din wa al-daulah dalam pelataran politik Islam. Dan sebagai
komitmen logis dari paradigma integralistik ini, negara Islam harus
ditegakkan demi terlaksananya hukum-hukum Allah dengan dipimpin
seorang imam atau khalifah.
b. Paradigma Simbiostik
Dalam pandangan ini, konsep hubungan agama dan negara
terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini,
agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat
berkembang.
46
Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi
negara, sementara pada posisi lain negara juga tidak bisa dibiarkan
berjalan sendiri tanpa agama, karena keterpisahan agama dari negara
dapat menimbulkan kekacauan dan a-moral.
47
Ibnu Taimiyah (1263-1328 M.), seorang tokoh Sunni salafi,
mengatakan: agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa
kekuasan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya.
45
Ibid.
46
M. Arskal Salim G.P., Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia dalam Abdul
Munim D.Z. (ed.), Islam di Tengah Arus Transisi, Jakarta: Kompas, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 8.
47
Ahamad Suaedy (ed.), Op. Cit., hlm. 92.
30
Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah
organisasi yang tiranik.
48
Ia juga mengatakan bahwa wilayah
organisasi politik bagi persoalan kahidupan sosial manusia merupakan
keperluan agama yang terpenting. Karena tanpanya, agama tidak akan
tegak kokoh.
49
Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa
antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi
saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.
Pandangan simbiostik tentang agama dan negara ini juga dapat
dipahami dalam pemikiran al-Mawardi (975-1059 M.). Dalam
kitabnya Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah, ia
menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan
instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama
dan pengaturan dunia.
50
Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia
merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan
secara simbiostik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi
kenabian. Ia memposisikan negara sebagai lembaga politik dengan
sanksi-sanksi kegamaan.
51
Menurut al-Mawardi dalam negara tersebut harus ada satu
pemimpin tunggal sebagai penganti Nabi untuk menjaga
48
Ibid.
49
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi
Terpimpin, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 180.
50
Imam al-Mawardi, Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah, Terj. Abdul
Hayyie dan Kamaluddin Nurdin Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam,
Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 15.
51
Miftah AF. Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Fiqh Siyasi dalam Al-
Ahkam, Volume XIII Edisi II, 2001, hlm. 26.
31
terselenggaranya ajaran agama dan memegang kendali politik, serta
membuat kebijakan yang berdasarkan syariat agama.
52
Sebagaimana
dikutip dalam Ahmad Suaedy (ed.), secara tegas ia mengatakan:
Sungguh, Tuhan telah mendelegasikan untuk satu komunitas,
seorang pemimpin yang diangkat-Nya sebagai penerus
kepemimpinan Nabi. Melaluinya (kepala negara) dia melindungi
agama. Tuhan mempercayakan kepadanya pengaturan
pemerintahan (kenegaraan) agar semua aturan yang diberlakukan
sesuai dengan agama dan supaya pendapat dan pikiran masyarakat
mengikuti pandangan yang dipertanggungjawabkan secara
otoritatif.
53
Pemikir lain yang senada ialah al-Ghozali (1058-1111 M.). Ia
mengisyaratkan hubungan pararel antara agama dan negara, seperti
dicontohkan pararelisme Nabi dan raja. Menurut al-Ghozali, Jika
Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka,
maka Dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka
kakuatan Ilahi. Keduanya memiliki tujuan yang sama: kemaslahatan
kehidupan manusia.
54
Pararelisme antara Nabi dengan raja menunjukkan adanya
hubungan simbiostik antara keduanya. Seorang raja atau pemimpin
negara mempunyai status yang tinggi dalam hubungannya dengan
Nabi. Ini berarti bahwa pemimpin negara mempunyai kedudukan yang
strategis dalam menciptakan nuansa kegamaan dalam lembaga negara
Pandangan yang dianut oleh sebagian besar kaum Sunni ini
memperlihatkan secara jelas bahwa kekuasaan kepala negara adalah
52
Almawardi, Op. Cit., hlm. 14.
53
Ahmad Suaedy (ed), Op. Cit., hlm. 93.
54
Andito (Abu Zahra) (ed.), Op. Cit., hlm. 48.
32
pemberian dan berasal dari Tuhan. Kekuasaan otoritatif kepala negara
ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan agama,
melainkan juga urusan keduniawian yang berdimensi politik.
55
Secara sepintas pernyataan ini tidak berbeda dengan konsep
negara integralistik seperti talah dikemukakan di atas. Akan tetapi
bacaan secara kritis atas wacana ini akan menemukan perbedaan yang
cukup signifikan. Teori simbiostik membiarkan tuntutan-tuntutan
realitas sosial politik yang berkembang, tetapi agama kemudian
memberikan justifikasinya. Agama tidak harus menjadi dasar negara.
Negara, Dalam pandangan ini tetap merupakan lembaga politik yang
mandiri. Dengan demikian, paradigma simbiostik di satu pihak bersifat
teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik.
Kenyataan ini, misalnya, juga muncul di dalam pandangan Ibnu
Taimiyah. Menurutnya bahwa agama tidak dapat ditegakkan dengan
tidak ada pemerintah. Dalam upayanya memerintah manusia adalah
sebesar-besarnya kewajiban agama, dan hendaknya dipimpin oleh
seseorang yang bertanggung jawab dan menjalankan hukum-hukum
Allah.
56
Dalam menentukan dan mengangkat kepala negara haruslah
berdasarkan pilihan rakyat. Dalam arti lain, rakyat memiliki kedaulatan
yang signifikan untuk menentukan sistem politik negara.
Jadi, pandangan simbiostik tetap memberi peluang bagi hak-hak
masyarakat, meskipun dibatasi dengan norma-norma agama. Perlu
55
J. Suyuti Pulungan, Loc. Cit.
56
Ahmad Shalaby, Studi Komprehensif Tentang Agama Islam, Surbaya: PT. Bina Ilmu, Cet.
Ke-1, 1988, hlm. 249.
33
dikemukakan bahwa hak-hak rakyat untuk menentukan kepala negara
dalam pandangan paradigma ini ditempuh melalui lembaga
representasi yang disebut ahl halli wal aqdi, dengan syarat-syarat
tertentu yaitu adil, ahli rayi (ilmuwan) dan memiliki kualifikasi moral
seorang pemimpin. Menurut al-Mawardi juga harus memenuhi syarat
khusus, misalnya; baik panca indra, tiada cacat anggota tubuhnya, dan
mempunyai buah pikiran yang bagus yang mengembangkan rakyat.
57
Jelaslah kiranya, bahwa paradigma ini telah menawarkan
formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis.
Meskipun syariat agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi
tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut
andil dalam menentukan kondisi sosial politik negara.
c. Paradigma Sekularistik
Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun
hubungan simbiostik antara agama dan negara.
58
Sebagai gantinya,
paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan
negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak
pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi
Islam akan bentuk tertentu dari negara.
59
Menurut paradigma ini Islam
hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal
yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara
57
Ibid., hlm. 252.
58
Abdul Munim D.Z. (ed.), Op. Cit., hlm. 9.
59
Ibid.
34
pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing
masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya
sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu
sama lain melakukan intervensi.
Berdasarkan pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum
positif yang berlaku adalah hukum yang benar benar berasal dari
kesepakatan manusia malalui social contrac dan tidak ada kaitannya
dengan hukum agama (syariah).
60
Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq
(1888-1966 M.), seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Pada tahun
1925, Ali Abdul Raziq menerbitkan sebuah risalah yang berjudul Al-
Islam wa Usul al-Ahkam
61
,yang banyak menimbulkan kontroversi. Isu
sentral dari risalahnya, seperti dikutip oleh Muhammad Diya ad Din
Rais adalah bahwa Islam tidak mempunyai kaitan apa pun dengan
sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafaur
Rasyidin, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman,
tetapi sebuah sistem yang duniawi.
62
Dalam kaitan di atas, Ali Abdur Raziq bermaksud membedakan
antara agama dan politik. Dia memberikan alasan yang cukup panjang
dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan bahwa
tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad seperti melakukan perang,
60
Dede Rosyada, et al., Op. Cit., hlm. 63-64.
61
Ali Abd Ar-Raziq, Al-Islam wa Usul al-Ahkam, Mesir, 1925, dan telah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Jendela Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan,
Yogyakarta: Jendela, 2000.
62
Andito (Abu Zahra) (ed.), Op. Cit., hlm. 50
35
tidak berhubungan dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan
Tuhan.
63
Maka dari itu, menurut Ali Abdur Raziq, asumsi yang
menyatakan perlunya mendirikan negara dengan sitem, peraturan
perundang-undangan serta pemerintahan yang Islami adalah sesuatu
yang keliru dan melenceng jauh dari sejarah.
64
Apa yang misalnya
dikatakan sebagai sistem khilafah, sistem imamah itu semua
bukanlah keharusan bagi kaum muslimin untuk mendirikannya, karena
bukan bagian dari Islam.
Ia juga menyatakan bahwa Nabi tidak membangun negara ketika
di Madinah. Otoritas murni bersifat spiritual. Nabi Muhammad,
menurutnya semata-mata utusan Tuhan, bukan sebagai kepala negara.
Walaupun dalam realitasnya Nabi menjadi kepala negara di Madinah,
semata-mata karena tuntutan situasi yang wajar dan manusiawi saja.
65
Dalam hal ini Ali Abdur Raziq mengatakan:
.Muhammad saw. Tidak lain hanya seorang rasul yang murni
mendakwahkan agama, tidak ada tendensi kekuasaan, tidak
mendakwahkan dawlah. Nabi tidak memiliki kerajaan dan
pemerintahan, Nabi saw. Tidak meletakkan dasar-dasar kerajaan
mamlakah dalam pengertian yang dipahami dalam politik dari
kata ini dan sinonimnya. Beliau tidak lebih dari seorang rasul
sebagaimana rasul-rasul lain. Ia bukan raja, atau peletak dasar
daulah, dan bukan pula orang yang menyeru kepada monarki.
66
Kemudian dalam halaman lain ia menambahkan bahwa al-Quran
diturunkan oleh Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak
63
Ibid.
64
Ali Abd Ar-Raziq, Op. Cit., hlm. xiv
65
Ahmad Suaedy (ed.), Op. Cit., hlm. 96-97.
66
Ali Abd Ar-Raziq, Op. Cit., hlm. 78.
36
mempunyai hak apa-apa atas umatnya selain hak risalah. Tugas nabi
atas umat manusia hanyalah sebagai nabi yang menyampaikan syariat
Allah.
67
Bahkan menurut Abdur Raziq dalam al-Quran dan Hadits
pun tidak ada yang meyakinkan kita bahwa Rasul saw. dengan risalah
keagamaannya, menyeru kepada daulah politik.
68
Bagi Abdur Raziq, pembentukan negara tidak disarankan oleh
agama (syariat) melainkan berdasarkan pertimbangan akal umat.
69
Pada Zaman Nabi di Madinah, dilihat dari sudut apapun, menurutnya,
bukanlah persatuan politik. Di sana tidak terkandung makna daulah
ataupun pemerintahan, tetapi murni persatuan agama yang tidak
dicampuri noda-noda politik. Persatuan iman dan pandangan agama
bukan persatuan daulah dan pandangan kekuasaan.
70
Semua ajaran
yang dibawa Islam menurutnya adalah murni aturan agama dan demi
kemaslahatan religius manusia semata. Karena memang nabi tidak
pernah menyinggung atau menyebutkan tentang ketatanegaraan.
Sepanjang hayatnya ia tidak pernah menyebut istilah daulah
islamiyyah atau daulah Arabiyyah.
71
Demikianlah paradigma sekularistik yang diwakili oleh Ali
Abdur Raziq. Adapun indikasi pola pikiran dalam paradigma ini, bila
dipahami dari tesis Abdur Raziq ialah; Islam tidak mewajibkan kepada
umat untuk mengangkat imam atau pemimpin tertinggi yang mengatur
67
Ibid., hlm. 86.
68
Ibid., hlm. 94.
69
J. Suyuti Pulungan, Op. Cit., hlm. 308.
70
Ali Abd Ar-Raziq, Op. Cit., hlm. 101.
71
Ibid.
37
kepentingan mereka. Hal ini dikarenakan memang dalam al-Quran,
hadits maupun ijma tidak ada yang mengatakan hal tersebut, sebagai
dalil dan landasan yang jelas; Melaksanakan syiar keagamaan,
hukum-hukum syariat dan kemaslahatan masyarakat, seluruhnya itu
tidaklah tergantung pada ada atau tidaknya imamah atau khalifah,
tetapi bergantung pada wujudnya suatu pemerintahan model apapun
konstitusinya maupun sistemnya. Karena Islam tidak dengan khusus
menentukan bentuk tertentu dalam urusan pemerintahan.
72
Pandangan ini jelas kontroversi dengan kebanyakan ulama-ulama
yang ada. Sehingga tidak sedikit kritikan yang tertuju kepadanya dan
menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Karena dalam kenyataan
banyak urusan agama keputusannya memerlukan campur tangan
pemerintah (negara) dan demikian pula sebaliknya.
Model teori politik Islam (integralistik) sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, cenderung menekankan aspek legal dan formal
ajaran Islam sebagai konstitusi dalam negara. Sebaliknya model kedua
dan ketiga lebih menekankan substansi dari pada bentuk formal.
Bahkan dalam paradigma sekularistik, menolak secara tegas penerapan
ajaran islam secara simbolis. Karena sifatnya yang simbolis, maka
kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagi
pendekatan yang dapat mengembangkan Islam dengan sistem politik
72
M.Yusuf Musa, Op. Cit., hlm. 101.
38
modern, dimana negara-bangsa merupakan salah satu unsur
utamanya.
73
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya
tradisi pemikiran politik Islam itu kaya dan beraneka ragam. Sehingga
berbicara mengenai konsepsi tentang negara Islam tidak akan mudah
diklaim atas suatu konstruk tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan
sebelumnya, pandangan kelompok terakhir beranggapan bahwa Nabi
tidak mencalonkan atau pun menunjuk penggantinya, juga tidak
menetapkan prosedur atau kerangka untuk mengangkat atau
menurunkan pengganti beliau. Demikian pula selama periode empat
khalifah khulafaur rasyidin, metode yang berlainan telah dipergunakan
dalam pengangkatan khalifah.
74
Sistem khalifah itu pun tidak bisa dipertahankan eksistensinya
oleh umat Islam. Pada tanggal 3 Maret 1924 sistem khalifah ini
berakhir setelah pembentukan negara nasionalis sekuler Republik
Turki pada bulan Oktober 1923 oleh Mustafa Kemal Attaruq (1881-
1938 M.).
75
Sejak itu institusi khalifah yang dipandang sebagai
supremasi politik dan simbol kesatuan umat Islam lenyap. Akhirnya,
sampai masa sekarang umat Islam hidup di bawah berbagai bentuk
pemerintahan yang merdeka dan berdaulat.
73
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 15.
74
Mumtaz Ahmad (ed.), Op. Cit., hlm. 62-63.
75
J. Suyuti Pulungan, Op. Cit., hlm. 48.
39
Dengan melihat realitas di atas menunjukkan bahwa di dalam
ajaran Islam tidaklah terdapat konsepsi tentang ketatanegaraan secara
kongkrit. Tidak adanya penjelasan tentang sistem pemerintahan baik di
dalam al-Quran maupun hadits nabi, serta berbedanya praktik dan
metode pemerintahan baik dalam pengangkatan, pergantian, maupun
bentuk suatu negara dari masing-masing khalifah terdahulu semakin
memperjelas bahwa di dalam Islam tidak terdapat konsepsi yang
spesifik dan definitif tentang negara.
B. Agama Sebagai Wacana Politik
Dalam agama (Islam) telah ada kesepakatan bahwa sumber utama
ajarannya adalah al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW. telah memberikan petunjuk kepada semua
umat manusia. Namun di sini terdapat perbedaan pemahaman mengenai
pokok-pokok ajaran Islam. Sebagian mengatakan bahwa dalam Islam
hanyalah diajarkan tentang ubudiyah, yaitu hal-hal yang secara pribadi
berkaitan dengan Allah (hubungan vertikal). Sebagaimana ditulis dalam ayat
al-Quran:
.,, . ., - .- , , .,_ ,
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembah-Ku..
76
76
QS. 5: 56, Al Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang: Karya Toha
Putra, hlm. 1058.
40
Melihat dari teks tersebut di atas jelaslah bahwa inti dari manusia (umat
Islam) hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena
itulah Islam hanya memberikan pengajaran tentang prinsip-prinsip serta nilai-
nilai ibadah semata. Sementara di sisi lain ada yang beranggapan bahwa Islam
adalah agama yang sempurna, mencakup pula hubungan dengan negara dalam
wilayah politik.
Bagi orang Islam yang taat menjalankan ajaran agamanya dan yang
sadar akan tugas dan kewajiban keagamaannya, maka bisa dipastikan
menjadikan syariat atau ajaran Islam sebagai sumber utama dan satu-satunya
kebenaran serta tata nilai hidupnya, baik secara pribadi, keluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dilandasi keyakinan bahwa tata nilai
yang berasal dari Tuhan mutlak kebenarannya untuk mahluk-Nya, maka
mereka akan berusaha sekuat tenaga agar tata nilai kehidupan dari Allah ini
menjadi tata nilai kehidupan manusia, termasuk dalam tataran hidup
berbangsa dan bernegara.
77
Oleh karena itu, bukan merupakan sesuatu yang ganjil bila kekuatan
Islam akan senantiasa berjuang untuk mewujudkan tugas suci keagamaan ini
dengan segala cara dan melalui semua jalur formal konstitusional maupun
kultural.
78
Upaya menjadikan Islam sebagai satu-satunya sumber nilai secara
formal, baik berupa Negara Islam maupun syariat Islam sebagai hukum
positif, mengakibatkan Islam secara praksis memasuki jalur politik. Dan
77
Okki F. Muttaqie, Penyunting dalam Taufiq Nugroho, Pasang Surut Hubungan Islam
dan Negara Pancasila, Yogyakarta: Padma, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 11.
78
Ibid.
41
ternyata keterlibatan agama dalam politik ini secara khusus memberikan
warna dan corak tersendiri.
Diskursus tentang agama dan politik sesungguhnya telah berlangsung
cukup lama dalam wacana agama (Islam). Namun, dalam beberapa tahun
terakhir ini, menjadi hangat dibicarakan, terutama berkaitan dengan fenomena
agama dan politik yang muncul di masyarkat. Misalnya, dengan munculnya
partai politik yang membawa bendera agama, munculnya kerusuhan-
kerusuhan sosial yang membongkar hubungan agama, politik dan negara.
Panji-panji Islam yang selalu diusung oleh kebanyakan muslim garis
keras banyak membawa perhatian bagi kalangan cendekiawan muslim
modern. Kekerasan yang sering ditampilkan demi tercapainya formalisasi
Islam: seperti halnya negara Islam, masyarakat Islam, partai Islam dan segala
sesuatu yang berdimensi Islam, mengakibatkan warna Islam politik di dunia
ini menjadi sentral background yang suram dan mengerikan. Para pelaku yang
membela Islam politik adalah kelompok Islamis, yang dengan gigihnya, di
semua wilayah, tetap berusaha menumbuhkan negara Islam.
79
Untuk lebih jelasnya, uraian Uwe Halbah tentang Islamisme politik
militan, sebagaimana di tulis oleh Rusli Karim berikut ini akan membantu
kita memahami hakikat dari istilah tersebut:
1. Istilah politik: perampasan kekuasaan melalui slogan keagamaan;
perjuangan demi negara Islam berarti merealisasikan kedaulatan
79
M.Rusli Karim, Op. Cit., hlm. 2.
42
Tuhan dan memusuhi sistem-sistem politik yang didasarkan pada
kedaulatan sekular (kadaulatan rakyat), seperti demokrasi.
2. Istilah undang-undang: perlaksanaan syariah, undang undang Tuhan,
yang tidak membenarkan adanya kekuatan sekuler apapun.
3. Istilah agama: pembatasan terhadap sumber utama agama, terhadap
tidak bolehnya menerjemahkan wahyu, terhadap pemahaman kaku al-
Quran dan Hadits; dan terhadap pemahaman menyeluruh agama,
mengikuti Islam yang benar mengatur semua urusan kemanusiaan dan
kemasyarakatan.
4. Istilah sejarah: utopia yang merujuk merujuk pada suatu bentuk
Islam yang telah berubah dari era Nabi dan komunitas Islam pertama,
yang merupakan dominasi dari negara.
5. Istilah kategorisasi tamaddun: penolakan terhadap pengaruh-pengaruh
non Islam, terutama budaya modern Barat; pembatasan untuk
menyerapnya dalam peradaban Islam disertai mendirikan peradaban
Islam.
6. Istilah metode: pengutukan, jika diperlukan, realisasi kekerasan
melalui konsep jihad Islam.
80
Menguatnya diskursus agama, politik dan negara yang telah berlangsung
cukup lama tersebut, setidaknya karena alasan bahwa masing-masing dari
ketiga hal tersebut sama-sama memiliki pengikut dan kepentingan. Agama
dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai sakral, karena itu memang acap
80
Ibid.
43
kali digunakan, diunggulkan untuk menjadi semacam pembawa ritual saksi
bagi para pengikutnya. Sakralisasi agama ini amat berperan dalam
membangun sebuah masyarakat yang percaya pada dimendsi transendental,
ke-Ilahi-an.
81
Ketiga-tiganya dari agama, politik dan negara yang sama-sama
berkepentingan terhadap umat itu sering menjadi rebutan, sehingga tidak
jarang terjadi bentrokan yang menyesatkan masyarakat. Masyarakat yang
mestinya mendapatkan manfaat atas agama, malah sering jadi korban atas
nama agama demi interes politisi. Pendek kata, agama oleh para politisi
biasanya dibuat tak berdaya dan diperalat. Inilah yang menjadi lahan paling
subur terjadinya politisasi agama, bahkan agama kemudian diredusir hanya
sebagai justifikasi politik, sehingga agama tak lebih sebagai ideologi politik.
82
Untuk mencapai tujuan politis, bahkan terkadang menganggap tindakan
kekerasan merupakan suatu kebaikan dan salah satu metode pencapaian tujuan
luhur
83
, maka tidak aneh kalau naluri agresif manusia terkadang tumbuh subur
di bawah naungan agama.
Tidak sulit untuk membuktikan hal ini apabila kita menelusuri fenomena
kekerasan dalam perjalanan sejarah kahidupan keagamaan; lumuran darah
para syuhada korban tangan ekstremis dari berbagai kelompok keagamaan
81
Abdul Munir Mulkhan, et al., Agama dan Negara, Perspektif: Islam, Katolik, Budha,
Hindu, Konghucu, Protestan, Yogyakarta: Institut Dian / Interfidei, Pustaka pelajar, Cet. Ke-1,
2002, hlm. vi.
82
Ibid.
83
Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Editor: Nurul A.
Rustamaji, Bandung: Mizan, Cet. Ke-5, 1999, hlm. 146.
44
telah mewarnai lembaran sejarah. Pada masa normatif Islam, tiga dari keempat
khulafaur rasyidin, terbunuh oleh tangan-tangan kelompok ekstremis.
84
Para ekstremis pelaku kekerasan ini, menurut Alwi Shihab, pada
umumnya di dorong oleh keyakinan keagamaan, bahwa apapun yang mereka
lakukan adalah sejalan dengan perintah Tuhan yang tercantum dalam teks
suci.
85
Ayat-ayat al-Quran dipahami hanya sebatas pemahaman yang sempit.
Sehinga keagamaan dan kekuasaan yang demikian itu tidak lagi peduli pada
penderitaan dan melayani kepetingan rakyat kecil, tetapi hanya bagi
kepentingan elit penguasa politik dan keagamaan. Tuhan lebih dipahami
sebagai ekstrim negatif kemanusiaan. Aksi-aksi negatif atas nama agama dan
atau Tuhan, terperangkap ke dalam aksi sepihak hanya bagi yang sefaham,
seagama dan seideologi politik.
86
Tampaknya fenomena kekerasan ini pada umumnya tidak terbatas pada
kurun waktu tertentu. Di Indonesia, misalnya masyumi
87
dan partai-partai
Islam lainnya terutama pada masa-masa awal pasca kemerdekaan menawarkan
Islam sebagi dasar negara dalam konstituante yang sangat dikenal.
88
Para
Islamis berhasrat sedemikian kuat untuk mendirikan negara Islam di Indonesia
dengan tujuan untuk menerapkan syariat secara efektif di segenap penjuru
wilayah negara. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa kemerdekaan
84
Ibid.
85
Ibid.
86
Abdul Munir Mulkhan, et al., Op. Cit., hlm. 4.
87
Partai masyumi didirikan pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, sebagai
penyalur aspirasi politik umat Islam. Lihat Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama:
Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Cet. Ke-
1, 1999, hlm. 59.
88
Taufiq Nugroho, Op. Cit., hlm. 8.
45
Indonesia merupakan bagian dari cita-cita perjuangan Islam. Klaim ini
mengarah pada argumen selanjutnya bahwa pencapaian kemerdekaan
Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan Islam untuk menerapkan
ajaran Islam dan syariat.
89
Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena tidak
mendapat dukungan secara mayoritas dan secara tegas di gagalkan oleh
kelompok nasionalis sekuler yang berparadigma berpikir lebih inklusif dan
mengedepankan faham kebangsaan.
Kegagalan formalisasi syariat Islam tersebut ternyata mendapat reaksi
keras dari para pemimpin umat Islam, dan menimbulkan kekecewaan bagi
mereka atas negara ini. Pada akhir 1949 Negara Indonesia yang berdasarkan
Pancasila mendapat kecaman dari Kartosuwiryo (w. 1962 M.) dan gerakan
militer Darul Islam-nya. Menyebut tentaranya dengan Tentara Islam
Indonesia, Kartosuwiryo mengangkat senjata dan memimpin pemberontakan
di Jawa Barat melawan pemerintah pusat.
90
DI/TII, sebuah gerakan radikal
yang memperjuangkan cita-cita negara Islam
91
di bawah komando
Kartosuwiryo, pada tangal 7 Agustus 1949 memproklamirkan berdirinya apa
yang disebut Negara Islam Indonesia ( NII )
92
, dan Kartosuwiryo sendiri
sebagai presiden.
89
Faisal Ismail, Op. Cit., hlm. 40-41.
90
Ibid., hlm. 4.
91
Sudirman Tebba, Op. Cit., hlm. 28.
92
Eko Prasetyo, Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik
Global, Yogyakarta: Insist Press, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 43.
46
Pemberontakan Kartosuwiryo ini kemudian diikuti oleh Kahar Muzakar
(1921-1965) pada tahun 1952 di Sulawesi Utara yang juga memproklamirkan
berdirinya NII di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo.
93
Meski Kartosuwiryo memperjuangkan Islam, menurut Faisal Ismail
sejauh menyangkut Darul Islam, harus tetap diingat bahwa cita-citanya
mendirikan negara berdasarkan Islam dengan kekuatan senjata semata-mata
merefleksikan kehendak politik kelompok minoritas di lingkungan Darul
Islam sendiri, dan tidak mewakili semua spektrum aspirasi politik umat Islam
Indonesia.
94
Label seperti ini tentunya justru merugikan citra Islam dan umat
Islam secara keseluruhan.
Namun dalam realitas, ternyata sikap eksklusif dan etnosentris dalam
memperjuangkan Islam dengan memakai simbol-simbol kegamaan tidak pula
kunjung reda. Pada masa-masa kini -- yang ditandai dengan meluasnya ajaran
sikap moderasi, toleransi dan saling pengertian antar dan inter umat beragama
-- kekerasan atas nama agama tetap sulit untuk dibendung.
95
Untuk melegitimasi kepentingan Partai Politik misalnya, para ekstremis
tidak merasa enggan mencantumkan simbol-simbol agama. Bahkan menurut
Munir Mulkhan (1946 M.), dalam perkembangannya kata qital dan jihad yang
dipahami sebagai perang fisik lebih popular dan familiar di dalam kesadaran
umat muslim dari pada dakwah. Kosa kata ini pun, tak jarang dipahami sebagi
perlawanan pada orang yang beragama dan atau berfaham lain walaupun
seagama. Suatu tindakan heroik bahkan mungkin jihad ketika merusak
93
Ibid., hlm. 44.
94
Faisal Ismail, Op. Cit., hlm. 58.
95
Alwi Shihab, Op. Cit., hlm. 147.
47
bangunan milik organisasi atau agama lain. Harta dan milik orang lain
dipandang halal, boleh dirusak, dan dirampas. Sehingga keagamaanpun
berubah menakutkan sebagai ancaman bagi pihak-pihak lain.
96
Hal tersebut tampak selama beberapa tahun belakangan ini, seperti
halnya kasus di Timor Timur, Timika, peristiwa kantor DPP PDI, dan Pasar
Tanah Abang, Situbondo, Sambas dan Pontianak, Tasikmalaya, dan
sebagainya. Hampir seluruh kerusuhan itu berkaitan dengan persoalan sosial,
dan politik dengan nuansa suku, agama dan antar golongan yang cukup
kental.
97
Meskipun tidak semua kerusuhan tersebut berkaitan dengan
persoalan-persoalan seperti itu, lanjut Azra.
98
Menurut Sudjatmoko, sebagaimana dikutuip oleh Syafii Maarif,
sebenarnya yang menjadi pemicu konflik agama adalah faktor dominan
yaitu sebagai pranata, sumber nilai, dan kekuatan mobilisasi yang berkali-
kali membawa manusia pada konflik yang penuh kekerasan.
99
Gejala tersebut menyebabkan agama yang seharusnya sebagai rahmatan
lil alamiin berubah menjadi teologi ideologis tertutup, bukan sebagai
pencerah kemanusiaan. Teks-tekas suci berubah menjadi teks mati, ajaran
agama menjadi tradisi mati dan gagal berbicara pada manusia dalam usianya
yang otentik.
100
Dengan timbulnya gejala tersebut selain merugikan suatu
96
Abdul Munir Mulkhan, et al., Op. Cit., hlm. 5
97
Azyumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan,
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 5.
98
Ibid.
99
A. Syafii Maarif, Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. Ke-1, 1997, hlm. 71.
100
Abdul Munir Mulkhan, et. Al., Op. Cit., hlm. 6.
48
agama tertentu, tentunya juga mengakibatkan keresahan masyarakat yang
akhirnya akan dapat menggoyahkan integritas suatu bangsa.
Karena begitu lekatnya peranan agama dalam menentukan kondisi
stabilitas bangsa, khususnya di Indonesia, dimana masalah politik selalu
berjalin mengait dengan masalah agama,
101
maka dari pemuka agama sendiri
haruslah mencegah timbulnya penafsiran-penafsiran keagamaan yang dapat
mengacau ke arah radikalisme dan kekerasan. Islam, di atas pundak pemuka
agama terletak kewajiban untuk mensosialisasikan konsep moderasi yang
menghindari sikap ekstrim guna menciptakan masyarakat penengah yang adil,
atau dalam bahasa al-Quran Ummatan Wasathan.
102
Sebagaimana dikutip oleh Taufiq Nugroho, Nurcholis Madjid (1939 M.)
menyatakan bahwa perjalanan Islam (di Indonesia khususnya) akan lebih
sukses lewat jalur budaya, dengan menghindari doktrin-doktrin yang simbolis
dan formalis. Bahkan menurutnya, santrinisasi secara antropologis jauh lebih
sukses dari pada melalui jalur politis.
103
Sehingga dalam hal ini perlu
dikembangkan kesadaran inklusivitas intern umat beragama agar terjadi
ukhuwah Islamiyah. Dalam kerangka politik kenegaraan, ajaran Islam
hendaknya dijadikan landasan etik dan moral dalam kehidupan berbangsa.
Dengan kata lain, umat Islam sebagai mayoritas hendaknya ikatan keislaman
menjadi perekat kehidupan nasional.
104
101
Taufiq Nugroho, Op. Cit., hlm. 33.
102
Al-Quran, QS. 2 :143.
103
Taufuq Nugroho, Op. Cit., hlm. 61.
104
Ibid.
49
Segala bentuk moderasi keagaman, baik dalam nilai, berinteraksi dengan
kelompok lain, maupun dalam menjalankan tuntunan agama perlu
mendapatkan tekanan. Rekonsiliasi intern dari setiap kelompok harus menjadi
prioritas utama dalam agenda tiap agama. Dalam bahasa Islam popular upaya
tersebut dikenal dengan istilah taqrib baina al madzahib ( pendekatan antar
sekte / madzhab ).
105
Kiranya dengan pendekatan ini, bentuk kekerasan dan
eksklusiv -- termasuk dalam tindakan politik -- dapat di minimalisir, sehingga
agama akan benar-benar berfungsi sebagai rahmatan lil alamiin.
C. Relasi Agama dan Negara Dalam Lintasan Historis di Indonesia
Mengkaji hubungan agama (Islam) dan negara di Indonesia, terutama
pasca kemerdekaan, pada waktu-waktu tertentu dapat dikatakan kurang
harmonis. Secara umum, peristiwa-peristiwa parlementer maupun non
parlementer yang terkait dengan Islam dan negara ikut menciptakan suasana
ketidakharmonisan tersebut. Dalam artian, Islam menjadi faktor dominan
dalam rangka membentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
106
Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh
terhadap politik.
107
Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena
secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Sehingga
sepak terjangnya lebih sering menjadi perhatian masyarakat luas. Kedua,
105
Alwi Shihab, Op. Cit., hlm. 149.
106
Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia,
Yogyakarta: Galang Press, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 162.
107
Andi Wahyudi, Muhammadiyah dan Gonjang-Ganjing Politik: Telaah Kepemimpinan
Muhammadiyah Era 1990, Editor: Darmawan, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet. Ke-1, 1999,
hlm. 48.
50
karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa Islam dan politik
tidak dapat dipisahkan. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa Islam
mempunyai konsep tentang negara Islam.
108
Pada satu sisi Islam menghendaki agar negara dan masyarakat Indonesia
diatur berdasarkan agama Islam. Kalaupun tidak demikian, Islam selalu
mendesak agar negara dan masyarakat berdasarkan pada etika dan moral
agama yang diyakini bersifat abadi dan universal karena datang dari Tuhan.
109
Pada sisi lain, negara menghendaki agar masyarakat Indonesia diatur
berlandaskan pada kesepakatan bersama. Negara menganggap bahwa Islam
hanyalah satu bagian dari bagian-bagian lain yang ikut membentuk Negara
Indonesia. Karena itu, negara menghendaki agar masyarakat Indonesia
dikelola berdasarkan ideologi bersama Pancasila.
110
Secara faktual, pada proses awal pembentukan negara Indonesia, dalam
sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia) permasalahan pokok yang dibicarakan adalah
persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain
yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Untuk bentuk negara
misalnya, hampir seluruh anggota memilih bentuk republik. Tetapi sekali
tentang dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat
hangat.
111
108
Taufiq Nugroho, Op. Cit., hlm. 23.
109
Ibid., hlm. 24.
110
Ibid.
111
Ahmad Syafii Maarif Pengantar dalam Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam
Sukarno Versus Natsir, Jakarta: Teraju, Cet. Ke-1, 2002, hlm. vii-viii.
51
Menurut Taufiq Abdullah, sebagaimana di tulis Abdul Ghofur, dasa
warsa 1920-an-1930-an merupakan dasawarsa dalam sejarah modern
Indonesia. Di masa-masa inilah berbagai jenis ideologi yang kemudian akan
berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideologi perjuangan
mulai diperdebatkan di kalangan kaum pergerakan nasional.
112
Ideologisasi ini
mengakibatkan, pertama makin diperjelasnya struktur intern panji-panji Islam,
sehingga perbedaan yang kemudian bersifat aliran ini bertambah rumit karena
adanya pengaruh ide yang bersumber dari Barat.
113
Kemudian benih-benih perdebatan ideologi ini mulai muncul secara
terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (kelompok
kaum nasionalis) dan Muhammad Natsir (kelompok kaum Islam) di sekitar,
hubungan antara agama dan negara.
114
Dan materi polemik itu sendiri sudah
menampilkan masalah-masalah yang sama dengan materi yang muncul dalam
perdebatan di BPUPKI dan konstituante mengenai dasar negara,
115
antara
nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam.
a. Relasi Agama dan Negara Pra-Kemerdekaan: Polemik Soekarno
Natsir
Kajian tentang Soekarno (1901-1970 M.) dan Natsir (1908-1993 M.),
khususnya mengenai polemik hubungan agama dan negara di tahun 1940,
112
Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 136.
113
Ibid.
114
Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media,
1999, hlm. 55.
115
Ibid.
52
memiliki makna historis sangat signifikan
116
, hal ini menurut Suhelmi
dikarenakan: Pertama, secara substansial, polemik Soekarno-Natsir ini
mewakili perbedaan pandangan dua golongan terkemuka di Indonesia,
yaitu golongan nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Polemik mereka
juga merefleksikan pertarungan ideologis kedua golongan yang mencakup
masalah prinsip kenegaraan. Sehingga polemik ini mewarnai corak
perkembangan politik, yang berkisar dalam masalah peranan Islam,
hubungan antara agama dan negara serta ideologi yang diperlukan dalam
menata sebuah negara.
Kedua, berkaitan dengan dua tokoh polemik, Sokarno dan Natsir.
Keduanya tokoh politik paling legendaris dalam sejarah Indonesia
kontemporer. Soekarno, ideolog dan politikus Indonesia telah banyak
memberikan kontribusi intelektual permanen bagi perkembangan
pemikiran politik Indonesia. Sedangkan Natsir, sebagai ideolog reformis
muslim dianggap identik dan mendominasi gagasan-gagasan politik Islam
Indonesia kontemporer, terutama di kalangan kaun reformis muslim.
Ketiga, polemik yang dilakukan secara demokratis itu, telah
memberikan kesadaran di kalangan umat Islam saat itu, bahwa Islam
tidaklah hanya sekedar sebagai sistem teologi, masalah yang hanya
menyangkut ketuhanan dan akhirat, tetapi juga mencakup kehidupan
pribadi, sosial budaya dan kenegaraan.
117
116
Ahmad Suhelmi, Op. Cit., hlm. 1.
117
Ibid., hlm.2-4.
53
Polemik ini merupakan salah satu letupan pertarungan-pertarungan
ideologis yang terjadi sebagai refleksi antara golongan nasionalis sekuler
dengan nasionalis Islam.
118
Nasionalis sekuler adalah mereka yang
berprinsip bahwa dalam kehidupan politik kenegaraan harus ada
pemisahan tegas antara agama dan politik. Golongan ini meyakini bahwa
agama merupakan ajaran-ajaran yang menyangkut masalah akhirat
sedangkan politik kenegaraan merupakan masalah duniawi. Sementara
golongan nasionalis Islam berprinsip bahwa agama tidak dapat terpisah
dari urusan kenegaraan. Golongan ini yakin dan mempunyai komitmen
pada pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam
sebagai agama.
119
Soekarno berpendirian bahwa demi kemajuan negara dan agama itu
sendiri, negara dan agama harus dipisahkan; sedangkan Natsir
berpendirian sebaliknya, bahwa hubungan agama dan negara harus
menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara
diurus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama.
120
Pada dasarnya, Soekarno tidak menyatakan secara tegas bahwa sama
sekali tidak boleh ada hubungan apapun antara keduanya. Dia memang
menentang pandangan mengenai hubungan formal-legal antara Islam dan
negara, khususnya dalam sebuah negara yang tidak semua penduduknya
118
Ibid.
119
Ibid.
120
Moh. Mahfud MD., Op. Cit., hlm.55.
54
beragama Islam. Ia sangat yakin bahwa orang-orang yang bukan penganut
ajara Islam akan menolak gagasan itu.
121
Sebagai seorang muslim, Soekarno menganut paham hubungan yang
bersifat substansialistik antara Islam dan Negara. Oleh sebab itu, bagi
Soekarno, otentisitas sebuah negara Islam tidak pertama-tama ditinjukkan
oleh penerimaan formal atau legal Islam sebagai dasar ideologi dan
semangat Islam dalam kebijakan-kebijakan negara. Dalam satu
kesempatan dia pernah menulis:
Lagi pua di suatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan
rakyat yang benar-benar mewakili rakyat di negeri yang demikian itu,
rakyatnya tokh bisa memasukkan segala macam kegamaannya ke dalam
tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang
dipakai dalam negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari
negara.
122
Kendati demikian Soekarno mengakui, bahwa apa yang dipraktekkan
Nabi dan Khulafaur Rasyidin adalah suatu negara dimana agama dan
negara bersatu, bahkan ia pun berpendapat bahwa persatuan agama dan
negara merupakan gagasan ideal. Dan masa pemerintahan Islam itu
menurut Soekarno adalah masyarakat yang dinamis dan mengandung
potensi untuk maju dengan pesat.
123
Pendapatnya tentang pemisahan negara dan agama, tampaknya ia
banyak dipengaruhi oleh gerakan politik Islam di Turki yang dipelopori
oleh Mustafa Kemal Attaruk (1881-1938 M.),
124
bahkan ia juga dianggap
121
Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Jakarta : Logos Wacana, Cet. Ke-1,
1999, hlm. 139.
122
Abdul Ghofur, Op. Cit ., hlm. 145.
123
Badri Yatim, Op. Cit., hlm. 140.
124
Abdul Munim, Op. Cit., hlm. 108.
55
sebagai orang yang mempropagandakan ide-idenya di Indonesia.
125
Kemal
Attaruk yang berorientasi berat memisahkan agama dari negara, menurut
Soekarno dengan alasan:
1. Bahwa pada masa khalifah-khalifah Usmaniyah di Turki, sudah
terdapat dualisme hukum, yang pertama hukum Islam atau syariat
dan yang kedua hukum yang difirmankan oleh sultan atau khalifah
dan parlemen.
2. Dualisme hukum ini membawa kemunduran, karena pengaruh
syaikhul Islam tetap dominan, sementara mereka berpandangan kolot
dan tidak menjamin kemajuan umat Islam, bahkan justru
menghambat.
3. Hal ini disebabkan, karena Islam yang dianut oleh masyarakat Turki
bukan lagi Islam yang sejati, tetapi menurutnya adalah Islam yang
berwajah tiga: Yunani, Iran dan Arab.
4. Oleh karena itu, bila hal ini berlanjut, dan manakala agama dibuat
untuk memerintah, ia selalu dipakai alat penghukum di tangam raja-
raja, orang-orang zalim dan orang-orang bertangan besi.
5. Oleh karena itu, persatuan agama dan negara tidak menjamin
kemajuan, terutama kemajuan ekonomi.
6. Agama Islam sendiri, dengan persatuan tersebut, justru terhambat dan
terkungkung.
125
Badri Yatim, Loc. Cit.
56
7. Karenanya, tindakan pemisahan ini mempunyai manfaat ganda yang
keduanya mendatangkan keuntungan. Yang pertama memerdekakan
agama dari negara, dan yang kedua memerdekakan negara dari
agama.
8. Kemerdekaan agama dan negara itu, memungkinkan keduanya untuk
bergerak maju.
126
Sekularisasi di Turki menurut Soekarno adalah sekularisasi atas
politik Islam, realisasi Islam yang telah memudarkan negara dan Islam
sendiri. Jadi sikap Turki waktu itu tidak memotong ajaran Islam, isi
perintah Islam. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh
Turki muda telah memusuhi atau bertindak anti Islam, tetapi malah
memerdekakannya dari keterikatannya pada negara agar dapat
berkembang dengan baik.
127
Lebih lanjut Mahfud MD (1957 M.) menegaskan, bahwa dari gaya
dan aksentuasi pemaparannya, Soekarno memang mendukung Kemal
Pasya serta memandang layak untuk diterapkan di Indonesia. Oleh sebab
itu ia memperkuat argumennya untuk melawan sangkaan kaum muslimin,
ia mengemukakan:
Tuan berkata, negara jangan dipisahkan dengan agama, negara harus
satu dengan agama. Accord, tetapi bagaimana Tuan mengerjakan Tuan
punya ideal itu dimana penduduk sebagian tidak beragama Islam,
seperti Turki, India, Indonesia, dimana milyunan orang beragama atau
beragama lain, dan dimana kaum intelektual umumnya tidak berfikir
Islamistis
126
Ibid., hlm. 140-141.
127
Moh. Mahfud MD., Op. Cit., hlm. 64.
57
Andainya, andainya Tuan menjadi pemerintah negeri yang banyak
bukan orang Islam, apakah Tuan mau tetapkan saja bahwa negara
harus negara Islam, undang-undang dasar harus Islam, semua hukum-
hukum yang beragama Kristen atau agama lain tidak mau terima,
bagaimanakah, Tuan apakah mau pakai sahaja kepada mereka, dengan
menghantamkan Tuan punya tinju di atas meja, bahwa mereka musti
ditundukkan kepada kemauan Tuan? Ai, Tuan mau diktator, mau
paksa mereka dengan senjata bedil dan meriam?
128
Pandangan Soekarno tampaknya lebih mengedepankan demokrasi
dan memperhatikan pluralitas. Sehingga formalisasi Islam dengan segala
bentuknya tidak dibenarkan olehnya.
Walaupun Soekarno menerima bahkan menganjurkan dipisahkannya
agama dan negara, namun yang dimaksudkan pemisahan itu adalah secara
formal agama tidaklah merupakan bagian dari negara, atau secara formal
dicantumkan dalam undang-undangnya bahwa negara adalah negara Islam.
Tetapi ia memiliki konsep penyatuan dan negara tersendiri. Konsep ini,
menurutnya merupakan arti yang sebenarnya dari cita-cita Islam. Seperti
di kutip oleh Yatim, ia mengatakan:
Baik kita terima negara dipisahkan dari agama, tetapi kita akan
kobarkan seluruh rakyat dengan apinya Islam, sehingga semua utusan
didalam badan perwakilan itu, adalah utusan Islam, dan semua
putusan-putusan badan perwakilan itu bersemangat dan berjiwa Islam.
Kalau betul-betul Tuan punya rakyat begitu, maka barulah tuan boleh
berkata bahwa Islam adalah Islam hidup, Islam subur, Islam yang
dinamis dan bukan Islam yang melempem yang hanya bisa berada, bila
mana ada asuhan dan perlindungan dari negara sahaja. Saya lebih
senang kepada sasuatu rakyat yang berani tantangannya modern
democratic itu, dari pada rakyat yang selalu merintih-rintih janganlah
Islamnya dipisahkan dari negara. Rakyat yang berani tantangan itulah
yang nantinya bisa meralisasikan cita-cita Islam dengan perjuangan
sendiri, keringatnya sendiri, banting tulangnya sendiri.
Renungkanlah perkataan saya ini. Sebab, sungguh, inilah menurut saya
punya keyakinan arti yang sebenarnya dari cita-cita Islam, bahwa
128
Ibid., hlm. 68.
58
negara bersatu dengan agama. Negara bisa bersatu dengan agama,
meskipun azas konstitusinya memisahkan ia dari agama.
129
Dengan demikian, dalam pendapatnya yang terakhir ini terlihat
bahwa adanya keserasian antara Islam dan demokrasi. Konsep demokrasi
dalam hal ini menurutnya ialah bahwa umat Islam dapat dapat menerima
dipisahkannya antara agama dan negara, namun umat Islam dapat
mengajukan usul agar hukum-hukum dan keputusan-keputusan yang
dihasilkan oleh badan perwakilan dapat disesuaikan dengan ajaran Islam.
Jadi, pemisahan agama dan negara menurut Soekarno hanyalah dalam
dataran konstitusi negara, sementara hukum Islam masih dapat ditolerir
dengan disesuaikan pada kondisi setempat, meskipun pelaksanaannya
tidak sebagai hukum formal.
130
Pendapat ini ditentang oleh Natsir, yang menganggap bahwa prinsip
musyawarah dalam Islam tidak selalu identik dengan azas demokrasi.
Sebagaimana dikutip oleh Suhelmi, Natsir mengungkapkan bahwa: Islam
anti istibdad (despotisme), anti absolutisme dan kesewenag-wenangan.
Akan tetapi ini tidak berarti, dalam pemerintahan Islam itu semua urusan
diserahkam kepada keputusan musyawarah Majlis Syura. Dalam parlemen
negara Islam, yang hanya boleh dimusyawarahkan adalah tata cara
pelaksanaan hukum Islam (sayariat Islam), tetapi bukan dasar
pemerintahannya.
131
129
Badri Yatim, Op. Cit., hlm. 143-144.
130
Ibid.
131
Ahmad Suhelmi, Op. Cit., hlm. 91.
59
Natsir menyayangkan persepsi bahwa jika ada pendapat bahwa
agama dan negara harus bersatu lalu yang dilihat adalah Islam yang keliru
dalam praktik. Sebagaimana keterangan Mahfud , Natsir mengatakan:
.maka terbayangkan sudah dimatanya seorang bahlul (bloadyfool)
duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh haremnya, menanti tari
dayang-dayangnya. Terbayang olehnya yang duduk mengepalai
kementerian kerajaan beberapa orang tua bangka memakai serban
besar, memegang tasbih sambil meminum koga. Sebab memang
begitulah gambaran pemerintah Islam yang digambarkan dalam
kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru
bangsa Barat selama ini.
132
Menurut Natsir, bila ingin memahami agama dan negara dalam Islam
secara jernih, maka hendaknya mampu menghapuskan gambaran keliru
tentang negara Islam seperti di atas. Jadi, harus dibedakan antara ajaran
Islam sebagai ide dengan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat.
Sementara yang dilakukan Kemal di Turki sebagaimana dikagumi oleh
Soekarno adalah mencampakkan ajaran Islam dengan alasan negara
Islam yang hidup dalam praktik tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Apa
yang hidup di kalangan Turki Usmani yang kemudian menjadi alasan
sekularisasi Kemal menurut Natsir bukanlah negara Islam.
133
Natsir menyangkal pandangan Soekarno yang menyandarkan
kebenaran tindakan Kemal pada sejarah. Seperti dikutip Suhelmi, Natsir
berpendapat bahwa Kemal sebenarnya telah tersesat, sebab:
.tidak reel tidak berurat berakar dalam kultur rakyat Turki, malah
dalam beberapa hal ia mencabut jiwa Turki dari tradisi dan kulturnya.
Ini sudah dibuktikan dalam masa yang akhir-akhir ini, lantaran
sesudahnya Kemal meninggal, maka berangsur-angsur kebudayaan
132
Moh. Mahfud MD., Op. Cit., hlm.82.
133
Ibid., hlm. 83.
60
Turki lama merebut tempatnya kembali, baik tentang agama atau pun
hal-hal di luar agama.
134
Natsir kokoh dalam pandangannya bahwa negara dan agama tidak
dapat dipisahkan karena hal itu diperlukan untuk menjamin terlaksananya
baik peraturan-peraturan agama seperti sholat, puasa, larangan judi,
larangan mabuk, dan sebagainya.
135
Natsir menganggap bahwa urusan kenegaraan pada pokoknya
merupakan bagian integral risalah Islam. Dinyatakan pula bahwa kaum
muslimin mempunyai falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan
Kristen, fasis atau komunisme. Natsir lalu mengutip nash al-Quran yang
dianggapnya sebagai dasar ideologi Islam: Tidaklah aku jadikan jin dan
manusia melainkan untuk mengabdi pada-Ku.
136
Bertitik tolak dari dasar
ideologi ini, ia berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di
dunia ini hanyalah menjadi hamba Allah. Dan untuk menjadi predikat
hamba Allah tersebut, menurut Natsir, Allah telah memberi aturan:
Aturan atau cara kita berlaku berhubungan dengan Tuhan yang
menjadikan kita dan cara kita yang berlaku berhubungan dengan
sesama manusia. Diantara aturan-aturan yang berhubungan dengan
sesama manusia. Diantara aturan-aturan yang berhubungan dengan
muamalah sesama mahluk kita, ada diberikan garis-garis besarnya
seseorang terhadap masyarakat, dan hak serta kewajiban masyarakat
terhadap diri seseorang. Yang terakhir ini tak lebih tak kurang, ialah
yang dinamakan orang sekarang dengan urusan kenegaraan.
137
Dari polemik tersebut di atas memberikan kesan adanya
pertentangan gagasan tajam di antara kedua tokoh tersebut. Soekarno,
134
Ahmad Suhelmi, Op. Cit., hlm. 93.
135
Mahfud MD., Op. Cit., hlm. 86.
136
Al-Quran, QS 51: 56.
137
Ahmad Suhelmi, Op. Cit., hlm. 87.
61
berdasarkan analisis perkembangan sejarah berkesimpulan bahwa agama
dan negara tidak dapat disatukan. Keduanya harus dipisahkan.
Sementara Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus
disatukan demi terlaksananya syariat Islam, sebab Islam tidak seperti
agama-agama lainnya, Islam adalah filsafat hidup yang menjadi
pedoman amal umat Islam dalam setiap bidang.
138
Ia merupakan agama
yang serba mencakup (komprehensif). Persoalan kenegaraan pada
dasarnya merupakan bagian dan diatur dalam Islam.
b. Dinamika Percaturan Politik Islam Pasca Kemerdekaan: Perdebatan di
Konstituante
Polemik Soekarno dan Natsir yang secara garis besar mewakili
pandangan-pandangan dua kelompok besar di Indonesia, yaitu para
nasionalis Sekuler dan naionalis Islam sebagian besar menentukan bentuk
dan perkembangan diskusi di dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
139
Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam sidang BPUPKI
berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara
dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi.
140
Namun perdebatan yang paling memanas dalam sidang tersebut adalah
138
Howard M. Federspiel, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century
Indonesia, Terj. Yudian W. Asmin dan H. Afandi Mochtar Persatuan Islam: Pembaharuan Islam
Indonesia Abad XX, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 200.
139
Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional
tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1,
1997, hlm. 10.
140
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Op. Cit., hlm. 102-103.
62
mengenai dasar negara. Setidaknya ada dua aliran yang muncul ke
permukaan: Islam dan aliran pemisahan negara dan agama.
141
Pada satu
pihak, kelompok pendukung dasar Islam ingin melaksanakan seluruh isi
syariat yang sesuai dengan al-Quran serta formulasi hukum Islam di
Indonesia, sementara kelompok nasionalis sekuler menghendaki lain.
Mereka lebih memilih faham kebangsaan, dan bagi mereka hukum Islam
adalah urusan pribadi bagi umat Islam itu sendiri.
142
Perdebatan tentang dasar negara tersebut telah memaksa para pendiri
Republik Indonesia untuk menjalani masa-masa yang sulit dalam sejarah
modern Indonesia. Tetapi akhirnya, sebuah kompromi politik dalam
bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dapat dicapai. Artinya,
keinginan dan kesepakatan luhur antara golongan Islam dan Golongan
nasionalis tertampung dalam satu piagam tersebut. Piagam Jakarta adalah
hasil kerja sebuah panitia kecil dalam BPUPKI yang diketuai Soekarno,
dan ditandatangani oleh sembilan anggota terkemuka, yaitu: Soekarno,
Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdul Kahar
Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad
Yamin.
143
Piagam Jakarta tersebut sebenarnya adalah sebuah preambule bagi
konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila
sebagai dasar negara telah disepakati, tetapi sila pertama, yaitu sila
141
Ibid., hlm. 104.
142
Ibid., hlm. 107.
143
Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah
Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, hlm.
66.
63
ketuhanan diikuti oleh anak kalimat: dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Anak kalimat yang dinilai
strategis ini bagi umat Islam menjadi sangat penting, sebab dengan itu
tugas pelaksanaan syariat Islam secara konstitusional terbuka pada waktu
yang akan datang. Inilah salah satu alasan mengapa wakil umat Islam
dalam BPUPKI dapat berkompromi dengan kelompok nasionalis.
144
Dan
pada akhirnya rumusan konstitusi ini dapat diterima dengan aklamasi pada
tangal 16 Juli 1945 oleh anggota sidang BPUPKI,
145
yaitu sebuah
mukadimah yang memuat Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara dan
Batang Tubuh UUD 1945 yang memuat dua ketentuan penting perjuangan
golongan Islam, yakni: pertama, Negara berdasarkan ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan
kedua, Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam.
146
Tetapi ternyata persetujuan tersebut tidaklah benar-benar telah
terselesaikan. Hasil kompromi politik tersebut mengalami perubahan
setelah proklamasi kemerdekaan. Anak kalimat dalam pembukaan UUD
1945; dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya, ternyata masih mengganjal dan dipandang sebagai
keputusan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
147
Oleh karena itu,
dari golongan Protestan dan Katolik menghendaki penghapusan anak
kalimat tersebut serta kalimat Islami lainnya dan atau lebih memilih
144
Ahmad Syafii Maarif, Op. Cit., hlm.107-108.
145
Ibid.
146
Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka
Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hlm. 45.
147
Endang Saifuddin Anshari, Op. Cit., hlm. 50.
64
berdiri di luar Republik Indonesia apabila anak kalimat dalam pembukaan
UUD tersebut masih tetap difungsikan.
148
Menyikapi hal tersebut, setelah melewati saat-saat yang cukup kritis,
maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam dalam
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
149
akhirnya menyetujui
penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan Batang Tubuh UUD
1945. Tetapi sila pertama, yaitu sila ketuhanan mendapat atribut yang
sangat kunci, dan menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa.
150
Modifikasi
sila pertama ini dipandang sangat berarti, sebab dengan jalan demikian
wakil-wakil umat Islam tidak keberatan dengan formula baru Pancasila itu.
Meskipun dalam kenyataan, ada kekecewaan dari wakil golongan Islam
yang pernah menjadi anggota di BPUPKI.
151
Perubahan diatas dipandang oleh sebagian orang sebagai kekalahan
politik wakil-wakil Islam. Tetapi, Alamsyah Ratu Perwiranegara
sebagaimana dikutip oleh Syafii Maarif menafsirkan bahwa peristiwa
tanggal 18 Agustus itu sebagai hadiah umat Islam kepada bangsa dan
kemerdekaan Indonesia, demi menjaga persatuan.
152
Setelah dua kali perdebatan tentang dasar falsafah negara baik dalam
sidang BPUPKI maupun PPKI sebagaimana telah tersebut diatas, dan
148
Ibid., hlm. 50-51.
149
PPKI dibentuk pada tangal 7 Agustus 1945 atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang
di Saigon dengan tugas mempersiapkan penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia.
Lihat Mahfud MD, Loc Cit. Panitia ini juga yang memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai
Presiden dan Wakil Presiden, dan mensahkan Preambule dan Batang Tubuh UUD hasil BPUPKI
dengan beberapa perubahan penting: dengan menghilangkan kalimat Islami. Lihat Endang
Saifuddin Anshari, Op. Cit., hlm. 208.
150
Ahmad Syafii Maarif, Op. Cit., hlm. 109.
151
Muh. Mahfud MD, Op. Cit., hlm. 49.
152
Ahmad Syafii Maarif, Loc. Cit.
65
untuk sementara menghasilkan suatu kesepakatan dan kompromi politik
dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Ternyata setelah pemilihan
umum yang pertama pada tanggal 15 Desember 1955, perdebatan tentang
dasar negara kembali muncul dipermukaan.
153
Namun untuk kali ini,
perdebatan terjadi dalam sidang majlis kontituante.
154
Ketika majlis ini memulai kerjanya pada bulan November 1956,
pada mulanya ada tiga usul yang diusulkan sebagai dasar negara :
Pancasila, Islam dan Sosial ekonomi.
155
Namun untuk yang ketiga ini
sangat sedikit pendukungnya, sehingga wajar bila Takdir Alisyahbana
sebagai mana dikutip oleh Endang Saifuddin Anshari menyatakan bahwa
yang tampak mencolok dalam perdebatan-perdebatan dalam penyusunan
kontitusi oleh majlis konstituante secara keseluruhan terbagi dalam dua
kelompok : yang pertama menghendaki Islam sedangkan yang lainnya
menuntut penerimaan Pancasila sebagai dasar negara.
156
Bagi pendukung Pancasila, mereka berpandangan bahwa agama
adalah sangat luhur dan sangat suci. Penafsiran pernyataan ini diwakili
oleh Suwiryo, ketua umum PNI, sebagaimana dikutip Endang Saifuddin
Anshori, ia berkta: Justru karena agama itu sangat luhur dan sangat suci,
153
Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional Kisah dan Analisis Perkembangan Politik
Indonesia 1945 1965, Bandung: Mizan, Cet. Ke-2, 2000, hlm. 282.
154
Konstituante adalah sebuah majlis yang terdiri lebih 500 anggota yang terpilih secara
demokratis pada tahun 1955, mewakili seluruh bangsa Indonesia dan diberi tugas untuk memberi
wujud nyata kepada pandangan bangsa mengenai demokrasi dan pemerintahan kontitusional, serta
secara independen merancang Undang-Undang Dasar yang devinitif bagi Indonesia. Lihat Adnan
Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-legal atas
Konstituante 1956 1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 408.
155
Endang Saifuddin Anshari, Op. Cit., hlm. 77.
156
Ibid., hlm. 78.
66
maka kami berkeberatan jika agama dipakai sebagai dasar negara.
157
Kemudian ia mengutip pernyataan yang ditandatangani oleh Soekarno dan
Hatta pada tanggal 4 September 1957: Bahwa Pancasila, yang
dicantumkan dalam mukadimah Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia tahun 1945, adalah jaminan hakiki bagi seluruh rakyat
Indonesia, untuk berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.
158
Sementara Natsir yang mewakili tokoh Islam sebagaimana dikutip
Endang Saifuddin Anshari berpendapat bahwa Pancasila sebagai falsafah
negara adalah kabur dan tidak berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam
yang sudah memiliki pandangan hidup yang tegas, terang dan hidup dalam
tuntunan kekuatan lahir dan batin, yakni Islam. Kepada para pendukung
Pancasila Natsir menghimbau :
Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara
pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa, baik sebagai
pendukang Pancasila atau sebagai orang yang beragama, malah akan
memperoleh satu state philoshophy yang hidup berjiwa, berisi tegas
dan mengandung kekuatan. Tak ada satu pun dari lima sila yang
terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput akan gugur, apabila
saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara.
159
Senada dengan pendapat Natsir, KH. Masykur juga mengemukakan
gagasan agar ketujuh kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya yang telah dihapus oleh PPKI dimasukkan
kembali ke dalam mukadimah UUD 1945.
160
Kenyataan inilah
menunjukkan bahwa wakil Islam di konstituante tidak ingin menerima
157
Ibid., hlm. 82.
158
Ibid.
159
Ibid., hlm. 84.
160
Deliar Noer, Op. Cit., hlm. 288.
67
UUD 1945 tanpa modifikasi, sehingga mereka mengambil keputusan
untuk mengembalikan anak kalimat tersebut. Akan tetapi, pendapat
tersebut sangat keras ditentang oleh golongan Pancasila.
161
Perdebatan-perdebatan yang mementingkan prinsip dan pandangan
masing-masing kelompok tersebut di atas terus berlangsung dalam sidang
konstituante, dan bahkan dirasa makin hari makin menajam.
Melihat kondisi tersebut, majlis konstituante sendiri kemudian
cenderung untuk mencari titik persetujuan. Wilopo, ketua umum majlis
konstituante memandang sangat perlu untuk menempuh kompromi dari
berjenis-jenis paham tersebut.
162
Semangat dan pendapat yang sama dituturkan pula oleh Firmansyah,
tokoh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Ia menyerukan kepada
segenap anggota konstituante untuk dapat menyatupadukan pendapat
dalam satu pendapat yang bulat, sehingga masing-masing pihak tidak
merasa kecewa dan dirugikan.
163
Namun ternyata perdebatan tentang ideologi negara tersebut terus
berlangsung sampai sidangnya yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959,
164
tanpa suatu keputusan bulat tentang dasar negara: Pancasila atau Islam.
165
Dengan demikian pembuatan suatu Undang-undang Dasar permanen
menjadi terbengkelai. Situasi ini, oleh pemerintah dianggap sebagai suatu
kemacetan konstitusional yang serius. Maka pada tanggal 5 Juli 1959,
161
Ibid.
162
Endang Saifuddin Anshari, Op. Cit., hlm. 85.
163
Ibid.
164
Ahmad Syafii Maarif, Op. Cit., hlm. 175.
165
Ibid.
68
Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari pihak militer
mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 menggantikan
UUDS 1950 dan sekaligus membubarkan konstituante.
166
Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka dasar Islam yang
diusulkan dengan sendirinya tertolak melalui sebuah dekrit tersebut. Akan
tetapi, perlu di ingat bahwa dalam dekrit tersebut tertuliskan: kami
berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai
Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian
kesatuan dengan konstitusi tersebut.
167
Tercantumnya konsiderasi
tersebut menurut Syafii Maarif jelas merupakan suatu kompromi politik
lagi antara pendukung dasar Pancasila dan pendukung dasar Islam.
168
Lebih lanjut Syafii Maarif menuturkan, sekalipun hanya secara
implisit, namun gagasan untuk melaksanakan syariat bagi pemeluk agama
Islam tidaklah dimatikan.
169
Inilah barangkali tafsiran yang akurat dan adil
terhadap kaitan dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Piagam Jakarta yang
ternyata tidak secara mutlak merugikan dan memarginalkan aspirasi
tokoh-tokoh Islam.
c. Pola Hubungan Agama dan Negara di Era Orde Baru
Pergantian kekuasaan di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru,
tahun 1965 / 1966, membawa implikasi yang cukup banyak dalam
166
Yusril Ihza Mahendra, Op. Cit., hlm. 82.
167
Endang Saifuddin Anshari, Op. Cit., hlm. 157.
168
Ahmad Syafii Maarif, Op. Cit., hlm. 181.
169
Ibid.
69
kehidupan berbangsa dan bernegara. Diantaranya ialah lenyapnya secara
formal ideologi kelas komunis yang menjadi musuh utama masyarakat
religius Indonesia, hilangnya kekuasaan demokrasi terpimpin yang
otoriter, dan lahirnya ideologi pembangunan yang pragmatis dan
kekuasaan non sektarian. Ciri utama yang sangat menonjol yaitu tampilnya
pemerintahan Orde Baru sebagi pelaku tunggal perubahan sosial. Orde
Baru dengan program pembangunan berencana pada lima tahunan (Pelita)
telah menjadikan dirinya sebagai pelaku utama transportasi sosial.
170
Kebijakan Orde Baru dalam memegang kakuasaan berpegang pada
prinsip non sektarian (termasuk dalam agama), dan keseragaman
ideologi Pancasila bagi semua organisasi sosial politik dan organisasi
kemasyarakatan.
171
Seluruh kebijakan Orde Baru, baik dalam bidang
politik, ekonomi, dan pendidikan ditujukan untuk semuanya, dalam arti
tidak memihak kepada salah satu golongan.
Mengkaji hubungan agama dan negara dalam masa Orde Baru ini
dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni hubungan yang bersifat
antagonistik; merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya
ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama, dan
hubungan yang bersifat akomodatif; sifat hubungan dimana negara dan
agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan mamiliki
kesamaan untuk mengurangi konflik.
172
170
Taufuq Nugroho, Op. Cit., hlm. 45.
171
Ibid., hlm. 87.
172
Dede Rosyada, et al., Loc. Cit.
70
a. Hubungan Antagonistik
Eksistensi Islam politik ( political Islam) pada masa kemerdekaan
dan sampai pasca revolusi pernah dianggap sebagi pesaing kekuasaan
yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Persepsi tersebut,
membawa implikasi terhadap gerak ideologi politik Islam. Sebagai hasil
dari kebijakan politik ini, bukan saja para dan aktifis Islam gagal untuk
menjadikan Islam sebagai ideologi dan atau negara (pada 1945 dan
decade 1990-an) tetapi mereka sering disebut sebagai kelompok yang
secara politik minoritas atau outsider. Lebih dari itu, bahkan politik
Islam dicurigai sebagai anti ideologi negara Pancasila.
173
Lebih lanjut Bahtiar mengatakan bahwa di Indonesia, akar
antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat
dilepaskan dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang
berbeda. Awal hubungan yang antagonistik ini dapat ditelusuri dari
masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional terlibat dalam
perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.
174
Kendatipun ada upaya-upaya untuk mencarikan jalan keluar dari
ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik
formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis
Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru. Antara
lain karena negara memberlakukan kebijakan the politics of
173
Bahtiar Effendy, Teologi Baru Politik Islam, Yogyakarta: Galang Press, 2001, hlm. 4.
174
Ibid., hlm. 9.
71
containment agar wacana politik Islam yang fomalistik, legalistik dan
simbolistik itu tidak berkembang lebih lanjut.
175
Kepada Islam politik Orde Baru hubungannya diwarnai dengan
kecurigaan, dan kepada Islam Ibadah menunjukkan kenaikan terus
menerus.
176
Pemerintah menunjukkan kebijakan yang meminggirkan
peran politik umat Islam, sehingga muncul sikap antagonistik dari umat
Islam.
177
Kebijakan Orde Baru di bawah kepeminpinan Soeharto, sekalipun
mengakui pentingnya nilai-nilai keagamaan dan moral, nilai-nilai
keagamaan dan moral ini diberi bingkai Pancasila. Ada pembatasan-
pembatasan tertentu yang mengarahkan pemikiran-pemikiran
keagamaan sehinga tidak memunculkan dan terbentuknya politik
keagamaan. Hal ini sangat kelihatan dengan usaha yang dilakukan
pemerintah Soeharto untuk menyederhanakan partai-partai Islam ke
dalam politik tunggal.
178
Syafii Maarif (1935 M.) menambahkan, bahwa pemerintah pun
kemudian menekankan agar nama partai ini tidak secara eksplisit
menampilkan Islam. Nama Partai Persatuan Pembangunan, merupakan
usaha sterilisasi pihak pemerintah untuk menghilangkan warna ke-
Islaman. Bahkan pada tahap yang lebih lanjut lambang Kabah, sebagai
simbol ke-Islamannya pun kamudian dilorotnya. Dan terakhir dengan
175
Ibid.
176
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung: Mizan, Cet. Ke-2, 1997, hlm. 198.
177
Khamami Zada, Islam Radikal Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di
Indonesia, Jakarta: Teraju, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 29.
178
Ahmad Syafii Maarif, pengantar dalam Rusli Karim, Op. Cit., hlm. xii.
72
ditekankan dan dipaksakannya pemakaian Asas Tunggal pada setiap
parpol dan ormas.
179
Dalam hal inilah timbul banyak tantangan.
Keberatan-keberatan masyarakat di seputar isu penunggalan asas
berkisar dari pelanggaran hak berserikat sampai penghilangan ciri , sifat
atau watak yang bisa juga bersifat keagamaan.
180
Sikap pemerintah yang demikaian ini tidaklah lepas dari
kecemasannya terhadap massa Islam. Pengalaman sejarah yang
menunjukkan kegigihan umat dalam memperjuangkan ideologi Islam
baik dalam parlemen maupun non parlementer. Sehingga, kecemasan
tersebut dilandasi oleh kekhawatiran akan lahirnya radikalisme Islam.
181
Bukti sejarah sudah cukup membuktikan hal tersebut. Islam sering
kali dijadikan simbol perlawanan terhadap pemerintah yang sedang
berkuasa. Islam memang sangat potensial untuk menjadi oposisi
abadi. Menurut Taufiq Nugroho, setidaknya ada dua alasan yang
mendukung pernyataan tersebut. Pertama, ajaran Islam selalu melihat
realitas sosial harus menyesuaikan terhadap tatanan moral ideal. Ajaran
ini selalu mengilhami penganutnya untuk melakukan amar maruf nahi
munkar tanpa lelah. Kedua, dibalik peran opososi tesebut terdapat
sejumlah kekecewaan, baik yang bersifat ideologis, politis, maupun
ekonomis, terutama dari mereka yang tersingkir (masyarakat lapisan
bawah). Sekali lagi Islam tampil sebagi simbol perlawanan kepada
179
Ibid.
180
Bahtiar Effendy, (Re)Politisasi Islam Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?, Editor: A.
Suryana Sudrajat, Bandumg: Mizan, Cet. Ke-1, 2000, hlm. 233.
181
Taufiq Nugroho, Op. Cit., hlm. 90.
73
siapapun tanpa pandang bulu lagi atau radikalisme inilah yang
kemudian mengesankan Islam sebagai kelompok pembangkang
abadi.
182
Kebijakan Orde Baru juga menutup rapat kapada Islam yang
bergerak pada jalur struktur. Yaitu pergerakan Islam dalam jalur politik.
Gerakan struktur ini membawa panji-panji Islam dengan tujuan
membawa aspirasi politik Islam melalui jalur parlemen. Bila ada
gerakan Islam yang mencoba memasuki jalur ini, maka Orde Baru tidak
segan-segan akan memotong sampai ke akar-akarnya dengan jalannya
sendiri.
183
Pengendalian birokrasi secara efektif talah menipiskan watak
ideologi kehidupan sosial umat Islam, sehingga kekuatan ideologis
partai-partai dan organisasi sosial Islam (santri) semakin melemah dan
tidak berfungsi. Tipisnya watak ideologis Islam tersebut
memperlonggar solidaritas primordial antara partai dan pemimpin umat
dengan para pemeluknya.
184
Menurut Mulkhan lebih lanjut, berdasarkan kondisi partai dan
organisasi Islam tersebut di atas , Orde Baru menerapkan politik
depolitisasi. Hubungan struktural massa rakyat dan umat Islam dengan
182
Ibid., hlm.91.
183
Ibid., hlm. 92.
184
Abdul Munir Mulkhan, Teologi Kiri Landasan Gerakan Membela Kaum Mustadlafin,
Yogyakarta: Kreasi Wacana, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 185.
74
partai menjadi terputus akibat politik massa mengambang dan
penyederhanaan partai-partai politik.
185
Dengan berpegang pada kebijakan di atas, maka negara kita tidak
segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap para perusuh ideologi
yang akan mengganggu ideologi negara dan jalannya pembangunan,
termasuk kalangan Islam yang mencoba mengibarkan ideologi
sektarian Islam.
186
Langkah-langkah demikian yang dilakukan oleh Soeharto
menurut Syafii Maarif, baik langsung maupun tidak langsung,
merupakan usaha-usaha yang sistematis untuk meminggirkan dan
bahkan menghilangkan simbol-simbol Islam dalam kancah politik
nasional Indonesia.
187
Setelah pemerintahan Orde Baru memantapkan
kekuasaannya, terjadi kontrol yang demikian berlebihan yang
diterapkan kepada kekuatan politik Islam, terutama pada kelompok
radikal yang dikhawatirkan semakin militan dan menandingi eksistensi
negara.
188
Realitas empirik inilah yang kemudian menjelaskan bahwa
hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik,
dimana negara benar-benar mencurigai Islam sebagai kekuatan yang
potensial dalam merongrong integritas negara.
189
Sementara di sisi lain
185
Ibid.
186
Taufuq Nugroho, Op. Cit., hlm. 88.
187
Ahmad Syafii Maarif , pengantar dalam Rusli Karim, Loc. Cit.
188
Dede Rosyada,et al., Op. Cit., hlm. 65.
189
Ahmad Syafii Maarif, Pengantar dalm M. Rusli Karim, Op. Cit., hlm. xiii.
75
umat Islam sendiri memiliki semangat untuk mendirikan Islam sebagai
sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan.
b. Hubungan Akomodatif
Pola hubungan yang bersifat akomodatif terlihat ketika mulai
munculnya agresifitas politik Islam yang mengakibatkan turunnya nilai
ketegangan dari hubungan antara agama (Islam) dengan negara pada
masa Orde Baru. Menurut Nugroho, gejala menurunnya ketegangan
hubungan ini mulai terlihat pada pertengahan tahun 1980-an. Hal ini
ditandai dengan semakin besarnya peluang umat Islam dalam
mengembangkan wacana politiknya serta munculnya kebijakan-
kebijakan yang dianggap positif bagi umat Islam. Kebijakan-kebijakan
tersebut berspektrum luas dalam memberikan kesempatan bergerak
kepada Islam kultural.
190
Menurut Fachry Ali, politik akomodasi ini mulai dilaksanakan
ketika negara mulai terasing dari lingkungannya. Gejala
keterasingan ini telah mulai tampak ketika aliansi negara dengan
kaum menengah kota gagal berlanjut dengan peristiwa Malari 1974.
191
Sementara menurut Affan Gaffar, sebagaimana dikutip dalam
Dede Rosyada, et al., kecenderungan akomodasi negara terhadap Islam
juga ditengarai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang
190
Yang dimaksud dengan Islam jalur kultur adalah pergerakan Islam melalui wilayah
budaya, tidak melalui gerakan jalur politik praktis. Taufiq Nugroho, Op. Cit., hlm. 91.
191
Fachry Ali, Golongan Agama dan Etika Kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam
Islam Indonesia, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. Ke-1, 1996, hlm. 3.
76
pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik
umat Islam sendiri. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam
merupakan kekuatan politik yang potensial, yang oleh karenanya,
negara lebih memilih akomodasi terhadap Islam, karena jika negara
menempatkan Islam sebagai outsider negara, maka konflik akan sulit
dihindari yang pada akhirnya akan membawa imbas terhadap proses
pemeliharaan negara kesatuan Republik Indonesia.
192
Munculnya sikap akomodatif negara terhadap Islam menurut
Thaba dikutip dari buku yang sama lebih disebabkan oleh adanya
kecenderungan bahwa umat Islam Indonesia dinilai telah semakin
memahami kabijakan negara, terutama dalam konteks pemberlakuan
dan penerimaan asas tunggal Pancasila.
193
Sehingga, pada tahun-tahun terakhir Orde Baru ditandai dengan
akomodatif negara terhadap aspirasi-aspirasi Islam seperti didirikannya
BMI dan ICMI,
194
disusun undang-undang dan peraturan yang
menjamin tercapainya politik Islam.
195
Sehingga, lahir kemudian UUP
(perkawinan) tahun 1971, pembentukan wadah musyawarah antar umat
beragama, penyesuaian dan penyetaraan sekolah agama (Islam) melalui
SKB Tiga Menteri tahun 1975, dan disahkannya UU Peradilan Agama
(UUPA) tahun 1989.
196
Dan untuk mempermudah proses penyelesaian
192
Dede Rosyada, et al., Op. Cit., hlm. 66.
193
Ibid.
194
Andito (Abu Zahra) (ed), Op. Cit., hlm. 39.
195
Abdul Munir Mulkhan, Op. Cit., hlm. 180.
196
Ibid., hlm. 181.
77
sengketa di Peradilan Agama, pemerintah menyusun Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, yaitu semacam fiqh ala Indonesia.
197
Ini semua berlangsung tidak sepihak. Disamping adanya
kenyataan bahwa mayoritas rakyat dan pemimpin Indonesia adalah
muslim dan karenanya wajar kalau nilai-nilai Islam turut membentuk
dan mempengaruhi kehidupan politik nasional, pada masa Orde Baru
terjadi transformasi pemikiran dan praktik politik Islam; dari yang
bersifat legalistik-formalistik ke substansifistik; dari politik formalisme
dan simbolisme ke politk yang lebih berorientasi pada isi.
198
Apapun
latar belakang politik Islam Orde Baru tampaknya telah
mengembangkan kehidupan muslim dan berbagai lembaga sosial dan
dakwah ke arah sikap rasional dan fungsional yang kemudian memberi
peluang perkembangan kualitatif kahidupan muslim di Indonesia.
Sikap akomodatif Orde Baru dengan mengendalikan dan
mengarahkan potensi umat Islam, sebagai umat mayoritas di negeri ini,
diharapkan akan lahir Islam yang nasionalis. Dengan demikian menurut
Nugroho, Orde Baru sangat berharap bahwa Islam akan menjadi
pendukung kuat terhadap Nasionalisme Indonesia.
199
Maka dalam kebijakan selanjutnya, dalam banyak hal, Islam
kultural memperoleh dukungan politik, bahkan fasilitas penguasa Orde
Baru. Bagi yang memakai jalur kultur ini, maka akan bisa
197
M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalm Wawasan Fiqh, Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2002, hlm. 91.
198
Andito (Abu Zahra) (ed), Loc. Cit.
199
Taufiq Nugroho, Loc. Cit.
78
berkomunikasi dan memperoleh fasilitas dari pemerintah secara mudah
dalam berbagai kegiatannya, misalnya organisasi haji yang selalu
memperoleh dukungan optimal. Disamping itu, sebagian cotoh dalam
mendukung jalur kultural ini, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan
Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang konsentrasinya adalah
mendirikan masjid-masjid.
200
Bila diamati, sikap akomodatif Orde Baru terhadap Islam ini
menyimpan muatan politis yang mendalam. Pergerakan Islam kultural
dibina sedemikian rupa oleh negara karena dipandang dapat membantu
suksesnya kinerja pemerintah. Sementara di sisi lain, Islam struktural
tidak diberi kesempatan bernafas sedikitpun dalam format legal
formalnya, karena dikhawatirkan akan menciptakan Islam radikal yang
dapat merongrong integritas rezim yang ada.
Dengan demikian, dari penjelasan dalam Bab ini dapat
disimpulkan bahwa pergulatan agama (Islam) dan politk (negara), baik
mengenai konsep politik Islam --baik yang klasik maupun modern,
mengenai kriteria penguasa, hubungan penguasa dan rakyatnya, bentuk
negara dan pemerintahan, dan lain-lainnya masih menjadi perdebatan
yang belum tuntas sampai sekarang. Konsep pemikiran tentang agama
(Islam) dan politik (negara) tersebut terus bergulir sesuai dengan
perjalanan waktu dan situasi yang berkembang.
200
Ibid., hlm. 91-92.
79
Kemudian, mengenai hubungan agama dan negara secara praksis,
khususnya di Indonesia, mengalami pasang surut. Dikatakan demikian
karena hubungan tersebut pada saat-saat tertentu bersifat konflik, tetapi
pada saat yang lain terjadi hubungan yang harmonis. Hubungan
konfliktual itu sendiri terjadi karena keduanya saling mencurigai. Di
satu sisi Islam curiga terhadap negara karena negara dinilai telah
menghalangi kepentingan Islam, yaitu umat Islam sebagai mayoritas
tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya. Sementara
di sisi lain negara juga senantiasa mencurigai Islam. Hal ini
dikarenakan cita-cita politik Islam adalah mendirikan Negara Islam,
sebagaimana yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh Islam dalam
Konstituante dengan menawarkan Islam sebagai dasar negara
Indonesia. Sehingga pemerintah sangat khawatir, karena dapat
menggoyahkan ideologi dan stabilitas negara
Sementara hubungan yang harmonis dari keduanya juga nyata.
Kondisi seperti ini tampak terjadi pada masa-masa separuh akhir dari
rezim Orde Baru, di mana pemerintah telah memberi banyak
kesempatan dan membantu pada berdirinya organisasi-organisasi Islam,
tempat-tempat peribadatan, dan jamiyah-jamiyah Islam, sebagaimana
telah dicontohkan di atas . Akan tetapi, solidaritas pemerintah terhadap
Islam ini hanya terbatas pada pergerakan Islam kultural. Sementara
pergerakan Islam politik yang bersifat struktural terus diawasi dan
dicurigai oleh pemerintah dalam setiap langkah dan perkembangannya.
80
81
Anda mungkin juga menyukai
- Format SPJ Penerima Hibah 2013Dokumen4 halamanFormat SPJ Penerima Hibah 2013JoesoefteaBelum ada peringkat
- Standar Akuntansi Keuangan Syariah JadiDokumen134 halamanStandar Akuntansi Keuangan Syariah JadiAndikaPramuktiBelum ada peringkat
- Teknik IndustriDokumen151 halamanTeknik IndustriCandu Naraya LanaBelum ada peringkat
- Sop KJKSDokumen291 halamanSop KJKSIrawan D Soedradjat100% (1)
- Konsep Psikologi Al-FarabiDokumen13 halamanKonsep Psikologi Al-FarabiSaepul RochmanBelum ada peringkat
- Maulid Diba - Terjemah WWW - Pustakaaswaja.web - Id PDFDokumen36 halamanMaulid Diba - Terjemah WWW - Pustakaaswaja.web - Id PDFThoque Isma'il100% (1)
- Laporan Keuangan Bank SyariahDokumen29 halamanLaporan Keuangan Bank SyariahCandu Naraya LanaBelum ada peringkat
- HAMKA - Tafsir Al Azhar Juz 30 PDFDokumen188 halamanHAMKA - Tafsir Al Azhar Juz 30 PDFMuhammad Arif Darmawan100% (3)
- Menumbuhkan Minat WirausahaDokumen10 halamanMenumbuhkan Minat WirausahaHikmah Ja'far MunabariBelum ada peringkat
- Out Look Bs 2013 Seminar 1Dokumen54 halamanOut Look Bs 2013 Seminar 1Candu Naraya LanaBelum ada peringkat
- Arah Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia.Dokumen26 halamanArah Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia.Candu Naraya LanaBelum ada peringkat
- Allah Dalam Akidah IslamDokumen41 halamanAllah Dalam Akidah IslamSyihabudin AhmadBelum ada peringkat
- Teologi Islam (Ilmu Kalam)Dokumen10 halamanTeologi Islam (Ilmu Kalam)Alfan Ghinan Rusydi100% (1)
- Struktur Logika Dalam Teori Hukum IslamDokumen29 halamanStruktur Logika Dalam Teori Hukum IslamRachael JohnsonBelum ada peringkat