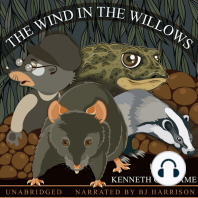Kritik Arsitektur Dan Teori Perilaku
Kritik Arsitektur Dan Teori Perilaku
Diunggah oleh
Nabila Febitsukarizky BunyaminHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kritik Arsitektur Dan Teori Perilaku
Kritik Arsitektur Dan Teori Perilaku
Diunggah oleh
Nabila Febitsukarizky BunyaminHak Cipta:
Format Tersedia
KRITIK ARSITEKTUR DAN TEORI PERILAKU
Jenis Kritik Arsitektur
1. Kritik Normatif Kritik ini berdasarkan pada pedoman baku normatif. Kritik normatif mempunyai dasar berupa doktrin, sistem, tipe atau ukuran tertentu. Kritik ini bergantung pada keyakinan yang digunakan sebagai pedoman baku untuk menilai rancangan bangunan atau kota. Hakikat kritik normatif adalah adanya keyakinan (conviction) bahwa di lingkungan dunia manapun, bangunan dan wilayah perkotaan selalu dibangun melalui suatu model, pola, standard atau sandaran sebagai sebuah prinsip. Dan melalui ini kualitas dan kesuksesan sebuah lingkungan binaan dapat dinilai. Norma bisa jadi berupa standar yang bersifat fisik, tetapi adakalanya juga bersifat kualitatif dan tidak dapat dikuantifikasikan. Norma juga berupa sesuatu yang tidak konkrit dan bersifat umum dan hampir tidak ada kaitannya dengan bangunan sebagai sebuah benda konstruksi. Karena kompleksitas, abstraksi dan kekhususannya kritik normatif perlu dibedakan dalam metode sebagai berikut :
a. Doktrin ( satu norma yang bersifat general, pernyataan prinsip yang tak terukur) b. Sistem ( suatu norma penyusunan elemen-elemen yang saling berkaitan untuk satu tujuan) c. Tipe ( suatu norma yang didasarkan pada model yang digenralisasi untuk satu kategori bangunan spesifik) d. Ukuran ( sekumpulan dugaan yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif)
a. D O K T R I N A L Doktrin sebagai dasar dalam pengambilan keputusan desain arsitektur yang berangkat dari keterpesonaan dalam sejarah arsitektur. Sejarah arsitektur dapat meliputi : nilai estetika, etika, ideologi dan seluruh aspek budaya yang melekat dalam pandangan masyarakat. Melalui sejarah, kita mengenal terjadinya bentuk dalam arsitektur melalui norma yang berkembang seperti : o Form Follow Function o Function Follow Form o Form Follow Culture o Form Follow World View o Less is More o Less is Bore o Big is beauty o Buildings should be what they wants to be
o Building should express : Structure, Function, Aspiration, Construction Methods, Regional Climate and Material o Ornament is Crime o Ornament makes a sense of place, genius loci or extence of architecture. Doktrin bersifat tunggal dalam titik pandangnya dan biasanya mengacu pada satu ISME yang dianggap paling baik untuk mengukur kualifikasi arsitektur yang diharapkan. Tidak etik menggunakan keberhasilan arsitektur masa lalu untuk bangunan fungsi mutakhir Tidak etik memperlakukan teknologi secara berbeda dari yang dilakukan sebelumnya Jika akan mereproduce objek yang muncul pada masa lalu untuk masa kini harus dipandang secara total dan dengan cara pandang yang tepat Bahwa desain arsitektur selalu mengekspresikan keputusan desain yang tepat Secara sosial bangunan akan tercela bila ia merepresentasikan sikap seseorang dan tidak didasarkan pada hasrat yang tumbuh dari kebutuhan masyarakatnya
b. S I S T E M A T I K Bagi Kritikus dan Desainer bergantung pada hanya satu doktrin sangat riskan untuk mendukung satu keputusan desain
Menggantungkan pada hanya satu prinsip akan mudah diserang sebagai : menyederhanakan (simplistic), tidak mencukupi (inadequate) atau kadaluarsa (out of dated )
Alternatifnya adalah bahwa ada jalinan prinsip dan faktor yang dapat dibangun sebagai satu system untuk dapat menegaskan rona bangunan dan kota.
Systematic Criticsm dipandang cukup lebih baik daripada doktrin yang tunggal untuk dihadapkan pada kompleksitas kebutuhan dan pengalaman manusia
c. T E R U K U R Kritik terukur menyatakan satu penggunaan bilangan atau angka hasil berbagai macam observasi sebagai cara menganalisa bangunan melalui hukum-hukum matematika tertentu. Norma yang terukur digunakan untuk memberi arah yang lebih kuantitatif. Hal ini merupakan satu bentuk analogi dari ilmu pengetahuan alam yang diformulasikan untuk tujuan kendali rancangan arsitektural. Pengolahan melalui statistik atau teknik lain secara matematis dapat mengungkapkan informasi baru tentang objek yang terukur dan wawasan tertentu dalam studi arsitektur. Perbedaan dari kritik normatif yang lain adalah terletak pada metode yang digunakan yang berupa standardisasi desain yang sangat kuantitatif dan terukur secara amtematis. Bilangan atau standard pengukuran secara khusus memberi norma bagaimana bangunan diperkirakan pelaksanaannya.
Standardisasi pengukuran dalam desain bangunan dapat berupa : a. Ukuran batas minimum atau maksimum b. Ukuran batas rata-rata (avarage) c. Kondisi-kondisi yang dikehendaki
Adakalanya standard dalam pengukuran tidak digunakan secara eksplisit sebagai metoda kritik karena masih belum cukup memenuhi syarat kritik sebagai sebuah norma
Norma atau standard yang digunakan dalam kritik terukur bergantung pada ukuran minimum/maksimum, rata-rata atau kondisi yang dikehendaki yang selalu merefleksikan berbagai tujuan dari bangunan itu sendiri.
Tujuan dari bangunan biasanya diuraikan dalam tiga ragam petunjuk sebagai berikut: 1. Tujuan Teknis ( Technical Goals) Kesuksesan bangunan dipandang dari segi standardisasi ukurannya secara teknis. Contoh : Sekolah, dievaluasi dari segi pemilihan dinding interiornya. Pertimbangan yang perlu dilakukan adalah :
a. Stabilitas Struktur - Daya tahan terhadap beban struktur - Daya tahan terhadap benturan - Daya dukung terhadap beban yang melekat terhadap bahan - Ketepatan instalasi elemen-elemen yang di luar sistem b. Ketahanan Permukaan Secara Fisik
- Ketahanan permukaan - Daya tahan terhadap gores dan coretan - Daya serap dan penyempurnaan air c. Kepuasan Penampilan dan Pemeliharaan - Kebersihan dan ketahanan terhadap noda - Timbunan debu yang mungkin menempel - Kemudahan dalam penggantian terhadap elemen-elemen yang rusak - Kemudahan dalam pemeliharaan baik terhadap noda atau kerusakan teknis dan alami. 2. Tujuan Fungsi ( Functional Goals) Berkait pada penampilan bangunan sebagai lingkungan aktifitas yang khusus maka ruang harus dipenuhi melalui penyediaan suatu area yang dapat digunakan untuk aktifitas tersebut. Pertimbangan yang diperlukan : Keberlangsungan fungsi dengan baik Khusus yang perlu dipenuhi Kondisi-kondisi khusus yang harus diciptakan Kemudahan-kemudahan penggunaan Pencapaian dan sebagainya.
3. Tujuan Perilaku ( Behavioural Goals) Bangunan tidak saja bertujuan untuk menghasilkan lingkungan yang dapat berfungsi dengan baik tetapi juga lebih kepada dampak bangunan terhadap
individu. Kognisi mental yang diterima oleh setiap orang terhadap kualitas bentuk fisik bangunan. d. T I P I K A L Studi tipe bangunan saat ini telah menjadi pusat perhatian para sejarawan arsitektur. Hal ini dapat dipahami karena desain akan menjadi lebih mudah dengan mendasarkannya pada type yang telah standard, bukan pada innovative originals (keaslian inovasi). Studi tipe bangunan lebih didasarkan pada kualitas, utilitas dan ekonomi dalam lingkungan yang telah terstandarisasi dan kesemuanya dapat terangkum dalam satu typologi. Menurut Alan Colquhoun (1969), Typology & Design Method, in Jencks, Charles, Meaning in Architecture, New York: G. Braziller : Type pemecahan standard justru disebut sebagai desain inovatif. Karena dengan ini problem dapat diselesaikan dengan mengembalikannya pada satu convensi (type standard) untuk mengurangi kompleksitas. March, Lionel and Philip Steadman (1974), The Geometry of Environment, Cambridge : MIT Press, bahwa pendekatan tipopolgis dapat ditunjukkan melalui tiga rumah rancangan Frank Lloyd Wright didasarkan atas bentuk curvilinear, rectalinear dan triangular untuk tujuan fungsi yang sama. Kritik Tipikal diasumsikan bahwa ada konsistensi dalam pola kebutuhan dan kegiatan manusia yang secara tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan
pembangunan lingkungan fisik Elemen Kritik Tipikal
Typical Criticsm didasarkan atas : 1. Struktural (Struktur) Tipe ini didasarkan atas penilaian terhadap lingkungan dikaitkan dengan lingkungan yang dibuat dengan material yang sama dan pola yang sama pula. 2. Function (Fungsi) Hal ini didasarkan pada pembandingan lingkungan yang didesain untuk aktifitas yang sama. 3. Form (Bentuk) Diasumsikan bahwa ada tipe bentuk-bentuk yang eksestensial dan memungkinkan untuk dapat dianggap memadai bagi fungsi yang sama pada bangunan lain. Penilaian secara kritis dapat difocuskan pada cara bagaimana bentuk itu dimodifikasi dan dikembangkan variasinya. Sebagai contoh bagaimana Pantheon telah memberi inspirasi bagi bentukbentuk bangunan yang monumental pada masa berikutnya. 2. Kritik Penafsiran Kritik ini merupakan penafsiran dan bersifat pribadi. Kritik ini menafsirkan dengan pandangannya sendiri dan bukan dengan pedoman-pedoman baku dari luar. Tujuannya adalah untuk menjadikan oran lain melihat lingkungan buatan seperti yang dilihatnya. Unsur kritik penafsiran ada 3, yaitu: a. Kritik Pembelaan
Menafsirkan dengan menggunakan cara baru untuk memandang obyek, biasanya dengan mengubah hiasan atau analogi yang kita gunakan untuk mengamati obyek bangunan. b. Kritik Evokatif Mempunyai maksud menimbulkan perasaan atau emosi yang serupa dengan yang dialami kritikan ketika mengamati bangunan atau suasana kota c. Kritik Impresionistib Kritikus menggunakan obyek yang diamati sebagai dasar untuk menciptakan karya seni yang lain. Masih terdapat unsur penafsiran tetapi fokus kritikan terletak pada penciptaan sesuatu yang baru.
3. Kritik Deskriptif Bersifat tidak menilai, tidak menafsirkan, semata-mata membantu orang melihat apa yang sesungguhnya ada. Kritik ini berusaha mencirikan fakta-fakta yang menyangkut sesuatu lingkungan tertentu. Dibanding metode kritik lain descriptive criticism tampak lebih nyata(factual) * Deskriptif mencatat fakta-fakta pengalaman seseorang terhadap bangunan atau kota * Lebih bertujuan pada kenyataan bahwa jika kita tahu apa yang sesungguhnya suatu kejadian dan proses kejadiannya maka kita dapat lebih memahami makna bangunan. * Lebih dipahami sebagai sebuah landasan untuk memahami bangunan melalui berbagai unsur bentuk yang ditampilkannya * Tidak dipandang sebagai bentuk to judge atau to interprete. Tetapi sekadar
metode untuk melihat bangunan sebagaimana apa adanya dan apa yang terjadi di dalamnya. Jenis Metode Kritik Deskriptif * Depictive Criticism (Gambaran bangunan) Static (Secara Grafis) * Depictive criticism dalam aspek static memfokuskan perhatian pada elemen-elemen bentuk (form), bahan (materials) dan permukaan (texture). Dynamic (Secara Verbal) Tidak seperti aspek statis, aspek dinamis depictive mencoba melihat bagaimana bangunan digunakan bukan dari apa bangunan di buat. Aspek dinamis mengkritisi bangunan melalui : Bagaimana manusia bergerak melalui ruang-ruang sebuah bangunan? Apa yang terjadi disana? Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik? Process (Secara Prosedural) Merupakan satu bentuk depictive criticism yang menginformasikan kepada kita tentang proses bagaimana sebab-sebab lingkungan fisik terjadi seperti itu. Biographical Criticism (Riwayat Hidup) Contextual Criticism ( Persitiwa)
JENIS TEORI PERILAKU
1. PRIVASI
Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang hidup dalam kelompok dan mempunyai organisme yang terbatas di banding jenis makhluk lain ciptaan Tuhan. Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan organisasinya itu, manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui
kemampuan akalnya seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup dan lain-lain. Dalam kehidupannya sejak lahir manusia itu telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lain. Seandainya manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jenis jiwanya akan terganggu.
Naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain disebut gregariousness dan oleh karena itu manusia disebut mahluk sosial. Dengan adanya naluri ini, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kehidupannya dan memberi makna kepada kehidupannya, sehingga timbul apa yang kita kenal sebagai kebudayaan yaitu sistem terintegrasi dari perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian manusia dikenal sebagai mahluk yang berbudaya karena berfungsi sebagai pembentuk kebudayaan, sekaligus apat berperan karena didorong oleh hasrat atau keinginan yang ada dalam diri manusia yaitu :
1.
Menyatu
dengan
manusia
lain
yang
berbeda
disekelilingnya
2. Menyatu dengan suasana dalam sekelilingnya
Manusia itu pada hakekatnya adalah mahluk sosial, tidak dapat hidup menyendiri. Ia merupakan Soon Politikon , manusia itu merupakan mahluk yang hidup bergaul, berinteraksi. Perkembangan dari kondisi ini menimbulkan kesatuan-kesatuan manusia, kelompok-kelompok sosial yang berupa keluarga, dan masyarakat. Maka terjadilah suatu sistem yang dikenal sebagai sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang mengatur kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan hidupnya.
Manusia Sebagai Mahluk Individu Individu berasal dari kata latin individuum artinya yang tidak terbagi, maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas yaitu sebagai manusia perseorangan. Dalam pandangan psikologi sosial, manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik dirinya dan bukan lagi mengikuti pola tingkah laku umum. Ini berarti bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan-peranan yang khas didalam lingkungan sosialnya, meliankan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya.
Dalam perkembangannya setiap individu mengalami dan dibebankan berbagai peranan, yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup dengan sesame manusia. Seringakli pula terdapat konflik dalam diri individu, karena tingkah laku yang khas dirinya bertentangan dengan peranan yang dituntut masyarakatnya. Keberhasilan dalam menyesuaikan diri atau memerankan diri sebagai individu dan sebagai warga bagian masyarakatnya memberikan konotasi maang dalam arti sosial. Artinya individu tersebut telah dapat menemukan kepribadiannya atau dengan kata lain proses aktualisasi dirinya sebagai bagian dari lingkungannya telah terbentuk.
Pertumbuhan Individu Perkembangan manusia yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir batin. Dalam arti bahwa individu atau pribadi manusia merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai cirri-ciri khas tersendiri. Walaupun terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli, namun diakui bahwa pertumbuhan adalah suatu perubahan yang menuju kearah yang lebih maju, lebih dewasa. Menurut para ahli yang menganut aliran asosiasi berpendapat, bahwa pertumbuhan pada dasarnya adalah proses asosiasi. Pada proses asosiasi yang primer adalah bagian-bagian. Bagian-bagian yang ada lebih dahulu, sedangkan keseluruhan ada pada kemudian. Bagian-bagian ini terikat satu sama lain menjadi keseluruhan asosiasi. Dapat dirumuskan suatu pengertian tentang proses asosiasi yaitu terjadinya perubahan pada seseorang secara tahap demi tahap karena pengaruh timbal balik dari pengalaman atau empiri luar melalui pancaindera yang menimbulkan sensations maupun pengalaman dalam mengenal keadaan batin sendiri yang menimbulkan sensation. Menurut aliran psikologi gestalt pertmbuhan adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi yang pokok adalah keseluruhan sedang bagianbagian hanya mempunyai arti sebagai bagian dari keseluruhan dalam hubungan fungsional dengan bagian-bagian yang lain. Jadi menurut proses ini keselurhan yang lebih dahulu ada, baru kemudian menyusul bagianbagiannya. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ini adalah proses perubahan secara perlahan-lahan pada manusia dalam mengenal suatu yang semula mengenal sesuatu secara keseluruhan baru kemudian mengenal bagian-bagian dari lingkungan yang ada. Konsep aliran sosiologi tentang pertumbuhan menganggap pertumbuhan itu adalah proses sosialisasi yaitu proses perubahan dari sifat mula-mula yang asosial atau juga sosial kemudian tahap demi tahap disosialisasikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan: 1. Pendirian Nativistik. Menurut para ahli dari golongan ini berpendapat
bahwa pertumbuhan itu semata-mata ditentukan oleh factor-faktor yang dibawa sejak lahir 2. Pendirian Empiristik dan environmentalistik. Pendirian ini berlawanan dengan pendapat nativistik, mereka menganggap bahwa pertumbuhan individu semata-nmata tergantung pada lingkungan sedang dasar tidak berperan sama sekali. 3. Pendirian konvergensi dan interaksionisme. Aliran ini berpendapat bahwa interaksi antara dasar dan lingkungan dapat menentukan pertumbuhan individu.
Dilihat pada Makna dan Nilai Privasi
Privasi dan Kontrol atas Informasi privasi berfokus pada kontrol atas informasi tentang diri yang dipertahankan oleh Warren dan Brandeis dan oleh William Prosser juga didukung oleh komentator yang lebih baru termasuk Fried (1970) dan Induk (1983). Selain itu, Alan Westin menggambarkan privasi sebagai kemampuan untuk menentukan untuk diri kita sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang kami dikomunikasikan kepada orang lain (Westin, 1967). Dia mendefinisikan privasi sebagai kondisi tidak memiliki didokumentasikan informasi pribadi diketahui atau dimiliki oleh orang lain. Orang tua menekankan bahwa ia mendefinisikan kondisi privasi, sebagai nilai moral bagi orang-orang yang hadiah individualitas dan kebebasan, dan bukan atau hukum hak moral untuk privasi. Informasi pribadi ditandai oleh Induk faktual (selain itu akan ditutupi oleh pencemaran nama baik, fitnah atau pencemaran nama baik), dan ini adalah fakta bahwa kebanyakan orang memilih untuk tidak mengungkapkan tentang diri mereka sendiri, seperti fakta tentang kesehatan, gaji, berat, orientasi seksual, dll , Personal. informasi didokumentasikan, Orang Tua pada tampilan, hanya ketika itu adalah milik publik catatan, yaitu, di koran pengadilan catatan, atau dokumen publik lainnya. Jadi, setelah informasi menjadi bagian dari catatan publik, tidak ada
invasi privasi dalam rilis masa depan informasi, bahkan bertahun-tahun kemudian atau ke khalayak luas, juga tidak mengintip atau pengawasan mengganggu privasi jika ada informasi diperoleh didokumentasikan. Privasi dan Martabat Manusia
"kepribadian terhormat" adalah nilai sosial yang dilindungi oleh privasi. Ini mendefinisikan's esensi satu sebagai manusia dan martabat termasuk individu dan integritas, otonomi pribadi dan kemandirian. Menghormati nilainilai ini adalah apa dasar dan menyatukan konsep privasi. Membahas masingmasing empat Prosser jenis hak privasi pada gilirannya, Bloustein membela pandangan bahwa setiap hak-hak privasi sangat penting karena melindungi terhadap penyusupan merendahkan kepribadian dan melawan affronts untuk martabat manusia. Dengan menggunakan analisis ini, secara eksplisit link Bloustein hak privasi dalam hukum gugatan dijelaskan oleh Prosser dengan perlindungan privasi di bawah Amandemen Keempat. Dia mendesak bahwa kedua meninggalkan terbuka individu untuk diawasi dengan cara yang daun's otonomi satu dan rasa diri sebagai orang yang rentan, melanggar martabat manusia satu dan kepribadian moral. Benang konseptual umum yang menghubungkan berbagai kasus privasi melarang penyebaran informasi rahasia, menguping, pengawasan, dan penyadapan, untuk beberapa nama, adalah nilai perlindungan terhadap cedera pada kebebasan individu dan
martabat manusia privasi. Invasi paling baik dipahami, dalam jumlah, sebagai penghinaan terhadap martabat manusia.
Privasi dan Keintiman Privasi sangat penting bagi hubungan dan ini membantu menjelaskan mengapa ancaman terhadap privasi adalah sebuah ancaman bagi integritas kita sebagai orang. Dengan karakteristik privasi sebagai konteks yang diperlukan untuk cinta, persahabatan dan kepercayaan, goreng adalah mendasarkan laporannya pada konsepsi moral bagi manusia dan kepribadian mereka, pada gagasan Kantian orang dengan hak-hak dasar dan kebutuhan untuk mendefinisikan dan mengejar sendiri nilai-nilai yang satu gratis dari tubrukan orang lain. Privasi memungkinkan seseorang kebebasan untuk mendefinisikan's hubungan satu dengan yang lain dan untuk menentukan diri sendiri.Dengan cara ini, privasi juga berhubungan erat dengan rasa hormat dan harga diri. Keintiman tanpa gangguan atau pengamatan diperlukan bagi kita untuk memiliki pengalaman dengan spontanitas dan tanpa malu. Inness berpendapat bahwa keintiman didasarkan bukan pada perilaku, tetapi pada motivasi. Inness berpendapat bahwa informasi intim atau kegiatan yang menarik makna dari cinta, menyukai, atau perawatan. Hal ini privasi yang melindungi kemampuan seseorang untuk menyimpan informasi intim dan aktivitas sehingga seseorang dapat memenuhi kebutuhan salah satu mencintai dan peduli Privasi dan Hubungan Sosial
Rachel (1975) mengakui tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan mengapa privasi adalah penting bagi kami, karena dapat diperlukan untuk melindungi's aktiva satu atau kepentingan, atau untuk melindungi salah satu dari malu, atau untuk melindungi satu terhadap konsekuensi buruk dari kebocoran informasi , untuk nama hanya beberapa. Namun demikian, ia secara eksplisit mengkritik pandangan reduksionis's Thomson, dan mendesak privasi yang merupakan hak khusus. Dia pada dasarnya membela pandangan bahwa privasi diperlukan untuk mempertahankan berbagai hubungan sosial, tidak intim yang adil.
2. TERITORIAL
Holahan (dalam Iskandar, 1990), mengungkapkan bahwa teritorialitas adalah suatu tingkah laku yang diasosiasikan pemilikan atau tempat yang ditempatinya
atau area yang senang melibatkan ciri pemilikannya dan pertahanan dari serangan orang lain Dengan demikian menurut Altman (1975) penghuni tempat tersebut dapat mengontrol daerahnya atau unitnya dengan benar, atau merupakan suatu teritorial primer. Apa perbedaan ruang personal dengan teritorialitas? Seperti pendapat Sommer dan de War (1963), bahwa ruang personal dibawa kemanapun seseorang pergi, sedangkan teritori memiliki implikasi tertentu yang secara geografis merupakan daerah yang tidak berubah-ubah. Teritorialitas merupakan perwujudan ego seseorang karena orang itu tidak ingin diganggu, atau dapat dikatakan sebagai perwujudan dari privasi seseorang. Jika kita amati lingkungan di sekitar kita dengan mudah, akan kita dapati indikator teritorialitas manusia seperti papan nama, pagar batas, atau papan pengumuman yang mencantumkan kepemilikan Julian Edney (1974) mendefinisikan teritorialitas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ruang fisik, tanda, kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personaliasi, dan identitas. Termasuk didalamnya dominasi, kontrol, konflik, keamanan, gugatan akan sesuatu, dan pertahanan.
Teritori berarti wilayah atau daerah dan teritorialitas adalah wilayah yang dianggap sudah menjadi hak seseorang. Contoh: 1. kamar tidur seseorang adalah wilayah yang dianggap sudah menjadi hal seseorang. Meskipun yang bersangkutan sedang tidur di sana dan ada orang yang memasuki kamar tersebut tanpa izinnya, ia akan tersinggung rasa teritorialitasnya dan ia akan marah.
2. misalnya bangku-bangku di kantin. Apabila ada orang yang menempati tempat tersebut, kemudian ingin pergi sebentar untuk memesan makanan, atau pergi ke toilet, ia akan meninggalkan sesuatu seperti buku atau tas di atas meja, dengan harapan orang lain yang melihat ada buku atau tas disitu diharapkan tahu bahwa bangku tersebut sudah menjadi teritorinya sehingga tidak diduduki. Dari uraian tersebut, teritorialitas dapat diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang atas suatu tempat atau suatu lokais geografis. Pola tingkah laku ini mencakup personalisasi dan pertahanan terhadap gangguan dari luar.
KLASIFIKASI TERITORIALITAS Tingkah laku teritorialitas manusia mempunyai dasar yang agak berbeda dengan binatang karena teritorialitas manusia berintikan pada privasi. Sementara itu, fungsi teritorialitas pada hewan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk mempertahankan hidup.
Tingkah laku teritorialitas hewan ini, antara lain membuat atau mendiami tempat hunian, menyimpan bahan makanan di tempat tertentu, mencari atau mengumpulkan makanan dari area tertentu, dan melindungi anak-anaknya dari serangan makhluk lain. Dorongan yang mendasari tingkah laku teritori pada hewan ini dinamakan naluri teritori. Teritorialitas pada manusia mempunya fungsi yang lebih tinggi daripada sekedar fungsi mempertahankan hidup. Pada manusia, teritorialitas ini tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan privasi saja, tetapi lebih jauh lagi teritorialitas juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi komunikasi.
Fungsi Sosial dari teritorialitas adalah misalnyatampak pada pertemuanpertemuan resmi ketika sudah ditentukan tempat duduk setiap orang sesuai dengan tempat kedudukan,jabatan dan pangkat yang bersangkutan. Seorang pegawai biasa tidak berani duduk di bangku terdepan meskipun bangkubangku itu kososng karena bangku-bangku itu untuk pejabat. Dengan demikian teritorialitas juga mencerminkan lapisan sosial dalam masyarakat. Sebagai media komunikasi, teritori juga terbagi dalam beberapa golongan, klasifikasi teritori yang terkenal adalah klasifikasi yang dibuat Altman (1980) yang didasarkan derajat privasi, afiliasi, dan kemungkinan pencapaian. a. Teritori Primer Teritori primer adalah tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya, hanya boleh dimasuki orang-orang yang sudah sangat akrab atau yang sudah mendapat ijin khusus. Teritori ini dimiliki oleh perseorangan atau sekelompok orang yang juga mengendalikan penggunaan teritori tersebut secara relatif tetap, berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Jenis teritori ini dimiliki serta dipergunakan secara khusus bagi pemiliknya. Pelanggaran terhadap teritori utama ini akan mengakibatkan timbulnya perlawanan dari pemiliknya dan ketidakmampuan untuk mempertahankan teritori utama ini akan mengakibatkan masalah yang serius terhadap aspek psikologis pemiliknya, yaitu dalam hal harga diri dan identitasnya. Contoh : ruang kerja, ruang tidur, pekarangan, wilayah negara, dan sebagainya. b. Teritori Sekunder Teritori sekunder adalah tempat-tempat yang dimiliki bersama oleh sejumlah orang yang sudah cukup saling mengenal. Kendali pada teritori ini tidaklah sepenting penggunaan dengan orang asing.
Jenis teritori ini lebih longgar pemakaiannya dan pengontrolan oleh perorangan. Teritorial ini dapat digunakan oleh orang lain yang masih di dalam kelompok ataupun orang yang mempunyai kepentingan kepada kelompok itu. Sifat teritorial sekunder adalah semi-publik. Contoh : sirkulasi lalu lintas di dalam kantor, toilet, zona, servis, ruang kelas, kantin kampus, ruang latihan olahraga, dan sebagainya. c. Teritori Publik Teritori publik adalah tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Pada prinsipnya, setiap orang diperkenankan untuk berada di tempat tersebut. Teritorial umum dapat digunakan oleh setiap orang dengan mengikuti aturanaturan yang lazim di dalam masyarakat di mana teritorial umum itu berada. Teritorial umum dapat dipergunakan secara sementara dalam jangka waktu lama maupun singkat. Contoh : taman kota, tempat duduk dalam bis kota, gedung bioskop, ruang kuliah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, lobi hotel, dan ruang sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum,
Kadang-kadang teritori publik dikuasai oleh kelompok tertentu dan tertutup bagi kelompok yang lain, seperti bar yang hanya untuk orang dewasa atau tempat-tempat hiburan yang terbuka untuk dewasa umum, kecuali anggota ABRI, misalnya. Berdasarkan pemakaiannya, teritorial umum dapat dibagi menjadi tiga: Stalls, Turns, dan Use Space. a. Stalls Stalls merupakan suatu tempat yang dapat disewa atau dipergunakan dalam jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara jangka waktu lama dan agak
lama. Contohnya adalah kamar-kamar di hotel, kamar-kamar di asrama, ruangan kerja, lapangan tenis, sampai ke bilik. b. Turns Turns mirip dengan stalls, hanya berbeda dalam jangka waktu
penggunaannya saja. Turns dipakai orang dalam waktu yang singkat, misalnya tempat antrian karcis, antrian bensin, dan sebagainya. c. Use Space Use Space adalah teritori yang berupa ruang yang dimulai dari titik kedudukan seseorang ke titik kedudukan objek yang sedang diamati seseorang. Contohnya adalah seseorang yang sedang mengamati objek lukisan dalam suatu pameran, maka ruang antara objek lukisan dengan orang yang sedang mengamati tersebut adalah Use Space atau ruang terpakai yang dimiliki oleh orang itu, serta tidak dapat diganggu gugat selama orang tersebut masih mengamati lukisan tersebut. Altman (1975) juga mengemukakan dua tipe teritori lain, yaitu objek dan ide. Meskipun keduanya bukan berwujud tempat, diyakini juga memenuhi kriteria teritori. Karena seperti halnya dengan tempat, orang juga menandai, menguasai, mempertahankan dan mengontrol barang mereka, seperti bukubuku, pakaian, motor, dan objek lain yang dianggap miliknya. Lyman dan Scott (1967) juga membuat klasifikasi tipe teritorialitas yang sebanding dengan klasifikasi Altman. Namun, terdapat dua tipe yang berbeda, yaitu:
1. Teritori interaksi
Ditujukan pada suatu daerah yang secara temporer dikendalikan oleh sekelompok orang yang berinteraksi. Misalnya, sekelompok anak yang masuk ke dalam lapangan bola ketika sedang ada pertandingan bola oprang dewasa, atau seorang anak kecil masuk dalam ruang kuliah yang tidak peruntukkan baginya.
2. Teritori badan Dibatasi oleh badan manusia. Namun, batasannya bukanlah ruang maya, melainkan kulit manusia, artinya segala sesuatu mengenai kulit tanpa izin dianggap gangguan.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12954)