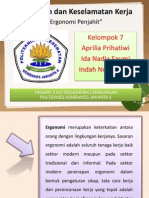Tugas 1 Ptps Complete
Tugas 1 Ptps Complete
Diunggah oleh
idanadiaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tugas 1 Ptps Complete
Tugas 1 Ptps Complete
Diunggah oleh
idanadiaHak Cipta:
Format Tersedia
Tugas 1 PTPS-B Pencemaran Tanah Oleh Sampah
TINGKAT 2 DIV
KELOMPOK 1 : 1. IDA NADIA SAUMI (P2.31.33.1.12.021) 2. INA ISNA SAUMI (P2.31.33.1.12.022) 3. INSAN AIDIL ICHSAN (P2.31.33.1.12.024) 4. NURMALA RUTH NAUMI (P2.31.33.1.12.031)
POLITEKKES JAKARTA II JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN DIPLOMA IV KESEHATAN LINGKUNGAN 2014
1. PENCEMARAN TANAH Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, pengertian tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam PP RI No. 150 tahun 2000 disebutkan bahwa Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Sedangkan Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan
pertanian,perkebunan, dan hutan tanaman. Menurut Wikipedia Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: Kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial Penggunaan pestisida Masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan Kecelakaan kendaraaan pengangkut minyak, Zat kimia, atau limbah Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping). Sumber Pencemaran Tanah Sumber pencemar tanah tidak jauh beda atau bisa dikatakan mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Sebagai contoh gas-gas oksida karbon, oksida nitrogen,oksida belerang yang menjadi bahan pencemar udara yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asam sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah.
Sumber bahan pencemar tanah dapat dikelompokkan juga menjadi sumber pencemar yang berasal dari, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah sakit, gunung berapi yang meletus / kendaraan bermotor dan limbah industri. DAMPAK PENCEMARAN TANAH Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah, diantaranya : Pada Bidang Kesehatan
Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Contohnya : Nama Senyawa Kromnium, Pestisida dan Herbisida Timbal Benzena Merkuri Organofosfat dan karmabat Siklodiena Bahan populasi Kerusakan otak dan ginjal Leukimia Kerusakan ginjal Gangguan saraf oto Keracunan hati Dampak karsinogenik untuk semua
Yang jelas pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Dampak Bagi Ekosistem kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia
Perubahan
beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing
yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat Kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. Dampak bagi pertanian
Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. 2. FUNGSI TANAH TERHADAP BAHAN PENCEMAR Tanah merupakan salah satu unsur lingkungan yang sangat penting terutama dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai sistem penyaring, penyangga kimia (buffer), pengendap, pengalihragaman (transformer), serta pengendali biologi. Dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan, fungsi-fungsi tanah tersebut sangat penting peranannya sebagai pelindung dan penetralisir zat-zat berbahaya yang terdapat dalam sampah maupun limbah. Tanah Sebagai Fungsi Penyaring Tanah sebagai fungsi penyaring karena tubuh tanah terdiri dari jaringan yang memiliki beberapa lapisan dengan kepadatan dan struktur yang berbeda pada tiap lapisan. Limbah atau sampah padat yang mengandung bahan beracun berupa debu yang mengendap, baik dari udara maupun dari perairan ditahan oleh tanah atas (top soil) sehingga tidak terbawa atau ikut terserap masuk ke dalam tanah (perkolasi). Oleh karena itu tanah bawah (sub soil) dan airtanah akan terhindar dari masuknya zat-zat beracun yang berasal dari limbah maupun sampah tersebut. Tanah Sebagai Fungsi Penyangga Sebagai fungsi penyangga tanah memiliki kemampuan untuk menjerap zat-zat beracun yang bersifat cair dan terlarut. Fungsi penyangga tanah tidak terlepas dari kadar lempung terutama mentmorilonit, dan bahan organik yang terkandung di dalam tanah. Fungsi pengendapan secra
kimiawi berkaitan dengan pH dan potensial redoks. Denga demikian maka air limpasan (runoff) dan air perkolasi terbersihkan dari zat-zat beracun, oksida-oksida N dan S, sisa pupuk dan sisa pestisida yang terlarut. Penangkapan senyawa-senyawa amonium, nitrat dan fosfat yang terlarut dalam air limpasan dan dalam air perkolasi sebelum masuk ke airtanah untuk menghindarkan eutrofikasi perairan. Tanah Sebagai Fungsi Pengalihragaman Sebagai fungsi pengalihragaman tanah memiliki edafon, khususnya flora renik, atas senyawa pencemar organik seperti zat-zat yang terkandung dalam air urin, tinja, kotoran hewan, serta rembesan pestisida organik. Senyawa-senyawa tersebut akan dirombak dan diubah dengan proses mineralisasi dan humifikasi menjadi zat-zat yang tidak berbahaya. Penguraian bahan organik juga dapat menanggulangi pemasukan bahan organik yang mudah teroksidasi ke perairan. Selain itu penguraian bahan organik juga bermanfaat untuk menetralisir penghangatan oksigen terlarut di perairan. Jika terjadi penghangatan perairan dapat mendorong dan memicu pertumbuhan tumbuhan air terutama alga dan enceng gondok yang tidak terkendali. Tanah Sebagai Fungsi Pengendali Biologi Sebagai fungsi pengendali tanah berguna untuk menekan serangan penyakit yang bersumber dari tanah. Beberapa jenis penyakit seperti jenis jamur patogen dapat ditekan perkembangannya dengan montmorilonit, koloid humus dan beberapa bakteri tanah. Lempung montmorilonit dapat memperbesar daya saing bakteri melawan jamur dengan cara menjerap miselium jamur yang tidak terjerap oleh bakteri. Dengan demikian lempung montmorilonit memperkuat daya tindih bakteri atas jamur patogen. Dengan demikian tanah yang banyak mengandung lempung montmorilonit atau koloid humus mampu menjalankan fungsinya sebagai pengendali biologi. Tanah yang memiliki kandungan lempung montmorilonit serta kaya akan koloid humus adalah vertisol. Ekosistem tanah yang sehat berarti memiliki keaneragaman edafon, yang menyebabkan tanah mampu serfungsi sebagai pengendali biologi. Dengan demikian maka ketersediaan vertisol serta tanah yang kaya akan bahan organik sangat diperlukan dalam upaya sanitasi lingkungan.
3. PENCEMARAN TANAH OLEH SAMPAH Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisahpisahkan dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pencegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka dilakukan langkah tindakan. Namun demikian pada dasarnya kita semua sependapat bahwa tindakan pencegahan lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum pencemaran terjadi, apabila pencemaran sudah terjadi baik secara alami maupun akibat aktivisas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baru kita lakukan tindakan penanggulangan. Tindakan pencegahan dan tindakan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan macam bahan pencemar yang perlu ditanggulangi. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran antara lain dapat dilakukan sebagai berikut: a. Langkah pencegahan Pada umumnya pencegahan ini pada prinsipnya adalah berusaha untuk tidak menyebabkan terjadinya pencemaran, misalnya mencegah/mengurangi terjadinya bahan pencemar, antara lain : 1. Penggunaan pupuk, pestisida tidak digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. 2. Sebelum dibuang ke tanah senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan lebih dahulu, misalnya dengan dibakar. 3. Usahakan membuang dan memakai detergen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan/diuraikan oleh mikroorganisme. 4. Melarang pembuangan sampah ke selokan, parit, sungai, dawnau dan laut. Sampah harus dibuang ke tempat-tempat yang telah ditentukan. 5. Memisahkan sampah organik dengan sampah non organic.
b. Langkah penanggulangan Apabila pencemaran telah terjadi, maka perlu dilakukan penanggulangan terhadap pencemara tersebut. Tindakan penanggulangan pada prinsipnya mengurangi bahan pencemar tanah atau mengolah bahan pencemar atau mendaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat. Tanah dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tanah subur adalah tanah yang dapat ditanami dan terdapat mikroorganisme yang bermanfaat serta tidak punahnya hewan tanah. Langkah tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain dengan cara: 1. Sampah-sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan (berada dalam jumlah cukup banyak) dan mengganggu kesejahteraan hidup serta mencemari tanah, agar diolah atau dilakukan daur ulang menjadi barangbarang lain yang bermanfaat, misal dijadikan mainan anak-anak, dijadikan bahan bangunan, plastik dan serat dijadikan kesed atau kertas karton didaur ulang menjadi tissu, kaca-kaca di daur ulang menjadi vas kembang, plastik di daur ulang menjadi ember dan masih banyak lagi cara-cara pendaur ulang sampah. 2. Bekas bahan bangunan (seperti keramik, batu-batu, pasir, kerikil, batu bata, berangkal) yang dapat menyebabkan tanah menjadi tidak/kurang subur, dikubur dalam sumur secara berlapis-lapis yang dapat berfungsi sebagai resapan dan penyaringan air, sehingga tidak menyebabkan banjir, melainkan tetap berada di tempat sekitar rumah dan tersaring. Resapan air tersebut bahkan bisa masuk ke dalam sumur dan dapat digunakan kembali sebagai air bersih. 3. Hujan asam yang menyebabkan pH tanah menjadi tidak sesuai lagi untuk tanaman, maka tanah perlu ditambah dengan kapur agar pH asam berkurang. 4. Landfill, yaitu pembuangan sampah ke dalam lobang (tempat yang lebih rendah).
5. Sanitary incine ration, pembuangan sampah ke dalam jurang kemudian ditutup lagi dengan tanah 6. Individual incineration, yaitu sampah dikumpulkan dan dibakar sendiri. 7. Incinerator, yaitu pembakaran sampah setelah sampah terkumpul banyak oleh petugas kebersihan. 8. Sampah organik yang dapat membusuk/diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompos/pupuk. Untuk mengurangi terciumnya bau busuk dari gas-gas yang timbul pada proses pembusukan, maka penguburan sampah dilakukan secara berlapis-lapis dengan tanah. 9. Sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat baik secara individual maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling/dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian dikubur. 10. Sampah zat radioaktif sebelum dibuang, disimpan dahulu pada sumursumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman, misal pulau karang, yang tidak berpenghuni atau ke dasar lautan yang sangat dalam. 11. Pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah, sebelum dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Dengan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup (pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah) berarti kita melakukan pengawasan, pengendalian, pemulihan,
pelestarian dan pengembangan terhadap pemanfaatan lingkungan) udara, air dan tanah) yang telah disediakan dan diatur oleh Allah sang pencipta, dengan demikian berarti kita mensyukuri anugerah-Nya. c. Penanganan Pencemaran Tanah 1. Remidiasi Kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah dikenal dengan remediasi. Sebelum melakukan remediasi, hal yang perlu diketahui: a. Jenis pencemar (organik atau anorganik), terdegradasi atau tidak, berbahaya atau tidak. b. Berapa banyak zat pencemar yang telah mencemari tanah tersebut. c. Perbandingan karbon (C), nitrogen (N), dan fosfat (P). d. Jenis tanah. e. Kondisi tanah (basah, kering). f. Telah berapa lama zat pencemar terendapkan di lokasi tersebut. g. Kondisi pencemaran (sangat penting untuk dibersihkan segera/bisa ditunda). 2. Remediasi onsite dan offsite Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu a. in situ (atau on site) Pembersihan on site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi. b. ex situ (atau off site) Pembersihan off site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak atau tanki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off site ini jauh lebih mahal dan rumit.
3.
Bioremediasi Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur, bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Proses bioremediasi harus memperhatikan temperatur tanah,
ketersediaan air, nutrien (N, P, K), perbandingan C : N kurang dari 30 : 1, dan ketersediaan oksigen. Ada 4 teknik dasar yang biasa digunakan dalam bioremediasi: a. Stimulasi aktivitas mikroorganisme asli (di lokasi tercemar) dengan penambahan nutrien, pengaturan kondisi redoks, optimasi pH, dan sebagainya. b. Inokulasi (penanaman) mikroorganisme di lokasi tercemar, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan biotransformasi khusus. c. Penerapan immobilized enzymes. d. Penggunaan tanaman (phytoremediation) untuk menghilangkan atau mengubah pencemar. 5. ANALISIS KOMPOSISI SAMPAH Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan sampah dan rencana manajemen persampahan suatu kota. Pengelompokkan sampah yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, kain, makanan, dan sampah lain-lain (Damanhuri, 2004).
Semakin sederhana pola hidup masyarakat semakin banyak komponen sampah organik (sisa makanan dll). Dan semakin besar serta beragam aktivitas suatu kota, semakin kecil
proporsi
sampah
yang
berasal
dari
kegiatan
rumah
tangga.
Komposisi sampah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut (Tchobanoglous, 1993): 1. Frekuensi pengumpulan. Semakin sering sampah dikumpulkan, semakin tinggi tumpukan sampah terbentuk. Sampah kertas dan sampah kering lainnya akan tetap bertambah, tetapi sampah organik akan berkurang karena terdekomposisi. 2. Musim. Jenis sampah akan ditentukan oleh musim buah-buahan yang sedang berlangsung. 3. Kondisi Ekonomi. Kondisi ekonomi yang berbeda menghasilkan sampah dengan komponen yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat ekonomi suatu masyarakat, produksi sampah kering seperti kertas, plastik, dan kaleng cenderung tinggi, sedangkan sampah makanannya lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh pola hidup masyarakat ekonomi tinggi yang lebih praktis dan bersih. 4. Cuaca. Di daerah yang kandungan airnya cukup tinggi, kelembaban sampahnya juga akan cukup tinggi;
5. Kemasan produk. Kemasan produk bahan kebutuhan sehari-hari juga akan mempengaruhi komposisi sampah. Negara maju seperti Amerika banyak menggunakan kertas sebagai pengemas, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia banyak menggunakan plastik sebagai pengemas. Analisis karakteristik sampah sangat diperlukan dalam desain sistem pengelolaan sampah kota, terutama dalam hal pengolahan sampah. A. Karakteristik Fisik Karakteristik fisik penting dalam hal pemilihan dan pengoperasian peralatan dan fasilitas pengolahan. Karakteristik fisik yang dianalisis adalah berat jenis, kelembaban, ukuran dan distribusi partikel serta penentuan angka kompaksi atau factor pemadatan. 1) Berat jenis Contoh: Berdasarkan penelitian didapatkan berat jenis sampah domestik di Kota Padang adalah 0,12 0,17 kg/liter dengan rata-rata 0,15 kg/liter. Dari literature juga didapatkan untuk komponen sampah makanan berat jenisnya adalah 0,29 kg/liter, sedangkan untuk sampah kertas dan plastik berat jenisnya 0,07 0,09 kg/liter (Tchobanoglous, 1993). 2) Faktor Pemadatan Faktor pemadatan atau angka kompaksi merupakan perbandingan volume akhir dan volume awal sampah, faktor pemadatan ini diperlukan untuk menentukan besarnya timbulan sampah dalam satuan volume. ContohL: faktor pemadatan sampah domestik Kota Padang berkisar antara 1,01 1,08 dengan rata-rata sebesar 1,05. Perbedaan angka kompaksi untuk kategori daerah pusat kota dan pinggir kota serta perbedaan tingkat pendapatan tidak terlalu besar atau tidak signifikan. Hal ini dikarenakan perbedaan komposisi sampah antara kedua kategori di atas juga tidak terlalu besar. 3) Ukuran dan Distribusi Partikel
Penentuan ukuran dan distribusi partikel sampah digunakan untuk menentukan jenis pengolahan sampah, terutama untuk memisahkan partikel besar dengan partikel kecil. Contoh: rata-rata distribusi partikel sampah domestik di Kota Padang umumnya berukuran kecil dari 250 mm . Hal ini berarti sampah domestik Kota Padang dapat dikelola dengan sistem composting, dimana untuk mendapatkan hasil yang optimal ukuran sampah berkisar 25 75 mm. Dengan ukuran partikel sampah yang relatif seragam diharapkan proses pembuatan kompos akan berjalan sempurna dalam waktu yang relatif sama. B. Karakteristik Kimia Penentuan karakteristik kimia sampah diperlukan dalam mengevaluasi alternatif suatu proses dan sistem recovery yang dapat dilakukan pada suatu limbah padat, misalnya untuk mengetahui kelayakan proses pembakaran sampah dan pengolahan biologis. 1) Kelembaban (Kadar Air) Dengan mengetahui kelembaban atau kadar air sampah dapat ditentukan frekuensi pengumpulan sampah. Frekuensi pengumpulan sampah dipengaruhi oleh komposisi sampah yang dikandungnya. Contoh dalam penelitian menunjukkan kadar air atau kelembaban sampah domestik Kota Padang berkisar 27 39% dengan rata-rata sebesar 32%. Hal ini sesuai dengan literatur dimana untuk sampah domestic tipikal kelembaban adalah 15 40% (Tchobanoglous, 1993). Kelembaban sampah juga dipengaruhi oleh komposisi sampah, musim dan curah hujan. 2) Kadar Volatil Penentuan kadar volatil sampah bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar efektifitas pengurangan (reduksi) sampah menggunakan metode pembakaran berteknologi tinggi (Incenerator). Kadar volatil sampah domestik Kota Padang berkisar 47 64% dengan rata-rata sebesar 58%. Hal ini sesuai dengan literatur untuk sampah domestic kadar volatil sampah berkisar 40 60% (Tchobanoglous, 1993).
Dengan kandungan rata-rata kelembaban sebesar 32% dan kadar volatil 58%, maka dapat dikatakan sebesar 90% sampah domestic Kota Padang akan dapat tereduksi dengan proses pembakaran pada suhu tinggi. 3) Kadar Abu Kadar abu merupakan sisa proses pembakaran pada suhu tinggi. Dengan penentuan kadar abu ini dapat dilihat keefektifan kinerja proses pembakaran tersebut. Kadar abu dari proses pembakaran pada suhu tinggi yaitu 9000 C, berkisar antara 7 16% dengan rata-rata sebesar 10%. Dari Literatur didapatkan kadar abu sebesar 10 30% (Tchobanoglous, 1993). Ini berarti dengan proses pembakaran suhu tinggi, sampah domestik Kota Padang akan tereduksinya sebesar 90% dan sisa pembakaran yang merupakan abu sebesar 10%. Dengan kata lain proses pembakaran sampah dengan suhu tinggi dapat menjadi alternatif pertimbangan dalam hal pengolahan sampah di Kota Padang. 4) Rasio C/N Rasio C/N merupakan faktor penting dalam mendesain pengolahan sampah biologi seperti dalam proses pembentukan kompos. Rasio C/N sampah domestik Kota Padang dalam penelitian ini berkisar 21 33 dengan nilai rata-rata sebesar 27. Dari literature nilai optimum rasio C/N antara 25 50. Hal ini berarti, dilihat dari rasio C/N sampah domestik Kota Padang dapat diolah secara biologi dengan proses composting. 5) Kandungan Energi Penentuan kandungan energi sampah diperlukan dalam proses pengolahan sampah terutama pengolahan secara thermal. Kandungan energi sampah domestik 7896 Btu/lb. Untuk menentukan rata-rata kandungan energi sampah domestik, maka hasil ini dikalikan dengan presentase komposisi masing-masing jenis sampah, sehingga didapatkan rata-rata kandungan energi sampah domestik Kota Padang 7422 Btu/lb.
Dengan kandungan yang cukup tinggi, pengolahan thermal dapat menjadi alternatif lain dalam pengolahan sampah domestik di Kota Padang. C. Karakteristik Biologi Karakteristik biologi yang diuji dalam penelitian ini hanyalah kehadiran (jumlah) lalat dalam sampel sampah. Jumlah Lalat Kehadiran atau jumlah lalat dalam sampel sampah dilakukan dengan meletakkan alat fly Grill di atas tumpukan sampah sesuai dengan masing-masing klasifikasinya. Rata-rata kehadiran lalat dalam sampel sampah untuk masing-masing alat adalah 7 ekor. Dengan demikian, semakin besar timbulan sampah dan komposisi sampah makanannya, jumlah kehadiran lalat pun semakin besar.
Sumber : PP RI No. 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDAQ FjAB&url=http%3A%2F%2Fhortikulturapolinela.files.wordpress.com%2F2012%2F10%2Ffuadamzani.pdf&ei=wZUIU_r2JcL_rQfBv4CwDg&usg=AFQjCNGVb0IvAKBannZzX5u8UJakX7Zuw&sig2=w2eYb9mfAiTndRPwttxJCg&bvm=bv.61725948,d.bmk (sabtu, 22 februari 2014 pukul 19.45 ) http://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran_tanah (sabtu, 22 februari 2014 pukul 19.45 ) http://www.slideshare.net/ReedhaCilliers/pencemaran-tanah-dan-penyebabnya (sabtu, 22 februari 2014 pukul 19.45 ) http://erfan1977.wordpress.com/2011/09/20/fungsi-tanah-dalam-pencemaran-lingkungan/ (Minggu, 23 Februari 2014 pukul 08.00) http://rebifirmansyah.wordpress.com/2012/03/27/makalah-pencemaran-tanah/ (Minggu, 23 Februari 2014 pukul 16.00) http://makalahsekolah.wordpress.com/2012/05/22/pencemaran-tanah-dampak-sertapenanggulangannya/ (Minggu, 23 Februari 2014 pukul 16.00) http://emoincubus.blogspot.com/2010/11/metode-pengendalian-pencemaran.html 23 Februari 2014 pukul 16.00) http://www.scribd.com/doc/46938779/Lap-praktikum-11-Analisa-Sampah Februari 2014 pukul 16.00) ilearn.unand.ac.id/pluginfile.php/.../Pengelolaan%20Sampah%202.pdf (Minggu, 23 Februari 2014 pukul 16.00) http://my.opera.com/MaRph0amat0nte/blog/timbulan-komposisi-dan-karakteristik-sampah (Minggu, 23 Februari 2014 pukul 16.00) SK SNI 19-3964-1994, Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan, Komposisi Sampah Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, Bandung. Tchobanoglous, G, 1993, Intergrated Solid Waste Management, McGraw Hill, New York. http://idkf.bogor.net/yuesbi/eDU.KU/edukasi.net/Peng.Pop/Lingk.Hidup/Pencemaran.Tanah/al l.htm (Minggu, 23 (Minggu,
Anda mungkin juga menyukai
- KAK Tes Kebugaran ANAK SEKOLAHDokumen5 halamanKAK Tes Kebugaran ANAK SEKOLAHidanadia100% (2)
- Kelompok 7 - 2div - Tukang JahitDokumen36 halamanKelompok 7 - 2div - Tukang JahitidanadiaBelum ada peringkat
- Tekanan Panas PakarDokumen25 halamanTekanan Panas PakaridanadiaBelum ada peringkat
- DASAR K3 Tekanan PanasDokumen14 halamanDASAR K3 Tekanan PanasidanadiaBelum ada peringkat