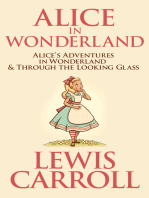Thailand - Ada Apa Denganmu
Diunggah oleh
AmeliaPurnama0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan4 halamanThailand - Ada Apa Denganmu
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniThailand - Ada Apa Denganmu
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan4 halamanThailand - Ada Apa Denganmu
Diunggah oleh
AmeliaPurnamaThailand - Ada Apa Denganmu
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Thailand: Ada Apa Denganmu?
-Indonesia harus bangga, demokrasi tumbuh makin matang-
Mengapa Thailand ribut terus? Ekonominya relatif berkembang pesat dan
reformasi politiknya sebenarnya sudah berjalan baik, tapi tetap saja negeri Gajah
Putih ini dilanda prahara politik tak berkesudahan. Di akhir 2013 hampir setiap
hari puluhan ribu orang menggelar demo di Bangkok, menduduki pusat
pemerintahan, serta menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mundur dari
jabatannya.
Mundur? Pemimpin pemerintahan yang terpilih secara sah diminta turun oleh
kaum demonstran? Otoritas jalanan ingin membatalkan suara mayoritas yang
diperoleh dengan susah payah lewat pemilu yang adil dan terbuka. Rasanya tak
masuk akal.
Tapi itulah Thailand. Beberapa hari pada Desember kemarin, situasinya sempat
menajam. Kaum demonstran rupanya didukung cukup luas oleh kaum intelektual
Bangkok, aktivis mahasiswa, aktivis LSM dan self-proclaimed moralists lainnya.
Dipimpin oleh Suthep Thaugsuban (64 tahun), mantan Deputi PM pada
pemerintahan sebelumnya, gerakan kaum demonstran ini disebut sebagai the
yellow-shirt movement, gerakan berkaos kuning (warna kuning adalah simbol
resmi Kerajaan Thailand). Mereka menegaskan bahwa mereka adalah pembela
rakyat dan penyelamat martabat raja.
Dengan call setinggi itu, mereka bertahan tidak akan surut sebelum PM Yingluck
menyerah, kalau perlu dengan melumpuhkan Bangkok, ibukota Thailand. Semua
ini diperburuk lagi oleh kelakuan kaum oposisi, yaitu Partai Demokrat. Wakil-
wakil mereka di parlemen serempak mengundurkan diri, bergabung dengan
kekuatan jalanan. Dalam situasi kritis, kaum oposisi di parlemen bukannya
membela aturan main demokrasi, mereka malah larut dan melebur menjadi
kekuatan ekstra-parlemen.
Terhadap semua itu, untungnya PM Yingluck dan para pendukungnya (the red-
shirt supporters, pendukung berkaos merah) mampu menahan diri, sehingga
sejauh ini tidak terjadi bentrok berdarah yang parah. Langkah pemimpin wanita
yang kalem dan berwajah menawan ini termasuk langkah yang taktis dan cerdas,
namun bukan tanpa resiko besar. Ia mengembalikan mandatnya kepada Raja
Bhumibol, membubarkan parlemen, serta menetapkan percepatan jadwal pemilu,
yaitu 2 Februari 2014.
Langkah seperti ini memang biasa diterapkan dalam sistem parlementer untuk
menghindari krisis berkepanjangan. Kalau perhitungan Yingluck tepat, maka dia
dan partainya, Pheu Thai, justru dapat memperbarui mandat lewat pemilu. Dengan
ini dia bisa membuktikan kepada kaum demonstran bahwa mayoritas rakyat masih
memberinya kepercayaan penuh. Tapi dia bisa juga salah perhitungan dan kalah,
sebab kaum oposisi dapat menggunakan waktu sebulan ini untuk meluaskan
pengaruh mereka.
Singkatnya, solusi yang ditawarkan Yingluck masuk akal, sebuah jalan keluar
yang adil buat semua. Lewat pemilu, Yingluck dan para penentangnya harus
bersaing meyakinkan rakyat siapa yang pantas dan mampu memimpin Thailand.
Pilih mana suka, pilih yang terbaik. Itulah demokrasi. Bagus, bukan?
Eh, ternyata tidak juga. Kaum demonstran dan kaum oposisi justru makin keras
dan membatu. Mereka menolak solusi Yingluck. Pemilu bulan depan? No.
Sebagai alternatifnya, kaum demonstran ingin agar pemerintahan Yingluck bubar
dulu. Setelah itu, mereka ingin membentuk dewan rakyat yang menjalankan
pemerintahan transisi sambil melakukan reformasi. Setelah semua ini berjalan,
barulah pemilu diadakan.
Enak betul. Tapi apa persisnya yang mereka maksud sebagai dewan rakyat? Siapa
yang memilih orang-orangnya dan bagaimana komposisinya? Bukankah aksi
jalanan kaum berkaos kuning adalah gerakan kontra-reformasi yang berkedok
kepentingan rakyat? Kalau memang didukung suara mayoritas, kenapa mereka
takut bersaing dalam pemilu?
Semua ini mengingatkan saya pada masa-masa awal reformasi di negeri kita.
Setelah Pak Harto turun, sebagian kaum demonstran menyuarakan pembentukan
dewan rakyat, atau presidium, yang berisi tokoh-tokoh masyarakat. Dewan ini
akan diberi kewenangan transisional, mengawal reformasi sampai diadakannya
pemilu yang jurdil. Tanpa ini, sebagian kaum demonstran kuatir bahwa sisa-sisa
Orde Baru akan terus bertahan.
Kita bersyukur, waktu itu tuntutan demikian tidak menjadi suara dominan. Kalau
diterima luas, pasti kerepotan kita akan berlipat kali dan krisis politik bisa makin
menajam, sebab ide presidium tersebut bersifat anti-demokratis serta mengandung
elemen yang membingungkan dan mudah mengundang konflik. Siapa yang
menjadi anggota dan pimpinan presidium? Bagaimana dan kewenangan apa yang
digunakan untuk memilihnya? Siapa yang mengontrolnya?
Indonesia memilih melakukan transisi demokrasi lewat jalan yang lebih
terlembaga. Pergantian kekuasaan selalu dilakukan secara teratur, relatif damai,
lewat pemilu yang semakin terbuka dan adil. Guncangan memang terjadi sedikit
pada masa Presiden Gus Dur, tetapi setelah itu, dari Ibu Megawati ke Pak SBY,
demokrasi Indonesia tumbuh semakin matang.
Eloknya lagi, Indonesia berhasil menjaga kesimbangan antara perubahan dan
kesinambungan, change and continuity. Kekuatan politik baru bermunculan
(PKB, NU, PKS, Partai Demokrat, Gerindra, dan partai lainnya) namun kekuatan
lama yang telah eksis dalam Orde Baru (Golkar, PDIP dan PPP) ternyata sanggup
bertahan dan menjadi bagian dari sistem demokrasi yang sehat dan berjalan baik.
Kita tidak membubarkan partai tertentu. Kita tidak menolak eksistensi kekuatan
apapun: kita justru menyerap mereka semua, menjadikannya bagian yang sah dan
terhormat dalam tenda besar demokrasi Indonesia.
Tahun ini akan ada dua pemilu besar, yaitu pileg dan pilpres. Demokrasi
Indonesia akan diuji lagi. Tapi saya yakin, kita akan lulus dengan baik dan
membuktikan sekali lagi, seperti kata majalah ternama The Economist beberapa
tahun silam, bahwa Indonesia adalah the shining example of democracy in
developing nations.
Begitulah seharusnya negeri yang besar dan mau melangkah maju. Dari segi ini,
sebagai warga RI, kita semua patut merasa bangga dan bersyukur. Walau kita
tidak boleh lengah, tidak ada salahnya jika kita meresapi kebanggaan tersebut
sedalam-dalamnya.
Kembali ke Thailand, kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Mudah-mudahan semua pihak di sana mengedepankan akal sehat. Betapa
sayangnya jika prestasi pembangunan ekonomi di negeri Gajah Putih ini, yang
cukup gemilang dalam beberapa dekade terakhir, harus kandas karena desakan
sepihak dari kaum yang justru mengatasnamakan kepentingan raja.
Kita tahu bahwa pada esensinya konflik yang terjadi sekarang memiliki
hubungan langsung dengan keberhasilan ekonomi tersebut. Akarnya terletak pada
perubahan sosial dan sukses pembangunan Thailand.
Kaum pendukung Yingluck, pasukan berkaos merah, umumnya memiliki akar
sosial di daerah pedesaan, kaum semi-urban, terutama di daerah padat di Thailand
utara. Pertumbuhan cepat ekonomi dalam dua dekade terakhir mengangkat nasib
mereka. Loyalitas tertinggi tetap pada Raja Bhumibol, tapi mereka juga tahu
bahwa kakak kandung Yingluck, yaitu mantan PM Thaksin Shinawatra, yang
dikudeta tentara pada 2006 lalu, adalah pemimpin yang menelurkan banyak
kebijakan yang membela nasib mereka, seperti subsidi kredit dan jaminan
kesehatan.
Sejak kudeta tersebut, Thaksin memang menjadi man in exile, hidup berpindah di
Hongkong, Dubai dan London. Namun terobosan kebijakan dari pemerintahan
yang dipimpinnya tetap dikenang sebagai kebijakan pro-rakyat yang progresif.
Singkatnya, Yingluck, walaupun secara pribadi sebenarnya merupakan salah satu
keluarga terkaya Thailand, adalah representasi politik arus bawah, kaum
underclass di pedesaan dan kaum urban pinggiran yang kini mulai menggeliat
serta menuntut porsi politik dan ruang partisipasi yang lebih besar lagi.
Sebaliknya, tokoh-tokoh gerakan berkaos kuning yang menentang Yingluck pada
umumnya adalah perwakilan kelas menengah lama, kaum terdidik di Bangkok
dan di wilayah selatan yang relatif lebih kosmopolitan. Mereka adalah warga
kelas atas dan kaum urban yang selama ini menikmati banyak previleges dalam
sistem monarki Thailand. Posisi sosial mereka makin terdesak, tersaingi oleh
munculnya kelas menengah baru, mantan petani dan orang desa semi-urban yang
jumlahnya semakin banyak. Bisa dikatakan, dalam posisi terdesak, kaum
pendukung monarki dan kelas menengah lama ini sekarang bermetamorfosis
menjadi kaum reaksioner yang berusaha mempertahankan masa lalu.
Itulah sebabnya di koran New York Times seorang ahli Asia Tenggara dari
Columbia University, Prof. Duncan McCargo, berkata bahwa protes kaum
demonstran terhadap Yingluck akhir-akhir ini pada dasarnya adalah the last gasp
of Thai paternalism.
Kita tahu bahwa dalam jangka panjang kehendak sejarah tidak mungkin dilawan.
Kaum berkaos kuning tak bisa memutar arah jarum jam. Karena itu, dalam jangka
pendek, satu-satunya yang mereka andalkan sekarang adalah dukungan kaum
tentara, yang memang dalam tradisi politik Thailand selalu gampang tergoda
untuk bermain politik. Sejauh ini, sikap tentara masih netral, cenderung menahan
diri. Mudah-mudahan sikap ini terus mereka pertahankan.
Faktor lainnya adalah sikap Raja Bhumibol dan institusi kerajaan Thailand. Inilah
faktor kunci, elemen pamungkas yang menutup semua argumen jika terjadi
perbedaan pendapat. Tetapi untungnya, sama dengan tentara, sejauh ini raja dan
keluarga kerajaan tidak memperlihatkan sikap yang eksplisit mendukung tuntutan
kaum berkaos kuning.
Sekali lagi, sebagai tetangga dari negeri seberang, kita berharap semoga Raja
Bhumibol, tentara, dan kaum yang bertikai di Thailand tetap mengedepankan akal
sehat. Asia Tenggara sudah berjalan cukup jauh dan dianggap sebagai kawasan
yang menjadi contoh sukses pembangunan di negara sedang berkembang. Kudeta
serta goyang-menggoyang kursi kekuasaan: mustinya semua ini sudah menjadi
masa lalu di kawasan kita.
Energi politik harus disalurkan secara terlembaga, lewat pemilu yang adil dan
terbuka. Energi selebihnya kita gunakan untuk membangun ekonomi,
meningkatkan pendidikan, memajukan kebudayaan, dan sebagainya.
Bukankah semua itu lebih baik?
8 J anuari 2014
*) Andi Mallarangeng Doktor I lmu Politik Lulusan Northern I llinois
University, DeKalb, I llinois, AS.
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20022)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3276)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]Dari EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3845)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)



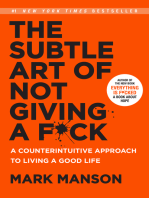







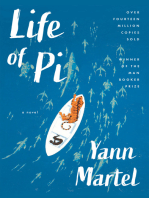









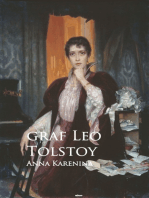

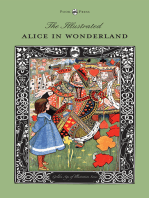

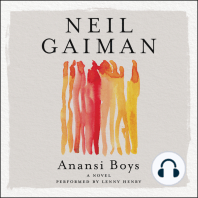
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)