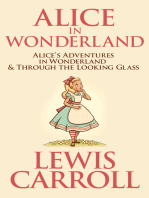McDonald Dan Coto Makassar - Pilihan Otonomi Daerah
Diunggah oleh
AmeliaPurnama0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan3 halamanMcDonald Dan Coto Makassar - Pilihan Otonomi Daerah
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniMcDonald Dan Coto Makassar - Pilihan Otonomi Daerah
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan3 halamanMcDonald Dan Coto Makassar - Pilihan Otonomi Daerah
Diunggah oleh
AmeliaPurnamaMcDonald Dan Coto Makassar - Pilihan Otonomi Daerah
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
McDonald dan Coto Makassar: Pilihan Otonomi Daerah
-McDonald sukses karena ia selalu beradaptasi dengan selera lokal-
SELERA makan ternyata tak luput dari imbas globalisasi. Urusan perut dan
citarasa di lidah diurus lewat metode supermodern yang melibatkan manajer-
manajer terbaik di dunia. Dari hal ini kita bisa belajar tentang banyak hal,
termasuk dalam melihat konsep ideal serta dilema yang ada dalam penerapan
otonomi daerah di Indonesia.
Dalam soal globalisasi makanan, contoh terbaik tentulah hamburger McDonald.
Diawali pada tahun 1940 di sebuah daerah kecil di AS, Oakbrook, Illinois,
restoran McDonald kemudian menjadi the worlds most recognized brand, dengan
34 ribu gerai yang menyebar di 119 negara. Dengan semua ini, sebagian orang
berkata bahwa McDonald kini bukan hanya menjadi simbol globalisasi, tetapi
bahkan simbol perdamaian dunia.
Di abad ke-18, Immanuel Kant, seorang tokoh besar filsafat dari Jerman, pernah
berkata bahwa perang antara dua negeri demokrasi tidak akan mungkin terjadi. Di
abad ke-21 barangkali para penikmat hamburger bisa berseru bahwa perdamaian
akan selalu terjadi di negara-negara yang membuka pintu seluas-luasnya bagi
penyebaran gerai McDonald.
Di mana letak keunggulan McDonald? Barangkali jawabnya mungkin sederhana
saja: standarnisasi rasa yang konsisten. Big Mac yang ditawarkan di New York
City akan persis sama rasa dan aromanya dengan Big Mac yang ada di Istanbul
atau Jakarta. Bahkan bukan hanya itu, desain, warna, pelayanan serta minuman
pelengkapnya pun akan relatif sama pula.
Dengan stardanisasi yang canggih dan hampir total tersebut para pelanggan dan
calon pembeli memiliki ekspektasi yang jelas. Konsumen tidak perlu lagi
menebak-nebak. Sekali lidah kita sudah merasakan nikmatnya Big Mac, maka ke
ujung dunia mana pun kita pergi, kenikmatan yang sama akan terus bisa kita
rasakan berulang-ulang.
Itulah perbedaan McDonald dengan coto makassar. Saya ingat, sewaktu saya
masih sekolah di Makassar sekian tahun lalu, ada beberapa warung coto yang
sangat sedap dan terkenal. Uniknya, hampir di semua warung ini dapat dibaca
plakat dengan tulisan besar-besar: tidak buka cabang di tempat lain. Maksudnya
memang ingin menyatakan bahwa warung coto tersebut rasanya khas dan tidak
ada duanya di tempat lain.
Memang pernah ada juga warung coto Makassar yang mencoba membuka cabang
di tempat lain, namun tidak sukses, seolah rasa dan lokasi menyatu tak
terpisahkan. Pelanggan merasa bahwa rasa coto Makassar di cabang yang baru
ternyata tidak seenak rasa di warung induknya. Pelanggan kecewa dan massalisasi
warung coto Makassar ala McDonald menjadi layu sebelum berkembang.
Kenapa ia gagal? Ternyata untuk coto Makassar berlaku prinsip: lain koki lain
masakan, lain warung lain rasanya. Di satu warung kuahnya lumayan kental dan
pekat kecoklatan, di warung lain kuahnya encer namun dagingnya begitu lembut.
Kualitas pelayanannya pun berbeda dari warung ke warung. Tidak ada quality
control yang jelas. Semua tergantung gaya pribadi dan selera pemilik warung.
Kalau pada McDonald kita bisa berkata bahwa everything goes global, maka pada
coto Makassar seruannya adalah everything is local.
Tapi jangan keliru, restoran McDonald pun selalu berusaha beradaptasi dengan
selera lokal. Jangan heran jika anda ke McDonald di Jepang maka anda akan
mendapati menu teriyaki burger. Di India anda akan melihat vegetarian burger
dalam menunya. Di Indonesia, ada paket hemat yang terdiri dari nasi, ayam
goreng dan telor orak arik. Bahkan asyiknya, ada juga hamburger McDonald rasa
rendang yang bisa dicicipi dengan sambal pedas.
Jadi kesimpulannya, selain standarnisasi secara global, sukses McDonald juga
dimungkinkan karena restoran AS ini mampu beradaptasi secara lokal. Dari sini
kita bisa memetik banyak pelajaran berharga, termasuk dalam soal konsep ideal
dan praktek otonomi daerah.
Pelayanan pemerintahan di seluruh daerah otonom harus sama untuk setiap warga
negara, seperti restoran McDonald. Standarnisasi diterapkan tanpa mengenal jenis
kelamin, suku bangsa, agama, maupun status sosial-ekonomi para warganya.
Karena itu, kita perlu terus mengembangkan sebuah patokan yang bersifat
nasional mengenai pelayanan pemerintah di masing-masing daerah. Di provinsi,
kabupaten, atau kota manapun, setiap warga Indonesia harus dilayani dengan
standar yang sama, baik dalam masalah pendidikan, kesehatan, maupun
pengurusan segala macam izin dan administrasi kependudukan.
Tentu saja daerah-daerah otonom berhak merumuskan menu khususnya masing-
masing yang berbeda satu dengan yang lain. Namun core business pemerintahan
daerah harus dibuat dengan profesional sehingga harapan masyarakat terhadap
pelayanan pemerintahan juga jelas di mana pun di seluruh Indonesia. Menu-menu
khusus dalam pelayanan pemerintahan ini penting untuk tetap memelihara
kebhinekaan tanpa mengabaikan ke-tunggal ika-an.
Satu hal yang dijaga betul oleh McDonald adalah quality control. McDonald tidak
segan-segan mencabut lisensi suatu gerainya apabila dianggap gerai tersebut tidak
menjalankan standar kualitas produk dan pelayanan yang telah ditetapkan. Hal
semacam ini juga kita butuhkan dalam pelayanan pemerintah di daerah, walaupun
tentu kita tidak begitu saja dapat mencabut lisensi seorang bupati, misalnya.
Yang jelas, kita tidak bisa membiarkan satu atau beberapa daerah otonom
menjalankan pelayanan pemerintahan secara seenaknya saja, tanpa mempedulikan
standar pelayanan untuk berbagai fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan
secara nasional. Bahkan, dalam undang-undang jelas diatur bukan hanya tentang
pembentukan daerah otonom, tetapi juga tentang penghapusannya. Yang terakhir
ini tampaknya tidak terlalu banyak dibicarakan, karena yang lebih mengemuka
adalah tentang pembentukan daerah otonomi baru.
Alangkah eloknya jika bagi semua warga negara, di Sabang atau Merauke, di
Miangas atau Pulau Rote, tersedia pelayanan pemerintah yang baik dan bermutu.
Justru hal inilah yang harus menjadi salah satu perekat utama NKRI.
Untuk sebuah negara besar dengan 34 propinsi serta lebih dari 500 kabupaten dan
kota, manajemen pemerintahan daerah ala McDonald adalah jawaban kita di masa
depan. Namun, kalau soal makanan, bagi lidah saya pribadi, kapan pun, di mana
pun (sejauh memang ada warungnya), saya tetap memilih coto Makassar.
Kuahnya panas, dagingnya lembut, sambalnya pedas, makan dua mangkok
lengkap dengan burasnya.
Jakarta, 13 November 2013
*) Andi Mallarangeng Doktor I lmu Politik Lulusan Northern I llinois
University, DeKalb, I llinois, AS.
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20022)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3276)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Don Quixote: [Complete & Illustrated]Dari EverandDon Quixote: [Complete & Illustrated]Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3845)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)



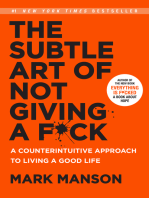







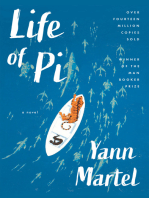









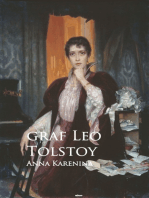

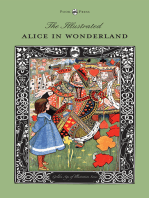

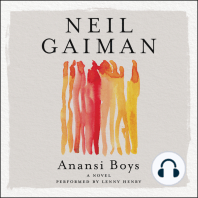
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)