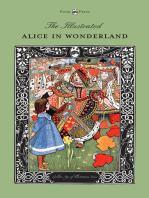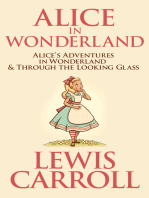Wartawan Berotak Kiri
Diunggah oleh
Sangkala Bhuwana0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
798 tayangan14 halamanmakalah
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
TXT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inimakalah
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai TXT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
798 tayangan14 halamanWartawan Berotak Kiri
Diunggah oleh
Sangkala Bhuwanamakalah
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai TXT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 14
hursday, November 24, 2005
Wartawan Berotak Kiri [1]
ILLUSTRATED BY MARGARET M. WENDELL
Prolog: Tulisan ini di bawah ini sebetulnya merupakan makalah, kompilasi dari ba
nyak sumber pustaka. Beberapa kali dipresentasikan di depan para redaktur suatu
media dan asosiasi wartawan yang mengundang saya. Beberapa teman lama yang sempa
t membaca, menilai makalah ini kaya gagasan, informatif. Membaca Wartawan Berota
k Kiri, ini kata salah seorang dari mereka, seperti membaca esai bahasa.
-ABT
-------------------------------------------
PERDANA Menteri Inggris pada Perang Dunia I, David Lloyd George, pernah berkata
kepada C.P Scott, redaktur harian Manchester Guardian, Bila semua orang mengetahu
i hal yang sebenarnya sekarang, perang akan berhenti esok hari. Tapi, mereka tid
ak tahu dan tidak pernah tahu.
Tiga belas tahun silam, tentara Amerika Serikat (AS) menyerang Irak. Pertempuran
menewaskan penduduk Kurdi dan kaum minoritas Shiah, dua kelompok warga Irak yan
g dijanjikan perlindungan dari George Bush dan John Major. Media AS memberitakan
, serangan itu hanya memakan sedikit korban. Jumlahnya, 250 ribu orang.
Pada medio 1998, NATO mengebomi wilayah permukiman di Kosovo, meneror, dan membu
nuh orang-orang yang dilindungi oleh Clinton dan Blair. Serangan meleset, tulis pe
rs di Brussel. Tentara AS menggunakan pesawat tempur A-10 Warthog, lengkap denga
n misil uranium. Inilah yang menyebabkan leukemia pada anak-anak di Irak bagian
selatan, sesuatu yang mengingatkan kita pada tragedi di Hiroshima. Dalam pemberi
taan BBC, dentuman bom di Kosovo disebut suara malaikat.
Tak seorang pun meragukan kebrutalan Milosevic, meski PBB telah meredakan ketega
ngan antara Serbia dan militer Kosovo pada 25 Maret 1998. Simak bagaimana pers I
nggris memberi headline: Milosevic Lebih Kuat dari Sebelumnya, Terima Kasih NATO.
Bayangkan juga bagaimana Peter Sissons membuka siarannya di radio BBC: Selamat ma
lam. NATO melanjutkan serangannya dengan membunuh orang-orang sipil tak bersalah
di Serbia. Setelah sepekan membantu 10 dari seribu pengungsi yang melarikan dir
i saat pengeboman, pemerintah Inggris menyumbangkan 20 juta poundsterling. Jumla
h itu sama dengan harga dua buah misil.
* * *
DARI penggalan cerita diatas, saya hanya ingin menarik garis pemisah antara menem
ukan peristiwa dan menyampaikan peristiwa. Vitalitas menuntun keberhasilan wartawan
menemukan peristiwa, tapi, keberhasilan wartawan menyampaikan peristiwa dituntun ol
eh relativitas. Apa yang wartawan temukan di suatu peristiwa, belum tentu sama d
engan apa yang ada di medianya. It is not as it was. Berlindung di balik kebajik
an media, tindakan menyampaikan peristiwa hari-hari ini merupakan kegiatan yang re
latif.
Sama dengan adagium gun doesnt kill, people do, bahasa jurnalistik untuk menyampai
kan peristiwa hanyalah alat. Lakunya menuruti derajat ketrampilan wartawan. Merek
a yang melatih otak kirinya dengan baik dan benar, bisa menjadikan bahasa jurnal
istik sebagai alat merekayasa, memanipulasi, atau memolesi fakta. Separo fakta,
setengah dusta.
Namun, wartawan juga bisa menjadikan bahasa jurnalistik sebagai alat efektif mem
antau kekuasaan dan menyuarakan kepentingan warga masyarakat yang tersisih. Di a
tas kertas, itu soal pilihan. Umumnya, wartawan yang tahu terlalu banyak cenderung
memilih bahasa jurnalistik yang mengaburkan fakta. Tujuannya, meminimalkan kesal
ahan yang tampak atas kekuasaan dalam perang, terorisme, pelanggaran HAM, skandal
, dan lain sebagainya. Itu sebabnya wartawan perang seperti John Pilger percaya
bahwa, Journalists are not giving us the real story.
Sementara itu, wartawan yang tahu terlalu sedikit cenderung memilih bahasa jurnali
stik yang melebih-lebihkan fakta. Tujuannya, memaksimalkan kesalahan yang tak tam
pak atas kekuasaan. Itu sebabnya pengacara seperti Adnan Buyung Nasution menggeru
tu, Ini merupakan trial by the press, melanggar asas praduga tak bersalah, dan ta
k akurat.
Tuduhan-tuduhan diatas tidak sepenuhnya benar. Terkadang wartawan dan media haru
s melindungi publik dari gambaran kengerian, penderitaan sehari-hari, dan perist
iwa hidup yang kelam. Di bawah payung adab dan moralitas, rekaman video atau fot
o otentik tentang peristiwa berdarah harus disimpan di dalam laci. Demikian pula
bahasa jurnalistik yang akan digunakan, harus dipilah-pilih sedemikian rupa. It
u sebabnya kritikus media seperti Joe Saltzman bersungut-sungut, It is a good tas
te, bad journalism.
Era pers gugup-gagap di era orde baru memang telah berlalu. Praktik berbahasa se
perti kurang gizi untuk tidak menulis kelaparan tinggal lelucon. Dulu, pers menu
lis penyesuaian harga tatkala harga kebutuhan bahan pokok naik mengikuti BBM. Po
koknya, apa saja yang dikataken daripada Presiden Soeharto dan petunjuk Menpen H
armoko, media menurunkan beritanya.
Reformasi melimpahkan politik kekuasaan kini sepenuhnya kepada pengiklan, pemili
k perusahaan media, tim sukses, serta pejabat humas dan segerombolan orang berpe
ngaruh.
Ledakan media massa yang mengencangkan persaingan antarmedia, di satu sisi dapat
mengendurkan self control terhadap bingkai-bingkai kepatutan. Pada saat bersama
an, media dapat menjadi sangat toleran terhadap kesalahan tampak sumber berita y
ang kebetulan seorang teman.
Situasi ini mendorong pengelola media massa mengonsolidasi kekuatannya demi kepe
ntingan pragmatis. Bahasa jurnalistik sebagai salah satu elemen kekuatan media t
erkonsolidasi pada pragmatisme tersebut. Ujungnya, praktik berbahasa tidak lagi
menjadi petualangan intelektual yang mengasyikkan di kalangan wartawan. Sebab, p
olitik kekuasaan yang mendistorsi praktik berbahasa, nyaris tak menyisakan ruang
bagi tumbuhnya eksperimen dalam berbahasa. Entah soal struktur, langgam, piliha
n lead, dan teknik penulisan satu reportase dengan lainnya dibuat nyaris sama. T
api, Who cares? Emang gue pikirin?
Paralel dengan itu, para penyunting/redaktur kita umumnya menempatkan diri sebag
ai penghalus. Mereka bagaikan kertas ampelas yang digosokkan pada berbagai bentuk
keaslian. Garis yang membentang antara jurnalisme yang cakap dan sikap orisinali
tas semakin kabur. Mereka masih mengurusi telur atau telor, apotik atau apotek,
atlit atau atlet, karir atau karier. Mereka lebih suka mencermati teks, tapi mal
as memeriksa konteks tulisan.
TENTU saja seorang wartawan harus memiliki fundamen bahasa Indonesia yang kokoh.
Dia harus tahu kaidah-kaidahnya. Sebab, banyak juga lho wartawan yang tak tahu
kapan di sebagai awalan dan kapan sebagai kata depan, bilamana menggunakan akhir
an i dan kan. Masih ada wartawan yang tak tahu mana subyek, mana predikat.
Kita belum menyadari bahwa morfologi bahasa Indonesia mengenal aturan peleburan
fonem p bila diimbuhi awalan me. Artinya, kita tak boleh pandang bulu terhadap s
emua kata yang berawalan fonem p. Jadi, tulislah memunyai, bukan mempunyai. Tuli
slah memengaruhi, memedulikan, dan memenetrasi; bukan mempengaruhi, mempedulikan
, dan mempenetrasi. Bukankah kita menulis memupuk, bukan mempupuk? Tapi, kita te
tap menulis mempelajari, bukan memelajari. Karena ajar yang berstatus kata kerja
, bukan pelajar.
Jangan terlalu bersemangat. Bahasa Indonesia mengenal pengecualian pada gugus ko
nsonan (cluster) yang mengikuti fonem p. Misalnya, kata prakarsa, kritik, protes
, dan proses. Opa Rosihan Anwar akan marah kalau Anda menulis memrakarsai, mengr
itik, memrotes, dan memroses. Tulislah memprakarsai, mengkritik, memprotes, dan
memproses.
Awalan me masih memusingkan wartawan kebanyakan. Terhadap kata bom, klon (clone)
, dan cek, misalnya. Bagaimana bila ia diimbuhi me? Apakah membom, mengklon, dan
mencek? Jika ragu, ingatlah ini: terhadap kata yang bersuku satu, awalan me har
us dalam bentuk alomorf menge. Alhasil, kita harus menuliskannya dengan mengebom
, mengeklon, dan mengecek. Demikian pula jika kata tersebut diberi awalan-akhira
n pe-an. Kita menulis pengeboman, pengeklonan, dan pengecekan.
Bagaimana dengan tanda baca? Wah, wartawan-cum-sastrawan Eyang Pramoedya Ananta
Toer bisa gusar kalau Anda keder pada tanda baca. Belum lama ini, ada satu naska
h saya di Pilars yang disunting oleh redaktur keder. Saya menulis:
Dengan perolehan suara sekitar 26 persen, pada putaran kedua Megawati perlu tamb
ahan suara sedikitnya 24 persen plus satu
Perhatikan perubahannya:
Dengan perolehan suara sekitar 26 persen pada putaran kedua, Megawati perlu tamb
ahan suara sedikitnya 24 persen plus satu
Pada naskah lain, saya menulis judul:
Mangkir, Itu Soalnya
Mungkin redaktur penyunting naskah tersebut sedang cekcok dengan kekasihnya. Mak
a, naskah itu menjadi:
Mangkir, Itu Soalnya!
Saya baru saja melumat sebuah novel pekan lalu. Ada percakapan seperti, Enyah kau
!; F you!; Kau akan menyesal!
Tanda seru pada judul bukannya tak boleh. Bandingkan dengan judul berikut:
Dibilang Intimidasi, Biar!
Judul tersebut saya temukan di majalah Gatra edisi 27 Januari 2001, halaman 68.
Isi berita tentang kelompok massa yang membela Gus Dur, agar tetap menduduki kur
si presiden. Seorang sumber, Syarifuddin Irsyad, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Samp
ang, Madura, berkata, Mau dibilang mengintimidasi, ya biar! Mereka juga melakukan
tindakan yang sama.
Bicara tentang judul, ada kemajuan dalam pers Indonesia. Tidak klise, tidak asal
sebagai kepala berita seperti dulu. Kendati begitu, masih banyak wartawan kita
yang payah memilih judul. Padahal, kuncinya hanya KISS (keep it short and simple
). Harus menarik, tapi tidak menipu. Judul adalah sudut pandang (angle) tulisan.
Sedangkan lead (teras) adalah etalasenya. Saya terkesan pada judul seperti:
Tommy dan Proyek Bomnas (Tempo, 2001)
Sudahlah, Gus (Tempo, 2001)
Bukan Kisah 1001 Malam (Tempo, 2004 tentang tewasnya seorang warga AS yang diteb
as oleh kelompok misterius di Bagdad)
Kring Tanpa Kabel dan Antre (Tempo, 2004 tentang telepon rumah berteknologi tele
pon seluler)
Wangi Cendana di Pohon Beringin (Tempo, 2004 tentang dukungan Tutut kepada capre
s dari Partai Golkar, Wiranto)
Tikungan Terakhir (Pantau, 2001 tentang drama kematian wartawan Pilar, Rudi P. S
inggih)
Tak Ada Film, Raam Pun Jadi (Pantau, 2002)
Mundur untuk Maju (Pilars, 2004 tentang mundurnya Jusuf Kalla dari jabatan Menko
Kesra)
Mingguan Time lebih mengesankan saya. Sepekan setelah tragedi WTC terjadi, baran
gkali Time merupakan satu-satunya majalah di dunia yang tidak memberi judul pada
kulit mukanya. Yang ada hanya sebuah foto yang menggambarkan gedung kembar di N
ew York itu meledak. Bagi Time, peristiwa ini tak perlu lagi dilukiskan dengan k
ata-kata.
Kalau bisa, biar pun miskin, wartawan harus kaya kata. Syukur bisa menyerap baha
sa Nusantara seperti kata santai yang berasal dari bahasa Ogan Komering, Sumater
a Selatan ke dalam tulisannya. Saya tak tahu kata semelehoi berasal, tapi seksi
juga kedengarannya.
Bahasa juga mengalami evolusi, lambat laun dalam waktu yang sangat panjang, ratu
san, bahkan ribuan tahun. Dengan usianya yang relatif muda, 76 tahun, bahasa Ind
onesia ditantang untuk menyerap dan mengungkapkan perasaan serta pikiran masyara
kat yang telah berkembang jauh, jauh lebih lama.
Ini bukan melulu perbendaharaan kata. Keanggunan juga. Bahasa yang anggun biasan
ya tidak lumrah. Misalnya, (kata) litak, tirus, moncer, dedah, sengkarut, kalang
, dan digadang-gadang. Akan tetapi, kekerapan penggunaan berpengaruh terhadap ke
anggunan bahasa. Bahasa yang sebetulnya anggun pun bisa menjadi norak jika terla
lu sering digunakan. Contohnya, wacana, kampanye dialogis, demi kepentingan raky
at, persatuan dan kesatuan, bebas dan bertanggung jawab, memasyarakatkan olah ra
ga. Kata-kata tersebut sekarang hanya diucapkan dan ditulis oleh orang-orang yan
g lmbng (ganjen). Ia sudah diselewengkan menjadi sekadar slogan propaganda.
Seorang redaktur, saya kira, perlu mengontrol frekuensi pemunculan sejumlah kata
tertentu (dibatasi). Itu pertama. Kedua, bahasa yang anggun biasanya terbentuk
dari kosa kata lama. Ketiga, bahasa yang anggun senantiasa bercitra baik, positi
f, luhur.
Sifat keanggunan kata mesti disertai kejujuran. Syahdan, bahasa ilmuwan lebih ju
jur dan benar walau pun tidak anggun. Bahasa politisi, meski anggun namun penuh
kepalsuan. Bahasa sastrawan memang sangat anggun, tapi omong kosong belaka. Nah,
maksud saya, bahasa yang anggun itu adalah bahasa orang-orang yang tidak menyan
dang pedang dan tidak menantang bintang.
Tidak skeptis? Skeptis itu sehat, sehingga wartawan pantas memeliharanya. Skepti
sisme menandakan wartawan bukanlah saluran tanpa kran dan tidak gampang percaya. C
ontoh:
Mereka sama-sama berstatus putri ayu yang terpilih setelah melewati seleksi yang
menurut penyelenggara melibatkan kriteria cerdas, cantik, dan berkepribadian. M
ooryati Soedibyo, Ketua Umum Yayasan Puteri Indonesia, yang menggelar hajatan te
rsebut sering menyebut kriteria itu sebagai tiga B: brain, beauty, dan behaviour
.
Jika sang putri dengan heroik berbicara soal penegakan hukum, itu tentu karena A
rtika Sari Devi (peraih Puteri Indonesia 2004. pen.) saat ini adalah mahasiswi pr
ogram S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Akan tetapi
, jika nanti ada kesempatan berkarier di bidang lain, termasuk hiburan, Artika m
engaku tidak akan menolak. Paling tidak, kelihatannya menggelar hiburan lebih mu
dah daripada menegakkan hukum di negeri ini.
Bayangkan jika putri itu nantinya juga berbicara soal penegakan hukum di negeri
ini.[1]
Dalam bahasa lisan, makna yang sesungguhnya ditentukan oleh intonasi, sedangkan
dalam bahasa tulisan, maksud yang terkandung dilihat dari konteksnya terhadap ke
seluruhan wacana. Terhadap konteks inilah pertama-pertama seorang redaktur memus
atkan perhatiannya.
Demikianlah, saya mengidealisasikan hubungan antara seorang redaktur dan seorang
penulis/reporter sebagai hubungan antara seorang penggubah (composer) dan seora
ng penyanyi. Pandangan yang menempatkan redaktur dan penulis/reporter sebagai hu
bungan antara pisau dan leher (ih, serem ya), harus diakhiri.
Para wartawan era baru tidak lagi memutuskan apa yang seharusnya diketahui publi
k. Mereka membantu publik mengerti secara runtut apa yang seharusnya publik keta
hui. Ini berarti menambahkan interpretasi atau analisis pada sebuah laporan beri
ta. Lebih tepat jika disebut tugas wartawan era baru adalah memverifikasi apakah
informasinya bisa dipercaya, lantas meruntutkannya sehingga publik bisa memaham
inya secara efisien. Ini dapat dicapai, apabila antara redaktur dan reporter men
ghayati hubungan antara penggubah dan penyanyi. Praktik berbahasa jurnalistik se
bagai proses menyampaikan peristiwa harus mencakup dua nilai sekaligus, yaitu logi
ka dan cita rasa. Keduanya harus disajikan dalam dosis yang seimbang. Punya nala
r seperti Albert Einstein, tentu sangat baik. Tapi, akan kering dan hampa bila t
ak mampu berimajinasi. Sebaliknya, penyajian stilistika bahasa yang menyamai Kah
lil Gibran, akan membuat laporan berita sebagai karya sastra yang tergesa-gesa.
Jangan lupa, berita harus selalu dengan peristiwa, peristiwa harus selalu dengan
jalan cerita. Di situlah logika dan cita rasa bahasa seorang wartawan diuji.
[1] Dikutip dari Sang Putri Ingin Menegakkan Hukum (Kompas Minggu, 8 Agustus 200
4).
KARENA bahasa jurnalistik muncul di media dalam dandanan, maka ia tak luput dari
kemungkinan salah persepsi. Bahkan, pada dosis maksimal pun, ini tak terhindark
an hanya mungkin dikurangi ke tingkat minimal karena menyangkut dua standar yang
saling bertentangan antara pers dan publik. Standar pers berasal dari tradisi,
pengetahuan, dan kecakapan mereka. Mereka berusaha mengungkapkan apa yang terjad
i. Penekanan penilaian pers terhadap penerimaan publik lebih pada terpeliharanya
kredibilitas mereka, ketimbang pada kepekaan publik atas pengaruh liputan.
Sedangkan standar publik, lebih menekankan pengaruh kuat atas liputan. Publik be
rharap, pers seharusnya menenggang perasaan pembaca, terutama dalam suatu kelomp
ok kecil masyarakat di mana pers diharapkan menjadi pendukung masyarakat. Para a
nggota publik ingin tahu apa yang terjadi, tapi konteks informasi yang mereka in
ginkan merupakan suatu jalinan interaksi komunitas, interaksi yang lebih kuat ke
timbang interaksi mereka dengan pers. Dalam suatu komunitas tempat mereka berada
, mereka berharap pers seharusnya mendukung komunitas, sama seperti para pimpina
n komunitas mendukungnya.
Standar pers versus standar publik menguatkan hipotesis, bahwa kualitas komunika
si bukanlah terletak pada apa yang ingin disampaikan oleh penyampai pesan, tapi
apa yang dimengerti oleh penerima pesan. Kita akan lihat contoh kasus.
Majalah Tempo edisi 1 - 7 Maret 2004 menerima surat keluhan dari seorang pembaca
setianya. Ratih Wulandari, si penulis surat, merasa terganggu oleh jokes pada l
iputan tentang demam berdarah. Di rubrik kesehatan, Tempo antara lain menulis: Se
puluh gigitan nyamuk kebun pun tak akan berbahaya, kecuali Anda menyopir mobil d
i jalan tol.
Ratih berkomentar: Saya terenyak. Aduh, kenapa hal serius ini dijadikan bahan ber
candaan? Hal yang dibicarakan ini menyangkut nyawa manusia!
Dia melanjutkan: Kenapa TEMPO dengan santai menjadikannya olok-olokan begitu? Say
a tahu majalah ini memang punya kebiasaan menggunakan jokes yang sedikit nakal dal
am tulisan-tulisannya, tapi menurut saya jokes di tulisan tersebut tidak pada te
mpatnya.
Serba salah. Mungkin Jeng Ratih sedikit terhibur, jika tahu betapa sulitnya Bill
Clinton memilih kata-kata yang tepat. Wartawan dan kolumnis hebat pun harus dik
erahkan. Ini amat sangat penting mengingat Clinton seorang presiden, yang harus
memberikan kesaksian perihal sejauh mana hubungannya dengan Monica Lewinsky.
Majalah Newsweek Asia terbitan 17 Agustus 1998 melaporkan, kalimat pengakuan yan
g diusulkan kepada Clinton terdiri dari tiga kategori. Yaitu berterus terang (core
confession), bermanis-manis (fudge phrase), dan berkepribadian(clever touch). Bahas
a di sini tidak bermaksud mengubah soal jelek menjadi baik, melainkan sekadar me
mbantu publik, agar kalau pun harus membeberkan skandal seks seseorang yang mema
lukan, dapat dilakukan dengan kepala tegak. Kata-kata lunak sekali-kali tak dima
ksudkan untuk mengaburkan dan memelintir fakta. Yang terpenting bukan apa yang h
endak dikatakan, melainkan bagaimana mengatakannya.
Taruhlah benar Clinton berselingkuh dengan Nona Lewinsky. Semestinya bisa saja d
ia berterus terang: Saya menjalin hubungan pribadi termasuk seks, sebagaimana usul
Fred Branfman, seorang wartawan. Dick Morris, mantan penasihat Clinton, menyara
nkan kalimat manis: Apa yang telah saya lakukan semata-mata urusan pribadi, bukan
politik. Ariana Huffington, seorang kolumnis, menekankan kesan berkepribadian da
n terhormat. Dia mengusulkan kalimat: Demi kepentingan keluarga, saya tak bersedi
a bertutur dengan rinci.
Tak seorang pun mengusulkan agar sebaiknya Clinton berkata: Ya, saya memang tidur
dengannya. Atau: Ya, saya bersetubuh dengannya.
Singkatnya, berbahasa menuntut tata krama dan kesantunan. Bukan cuma benar atau
salah, tapi pantas atau tidak pantas. Kebenaran, apa boleh buat, terkadang mesti
didandani tanpa kehilangan konteks dan substansinya.
Lewat siaran televisi, Clinton akhirnya memilih kata-kata hubungan yang tidak "pa
ntas (relationship that was not appropriate). Clinton juga menuturkan penyesalann
ya (I deeply regret that).
Bagaimana reaksi warga AS? Berdasarkan jajak suara, sebagian dari mereka tetap k
urang puas dan berpendapat, seharusnya Presiden Clinton juga minta maaf. Sebab, nu
ansa antara regret dan sorry berbeda. Kata menyesal bersifat eksklusif terhadap di
ri sendiri. Sementara kata apologia maaf, selain mengandung makna semantis (makna
batin) menyesal, sekaligus pula menyiratkan perasaan minta dikasihani, berkesan
simpatik.
Praktik berbahasa jurnalistik dengan demikian menuntut diksi yang tepat. Redaktu
r tak selalu menggubahnya menjadi tampak feminin. Terkadang bahasa jurnalistik har
us berdandan dengan pilihan kata yang maskulin agar lebih bertenaga. Perhatikan:
Sederet gelar yang diselempangkan ke pundaknya dari Putra Sang Fajar, Pemimpin B
esar Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, Amirul Amri, sampai Panglima Tertinggi s
udah lebih dari cukup untuk memperlihatkan kebesaran Bung Karno. Tapi, keasyikan
berlayar mengikuti angin revolusi belum selesai dengan perahu Nasakom, membuat So
ekarno lupa daratan. Inflasi ratusan persen, beras sulit, kelaparan meruyak, dem
onstrasi merebak, membangunkan Soekarno perlahan dari mimpi-mimpinya. Sampai di
sini kita tidak tahu pasti, kecuali bahwa kita menduga G30S/PKI merupakan salah
satu bangsat terbesar dalam sejarah Indonesia.[2]
Pengajaran tentang diksi tidak mudah. Ini menyangkut karakter, kepekaan, nilai-n
ilai yang dianut, dan kebijakan redaksional media. Seorang redaktur mengira kali
mat berikut sudah tepat diksinya:
Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) membuktikan, pasangan SBY-Kalla lebih popul
er ketimbang Mega-Hasyim.
Namun, seorang redaktur lain dapat menganggapnya kurang tepat, karena kata membu
ktikan di situ terasa kasar. Maka, dia mengganti kata membuktikan dengan menemukan
.
Seringkali, para wartawan berusaha menghindari pengulangan kata yang sama dalam
tulisannya. Mereka mengira kata, ujar, ucap, tutur, cetus, ungkap, papar, jelas,
terang, sergah, tukas, tandas, dan aku adalah kata-kata yang bersinonim. Padaha
l, frasa tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain begitu saja. Akan ber
tele-tele jika dijelaskan di sini, tapi saya ambil satu contoh saja:
Saya tidak bisa menerima perlakuan seperti itu, aku Sarah Azhari.
Diksi aku di atas keliru, karena seolah-olah Sarah Azhari telah membantah pernya
taan sebelumnya, sehingga kini dia mengaku. Padahal, si wartawan hanya enggan me
nulis kata atau ujar. Hanya saja si wartawan tidak tahu bahwa to say (berkata) b
erbeda dari to admit (mengaku).
Salah kaprah terjadi pula pada penyebutan status pekerjaan sumber berita. Saya m
afhum penyebutan status seperti rohaniawan, wartawan, kamerawan, sejarahwan, ilm
uwan, dan sastrawan. Tapi, saya bingung untuk memahami status, misalnya, budayaw
an. Makhluk apa ini? Apakah wartawan sendiri bingung untuk menjelaskan status or
ang-orang seperti Goenawan Mohamad, Emha Ainun Najib, Mudji Soetrisno, Eros Djar
ot?
Encik Mahatir boleh surprise baca suratkabar di negeri jiran. Oleh kerena, di In
donesie so many many pakar. Encik punya dictionary di KL, pakar means cerdik pan
dai and writing a lot of books.
Nah, jangan biarkan si encik sakit perutnya menahan geli. Sebaiknya, tulislah st
atus orang-orang seperti Roy Suryo, Andi Alfian Mallarangeng, Riswandha Imawan s
ebagai analis. Roy Suryo, analis multimedia. Riswanda Imawan, analis politik.
Kata pengamat lain lagi. Istilah ini sebetulnya muncul selama Perang Dingin, 195
1 - 1989, antara dua kekuatan adidaya, AS dan Uni Soviet. Ketegangan yang menyel
imuti kedua belah pihak, membuat media massa di sana was-was untuk terjun ke lap
angan. Maka, diambillah orang-orang tertentu yang dapat mengisahkan pergolakan p
olitik di Uni Soviet. Juga Cina. Mereka disebut watcher.
Menjelang diruntuhkannya gerbang Brandenburg pintu utama Tembok Berlin, di Berli
n pada 22 Desember 1989, istilah tersebut tak lagi digunakan. Jadi?
Jadi, sebelum Kamerad Gorbachev (soalnya Mr. Reagan sudah meninggal) mengira kit
a sedang mengalami perang dingin, tidak glasnost dan perestroika, gantilah istil
ah pengamat yang menyesatkan itu. Jangan tanggung-tanggung menggantinya dengan p
emerhati atau pencermat (apa pula ini?). Saran saya, tulislah analis.
Bahasa Indonesia mengenal kata perkosa. Seolah belum cukup, wartawan menggantiny
a dengan kata gagah, garap, gilir, dan antre. Hebatnya, kata-kata ini laksana ma
ntra sihir. Kelenjar adrenalin pembaca (terutama lelaki) akan mengalir cepat kal
au membaca berita:
1. Setelah berkenalan, Har menggagahi Mawar saat itu juga.
2. Di dalam gudang tebu itulah Cipluk digarap.
3. Seorang SPG ditemukan pingsan di terminal setelah digilir empat lelaki.
4. Pulang kuliah, seorang mahasiswi diantre lima pemuda berandalan.
Apa salah si mahasiswi di mata wartawan sampai dia diantre? Barangkali wartawan
merasa tulisannya takkan menarik jika menulis:
Pulang kuliah, seorang mahasiswi diperkosa lima pemuda berandalan.
Tidak perlu ikut gerakan kaum feminis untuk memahami perasaan perempuan. Wartawa
n perlu memiliki empati, bahwa perempuan teraniaya bukan cuma oleh perbuatan nya
ta, melainkan juga oleh kata-kata. Pada konteks tertentu, kata-kata seperti diga
gahi, digarap, digilir, dan diantre sudah bisa dianggap melecehkan perempuan. Ka
rena ia sengaja dipakai untuk mengeksploitasi peristiwa pemerkosaan supaya lebih
dapat dinikmati oleh pembaca.
[2] Dikutip dari Kursi RI-1 di Panggung Srimulat oleh A. Bakti Tejamulya (Majala
h Forum Keadilan, 2002)
MENJADI wartawan berarti menyembah fakta. Ketika menulis, pakailah imajinasi unt
uk mengungkapkannya. Simak contoh berikut:
Dan sepatu jang berat serta nakal
jang dulu biasa menempuh
djalan-djalan jang mengchawatirkan
dalam hidup lelaki yang kasar dan sengsara,
kini telah aku lepaskan
dan berganti dengan sandal rumah
jang tenteram, djinak dan sederhana
Sandal rumah itu memang telah dipakainja, tapi W.S. Rendra tidak mendjadi djinak
. Uban dikepalanja makin bertambah, tapi begitu pula pandjang rambutnja. Kerut-k
erut sudah mulai membajang disekitar matanja, tapi pandangan itu masih seperti t
atapan anak kidjang tjuma terkadang berkatjamata. Umur 36, anak 5, isteri 2: sta
tistik ini bisa mengetjutkan laki-laki lain djadi runduk, tapi Rendra tidak rund
uk. Ia hampir tidak berubah.
Ia memang bukan lagi Willy jang menjeru ibunja mamma hingga disadjak-sadjak. Puisi
nja kini adalah gumpalan ekspresi yang lebih keras, bukan lagi baris-baris balla
da dan njanjian manis. Hidup tak lagi ditemuinja seperti gadis ditemui djedjaka
remadja, melainkan hidup telah saja setubuhi dan keringat sudah membasahi randjan
g; dan bagi Rendra, itulah sebabnja kemanisan tahun 1950-an susut dari sadjaknja,
karena saja agak kaget setelah mendjumpai hidup ini tidak lagi perawan.[3]
Intinya, kalau ingin berbicara tentang buruh, berceritalah tentang pohon karet a
tau kelapa sawit. Kalau ingin meliput kehidupan sekelompok aktivis LSM, pilihlah
tokoh yang bau keringatnya bisa tercium. Setidaknya, pelajarilah teknik Ayu Uta
mi menggelitik bahasa lewat romannya, Saman.
Saya tidak menyarankan Anda menjadi sastrawan (meski apa salahnya jadi sastrawan
?). Yang Anda butuhkan adalah kemauan untuk memastikan sel-sel otak kiri tempat
kemampuan berbahasa dikendalikan tumbuh. Yang Anda lakukan adalah mengapresiasi
semua karya sastra bermutu. Ini bagus untuk melatih kepekaan dalam berbahasa tul
is dan kesehatan jiwa Anda sendiri. Dari situ, Anda akan mengenal kosa kata baru
, gaya bertutur, pola-pola kalimat kompleks, paragraf-paragraf yang berkesan, ba
gaimana membangun ritme ketegangan dan kelucuan, menempatkan kutipan menarik, se
rta banyak lagi.
Tak berarti Anda harus mencangkok kata-kata sastrawi ke dalam karya jurnalistik.
Dengan mengapresiasi karya sastra, Anda akan semakin yakin bahwa bahasa Indones
ia punya fasilitas yang cukup bagi mereka yang mau memikat khalayaknya.
Terinspirasi oleh langgam sastra, para wartawan suka menciptakan penyosokan (pro
filing) terhadap sumber berita. Yang terkenal, misalnya, manajer satu miliar untuk
menyebut Tanri Abeng. Atau, kiai sejuta umat untuk KH. Zainuddin Mz. Atau, ratu go
yang ngebor untuk pesohor dangdut Ainur Rokhimah alias Inul Daratista. Atau, senim
an serba bisa untuk Remy Silado. Atau, paus sastra Indonesia untuk H.B Jassin. Atau
, kaum sarungan untuk nahdliyin.
Baru-baru ini, pers Inggris menjuluki Tony Blair sebagai Tony teflon, karena kata-
kata si perdana menteri ternyata licin (seperti penggorengan teflon) alias bohon
g soal senjata pemusnah massal di Irak. Saya tidak tahu Paman Bush dijuluki apa.
Itu bagus, karena menunjukkan sang wartawan kreatif dan imajinatif. Pengelola pa
riwisata mesti berterima kasih kepada wartawan yang telah menyumbang kata Pulau D
ewata bagi Bali.
Toh, Anda yang terobsesi pada kreativitas dalam penyosokan, tetaplah waspada. Pe
nyosokan sumber berita juga harus mempertimbangkan relevansinya dengan konteks p
eristiwa. Umpama begini:
Preman asal Flores itu melakukan aksinya di Pasar Tanah Abang.
Penjudi ding-dong bermata sipit itu berusaha menyogok petugas.
Polisi menduga, pengusaha berkulit hitam itu sudah kabur ke luar negeri.
Penyosokan semacam itu bukan saja tidak relevan, tapi juga dapat melukai hati or
ang lain yang tak ada hubungannya dengan sumber berita. Seperti kata pepatah, un
tuk membuat kebakaran besar, kita cuma membutuhkan satu kali percikan api kecil.
Ingatlah petatah-petitih: Oleh pedang kita cuma mati sekali. Oleh kata kita terh
ina bergenerasi.
Sejumlah wartawan kawakan seperti Mark Kramer, John Hersey, Jimmy Breslin, dan T
ruman Capote, bahkan mampu menghidupkan karya jurnalistik mereka melebihi gaya nov
elistik, menjadi sinematik. Simak nukilan reportase Hersey bertitel Hiroshima be
rikut:
I A NOISELESS FLASH
At exactly fifteen minutes past eight in the morning, on August 6, 1945, Japanes
e time, at the moment when the atomic bomb flashed above Hiroshima, Miss Toshiko
Sasaji, a clerk in the personnel department of the East Asian Tin Works, had ju
st sat down at her place in the plant office and was turning her head to speak t
o the girl at the next desk. At the same moment, Dr. Masakazu Fujii was settling
down cross-legged to read the Osaka Asahi on the porch of his private hospital,
overhanging one of the seven deltaic rivers which divide Hiroshima; Mrs. Hatsuy
o Nakamura, a tailors widow, stood by the window of her kitchen, watching a neigh
bor tearing down his house because it lay in the path of an air-raid-defense fir
e lane; Father Wilhelm Kleinsorge, a German priest of the Society of Jesus, recl
ined his underwear on a cot on the top floor of his orders three-story mission ho
use, reading a Jesuit magazine, Stimmen der Zeit: Dr. Terufumi Sasaki, a young m
ember of surgical staff of the citys large, modern Red Cross Hospital, walked alo
ng one of the hospital corridors with a blood specimen for a Wassermann test in
his hand; and the Reverend Mr. Kiyoshi Tanimoto, pastor of the Hiroshima Methodi
st Church, paused at the door of a rich mans house in Koi, the citys western subur
b. And prepared to unload a handcraft full of things he had evacuated from town
in fear of the massive B-29 raid which everyone expected Hiroshima to suffer. A
hundred thousand people were killed by the atomic bomb, and these six were among
the survivors. They still wonder why they lived when so many others died. Each
of them counts many small items of chance or volition a step taken in time, a de
cision to go indoors, catching one streetcar instead of the next that spared him
. And now each knows that in the act of survival he lived a dozen lives and saw
more death than he ever thought he would see. At the time, none of them knew any
thing.[4]
Atau, simaklah bagaimana Breslin menulis reportasenya tentang prosesi pemakaman
jenazah John F. Kennedy. Kata-kata yang mengalir di situ seperti rekaman kamera
video: bergerak.
Clifton Pollard was pretty sure he was going to be working on Sunday, so when he
woke up at 9 a.m. in his three-room apartment on Corcoran Street, he put on kha
ki overalls before going into the kitchen for breakfast. His wife, Nettie, made
bacon and eggs for him. Pollard was in the middle of eating them when he receive
d the phone call he had been expecting.
It was from Mazo Kawalchik, who is the foreman of the gravediggers at Arlington
National Cemetery, which is where Pollard works for a living. Polly, could you pl
ease be here by eleven oclock this morning? Kawalchik asked. I guess you know what
its for.
Pollard did. He hung up the phone, finished breakfast, left his apartment so he
could spend Sunday digging a grave for John Fitzgerald Kennedy.
When Pollard got to the row of yellow wooden garages where the cemetery equipmen
t is stored, Kawalchik and John Metzler, the cemetery superintendent, were waiti
ng for him.
Sorry to pull you out like this on a Sunday, Metzler said.
Oh, dont say that, Pollard said. Why, its an honor for me to be here.
Pollard got behind the wheel of a machine called a reverse hoe. Gravedigging is
not done with men and shovels at Arlington. The reverse hoe is a green machine w
ith a yellow bucket which scoops the earth toward the operator, not away from it
as a crane does. At the bottom of the hill in front of the the Tomb of the Unkn
own Soldier, Pollard started the digging.
Leaves covered the grass. When the yellow teeth of the reverse hoe first bit int
o the ground, the leaves made a threshing sound which could be heard above the m
otor of the machine. When the bucket came up with its first scoop of dirt, Metzl
er, the cemetery superintendent, walked over and looked at it.
Thats nice soil, Metzler said.
Id like to save a little of it, Pollard said. The machine made some tracks in the gr
ass over here and Id like to sort of fill them in and get some good grass growing
there, Id like to have everything, you know, nice.
James Winners, another gravedigger, nodded. He said he would fill a couple of ca
rts with this extra-good soil and take it back to the garage and grow good turf
on it.
He was a good man, Pollard said.
Yes, he was, Metzler said.
Now, theyre to come and put him right here in this grave Im making up, Pollard said.
You know, its an honor just for me to do this.
Pollard is forty-two. He is a slim man with a mustache who was born in Pittsburg
h and served as a private in the 352d Engineers battalion in Burma in World War
II. He is an equipment operator, grade 10, which means he gets $3.01 an hour. On
e of the last to serve John Fitzgerald Kennedy, who was the thirty-fifth Preside
nt of this country, was a working man who earns $3.01 an hour and said it was an
d honor to dig the grave.
Yesterday morning, at 11:15, Jacqueline Kennedy started walking toward the grave
. She came out from under the north portico of the White House and slowly follow
ed the body of her husband, which was in a flag-covered coffin that was strapped
with two black leather belts to a black caisson that had polished brass axles.
She walked straight and her head was high. She walked down the bluestone and bla
cktop driveway and through shadows thrown by the branches of seven leafless oak
trees. She walked slowly past the sailors who held up flags of the states of thi
s country. She walked past silent people who strained to see her and then, seein
g her, dropped their heads and put their hands over their eyes. She walked out t
he northwest gate and into the middle of Pennsylvania Avenue. She walked with ti
ght steps and her head was high and she followed the body of her murdered husban
d through the streets of Washington.
Everybody watched her while she walked. She is the mother of two fatherless chil
dren and she was walking into the history of this country because she was showin
g everybody who felt old and helpless and without hope that she had this terribl
e strength that everybody needed so badly. Even though they had killed her husba
nd and his blood ran onto her lap while he died, she could walk through the stre
ets and to his grave and help us all while she walked.
There was mass, and then the procession to Arlington. When she came up to the gr
ave at the cemetery, the casket already was in place. It was set between brass r
ailings and it was ready to be lowered into the ground. This must be the worst t
ime of all, when a woman sees the coffin with her husband inside and it is in pl
ace to be burried under the earth. Now she knows that it is forever. Now there i
s nothing. There is no casket to kiss or hold with your hands. Nothing materials
to cling to. But she walked up to the burial area and stood in front of a row o
f six green-covered chairs and she started to sit down, but then she got up quic
kly and stood straight because she was not going to sit down until the man direc
ting the funeral told her what seat he wanted her to take.
The ceremonies began, with jet planes roaring overhead and leaves falling from t
he sky. On this hill behind the coffin, people prayed aloud. They were cameramen
and writers and Secret Service men and they were saying prayers out loud and ch
oking. In front of the grave, Lyndon Johnson kept his head turned to his right.
He is President and he had to remain composed. It was better that he did not loo
k at the casket and grave of John Fitzgerald Kennedy too often.
Then it was over and black limousines rushed under the cemetery trees and out on
to the boulevard toward the White House.
What time is it? a man standing on the hill was asked. He looked at his watch.
Twenty minutes past three, he said.
Clifton Pollard wasnt at the funeral. He was over behind the hill, digging graves
for $3.01 an hour in another section of the cemetery. He didnt know who the grav
es were for. He was just digging them and then covering them with boards.
Theyll be used, he said. We just dont know when.
I tried to go over to see the grave, he said. But it was so crowded a soldier told
me I couldnt get through. So I just stayed here and worked, sir. But Ill get over
there later a little bit. Just sort of look around and see how it is, you know.
Like I told you, its an honor.[5]
Bagaimana meliput optimisme pekerja kerah putih di tengah hiruk-pikuk metropolit
an seperti Shanghai? Saya suka bagaimana Pamela Yatsko, seorang wartawati majala
h Far Eastern Economic Review, menuliskan laporannya:
Jimmy Zou adalah seorang pegawai bank dan investasi milik provinsi di pelosok ne
geri. Kami bertemu sambil makan siang di Pasta Fresca, salah satu tempat makan b
aru masakan Italia di Shanghai. Mengenakan jas luar panjang dari bahan wol untuk
melawan dinginnya musim dingin, pria berusia 30 tahun ini terlihat seperti oran
g kaya. Cincin emas bermata berlian menghiasi jarinya dan kantongnya menggembung
berisi telepon seluler model baru pada umumnya penduduk Shanghai waktu itu masi
h masih mengandalkan seranta.
Apa maksud Anda bahwa Anda memunyai seorang teman di bursa saham yang membantu An
da memperoleh banyak uang? tanya saya.
Oh, dia (perempuan) menyampaikan berita baik kepada saya.
Apa maksud Anda dengan berita baik?
Dia memberitahu saya informasi di dalam cukup awal. Dia akan memberitahu saya sah
am-A yang sebaiknya dibeli, dan, tidak pernah meleset, dalam dua hari harganya a
kan naik.
Memang berita baik. Berapa banyak uang yang berhasil Anda peroleh tahun itu?
Oh, sekitar 200 ribu yuan, katanya sambil tertawa kecil.
Zou memunyai uang banyak untuk bisa tertawa. Dua ratus ribu yuan bernilai sekita
r 24.100 dolar AS. Dia cepat-cepat keluar dari biro turisme dan lebih memilih bi
snis perdagangan saham untuk menjadi jutawan dalam arti yuan.
Pada waktu pelayan mengantarkan pesanan cappucino kami, Zou sudah merasa amat sa
ntai. Kalau Anda mau, saya dapat melakukan sesuatu untuk Anda, katanya, menatap le
kat-lekat langsung ke mata saya.
Tapi saya seorang asing. Saya tidak diperkenankan untuk berdagang saham-A, jawab s
aya.
Tidak terkejut, Zou meneruskan: Tahun 1997 akan menjadi tahun yang amat makmur. S
aya amat yakin, bahwa semakin lama semakin banyak peluang yang menunggu kami. Di
Cina, bila Anda ingin memperoleh uang, Anda hanya perlu membeli, membeli, membe
li, dan pasar saham akan terus naik dan naik lagi! Anda hanya perlu mengetahui k
apan menjual dan kapan membeli dan saya yakin mengenai kapan melakukannya. Saya
yakin tahun ini saya dapat memperoleh laba 50 persen atau bahkan lebih besar lag
i, katanya sambil tersenyum lebar.
Bagaimana mungkin Anda begitu pasti?
Pasar saham-A mula-mula akan menurun karena koreksi tetapi kemudian harganya akan
naik karena ada modal menganggur dalam jumlah yang amat besar di Cina dan sedik
it peluang investasi, jadi pasar saham merupakan satu-satunya pilihan Anda tahu,
orang-orang terkaya di Cina hanya mereka yang bermain dalam saham. Beberapa di
antaranya tidak memunyai pendidikan tinggi. Tingkat budaya mereka rendah. Mereka
tidak memahami seni. Tetapi mereka mengetahui cara mencari uang.
Pelayan mengantarkan tagihan. Ketika saya membayar, saya bertanya kepada Zou apa
pendapat keluarganya mengenai keberhasilannya. Sambil meremas hidung, dia menja
wab, Mereka ingin saya bekerja di sebuah kantor menjadi pejabat pemerintah atau i
nsinyur. Mereka ingin saya menjadi pekerja kerah putih.
Tetapi Anda ADALAH pekerja kerah putih.
Mereka menduga saya penjudi. Tetapi sekarang, semakin lama semakin banyak orang C
ina yang berjudi dari profesor sampai pekerja sampai pengemis.[6]
Bagaimana mencampurkan elemen deskripsi, narasi, percakapan, pengadeganan ke dal
am loyang cerita yang utuh, silakan baca Harga Sebuah Keaslian.
Kutipan langsung dalam reportase bukanlah sekadar kiat untuk mendistribusi infor
masi. Ia juga unsur pemikat guna memuluskan jalan cerita. Ia merupakan sesuatu y
ang sangat penting, berharga, tidak bisa digantikan atau dihilangkan semau gue.
Wartawan dan redaktur harus jeli memilih kutipan dari sumber berita untuk dileta
kkan pada konteks yang tepat.
Kutipan yang baik umumnya merupakan kiasan. Sifatnya orisinil, khas, dan eksklus
if. Hingga hari ini, saya ingat kutipan-kutipan seperti:
Lengser keprabon madek pandhita, kata Presiden Soeharto.
Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, selama ia mampu menangkap tikus, ia ada
lah kucing yang baik, kata Deng Xiao Ping.
War can not be divorced from politics even for a single moment, kata Mao Ze Dong.
Read my lips, kata Presiden Bill Clinton.
History has called us, kata Presiden George W. Bush.
Gitu aja kok repot, kata Gus Dur.
Saya ini seperti mentimun. Bagaimana mungkin bisa melawan durian? kata Amien Rais
mengomentari kekalahannya dalam pemilu presiden.
Quand la Chine svelera, le monde tremblera, kata Raja Prancis, Napoleon Bonaparte,
tahun 1817. Artinya, ketika Cina bangkit, dunia pun bergetar.
Yang berani saya janjikan dalam sinetron ini adalah tanpa setan, tanpa kekerasan,
dan tanpa pornografi, kata Arswendo Atmowiloto, sutradara serial Keluarga Cemara
.
Ada tiga penemuan besar dalam peradaban, yaitu api, roda, dan Playboy, canda Hugh
Hefner, 77 tahun, pendiri majalah Playboy.
Memang, sedikit pejabat (terutama orde baru) di Indonesia yang punya pernyataan
menarik untuk dikutip. Pernyataan mubazir lebih banyak. Mereka tak terlatih meng
emukakan pemikiran atau gagasannya dengan cara sendiri, khas, dan orisinil. Di A
mrik, George Seldes sampai membuat dua buku, The Great Quotations (1960) dan The
Great Thoughts (1985), yang merupakan kumpulan gagasan dan kutipan terbaik dari
sumber-sumber beritanya.
Jangan putus asa. Coba rangsang sumber berita Anda agar menjadi dirinya sendiri se
waktu wawancara. Sekali seumur hidup, saya pernah membaca kutipan terbaik dari J
endral (Purn.) TNI L.B Moerdani selama menjabat sebagai Menhankam. Ketika dimint
ai komentar tentang organisasi militer Israel, dia menjawab, Saya suka tentara Is
rael. Di sana tidak ada perkumpulan seperti Dharma Wanita.
Sebagai wartawan, sekurangnya Anda bertugas membantu orang-orang untuk mengerti
apa yang terjadi di sekitar mereka; di desa, di kota, di negara, dan di dunia. S
ebagian besar dari mereka tidak memiliki kecakapan berbahasa seperti Anda. Anda
harus bisa memilah peristiwa dan pokok isu yang paling rumit, lalu menyampaikann
ya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti. Jika gagal melakukan hal ini, orang ak
an berhenti membeli suratkabar atau majalah Anda. Jika ini terjadi, saran saya:
carilah pekerjaan lain.
[3] Dikutip dari Rendra, Dimanakah Kau Saudaraku oleh Goenawan Mohamad (Majalah
Tempo, 1972).
[4] Dikutip dari Hiroshima oleh John Hersey (Majalah The New Yorker, 1946).
[5] Dikutip dari buku The Art of Fact (1984) yang disunting oleh Ben Yagoda.
[6] Dikutip dari New Shanghai oleh Pamela Yatsko (John Wiley & Sons, 2003).
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20018)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)



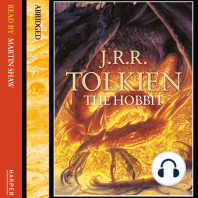




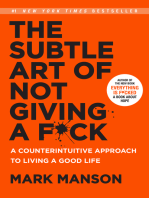

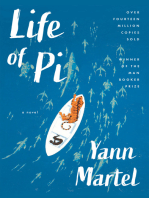









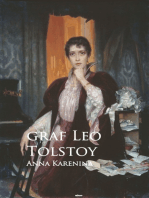
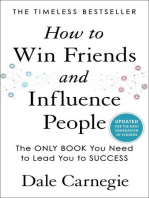


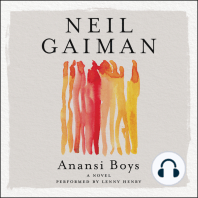
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)