Tatkala Pendidikan Terlalu Diformalkan
Diunggah oleh
Prof. DR. H. Imam SuprayogoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tatkala Pendidikan Terlalu Diformalkan
Diunggah oleh
Prof. DR. H. Imam SuprayogoHak Cipta:
Format Tersedia
Tatkala Pendidikan Terlalu Diformalkan
Bagikan
09 April 2009 jam 23:39
Semula pendidikan hanya berlangsung sederhana, yakni dilakukan
oleh orang tua masing-masing di dalam kehidupan keluarga. Tetapi
dalam perkembangan selanjutnya, ketika masyarakat semakin maju
seperti sekarang ini, pendidikan diurus oleh lembaga dan bahkan juga
pemerintah. Pendidikan kemudian ada yang bersifat formal, selain
yang masih bersifat informal dan non formal. Pendidikan yang diurus
oleh pemerintah dengan berbagai aturannya itu, maka diperuntukkan
bagi seluruh warga Negara, yang kemudian disebut pendidikan formal
itu.
Jika pendidikan semula hanya merupakan kepentingan keluarga, yakni
orang tua, agar para anak-anaknya bisa menyesuaikan dengan
lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat, maka
orang tua saja yang menjalankan pendidikan itu. Akan tetapi setelah
pendidikan ditangani oleh pemerintah dan menjadi formal, maka
pendidikan memiliki fungsi lebih luas, selain untuk memenuhi
kebutuhan anak yang bersangkutan, keluarga, tetapi juga untuk
kepentingan Negara. Pendidikan dilaksanakan oleh negara, sebagai
tanggung-jawabnya mensejahterakan warganya. Selain itu juga agar
para peserta didik menjadi warga Negara yang baik.
Setelah pendidikan diformalkan tidak berarti pendidikan lainnya, yaitu
pendidikan keluarga dan juga pendidikan masyarakat, dihilangkan.
Tidak. Pendidikan keluarga dan masyarakat masih tetap berjalan
sebagaimana lazimnya. Hanya saja, mungkin bisa jadi keluarga dan
masyarakat memahami bahwa peran-perannya sudah diambil alih oleh
lembaga pendidikan formal. Anggapan itu sesungguhnya tidak
seluruhnya benar. Pendidikan formal hanya berlangsung sebentar,
sekitar antara 6 sampai 7 jam sehari. Selain itu, anak-anak masih
sebagaimana biasa, hidup bersama keluarga. Jika ada pengecualian itu
adalah pendidikan pesantren dan boarding school atau pendidikan
berasrama. Lembaga pendidikan yang disebutkan terakhir ini, para
siswa bertempat tinggal bersama kyai atau pengurus lembaga
pendidikan secara bersama-sama.
Setelah pendidikan menjadi formal maka yang terjadi adalah juga
serba formal, pendidikan diatur sedemikian rupa. Semua yang terkait
dengan pendidikan distandarkan. Visi dan misinya harus jelas
rumusannnya. Demikian pula yang terkait dengan pelaksanaan
pendidikan, semua distandarkan. Ada standard isi, standart kurikulum,
standar sarana dan prasarana, standar tenaga pengajar, standart
biaya, standar lingkungan, ruang kelas dan semua apa saja distandar.
Bahkan juga jam belajar, cara penilaian, baju seragam, sepatu.
Pokoknya semua thethek bengek menyangkut pendidikan harus
mengikuti standar.
Orientasi pendidikan yang distandarkan itu, maka kemudian juga
mempengaruhi cara berpikir bagi siapa saja yang terkait dengan
pelaksanaan pendidikan itu. Orang dan lebih-lebih para pejabatnya
menjadi sibuk menyusun dan merumuskan standar pendidikan.
Demikian pula para pelaku pendidikan, seperti kepala sekolah, guru,
murid-murid semua dituntut menyesuaikan dengan standar itu.
Semakin berhasil mendekati standar, maka dianggap usahanya
berhasil. Oleh sebab itu kemudian muncul istilah standar minimal,
sesuai dengan standar, melebihi standar yang ditetapkan, dan
seterusnya.
Akibatnya, pendidikan seolah-olah menjadi mesin. Di sana ada input,
transformasi dan out put. Input pendidikan harus terstandar. Kapan
seseorang boleh memulai mengikuti pendidikan, waktu mengikuti
pendidikan pada setiap jenjang, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan
seterusnya. Demikian pula terkait dengan transpormasi, akan dilihat
persyaratan guru, waktu yang digunakan untuk keberlangsungan
pendidikan atau proses belajar mengajar, target-target kurikulum yang
telah dijalankan, buku pegangan yang telah dibaca, ujian dan
seterusnya. Semua syarat formal harus dipenuhi, karena pendidikan
menjadi formal. Demikian pula output pendidikan, harus memenuhi
standart. Ukuran-ukuran keberhasilan pendidikan ditetapkan. Bahkan
standar itu, karena pendidikan formal adalah otoritas pemerintah,
maka pemerintah pun kemudian juga menyelenggarakan ujian,
sehingga muncul istilah ujian nasional. Siapapun harus mengikuti ujian
ini, karena memang pendidikan harus dijalankan seperti itu.
Untuk menjalankan pendidikan formal ternyata tidak mudah. Ambil
saja misalnya terkait dengan guru. Guru harus memenuhi syarat lulus
S1 dan bersertifikat sebagai pendidik. Padahal yang terjadi di
lapangan, belum semua guru yang selama ini mengajar telah memiliki
sertifikat. Bahkan juga ternyata belum semua guru telah memiliki
ijazah S1.
Sebagai lembaga pendidikan formal, maka aturannya, semua
persyaratan harus dipenuhi. Maka akhir-akhir ini perlu diselenggarakan
serifikasi guru. Agar secara formal memenuhi syarat, guru harus
disertifikasi. Maka, dibentuklah lembaga sertifikasi guru. Perguruan
tinggi yang mengembangkan bidang studi kependidikan ditugasi
memberi sertifikat sebagai pendidik kepada guru yang telah
memenuhi syarat. Kemudian, para guru untuk mendapatkan sertifikat
harus menyusun porthofolio dengan melampirkan berbagai
kelengkapannya. Atas dasar porthofolio ditetapkan seorang guru lulus
dan berhak mendapatkan sertifikat atau masih harus mengikuti
persyaratan lainnya. Mereka yang dinyatakan lulus porthofolio
diberikan sertifikat dan kemudian diberikan tunjangan profesi sebesar
gaji pokok pada setiap bulannya.
Bagi mereka yang belum lulus mereka diberi pelatihan beberapa hari
oleh perguruan tinggi yang ditunjuk. Setelah mengikuti latihan, tentu
dinyatakan lulus dan kemudian secara formal pula akan mendapatkan
tunjangan sebagaimana guru-guru lainnya yang telah dinyatakan lulus
melalui porthofolio. Guru setelah melewati proses seperti ini, sebagai
syarat menjadi guru professional maka kesejahteraannya pun
meningkat. Mungkin ada orang usil lalu bertanya, mengapa sebatas
mensejahterakan guru yang sudah sekian lama bergaji rendah itu
harus melewati proses panjang dengan biaya dan energi yang tidak
sedikit. Maka jawaban standarnya adalah, bahwa lembaga pendidikan
formal harus mengikuti ketentuan formal. Inilah pendidikan formal,
yang sekalipun berliku-liku dan lewat proses panjang dan biaya mahal,
maka harus ditempuh agar keformalan menjadi syah.
Proses sertifikasi itu ternyata masih harus berhadapan dengan
kenyataan, bahwa tidak semua guru telah memiliki ijazah S1. Padahal
yang bersangkutan telah bertaun-tahun menjadi guru. Mereka itu jika
ditinggalkan kasihan, sehingga agar mereka bisa ikut disertifikasi
harus dicarikan jalan keluarnya. Maka diputuskan bahwa guru-guru
yang belum berpendidikan S1, sedang umurnya masih di bawah 50
tahun, diberi peluang sekolah lagi. Persoalannya kemudian muncul,
ialah jika mereka harus belajar lagi sedangkan jumlah mereka banyak,
siapa yang mengajar tatkala mereka menempuh program S1.
Munculnya persoalan baru ini, tidak saja membuat para pejabat
posing, harus mencari jalan keluar di mana para guru harus kuliah lagi,
tetapi juga harus menyediakan biaya kuliah yang tidak sedikit
jumlahnya. Sekali lagi karena ini lembaga pendidikan formal, sekalipun
hanya bersifat formalitas, maka bagaimanapun dan dengan cara
apapun persyaratan itu harus dipenuhi.
Akhir-akhir ini kabarnya sudah ada perguruan tinggi yang kreatif,
mendapatkan strategi untuk mensarjanakan (S1) para guru yang
belum memenuhi syarat itu. Strategi itu disebut dengan istilah dual
mode. Pelaksanaan pendidikan S1 bagi para guru tersebut masih
dipercayakan pada perguruan tinggi yang memiliki program studi
pendidikan. Strateginya, para guru masih diwajibkan sebagaimana
biasa, menunaikan tugas mengajar setiap hari, tapi harus mengikuti
program pendidikan S1 jarak jauh itu. Program dual mode, dirancang
sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Universitas Terbuka. Para
peserta kuliah yang terdiri atas para guru yang belum memenuhi
persyaratan sertifikasi ini diberi materi kuliah melalui modul-modul,
agar dipelajari sendiri di kampung halamannya bersama para guru
peserta program yang sama.
Sebagai bagian dari proses perkuliahan para guru peserta program ini
diberi kesempatan beberapa kali saja pada setiap semester
bersilaturrahmi ke kampus penyelenggara dual mode. Demikian juga
mereka diberikan tutor yang terdiri atas para dosen perguruan tinggi
yang bersangkutan, termasuk bimbingan penulisan makalah atau
skripsi, jika dipersyaratkan harus menulis skripsi. Jika para guru telah
mengikuti proses sebagaimana diprogramkan oleh perguruan tinggi
penyelenggara, maka mereka dinyatakan lulus sarjana S1 dan
kemudian bisa disertifikasi.
Program yang tidak sebagaimana standar selayaknya untuk
mendapatkan ijazah sarjana S1, banyak orang mempertanyakan.
Misalnya, bagaimana kualitas hasil program ini. Tentu jawabnya
mudah, bahwa program ini adalah telah memenuhi standar resmi yang
direstui oleh pejabat resmi. Sehingga, menurut ukuran resmi yang
serba formal itu, apa yang dijalankan ini sudah berkualitas. Tokh,
kualitas yang dimaksudkan adalah yang memenuhi standar atau
peraturan yang telah dibuat. Kualitas itu bukan sebagaimana yang
dimaksudkan oleh ukuran-ukuran para ahli yang obyektif dan rasional.
Ukuran itu adalah terpenuhinya kebutuhan formal.
Jika di sana sini ada sementara orang yang tidak puas, maka
semestinya mereka sadar, bahwa inilah resiko pendidikan yang
berorientasi pada ukuran-ukuran formal. Memang bagi siapapun yang
bertanggung jawab terhadap kualitas kehidupan bangsa ke depan,
tidak semestinya hanya mengejar terpenuhinya syarat-syarat
formalitas seperti ini. Kita memang menjadi prihatin dengan
pendidikan kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah, sehingga
ke depan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pihak-pihak
yang berwenang, tidak terlalu sembrono sehingga menyesakkan dada,
agar bangsa ini tetap selamat dan bermartabat. Memang ini semua
adalah sebagai resiko dari pendidikan yang terlalu diformalkan
itu.Allahu a’lam.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20020)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
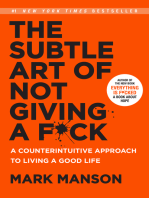












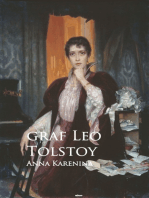
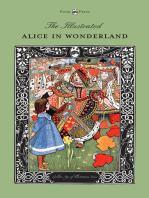

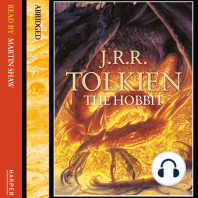

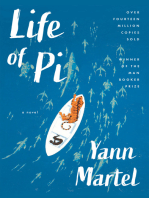





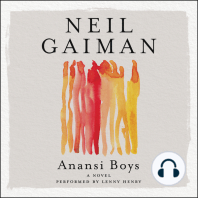



![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)