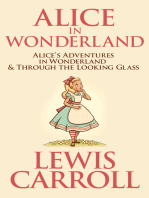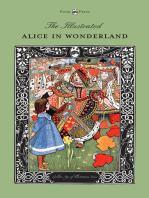Konsep Ekologis Berbasis Sosial Budaya PDF
Konsep Ekologis Berbasis Sosial Budaya PDF
Diunggah oleh
Putri Ajeng Sawitri0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
108 tayangan18 halamanJudul Asli
Konsep Ekologis Berbasis Sosial Budaya.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
108 tayangan18 halamanKonsep Ekologis Berbasis Sosial Budaya PDF
Konsep Ekologis Berbasis Sosial Budaya PDF
Diunggah oleh
Putri Ajeng SawitriHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 18
Konsep ekologis berbasis sosial budaya (ethno-ecology)
sebagai identitas masyarakat Hubula di lembah Palim,Papua
Ye, wam, he, eka, agatma werek
Batu ye (manifestasi dari para leluhur dan mitos asal usul), babi, perempuan dewasa dan uang,
semuanya dapat ditemukan dalam tanah
Yulia Sugandi
1
Abstrak
Tulisan ini berdasarkan pada penelitian etnografi dalam menelusuri makna tanah ulayat dalam
kerangka lanskap (landscape) bagi masyarakat Hubula di lembah Palim, Papua. Tanah ulayat
menjadi arena pergulatan antara konsep Hubula tentang kesuburan hidup menghadapi konsep
kemajuan modern yang dibawa oleh agen perubahan sosial. Konsep ekologis berbasiskan sosial
budaya (ethno-ecology) yang mengetengahkan relasi identitas dan tak terpisahkan (inalienable)
antara Hubula dengan tanah ulayatnya berinteraksi dengan pola relasi komoditas dalam aplikasi
program pembangunan yang berakibat pada alienasi antara Hubula dengan realitas kolektif
kosmologisnya. Upaya sebaliknya dilakukan dengan ethnodevelopment yang meniadakan
inferiority complex, guna memberikan ruang bagi perubahan sosial yang bermartabat.
Kata kunci: ethno-ecology, relasi identitas, tanah ulayat dalam lanskap, komodifikasi, inferiority
complex, ethnodevelopment
Pembangunan sebagai alat negosiasi identitas
Konsep pembangunan dan modernisasi di Dunia Ketiga kerap digunakan dalam proses
negosiasi identitas. Tradisi lokal terus menerus berinteraksi dengan proses globalisasi berikut nilai-
nilai dan praktek modern. Menjadi bagian dari masyarakat yang 'maju' merupakan idaman banyak
pihak. Standar tahap kemajuan suatu masyarakat mengacu pada model universal. Proses
pembangunan dilaksanakan guna mendorong perubahan sosial ke arah pencapaian yang ditetapkan
dalam model universal tersebut. Dalam hal ini, pembangunan kerap dipresentasikan dalam kerangka
1 Penulis adalah alumni Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Artikel ini merupakan ekstraksi dari
disertasi Doktoral penulis berjudul The Notion of Collective Dignity among Hubula in Palim Valley, Papua
(Martabat Kolektif masyarakat Hubula di lembah Palim, Papua) yang telah diuji pada tahun 2013 di Institut
Etnologi, Universitas Muenster, Jerman.
1
pertumbuhan ekonomi dan modernitas (Lewis 2005: 473-474). Semakin tinggi angka pertumbuhan
ekonomi dan semakin modern suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula status 'kemajuannya'.
Pergulatan status taraf kemajuan dalam proses pembangunan diwarnai oleh dinamika kekuasaan
antara agen perubahan sosial. Pembangunan merupakan simbol sekaligus alat ampuh dari hegemoni
barat yang secara lahiriah didefinisikan sebagai asmiliasi, tapi dalam prakteknya bertujuan sebagai
dominasi (Herzfeld 2001: 152). Kemajuan masyarakat apa pun didefinisikan secara seragam oleh
paradigma Barat tanpa mengindahkan keragaman latar belakang budaya. Model universal yang
diterapkan dalam kebijakan pembangunan menciptakan kesenjangan persepsi antara negara dan
masyarakat. Konstruksi realitas lokal tidak senantiasa sejalan dengan parameter pembangunan.
Proses pembangunan menjadi makin terlepas dari masyarakat setempat karena diarahkan oleh
lembaga-lembaga dan para ahli pembangunan yang menerapkan bahasa industri pembangunan dan
negara donor ketimbang memahami bahasa dan nilai-nilai lokal (cf. Van Esterik 1995: 256-257).
Konteks lokal yang tidak sesuai dengan standar kemajuan modern di atas kerap mendapat status
marjinal dan 'terbelakang'.
Ada beberapa hal signifikan yang patut diperhatikan dalam penerapan model universal guna
mengukur standar kemajuan suatu masyarakat sebagai keberhasilan program pembangunan.
Pertama, model universal mengarah kepada standar ilmu ekonomi baku, di mana 'manusia
ekonomis yang ideal' adalah individual yang berorientasi pada keuntungan yang terlepas dari relasi
sosial (cf. Gudeman 1986: vii, 29). Kedua, keseragaman standar kemajuan mencerminkan proses
evolusi satu arah (a unilineal evolutionary process) yang dipercepat dengan mengadopsi
teknologi,model dan metode Barat (cf. Cernea 1996: 15-16). Kedua hal ini berbeda dengan
pandangan antropologi, karena antropolog memperhatikan dampak perubahan sosial, bukan hanya
yang terkait dengan perikehidupan, namun lebih kepada persepsi tentang dunia.Antropolog
diharapkan mengungkapkan keanekaragaman budaya yang berlimpah serta menekankan pada nilai-
nilai dan pengetahuan lokal. Sejalan dengan Cernea (1996: 15-16), bahwa antropologi dan sosiologi
pembangunan sepatutnya menolak keras tiga model pembangunan yang dianggap sebagai model
reduksionis dari perubahan sosial (the econocentric, the technocentric, and the commodocentric),
serta sebaliknya menyediakan alternatif dan aksi terpadu. Pembangunan bukan mengenai
komoditas. Bukan pula tentang teknologi atau informasi semata. Pembangunan dalam kerangka
alternatif ini adalah tentang masyarakat, lembaganya, pengetahuannya, serta bentuk organisasi
sosialnya. Pembangunan bukan tentang akumulasi modal, tapi lebih kepada penemuan dalam
pelbagai relasi masyarakat (Gudeman 2001: 158).
Model alternatif dalam melihat perubahan sosial mencanangkan bahwa identitas masyarakat
terbangun dari jaringan yang ditempa melalui praktek dan konsep bersama, seperti hubungan
2
kekerabatan (kinship), pertemanan dan tempat tinggal. Identitas individu tercerminkan dalam relasi
dan nilai-nilai yang dibagi dengan pihak-pihak lain. Hal ini merujuk pada model budaya. Gudeman
(1986) berpendapat bahwa proses-proses utama dalam melangsungkan kehidupan adalah
berlandaskan model budaya yang berbeda dengan model ekonomi, karena model budaya lebih
merupakan praksis kebudayaan yang meliputi kepercayaan dan praktek yang membentuk dunia
seseorang. Ekonomi sebagai proses budaya memaparkan makna-makna setempat dari obyek yang
digunakan oleh masyarakat dalam modus kehidupan tertentu. Secara tersirat hal ini membebaskan
masyarakat untuk membuat model ekonomi mereka sendiri.
Sillitoe (2002: 9) menjabarkan bahwa pelekatan nilai identitas kolektif berdasarkan
konstruksi budaya ekonomi lokal erat kaitannya dengan konsep ilmu pengetahuan pribumi, di mana
konteks pembangunan terhubung dengan pengetahuan yang dimiliki secara kolektif oleh penduduk
setempat berisikan pemahaman tentang dunia yang terbentuk secara budaya tentang pemahaman
yang tertanam dalam seseorang sejak dia lahir yang membentuk pola interaksinya dengan
lingkungan. Hal tersebut berbasiskan pada masyarakat, tertanam dan dikondisikan oleh tradisi lokal.
Pembangunan mempertemukan tradisi lokal dan modenisasi yang dibawa dari luar. Sahlins (2005:
34-35) menyatakan bahwa tradisi tidak statis dalam hal ini dan bertentangan dengan 'modernitas'.
Dewasa ini, 'tradisional' paling banyak dirujuk pada suatu modus perubahan budaya yang
merupakan karakteristik dari perluasan pinggiran dari aturan kapitalis global. Tradisi lokal secara
terus menerus berinteraksi dengan proses globalisasi beserta nilai-nilai dan praktek modern. Tulisan
ini bermaksud mendeskripsikan perubahan sosial dari model budaya, khususnya konsep ekologis
yang terbentuk di kalangan masyarakat Hubula di lembah Palim, Papua. Lebih jauh tulisan akan
menelusuri pergulatan tradisi lokal Hubula yang berkaitan dengan ekologis ini menghadapi arus
pembangunan yang dibawa dari luar.
Stigmatisasi, inferiority complex dan modernisasi
Hubula, sebagai bagian dari masyarakat Papua secara keseluruhan memiliki tingkat
keamanan manusia yang rendah sebagaimana yang dideskripsikan oleh badan pembangunan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Ini mengindikasikan rendahnya akses terhadap hak-hak
dasar, terutama yang berkaitan dengan penyebab ketidakamanan dalam kerangka pembangunan
manusia seperti ekonomi, keuangan, pangan, kesehatan, lingkungan, keamanan pribadi, jender,
masyarakat dan politik. Unsur budaya tidak disebutkan secara eksplisit dalam parameter tersebut di
atas. Dalam hal ini, Hubula sebagai bagian dari masyarakat pribumi dari pegunungan Papua kerap
disebut sebagai kelompok garis keras yang menentang pemerintah Indonesia. Banyak areal di
wilayah pegunungan ini dilabelkan sebagai 'daerah merah' yang dianggap oleh aparat keamanan
3
sebagai basis Organisasi Papua Merdeka. Dengan alasan tersebut, akses ke wilayah tersebut
terbatas termasuk bagi para peneliti dan jurnalis.Stigmatisasi masyarakat pegunungan Papua ini
diperkuat oleh beberapa stereotipe negatif yang klasik. Hubula dikatakan sebagai masyarakat yang
terisolasi dan terpencil (Koentjaraningrat et al. 1993), primitif (Soepangat 1986: 144-145), orang
jaman batu atau Stone Age people (Dekker and Neely 1996), kanibal (Hitt 1962, Meiselas 2003: 38-
39), gemar berperang (Meiselas 2003: 62; cf. Schoorl 2001: 66), serta tidak mampu untuk hidup
secara damai dan harmonis (Schoorl 2001: 79-83).
Stigmatisasi ini berdasarkan pada persepsi yang meletakkan Hubula dalam posisi inferior,
yang mengantar mereka ke arah marjinalisasi dan pemaksaan pendekatan teknis oleh agen
pembangunan yang mengedepankan teknologi modern ketimbang pengetahuan dan nilai-nilai yang
dimiliki Hubula dalam proses perubahan sosial. Secara implisit, pendekatan teknis murni ini (purely
technicist approach) tidak mengindahkan hak-hak budaya masyarakat Hubula.Kondisi yang
terjadi dalam proses perubahan sosial di kalangan Hubula ini mengilustrasikan argumen Sahlins
(1990: 79) bahwa agen pembangunan menggunakan rasa superioritas dan teknologi untuk
mempermalukan masyarakat pribumi dalam melalui perubahan sosial. Peristilahan macam budaya,
keterbelakangan, pembangunan, kemajuan dan modernisasi digunakan dengan nada
mempermalukan. Para penggiat pembangunan menganggap bahwa aksi mempermalukan tersebut
merupakan langkah penting dalam pembangunan ekonomi, dan suatu prekondisi yang diperlukan
untuk mencapai ekonomi 'lepas landas'. Aksi mempermalukan memutus siklus reproduksi dan
ekspansi dalam pembangunan dengan jalan meyakinkan kelompok masyarakat tentang
ketidakberhagaan budaya mereka dan menumbuhkan rasa rendah diri menyeluruh (global
inferiority complex) yang mendorong mereka untuk secara aktif berubah (1992a: 24)
2
. Ungkapan
yang sering diutarakan Hubula yang menggambarkan pergulatan mereka dalam proses perubahan
sosial adalah pagar hidup telah terbongkar (eyuu...leget misalaga yire). 'Pagar' digambarkan
Hubula sebagai parameter identitas kelompok (in-group dan out-group). Hubula yang keluar dari
jalur leluhur dianggap 'di luar pagar' (leget itigma) sedangkan yang mengikuti jalur leluhur
dianggap 'di dalam pagar' (leget akmake). Dinamika persinggungan antara jalur leluhur dengan agen
perubahan sosial dari luar lembah Palim menghasilkan kondisi 'pagar' di atas.
Jalur leluhur sebagai landasan ekologis
Strategi yang digunakan dalam perang, teknik memancing, keterampilan berorasi serta pola
pertukaran disebut jalur (path). Namun demikian, jalur juga meliputi hubungan yang terjalin, pola
relasi dan asosiasi antara orang, kelompok dan unit politik yang diciptakan oleh aksi tertentu di
2 Sebagaimana dikutip dalam Robbins 2005: 4, 10-11.
4
masa lalu. Hal ini juga secara implisit mencakup kemungkinan dan kewajiban guna mengikuti jalur
pertukaran dalam pernikahan, kerja sama dan kompetisi (Parmentier 1987: 109). Aplikasi ide ini ke
dalam konteks Hubula memungkinkan kita melihat bahwa jalur leluhur (the ancestors path) yang
berdasarkan pengalaman hidup mereka, membentuk latar belakang sejarah obyek dan tempat yang
dianggap sakral dan tabu. Mitos Hubula berfungsi sebagai model bagi perilaku, dan Hubula melihat
sejarah dan mitos sebagai kerangka acuan bagi aksi di masa depan (cf. Itlay et al.1993: 21). Oleh
karena itu, maka dalam rangka memahami struktur masyarakat Hubula kita hendaknya menyadari
bahwa landasan jalur bagi aksi diletakkan oleh cerita leluhur yang meliputi moiety, mitos dan
perang tradisional.
Figur 01. Zone teritorial Hubula secara fungsional (Yayasan Bina Adat Walesi 2003)
Landasan ekologis Hubula secara sosial budaya meliputi pengharagaan holistik Hubula
terhadap pelbagai elemen yang ada di lingkungan tanah ulayat. Ini termasuk menghargai relasi
dengan tanah, sumber daya alam dan binatang dalam konsep eksploitasi dan ekonomi : (a) seluruh
tumbuhan dan binatang memiliki hak sama dengan manusia dalam menduduki tanah (ika oka sue
hageo aroma ewe apuni), (b) hanya berburu binatang di zone yang diizinkan, (c) tempat di dataran
paling tinggi merupakan habitat para leluhur dan ruh penunggu tanah (hunkepu) sehingga
menjadikannya sebagai zone bebas ekploitasi, (d) makin rendah ketinggian, makin terbuka untuk
eksplotasi dan peranan gender, (e) Menghormati yang bersemayam di dunia ruh (mokatma),
misalnya makhluk yang menanam, memelihara dan melindungi pohon (oi yare). Ikatan yang kuat
terjalin bukan hanya antara Hubula, para ruh, binatang, tanaman serta para penghuni lainnya,
namun juga antara Hubula dengan tanah ulayat itu sendiri.Ketidakterpisahan Hubula dengan tanah
diungkapkan dengan relasi kekerabatan (kinship) langit adalah bapak, sementara tanah adalah ibu
5
(pogot ninopase nen agat ninagosa), serta identifikasi diri Hubula adalah sebagai manusia dari
Palim (akhuni palim meke). Siapa saja yang menjual tanah ulayat dianggap bertindak tidak hormat
terhadap ibu sendiri dan melanggar aturan adat leluhur. Oleh sebab ini, maka tanah ulayat secara
prinsip tidak terpisahkan dari Hubula.
Hubula tidak mengenal status tanah tidak bertuan karena mereka percaya bahwa seluruh
alam di lembah Palim termasuk gunung, lembah, sungai, tanah, hutan, batu dan lain sebagainya,
milik akenak werek (secara harfiah berarti tanahku berada). Status akenak werek meliputi
segenap teritorial Hubula termasuk zone ekologis. Mitos tentang sejarah eksplotasi tanah ulayat dan
lahirnya status akenak werek adalah sebagai berikut: Pada saat itu ada satu dari wita dan waya
datang dari arah selatan dan menempati satu lokasi dan mengklaim bahwa itu tanahnya dengan cara
menyalakan api dan merokok. Selanjutnya membuat kebun, dan selanjutnya orang lain membuat
perkampungan dan membuka lahan. Pada saat pertama ditempat, mereka potong babi dan percikkan
tanah dan bilang bahwa tanah ini saya yang punya. Selanjutnya setelah lama satu klen berkembang
menjadi lebih banyak dan tinggal di lokasi tersebut.
Setiap batas wilayah memiliki cerita leluhur tersendiri. Menurut tetua Hubula, setiap
tempat, setiap pojok, setiap sudut di lembah Palim mengandung cerita leluhur yang perlu
dilestarikan. Narasi ini tampak dalam sepanjang tanah serta lingkungan sekitarnya di lembah
Palim. Narasi leluhur merupakan representasi emik dari topografi lembah Palim sekaligus eko-
kosmologis antara Hubula dengan tanahnya. Para leluhur yang digambarkan dalam narasi adalah
pemilik tanah, lembah, sungai, batu, hutan dan segenap yang dihasilkannya (akenak werek) ,
sementara keturunannya dengan pasangan moiety nya merupakan penjaga yang memelihara tanah
leluhur. Setiap anggota garis keturunan akenak were memahami batas-batas teritorial yang diwarisi
dari generasi ke generasi. Pewarisan ini bersifat permanen, tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat
diambil alih atau tukar ganti. Para pemimpin honai adat mewakili akenak werek sehingga hanya
lelaku dewasa Hubula yang telah diinisiasi yang juga anggota dari honai adat adalah penjaga/wali
tanah ulayat.
Ekologis berbasis sosial budaya (ethno-ecology) di lembah Palim mengilustrasikan
ketidakterpisahan antara identitas Hubula dengan tanahnya, serta penyatuan dunia material dan non
material leluhur. Tanah bermitos di mana Hubula dan makhluk hidup lainnya di lembah Palim
menunjukkan bahwa para leluhur berdaulat secara kosmologis di sana, dilokalisasikan dalam tanah
melalui pemercikan darah dari kurban babi. Kurban babi memegang peranan penting di kalangan
Hubula. Tanah leluhur dilegitimasi melalui percikan darah babi (wam mep) sebagai bagian upaya
menghadirkan leluhur (yerebo). Setiap upacara adat Hubula guna menegaskan status tanah leluhur
membutuhkan kehadiran leluhur tersebut. Percikan darah babi menunjukkan hadiah pengorbanan
6
(sacrificial gift) demi akses terhadap kesuburan, tanah serta produktivitasnya.
Tanah ulayat pembentuk kesuburan hidup bersama
Jalur leluhur melekat pada obyek sakral, tanah leluhur dan sumber daya alam yang ada di
lembah Palim, sehingga pengelolaannya senantiasa merujuk pada narasi leluhur. Ini termasuk
memprioritaskan para leluhur melalui upacara adat dan menghormati segenap obyek dan wilayah
sakral. Relasi antara Hubula dengan para leluhurnya dan ruh diproyeksikan terhadap relasi
ekologisnya serta digunakan sebagai parameter dalam nilai ekonomi dari tanah beserta hasil alam.
Ekonomi merupakan bagian kecil dari sebuah siklus yang lebih panjang, di mana segala yang
dihasilkan dari tanah leluhur dikembalikan pada para leluhur.Hal ini terlihat pula dari upacara adat
yang dilakukan selama masa cocok tanam.
Berdasarkan alasan ini, maka relasi antara Hubula dengan tanah leluhurnya bukan relasi
kepemilikan, melainkan relasi identitas. upacara adat yang dilakukan Hubula menegaskan penilaian
mereka terhadap relasinya dengan para leluhur yang melebihi kepentingan ekonomi: tanah bukanlah
properti dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai komoditas. Pemaknaan cerita atau 'jalur' leluhur
bagi Hubula diterjemahkan ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil yakni rumah tangga. Hubungan
antara Hubula dengan cerita para leluhurnya terlihat dari pelbagai bentuk obyek yang terdapat di
tempat tinggal baik sebagai artefak atau obyek sakral maupun makhluk hidup. Hubula memaknai
nilai tempat tinggal secara keseluruhan melalui upaya memelihara 'jalur' leluhur.
Para leluhur memegang otoritas utama yang mempengaruhi ruang hidup dan kesejahteraan
para mahluk yang bertempat tinggal di atas tanah ulayat Hubula. Ini merupakan argumen mendasar
yang membuat tanah beserta sumber daya alam di lembah Palim sebagai wilayah kediaman leluhur.
Relasi Hubula dengan para peluhurnya diproyeksikan terhadap tanah, serta direfeleksikan dalam
tata cara pengelolaannya. Evans-Pritchard (1956) menunjuk pada unsur penebusan dalam upacara
pengorbanan masyarakat Nuer untuk mendapatkan perlindungan dari para leluhur. Namun
demikian, dalam konteks Hubula, upacara adat ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan
sekaligus mencegah amarah dari para leluhur. Melanggar jalur leluhur dalam pengelolaan tanah
ulayat beserta hasil alamnya akan mendatangkan kemarahan para leluhur yang pada akhirnya akan
menyebabkan menurunnya tingak kesuburan hidup. Dapat dikatakan bahwa ksejahteraan (well
being) Hubula dan segenap mahluk di lembah Palim tergantung pada keseimbangan kosmologis,
terutama relasi dengan para leluhur. Hubula senantiasa memposisikan diri di bawah kekuasaan para
leluhur , dan melalui upacara adat mereka memelihara hubungan hutang budi yang tak kunjung
habis terhadap leluhur atas kesuburan yang didapat dari mereka. Relasi yang harmonis dengan para
leluhur dan ruh menghasilkan perlindungan, dukungan dan kelangsungan kesuburan; sebaliknya,
7
relasi yang tidak harmonis dengan para leluhur akan mengantarkan mereka pada
ketidakberuntungan dan ketidaksuburan. Para leluhur dapat melindungi atau mengancam
kesejahteraan Hubula. Tanah merupakan milik leluhur dan kesuburan Hubula serta akses terhadap
tanah tergantung pada relasi dengan para leluhur. Para penerus garis keturunan memelihara
hubungan tersebut di atas melalui upacara adat dan relasi baru yang terbangun di masa kini
sepatutnya bertujuan untuk memperkuat relasi awal yang dibangun leluhur.Dalam hal ini, posisi
subordinat Hubula terhadap para leluhur pemilik tanah ulayat menegaskan argumen De Coppet
(1981) dan Williams (1986) bahwa masyarakat mengasosiasikan tanah bermitos (mythical land)
bukan sebagai pemilik atau warga penghuni, akan tetapi sebagai organik atau komponen spiritual
dari tanah dan kekuatan yang terkandung di dalamnya dimana 'tanah bermitos memiliki
penduduknya' dan bukan sebaliknya.
3
Figur 02. Penyembuh tradisional (ubule) saat melalukan upacara adat penyembuhan terhadap
seorang pasien yang terganggu akibat kemarahan akenak werek
3 Abramson (2000: 8-9) mengutip De Coppet (1981) dan Williams (1986). Penduduk Indonesia timur juga
merupakan bagian dari tanah atau 'para pemilik' wilayah alam. Cf Visser (1989: 12, 28) dan Platenkamp (1988: 112,
115).
8
Figur 03. Akenak werek berhak secara tunggal terhadap produksi tanah yang dapat dilihat dari
persembahan berupa pemercikan darah babi di awal periode cocok tanam, pemeliharaan babi adat sepanjang
periode cocok tanam serta petatas hasil panen pertama yang ditaruh di atas tanah.
Tanah ulayat sebagai bagian dari lanskap
Pepatah Hubula 'memegang erat hidup yang baik dengan tangan kita' (niniki hano rogo fago
dogosak) mencerminkan pandangan hidup berdasarkan pada 'ibu' atau tanah ulayat yang
menghasilkan petatas (hipere), yang memungkinkan untuk memelihara babi (wam) yang pada
saatnya digunakan sebagai mas kawin. Pengantin perempuan kemudian melahirkan anak-anak yang
akan melindungi jalur leluhur dan menjaga tanah ulayat. Seluruh elemen ini dalam siklus ini saling
terkait, tak terpisahkan dan saling ketergantungan, di mana ancaman terhadap satu elemen akan
mempengaruhi seluruh elemen yang ada. Pentingnya tanah ulayat jelas terlihat sebagaimana
diungkapkan Hubula, tanpa tanah ulayat tidak akan ada petatas atau bahkan ruang untuk melindungi
jalur leluhur. Tanpa tanah ulayat, tidak akan ada babi atau Hubula, atau kehidupan. Ritus peralihan
Hubula (rites of passage ) memerlukan partisipasi para pemimpin honai adat, pengorbanan babi
adat serta jenis petatas tradisional seperti helalekue lama, arugulek, musaneken, hulok, hoboak, and
bogoreken
4
.
4 There are some other traditional sweet potatoes that are used to feed the pigs, including opem, ouluk, duak, musan,
mikmak. The differences between new and old (traditional) sweet potato cultivars include the persistent stem after
harvest. Stems of old sweet potato cultivars do not dry out quickly after harvest and keep on producing new shoots
until they are utilized as new planting material or fed to the pigs. The stems of new cultivars usually do not produce
new shoots after harvest (Widyastuti, et.al. 2002: 152, 154-155).
9
Strathern menekankan pentingnya peranan babi bagi masyarakat Maring di Papua Nugini
dalam produksi dan ritual pertukaran yang bertujuan mendapatkan dukungan dari para leluhur
(Strathern 1983: 79). Di lain pihak, Hubula melihat ketergantungan antara tanah ulayat, Hubula,
petatas dan babi sebagai simbol perwujudan dari totalitas kosmos. Tanah ulayat diletakkan dalam
kerangka lanskap ketimbang unsur terpisah. Lanskap juga sekaligus merupakan peta tofografi, suatu
penafsiran kosmologis (cosmological exegesis), suatu lanskap klen (clanscape), serta suatu entitas
ritual dan politik (Barnard and Spencer 2002: 323). Lanskap tidak pernah pasif. Masyarakat terlibat
pembentukan di dalamnya. Lanskap merupakan bagian di mana identitas diciptakan dan
diperebutkan, baik oleh individu, kelompok maupun negara. Oleh karena bekerja dalam
persimpangan sejarah dan politik,relasi sosial dan persepsi budaya, lanskap merupakan konsep yang
menciptakan ketegangan (Barnard and Spencer 2002: 324). Lanskap di mana Hubula hidup dan
bekerja di lembaah Palim adalah sebagai berikut:
Figur 04. Siklus Hubula dalam membangun perikehidupan yang berkesinambungan
Perang tradisional sebagai landasan ontologis struktur sosial
Tanah bagi masyarakat Melanesia bukan semata aset ekonomi namun salah satu aspek
fundamental bagi organisasi sosial politik yang menyokong kelanjutan eksistensi masyarakat
setempat (Silitoe 2000: 86-88).Tanah ulayat Hubula berkaitan erat dengan upacara adat Hubula
yang terhubung dengan sejarah perang tradisional, obyek sakral/simbol leluhur, pemimpin adat
penjaga jalur leluhur (kanekela) serta pengorbanan babi. Dalam periode masa lalu, perang
tradisional Hubula telah digambarkan sebagai aksi kekerasan yang berfungsi membentuk karakter
Hubula serta merupakan landasan kebanggaan bersama (cf. Heider 1970; Koentjaraningrat 1993).
Namun demikian, pandangan ini tidak mencakup fakta bahwa melalui upacara adat, perang
tradisional adalah media pertukaran kekerasan (an exchange of violence) secara kosmologis antara
10
Sweet potatoes
(hipere)
Pig
(wam)
Hubula
Land (agat)
identitas leluhur (intra ancestral identities) di mana pada saat yang sama membentuk landasan
struktur sosial Hubula. Perang tradisional yang diupacara adatkan ini merupakan mekanisme
internal yang berlaku eksklusif bagi Hubula di lembah Palim guna mencapai tingkat kesuburan
yang dikehendaki. Perang tradisional Hubula menghasilkan simbol leluhur (ancestral emblem) yang
mendasari kategori sosial yang membentuk empat aspek masyarakat Hubula. Aspek pertama, yakni
lahirnya obyek sakral berupa simbol leluhur. Pertukaran kekerasan yang terjadi dalam perang
tradisional dimulai dengan pengambilan simbol leluhur dari korban dari pihak musuh yang gugur
dalam pertempuran yang dinamakan apwarek. Dalam saat yang sama, kaneke dibuat sebagai tanda
penghargaan yang diberikan kepada leluhur yang gugur dalam medan pertempuran.
Kedua simbol leluhur di atas adalah obyek sakral bagi Hubula yang juga melandasi
pembentukan aspek kedua, yakni unit ritual (kanekela) beserta pemimpinnya (yaman, metek and
apisan), yang sekaligus berstatus sebagai penjaga jalur leluhur dan tanah ulayat serta bertugas
melegitimasi upacara adat Hubula melalui pengorbanan babi. Setiap kanekela dipimpin oleh tiga
kelompok pemimpin kanekela yang terbentuk dari sejarah perang tradisional: sang penjaga
(yaman), sang pengatur (metek) dan sang pemerintah (apisan). Ketiga posisi ini berdasarkan
kronologis leluhur yang yang gugur dalam sejarah perang tradisional. Leluhur pertama yang gugur
menjadi yang tertua (yaman), yang kedua menjadi metek dan ketiga menjadi apisan. Apabila ada
korban gugur yang keempat biasanya dikategorikan sebagai yaman. Dan begitu seterusnya.
Kepemimpinan tradisional ini mencerminkan keterlibatan para leluhur selaku pemilik tanah ulayat
(akenak werek) lebih dari pada campur tangan perseorangan.
Aspek ketiga adalah pola relasi yang terbentuk dari hasil aliansi dalam perang tradisional
adalah hutang sosial atau balas budi (social debt) yang menentukan relasi kekerabatan yang nyata
dan semu di antara anggota kanekela, preferensi dalam pernikahan dan akses terhadap tanah ulayat
beserta hasil alamnya. Di saat yang sama lahir pula status 'musuh abadi' (silimeke), kelompok lawan
saat perang tradisional di mana 'pihak lain' permanen didefinisikan. Sejatinya, batas dengan
kelompok luar (out-group) tidak dapat dirubah. Baik relasi hutang sosial maupun musuh abadi
menghasilkan pola pertukaran yang unik.
Aspek keempat, kejelasan identitas leluhur sebagaimana terwujud dalam benda-benda sakral
merupakan landasan (ero; akar) dari struktur sosial Hubula serta unsur penting dalam mencapai
kesuburan. Beberapa mantera yang diucapkan pada saat upacara adat Hubula adalah berdasarkan
harane (secara harfiah diartikan sebagai suara raja), suatu permohonan terhadap para leluhur yang
merancang startegi dalam pertempuran (wim awok ikerekmeke). Kejelasan sejarah pertempuran
tertentu (misalnya siapa taun perang yang merencanakan pertempuran dan siapa yang mengugurkan
lawan) menentukan keaslian mantera tersebut. Keempat aspek tersebut di atas membentuk argumen
11
bahwa perang tradisional Hubula merupakan landasan ontologis struktur sosial Hubula yang
berperan terhadap pencapaian kesuburan bersama. Para pemimpin honai adat di atas (kanekela)
terus berupaya melalui upacara adat guna memperkuat relasi yang terwujud dalam simbol leluhur
dan menjinakkan leluhur lawan. Para pemimpin kanekela (yaman, metek and apisan) adalah
jembatan leluhur antara peradaban dan wilayah ruh yang diciptakan melalui pengorbanan babi. Bagi
Hubula, pengorbanan babi dengan puncak upacara adat yakni pemercikan darah babi di atas tanah
ulayat membawa inti sari kehidupan bagi seluruh makhluk di tanah leluhur di lembah Palim.
Pada dasarnya, keempat aspek tersebut di atas memperlihatkan bahwa seluruh pola relasi
Hubula, baik secara kosmologis, sosio-budaya dan ekologis, maupun relasi sosial di antara anggota
masyarakat Hubula berakar dari sejarah perang tradisional. Secara singkat, konflik dalam bentuk
perang tradisional berkaitan dengan konsep kesuburan hidup sebagaimana terwujudkan dalam
kondisi tanah ulayat, produktivitas kebun dan kemakmuran manusia dan babi peliharaan.
Figur 05. Pemercikan darah babi di atas tanah ulayat setelah 'melepaskan' tanah ulayat pada Perusahaan Air
Minum (PAM). upacara adat yang dilakukan menegaskan leluhur sebagai pemilik tunggal tanah ulayat
(akenak werek) serta ikatan tak terpisahkan antara Hubula, tanah ulayat dan para leluhur.
Alienasi tanah ulayat: relasi identitas versus komodifikasi
Kerangka hukum tentang tanah ulayat di Indonesia melihat tanah sebagai entitas terpisah
dari masyarakat pribumi. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Dasar Agraria (Basic
Agrarian Act, atau BAA) tahun 1870 yang dirumuskan oleh pemerintah kolonial Belanda, hutan
merupakan lahan tidak produktif atau tanah tak bertuan (no man's land) dan dikuasai oleh negara.
Peraturan ini mengizinkan warga asing untuk mencicil tanah dari pemerintah dalam jangka waktu
12
lama dalam rangka investasi praktis dan menyewa menyewa tanah dari masyarakat pribumi.
Kebijakan ini dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia dalam Hukum Pokok Agaria 1960. UU
No.44/1999 tentang kehutanan mempertimbangkan hutan adat sebagai bagian dari kepemilikan
hutan secara nasional, hanya mengakui sebagai hutan yang dimiliki privat atas nama individu.
Meskipun Hukum Pokok Agraria di atas secara eksplisit memaparkan bahwa relasi antara
masyarakat dengan tanah ulayatnya bukanlah relasi kepemilikan atau properti, namun tetap
mengakui kepemilikan individu. Undang-Undang Republik Indonesia No.5/1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 2 ayat 4 menyatakan Hak menguasai dari Negara tersebut diatas
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
Verifikasi legal status tanah ulayat berdasarkan pada kesaksian lisan dari para pemimpin dan
tetua adat, dan banyak tanah ulayat belum terdaftar di kantor pemerintah karena persepsi pada
umumnya bahwa hukum adat telah ada sebelum kedatangan pemerintah. Meskipun TAP MPR No
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, pasal 41 menyatakan bahwa Identitas
budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan
perkembangan zaman, akan tetapi pada kenyataannya hak-hak adat terhadap tanah ulayat kerap
tersubordinasi oleh sertifikat kepemilikan secara legal.
Aplikasi legal terhadap tanah ulayat berarti bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk
mengaturnya. Pada bulan December 1956, Frits Veldkamp, kepala administratif dari pemerintah
kolonial Belanda (Hoofd van Plaatselijk Bestuur or HPB) yang pertama tiba di lembah Palim
berasama dengan 15 orang lainnya, kebanyakan berasal dari daerah pesisir Papua. Berlandaskan
argumen tanah tak bertuan, mereka menerapkan program pembangunan seperti pembukaan
landasan pacu pesawat terbang yang pertama (cikal bakal bandara udara kota Wamena). Pada
periode berikutnya, pemerintah Indonesia mendefinisikan tanah ulayat Hubula sebagai milik negara.
Hal tersebut dapat dilihat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kota Wamena dalam mengatasi
urusan pertanahan. Salam satu penyebab konflik pertanahan di lembah Palim, menurut BPN adalah
kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanah secara legal. Namun demikian,
persepsi ini hanya menyentuh segi kepemilikan namun tidak mengakomodir tanah ulayat dalam
konteks identitas.
Pendaftaran tanah ulayat secara legal dapat berdampak negatif. Stewart and Strathern
(1999: 190) mendeskripsikan perlawanan di Mount Hagen terhadap usulan untuk mendaftarkan
tanah adat, dengan anggapan bahwa mengurangi penggunaan tanah atas nama perseorangan akan
membuka kemungkinan adanya alienasi terhadap tanah. Studi kasus dari Sinakma di lembah Palim,
13
mengilustrasikan hal tersebut. Kasus ini berkisar tentang konflik yang dihasilkan dari
pengaplikasian aturan hukum pemerintah, yang mengarah pada proses alienasi tanah ulayat Hubula
kepada pihak luar, serta transfer berikutnya kepada para pihak lainnya. Pada tahun 1962,
perwakilan dari badan misionaris Protestan dari Amerika yakni Christian and Missionary Alliance
(CAMA) membuat kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewa tanah ulayat
Hubula yang dianggap sebagai tanah tak bertuan dan telah dikompensasi dengan sejumlah kulit
kerang (cowry shells). Pada tahun 1963, seiring dengan penyerahan New Guinea dari pihak Belanda
pada Indonesia, tanah tersebut diakuisisi oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, kepemilikan
tanah ulayat termaksud berpindah-pindah kepemilikan, mulai dari Dinas Peternakan, pemerintah
Kabupaten, dan perusahaan listrik negara. Kepemilikan tanah ini juga merambah ruang lingkup
perseorangan dengan adanya klaim dari beberapa kelompok klen Hubula sampai dengan konflik
horisontal antar anggota masyakarat (Hubula dan non Hubula). Kompleksitas status kepemilikan
menjadi rumit dengan peralihan dari banyak pihak tanpa didukung dokumen legal yang layak serta
kesenjangan persepsi antara pemerintah dan Hubula tentang status tanah ulayat.
Komoditas digunakan sebagai kompensasi terhadap tanah ulayat Hubula. Sebelum Hubula
diperkenalkan dengan uang tunai, pelbagai komoditas lain digunakan seperti alat pertanian dan kulit
kerang. Pada perkembangan selanjutnya, kompensasi ini menghasilkan individualisasi dan
komodifikasi, bahkan konflik yang memakan korban jiwa. Sebagai contoh terlihat dari kasus yang
terjadi tahun 1960an di utara lembah Palim, saat misionaris Katolik dari Belanda memberikan
kompensasi dalam bentuk alat pertanian dan kulit kerang untuk sebidang tanah ulayat di bagian
utara lembah Palim. Bangunan sekolah dibangun di atas tanah ulayat tersebut yang sejatinya adalah
wilayah jalur leluhur yang sakral. Oknum Hubula yang menerima kompensasi tersebut di atas
melakukan serah terima secara diam-diam tanpa memberitahukan anggota masyarakat Hubula
lainnya. Meskipun pembangunan sekolah mendapat sambutan tidak hangat dari masyarakat Hubula
sekitar, namun misionaris yang bertugas melanjutkan proses pembangunan karena merasa telah
berhak atas tanah setelah pemberian kompensasi. Kemarahan anggota masyakarat memuncak dan
berakhir dengan terbunuhnya guru sekolah berasal dari Fak Fak yang dipekerjakan oleh misionaris
Belanda.
Program pembangunan berjalan seiring dengan alienasi tanah ulayah di lembah Palim.
Selain kompensasi berupa komoditas, pemerintah kolonial Belanda dan misionaris merasa berhak
atas tanah ulayat karena telah melaksanakan program pembangunan. Di lain pihak, pemerintah
Indonesia menggunkan program pembangunan yang ditetapkan dari pusat, sebagai salah satu solusi
penyelesaian sengketa tanah ulayat. Pendirian kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
pada tahun 1988 di lembah Palim bertujuan untuk mengatasi konflik sengketa tanah ulayat akibat
14
klaim dari Hubula terhadap tanah ulayat yang digunakan sebagai bandara udara Wamena. Misi
pembangunan dengan teknologi tepat guna yang diemban LIPI beserta para ahli tekniknya dianggap
sebagai kompensasi atas tanah ulayat. Para ahli teknik yang dikerahkan dalam misi ini berfokus
pada pencapaian hasil yang dapat diterapkan ketimbang memperhatikan proses-proses budaya itu
sendiri (cultural processes). Pembangunan yang dilakukan dari sudut pandang pertumbuhan
ekonomi dan modernisasi ini juga bertujuan untuk membuat penduduk Wamena guna mengakui
keberadaan dan otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Proses alienasi tanah ulayat berlanjut dengan komodifikasi berupa kompensasi tanah ulayat
dengan uang tunai dan dalam beberapa kasus, deskaralisasi jalur leluhur. Beberapa studi kasus
menunjukkan bahwa mengkorelasikan tanah ulayat dengan uang tunai menghasilkan dinamika
internal antara anggota masyarakat Hubula. Banyak tanah ulayat yang telah 'dilepas' dengan
kompensasi uang tunai, mengalami sengketa berkelanjutan karena banyak pihak datang silih
berganti mengaku sebagai yang berhak atas tanah ulayat tersebut dan mengklaim kompensasi.
Selain dari meningkatnya individualisasi yang mengarah pada 'manusia ekonomis yang ideal'
terlepas dari relasi sosial (lihat bagian awal tulisan ini), kesenjangan persepsi tentang nilai tanah
ulayat terjadi antara kelompok Hubula dari generasi yang berbeda. Nilai ekonomi berpola
konsumtif berbenturan dengan nilai idealis-spiritual dari tanah ulayat. Namun demikian, dalam
beberapa kasus, logika ekonomi-hadiah (gift economy) berjalan bersama dengan logika komoditas
(commodity economy).Sebagai contoh adalah kasus 'pelepasan' tanah ulayat berikut sumber mata air
di Napua bagi proyek Perusahaan Air Minum (PAM). Dari kaca mata pihak luar memandang bahwa
persoalan tanah ulayat itu sudah selesai ketika kompensasi berupa uang tunai diserahakan pada
Hubula yang mengakui sebagai akenak werek. Akan tetapi, upacara adat yang dilakukan termasuk
pemercikan darah babi di atas tanah tanah ulayat tersebut menegaskan ketidakterpisahan
(inalienability) antara Hubula dan para leluhur. Dus, kemungkinan terjadinya siklus klaim
kompensasi atas tanah ulayat ini masih terbuka selama belum ditemukan mekanisme penyelesaian
yang tepat.
Dialog antara konsep kesuburan hidup dengan kemajuan modern?
Konsep ekologis berbasis sosial budaya Hubula meletakkan tanah ulayat dalam konteks
lanskap. Kesuburan hidup yang berakar dari relasi antara Hubula dengan para leluhur dan dunia
immaterial merupakan landasan dari ekologis sosial budaya Hubula. Jalur leluhur yang terdapat
dalam lanskap tanah ulayat memiliki peranan penting dalam mencapai kesuburan hidup Hubula.
Penggunaan tanah ulayat beserta sumber daya alam di lembah Palim berdasarkan prinsip-prinsip
ekologis sosial budaya yang memprioritaskan relasi kosmologis yang harmonis dari pada
15
komodifikasi. Sejak pertemuan dengan pihak luar, Hubula telah menyaksikan pergulatan
kekuasaaan antara otoritas negara dan lembaga agama di lembah Palim. Paradigma baru yang
ditawarkan oleh pemerintah dan gereja mencakup penggantian pandangan tradisional Hubula yang
menyeluruh dengan konsep kemajuan modern yang menyangkal jalur leluhur. Hal ini mendorong
adanya pelbagai kampanye dalam bentuk program pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Bagi Hubula, tanah ulayat adalah kunci menuju reproduksi sosial, dan, menggunakan
istilah Robbins dan Akin (1999), telah ditunggalkan (singularised) atau dilindungi dari
komodifikasi. Konsep kepemilikan (ownership) yang dibawa oleh baik pemerintah dan misionaris
bertentangan langsung dengan ideologi Hubula tentang perwalian (guardianship) atau penjaga
tanah ulayat. Hubula mempertahankan kesuburan hidup bersama melalui pemercikan darah babi di
atas tanah ulayat. Daya tahan Hubula dalam menghadapi modernisasi bertujuan untuk melindungi
relasi identitas tak terpisahkan antara mereka dengan tanah ulayat dan para leluhurnya. Beberapa
studi kasus yang dimuat dalam tulisan ini menunjukkan biaya kemanusiaan yang timbul akibat
konflik yang dihasilkan oleh ketidakseimbangan paradigma antara Hubula dan pelbagai agen
perubahan sosial. Dialog antara paradigma di atas patut di pertimbangkan tanpa mengikutsertakan
inferiority complex.
Bibliografi
Abramson, A.
2000 Mythical Land, Legal Boundaries: Wondering about Landscape and Other Tactics. In: A. Abramson
and D. Theodosspoulos (eds.), Land, law and Environment, pp.1-30. London: Pluto.
Barnard, A. and J. Spencer (eds.)
2002 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. New York: Routledge.
Cernea, M.M.
1996 Social Organization and Development Anthropology: the 1995 Malinowski Award Lecture.
Washington D.C: World Bank.
Dekker, J. and L. Neely
1996 Torches of Joy: a Stone Age Tribes Encounter with the Gospel. Seattle: YWAM Publishing.
Evans-Pritchard, E.E.
1956 Nuer Religion. Oxford: Clarendon Press.
Gudeman, S.
1986 Economic as Culture - Models and Metaphors of Livelihood. London: Routledge and Kegan
Paul.
2001 The Anthropology of Economy: Community, Market and Culture. Malden, MA: Blackwell.
Heider, K.G.
1970 The Dugum Dani - a Papuan Culture in the Highlands of West New Guinea. Chicago: Aldine.
16
Herzfeld, M.
2001 Anthropology: Theoretical Practice in Culture and Society. Oxford: Blackwell.
Hitt, R.T.
1962 Cannibal Valley. New York: Harper & Row.
Itlay, S. and B. Hilapok
1993 Kepribadian dan Kebudayaan Orang Balim. In: A.S. Susanto-Sunario (ed.), Kebudayaan Jayawijaya
dalam Pembangunan Bangsa, pp. 20-40. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Koentjaraningrat and V. Simorangkir (eds.)
1993 Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Departemen Sosial, Dewan Nasional Indonesia
untuk Kesejahteraan Sosial dan PT Gramedia Pustaka.
Lewis, D.
2005 Anthropology and Development: the Uneasy Relationship. In: Carrier,J.G. (ed.), A Handbook of
Economic Anthropology, pp. 472-486. Cheltenham: Edward Elgar.
Meiselas, S.
2003 Encounters with the Dani. Gttingen: Steidl Publishers.
Parmentier, R.J.
1987 The Sacred Remains - Myth, History and Polity in Belau. Chicago: University of Chicago
Press.
Platenkamp, J.D.M.
1988 Tobelo: Ideas and Values of a North Moluccan Society. Leiden: Repro Psychologie.Robbins, J. and
Robbins, J. and D. Akin (eds.)
1999 Money and Modernity - State and Local Currencies in Melanesia. Pittsburgh: University of
Pittsburgh Press .
Sahlins, M.
2005 The Economics of Develop-man in the Pacific. In: J. Robbins and H. Wardlow (eds.), The
Making of Global and Local Modernities in Melanesia- Humiliation, Transformation and the
Nature of Culture Change, pp.23-42.Aldershot : Ashgate.
Schoorl, P.
2001 Belanda di Irian Jaya - Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962. Jakarta: KITLV and Garba
Budaya.
Sillitoe, P.
2002 Participant Observation to Participatory Development- Making Anthropology Work. In: P. Sillitoe et
al. (eds.),Participating in Development: Approaches to Indigenous Knowledge, pp. 1-23. London:
Routledge.
Soepangat, S.
1986 Indonesian School as Modernizer: a Case Study of the Orang Lembah Baliem Enculturation. PhD
Dissertation, Florida State University.
Strathern, A.
1983 Pigs and Politics in Papua New Guinea. Bikmaus 4(4): 73-79.
Visser, L.E.
1989 My Rice Field is my Child - Social and Territorial Aspects of Swidden Cultivation in Sahu,
17
Eastern Indonesia. Dordrecht: Foris.
Wardlow H. (eds.)
2005 The Making of Global and Local Modernities in Melanesia- Humiliation, Transformation and the
Nature of Culture Change. Aldershot : Ashgate.
Widyastuti, C.A., et.al.
2002 Dani Women's Knowledge On and its Contribution to Maintenance of Sweet Potato in Baliem
Valley. In: R. Rao and D. Campilan (eds.), Exploring the Complementarities of In Situ and Ex Situ
Conservation Strategies for Asian Sweetpotato Generic Resources, pp. 150-158. Serdang, Malaysia:
International Plant Genetic Resources Institute Regional Office for Asia, the Pacific and
Oceania (IPGRI-APO). [Proceedings of the 3
rd
International Workshop of the Asian Network for
Sweetpotato Genetic Resources (ANSWER), Denpasar, Bali, Indonesia, 2-4 October 2001.]
18
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (730)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12956)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5734)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)