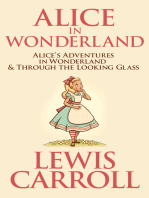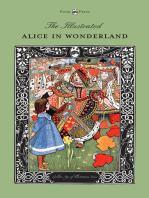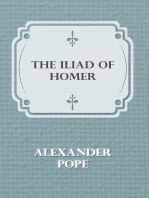Ternyata Amerika Itu Ada Di Kampungku
Ternyata Amerika Itu Ada Di Kampungku
Diunggah oleh
wt_alkatiri0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
280 tayangan4 halamanModernisasi dan Kesehatan Jiwa. Gangguan mental yang ditimbulkan oleh materialisme dan hiper-konsumtif.
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniModernisasi dan Kesehatan Jiwa. Gangguan mental yang ditimbulkan oleh materialisme dan hiper-konsumtif.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
280 tayangan4 halamanTernyata Amerika Itu Ada Di Kampungku
Ternyata Amerika Itu Ada Di Kampungku
Diunggah oleh
wt_alkatiriModernisasi dan Kesehatan Jiwa. Gangguan mental yang ditimbulkan oleh materialisme dan hiper-konsumtif.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Ternyata Amerika itu ada di kampungku
Modernisasi dan Kesehatan Jiwa
Psikolog John F. Schumaker, penulis buku The Age of Insanity: Modernity
and Mental Health yang di dalam bukunya berbicara tentang gangguan kesehatan
jiwa dari individu dan masyarakat yang hidup di tempat-tempat yang mengalami
‘modernisasi’ itu akhirnya tidak sanggup hidup lebih lama lagi di tanah kelahirannya
sendiri. Dia pun meninggalkan Amerika dan pindah ke negara kecil di belahan bumi
selatan, New Zealand. Kepada majalah New Internationalist Magazine dia
menceritakan perasaan gundah yang telah membuatnya hengkang itu selalu
datang lagi ketika dia mengunjungi kampung halamannya di Wisconsin setelah
kepindahannya beberapa tahun lalu. Dengan rinci dia mengungkapkan perasaan
tersiksa yang dialaminya ketika dia berada dalam sebuah mall yang ramai
pengunjung lengkap dengan ilustrasi suasana ruang dan suara di tempat itu, serta
pengamatannya pada seorang anak yang berjalan dengan ibunya yang membawa
penuh tentengan belanja. Membacanya, saya langsung teringat dengan suasana
mall-mall dan orang-orang di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Solo,
Yogya, Balikpapan, Palembang, dan kota2 besar lainnya. Ternyata kalau Amerika
cuma seperti itu berarti Amerika juga ada di kampung saya, di Indonesia.
Orang Amerika, kata dia, telah mengalami capitalism’s psychological dead
end - kebuntuan psikologis akibat kapitalisme - istilah halus yang dia pakai untuk
mengatakan ‘penyakit jiwa’ yang ditimbulkan oleh kapitalisme, dimana hidup
bertopeng kaleidoskop pilihan-pilihan konsumen. Diapun merasakan ada semacam
gangguan jiwa pada dirinya setiap kali dia pulang ke kampung halamannya,
existential loneliness, yang kurang lebih berarti merasa kesepian di tengah
keramaian.
Amerika, yang oleh ilmuwan sosial sering disebut sebagai the all consuming
society atau masyarakat yang maha meng-konsumsi itu telah mengekspor
budayanya ke seluruh penjuru dunia. Budaya over-konsumsi telah diinstitusikan
menjadi sebuah kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Rakus, tamak
dan serakah sekarang bukan lagi hal tercela, ini merupakan persyaratan mutlak bagi
kemajuan ekonomi suatu bangsa. Lulusan perguruan tinggipun beramai2
mengambil program MBA. Sekolah bisnis dan kursus apapun yang dibuat berbau
bisnis, menjadi jurusan paling laku di dunia pendidikan. Setiap manusia kini adalah
customer, jadi jumlah manusia yang banyak sama dengan pasar yang besar.
Ideologi ini telah secara mengagumkan melontarkan perekonomian di banyak
negara, jadi siapapun yang mau maju harus mengadopsinya juga.
Kejadian berikutnya adalah tragedi kemanusiaan!. Thornton Wilder
meramalkan itu di dalam karyanya The Bridge of San Luis Rey. Di sana dia
menggambarkan orang-orang yang mabuk-kepayang dengan dirinya sendiri dan
kepentingannya sendiri, dan tentu saja mereka selalu dirundung kecemasan akan
apa-apa yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan keinginannya itu. Cobalah
sejenak kita mengorek di bawah permukaan kemajuan ekonomi suatu tempat, pasti
terkuak di sana ada wabah penyakit ketamakan dan keserakahan. Budaya “setiap
orang adalah customer” memang telah terbukti sebagai pemenang dari sudut
pandang ekonomi yang digerakkan oleh over-konsumsi. Sebelum krisis ekonomi,
total aktivitas ekonomi yang dihasilkan dari belanja pribadi di Amerika adalah 70% -
jauh lebih besar dari negara manapun. Belanja pribadi di sana berkisar 50% sampai
dua kali lipat dibandingkan dengan semua negara-negara Eropa. Di sana, orang
juga tidak perlu malu menjadi penghutang. Tahun 1999 total hutang kartu kredit
penduduk Amerika adalah USD 1.5 triliun, sedang total hutang konsumen mencapai
USD 6 triliun.
Selanjutnya, mari kita tengok bagaimana keadaan sampah di sana. Orang
Amerika meninggalkan jejak perusakan lingkungan terbesar di dunia. Strategi
ekonomi over-produksi, over-belanja, dan over-konsumsi mereka telah
meninggalkan tumpukan sampah yang tinggi. Satu keluarga dengan 4 anggota di
sana membuang sampah non-biodegradable, tak terkomposkan dan tak terdaur
ulang, sebanyak 15 kg per hari. Mayoritas orang Amerika menganut kaidah ekonomi
primitif yang melandasi tindakan mereka menjarah sumber daya alam di negara-
negara lain untuk memenuhi hasrat over-konsumsi yang mereka yakini baik bagi
kepentingan negaranya sendiri. Keinginan terus berbelanja kini dianggap terhormat.
Terus mencari sensasi baru dengan barang baru kini menjadi semacam perbuatan
terpuji. Mencari ilmu tidak lagi menjadi tujuan anak muda di sana. Di tahun 1970
hasil survey perguruan tinggi Amerika menunjukkan 80% mahasiswanya bercita-cita
membangun filsafat hidup yang bermakna, di tahun 1989 angka itu turun menjadi
41%. Dalam kurun waktu yang sama jawaban ‘ingin menjadi sangat kaya’ meningkat
dari 39% menjadi 75% - yang bisa jadi 20 tahun kemudian, yaitu hari ini, menjadi
hampir 100%. Telah terjadi pergeseran besar-besaran makna pendidikan di dalam
masyarakatnya.
Penelitian para ahli kesehatan jiwa menunjukkan bahwa materialisme
membawa efek meracuni kesehatan psikologis seseorang dan juga social well-being
nya atau kemampuannya hidup bermasyarakat. Orientasi materialistik yang kuat
pada seseorang terkait erat dengan rendahnya kemampuan merasa puas dan
bersyukur, rendahnya harga diri, ketidak mampuan menghargai persahabatan dan
menikmati hal-hal menyenangkan di dalam hidup, serta mudahnya seseorang
mengalami depresi. Penelitian mereka menunjukkan tingginya faham materialisme
di tengah masyarakat Barat telah menjadi penyumbang utama peningkatan tajam
jumlah pasien depresi di sana sebanyak 10 kali lipat dalam 50 tahun terakhir.
Kelainan psikologis lain yang terkait dengan materialisme adalah compulsive
shopping (belanja berlebihan), consumer vertigo (membeli aneka barang yang
sebetulnya dia bisa hidup baik2 saja tanpa itu semua), dan kleptomania. Hiper-
materialisme juga memunculkan gangguan kelainan eksistensial seperti chronic
boredom (kebosanan kronis), ennui (keengganan), jadedness (lesu-layu),
purposelessness (tidak bertujuan), meaninglessness (hampa makna) serta
alienation (ter-alienasi). Survei yang dilakukan terapis menunjukkan 40% orang
Amerika yang mencari jasa pychoterapy mengalami gangguan2 itu yang sering
disebut dengan psychic.deadness atau kematian psikis. Sekali materialisme menjadi
epicenter kehidupan seseorang, maka akan sulit baginya untuk merasakan ‘hidup’
yang sesungguhnya, diluar kepungan benda-benda ‘mati’ yang mengelilingi dunia
konsumen. Penelitian terkini pada perguruan tinggi Amerika menunjukkan 91%
mahasiswa merasakan kehampaan eksistensial. Anak2 di Amerika pun terkena
wabah ini. Rata2 anak berusia 8 tahun di sana bisa menyebutkan 30 merek
terkenal. Lebih dari 90% anak perempuan berusia 13 tahun menyebutkan shopping
sebagai pengisi waktu luang paling favorit yang kemudian diikuti dengan menonton
TV. Ahli periklanan dan pemasaran di sana telah berhasil menerapkan strategi
indoktrinasi “berbelanja dari buaian ibu sampai liang lahat”.
Bukankah membaca tulisan ini seakan kita sedang bercermin melihat wajah
sendiri? Amerika yang seperti itu juga ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan,
Semarang, Solo, Yogya, Balikpapan, Palembang, dan kota2 besar lain di Indonesia.
Boleh jadi materialisme itu juga yang menyebabkan tingginya kejadian bunuh diri
akhir2 ini di sana. Materialisme bisa menjangkiti siapa saja, kaya maupun miskin.
Kalau John F. Schumaker yang agnostic saja bisa begitu kritis terhadap
materialisme bagaimana dengan kita yang selalu mengaku sebagai orang
beragama? Bukankah itu juga maksud pesan Rasulullah pada umatnya, bahwa
sebenar-benarnya keburukan adalah tergila-gila pada duniawi. Schumaker menutup
wawancara majalah itu dengan pesan “menemukan obat penawar keracunan
Amerika harus menjadi prioritas nomer satu bagi komunitas internasional”
Sanggupkah kita?
----------------------------
Oleh: Wardah T. Alkatiri
Penulis sedang melakukan penelitian Doktoral Social Science bertema Adaptasi Climate
Change di Indonesia, di Lincoln University, New Zealand. Penulis mendapat Master di bidang
Islamic Philosophy dari Islamic College for Advanced Stuides (ICAS) Jakarta
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)