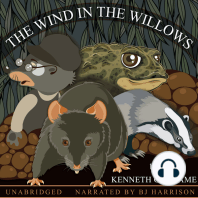PKL Tnap
PKL Tnap
Diunggah oleh
nin$Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
PKL Tnap
PKL Tnap
Diunggah oleh
nin$Hak Cipta:
Format Tersedia
MAKALAH KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG PROFESI DI
TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
Judul
: Evaluasi Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati (Banteng dan Penyu) di Taman Nasional Alas
Purwo
Oleh
: Nini Sriani
(E34070014)
Putu Parta Yudha
(E34070015)
Ulfah Zul Farisa
(E34070026)
Elmilia Alda
(E34070046)
Akbar Sumirto
(E34070055)
Juli Setiawan
(E34070074)
I. PENDAHULUAN
Nurul Handayani
1.1. Latar Belakang
(E34070111)
Kawasan
konservasi merupakan salah satu benteng terakhir dalam
Pembimbing
: Dr. Ir. Rinekso
Soekmadi,
M.Sc.f
upaya perlindungan dan penyelamatan
sumberdaya
hayati
secara in-situ.
Dr.yang
Ir. Agus
P. Kartono,
M.Silokasi diharapkan
Kehadiran kawasan konservasi
dilindungi
pada suatu
memberi peran signifikan dalam upaya konservasi SDA di dalam kawasan
yang ditetapkan (Soekmadi, 2003). Taman Nasional Alas Purwo merupakan
salah satu taman nasional yang memiliki potensi berbeda meliputi tumbuhan
dan satwa yang khas dan dilindungi. Banteng dan penyu merupakan jenisjenis satwa yang mendapatkan pengelolaan khusus di Taman Nasional Alas
Purwo. Terdapat empat jenis penyu yaitu, penyu abu-abu (Lepidochelys
olivacea) penyu belimbing (Dermochelys coriacea), penyu sisik
(Eretmochelys imbricata), dan penyu hijau (Chelonia mydas). Banteng
merupakan satwa khas pulau Jawa. Jenis Bos javanicus javanicus hanya
terdapat di pulau Jawa bagian timur dan populasinya semakin terancam
karena adanya perburuan liar, termasuk di kawasan konservasi. Banteng di
Taman Nasional Alas Purwo tersebar hampir di seluruh kawasan, namun
untuk orientasi terkonsentrasi banyak dijumpai di Padang Rumput
Sadengan. Untuk itu, di lokasi tersebut seringkali diadakan pembinaan
habitat banteng agar populasinya tetap lestari.
1.2. Tujuan
1) Mengidentifikasi pengelolaan banteng (Bos javanicus) di Feeding Groud
Sadengan
2) Mengidentifikasi pengelolaan penetasan penyu semi alami di Ngagelan
II. METODE KEGIATAN
2.1. Waktu dan Tempat
Kegiatan praktek kerja lapang profesi ini dilaksanakan padai
tanggal 21 Februari 22 Maret 2011 dan berlokasi di SPTNW I
Tegaldlimo (resort Rowobendo, Bedul, Grajagan) Taman Nasional Alas
Purwo.
2.2. Alat dan metode yang digunakan
Jenis Data
Pengamatan populasi
Banteng (Bos javanicus)
Pengukuran produktivitas
pakan Banteng (Bos
javanicus)
Aspek penangkaran
Penyu semi alami
a) Pengamatan
jumlah individu
penyu pada tiap
jenis
b) Pengamatan
habitat penyu
Metode
Terkonsentrasi
Analisis vegetasi
tumbuhan bawah
Alat yang digunakan
Binokuler dan teleskop
Meteran, patok bambu,
dan tali rafia
Gunting rumput
Kertas koran
Kantong plastik
Neraca pegas
Sumber
Pengamatan
langsung
Pengamatan
langsung
Pengukuran SVL
Meteran
Caliper
Kamera
Senter
Alat tulis
Neraca pegas
Pengamatan
langsung
Pengukuran
kandang,
Lalar
Meteran
Senter
Alat tulis
Pengamatan
langsung
2.3. Jenis dan Cara Pengambilan Data
2.3.1. Pengelolaan Banteng (Bos javanicus) di STPNW 1 Tegaldlimo
2.3.1.1. Populasi
Pengamatan menggunakan metode terkoinsentrasi. Data yang
diambil yaitu jumlah individu dan komposisi kelas umur (individu
jantan, betina, muda dan anak).
2.3.1.2. Habitat
Komposisi jenis rumput atau pakan, pendugaan produktivitas pakan,
ketersediaan air, dan kondisi cover atau shelter.
2.3.1.1. Metode Analisis Fisik
Berkaitan dengan konservasi sumberdaya air yaitu dengan
melakukan pengukuran suhu udara, kelembaban udara, debit air,
dan persentase kecerahan sumber air.
2.3.2. Pembinaan Penyu Semi Alami di Ngagelan
2.3.2.1 Jumlah individu penyu
Penetasan penyu semi alami di resort Ngagelan adalah jumlah
individu penyu, musim penyu bertelur, ukuran karapas, dan
produktivitas penyu yang meliputi jumlah telur serta jumlah telur
yang menetas.
2.4. Analisis Data
2.4.1. Pengelolaan Banteng (Bos javanicus) di STPNW 1 Tegaldlimo
TNAP
2.4.1.1. Populasi Banteng
Persamaan penduga ukuran populasi dengan metode penghitungan
terkonsentrasi :
Keterangan :
= Nilai rata-rata contoh pada titik konsentrasi ke h
= Jumlah individu pada titik konsentrasi ke h
= Jumlah titik pengamatan pada ke h
= Dugaan populasi total pada titik konsentrasi ke h
= Jumlah ulangan pada titik konsentrasi ke h
2.4.1.2. Habitat Banteng
Analisi habitat dilakukan secara deskriptif kualitatif.
2.4.2. Pembinaan Penyu Semi Alami di Ngagelan
Data diperoleh dari hasil wawancara, studi pustaka, dan observasi
langsung ke lapangan. Diolah dan di analisis secara deskriptif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengelolaan Banteng (Bos javanicus) di STPNW 1 Tegaldlimo TNAP
3.1.1. Populasi Banteng
Data populasi banteng (Bos javanicus) diambil melalui pengamatan
langsung di padang rumput Sadengan. Pengamatan dilakukan pagi hari
(07.00-10.00) dan sore hari (pukul 15.00-17.00). Pengamatan dilakukan
dengan cara menghitung semua individu banteng di padang rumput
Sadengan.
Gambar 1 Grafik tingkat perjumpaan banteng di feeding ground Sadengan
selama periode 24 Februari-13 Maret 2011.
Berdasarkan grafik diperoleh jumlah populasi tertinggi banteng
mencapai 72 ekor yang terjadi pada cuaca cerah dan jumlah populasi
terendah banteng mencapai 27 ekor pada hari hujan. Diperoleh juga rata-rata
pada cuaca mendung dan hujan jumlah banteng yang keluar untuk
merumput lebih sedikit dibandingkan pada hari cerah. Struktur umur
banteng menunjukkan usia dewasa 85% dan anak 15%. Hal ini
menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah. Tingkat pertumbuhan
Banteng yang rendah dikarenakan strategi reproduksi banteng yang
termasuk tipe k yaitu jumlah anak yang sedikit namun dipertahankan hingga
dewasa. Sedangkan untuk perbandingan jenis kelamin diperoleh 1: 3.
Menurut Alikodra (1983) rasio jenis kelamin untuk banteng yang ideal
adalah sekitar 1:4-8. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui tingkat strukur umur yang lebih spesifik yaitu tua, dewasa,
remaja dan anak. Hal ini sangat penting untuk mengambil kebijakan
pengelolaan populasi yang tepat.
a.
b.
Gambar 2 Diagram a. perbandingan jenis kelamin Banteng di TNAP, dan b.
komposisi banteng pada setiap perjumpaan.
Berikut disajikan grafik perjumpaan banteng periode bulan JanuariDesember 2010.
Gambar 3 Grafik perjumpaan populasi bulanan banteng di feeding ground
Sadengan periode Januari-Desember 2010.
Konsentrasi banteng paling tinggi yang dapat dijumpai di feeding
ground Sadengan adalah pada bulan Juni, namun tidak menunjukkan
perbedaan jumlah yang signifikan dengan bulan-bulan lain. Hal ini berbeda
dengan hasil penelitian Dewi dkk (2009) yang menyebutkan bahwa
konsentrasi tertinggi perjumpaan banteng adalah bulan Mei yang merupakan
awal musim kemarau. Hal ini dimungkinkan karena banteng mencari lokasi
persediaan air minum dan pakan yang tidak tersedia di lokasi lain.
3.1.2. Habitat Banteng
Feeding ground Sadengan memiliki luas 84 Ha. Antara tahun 1999
hingga 2008 feeding ground Sadengan mengalami penyusutan luasan karena
invasi semak dan pepohonan, terutama alang-alang (Imperata cylindrica)
dan enceng-enceng (Casia tora). Menurut Sunandar (2000) dalam Nurhara
dkk. (2008), desakan ini mempersempit luas sampai sekitar 13,35 ha atau
16% pada tahun 1999 dari luas aslinya pada tahun 1975. Struktur vegetasi
juga ikut berubah. Data tutupan lahan terakhir yaitu pada tahun 2008
(Nurhara dkk 2008) menunjukkan luasan feeding ground Sadengan yang
ditumbuhi rumput yang bisa dimakan satwa hanya tinggal 14,791 Ha.
3.1.3. Pengelolaan Habitat Banteng
Pengelolaan habitat yang dilakukan yaitu di feeding ground
Sadengan antara lain:
a. Penataan areal kerja/Desain Blok Pengelolaan
Desain blok dibuat untuk mempermudah pengelolaan dan
pengawasannya. Berdasarkan pertimbangan fesibility faktor sadengan
dibagi menjadi 6 blok. Sebagian blok memanfaatkan sungai sebagai node
pembatas, sebagian lagi menggunakan titik pancang sementara.
b. Rencana rehabilitasi berdasarkan blok pengelolaan
Rehabilitasi feeding ground Sadengan diawali dengan interseksi
data antara blok, tutupan lahan dan kebutuhan suplai air. Upaya
Rehabilitasi padang rumput Sadengan yang telah dilakukan adalah :
Pembabatan enceng-enceng dan kirinyuh
Pendongkelan
Pembuatan Titik air yang berupa springkle
Restoking rumput
c. Pemberantasan Tumbuhan Pengganggu dan Pembabatan Semak Perdu
3.2. Pembinaan Penyu Semi Alami di Ngagelan
3.2.1. Jenis Penyu
Ada enam jenis (species) penyu laut yang hidup di perairan
Indonesia, empat jenis penyu diketahui hidup di perairan Alas purwo. Empat
jenis penyu tersebut adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu sisik
(Eretmochelys imbricata), penyu abu-abu (Lepidochelys olivacea) dan
penyu belimbing (Dermochelys coreacea).
3.2.2.Jumlah (BTNAP, 2010)
Kawasan Taman Nasional Alas Purwo khususnya di wilayah
pantainya masih menjadi tempat yang ideal bagi satwa penyu untuk
mendarat dan bertelur. Empat jenis penyu telah mendarat di Taman Nasional
Alas Purwo. Wilayah pantai yang menjadi tempat pendaratan penyu adalah:
Payaman, Ksatrian, Tanjung Pasir, Sumur Tong, Brobos, Plengkung, Pancur,
Marengan sampai pantai Cungur Grajagan.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kerangka acuan kerja dan
pengelolaan Ngagelan terhadap konservasi penyu yang ada di kawasan
Taman Nasional Alas Purwo dari masing-masing aspek yang dibuat di
dalam kerangka acuan kerja telah dilaksanakan dengan baik mulai dari
penjagaan hingga urusan rumah tangga. Akan tetapi dalam hasil perlakuan
telur secara semi alami tidak begitu memuaskan.
Gambar 4 Jumlah telur dari seluruh jenis penyu tahun 2005-2009
Berdasarkan hasil tersebut, presentase keberhasilan tiap jenis penyu
pada gambar 5.
Gambar 5 Presentase penetasan pada tahun 2005-2009
Untuk jumlah peneluran pada tahun 2010 digolongkan berdasarkan
jumlah telur per jenis dengan hasil rata-rata telur dan jumlah maksimum dan
minimum telur per bulan pada tahun 2010. Data jumlah telur yang
dihasilkan oleh masing-masing penyu dari tahun 2010 dapat dilihat pada
Gambar 6.
Gambar 6 Presentase keberhasilan tiap penyu tahun 2010
Sebagian besar, kegagalan penetasan yang terjadi lebih diakibatkan
oleh factor cuaca yang kurang mendukung. Menurut petugas, hampir
sepanjang tahun 2010 terjadi hujan, sehingga suhu pada sarang turun yang
mengakibatkan telur menjadi busuk dan gagal menetas. Selain itu, kegiatan
penetasan di Ngagelan masih terbatas pada pemindahan sarang ke dalam
lokasi penetasan semi alami. Sarang-sarang yang ada di lokasi penetasan
telur tidak dimonitoring secara rutin terkait kondisi fisik maupun biologi
sarang. Sehingga, kegagalan penetasan di lokasi sarang semi alami tidak
dapat diketahui secara pasti. Selain itu, penggunaan sarang yang berulangulang dapat menjadi indikasi lain dari kegagalan penetasan, karena sarang
bekas yang digunakan tidak dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui
kelayakannya, baik berupa kandungan mikroorganisme maupun kesesuaian
fisik lain seperti suhu dan kelembaban sarang.
VI. KESIMPULAN
Pengelolaan habitat yang dilakukan di Sadengan belum sepenuhnya
berjalan dengan baik, perlu pengelolaan yang berkesinambungan, artinya
pengelolaan bukan hanya bersifat keproyekan atau sementara
Kegiatan pelestarian penyu di Alas Purwo sudah berjalan cukup baik
dengan dipusatkan di pantai Ngagelan, yang ditandai dengan mempunyai
program utama yaitu pengumpulan telur penyu, penetasan telur penyu
disarang semi alami, pemeliharaan tukik dan pelepasan tukik ke laut
bebas. Tetapi, dalam hal hasil penetasan masih belum maksimal, karena
belum adanya kajian khusus terutama analisis fisik sarang semi alami.
DAFTAR PUSTAKA
Alikodra, H.S. 1983. Ekologi Banteng (Bos javanicus dAlton). Fakultas Pasca
Sarjana: Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Alikodra, H.S. 2002. Pengelolaan Satwaliar jilid 1. Bogor: Yayasan Penerbit
Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
[BTNAP] Balai Taman Nasional Alas Purwo. 2008 . Buku Informasi Balai Taman
Nasional Taman Nasional Alas Purwo . Banyuwangi.
[BTNAP] Balai Taman Nasional Alas Purwo. 2010 . Laporan Pelaksanaan Tugas
Operasional Resort Rowobendo SPTN Wilayah I Tegaldlimo .
Pasaranyar.
[BTNAP] Balai Taman Nasional Alas Purwo. 2010 . Laporan Pelaksanaan Tugas
Operasional Resort Grajagan SPTN Wilayah I Tegaldlimo . Pasaranyar.
Direktorat Bina Sumber Hayati. 1985. Masalah Pemanfaatan Penyu di Indonesia:
Sarasehan Pelestarian Penyu Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia.
Dewi L.K, Septiyani M, Handini M.E, Satyasari I, Yanuarefa M.F, Riharno B,
Kurniawan I. 2009. Laporan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP)
Mahasiswa Program Sarjana Di Taman Nasional Alas Purwo (TNAP).
Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
Lubis, M.F., R.Rahmayulis., B. Darmawan., R. Risnawati., Imran., Ardiansyah.
2007. Laporan Praktek Kerja Lapang Profesi (PKLP) Mahasiswa
Program Sarjana Taman Nasional Alas Purwo (TNAP). Departemen
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata. Fakultas Kehutanan IPB.
Bogor.
Murdyatmaka W, Purwanto, Hariyanto G, Misijo, Dwiyono J. 2009. Laporan
Final Monitoring Habitat dan Home Range Banteng (Bos Javanicus
Dalton) di Luar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Balai Taman
Nasional Alas Purwo. Tidak dipublikasikan.
Nurhara, B., Margo dan Murdyatmoko Wahyu. 2008. Laporan Kegiatan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Feeding Ground Sadengan. Taman
Nasional Alas Purwo. Banyuwangi.
Soekmadi, R. 2003. Pergeseran Paradigma Pengelolaan Kawasan Konservasi:
Sebuah Wacana Baru Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. Media
konservasi. Vol VIII. No.3; 87-93.
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)