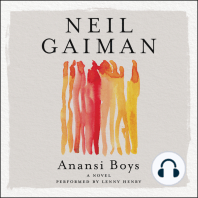Sandera Yoshimoto
Diunggah oleh
febriansasi0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
31 tayangan45 halamanJudul Asli
09
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
31 tayangan45 halamanSandera Yoshimoto
Diunggah oleh
febriansasiHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 45
Sandera Yoshimoto
RAKYAT di Provinsi Suruga tidak menyebut ibu kota
mereka dengan nama Sumpu. Bagi mereka, kota itu
adalah Tempat Pemerintah, dan bentengnya dikenal
sebagai Istana. Para warga, mulai dari Yoshimoto dan
para anggota marga Imagawa sampai ke penduduk
kota, yakin bahwa Sumpu merupakan ibu kota
provinsi terbesar di pantai timur. Kotanya diliputi
suasana aristokrat, dan orang-orang biasa pun meniru
gaya kota kekaisaran Kyoto.
Dibandingkan Kiyosu, Sumpu merupakan dunia
lain. Suasana di jalan-jalannya dan tindak-tanduk para
warga, bahkan kecepatan melangkah orang-orang, dan
cara mereka berpandangan dan berbicara. Para warga
Sumpu tampak santai dan penuh percaya diri. Pangkat
mereka tercermin dari kemewahan pakaian yang
mereka kenakan, dan jika keluar rumah, mereka
menutupi mulut dengan kipas. Seni musik, tari. dan
sastra tumbuh subur. Ketenteraman yang terlihat pada
semua wajah berasal dari suatu mata air ketenangan di
masa lampau. Sumpu diberkahi. Jika cuaca sedang
baik, orang bisa melihat Gunung Fuji; jika berkabut,
alunan ombak terlihat di pohon-pohon cemara di Kuil
Kiyomidera. Pasukan Imagawa amat dan Mikawa.
wilayah kekuasaan marga Tokugawa hanya merupakan
provinsi bawahan.
Dalam tubuhku mengalir darah Tokugawa, tapi aku
berada di sini. mnagikut-pcngikutku di Okazaki terus
mempertahankan bentengku. Provinsi pun tetap ada,
namun sang Penguasa terpisah dari para pengikutnya...
Siang-malam Tokugawa Ieyasu memikirkan hal-hal ini,
tapi ia takkan membicarakannya secara terbuka, ia
merasa iba kepada para pengikutnya. Tapi, ketika
merenungkan keadaannya sendiri, ia bersyukur bahwa
ia masih hidup.
Ieyasu baru berusia tujuh belas, tapi ia telah men-
jadi ayah. Dua tahun setelah upacara akil balignya,
Imagawa Yoshimoto mengatur pernikahan Ieyasu
dengan putrì seorang saudaranya. Putra Ieyasu lahir di
musim semi berikutnya, jadi umurnya belum men-
capai enam bulan. Ieyasu sering mendengar tangis
bayinya dari ruang tempat mejanya berada. Istrinya
belum pulih dari persalinan dan masih dirawat di
ruang bersalin.
Kalau ayah berusia tujuh belas tahun ini mendengar
bayinya menangis, ia mendengar suara darah daging-
nya sendiri. Tapi ia jarang menjenguk keluarganya, ia
tidak memahami perasaan kasih sayang terhadap anak-
anak yang sering dibicarakan orang lain. Ia mencoba
mencari perasaan ini di hatinya, dan mendapati
perasaan itu bukan hanya cuma sedikit, melainkan
benar-benar sangat tipis. Sadar akan kekurangannya
sebagai suami dan ayah, ia merasa kasihan pada istri
dan anaknya. Namun, setiap kali ia merasa demikian,
rasa ibanya tidak ditujukan pada keluarganya sendiri,
melainkan kepada para pengikutnya yang jatuh miskin
dan terhina di Okazaki.
Setiap kali memaksakan diri untuk memikirkan
putranya, ia jadi sedih. Tak lama lagi dia akan
menempuh perjalanan melewati hidup yang getir, dan
akan mengalami kemelaratan yang sama seperti aku.
Pada usia lima tahun, Ieyasu dikirim sebagai
sandera kepada marga Oda. Ketika mengenang
kesengsaraan yang telah dilaluinya, mau tak mau ia
menaruh belas kasihan pada bayinya yang baru lahir.
Kesedihan dan tragedi kehidupan manusia pasti akan
dialami juga oleh anaknya. Namun sekarang ini, dari
luar, orang-orang hanya melihat bahwa ia dan
keluarganya mendiami rumah yang tak kalah mewah
dari rumah orang-orang lmagawa.
Apa itu? Ieyasu keluar ke teras. Seseorang di luar
telah menarik tanaman rambat yang tumbuh di
pohon-pohon di pekarangan, dan memanjat ke atas
tembok.
"Siapa itu?" Ieyasu berseru. Kalau orang itu berniat
buruk, ia tentu akan kabur. Namun tidak terdengar
suara langkah. Ieyasu mengenakan sandal dan me-
lewati gerbang belakang. Seorang laki-laki sedang
menyembah, seakan-akan telah menanti kedatangan-
nya. Sebuah keranjang anyaman berikut tongkat ter-
geletak di sampingnya.
"Jinshichi?"
"Sudah lama sekali, tuanku."
Empat tahun sebelumnya, ketika ia akhirnya men-
dapat izin dari Yoshimoto. Ieyasu pernah kembali ke
Okazaki untuk berziarah ke makam para leluhurnya.
Dalam perjalanan itu salah seorang pengikut, Udono
Jinshichi, menghilang. Ieyasu terharu ketika melihat
keranjang dan tongkat serta sosok Jinshichi yang telah
berubah.
"Kau menjadi biksu pengembara."
"Ya, ini penyamaran yang baik untuk berkeliling
negeri."
"Kapan kau tiba di sini?"
"Baru saja. Hamba ingin menemui tuanku sebelum
berangkat lagi."
"Empat tahun telah berlalu. Aku menerima laporan-
laporanmu, tapi karena tidak mendapat kabar darimu
setelah kau berangkat ke Mino, aku menyangka yang
terburuk telah terjadi."
"Hamba terperangkap dalam perang saudara di
Mino, dan selama beberapa waktu, pengamanan di
pos-pos perbatasan sangat ketat."
"Kau mengunjungi Mino? Waktunya tepat sekali."
"Hamba tinggal di Inabayama selama satu tahun.
Seperti tuanku ketahui, benteng Saito Dosan di-
hancurkan, dan kini Yoshitatsu yang menjadi
penguasa Mino. Setelah keadaan mulai tenang, hamba
pindah ke Kyoto dan Echizen, melewati provinsi-
provinsi utara dan melanjutkan perjalanan ke Owari."
"Kau pergi ke Kiyosu?"
"Ya, hamba berada di sana selama beberapa saat."
"Berceritalah. Walaupun aku berada di Sumpu, aku
bisa menduga apa pmg akan terjadi di Mino, tapi
situasi marga Oda tidak semudah itu memperkirakan."
"Apakah hamba perlu menulis laporan dan
menyerahkannya nanti malam?"
"Jangan, jangan secara tertulis." Ieyasu berpaling ke
gerbang belakang, tapi rupanya ia masih memikirkan
sesuatu.
Jinshichi merupakan mata dan telinga yang meng-
hubungkannya dengan luar. Sejak berusia lima tahun,
Ieyasu tinggal bersama marga Oda, dengan orang-
orang Imagawa, berpindah-pindah dalam pengasingan
di provinsi musuh. Sebagai sandera, ia tak pernah
mengenal kebebasan, sampai sekarang pun keadaan-
nya belum berubah. Mata, telinga, dan jiwa seorang
sandera tertutup, dan jika ia tidak berusaha sendiri,
tak ada yang menegur maupun memberi semangat
padanya. Walaupun demikian, justru karena ter-
kungkung sejak masa kanak-kanak, Ieyasu menjadi
ambisius.
Empat tahun yang lalu, ia mengutus Jinshichi ke
provinsi-provinsi lain agar ia dapat mengetahui apa
saja yang terjadi di dunia—suatu tanda awal ambisi
Ieyasu yang semakin berkembang. "Kita akan terlihat
di sini, dan kalau kita masuk ke rumah, para
pengikutku akan curiga. Kita ke sana saja." Dengan
langkah panjang Ieyasu berjalan menjauhi rumahnya.
Tempat kediaman Ieyasu berada di salah satu daerah
paling sepi di Sumpu. Jika berjalan menjauhi tembok
luar, dalam waktu singkat orang sudah sampai ke tepi
Sungai Abe. Waktu Ieyasu masih kanak-kanak yang
terus digendong oleh para pengikutnya, ia selalu
dibawa ke Sungai Abe kalau ia mengatakan ingin
bermain di luar. Aliran sungai itu tak pernah berhenti,
dan tepiannya seakan-akan tak pernah berubah.
Pemandangan ini membawa banyak kenangan bagi
Ieyasu.
"Jinshichi, lepaskan tali perahu," ujar Ieyasu sambil
melangkah ke sebuah perahu kecil. Pada waktu
Jinshichi menyusulnya dan mendorong galah, perahu
itu mengambang menjauhi tepi sungai, seperti daun
bambu terbawa arus. Junjungan dan pengikut ber-
bicara dengan bebas, sadar bahwa untuk pertama kali
mereka terlindung dari pandangan orang. Dalam
tempo satu jam, Ieyasu menyerap seluruh informasi
yang dikumpulkan Jinshichi dalam pengembaraannya
selama empat tahun. Namun, selain apa yang
dipelajari Jinshichi, masih ada sesuatu yang samar-
samar tersembunyi dalam hati Ieyasu.
"Kalau orang-orang Oda jarang menyerang provinsi
lain dalam beberapa tahun terakhir—berbeda dengan
di masa kekuasaan Nobuhide—itu berarti mereka
sedang berbenah diri," ujar Ieyasu.
"Tak peduli apakah orang-orang yang menentangnya
merupakan kerabat atau pengikut. Nobunaga men-
curahkan perhatiannya secara penuh pada tugas itu.
Dia menjatuhkan mereka yang harus dijatuhkan, dan
mengusir mereka yang harus diusir. Dia hampir
berhasil membersihkan Kiyosu dari orang-orang itu."
"Nobunaga sempat menjadi bahan tertawaan orang-
orang Imagawa. dan menurut kabar burung dia hanya
anak manja yang bodoh."
"Dia sama sekali bukan orang pandir seperti yang
dikabarkan orang," kata Jinshichi.
"Sudah lama aku menduga bahwa cerita itu hanya
desas-desus jahat. Tapi kalau Yoshimoto membicara-
kan Nobunaga, dia mempercayai segala omong kosong
itu, dan dia tidak menanggapinya sebagai ancaman."
"Semangat tempur orang-orang Owari berbeda sama
sekali dibandingkan dengan beberapa tahun yang
lalu."
"Siapa saja pengikut andalannya?" tanya Ieyasu.
"Hirate Nakatsukasa sudah mati, tapi dia masih
mempunyai sejumlah orang seperti Shibata Katsuie,
Hayashi Sado, Ikeda Shonyu, Sakuma Daigaku, dan
Mori Yoshinari. Baru-baru ini seorang laki-laki luar
biasa bernama Kinoshita Tokichiro bergabung dengan-
nya. Orang itu berpangkat rendah, namun entah
kenapa namanya sering menjadi buah bibir para
penduduk kota."
"Bagaimana pandangan orang-orang mengenai
Nobunaga?"
"Inilah yang paling mengherankan. Pada umumnya
seorang penguasa provinsi mencurahkan perhatiannya
untuk memerintah rakyatnya. Dan rakyat selalu
tunduk pada junjungannya. Tapi di Owari keadaannya
berbeda."
"Dari segi apa?"
Jinshichi berpikir sejenak. "Entah bagaimana cara
mengatakannya? Dia tidak melakukan hal-hal yang
luar biasa, tapi selama ada Nobunaga, rakyat Owari
merasa tenang menghadapi masa depan—dan walau-
pun mereka sadar bahwa Owari sebuah provinsi kecil
dan miskin dengan penguasa tak berharta, inilah
anehnya, seperti penduduk sebuah provinsi kuat,
mereka tidak takut perang maupun cemas mengenai
masa depan mereka."
"Hmm. Kira-kira apa sebabnya?"
"Barangkali karena Nobunaga sendiri. Dia mem-
beritahu mereka apa saja yang terjadi hari ini dan apa
yang akan terjadi besok, dan dia menentukan tujuan
yang hendak mereka capai bersama-sama."
Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, tanpa
bermaksud berbuat demikian, Jinshichi membanding-
kan Nobunaga yang berusia dua puluh lima tahun
dengan Ieyasu yang delapan tahun lebih muda. Dalam
beberapa hal, Ieyasu jauh lebih matang daripada
Nobunaga—tak ada sifat kekanak-kanakan tersisa
dalam dirinya. Keduanya menjadi dewasa dalam
keadaan sulit, tapi sesungguhnya mereka tak dapat
dibandingkan. Pada umur lima tahun Ieyasu telah
diserahkan kepada musuh, dan kekejaman dunia telah
menyebabkan hatinya menjadi dingin.
Perahu kecil itu membawa Jinshichi dan Ieyasu ke
tengah sungai, dan waktu terus berjalan selama pem-
bicaraan rahasia mereka. Setelah selesai, Jinshichi
membawa mereka kembali ke tepi.
Jinshichi cepat-cepat memikul keranjang dan
meraih tongkatnya, ia mohon diri dan berkata.
"Hamba akan menyampaikan pesan tuanku kepada
para pengikut. Masih ada lagi, tuanku?"
Ieyasu berdiri di tepi sungai, langsung cemas kalau-
kalau mereka akan terlihat. "Tak ada. Pergilah cepat."
Sambil menganggukkan kepala untuk menyuruh
Jinshichi berangkai, ia tiba-tiba berkata, "Beritahu
mereka bahwa aku sehat-sehat saja—tak sekali pun aku
jatuh sakit." Kemudian ia berjalan ke rumahnya
seorang diri.
Para pelayan istrinya telah mencarinya ke mana-
mana, dan ketika mereka melihatnya kembali dari
sungai, salah seorang berkata. "Tuan Putri sedang
menunggu, berkali-kali kami disuruh mencari tuanku.
Tuan Putri sangat mencemaskan tuanku."
"Ah, begitukah?" ujar Ieyasu. "Tenangkan dia dan
katakan padanya bahwa aku segera datang." Setelah itu
ia pergi ke kamarnya sendiri. Ketika duduk, ia
menemukan pengikut lain, Sakakibara Heishichi,
telah menantinya.
"Tuanku habis berjalan-jalan ke tepi sungai?"
"Ya... untuk mengisi waktu. Ada apa?"
"Seorang kurir datang."
"Dari mana?"
Tanpa menjawab, Heishichi menyodorkan sepucuk
surat yang dikirim oleh Sessai. Sebelum membuka
sampulnya, dengan penuh hormat Ieyasu menempel-
kannya ke kening. Sessai adalah biksu aliran Zen yang
bertindak sebagai instruktur militer untuk marga
Imagawa. Bagi Ieyasu, ia merupakan guru, baik dalam
hal mempelajari kitab-kitab maupun ilmu bela diri.
Suratnya ringkas:
Ceramah rutin untuk Yang Mulia dan tamu-tamunya
akan diberikan malam ini. Tuan akan ditunggu di
gierbang Barat Laut Istana.
Hanya itu. Tetapi kata "rutin" merupakan kata sandi
yang sangat dikenal Ieyasu. Kata itu menunjuk-kan
bahwa Yoshimoto dan para jendralnya bertemu untuk
membahas rencana menuju ibu kota.
"Mana kurirnya?"
"Ia sudah pergi. Apakah tuanku akan pergi ke
Istana?"
"Ya." jawab Ieyasu, sibuk dengan pikirannya sendiri.
"Hamba menduga tak lama lagi rencana menuju ibu
kota akan diumumkan." Beberapa kali Heishichi
sempat mendengarkan rapat penting dewan perang
yang membahas masalah itu. Ia mengamati wajah
Ieyasu. Ieyasu menggumamkan sesuatu, seakan-akan
tidak tertarik.
Penilaian orang-orang Imagawa perihal kekuatan
Owari dan mengenai Nobunaga sangat berbeda dari
apa yang baru saja dilaporkan Jinshichi. Yoshimoto
merencanakan memimpin pasukan besar, yang me-
rupakan gabungan kekuatan Provinsi Suruga, Totomi.
dan Mikawa ke ibu kota, dan mereka menduga akan
mendapat perlawanan di Owari.
"Kalau kita maju dengan pasukan besar, Nobunaga
akan menyerah tanpa penumpahan darah."
Pandangan dangkal ini dikemukakan oleh beberapa
anggota dewan perang, namun meski Yoshimoto dan
para penasihatnya, termasuk Sessai tidak menganggap
Nobunaga demikian rendah, tak seorang pun dari
mereka memandang Owari seserius Ieyasu. Ia pernah
mengutarakan pendapatnya, tapi disambut dengan
tawa mengejek. Bagaimanapun, Ieyasu hanyalah
seorang sandera yang masih muda, dan oleh para
panglima ia tidak dipandang sebelah mata.
Perlukah aku menyinggung hal ini nanti? Biarpun
masalah ini kutekankan...
Ieyasu sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri,
dengan surat dari Sessai di hadapannya, ketika seorang
dayang tua menyapanya dengan pandangan cemas.
Istrinya sedang gundah, kata perempuan tua itu, dan
Ieyasu diminta menjenguknya sejenak saja.
Istri Ieyasu perempuan yang hanya memikirkan diri
sendiri. Ia sama sekali tak peduli pada masalah negara
dan situasi suaminya. Tak ada yang mengusik pikiran-
nya selain urusan sehari-hari serta perhatian suaminya.
Dayang tua tadi memahami ini, dan ketika ia melihat
Ieyasu masih berbicara dengan seorang pengikutnya, ia
menunggu dengan gelisah sambil membisu, sampai
pelayan perempuan lain menyusul dan berbisik ke
telinganya. Si dayang tak punya pilihan. Sekali lagi ia
memotong pembicaraan dan berkata, "Ampun,
tuanku... Maafkan hamba atas kelancangan ini, tapi
Tuan Putri sangat rewel." Sambil membungkuk ke
arah Ieyasu, ia mendesaknya dengan takut-takut agar
segera menemui istrinya.
Ieyasu sadar bahwa tak ada yang lebih disulitkan
oleh situasi ini daripada para pelayan istrinya,
sedangkan ia sendiri laki-laki sabar. "Ah, baiklah." kata-
nya sambil menoleh. Lalu ia berkata pada Heishichi,
"Hmm... lakukan persiapan yang diperlukan, dan
beritahu aku kalau sudah waktunya." Ia berdiri. Kedua
perempuan di hadapannya berlari dengan langkah
kecil-kecil, ekspresi wajah mereka seperti orang yang
baru saja terselamatkan dari bencana.
Bagian dalam rumahnya berjarak cukup jauh, jadi
bukan tanpa alasan jika istrinya sering rindu untuk
bertemu dengannya. Setelah melewati banyak belokan
di selasar tengah yang beratap, akhirnya ia sampai di
ruang pribadi istrinya.
Pada hari pernikahan mereka, pakaian si pengantin
pria miskin dari Mikawa tak dapat mengimbangi
kemewahan dan kegemerlapan baju Putri Tsukiyama.
putri angkat Imagawa Yoshimoto. "Laki-laki dari
Mikawa"—menyandang sebutan itu, Ieyasu menjadi
sasaran celaan marga Imagawa. Dan dari tempat
tinggalnya yang terpisah, istri Ieyasu memandang hina
para pengikut dari Mikawa, tapi membanjiri suaminya
dengan curahan cinta yang buta dan berpangkal pada
diri sendiri, ia juga lebih tua daripada Ieyasu. Dalam
batas-batas kehidupan suami-istri yang hambar, Putri
Tsukiyama menganggap Ieyasu tak lebih dari seorang
pemuda penurut yang berutang nyawa pada orang-
orang Imagawa.
Setelah melahirkan di musim semi sesudah per-
nikahan mereka, ia semakin mementingkan diri
sendiri. Setiap hari ia memperlihatkan kekerasan hati-
nya.
"Oh, kau sudah bangun. Keadaanmu sudah lebih
baik?" Ieyasu menatap istrinya, dan sambil bicara,
hendak membuka pintu geser. Pikirnya, jika istrinya
melihat keindahan warna-warni dan langit musim
gugur, suasana batinnya akan lebih cerah.
Putri Tsukiyama duduk di ruang tamu dengan
ekspresi dingin pada wajahnya yang pucat kelabu, ia
mengerutkan alis sambil berkata, "Biarkan tertutup!"
Ia tidak seberapa cantik, tapi, seperti umumnya para
perempuan yang dibesarkan di lingkungan keluarga
kaya, kulitnya berkilau lembut. Disamping itu, baik
wajahnya maupun ujung-ujung jarinya begitu putih,
hingga hampir tembus cahaya, mungkin karena ia
baru pertama kali melahirkan. Kedua tangannya ter-
lipat rapi di pangkuan.
"Silakan duduk, tuanku. Ada sesuatu yang ingin
kutanyakan." Mata dan nada suaranya sedingin abu.
Tapi sikap Ieyasu sama sekali bukan seperti yang
diharapkan dari seorang suami muda—perlakuan
lemah lembut terhadap ini lebih panras bagi laki-laki
yang telah matang. Atau mungkin ia mempunyai
pandangan tertentu mengenai perempuan, sehingga
orang yang seharusnya paling disayangi justru dinilai-
nya secara objektif.
"Ada apa?" ia bertanya sambil duduk di hadapan
istrinya, seperti yang diminta. Namun, semakin patuh
Ieyasu, semakin tak masuk akal sikap yang diperlihat-
kan istrinya.
"Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah
tuanku pergi ke luar beberapa saat yang lalu? Seorang
diri, tanpa pelayan?" Matanya mulai berkaca-kaca.
Darah mulai naik ke wajahnya yang masih kurus
akibat persalinan. Ieyasu mengetahui keadaan
kesehatannya maupun wataknya, dan ia tersenyum,
seolah-olah hendak menghibur bayi.
"Beberapa saat yang lalu? Aku bosan membaca, jadi
aku berjalan-jalan menyusuri tepi sungai. Kapan-kapan
kau juga harus ke sana. Warna-warni musim gugur
diiringi bunyi serangga—suasana di tepi sungai sangat
menyenangkan pada musim ini."
Putri Tsukiyama tidak mendengarkan. Ia menatap
lurus ke arah suaminya, menegurnya tanpa kata,
karena lelah berbohong. Ia duduk tegak dengan sikap
tak peduli, tapi tanpa sikap sibuk sendiri seperti
biasanya. "Aneh. Kalau kau pergi untuk mendengar-
kan suara serangga dan mengagumi warna-warni
musim gugur, mengapa kau harus naik perahu ke
tengah sungai dan bersembunyi begitu lama?"
"Aha... ternyata kau mengetahuinya."
"Mungkin aku memang terkungkung di sini, tapi
aku tahu segala sesuatu yang kaulakukan."
"Begitukah?" Ieyasu memaksakan senyum, tapi tidak
menyinggung pertemuannya dengan Jinshichi.
Walaupun perempuan ini telah menikah dengan-
nya, Ieyasu tak sanggup meyakinkan diri bahwa ia
betul-betul istrinya. Jika pengikut atau kerabat ayah
angkatnya berkunjung, Putri Tsukiyama akan men-
ceritakan segala sesuatu yang diketahuinya, dan ia pun
terlibat surat-menyurat dengan rumah tangga
Yoshimoto. Ieyasu harus lebih berhati-hati terhadap
kecerobohan istrinya daripada terhadap mata-mata
Yoshimoto.
"Sebenarnya aku menaiki perahu di tepi sungai
tanpa pikir panjang. Kusangka aku sanggup
mengemudikan perahu, tapi waktu perahunya terbawa
arus, aku tak dapat berbuat apa-apa." Ia tertawa. "Persis
seperti anak kecil. Di mana kau waktu melihatku?"
"Kau bohong. Kau tidak sendirian, bukan?"
"Hmm, beberapa saat kemudian seorang pelayan
menyusulku."
"Tidak, tidak. Tak ada alasan untuk mengadakan
pertemuan rahasia di dalam perahu dengan seseorang
yang kelihatan seperti pelayan."
"Siapa yang menyampaikan omong kosong ini pada-
mu?"
"Walaupun aku terkurung di sini, masih ada orang
setia yang memikirkanku. Kau punya gundik, bukan?
Atau kalau bukan itu, barangkah kau sudah bosan
denganku, dan berencana melarikan diri ke Mikawa.
Menurut desas-desus yang beredar, kau telah mem-
peristri perempuan lain di Okazaki. Kenapa kau
menyembunyikannya dariku? Aku tahu kau menikahi-
ku hanya karena takut terhadap marga Imagawa."
Tepat pada waktu tangisnya meledak, Sakakibara
Heishichi muncul di ambang pintu. "Tuanku, kuda
tuanku sudah siap. Sudah hampir waktunya.
"Kau mau pergi?" Sebelum Ieyasu sempat menjawab.
Putri Tsukiyama mendahuluinya. "Belakangan ini kau
semakin sering keluar pada malam hari, jadi ke mana
lagi kau hendak pergi sekarang?"
"Ke Istana." Tanpa mengacuhkan istrinya, Ieyasu
mulai berdiri.
Tapi Putri Tsukiyama tidak puas dengan jawaban
singkatnya. Kenapa suaminya harus ke Istana malam-
malam begini? Dan apakah ia akan pergi sampai
tengah malam, seperti biasanya? Siapa yang akan
menyertainya? Ia mengajukan pertanyaan demi per-
tanyaan.
Sakakibara Heishichi menunggu majikannya di luar
pintu, dan walaupun ia hanya seorang pengikut, ia
mulai tak sabar. Ieyasu, sebaliknya, menenangkan
istrinya dengan riang, dan akhirnya berangkat. Putri
Tsukiyama mengabaikan peringatan Ieyasu bahwa ia
akan sakit lagi, dan mengantar suaminya sampai ke
pintu.
"Pulanglah secepatnya," ia memohon, seluruh cinta
dan kesetiaannya tercurah dalam kata-kata itu.
Sambil membisu, Ieyasu berjalan ke gerbang utama.
Namun, ketika ia berangkat, disaksikan bintang-
bintang di langit dan diterpa angin sejuk, ia
mengusap-usap bulu tengkuk kudanya dan suasana
hatinya berubah sama sekali—suatu bukti bahwa darah
muda mengalir dalam tubuhnya. "Heishichi. Seperti-
nya kita akan terlambat, bukan?" Ieyasu serunya.
"Tidak. Dalam surat itu tidak tercantum jam ter-
tentu, jadi bagaimana kira bisa terlambat?"
"Bukan itu masalahnya. Meski Sessai sudah tua, dia
tak pernah terlambat. Aku akan merasa pedih jika
aku, sebagai anak muda dan seorang sandera,
terlambat muncul pada suatu pertemuan sementara
para pengikut senior dan Sessai sudah hadir. Cepat-
lah," ia berkata, dan memacu kudanya.
Selain seorang tukang kuda dan tiga pelayan.
Heishichi-lah satu-satunya pengikut yang menyertai
Ieyasu. Ketika Heishichi berupaya mengimbangi kuda
majikannya, ia menitikkan air mata bagi Ieyasu yang
sudah memperlihatkan kesabaran pada istrinya dan
kepatuhan pada Istana—artinya, pada Imagawa
Yoshimoto—padahal sikap itu tentu sangat menyakit-
kan baginya.
Sebagai pengikut, ia telah bersumpah untuk
melepaskan junjungannya dari segala belenggu, ia
harus membebaskan Ieyasu dari posisinya sebagai
bawahan dan mengembalikannya ke kedudukan
sebagai penguasa Mikawa. Dan bagi Heishichi, setiap
hari yang berlalu tanpa mencapai tujuan merupakan
satu hari penuh ketidaksetiaan.
Ia terus berlari, menggigit-gigit bibir sambil berikrar,
dengan mata berkaca-kaca.
Selokan pertahanan mulai terlihat. Setelah mereka
menyeberangi jembatan, k ada lagi toko-toko dan
rumah rakyat jelata. Diapit oleh pohon-pohon
dinding-dinding putih dan gerbang-gerbang megah
kediaman atau kerja orang-orang Imagawa tampak
berderet-deret. "Bukankah itu si Penguasa Mikawa?
Tuanku Ieyasu!" Sessai berseru dari bayang-bayang
pepohonan.
Hutan pinus yang mengelilingi benteng merupakan
lapangan militer di saat perang, tapi di masa damai
jalan-jalan setapaknya yang panjang dan lebar diguna-
kan sebagai tempat berkuda.
Ieyasu segera turun dari kuda, dan membungkuk
penuh hormat ke arah Sessai.
"Terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan
kami, Yang Mulia."
"Pesan-pesan ini selalu datang secara mendadak.
Tuan tentu direpotkan sekali."
"Sama sekali tidak." Sessai seorang diri. Kakinya
terbungkus sandal tua berukuran sebanding dengan
tubuhnya, Ieyasu mulai berjalan bersamanya, dan
sebagai penghormatan pada gurunya, satu langkah di
belakangnya, menyerahkan tali kekang pada
Heishichi.
Ketika mendengarkan gurunya, Ieyasu tiba-tiba
dilanda rasa terima kasih yang tak dapai diungkapkan
dengan kata-kata. Takkan ada yang menyangkal bahwa
penahanan sebagai sandera oleh provinsi lain
merupakan nasib buruk, tapi ketika merenungkannya,
Ieyasu menyadari bahwa kesempatan untuk belajar
dari Sessai justru merupakan suatu keberuntungan.
Sukar sekali menemukan guru yang baik.
Seandainya ia tetap di Mikawa, ia takkan pernah
mendapat kesempatan berguru pada Sessai. Jadi. ia
takkan pernah menerima pendidikan klasik dan
militer yang dimilikinya sekarang—ataupun latihan
Zen yang dianggapnya pelajaran paling berharga yang
ia peroleh dari Sessai.
Mengapa Sessai, seorang biksu aliran Zen, mengabdi
pada penguasa marga Imagawa dan bersedia menjadi
penasihat militernya, menjadi tanda tanya bagi
provinsi-provinsi lain, dan mereka menganggapnya
agak ganjil. Karena itu ada orang yang menjuluki
Sessai "biksu militer" atau "biksu duniawi", namun
seandainya garis keturunannya diteliti, mereka akan
menemukan bahwa ia masih tergolong kerabat
Yoshimoto. Meski demikian, Yoshimoto hanya
menguasai Suruga. Totomi, dan Mikawa, sedangkan
kemasyhuran Sessai tidak mengenal batas; ia milik
seluruh jagat raya.
Tetapi Sessai telah menggunakan bakatnya untuk
kepentingan orang-orang Imagawa. Begitu melihat
tanda-tanda bahwa orang-orang Imagawa akan kalah
perang melawan marga Hojo, biksu itu membantu
Suruga merundingkan perjanjian damai yang tidak
merugikan Yoshimoto. Dan ketika ia mengatur
pernikahan Hojo Ujimasa dengan salah seorang putri
Takeda Shingen, sang penguasa Kai, provinsi kuat di
perbatasan utara, serta pernikahan putri Yoshimoto
dengan putra Shingen, ia memperlihatkan kemampu-
an politik tinggi dengan mengikat ketiga provinsi itu
sebagai sekutu.
Ia bukan biksu yang menyendiri berbekal tongkat
dan topi lusuh, ia bukan biksu Zen "murni". Bisa
dikatakan bahwa ia biksu politik, biksu militer, atau
bahkan biksu bukan biksu. Apa pun julukan yang
diberikan padanya, keharuman namanya tak terusik.
Sessai selalu berbicara seperlunya, tapi satu hal yang
dikatakannya pada Ieyasu di pelataran Kuil Rinzai
terus melekat di kepala Ieyasu. "Bersembunyi di gua.
mengembara seorang diri seperti awan dan air
mengalir—bukan itu saja yang membentuk seorang
biksu besar. Tujuan seorang biksu selalu berubah-
ubah. Di dunia sekarang, hanya memikirkan pen-
cerahanku sendiri dan menjalani kehidupan seperti
orang yang 'mencuri ketenteraman gunung dan
padang', dan bersikap seakan-akan aku membenci
dunia, merupakan penerapan ajaran Zen yang terlalu
terfokus pada diri sendiri."
Mereka menyeberangi Jembatan Cina dan melewati
Gerbang Barat Laut. Sukar dipercaya bahwa mereka
berada di balik tembok sebuah benteng. Rasanya
seperti istana sang Shogun dipindahkan ke sini. Ke
arah Atago dan Kiyomizu, puncak Gunung Fuji yang
agung tampak samar di keremangan senja. Lampu-
lampu di relung-relung selasar yang membentang
sejauh mata memandang telah dinyalakan.
Perempuan-perempuan yang cantik bagaikan putri
istana berlalu, membawa kolo atau botol-botol sake.
"Siapa itu di pekarangan?" Imagawa Yoshimoto
menutupi wajahnya yang agak memerah dengan kipas
berbentuk daun ginkgo. Ia baru saja melewati jembatan
bulan sabit. Pelayan-pelayan yang meng-ikutinya pun
mengenakan pakaian mewah dan menyandang
pedang.
Salah seorang pelayan kembali menyusuri selasar
dan bergegas ke pelarangan. Seseorang menjerit. Bagi
telinga Yoshimoto, kedengarannya seperti suara
wanita, jadi karena menganggapnya ganjil, ia berhenti.
"Ke mana pelayan tadi?" Yoshimoto bertanya setelah
beberapa menit. "Dia belum kembali. Iyo, coba
kaulihat."
Iyo melangkah ke pekarangan. Walaupun disebut
pekarangan, kawasan mi demikian luas hingga seakan-
akan membentang sampai ke kaki Gunung Fuji.
Bersandar pada sebuah pilar, Yoshimoto mengetuk-
ngetuk kipasnya dan bersenandung seorang diri.
Ia cukup pucat untuk disangka wanita, karena
menggunakan dandanan muka berwarna terang.
Usianya empat puluh tahun, dan ia sedang di puncak
kejayaannya sebagai laki-laki. Yoshimoto menikmati
dunia dan kemakmurannya. Rambutnya ditata dengan
gaya bangsawan, giginya dihitamkan, dan di bawah
hidungnya membentang kumis. Dalam dua tahun
terakhir, berat badannya bertambah, dan karena
dilahirkan dengan badan panjang dan kaki pendek, ia
kini tampak sedikit cacat. Tapi pedangnya rang ber-
lapis emas dan pakaiannya yang mewah
menyelubunginya dengan pancaran penuh martabat.
Akhirnya seseorang kembali, dan Yoshimoto berhenti
bersenandung.
"Kaukah itu, lyo?"
"Bukan, ini Ananda, Ujizane."
Ujizane adalah putra dan pewaris Yoshimoto. dan
penampilannya menunjukkan bahwa ia tak pernah
mengenal susah.
"Mengapa kau berada di pekarangan menjelang
senja?"
"Ananda sedang memukul Chizu, dan waktu
Ananda mencabut pedang, dia langsung kabur."
"Chizu? Siapa Chizu?"
"Dia gadis yang mengurus burung-burung Ananda."
"Seorang pelayan?"
"Ya."
"Apa yang dilakukannya hingga kau terpaksa
menghukumnya dengan tanganmu sendiri?"
"Dia menjengkelkan. Dia bertugas memberi makan
seekor burung langka yang dikirimkan pada Ananda
dari Kyoto, dan dia membiarkannya lepas." Ujizane
berkata dengan sungguh-sungguh. Ia sangat
menyayangi burung hias. Sudah menjadi rahasia
umum di kalangan bangsawan bahwa jika seseorang
menemukan seekor burung langka dan mengirim-
kannya pada Ujizane. Ujizane akan bahagia sekali.
Jadi, tanpa perlu mengangkat jari, ia telah menjadi
pemilik koleksi burung dan kandang yang luar biasa.
Menurut kabar angin, ia lebih mementingkan burung
daripada nyawa manusia. Ujizane begitu murka,
seakan-akan urusannya merupakan masalah negara
yang sangat penting.
Sebagai ayah yang sabar, Yoshimoto hanya meng-
gerutu kecewa ketika menghadapi amarah konyol yang
diperlihatkan putranya. Meski Ujizane pewarisnya,
setelah menunjukkan ketololan seperti ini, para
pengikut takkan memandangnya sebelah mata.
"Bodoh!" seru Yoshimoto, berniat mengungkapkan
kasih sayangnya yang mendalam. "Ujizane. berapa
usiamu? Upacara akil baligmu sudah lama berlalu.
Kau pewaris marga Imagawa. tapi kau tidak berbuat
apa-apa selain menghibur diri dengan memelihara
burung. Kenapa kau tidak melakukan meditasi Zen,
atau mempelajari perjanjian-perjanjian militer?"
Dibentak begitu oleh seorang ayah yang hampir tak
pernah memarahinya. Ujizane menjadi pucat dan
terdiam. Pada dasarnya, ia menganggap ayahnya
mudah ditangani, namun pada usianya sekarang ia
juga sudah dapat mengamati tindak-tanduk ayahnya
secara kritis. Kini, daripada berdebat, ia memilih
merengut dan mendongkol. Ini pun dipandang
sebagai kelemahan oleh Yoshimoto. Ia sangat
menyayangi putranya yang tolol, dan ia sadar bahwa ia
tak pernah memberi contoh baik bagi Ujizane.
"Cukup. Mulai sekarang kau harus lebih mengekang
diri. Bagaimana, Ujizane?"
"Ya."
"Kenapa kau kelihatan kecewa?"
"Ananda tidak kecewa."
"Hmm, kalau begitu, pergilah! Ini bukan waktunya
memelihara burung."
"Baiklah, tapi..."
"Apa yang ingin kaukatakan?"
"Apakah sekarang waktunya untuk minum sake
bersama perempuan-perempuan dari Kyoto, serta
menari dan memukul gendang sepanjang sore?"
"Jaga mulutmu!"
"Tapi, Ayahanda..."
"Diam!" Yoshimoto berkata sambil melemparkan
kipasnya ke arah Ujizane.
"Mestinya kau lebih tahu diri. Bagaimana aku bisa
mengangkatmu sebagai pewarisku, kalau kau tidak
memperlihatkan minat pada masalah militer dan tidak
mau mempelajari seluk-beluk pemerintahan dan
ekonomi? Ayahmu mendalami Zen ketika masih
muda, melalui segala macam kesulitan, dan
mengambil bagian dalam pertempuran yang tak ter-
hitung jumlahnya. Kini aku penguasa provinsi kecil
ini, tapi suatu hari nanti aku akan memerintah
seturuh negeri. Kenapa aku diberin putra yang begitu
kecil hati dan bercita-cita kerdil? Tak ada yang patut
kukeluhkan selain kekecewaanku terhadapmu."
Para pengikut Yoshimoto gemetar ketakutan di
selasar. Mereka masing-masing menatap lantai sambil
membisu. Bahkan Ujizane pun menundukkan kepala
dan memandang kipas ayahnya yang tergeletak di
kakinya.
Pada saat itu seorang samurai masuk dan
mengumumkan. "Yang terhormat Tuan Sessai, Tuan
Ieyasu, dan para pengikut senior menanti tuanku di
Paviliun Jeruk Mandarin."
Paviliun Jeruk Mandarin didirikan di lereng bukit
yang ditumbuhi pohon jeruk mandarin, dan ke
sanalah Yoshimoto mengundang Sessai dan para
penasihat lainnya, dengan alasan mengadakan upacara
teh pada malam hari.
"Ah! Begitukah? Semuanya sudah datang? Sebagai
tuan rumah, tidak sepatutnya aku terlambat."
Yoshimoto berkata seakan-akan terselamatkan dari
konfrontasi dengan putranya, lalu menyusuri selasar
ke arah berlawanan.
Sejak semula upacara minum teh itu hanya tipu
muslihat belaka. Namun bayangan menari-nari yang
ditimbulkan oleh cahaya lentera menyelubungi tempat
itu dengan suasana anggun, cocok untuk upacara
minum teh pada malam hari. Tapi begitu Yoshimoto
masuk dan pintu-pintu ditutup, para pengawal
menerapkan pengawasan yang begitu ketat, sehingga
air pun tak dapat menyusup tanpa diketahui.
"Yang Dipertuan Agung." Seorang pengikut
mengumumkan kedatangan junjungannya, seakan-
akan mengumumkan kedatangan seorang raja. Di
dalam ruangan besar itu, sama seperti di kuil-kuil.
sebuah lentera redup berkelip-kelip. Sessai dan para
pengikut senior duduk membentuk barisan, dengan
Tokugawa Ieyasu di ujungnya. Barisan orang itu mem-
bungkuk ke arah junjungan mereka.
Pakaian sutra Yoshimoto terdengar berdesir dalam
keheningan. Ia mengambil tempat duduk, tanpa di-
sertai pelayan maupun pembantu. Kedua pem-
bantunya menjaga jarak dua atau tiga meter di
belakangnya.
"Maafkan keterlambatanku," Yoshimoto menang-
gapi salam para pengikutnya. Kemudian, secara
khusus ia berkata pada Sessai. "Ini tentu merupakan
beban bagi Yang Terhormat." Belakangan ini
Yoshimoto selalu menanyakan kesehatan Sessai pada
waktu mereka bertemu. Sudah sejak lima atau enam
tahun ini Sessai sering sakit-sakitan, dan dalam bulan-
bulan terakhir terlihat jelas bahwa ia bertambah tua.
Sessai telah membimbing, melindungi, dan
mengilhami Yoshimoto sejak masa kanak-kanaknya.
Yoshimoto menyadari bahwa ia mencapai kejayaannya
berkat keahlian Sessai sebagai negarawan, serta
kemampuannya menyusun rencana. Jadi, mula-mula
Yoshimoto merasakan pertambahan usia Sessai seperti
pertambahan usianya sendiri, tapi ketika mengetahui
bahwa kekuatan marga Imagawa tidak berkurang
karena tidak mengandalkan Sessai, dan bahwa
kekuatannya justru semakin berkembang, ia mulai
percaya bahwa keberhasilannya merupakan akibat dari
kemampuannya sendiri.
"Karena aku kini telah dewasa.'' Yoshimoto pernah
berkata pada Sessai. "jangan risaukan urusan
pemerintahan provinsi atau urusan militer. Nikmati-
lah sisa waktumu, dan pusatkanlah pikiranmu pada
penyebaran Jalan Buddha." Jelaslah bahwa ia mulai
mengambil jarak terhadap Sessai.
Namun dari sudut pandang Sessai, Yoshimoto
menyerupai anak kecil yang terseok-seok, dan ia
merasakan keprihatinan yang sama. Sessai
memandang Yoshimoto persis seperti Yoshimoto
memandang putranya, Ujizane. Sessai menganggap
Yoshimoto tak dapat diandalkan. Ia tahu bahwa
Yoshimoto merasa kikuk dengan kehadirannya dan
telah berupaya menjauhkannya, tapi ia terus berusaha
membantu, baik dalam urusan pemerintahan maupun
militer. Sejak awal musim semi tahun itu, tak satu pun
dari kesepuluh pertemuan di Paviliun Jeruk Mandarin
yang tidak diikutinya.
Apakah mereka akan bergerak sekarang, atau
menunggu sedikit lebih lama? Pertemuan ini akan
menentukannya, dan masa depan seluruh marga
Imagawa tergantung pada keputusan yang akan
diambil.
Diiringi suara jangkrik, pertemuan yang akan
mengubah peta kekuasaan seluruh negeri berlangsung
di bawah pengamanan ketat. Ketika nyanyian serangga
tiba-tiba terhenti, para pengawal langsung mondar-
mandir menyusuri semak-semak di luar paviliun.
"Sudahkah kau menyelidiki apa yang kita bicarakan
pada penemuan terakhir?" Yoshimoto bertanya pada
salah seorang jendralnya.
Jendral itu merentangkan beberapa dokumen di
lantai dan membuka penemuan dengan memberi
penjelasan secara garis besar. Ia telah menyusun
laporan mengenai kekuatan militer dan ekonomi
marga Oda. "Mereka dikabarkan sebagai marga kecil,
tapi belakangan ini terlihat tanda-tanda bahwa
ekonomi mereka berkembang pesat." Sambil bicara, ia
memperlihatkan beberapa diagram pada Yoshimoto.
"Owari dipandang sebagai satu kesatuan, tapi di
bagian timur dan selatan ada beberapa tempat, seperti
benteng Iwakura, yang telah bersumpah setia pada
tuanku. Disamping itu, ada sejumlah orang yang
walaupun pengikut Oda, diketahui merasa bimbang
mengenai kesetiaan mereka. Jadi, dalam keadaan
sekarang, kurang dari setengah, mungkin hanya dua
per lima, dari seluruh Owari yang berada di bawah
kekuasaan marga Oda."
"Begitu," ujar Yoshimoto. "Sepertinya mereka hanya
marga kecil, persis seperti yang kita dengar. Hmm,
berapa banyak prajurit yang sanggup mereka
kerahkan?"
"Mengingat mereka hanya menguasai dua per lima
dari Owari, wilayah mereka mampu menghasilkan
sekitar seratus enam puluh ribu sampai tujuh puluh
ribu gantang padi. Dengan perhitungan bahwa
sepuluh ribuu gantang padi cukup untuk sekitar dua
ratus lima puluh orang, walaupun seluruh pasukan
Oda dikerahkan, jumlah mereka takkan melebihi
empat ribu orang. Dan jika dikurangi dengan jumlah
pengawal di benteng-benteng, hamba meragukan
kemampuan mereka untuk mengumpulkan lebih dari
sekitar tiga ribu orang."
Tiba-tiba Yoshimoto tertawa. Kalau tertawa, telah
menjadi kebiasaannya untuk mencondongkan badan-
nya sedikit dan menutupi giginya yang hitam dengan
kipas. "Tiga atau empat ribu, katamu? Hah, itu nyaris
tak cukup antuk mendirikan provinsi. Sessai ber-
pendapat bahwa musuh yang harus diperhatikan saat
kita bergerak menuju ibu kota adalah orang-orang
Oda, dan kalian semua pun berulang kali
menyinggung marga itu. Karena itulah aku minta agar
laporan-laporan ini disusun. Tapi apa yang akan
dilakukan tiga atau empat ribu orang di hadapan
pasukanku? Apa sulitnya menjadikan mereka bulan-
bulanan, lalu menghancurkan mereka dengan sekali
pukul?"
Sessai tidak mengatakan apa-apa; yang lain pun
tetap membisu. Mereka tahu bahwa Yoshimoto takkan
berubah pikiran. Rencana itu sudah tersusun sejak
bertahun-tahun, dan tujuan segala persiapan militer
serta administrasi wilayah marga Imagawa adalah
gerakan Yoshimoto ke ibu kota serta penguasaan
seluruh negeri. Waktunya sudah tiba dan Yoshimoto
tak sanggup menahan diri lebih lama lagi. Meski
demikian, jika beberapa pertemuan telah diadakan
sejak musim mi dengan maksud mengambil
keputusan, sedangkan tujuan belum juga tercapai, itu
berarti dalam kelompok penentu ini terdapat
seseorang yang berpendapat bahwa waktunya belum
tepat. Suara sumbang ini milik Sessai. Ia bukan hanya
berpendapat bahwa waktunya belum tiba, melainkan
juga memberikan saran agar pembenahan administrasi
internal diutamakan dulu. Ia tidak mengkritik ambisi
Yoshimoto untuk menyatukan seluruh negeri, tapi ia
juga tidak memberikan persetujuannya.
"Marga Imagawa merupakan marga termasyhur pada
masa ini." ia sempat berkala pada Yoshimoto. "Jika
suatu ketika tak ada yang mewarisi kekuasaan sang
Shogun, anggota marga Imagawa-lah yang harus tampil
ke depan. Kau harus memelihara cita-cita besar ini,
dan mulai sekarang kau melatih diri agar mampu
memerintah seluruh negeri." Sessai sendirilah yang
mengajari Yoshimoto untuk berpandangan luas.
Daripada menjadi penguasa sebuah benteng, jadilah
penguasa seluruh provinsi. Daripada jadi pemimpin
satu provinsi, jadilah pemimpin seluruh distrik.
Daripada memerintah seluruh distrik, lebih baik
memerintah seluruh negeri.
Semua orang memberi nasihat seperti ini. Dan
semua anak samurai menghadapi dunia yang kacau
dengan ajaran ini terpatri di kepala. Ini pula yang
menjadi fokus latihan yang diberikan Sessai pada
Yoshimoto. Jadi, sejak Sessai bergabung dengan dewan
pimpinan Yoshimoto, pasukan marga Imagawa
berkembang pesat. Dengan langkah pasti Yoshimoto
meniti tangga menuju kekuasaan tertinggi. Namun
belakangan ini Sessai merasakan pertentangan antara
ajaran yang diberikannya pada Yoshimoto dan
perannya sebagai penasihat—ada sesuatu yang mem-
buatnya bimbang mengenai penyatuan seluruh negeri
yang direncanakan Yoshimoto dengan rasa percaya
diri yang semakin kuat.
Dia tidak memiliki kemampuan untuk itu, pikir Sessai.
Seiring peningkatan rasa percaya diri Yoshimoio,
terutama pada tahun-tahun belakangan ini, pemikiran
Sessai jadi semakin konservatif. Inilah puncaknya.
Kemampuan Yoshimoto sebagai penguasa takkan ber-
kembang lagi. Aku harus berusaha agar dia mau
membatalkan niatnya. Inilah sumber kesedihan Sessai.
Tapi harapan bahwa Yoshimoto, yang begitu bangga
akan kemajuan duniawinya, tiba-tiba bersedia mem-
batalkan niat untuk meraih kekuasaan tertinggi
amatlah kecil. Keberatan Sessai disambut dengan tawa
dan dipandang sebagai tanda bahwa ia mulai uzur,
dan karena itu tidak mendapat tanggapan. Yoshimoto
menganggap seluruh negeri sudah berada dalam
genggamannya.
Ini harus diakhiri secepatnya. Sessai tidak lagi
mengingatkannya. Malah sebaliknya, dalam setiap
pertemuan ia bersikap teramat hati-hati.
"Kesulitan apa yang mungkin menghadangku jika
aku bergerak menuju Kyoto dengan seluruh
kekuatanku serta pasukan gabungan Suruga, Totomi.
dan Mikawa?" Yoshimoto kembali bertanya. Ia
merencanakan untuk menempuh perjalanan ke ibu
kota tanpa penumpahan darah, mempelajari kondisi
di semua provinsi yang akan dilaluinya, dan
menyiapkan kebijakan diplomasi sejak jauh hari.
untuk sedapat mungkin menghindari pertempuran.
Namun pertempuran pertama dalam perjalanan
menuju Kyoto bukanlah melawan provinsi-provinsi
kuat seperti Mino atau Omi. Pertempurannya akan
berlangsung melawan marga Oda dari Owari. Mereka
tak berarti. Tapi mereka tidak bisa diajak berdamai
melalui diplomasi, atau disuap dengan uang.
Mereka memang musuh yang merepotkan. Dan
bukan hanya sekarang atau kemarin. Selama empat
puluh tahun terakhir, marga Oda dan marga Imagawa
berperang, iika sebuah benteng direbut, benteng lain
akan jatuh ke tangan lawan, dan jika sebuah kota
dibakar, sepuluh desa akan musnah dilahap api.
Bahkan dari zaman ayah Nobunaga dan kakek
Yoshimoto pun kedua marga itu seakan-akan berikrar
bahwa mereka akan terus saling menggempur di
perbatasan kedua provinsi.
Ketika desas-desus mengenai rencana Yoshimoto
sampai ke telinga marga Oda, mereka segera
memutuskan untuk menentukan nasib dalam satu
pertempuran besar. Bagi Yoshimoto, orang-orang Oda
merupakan korban ideal untuk pasukannya yang
hendak maju ke ibu kota, dan ia terus mematangkan
rencana untuk melawan mereka.
Inilah pertemuan terakhir dewan perang. Sessai,
Ieyasu,. dan para pembantunya meninggalkan istana.
Mereka menempuh perjalanan pulang dalam keadaan
gelap gulita, tak satu lentera pun menyala di Sumpu.
"Tak ada yang dapat kita lakukan sdain berdoa agar
keberuntungan berada di pihak kita." gumam Sessai.
Semakin tua seseorang, bahkan jiwa yang paling
gemilang pun kembali kekanak-kanakan. "Dingin
sekali rasanya." Padahal malam itu bukanlah malam
yang patut disebut dingin.
Belakangan, ketika orang-orang mengingat keiadian
ini, jelas bahwa itulah awal memburuknya kesehatan si
biksu. Itulah malam terakhir kaki Sessai menapak di
bumi. Dalam kesunyian musim gugur. Sessai
meninggal dengan tenang, tanpa diketahui.
***
Di tengah-tengah musim dingin tahun itu.
pertempuran-pertempuran kecil di sepanjang per-
batasan mendadak berkurang. Namun sesungguhnya
ini merupakan masa penggalangan kekuatan untuk
menjalankan rencana yang lebih besar. Tahun
berikutnya gandum di ladang-ladang subur di provinsi-
aaovinsi pesisir tumbuh tinggi. Bunga-bunga ceri
berguguran, dan wangi daun-daun muda naik ke
langit.
Awal musim panas. Dari Sumpu. Yoshimoto
memberi perintah kepada pasukannya untuk bergerak
menuju ibu kota. Kemegahan pasukan Imagawa
membuat dunia terbelalak kagum. Dan pengumuman-
nya menyebabkan provinsi-provinsi kecil gemetar
ketakutan. Pesannya singkat dan jelas:
Mereka yang menghalangi pasukanku akan di-
hancurkan. Mereka yang menerimanya dengan penuh
kesopanan akan diperlakukan dengan baik.
Seusai Perayaan Anak-Anak Laki-Laki, Sumpu
diserahkan ke tangan pewaris Yoshimoto, Ujizane,
dan pada hari kedua belas di bulan kelima, pasukan
utama mulai bergerak, diiringi sorak-sorai rakyat. Para
prajurit gagah, dengan pancaran cemerlang menyaingi
matahari, berangkat menuju ibu kota. Pasukan itu
mungkin terdiri atas dua puluh lima ribu atau dua
puluh enam ribu orang, tapi sengaja dikabarkan
sebagai pasukan berkekuatan empat puluh ribu orang.
Pada hari kelima belas, barisan terdepan memasuki
kota Chiryu. dan mendekati Narumi pada hari
ketujuh belas, mereka membakar desa—di bagian
Owari itu. Cuaca terus baik dan hangat. Alur-alur di
ladang gandum dan tanah yang sedang berbunga
tampak memutih. Di sana-sini di langit biru terlihat
kepulan asap hitam yang berasal dari yang dibakar.
Namun tak satu letusan senapan pun datang dan
marga Oda. Para petani telah diperintahkan untuk
mengungsi, dan meninggalkan apa pun bagi pasukan
Imagawa yang terus mendesak.
"Kalau begini, bisa-bisa benteng di Kiyosu juga
dalam keadaan kosong!"
Para perwira dan prajurit Imagawa merasakan baju
tempur mereka menjadi beban di tengah kejemuan di
jalan-jalan yang datar dan tenteram.
Di Benteng Kiyosu, lentera-lentera menyala seperti
biasa. Namun lentera-lentera itu seakan-akan dinyala-
kan untuk menghadapi hantaman badai dahsyat yang
akan datang. Pohon-pohon yang berdiri tak bergerak
di pekarangan benteng mengingatkan akan
ketenangan di pusat badai. Dan sampai sekarang
belum juga ada petunjuk dari benteng kepada rakyat.
Tak ada perintah untuk mengungsi atau mempersiap-
kan penahanan, bahkan tak ada pengumuman untuk
membangkitkan semangat. Para pedagang membuka
toko seperti biasa. Para pengrajin bekerja seperti biasa.
Para petani pun pergi ke ladang seperti biasa. Tapi lalu
lintas di jalan-jalan telah terhenti selama beberapa
hari.
Kota agak lebih sepi dan desas-desus merajalela.
"Kudengar Imagawa Yoshimoto menuju ke barat
dengan pasukan berkekuatan empat puluh ribu
orang."
Setiap kali para warga yang gelisah bertemu, mereka
mengira-ngira nasib mereka.
"Tak ada jalan untuk bertahan. Kekuatan kita tak
sampai sepersepuluh pasukan Imagawa."
Dan di tengah-tengah suasana serbaragu, mereka
melihat para jendral melewati kota, satu per satu.
Beberapa di antara mereka adalah komandan yang
meninggalkan benteng untuk kembali ke wilayah
masing-masing, tapi ada juga yang mengambil tempat
di benteng.
"Mungkin mereka sedang membahas apakah lebih
baik menyerah kepada orang-orang Imagawa. atau
mempertaruhkan nasib marga dengan bertempur."
Dugaan rakyat jelata menyangkut hal-hal yang tak
dapat mereka saksikan, namun biasanya tanda-tanda
yang tampak tak luput dari pengamatan mereka.
Sebenarnya masalah tersebut sudah beberapa hari
menjadi pokok pembicaraan di benteng. Pada setiap
pertemuan, para jendral terbagi dalam dua kutub.
Para pendukung "rencana aman" dan "utamakan
marga" berpendapat bahwa sebaiknya mereka
menyerah pada orang-orang Imagawa. Tetapi per-
bedaan pendapat itu tidak berlangsung lama. Dan ini
karena Nobunaga telah membulatkan tekad.
Satu-satunya alasan ia mengadakan pertemuan
dengan para pengikut senior adalah untuk
menyampaikan keputusannya pada mereka, bukan
guna membahas rencana pertahanan maupun
kebijaksanaan untuk mengamankan Owari. Setelah
mendengar keputusan Nobunaga, banyak jendral
memberi tanggapan positif, dan dengan semangat
baru, kembali ke benteng masing-masing.
Kemudian Kiyosu kembali tenteram seperti biasa,
dan jumlah prajurit tidak bertambah secara mencolok.
Namun, seperti bisa diduga, malam itu Nobunaga
berulang kali dibangunkan agar membaca pesan yang
dibawa oleh kurir-kurir.
Keesokan malamnya, segera setelah menyelesaikan
makan malam sederhana, Nobunaga pergi ke ruang
utama untuk membahas situasi militer. Di sana, para
jendral yang belum meninggalkan benteng masih terus
mengelilinginya. Semuanya kurang tidur, dan wajah-
wajah pucat mereka memperlihatkan kecerahan hati.
Para pengikut yang tidak terlibat langsung dalam
pembicaraan berdesak-desakan di ruang sebelah dan di
ruang setelah itu. Orang seperti Tokichiro duduk
dalam ruangan yang terpisah jauh. Dua malam
sebelumnya, begitu juga malam kemarin dan malam
ini. mereka cemas dan tak bersuara, seakan-akan
menahan napas. Dan pasti tak sedikit orang yang
menatap lentera-lentera dan rekan-rekan mereka,
sambil berpikir, "Ini sama saja dengan menjaga
jenazah."
Di tengah kegalauan, suara tawa terdengar dari
waktu ke waktu. Nobunaga-lah yang tertawa. Mereka
yang duduk di tempat jauh tidak mengetahui apa yang
ditertawakan, tapi mereka mendengarnya berulang-
ulang.
Tiba-tiba seorang kurir terdengar berlari menyusun
selasar. Shibata Katsuie, yang bertugas membacakan
laporan dari garis depan di hadapan Nobunaga,
menjadi pucat sebelum kata-kata melewati bibirnya.
"Tuanku!"
"Ada apa?"
"Pesan keempat sejak pagi tadi baru saja tiba dari
benteng di Marune."
Nobunaga memindahkan sandaran tangannya ke
depan. "Bagaimana?"
"Kelihatannya malam ini pasukan lmagawa akan
bergerak ke Kutsukake."
"Begitukah?" Hanya ini yang dikatakan Nobunaga,
sementara matanya menatap kosong ke arah jendela
kecil di atas pintu. Bahkan Nobunaga pun tampak
bingung. Meski sejak beberapa saat lalu orang
mengandalkan ketegaran Nobunaga, kini perasaan
putus asa menyusup ke hati mereka. Kutsukake dan
Marune berada di wilayah kekuasaan marga Oda. Dan
jika garis pertahanan penting itu telah terputus.
Dataran Owan nyaris tanpa pertahanan, dan jalan
menuju Benteng Kiyosu tak terhalang lagi.
"Apa yang akan tuanku lakukan?" tanya Katsuie.
seakan-akan tak sanggup lagi menahan kesunyian.
"Kami mendengar pasukan Imagawa mungkin
berjumlah empat puluh ribu orang. Kekuatan kita
sendiri kurang dari empat ribu orang. Di Benteng
Marune paling banyak hanya ada tujuh ratus orang.
Walaupun barisan terdepan Imagawa, pasukan di
bawah pimpinan Tokugawa Ieyasu, hanya berjumlah
dua ribu lima ratus orang, Marune tetap menyerupai
kapal yang dipermainkan gelombang."
"Katsuie. Katsuie!"
"Sanggupkah kita mempertahankan Marune dan
Washizu sampai fajar..."
"Katsuie! Tulikah kau? Mengapa kau berceloteh
tanpa ujung-pangkal? Percuma saja mengulang-ulangi
yang sudah jelas."
"Tapi..." Tepat pada saat Katsuie angkat bicara, ia
dipotong oleh suara langkah kurir berikut. Orang itu
bicara dengan gaya sok penting dan ambang pintu
ruang sebelah.
"Hamba membawa berita penting dari benteng-
benteng di Nakajima dan Zenshoji." Laporan-laporan
dan pasukan di garis depan yang telah bertekad untuk
bertempur sampai titik darah penghabisan selalu
bernada menyedihkan, dan kedua laporan yang baru
tiba pun bukan perkecualian. Kedua-duanya dimulai
dengan. "Ini mungkin pesan terakhir kami untuk
Benteng Kiyosu..."
Kedua laporan terakhir dari garis depan berisi
serupa. Kedua-duanya menjelaskan susunan pasukan
musuh, dan kedua-duanya meramalkan serangan pada
keesokan harinya.
"Ulangi bagian mengenai susunan pasukan musuh."
Nobunaga memberi perintah pada Katsuie, sambil
bertopang pada sandaran tangan. Katsuie kembali
membacakan bagian itu, bukan hanya untuk
Nobunaga, tapi untuk semua yang sedang duduk
berbaris di situ.
"Pasukan musuh yang menuju benteng di Marune:
sekitar dua ribu lima ratus orang. Pasukan musuh
yang menuju benteng di Washizu: sekitar dua ribu
orang. Pasukan pendamping: tiga ribu orang. Pasukan
ulama yang mengarah ke Kiyosu: sekitar enam ribu
orang. Pasukan utama Imagawa: sekitar lima ribu
orang." Sambil terus membaca. Katsuie menambahkan
bahwa tidak terlihat dari angka-angka itu berapa
banyak gerombolan musuh yang bergerak sambil
menyamar. Setelah selesai. Katsuie meletakkan
gulungan berisi pesan ke hadapan Nobunaga.
Semuanya menatap lentera putih sambil membisu.
Mereka akan bertempur sampai titik darah peng-
habisan. Jalan hidup mereka telah ditentukan. Tak
ada tempat untuk debat berkepanjangan. Namun
mereka merasa tersiksa, karena mereka hanya
menunggu tanpa berbuat apa-apa. Washizu, Marune,
maupun Zenshoji tidak berjarak jauh. Dengan
memacu kuda, tempat-tempat itu bisa dicapai dengan
cepat. Pasukan Imagawa hampir terlihat di depan
mereka, empat puluh ribu orang, menerjang bagaikan
air bah. Suara mereka hampir tertangkap oleh telinga.
Dari salah satu sudut terdengar suara orang tua
yang dilanda kesedihan, "Tuanku sudah mengambil
keputusan jantan, tapi janganlah beranggapan bahwa
gugur di medan tempur merupakan satu-satunya jalan
bagi para samurai. Bukankah lebih baik tuanku
mempertimbangkannya kembali? Walaupun dicap
pengecut, hamba merasa masih ada tempat untuk ber-
pikir, untuk menyelamatkan marga dari kemusnahan."
Orang itu Hayashi Sado, orang yang paling lama
mengabdi dari antara mereka semua. Bersama Hirate
Nakatsukasa, yang melakukan bunuh diri untuk
memperingatkan Nobunaga, ia salah satu dari ketiga
pengikut senior yang oleh Nobuhide. menjelang
ajalnya, ditugaskan untuk mengurus Nobunaga. Dan
ia satu-satunya yang masih hidup dari ketiga orang itu.
Saran Hayashi diterima baik oleh semua yang hadir.
Dan dalam hati mereka berdoa agar Nobunaga mau
mendengarkan kata-kata orang tua itu.
"Jam berapa sekarang?" tanya Nobunaga.
mengalihkan pembicaraan.
"Jam Tikus." balas seseorang dari ruang sebelah.
Ketika kata-kata bertambah lemah dan malam semakin
larut, semuanya seperti diliputi kemurungan.
Akhirnya Hayashi menyembah, dan dengan kepala-
nya yang ubanan tertunduk ke lantai, ia bicara ke arah
Nobunaga, "Tuanku, mari kita pertimbangkan sekali
lagi. Mari mengadakan perundingan. Hamba
memohon. Kalau tajar tiba, seluruh pasukan dan
benteng-benteng kita terancam remuk di tangan
pasukan Imagawa. Kita terancam kekalahan total.
Daripada begitu, lebih baik mengadakan perundingan
perdamaian. Ikat mereka dalam perundingan
perdamaian sebelum..."
Nobunaga meliriknya. "Hayashi?"
"Ya, tuanku."
"Kau sudah tua. Jadi tentu sukar bagimu untuk
duduk berlama-lama. Pembicaraan kita sudah selesai,
dan malam telah larut. Pulanglah dan beristirahatlah."
"Ini sudah melebihi batas,..." ujar Hayashi sambil
berurai air mata. Ia menangis karena mengira akhir
marga telah dekat. Ia pun bersedih karena dianggap
orang tua tak berguna. "Jika tuanku telah membulat-
kan tekad, hamba takkan mengatakan apa-apa lagi
mengenai keinginan tuanku untuk bertempur."
"Jangan!"
"Tampaknya keinginan tuanku untuk bertempur
tak tergoyahkan lagi."
"Memang begitu."
"Pasukan kita kecil—kurang dari sepersepuluh
pasukan musuh. Jika bertempur melawan mereka,
peluang kita kurang dari satu banding seribu, jika kita
mengurung diri di dalam benteng, kita masih sempat
menyusun rencana."
"Menyusun rencana?"
"Kalau kita sanggup menahan pasukan Imagawa
selama dua minggu atau satu bulan saja, kita bisa
mengutus kurir ke Mino atau Kai untuk minta
bantuan. Mengenai strategi lain, di sini cukup banyak
orang yang tahu bagaimana mengganggu musuh."
Nobunaga tertawa begitu keras, hingga gemanya
terdengar memantul langit-langit. "Hayashi, itu strategi
untuk keadaan normal. Kaupikir ini normal untuk
marga Oda?"
"Pertanyaan tuanku tak memerlukan jawaban."
"Walaupun kita memperpanjang hidup selama lima
atau sepuluh hari, yang tak dapat dipertahankan tetap
tak dapat dipertahankan. Tapi ada yang berucap.
'Arah perjalanan nasib tak pernah diketahui.'
"Kalau kupikir-pikir, aku menarik kesimpulan
bahwa kita telah mencapai titik terendah
kesengsaraan. Dan kesengsaraan kita sungguh
menarik. Dan, tentu saja, juga amat besar. Meski
demikian, mungkin inilah kesempatan seumur hidup
yang disediakan nasib bagiku. Andai kata kita
mengurung diri dalam benteng, haruskah kita berdoa
agar diberi umur panjang tanpa kehormatan? Orang
dilahirkan untuk mati. Relakanlah hidup kalian
untukku. Bersama-sama kita akan maju di bawah
langit biru dan gugur seperti prajurit sejati." Setelah
selesai berbicara. Nobunaga langsung mengubah nada
suaranya.
"Hmm, kalian semua kelihatan kurang tidur."
Senyum tipis muncul di wajahnya. "Hayashi. kau
tidurlah juga. Semuanya perlu tidur. Aku yakin tak
seorang pun di antara kita begitu pengecut, sehingga
tak sanggup memejamkan mata."
Setelah kata-kata itu terucap, rasanya tak pantas
untuk tidak tidur. Namun sesungguhnya tak seorang
pun dari mereka tidur nyenyak selama dua malam
terakhir. Nobunaga satu-satunya perkecualian. Ia tidur
lelap pada malam hari, bahkan sempat tidur sebentar
pada siang hari, bukan di kamar tidurnya, melainkan
di mana saja.
Sambil bergumam seakan-akan pasrah, Hayashi
membungkuk ke arah junjungannya dan rekan-
rekannya, lalu mengundurkan diri.
Seperti gigi yang dicabut, semua orang berdiri dan
pergi satu per satu. Akhirnya tinggal Nobunaga di
ruang pertemuan yang luas. Ia tampak tenang, seolah-
olah tak ada yang membebani pikirannya. Ketika
menoleh ke belakang, ia melihat dua pelayan yang
tidur sambil saling bersandar. Salah satu dan mereka.
Tohachiro. baru berusia tiga belas tahun. Ia adik
Maeda lnuchiyo. Nobunaga memanggilnya.
"Tohachiro!"
"Tuanku?" Tohachiro duduk tegak, menghapus air
liur yang mengalir dari sudut mulutnya dengan satu
tangan.
"Kau tidur nyenyak."
"Maafkan hamba."
"Bukan, bukan. Aku tidak bermaksud memarahi-
mu. Justru sebaliknya, aku memujimu. Aku pun akan
tidur sejenak. Ambilkan sesuatu untuk bantal."
"Tuanku hendak tidur di sini?"
"Ya. Fajar cepat tiba pada musim ini, jadi
sekaranglah waktu yang baik unruk tidur sebentar-
sebentar. Ambilkan kotak di sebelah sana. Biar
kupakai itu saja." Nobunaga merebahkan diri sambil
bicara, menopang kepala dengan siku, sampai
Tohachiro membawakan kouk yang diminu.
Tubuhnya terasa bagaikan perahu yang mengambang.
Tutup kotak itu dihiasi gambar pinus, bambu, dan
pohon prem—lambang-lambang keberuntungan. Sam-
bil menyelipkannya ke bawah kepala. Nobunaga
berkata. "Bantal ini akan memberikan mimpi baik."
Kemudian, sambil tertawa-tawa kecil, Nobunaga
memejamkan mata, dan akhirnya, ketika si pelayan
mematikan lampu-lampu satu per satu, senyum tipis
pada wajahnya menghilang seperti salju yang mencair.
Ia segera terlelap, wajahnya tampak damai di sela-sela
bunyi mendengkur
Tohachiro merangkak keluar untuk memberitahu
para samurai di ruang jaga. Para pengawal merasa
muram, menyangka bahwa akhirnya telah dekat. Dan
yang mutlak, tentu saja, tak ada yang menanti mereka
selain kematian Orang-orang di dalam benteng
berhadapan langsung dengan kematian, sementara
waktu sudah melewati tengah malam
"Aku tidak keberatan mati. Masalahnya, dengan
cara apa kita akan mati?"
Inilah dasar kegelisahan mereka, dan pertanyaan itu
tetap berkecamuk dalam dada masing-masing. Karena
itu, di antara mereka masih ada orang-orang yang
belum membulatkan tekad.
"Beliau tidak boleh kedinginan." Sai, dayang
Nobunaga, berkata, dan menyelimuti Nobunaga
dengan kain penutup tempat tidur. Setelah itu,
Nohunaga tidur selama dua jam.
Persediaan minyak di dalam lampu-lampu kini
hampir habis, apinya yang nyaris padam menimbulkan
bunyi gemercik. Tiba-tiba Nobunaga mengangkat
kepala dan berseru.
"Sai! Sai! Siapa yang ada di sini?"
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20036)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5796)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12948)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6523)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2568)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3282)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)

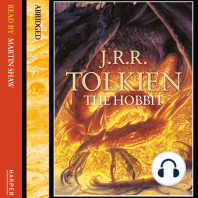









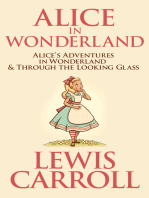




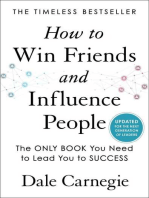





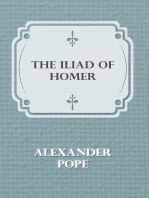


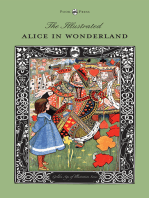

![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)