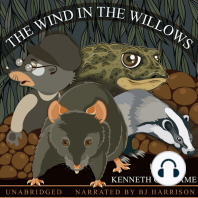#3 Masukan
#3 Masukan
Diunggah oleh
Hibatullah HindamJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
#3 Masukan
#3 Masukan
Diunggah oleh
Hibatullah HindamHak Cipta:
Format Tersedia
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
Evaluasi
Merapi
Strategi
Pengadaan
Hunian
Paska
Erupsi
Penekanan pada Aplikasi Struktur Tahan Gempa pada fase Pengembangan Mandiri
oleh Pengguna
Maria Ariadne Dewi Wulansari / 25213003
Buat rumusan dari literatur2, mengelompokkan sendiri
Hunian dalam Konteks Paska Bencana
Dalam literatur mengenai kebencanaan, terdapat penggunaan istilah penampungan
post disaster shelter dan perumahan post disaster housing yang tidak jelas dan tidak
konsisten. bisa dimasukkan pendapat2 yang berbeda2 itu, baru disimpulkan apakah
konsisten atau memang terbukti tidak konsisten, hati2 dalam memilih jurnal, pastikan yg
dapat dipercaya. Secara umum, penggunaan istilah shelter mengacu pada tempat
tinggal yang digunakan segera setelah bencana saat kegiatan rutin harian pengguna
masih mengalami gangguan, dalam artian aktivitas sehari-hari masih terganggu.
Sementara istilah housing mengacu pada tempat tinggal saat pengguna telah kembali ke
tanggung jawab rumah tangga dan rutinitas sehari-hari dengan normal (Quarantelli
(1995)).
Berdasarkan perbedaan definisi tersebut, jika berbicara mengenai hunian paska
bencana, terdapat 4 tahapan hunian, yaitu: bisa disebutkan tokohnya, tahun berapa,
melekat pd pendapatnya
1) emergency shelter, yaitu tempat di mana korban tinggal untuk waktu singkat
selama puncak darurat terjadi; yang dapat di berupa rumah kerabat atau di
tempat penampungan umum,
2) temporary shelter, yaitu tempat yang diharapkan untuk ditinggali dalam jangka
waktu pendek, idealnya tidak lebih dari beberapa minggu setelah bencana; dapat
berupa tenda, tempat penampungan massal umum, dll,
3) temporary housing, yaitu tempat dimana para korban dapat tinggal sementara,
biasanya direncanakan selama 6 bulan sampai 3 tahun, dengan kembali ke
kegiatan normal mereka sehari-hari; dari jenis bangunan dapat mengambil bentuk
rumah prefabrikasi, rumah sewaan, dll,
4) permanent housing, yaitu rumah sebelum bencana yang telah dibangun kembali
atau bermukim kembali dengan membangun rumah baru di lokasi yang baru
secara permanen.
Posisi Pengadaan Hunian dalam Fase Penanganan Bencana
Gambaran singkat dari berbagai tahap dari bencana akan membantu untuk
menempatkan pemulihan paska-bencana di sebuah kontinum peristiwa yang diperlukan
untuk pemahaman tersebut. Literatur mengklasifikasikan bencana ke dalam fase sesuai
dengan tindakan dan kondisi yang terjadi sebelum, selama atau setelah bencana (Haas
et al, 1977;. Drabek, 1986).
Klasifikasi tahapan dalam kebencanaan ialah :
Tahap Pra-Bencana
adalah tahapan pada kondisi sebelum kejadian bencana. Tindakan yang dapat
dilakukan dalam tahap ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran akan resiko bencana, mengurangi resiko bencana ataupun mengurangi
kerugian jika terjadi bencana. antara lain adalah:
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
a. Kesiagaan: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna
dan berdaya guna.
b. Peringatan dini: memberi peringatan kepada masyarkat tentang bencana
yang dapat atau akan terjadi.
c. Mitigasi bencana: serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik
melalui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Tahap Bencana
Tahap saat kejadiaan bencana merupakan tahap yang krusial karena saat inilah
bencana sesungguhnya terjadi. Dalam tahap ini didahului oleh kegiatan tanggap
darurat, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti
kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta
pemulihan sarana dan prasarana.
Tahap ini juga disebut sebagai fase darurat (immediate relief period), yang
dimulai segera setelah terjadinya bencana hingga hari kelima (Drabek, 1990).
Dari perspektif perumahan, fase ini dinyatakan berakhir ketika tidak ada lagi
operasi pencarian dan penyelamatan maupun operasi evakuasi yang dilakukan,
kebutuhan hunian sementara segera terpenuhi, tingkat permintaan hunian
sementara mulai stabil atau mulai menurun, penilaian awal atas kerusakan
keseluruhan selesai dilakukan, dan dengan adanya penyingkiran atas puing-puing
dan membangun kembali properti yang rusak.
Tahap Paska Bencana
Setelah proses tanggap darurat terlewati, tahap selanjutnya adalah tahap paska
bencana yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi.
o Fase Rehabilitasi
Periode ini terjadi mulai dari hari kelima bencana hingga 3 bulan paska
bencana. Rehabilitasi sendiri adalah perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai
pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi
atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah paskabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui
kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan
sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat,
pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi
konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan
ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi
pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan
mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi sosial, adat istiadat,
budaya,dan ekonomi (BNPB, 2008).
o Fase Rekonstruksi
Fase ini dimulai dari 3 bulan paska bencana. Rekonstruksi sendiri adalah
perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang
terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali
secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik
di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama
tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi
masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah
paska bencana (BNPB, 2008). Rekonstruksi dapat disebut juga sebagai
proses membangun kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan
pada wilayah benca paska bencana, baik pada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat.
Selama periode rekonstruksi, dana bantuan dan rekonstruksi disediakan
oleh pemerintah. Periode ini berakhir dengan pengembangan menuju
kondisi yang kembali stabil mendekati kondisi prabencana, pembangunan
kembali bangunan hingga yang berada dalam kondisi paling rusak,
pengembalian saham perumahan hingga mencapai tingkat kondisi prabencana dan diawalinya periode pemulihan jangka panjang (Haas et al.,
1977 ; Schwab et al, 1998;. Arnold, 1993).
Tahap Pemulihan Jangka Panjang
Tahap pemulihan jangka panjang adalah periode terakhir dari bencana. Dimulai
ketika upaya-upaya yang diambil berorientasi pada membangun kembali pola
prabencana di masyarakat daripada menyediakan perumahan sementara dan
bantuan darurat (Cuny, 1983; Bates dan Peacock, 1989). Meskipun tidak selalu
mungkin untuk mengidentifikasi dengan presisi saat tertentu menandai awal dari
pemulihan, fase ini dikatakan lengkap dengan penggantian kerugian fisik dan
merebut kembali pembangunan dan pertumbuhan tujuan yang mungkin telah
terlewatkan sebagai akibat dari bencana (Bolin dan Stanford, 1998). Untuk tujuan
perumahan, tujuan ini tercermin oleh berbagai indikator seperti hunian dan
tingkat keterjangkauan, tingkat perpindahan penduduk setempat, jumlah unit
perumahan, perbaikan struktural, derajat retrofit dan kualitas hidup secara
keseluruhan di daerah yang mengalami kerusakan tinggi.
Relokasi dan Pengadaan Hunian Paska Bencana
Banyak kasus yang menunjukkan bahwa pemerintah sering mempertimbangkan relokasi
seluruh permukiman sebagai bagian dari kebijakan rekonstruksi mereka. Relokasi
biasanya merefleksikan keinginan untuk mengosongkan lahan yang terlalu berbahaya.
Hal ini juga dapat menjadi upaya untuk menghapus orang-orang yang menempati lahan
hunian secara ilegal (seperti permukiman ilegal), atau juga sebagai ekspresi dari
kemauan politik untuk perubahan dan reformasi hunian.
Permasalahan yang timbul dari relokasi sangatlah beragam, antara lain:
Relokasi jauh dari pusat-pusat perkotaan sebagian besar didorong oleh
ketersediaan lahan yang murah (dan seringkali berupa lahan yang tidak
diinginkan)
Jarak dari pekerjaan dan biaya transportasi adalah penyebab dari penurunan
pendapatan atau kehilangan kesempatan untuk bekerja bagi penghuni
Pelayanan perkotaan sering kali tidak tersedia (sekolah, rumah sakit, toko, pasar,
dll)
Sistem utilitas seperti air, saluran air limbah, dan listrik sering tidak cukup, atau
tidak ditemukan, karena kurangnya perencanaan dan persiapan disebut
namanya
Hanya sedikit kelompok pembina dilengkapi dengan
masterplan, jenis
pembangunan ini sebagai bagian dari manajemen bantuan paska bencana.
Situasi ini diperparah ketika pemerintah daerah juga kekurang tenaga perencana,
arsitek, administrator, maupun sumber daya modal.
Jika situasi ekonomi dan lingkungan memburuk tak tertahankan, orang akan
bermigrasi kembali ke daerah dan pekerjaan asli mereka, meninggalkan
kekosongan di belakang mereka, yang kemudian dengan cepat diisi oleh
pedesaan untuk migran perkotaan, sehingga muncul masalah urbanisasi yang
tidak terkendali.
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
Jika pemukiman baru berada dalam batas-batas administratif kota yang terkena
bencana, utilitas (air, saluran air, listrik, dll) harus diperpanjang. Permintaan untuk
layanan baru akan bersaing dengan kebutuhan untuk perbaikan dan rekonstruksi
di daerah yang hancur, pada biaya masalah sosial dan ekonomi.
Penyelesaian dengan relokasi akan menciptakan batas-batas kota luar yang
bertahan hidup dalam semacam limbo, tanpa kesediaan pemerintah lokal maupun
daerah untuk menanggung biaya pembangunan dan pemeliharaan
Pada negara berkembang, biaya sarana infrastruktur perkotaan sangat tinggi,
biaya per kapita jauh melebihi kapasitas per kapita untuk memenuhi biaya
tersebut. Harga dari tanah yang dilayani oleh infrastruktur telah meningkat
sebanding dengan biaya sumber daya dan jasa lainnya, dan terutama dalam
kaitannya dengan upah .
Dalam penanganan paska bencana, respon pemerintah yang sering diberikan ialah
adalah janji untuk memindahkan korban ke yang baru, pada daerah yang lebih aman dari
bencana. Tapi bukti-bukti yang jelas menyatakan bahwa dalam prakteknya relokasi
jarang menghasilkan hunian yang layak, karena alasan berikut ini:
Rekonstruksi, khususnya perumahan, biasanya dimulai sangat cepat setelah
bencana
Orang tidak mau meninggalkan pola mapan kepemilikan tanah
Bahkan dalam bencana besar, ada kemungkinan bahwa hanya sebagian kecil
bagian kota yang mengalami kehancuran. Biaya relokasi besar-besaran lebih
besar daripada biaya perbaikan dan rekonstruksi.
Kepentingan pribadi biasanya menerapkan tekanan untuk membangun kembali,
bukan relokasi
Meskipun mangalami efek dari bencana, orang secara alami menolak pindah dari
lingkungan yang mereka kenal
Di banyak negara berkembang tidak ada cara keluar yang formal dari dilema ini:
mungkin satu-satunya pendekatan adalah untuk membujuk masyarakat untuk
mengurangi kerentanan mereka sendiri, melalui pendidikan publik tentang dampak
bahaya alam yang parah, dan keuntungan yang akan diperoleh dari relokasi parsial.
Ada beberapa pra - kondisi yang harus dipenuhi untuk relokasi parsial yang sukses:
Persetujuan dari masyarakat yang terkena dampak
Ketersediaan lahan yang aman dengan biaya yang berada dalam kemampuan
masyarakat
Kedekatan dengan pekerjaan dan pelayanan sosial
Penyediaan utilitas di tingkat masyarakat (jika tidak dapat dipenuhi untuk setiap
keluarga)
Fasilitas untuk membangun rumah yang memadai
Kalau ambil banyak dari satu literatur, jarang, kalau memang penting, taruh di
footnote, tulis yang perlu saja, lainnya sebutin di footnote, biar dicari sendiri
Tapi ITB tidak menggunakan footnote, jadi? metode footnote tidak dipakai, tapi
pakai sistem referensi, kasih nomor, di footnote ditulis sourcenya lengkap sampai
sebut halamannya
Jenis-jenis Strategi/Pendekatan Pengadaan Rumah Paska Bencana
Untuk mencapai tujuan pengadaan rumah paska bencana, ada berbagai strategi yang
dapat dilakukan. Perbedaan antar strategi sendiri terbagi berdasarkan peran serta korban
bencana dalam proses pengadaan rumah paska bencananya. Komponen pembeda antar
strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
Proses tabulasinya diperlihatkan
Komponennya ambil dari pendapat siapa
Jenis2 strateginya dari siapa
Komponen
Donor Driven
Approach
Dibentuk organisasi
tingat desa dengan
gabungan warga dan
penyedia
People Centric
Approach
Design
Using Local
Resources
Decision
Making
Oleh penyedia
Semua diambil penyedia
dari luar daerah
Oleh penyedia
Partisipasi aktif warga
Partisipasi warga
Oleh warga
Dari dalam desa
Oleh warga
Training
Programme
Tidak ada pelatihan
maupun pertemuan
desa
Warga dengan
berkonsultasi dengan
penyedia
Diadakan pelatihan dan
pertemuan
Ownership
Sistem kontrak
Maintenance
Monitoring
Tidak terkoordinasi
Tidak ada
Organization
al set up
Dipandu oleh
organisasi desa,
terdiri dari semua
tokoh masyarakat dan
penyedia
Kepemilikan penuh
warga
Oleh warga
Oleh tokoh desa dan
penyedia
Owner Driven
Approach
Oleh warga, dipandu
oleh tim mandiri
profesional dalam desa
Pelatihan untuk semua
warga, pertemuan
hanya pada tim
pembangunan
Kepemilikan penuh
warga
Oleh warga
Oleh tim pembangun
Evaluasi Strategi Pengadaan Rumah Paska Bencana
Dari literatur yang dikumpulkan (Al-Hussaini et al (1999), Samaddar et al (2006), Leon
et al (2009), nder et al (2010), Ratnayake et al (2010), etc) jangan dijentreng,
sebutin per penemuan , strategi pengadaan rumah paska bencana dapat dievaluasi
melalui:
1. Ketercapaian Target
a. Ketepatan penyelesaian program (si A, tahun a)
b. Ketercapaian pemenuhan kebutuhan sesuai program (si B, tahun b)
c. Kesadaran akan mitigasi bencana pada masyarakat
d. Pemahaman prinsip bangunan tahan bencana pada masyarakat
e. Pemahaman konsep sustainable settlement and community
pada
komunitas masyarakat penghuni
2. Keberhasilan Penggunaan
a. Persentase hunian yang dihuni
b. Kecukupan ketersediaan ruang dalam hunian
c. Kemudahan akses
3. Kualitas Fisik Bangunan
a. Ketahanan bangunan terhadap gempa
b. Kelengkapan dan kondisi fasilitas pendukung
c. Estetika dalam bangunan
d. Pemenuhan aspek fungsional dalam bangunan
4. Kualitas Sosial Masyarakat
a. Penerimaan masyarakat terhadap tata pemukiman dan tata ruang dalam
hunian
b. Kesamaan kondisi hunian yang diterima masing-masing warga
c. Hubungan dengan warga asli di sekitar pemukiman
d. Keberhasilan hunian paska bencana dalam mendukung recovery warga
5. Keberlanjutan Hunian
a. Kemudahan pengembangan mandiri
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
b. Keberhasilan dalam keberlanjutan pemukiman dan komunitas
Pengembangan Rumah Sementara Paska Bencana
Hunian paska bencana haruslah memungkinkan adanya keberlanjutan, karena berkaitan
dengan keberlangsungan hidup penghuninya.
Dalam tulisan Transitional Shelter: Understanding Shelter from The Emergency Through
Reconstruction and Beyond (ALNAP : 2010), dikatakan bahwa untuk memperbaiki kinerja
bangunan sementara paska bencana, salah satu pendekatan yang digunakan adalah
penerapan sifat upgradable pada bangunan. Maksud dari sifat upgradable ini ialah
sementara dihuni, hunian sementara dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk
menjadi tempat tinggal permanen. Hal ini dicapai melalui pemeliharaan, pengembangan,
atau dengan mengganti bahan asli dengan bahan alternatif yang lebih tahan lama.
Studi Kasus Global
Dola K dan Parva M dalam penelitiannya Transformation Of Earthquake Disaster Victims
Shelter Into Sustainable Home : The Case Of Lar City, Iran melakukan penelitian terhadap
transformasi hunian sementara paska bencana menuju hunian permanen, yang
disebabkan oleh ketidakpuasan dari segi sosio-kultural dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Sementara itu penelitian A Post-Disaster Dilema : Temporary Settlement In Dulce, Turkey
oleh Esra Bektas mengungkapkan penyebab terjadinya transformasi hunian sementara
paska bencana menuju hunian permanen, yaitu adanya ketidakpuasan dari segi sosiokultural, kegagalan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemilihan material yang
tidak tahan lama.
Dalam Sosial Sustainability Of New-Ngelepen New Dome Housing As Post Disaster
Housing Reconstruction Of Central Java-Yogyakarta Earthquake, Edward Endrianto
Pandelaki melakukan evaluasi paska huni terhadap hunian paska bencana dan
menyatakn bahwa faktor penghambat keberlanjutan sosial dari hunian paska bencana
yaitu kurangnya kesesuaian bangunan dengan budaya dan karakter setempat.
Pada studi yang dilakukan Iwasa dan rekan mengenai A Practical Approach To Temporary
Housing For Disaster Victims, dilakukan pengamatan terhadap pemberian temporary
open caf project pada lingkungan hunian paska bencana sebagai self improved
practical support. Dari hasil penelitian tersebut penyediaan self-improved practical
support dalam hunian paska bencana berperan sebagai strategi pencapaian
keberlanjutan dalam hunian paska bencana. Dengan keberadaan cafe tersebut perlahan
mulai digunakan oleh penduduk, mula-mula sebagai tempat bersosialisasi hingga mulai
menumbuhkan area ekonomi aktif dalam masyarakat.
Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Erupsi Merapi
Dalam factsheet REKOMPAK Kementerian Pekerjaan Umum, Building Back Better :
Menuju Pernataan Permukiman yang Lebih Baik (2012), disampaikan bahwa dalam
rehabilitasi rekonstruksi pascaerupsi Merapi, semua langkah-langkah rekonstruksi
disiapkan sejalan dengan penyiapan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Erupsi
Merapi yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan
Bappenas. Mengacu pada konsep Rencana Aksi tersebut, kebijakan umum rehabilitasi
rekonstruksi bidang perumahan adalah sebagai berikut :
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memilih bertempat tinggal di lokasi
yang lebih aman sebagai upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
2. Memberikan stimulan Bantuan Dana Rumah (BDR) maksimal Rp. 30 juta per
rumah per KK;
3. Masyarakat diberi keleluasaan dalam menentukan pilihan tipe rumah namun
diupayakan memenuhi luas minimal rumah inti yaitu 36m2;
4. Konstruksi rumah harus memenuhi persyaratan teknis dan metode pembangunan
rumah tahan gempa;
5. Pelaksanaan pembangunan rumah dilakukan oleh masyarakat dengan didampingi
oleh tim fasilitator.
Prinsip Ketahanan Gempa pada Rumah Pasca Bencana
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Tembok Tahan Gempa dari Direktorat Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan syarat pembangunan bangunan tembok
tahan gempa sebagai berikut:
1. Bangunan harus terletak di atas tanah yang stabil
2. Denah bangunan rumah sebaiknya sederhana dan simetris, dengan sloof yang
diangkur ke pondasi
3. Gunakan kayu kering, pilih bahan atap yang ringan
4. Dinding pasangan bata/batako, dipasang angkur setiap jarak 30 cm ke kolom
5. Setiap luasan dinding 12 m2 harus dipasang kolom praktis
6. Dipasang balok ring/cincin yang diikat kaku dengan kolom
7. Seluruh kerangka bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku
8. Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan kayu diberi baut dan
plat pengikat
9. Perhatikan bahan spesi adukan (1pc : 3 pasir)
10. Pelaksanaan konstruksi oleh tukang berpengalaman
Sementara itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta
Karya Nomor: 111/Kpts/Ck/1993 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Tahan
Gempa, dalam pembangunan bangunan tembok bata, hal-hal yang perlu diperhatikan
ialah:
1. Dinding
a. Sistem dinding pemikul:
1) Bangunan sebaiknya tidak dibuat bertingkat.
2) Besar lubang pintu dan jendela dibatasi. Jumlah lebar lubanglubang dalam satu bidang dinding tidak melebihi panjang dinding
itu. Letak lubang pintu/jendela tidak terlalu dekat dengan sudutsudut dinding, misalnya minimum 2 kali tebal dinding. Jarak antara 2
lubang sebaiknya juga tidak kurang dari 2 kali tebal dinding. Ukuran
bidang dinding juga dibatasi, misalnya tinggi maksimum 12 kali tebal
dinding, dan panjangnya diantara dinding-dinding penyekat tidak
melebihi 15 kali tebalnya.
3) Apabila bidang dinding diantara dinding-dinding penyekat lebih
besar dari pada itu, maka dipasang pilaster-pilaster/tiang-tiang
tembok. Blok lintel dibuat menerus keliling bangunan dan sekaligus
berfungsi sebagai pengaku horizontal. Blok lintel tersebut perlu diikat
kuat dengan pilaster-pilaster.
4) Pilaster diperkuat dengan jangkar-jangkar. Jangkar dapat terdiri dari
kawat anyaman ataupun seng tebal yang diberi lubang-lubang paku
seperti parutan.
5) Pada bagian atas dinding dipasang balok pengikat keliling/ring balk.
Ring balk dijangkarkan dengan baik kepada pilaster-pilaster.
6) Pada sudut-sudut pertemuan dinding, hubungan antara balok-balok
pengikat keliling (ring balok) perlu dibuat kokoh.
7) Hubungan antara bidang-bidang dinding pada pertemuanpertemuan dan sudut-sudut dinding perlu diperkuat dengan jangkar-
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
jangkar. Jangkar dapat berupa seng tebal dengan lubang-lubang
bekas paku atau berupa kawat anyaman.
8) Disekeliling lubang pintu dan jendela dapat juga dipasang
perkuatan ekstra.
b. Sistem rangka pemikul dengan dinding pengisi
1) Dipasang
kolom-kolom
pengaku
dinding
dan
pengaku
dinding/perkuatan horizontal sedemikian sehingga luas bidang
tembok diantara rangka yang mengapitnya tidak melebihi 12 m2.
Balok lintel dibuat menerus keliling bangunan. Dalam hal ini balok
lintel berfungsi sebagai pengaku/penguat horizontal. Pada bagian
atas dinding dipasang balok pengikat keliling/ring balk yang terdiri
dari bahan yang sama dengan kolom pengaku dinding.
2) Kolom-kolom pengaku dinding perlu diikat kepada pondasi
3) Balok lintel perlu diikat dengan kolom-kolom pengaku dinding.
4) Ring balk perlu diikat dengan kolom-kolom pengaku dinding.
5) Hubungan ring balk pada sudut-sudut pertemuan dinding harus
kuat.
6) Antara tembok dengan kolom pengakunya perlu diadakan
pengikatan dengan jangkar-jangkar. Jangkar antara lain berupa seng
tebal yang diberi lubang-lubang paku seperti parutan.
7) Antara tembok dengan kusen pintu/jendela juga perlu diadakan
pengikatan dengan jangkar-jangkar.
2. Atap
a. Rangka atap/kuda-kuda perlu dijangkarkan pada dinding dengan besi
berdiameter minimum 12 mm.
3. Pelaksanaan Pasangan Tembok
a. Adukan spesi diisikan penuh/merata pada hubungan horizontal maupun
vertikal antara blok-blok bata.
b. Komposisi campuran spesi yang baik
CATATAN:
1) Dianjurkan memakai sistim rangka pemikul dengan dinding pengisi.
2) Bagian-bagian yang terdiri dari kayu sebaiknya diawetkan dahulu untuk
menghindari kerusakan oleh rayap (anai-anai)
3) Panjang paku yang dipakai untuk pengikat minimum 2,5 kali tebal kayu
terkecil.
4) Kalau tidak tersedia semen PC., semen merah juga dapat dipakai untuk
bahan campuran spesi, umpamanya dengan perbandingan campuran
sebagai berikut:
a. Untuk dinding pemikul: 1 Semen Merah: 1 Kapur : 1 Pasir atau 1
Kapur: 3 tras
b. Untuk dinding pengisi: 1 Semen Merah : 3 Kapur : 5 Pasir atau 1
Kapur: 5 tras
Masukan Umum dari yang lain-lain:
jangan berbentuk kurikulum
mengutip dibikin paragraf sendiri agak dimasukkan, untuk definisi atau pendapat yang
harus digunakan, tidak bisa diganti
paparan nggak bertujuan mengajar, tetapi sesuaikan dengan topik/judul, ambil yang
kunci saja
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
Pustaka mengenai hunian paska bencana
Arnold, C. (1993). Reconstruction after Earthquakes: Issues, Urban Design, and Case
Studies. San Mateo, CA: Building Systems Development.
Batchelor, Victoria. (2011). Tarpaulins, transitional shelter or permanent houses : how
does the shelter assistance provide affect the recovery of communities after
disaster? Dissertation on Oxford Brookes University
Bates, F. L. and Peacock, W. G. (1989). Long Term Recovery. International Journal of Mass
Emergencies and Disasters, 7(3), pp. 349365.
Bekta, Esra. (2006). A Post-Disaster Dilemma: Temporary Settlements In Dzcecity,
Turkey. Proceeding on iRec International Conferrence. Florence. Diakses melalui
www.grif.umontreal.ca/pages/BEKTAS_Esra.pdf
BNPB (2008). Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Paska Bencana. Peraturan Kepala
Badan nasional Penanggulangan Bencana. Republik Indonesia.
Bolin, R. C. and Stanford, L. (1998). The Northridge Earthquake: Vulnerability and
Disaster. New York: Routledge.
Collins, Sam. Corsellis, Tom. Vitale, Antonella. (2010).Transitional Shelter: Understanding
Shelter from The Emergency Through Reconstruction and Beyond. ALNAP. Diakses
melalui www.sheltercenter.org
Cuny, F. C. (1983). Disasters and Development. New York: Oxford University Press.
Dola, K. and Parva, M. (2012). Transformation Of Earthquake Disaster Victims Shelter
Into Sustainable Home: The Case Of Lar City, Iran. ALAM CIPTA, International
Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice. Universiti Putra
Malaysia. Volume 5 (2) December 2012
Drabek, T. E. (1986). Human System Responses to Disaster: An Inventory of Sociological
Findings. New York: Springer-Verlag.
Drabek, T. E. (1990). Emergency Management: Strategies for Maintaining Organizational
Integrity. New York: Springer-Verlag.
Haas, E., Kates, R. and Bowden, M. (1977). Reconstruction following Disaster. Cambridge,
MA: MIT Press.
Johnson, C. (2007). Impacts of prefabricated temporary housing after disasters: 1999
earthquakes in Turkey. Habitat International 31 , 36-52.
Kamel, Nabil M. O. and Loukaitou-Sideris, Anastasia (2003). Residential Assistance and
Recovery Following the Northridge Earthquake. Urban Studies, Vol. 41, No. 3, 533
562, March 2004.
Quarantelli, E. L. (1989). A Review of The Literature in Disaster Recovery Research.
Newark, DE: Disaster Research Center, University of Delaware.
Quarantelli, E. L. (1995). Patterns of Sheltering and Housing in US Disasters. Disaster
Prevention and Management 4, 43-53.
REKOMPAK. (2012). Building Back Better : Menuju Pernataan Permukiman yang Lebih
Baik. Kementerian Pekerjaan Umum. Republik Indonesia.
UNDRO, (1982). Shelter after Disaster: Guidelines for Assistance. New York: United
Nations.
Schwab, J., Topping, K. C., Deyle, R. E. Et Al. (1998). Planning for Post-disaster Recovery
and Reconstruction. Chicago, IL: American Planning Association.
Pustaka mengenai prinsip ketahanan gempa
Boen, T. dan rekan (2006). Syarat-Syarat Minimum Bangunan Tembokan Bata/Batako
Aman Gempa Dengan Perkuatan Beton Bertulang Dinding Ampig Batu Bata.
TUGAS RISET TEMATIK 2
3.0. Kajian Literatur
Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, Jakarta.
Boen, T. dan rekan (2009). Persyaratan Pokok Rumah yang Lebih Aman. Kementerian
Pekerjaan Umum dan JICA, Jakarta.
Boen, T. dan rekan (2010). Membangun Rumah Tembokan Tahan Gempa. AustraliaIndonesia Facility for Disaster Reduction dan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, Jakarta.
Cipta Karya (1993). Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya : Pedoman
Pembangunan Bangunan Tahan Gempa. Kementerian Pekerjaan Umum.
10
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)