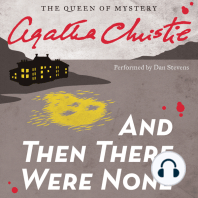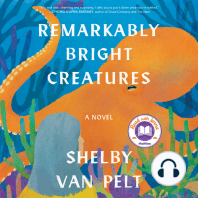Hak & Batasan Wanita Dalam Politik
Diunggah oleh
Muhammad Enal0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
16 tayangan2 halamanFREE
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniFREE
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
16 tayangan2 halamanHak & Batasan Wanita Dalam Politik
Diunggah oleh
Muhammad EnalFREE
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
HAK DAN BATASAN WANITA
DALAM MASALAH POLITIK
Di negeri Kuwait wanita dilarang mengikuti proses pemilihan (hak suara)
anggota Majelis Ummah. Perbuatan ini tergolong telah mengharamkan apa yang
dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal ini karena dalam Majelis Ummah
dalam pandangan Islam hanyalah sebuah majelis yang anggota-anggotanya
'wakil' dari rakyat untuk 'menyampaikan' aspirasi dan suara rakyat terhadap
penguasa, baik kritikan maupun usulan. Jadi haknya hanya sebatas
'penyampaian' dan tidak berwenang dalam penentuan/pembuatan hukum
maupun perundang-undangan. (Lihat Nizhamul Hukmi fil Islam, Syekh AnNabhani, hal 212).
Karena kedudukan mereka sebagai wakil, maka sebenarnya hak ini
(muwakalah) juga dimiliki oleh kaum wanita, sebagaimana bagi kaum pria,
apalagi jika permasalahan yang akan diwakilkan itu berkait dengan problema
kewanitaan, karena tidak mungkin mewakilkannya kepada kaum pria.
Dalam hal ini mari kita simak kejadian pada masa Khalifah Umar bin
Khatthab, dimana beliau selaku pimpinan negara berniat akan menetapkan
batasan mahar (mas kawin) bagi kaum wanita agar tidak terlalu besar dan
menyulitkan bagi kaum pria untuk menikah (maksimal 400 dinar), ternyata
kebijakan ini ditentang oleh seorang wanita dengan menyampaikan sebuah
firman Allah yang tidak pernah membatasi jumlah mahar. Mendengar teguran itu,
Umar berkata : "Benarlah wanita itu dan salahlah Umar"
Kisah lain yang juga perlu untuk disimak adalah ketika Khalifah Umar
akan mengambil keputusan tentang beberapa lama para prajurit mujahiddin akan
dikirim untuk bertugas ke perbatasan (meninggalnkan isteri dan keluarganya).
Beliau meminta pendapat para wanita (kaum ibu) untuk menetapkan berapa
lama waktu yang layak bagi mereka ditinggalkan suaminya dan ayahnya.
Setelah mengumpulkan pendapat dari para wanita itulah, maka Umar
menetapkan waktu selama 4 bulan bagi para tentara/prajurit untuk bertugas di
perbatasan. Setelah 4 bulan mereka harus diganti dengan pasukan baru. Dua
contoh kecil ini menunjukkan betapa 'suara' kaum wanita tetap diakui Islam untuk
mengurusi berbagai problematika kemasyarakatan; baik atas nama dirinya
sendiri maupun dalam rangka mewakili wanita yang lainnya. Karenanya wanita
diperbolehkan emnjadi anggota Majelis Ummah (selama majelis ummah itu tetap
berperan sebagai penyampaian pendapat atau kritik; tidak sebagai penetap atau
pembuat hukum). Melarang kenyataan in adalah bertentangan dengan ajaran
Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan kehidupan masa Rasul dan para
sahabat.
Untuk memperkuat hal itu, kita bisa juga melihat realita Bai'atul Aqabah
kedua, dimana kaum muslimin Yastrib, diantaranya beberapa wanita yang
menyatakan sumpah setia dan ketaatan keada Rasul SAW. Kisah lain juga
terlihat saat Abdurrahman bin Aufmengumpulkan suara untuk mencari pengganti
Umar bin Khatthab sebagai Khalifah; beliau mendatangi setiap rumah dan
menanyakan pendapat mereka tentang siapa yang berhak/lebih layakantara
Utsman bin Affan ataukah Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman menanyai seluruh
masyarakat tanpa membedakan antara pria dan wanita. Semua kisah nyata
terseut menunjukkan bahwa dalam Islam, kaum wanita tetap memiliki hak
berpolitik, terutama dalam menyampaikan suara atau dipilihuntuk wakil rakyat di
Majelis Ummah.
Adapun pembahasan wanita dalam posisi sebagi 'penguasa' maka
memang terdapat dalil yang melarangnya denga tegas, yakni ketika Rasul
bersabda, melalui jalur sahabat Abi barkah :
"Tidaklah akan beruntung suatu kaumyang menyerahkan urusannya (hukum dan
kekuasaan) kepada seorang wanita."
Sesungguhnya hadits ini muncul ketika kerajaan Persia kehilangan
rajanya, lau rakyat memilih seorang pengganti yaitu anak perempuan Kisra. Lalu
berita ini didengar oleh RasulullahSAW dan beliau mengatakan hadits di atas
kepada para shahabatnya. Pemberitaan Rasul ini menjadi penjelasan bagi kita
bahwa kaum wanita diatur oleh Islam untuk tidak menempati posisi sebagai
'penguasa' dalam sistem pemerintahan Islam. Penguasa yang dimaksud di sini
adalah
posis
yang
berkait
dengan
kebijakan
dan
keputusan
hukum/pemerintahan; dan tidak termasuk bagian dalam urusan politik yang
hanay sebatas perwakilan suara, administratif dan hal lain yang tidak berkait
dengan pengambilan dan penetapan hukum.
Larangan (baca pengaturan) bagi wanita menduduki posisi penguasa ini,
bukanlah merendahkan posisi wanita atau memuliakan posisi pria. Aturan ini
hanyalah ketetapan dari Allah SWT untuk dilaksanakan manusia, tidak
seperti pandangan musuh-musuh Islam yang sering menyudutkan posisi wanita
dalam Islam. Pria dan wanita, keduanya bisa mulia bisa hina, tergantung
ketakwaan dan keterikatannya terhadap aturan Allah SWT.
Wallahu 'alam bi al-shawab.
rekayasa sosial dimulai dengan mengubah kepribadian individu yang terlibat
dalam pranata sosial itu. Cara mengubahnya adalah dengan menanamkan ideide perubahan pada dirinya
Referensi:
1. Nizhamul Hukmi fil Islam. Pustaka Thariqul Izzah
2. Tata Kehidupan Wanita dalam Islam. Wahyu Press
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20023)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3276)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5505)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)



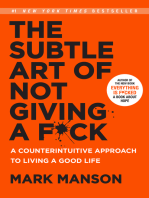







![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)