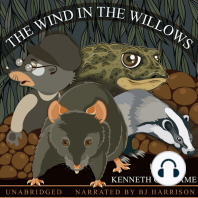Isi
Isi
Diunggah oleh
esraJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Isi
Isi
Diunggah oleh
esraHak Cipta:
Format Tersedia
1
A. Latar belakang
Tulang adalah bagian tubuh pada mahluk hidup yang memiliki kegunaan
alat gerak tubuh pembentukan rangka, penyimpanan mineral seperti kalsium
dan fosfat, dan pelindung organ-organ internal tubuh. Dalam pembentukan
tulang yang biasa disebut osifikasi terjadi pada perkembangan fetus (prenatal)
dan setelah lahir (postnatal). Pada tulang yang mengalami pemanjangn
perkembanganya sampai pada umur dewasa (Hill dan Orth, 1998; Fernandez et
al., 2006).
Jaringan tulang mempunyai tiga tipe sel yaitu osteosit, osteoblas, dan
osteoklas. Proses remodeling tulang melibatkan osteoklas dan osteoblas
melalui signal parankrin dan endokrin. Pada dasarnya osteoblas berkembang
dari osteo progenitor yang berada didalam sumsum tulang dan periosteum.
Osteoblas memiliki kegunaan sebagai penghasil matriks organik meliputi
protein kolagen dan kolagen, osteoblas juga berfungsi palam pengaturan proses
mineralisasi pembentukan osteoid (Orwoll, 2003). Tulang merupakan jaringan
yang dinamis karena selalu mengalami pembaruan secara konstan yang
dinamakan proses remodeling. Proses ini sangat kompleks karena melibatkan
proses pengurangan matriks tulang atau yang biasa sering disebut dengan
resorpsi dan pembentukan tulang kembali. Fungsi remodeling tulang itu sendiri
yaitu untuk menjaga homeostasis, pembentukan kerangka pada masa
pertumbuhan, memperbaiki jaringan yang rusak akibat kerusakan minor karena
faktor stres dan memperbaiki jaringan yang rusak akibat pergerakan fisik (Hill
dan Orth, 1998; Fernandez et al., 2006).
Salah satu faktor penting dalam proses remodeling yaitu proses
diferensisasi osteoblas. Proses proliferasi dan diferensiasi osteoblas diatur oleh
growth factor (faktor pertumbuhan) yang dihasilkan oleh osteoblas. Growth
faktor yang terlibat yaitu insulin growth factor (IGF I dan II), bone
morphogenic protein (BMPs), fibroblas growth factor (FGF), platelet derived
growth faktor (PDGF) yang bekerja secara autokrin dan parakrin, serta hormon
estrogen (Hofbauer et al., 1999; Ogita et al., 2008).
Ketidakseimbangan antara resorpsi dan pembentukan tulang pada proses
remodeling tulang dapat mengakibatkan kepadatan tulang berkurang sehingga
dapat menimbulkan penyakit metabolik tulang (Seeman, 2003). Kepadatan sel
tulang juga dapat berkurang karena kadar mineral yang mengalami penurunan
atau jumlah osteosit pada jaringan tulang berkurang sehingga dapat
mengakibatkan kerapuhan tulang (Manolagas, 2000). Kekurangan growth
faktor pada proses diferensiasi dan proliferasi osteoblas dapat juga sebagai
pemicu terjadinya penyakit tulan salah satunya jika kekurangan estrogen.
Estrogen mempunyai peran penting dalam proses remodeling tulang. Pada
wanita pascamenopouse berkurangnya hormon estrogen mengakibatkan
terjadinya osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit degenerasi tulang yang
ditandai dengan penurunan densitas dan deteriorasi mikroarsitektural dari
jaringan tulang yang menyebabkan kerapuhan dan kerentanan terhadap fraktur,
terutama pada tulang belakang (Shen dkk., 2009). Osteoporosis dipengaruhi
ileh jenis kelamin. Wanita empat kali berisiko untuk terkena osteoporosis
dibandingkan dengan pria karena penurunan tingkat estrogen setelah
menopouse. Estrogen menghambat kehilangan tulang dengan cara menghambat
apoptosis osteoblas (Tanaka dkk., 2003).
Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa sel osteoblas dan
osteoklas bertugas dalam pengaturan metabolisme tulang dan keduanya terlibat
dalam perkembangan osteoporosis. Ketidakseimbangan antara pembentukan
tulang dan resorpsi tulang adalah kunci dari patofisiologi dari penyakit
metabolik tulang seperti osteoporosis. Studi sebelumnya memper-lihatkan
bahwa diferensiasi osteo-blastik dihambat oleh stress oksidatif melalui
extracellular signal-regulated kinases (ERK) dan ERK-dependent nuclear
factor-B signaling pathways (Bai., 2004). Estrogen mengurangi stress
oksidatif sehingga osteoblas dapat ber-diferensiasi. Penurunan estrogen menyebabkan stress oksidatif meningkat sehingga jumlah sel osteoblas me-nurun,
kemudian mempercepat osteo-porosis(Almeida dkk., 2009). Untuk mengatasi
permasalahan ini perlunya pencarian bahan alami untuk mengurangi stres
oksidatif agar osteoblas meningkat dan memperkecil terjadinya osteoporosis.
Polifenol diketahui tidak hanya berperan dalam pencegahan penyakit
jantung dan kanker, tetapi juga pencegahan osteoporosis karena memiliki
potensi antioksidannya (Subhashini dkk., 2010). Salah satu tanaman yang
mengandung polifenol paling banyak adalah cengkeh, jenis polifenol yang
ditemukan pada tanaman ini adalah flavonoid. Beranjak dari hal-hal diatas,
diperlukan suatu penelitian mengenai hubungan pemberian ekstrak cengkeh
terhadap jumlah sel osteoblas tulang tibia tikus putih pascaovariektomi untuk
memperlambat progresi osteoporosis.
B. Perumusan masalah
1. Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak cengkeh (syzygium aromaticum)
terhadap jumlah osteoblas pada tulang tibia tikus wistar?
2. Apa kandungan ekstrak cengkeh yang dapat mempengaruhi osteoblas pada
tulang tibia tikus wistar?
C. Tujuan penelitian
1. Mengetahui pengaruh ekstrak cengkeh (syzygium aromaticum) terhadap
oseoblas pada tulang tibia tikus wistar yang dibuat osteoporosis
pascaovariektomi
2. Mengetehui kandungan ekstrak cengkeh yang dapat mempengaruhi
osteoblas pada tulang tibia tikus wistar
D. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ilmiah tentang peran
dan manfaat cengkeh dalam peningkatan osteoblas terutama pada penyakit
osteoporosis.
E. Landasan Teori
1. Osteoporosis
Osteoporosis berasal dari kata Osteo dan porous, osteo artinya
tulang, dan porous berarti berlubanglubang atau keropos. Jadi, osteoporosis
adalah tulang yang keropos, yaitu penyakit yang mempunyai sifat khas
berupa massa tulangnya rendah atau berkurang,disertai gangguan mikro
arsitektur tulang dan penurunan kualitas jaringan tulang, yang dapat
menimbulkan kerapuhan tulang ( Tandra, 2009). Menurut WHO pada
International Consensus Development Conference, di Roma, Itali, 1992)
Osteoporosis adalah penyakit dengan sifatsifat khas berupa massa tulang
yang rendah, disertai perubahan mikroarsitektur tulang, dan penurunan
kualitas jaringan tulang, yang pada akhirnya menimbulkan akibat
meningkatnya kerapuhan tulang dengan risiko terjadinya patah tulang
(Suryati, 2006). Tulang adalah jaringan yang hidup dan terus bertumbuh.
Tulang mempunyai struktur, pertumbuhan dan fungsi yang unik. Bukan
hanya memberi kekuatan dan membuat kerangka tubuh menjadi stabil,
tulang juga terus mengalami perubahankarena berbagai stres mekanik dan
terus mengalami pembongkaran, perbaikan dan pergantian sel. Untuk
mempertahankan kekuatannya, tulang terus menerus mengalami proses
penghancuran dan pembentukan kembali. Tulang yang sudah tua akan
dirusak dan digantikan oleh tulang yang baru dan kuat. Proses ini
merupakan peremajaan tulang yang akan mengalami kemunduran ketika
usia semakin tua. Pembentukan tulang paling cepat terjadi pada usia akil
balig atau pubertas, ketika tulang menjadi makin besar, makin panjang,
makin tebal, dan makin padat yang akan mencapai puncaknya pada usia
sekitar 25-30 tahun. Berkurangnya massa tulang mulai terjadi setelah usia
30 tahun, yang akan makin bertambah setelah diatas 40 tahun, dan akan
berlangsung terus dengan bertambahnya usia, sepanjang hidupnya. Hal
inilah yang mengakibatkan terjadinya penurunan massa tulang yang
berakibat pada osteoporosis ( Tandra, 2009).
2. Beberapa penyebab osteoporosis, yaitu:
a. Osteoporosis pascamenopause terjadi karena kurangnya hormon estrogen
(hormon utama pada wanita), yang membantu mengatur pengangkutan
kalsium kedalam tulang. Biasanya gejala timbul pada perempuan yang
berusia antara 51-75 tahun, tetapi dapat muncul lebih cepat atau lebih
lambat. Hormon estrogen produksinya mulai menurun 2-3 tahun sebelum
menopause dan terus berlangsung 3-4 tahun setelah menopause. Hal ini
berakibat menurunnya massa tulang sebanyak 1-3% dalam waktu 5-7
tahun pertama setelah menopause.
b. Osteoporosis senilis kemungkinan merupakan akibat dari kekurangan
kalsium yang berhubungan dengan usia dan ketidakseimbangan antara
kecepatan hancurnya tulang (osteoklas) dan pembentukan tulang baru
(osteoblas). Senilis berarti bahwa keadaan ini hanya terjadi pada usia
lanjut. Penyakit ini biasanya terjadi pada orang-orang berusia diatas 70
tahun dan 2 kali lebih sering menyerang wanita. Wanita sering kali
menderita osteoporosis senilis dan pasca menopause.
c. Kurang dari 5% penderita osteoporosis juga mengalami osteoporosis
sekunder yang disebabkan oleh keadaan medis lain atau obat-obatan.
Penyakit ini bisa disebabkan oleh gagal ginjal kronis dan kelainan
hormonal (terutama tiroid, paratiroid, dan adrenal) serta obat-obatan
(misalnya kortikosteroid, barbiturat, antikejang, dan hormon tiroid yang
berlebihan). Pemakaian alkohol yang berlebihan dan merokok dapat
memperburuk keadaan ini.
d.
Osteoporosis juvenil idiopatik merupakan jenis osteoporosis yang
penyebabnya tidak diketahui. Hal ini terjadi pada anak-anak dan dewasa
muda yang memiliki kadar dan fungsi hormon yang normal, kadar
vitamin yang normal, dan tidak memiliki penyebab yang jelas dari
rapuhnya tulang ( Junaidi, 2007).
3. Estrogen
Estrogen adalah hormon steroid seks endogen yang diproduksi oleh
ovarium, korteks adrenal, testis, dan plasenta pada masa
kehamilan(suherman, 2007). Estrogen mempunyai peran sebagai
antioksidan yang dapat menekan aktivitas radikal bebas (badeu, 2008).
Estrogen konsentrasi tinggi dapat berperan sebagai free radical scavenger
dan juga dapat menginduksi antioksidan enzimatik endogen seperti
manganese superoxide dismutase (MnSOD), heme oxygenase, thioredoxin,
glutathione peroxidase (GPx) (mahn, 2005). Kondisi hipoestrogen pada
wanita menopause akan meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh.6
Peningkatan stres oksidatif secara drastis di dalam tubuh dapat terjadi akibat
penurunan kadar estrogen sebagai antioksidan.7Stres oksidatif terjadi karena
ketidakseimbangan antaraprooksidan dengan antioksidan, dimana produksi
radikal bebas melebihi kemampuan penghambat radikal alami atau
mekanisme scavenging. Mekanisme penghambat radikal bebas terdiri dari
antioksidan endogen dan eksogen. Akibatnya radikal bebas merusak sel
dengan bereaksi dengan makromolekuler sel melalui proses peroksidasi
lipid, oksidasi DNA, dan protein.8 Malondialdehyde (MDA) merupakan
produk akhir dari peroksidasi lipid di dalam tubuh, dan biasanya digunakan
sebagai biomarker biologis peroksidasi lipid untuk menilai stres oksidatif.
Konsentrasi MDA yang tinggi merupakan bukti status antoksi dant ubuh
yang rendah, sehingga tidakdapat mencegah reaktivitassenyawa radikal
bebas.10berkurangnya kadar estrogen pada masa menopause dihubungkan
dengan peningkatan resorbsi tulang alveolar, penurunan estrogen
menyebabkan stress oksidatif meningkat sehingga jumlah sel osteoblas menurun, kemudian mempercepat osteo-porosis. Untuk mengatasi
permasalahan ini, antioksidan sangat baik digunakan untuk terapi,
antioksidan dapat berasal dari senyawa polifenol (Arkhaesi, 2008).
4. Tanaman cengkeh
Cengkeh (Syzygium aromaticum, syn. Eugenia aromaticum), dalam
bahasa Inggris disebut cloves, adalah tangkai bunga kering beraroma dari
suku Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan
sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan
utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh juga digunakan sebagai bahan
dupa di Tiongkok dan Jepang. Minyak cengkeh digunakan di aromaterapi
dan juga untuk mengobati sakit gigi. Cengkeh ditanam terutama di
Indonesia (Kepulauan Banda) dan Madagaskar, juga tumbuh subur di
Zanzibar (Aksan, 2008). Pohon cengkeh merupakan tanaman tahunan yang
dapat tumbuh dengan tinggi mencapai 10-20 m, mempunyai daun berbentuk
lonjong yang berbunga pada pucuk-pucuknya. Tangkai buah pada awalnya
berwarna hijau, dan berwarna merah jika sudah mekar. Cengkeh akan
dipanen jika sudah mencapai panjang 1,5-2 cm. Pengeringan bunga cengkeh
dapat dilakukan juga dengan menggunakan alat pengering tipe bak (batch
dryer) bunga cengkeh diletakkan di atas bak yang terbuat dari logam yang
berlubang udara panas kemudian di alirkan ke bawah bak dengan bantuan
kipas, sumber panas diperoleh dengan cara membakar sekam padi, arang
atau menggunakan minyak tanah, dengan menggunakan alat buatan ini
dibutuhkan waktu pengeringan 2-3 hari (Agus, 2004). Bunga cengkeh
mengandung minyak atsiri, fixed oil (lemak), resin, tannin, protein,
cellulosa, pentosan dan mineral, karbohidrat terdapat dalam jumlahnya
bervariasi tergantung dari banyak faktor diantaranya jenis tanaman, tempat
tumbuh dan cara pengolahan (Purseglove et al., 1981). Zat yang terkandung
di dalam cengkeh bernama eugenol sering digunakan dokter gigi untuk
menghilangkan rasa sakit pada gigi yang karies dan bahan dasar
penambalan gigi, eugenol yang diproses lebih lanjut akan menghasilkan isoeugenol yang digunakan untuk pembuatan parfum dan vanilin sintesis,
minyak cengkeh juga digunakan untuk bahan baku pembuatan balsem
cengkeh dan obat kumur (Hamid, 2008). Minyak atsiri akhir-akhir ini
menarik perhatian dunia, karena ada beberapa jenis minyak atsiri dapat
digunakan sebagai bahan antiseptik internal atau eksternal, sebagai bahan
analgesik, minyak atsiri juga mempunyai sifat membius, merangsang,
disamping itu beberapa jenis minyak atsiri lainnya dapat digunakan sebagai
obat cacing (Guenther, 1987). Kadar polifenol tertinggi dimiliki cengkeh,
yaitu sebesar 619.94 mg/g solid untuk cengkeh segar dan 790.06 mg/g solid
untuk cengkehbubuk. Cengkeh mengandung kadar polifenol yang sangat
tinggi karena cengkeh merupakan rempah utama penghasil eugenol dan
senyawa galat ,polifenol yang terdapat pada cengkeh yaitu flavonoid
(christine, 2007).
Senyawa-senyawa flavonoid adalah senyawa-senyawa polifenol
yang mempunyai 15 atom karbon, terdiri dari dua cincin benzena yang
dihubungkan menjadi satu oleh rantai linier yang terdiri dari tiga atom
karbon. Senyawa-senyawa flavonoid adalah senyawa 1,3 diaril propana,
senyawa isoflavonoid adalah senyawa 1,2 diaril propana, sedangkan
senyawa-senyawa neoflavonoid adalah 1,1 diaril propana. Istilah flavonoid
diberikan pada suatu golongan besar senyawa yang berasal dari kelompok
senyawa yang paling umum, yaitu senyawa flavonoid suatu jembatan
oksigen terdapat diantara cincin A dalam kedudukan orto, dan atom karbon
benzil yang terletak disebelah cincin B. Senyawa heterosoklik ini, pada
tingkat oksidasi yang berbeda terdapat dalam kebanyakan tumbuhan. Flavon
adalah bentuk yang mempunyai cincin C dengan tingkat oksidasi paling
rendah dan dianggap sebagai struktur induk dalam nomenklatur kelompok
senyawa-senyawa ini. (Manitto, 1981). Senyawa flavonoid sebenarnya
terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit,
tepung sari, bunga, buah, dan biji. Kebanyakan flavonoid ini berada di
dalam tumbuh-tumbuhan, kecuali alga. Namun ada juga flavonoid yng
terdapat pada hewan, misalnya dalam kelenjar bau berang-berang dan
sekresi lebah. Dalam sayap kupu - kupu dengan anggapan bahwa flavonoid
berasal dari tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan hewan tersebut dan
tidak dibiosintesis di dalam tubuh mereka. Penyebaran jenis flavonoid pada
golongan tumbuhan yang tersebar yaitu angiospermae, klorofita, fungi,
briofita. (Markham, 1988).
Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga
menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan
spektrum sinar tampak, umumnya dalam tumbuhan terikat pada gula yang
disebut dengan glikosida. (Harborne, 1996). Pada flavonoida O-glikosida,
satu gugus hidroksil flavonoid (atau lebih) terikat pada satu gula (lebih)
dengan ikatan yang tahan asam. Glukosa merupakan gula yang paling
umum terlibat dan gula lain yang sering juga terdapat adalah galaktosa,
ramnosa, silosa, arabinosa, dan rutinosa. Waktu yang diperlukan untuk
memutuskan suatu gula dari suatu flavonoid O-glukosida dengan hidrolisis
asam ditentukan oleh sifat gula tersebut. Pada flavonoid C-glikosida, gula
terikat pada atom karbon flavonoid dan dalam hal ini gula tersebut terikat
langsung pada inti benzena dengan suatu ikatan karbon-karbon yang tahan
asam. Gula yang terikat pada atom C hanya ditemukan pada atom C nomor
6 dan 8 dalam inti flavonoid, misalnya pada orientin. (Markham, 1988)
5. Antioksidan
Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan
yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif, mampu menghambat
terjadinya penyakit degeneratif, serta mampu menghambat peroksidase lipid
pada makanan (Sunarni 2005). Senyawa flavonoid diketahui mampu
berperan menangkap radikal bebasatau sebagai antioksidan alami (Amic et
al. 2003). Aktivitas antioksidan dari suatu bahan alam dapat diujidengan
berbagai metode diantaranya kemampuan mereduksi ion feri (FRAP), 1,1difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), dan kapasitas mereduksi kupri (CUPRAC)
(Pannangpetch et al.2007).
F. Metode penelitian
1. Kerangka konsep
Variabel terkendali
Sterilisasi alat, bahan
coba, dan media
Variabel bebas
Variabel terikat
Ekstrak cengkeh P1 125
mg/kgBB, P2 250 mg/kgBB
Jumlah osteoblas pada tulang
dan P3 500 mg/kgBB)
tibia tikus wistar pasca
ovariektomi
Variabel Tak
Terkendali
Kontaminasi bakteri
2. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris dengan
rancangan penelitian post test only control group design.
3. Lokasi penelitian
10
a. Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Taksonomi Tumbuhann
Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
b. Pembuatan ekstrak cengkeh dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
c. Laboratorium anatomi-histologi UGM yogyakarta
4. Variabel penelitian
a. Variabel bebas
Ekstrak cengkeh P1 125 mg/kgBB, P2 250 mg/kgBB dan P3 500
mg/kgBB
b. Variabel terikat
Jumlah osteoblas pada tulang tibia tikus wistar pasca ovariektomi
c. Variabel terkendali
Sterilisasi alat, bahan coba, dan media
d. Variabel tidak terkendali
Kontaminasi bakteri
5. Sampel penelitian
a. Teknik pengambilan sampel
Teknik randomisasi untuk pengelompokan perlakuan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) mengingat baik
hewan coba, bahan pakan, dan bahan penelitian lainnya adalah homogen.
Pada rancangan ini setiap hewan coba berpeluang sama untuk mendapat
kesempatan sebagai sampel baik dalam kelompok perlakuan maupun
dalam kelompok kontrol.
b. Besaran sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sediaan
tulang tibia kiri yang diambil dari tikus yang telah dihomogenkan jenis
kelaminnya, varietasnya, berat badannya dan usianya. Penelitian ini
menggunakan lima kelompok perlakuan (p=5), sehingga jumlah
pengulangan (jumlah sampel) yang dibutuhkan adalah minimal empat
kali pengulangan (jumlah sampel) untuk masing-masing kelompok.
Dalam penelitian ini digunakan lima ekor tikus untuk masing-masing
kelompok sehingga besar sampel secara keseluruhan adalah lima ekor
tikus dikali lima kelompok perlakuan, sehingga dibutuhkan 25 ekor tikus.
11
6. Ringkasan cara kerja
a. Pembuatan ekstrak cengkeh
Proses pembuatan ekstrak sampel dilakukan sebagai berikut:
Menggunakan metode maserasi. Sampel segar dicacah halus dan
ditimbang sebanyak 100 gram lalu dikeringkan dengan oven vakum pada
suhu 60 C dan tekanan 250 mmHg. Sampel segar yang sudah kering lalu
diblender, ditimbang sebanyak 25 gram, lalu dimasukkan ke dalam 150
gram pelarut (etanol). Cengkeh dan rempah bubuk dapat langsung
ditimbang sebanyak 25 gram dan dimasukkan ke dalam 150 gram pelarut
(etanol). Sampel dan pelarut lalu direfluks pada suhu 50 C selama dua
jam. Ekstrak yang diperoleh disaring dengan filter vakum dan sampel
dicuci sebanyak dua kali dengan masing-masing 50 gram etanol,
sehingga total etanol (pelarut) yang digunakan sebanyak 250 gram.
Ekstrak hasil refluks lalu dipekatkan dengan rotavapor pada suhu 50oC
selama kurang lebih 50 menit hingga volumenya kurang dari 10 ml.
Ekstrak yang diperoleh dimasukkan dalam labu takar 10 ml yang telah
ditimbang terlebih dahulu berat kosongnya lalu ditera dengan
menambahkan bilasan labu rotavapor agar tidak ada ekstrak pekat yang
tertinggal di dalam labu rotavapor. Setelah ekstrak beserta labu takar
ditimbang, ekstrak dituang ke dalam botol atau vial. Ekstrak lalu
disimpan di dalam lemari es dan siap digunakan.
b. Pemberian ekstrak cengkeh
1) Tikus diadaptasikan di labolatorium dengan cara dikandangkan, diberi
pakan standar dan minum selama 7 hari.
2) Secara random binatang percobaan dibagi 5 kelompok, tiap kelompok
terdiri dari 5 tikus. Kelompok pertama adalah tikus normal (kontrol
negatif), kelompok kedua adalah tikus yang di ovariektomi dan di
pertahankan selama 6 minggu (kontrol positif), kelompok ketiga tikus
yang di ovariektomi di pertahankan selama 1 bulan dan di beri ekstrak
cengkeh dengan dosis 125mg/kgBB (perlakuan 1), kelompok ke
empat yang diovariektomi di pertahankan selama 1 bulan dan di beri
ekstrak cengkeh dengan dosis 250mg/kgBB (perlakuan 2), kelompok
12
ke lima yang diovariektomi di pertahankan selama 1 bulan dan di beri
ekstrak cengkeh dengan dosis 500mg/kgBB (perlakuan 3).
3) Tikus diovariektomi dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum diberi
ekstrak kakao selama 30 hari.
4) Pemberian ekstrak di-lakukan secara per oral pada pagi hari (pukul
07.00) selama 4 minggu pada kelompok perlakuan (P1, P2, P3)
masing-masing dengan dosis yang berbeda. Setelah adanya perlakuan,
tikus dieuthanisia kemudian dilakukan penghitungan jumlah sel
osteoblas.
5) Sel osteoblas pada preparat histologi tulang tibia dengan pewarnaan
Hematoksilin-Eosin de-ngan pemeriksaan mikroskop berupa sel
berbentuk kubus berinti satu yang berada di endosteum dengan
sitoplasma yang basofilik. Penentuan rata-rata sel osteoblas dilakukan
secara manual dengan menghitung sel osteoblas melalui preparat
histologis dibawah pemeriksaan mikroskop dengan pembesaran 400x
dan dihitung per empat lapangan pandang.
7. Metode analisis
Dilakukan uji normalitas data untuk menginterpretasikan apakah
suatu data memiliki sebaran normal atau tidak. Uji homogenity of varience
untuk menguji berlaku atau tidaknya asumsi ANOVA, yaitu data yang
diperoleh dari setiap perlakuan memiliki varian yang homogen. Jika
didapatkan varian yang homogen, maka analisa dapat dilanjutkan dengan uji
ANOVA. dilanjutkan uji Post Hoc berupa uji Least significance difference
(LSD) untuk menganalisis perbedaan yang signifikan antara kelompok
kontrol dan kelompok gel ekstrak rumput laut dengan dosis 125mg/kgBB,
250mg/kgBB, dan 500mg/kgBB. Untuk mengetahui hubungan antara
pemberian ekstrak cengkeh dengan peningkatan jumlah sel osteoblas
digunakan uji korelasi pearson. Uji ini digunakan untuk membuktikan
korelasi antara peningkatan dosis ekstrak cengkeh terhadap jumlah
osteoblas tulang tibia tikus wistar.
13
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)