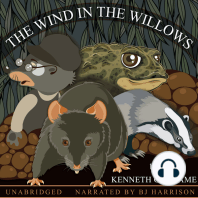MKP Tugas
MKP Tugas
Diunggah oleh
Imaz IswandariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
MKP Tugas
MKP Tugas
Diunggah oleh
Imaz IswandariHak Cipta:
Format Tersedia
Diduga dapat menimbulkan hilangnya unsur yang berupa items, traits, traits
complex, atau cultural activities itu sendri. Kegiatan pendidikan dalam kelima
lembaga penddikan yang menghadapi masalah akulturasi kebudayaan dapat
dipelajari dari berbagai sudut pandang ilmu.
3 praktek pendidikan dan keilmuan pendidikan di Indonesia
Dalam kegiatan pendidikan ditemukan unsur-unsur yang berupa (i) pendidik, seorag
yang bertindak mendidik seseorang dalam rangka mendidikkan suatu perilaku, ilmu
pengetahuan, kesenian, moral, nilai, dan symbol. Dalam tindak mendidik seorang
pendidik mengupayakan kemajuan domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor,
(ii) terdidik, seorang subyek yang terkena tindakan mendidik. Sang terdidik adalah
seseorag yang berbakat rasional dan non rasional yang berjiwa, berkepribadian
emansipatoris, dan melakukan identifikasi (pasif, aktif, kritis) bertujuan untuk
memiliki kepribadian sendiri yang unik. (iii) tujuan pendidikan, dari sisi pendidik
tujuan pendidikan merupakan hal-hal yang ideal, suatu idealisasi kemanusiaan pada
zaman tertentu. Idealisasi kemanusiaan dapat diperoleh dari agama, filsafat, dan
nilai kebudayaan. Dari sisi sang terdidik, tujuan pendidikan bersumber dari
pengalaman individualnya, keinginan, kemauan, dan cita-citanya. Kemauan dan
cita-cita sang terdidik akan berpengaruh pada gerak identifikasinya, nisbi
ketergantunagn kemandirian individualnya, dan tekanan mendidik sang pendidik,
yang terumus sebagai ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri
andayani. (iv) terkait dengan tujuan pendidikan adalah hal isi pendidikan. Isi
pendidikan pada dasarnya adalah usur-unsur kebudayaan yang terpilih dan bernilai
yang berwujud benda, perilaku, idea, norma, nilai, dan symbol. Isi pendidikan
tergantung pada kemajuan sesuatu kebudayaan. (v) dalam interaksi antara pendidk
dan anak didik ditemukan adanya kewibawaan pendidikan identifikasi pendidikan.
Baik kewibawaan pendidikan maupun identifikasi pendidikan bersegi dua, bersifat
berbanding terbalik, dan berakhir denagn kemandirian sang terdidik.
LANDASAN PENDIDIKAN
Kemandirian sang terdidik merupakan batas akhir kegiatan pendidikan, suatu ujung
perjalanan yang bermula dari ketidakberdayaan sang terdidik. Praktek pendidikan
sudah lama berlangsung dalam masyarakat Indonesia, sejalan dengan kemajuan
kebudayaan Indonesia. Berkat adanya pengalaman kependidikan tersebut tiap
kebudayaan memiliki pengetahuan untuk melakuakan tindak mendidik. Kegiatan
pendidikan merupakan bagian integral kebudayaan. Pada satu sisi, kegiatan
pendidikan akan melestarikan unsur-unsur kebudayaan yang baik dan bernilai. Pada
sisi lain, terdapat unsur yang berupa benda, perilaku, norma, idea, nilai, dan simbol.
Adanya praktek pendidikan dalam suatu masyarakat tidak secara otomatis
menunjukkan bahwa praktek pendidikan berpijak dari pemikiran keilmuan
pendidikan. Sebab praktek pendidikan didasarkan pada (i) pemikiran berdasar akal
sehat semata-mata, (ii) pemikiran awam atas pengalaman hidup, (iii) pemikiran
berdasar wawasan agama. Secara sosiologis terbukti bahwa timbulnya ilmu
pengetahuan (dalam hal ini keilmuan pendidikan) berkat adanya tantangan
kebutuhan obyektif masyarakat, dan adanya individu atau kelompok individe
berbakat, yang berdedikasi dalam memecahkan masalah untuk memenuhi
kebutuhan obyektif masyarakat. Pemikiran keilmuan merupakan gejala universal,
dan dalam pemikiran keilmuan tersebut dapat dibedakan adanya subyek pemikir
dan obyek terfikir. Sebagai gejala universal, pemikiran keilmuan baru terjadi dalam
kebudayaan yang berada dalam tahap ontologis.
Menurut Suwarno (1993) pertumbuhan kebudayaan dan pembentukan nilai budaya
Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa tahap sebagai berikut. (i) pertumbuhan
nilai budaya Indonesia dalam zaman sejarah kerajaan di nusantara pada tahun 4001500-an. Pada saat ini terbentuklah kerajaan kutai, sriwijaya, dan Majapahit. (ii)
identifikasi nilai-nilai budaya Indonesia pada tahun 1500-18000-an. Pada saat ini
muncullah kerajaaan-kerajaan lokal seperti Mataram II, Makasar, Aceh, dan Tidore.
Unsur kebudayaan yang diadaptasi oleh kebudayaan Indonesia antara lain adalah
lembaga sekolah, dalam arti tentara portugis membuat gedung sekolah di Ternate
pada tahun 1538-an. Sekolah ini kemudian dikelola oleh ordo Je suits (Kroeskamp,
1974:8). (iii) idealisasi nilai-nilai budaya Indonesia pada tahun 1800-1942. Dalam
periode ini Belanda berhasil membentuk pemerintah Hindia Belanda dan
memperkenalkan birokrasi pemerintahan yang merupakan kepanjangan dari
birokrasi pemerintahan kerajaan Belanda di Belanda. Belanda mentransformasikan
nilai-nilai barat ke Indonesia lewat pemerintahan, perdagangan, system ekonomi
dengan cultur stelsel tahun 1970-an, dan system persekolahan untuk membentuk
masyarakat industri. Birokratisasi pemerinthan Hindia Belanda tidak menghapuskan
seluruh unsur kebudayaan nusantara. Kesenian, kesusasteraan, kerajinan, pencak
silat, bahasa daerah masih dibiarkan. Dengan politik etis awal abad ke-20, maka
perluasan sekolah dalam kerangka sistem pendidikan yang dualistis
diselenggarakan. Muncullah kelompok-kelompok terpelajar yang melakukan
idealisasi nilai-nilai budaya Indonesia. Kelompok terpelajar inilah yang kemudian
bangkit menjadi perintis yang memperjuangkan kemajuan bagi Hindia, (iv)
idealisasi nilai-nilai budaya Indonesia tahun 1942-1945, suatu periode perumusan
pancasila sebagai dasar Negara Indonesia merdeka. Pada periode ini bangsa
Indonesia dibawah pemerintahan jepang. Jepang membagi Indonesia menjadi tiga
wilayah administrative, seperti (i) wilayah Tentara Keenambelas di Jawa & Madura
dengan pusatnya di Jakarta, (ii) wilayah tentara keduapuluh Lima di Sumatera
dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi, dan (iii) wilayah Armada seltan kedua
meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusat
pemerintahan di Makasar. Pada periode ini dualisme system pendidikan dan
pengajaran dihapuskan dan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar
pendidikan.
Pemikiran keilmuan pendidikan di Indonesia tidak terpisah dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada kebudayaan dunia. Adaptasi lembaga sekolah di
Ternate tahun 1538 merupaka awal akulturasi sistem persekolahan Eropa. Sistem
sekolah di Eropa merupakan sistem pendidikan keilmuan masyarakat industri.
Sistem sekolah berusaha membakukan segala komponen pendidikan. Penemuan
alat cetak, dan mesin-mesin yang menimbulkan revolusi industry di Eropa
berpengaruh pada sistem sekolah dan akulturasi pendidikan di Indonesia. Akulturasi
kebudayaan dapat dilukiskan dalam Bagan 03 halaman berikut.
Bagan 03 melukiskan pertumbuhan dan perkembangan nilai kebudayaan Indonesia
serta perkembangan pemikiran keilmuan pendidikan Indonesia sebagai berikut.
Kegiatan pendidika adalah bagian integral suatu kebudayaan. Kegiatan pendidikan
dapat digolongkan sebagai suatu unsur cultural-activity dan specialty, sebab
kegiatan tersebut menuntut suatu keahlian dan kebijaksanaan eksistensial
emansipatoris. Kegiatan pendidikan adalah hal praktis, yang menuntut alasan dasar
tindakan yang berupa jawab terhadap pertanyaan mengapa bertindak A dan bukan
B. kegiatan pendidan mengolah kemajuan generasi muda, suatu rentang usia
0;0;1-18;0;0 atau lebih yang dikategorikan dewasa. Dengan demikian kegiatan
pendidikan mengupayakan terbentuknya pendukung kebudayaan yang muda usia
sebagai spesialis. Dalam hal ini kebudayaan Indonesia berhubungan dengan
kebudayaan Eropa dan kebudayaan asing lain. (i) kebudayaan Eropa mengalami
tahap mitis (lebih kurang 200.000 SM-abad 5 SM), tahap ontologis (abad % SM-19
Masehi),
Dan tahap fungsional (abad 19/20-sekarang). Untuk pertama kali terjadilah
globalisasi agama di dunia yang memperbaharui kebudayaan mitis. Tahap ontologis
ditandai oleh munculnya pemikiran-pemikiran filsafat yang bermula dari Eropa
(Yunani). Sejak abad 5 SM timbullah aliran-aliran filsafat seperti aliran kosmologi,
empirisme, rasionalisme, Thomisme, Kantianisme, Hegelianisme, historisme,
evolusionisme, irrasionalisme, vitalisme, spiritualisme, neopositivisme,
pragmatisme, personalisme, fenomenologi, existensialisme, dan post-modernisme.
Aliran filsafat tersebut jga mengembangkan cabang-cabang filsafat seperti
epistemology, etika, aestetika, metodologi, dan ogika, serta melakukan studi-studi
khusus seperti teologia, antropologi, filsafat kebudayaan, filsafat pendidikan, yang
juga mendorong timbulnya ilmu pengetahuan otonom.
Disiplin ilmu pengetahuan yang muncul antara lain adalah ilmu fisika (abad XVIII),
ilmu ekonomi, (Adam Smith 1723-1790), ilmu politik (Francis Lieber, 1858), sosiologi
(August Comte, 1798-1857), antropologi (Lewis Henry Morgan 1858-1881), geografi
(Alexander von Humbooldt,1769-1859), ilmu sejarah (JB Bury, 1903), psikologi
(Wilhelm Wundt,1832-1920), paedagogiek (1925-an), kurikulum (Franklin Bobbitt,
1918), teknologi pendidikan (James Finn, 1961), teknologi pembelajaran
(instructional technologi, 1972). Disamping itu kebudayaan Eropa, yang
menyimpang dari pola umum perkembangan, juga menciptakan sistem-sistem
seperti industri, perbankan, ke-kota-an, persekolahan, ke-teknikan modern,
kapitalisme, imperalisme modern, nasionalisme, sistem politik modern, dan sistemsistem lain yang modern. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi modern, dan
sistem-sistem lain dapat terjadi berkat adanya kegiatan penelitian keilmuan yang
dilakuakan oleh para ilmuan yang berdedikasi tinggi, dan tidak mengenal lelah.
Terjadinya difusi unsur kebudayaan Eropa ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian
menciptakan globalisasi kebudayaan dunia dengan pusatnya Eropa dan Negara
maju lain. (ii) pada sisi lain, kebudayaan Indonesia mengalami pertumbuhan dan
perkembangan tersendiri. Kebudayaan Indonesia bermula dari munculnya
homosapiens di nusantara pada kurang lebih 80.000 tahun SM. Menurut Suwarno
(1993) perkembangan kebudayaan Indonesia dapat
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)