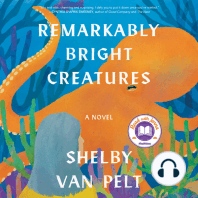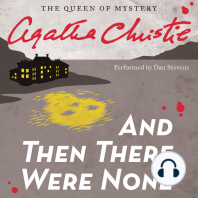Surau Dalam Rumah Keluarga Madura
Diunggah oleh
Raziq HasanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Surau Dalam Rumah Keluarga Madura
Diunggah oleh
Raziq HasanHak Cipta:
Format Tersedia
Kalau orang Madura disebut sebagai muslim yang kolot, taat, fanatik dan selalu
menempatkan kesenian atau seluruh perangkat kebudayaan yang bercirikan Islam
sebagai yang tertinggi, sebagaimana banyak ditulis oleh para sosiolog, antropolog
maupun etnolog Madura sebutlah John Smith, Anke Neihof, Roy Jordaan, Ellen Town
Bousma, Helena Bouvier atau Kuntowijoyo.
Tentu bukan hanya karena hasrat masyarakatnya yang menggelegak untuk segera
melunaskan ibadah haji dan kemudian merasa alim dan jeri dari tingkah dosa dengan
tambahan gelar Haji di depan namanya. Sekalipun untuk itu mereka rela menjual
rumah, tanah, kendaraan atau apapun harta yang dimilikinya sampai tak ada lagi
yang tersisa. Sehingga banyak para materialist meremehkan mereka sebagai orang
yang tidak rasional dan memutus harapan masa depan.
Juga bukan karena para lelakinya yang kemana-mana bangga dengan hanya selalu
memakai kopiah dan sarung, pakaian wajib untuk menunaikan sholat. Atau
perempuannya cukup dengan baju kutobedah dan kerudung menutupi kepalanya demi
menyimpan aurat sebagaimana diperintahkan Islam.
Juga tentu saja bukan karena masyarakatnya yang sangat maklum bila banyak di
antara para lelakinya punya istri hingga empat orang sebagaimana dipercaya sebagai
sunnah Rasulullah. Dan para perempuannyapun tak hirau harus hidup serumah dengan
para madunya. Baginya punya anak dan membesarkannya dengan penuh tanggung jawab
dua pihak adalah akhir dari cinta. Dan mereka tak kurang sejumputpun cinta lelaki
suami diantara riuhnya perempuan yang dinikahinya. Tak ada ruang untuk saling iri.
Justru mereka sukarela untuk saling bekerja sama membesarkan anak-anak keluarga
besar mereka dengan damai dan cinta kasih.
Lalu mengapa? Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat yang sangat Islami?
Sudah tamat saya keliling seluruh Indonesia mengamati seluruh arsitektur dan
keterkatannya dengan kondisi sosio kultural masyarakatnya. Sudah pula kami amati
bagaimana manusia dan masyarakatnya berinteraksi dengan ruang-ruang yang
dibangunnya di atas hamparan bumi Ilahi. Dari ujung pulau Barat di seberang
Malahayati hingga ke Timur di Merauke. Bahkan di negeri mashur tempat puncak
kejayaan Islam dan di seluruh literatur arsitektur Islam yang sempat saya baca.
Tidak ada satupun tempat sebagaimana rumah tradisional masyarakat Madura yang
menjadikan surau sebagai elemen penting yang harus ada melebihi fungsi bangunan
lainnya.
Surau di dalam perkampungan rumah tradisional Madura adalah bangunan kedua yang
selalu di bangun sesudah rumah induk (roma tongghu). Biasanya selalu ditempatkan
di sebelah Barat atau arah kiblat. Dan di depannya terhampar tanean lanjhang
(halaman yang panjang) yang terbentuk karena perkembangan pembangunan rumah
selanjutnya yang dibangun berjejer berturut-turut di sebelah rumah induk untuk
anak-anak perempuan dan keluarganya.
Perletakan surau betul-betul menjadi sumbu utama yang mengikat keseluruhan
bangunan di dalam satuan komunitas (soma) keluarga-keluarga besar Madura. Surau
biasanya selain untuk sholat dan mengaji juga dijadikan tempat tidur anak lelaki
mereka yang belum berkeluarga dan para tamu lelaki yang datang menginap. Pada
titik ini surau telah menjadi ruang transisi atau ruang antara yang memisah gender
lelaki dan wanita. Suatu taktik jitu untuk menghindarkan nista. Tanpa disadari
tamu pun mahfum bahwa ruang mukim Madura sedemikian rupa di jenjang dalam tahap-
tahap yang sistematik. Antara ruang publik dan ruang privat, ruang lelaki dan
ruang wanita, ruang profan dan ruang sakral, ruang anak dan ruang tetua, ruang
keluarga sendiri (oreng dhibi’) atau bukan (oreng laen). Semuanya memiliki
tatakrama-nya sendiri.
Secara visual dan audial, surau membangun atmosfir Islami yang sangat sempurna.
Bentuk atap yang lancip dengan lantai agak lebih tinggi dari bangunan lain
menjadikan surau bagai pemimpin di tengah massa yang lain. Lima kali sehari
suaranya mengumandangkan azdan setiap menjelang waktu solat. Anak-anak tanpa diaba
saling berebut untuk menjadi muadzin dan bergegas meninggalkan apapun yang sedang
mereka kerjakan. Pun para orang tua juga hirau meninggalkan apapun kegiatannya
untuk berjamaah dan memimpin anak-anak mereka tunaikan solat. Dan sesekali
diberinya kesempatan remaja mereka yang mulai fasih melafadz sedikit al-Qur’an
untuk menjadi imam dan merasai peran kepemimpinan yang akan dipikulnya kelak.
Ketika fajar menyingsing, surau mulai meneriakkan ajakan subuh bersama. Itulah
waktu pertama dimulainya hari hidup ke depan sebelum anak-anak mereka bergegas
menuntut ilmu dan para orang tua mengais rahmat Allah. Ketika terik langit
tergelincir dari puncaknya, dhuhur segera ditegakkan. Sesudahnya, sanak keluarga
berkumpul untuk sekadar makan siang dalam keriuhan bersama. Lalu merekapun
istirahat sejenak sampai cahaya matahari telah lepas dan bayangannya melebihi
panjangnya benda, petanda ashar telah tiba. Sesudahnya riuh anak berlarian
diantara pandangan kasih sanak keluarganya di tengah tanean lanjang yang
bersinggungan dengan beranda rumah-rumah yang berjejer. Dan ketika langit merah
telah usai ditimpa bulan yang masuk ke semburat langit seluruh keluarga dan
berayat bergegas siap mengambil tempat untuk berebut shaf paling depan dalam
barisan jemaah maghrib. Dan sesudahnya anak-anak mereka reriung belajar membaca
al-Qur’an pada orang tua pemimpin mereka sampai saat Isya tiba. Di tengah temaram
lentera riuh ayat demi ayat membubung ke langit sunyi tempat semayam para
malaikat.
Demikianlah masa demi masa berlalu dengan penuh pembinaan dan hikmah. Surau telah
mengambil peran yang begitu penting dalam hidup orang Madura. Keheningaannya
mengumandangkan nuansa Islami yang sempurna sejak hidup dijejak sampai ajal
menjemput. Penghuni pemukiman itu datang silih berganti bersamaan dengan usainya
batas usia mereka. Dan surau itu masih saja setia menunaikan tugasnya… the truly
Islamic semiotica…
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20024)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3277)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5507)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)








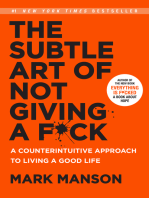



![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)