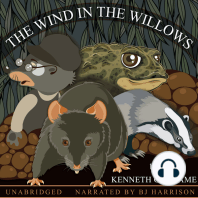Case 3 KV
Case 3 KV
Diunggah oleh
melovevyaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Case 3 KV
Case 3 KV
Diunggah oleh
melovevyaHak Cipta:
Format Tersedia
Penyakit Jantung Koroner!!
Penyakit Jantung Koroner (PJK) atau disebut juga Ischemic Heart Disease (IHD) adalah penyakit jantung yang disebabkan karena kelainan pembuluh darah koroner. Salah satu penyebab utamanya adalah aterosklerosis koroner. Aterosklerosis adalah penyakit arteri yang berkembang secara perlahan, dengan penebalan tunika intima yang terjadi akibat disfungsi endotel, inflamasi vaskular, terbentuknya lipid kolesterol, kalsium, dan debris seluler pada dinding pembuluh darah. Pembentukan ini akan menghasilkan plak, remodelling pembuluh darah, obstruksi lumen pembuluh darah akut dan kronik, abnormalitas aliran darah dan menurunnya suplai oksigen ke organ target.1,2 PATOGENESIS Penyebab aterosklerosis hingga saat ini belum ditentukan secara pasti, akan tetapi teori yang paling mendekati adalah teori kerusakan endotel. Rusaknya endotel kemungkinan disebabkan karena kolesterol LDL yang teroksidasi, agen infeksius, rokok, hiperglikemi, dan hiperhomocystenemia. Akibat oksidasi LDL, monosit akan masuk ke dalam tunika intima dan diubah menjadi makrofag. Proses ini akan melepaskan radikal 02 yang reaktif, terutama anion superoksida 02- (juga dibantu oleh homocystein) yang merusak sel endotel dan mengakibatkan NO yang dibentuk oleh endotel kehilangan aktivitasnya untuk menghambat adhesi trombosit dan monosit di endotel serta efek anti proliferative serta vasodilatasi otot pembuluh darah.1,2,3 Penghambatan vasodilatasi akan mendorong terjadinya spasme. Bahkan pada stadium awal, LDL akan merangsang ekspresi molekul adhesi yang memungkinkan pembuluh darah berploriferasi. Oksidasi juga menyebabkan perubahan ikatan LDL. LDL tidak lagi dikenali oleh reseptor Apo B 100 namun dikenali oleh scavenger receptor yang sebagian besar terdapat di makrofag. Akibatnya makrofag banyak memfagosit LDL dan akan berubah menjadi sel busa yang menetap. Lipoprotein(a) dapat dioksidasi dan difagosit melalui cara yang sama. Secara bersamaan, faktor kemotaksis monosit dan trombosit akan memicu perpindahan sel otot polos dari media ke intima. Di intima, sel tersebut akan dirangsang berploriferasi oleh PDGF dan berbagai faktor pemicu pertumbuhan lainnya. Sel otot juga akan diubah menjadi sel busa dengan mengambil LDL teroksidasi. Sel busa akan membentuk matriks ekstrasel yang juga berperan dalam pembentukan ateroma. 1,2,3 Perubahan patologis yang terjadi pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan dapat diringkas sebagai berikut:4 1. Dalam tunika intima timbul endapan lemak dalam jumlah kecil yang tampak bagaikan garis lemak. 2. Penimbunan lemak, terutama beta-lipoprotein yang mengandung banyak kolesterol pada tunika intima dan tunika media bagian dalam. 3. Lesi yang diliputi jaringan fibrosa menimbulkan plak fibrosa. 4. Timbul ateroma atau kompleks plak aterosklerotik yang terdiri dari lemak, jaringan fibrosa, kolagen, kalsium, debris selular, dan kapiler. 5. Perubahan degeneratif dinding arteria. Meskipun penyempitan lumen berlangsung progresif dan kemampuan vaskular untuk memberikan respon juga berkurang, manifestasi klinis penyakit belum tampak sampai proses ini sudah mencapai tingkat lanjut. Fase preklinis ini dapat berlangsung sampai 20-40 tahun. Lesi yang bermakna secara klinis, yang dapat mengakibatkan iskemik dan disfungsi miokardium biasanya menyumbat lebih dari 75% lumen pembuluh darah. Langkah akhir proses patologis yang menimbulkan gangguan klinis dapat terjadi dengan cara: penyempitan
lumen progresif akibat pembesaran plak, perdarahan akibat pembesaran plak, perdarahan pada plak ateroma, pembentukan thrombus yang diawali oleh agregasi trombosit, embolisasi thrombus atau fragmen plak, dan spasme arteri koronaria.4 Akibat penumpukan plak selain penyempitan lumen adalah kalsifikasi (kekakuan dinding pembuluh darah), emboli perifer akibat trombus, penyempitan tambahan oleh hematoma. Karena melemah, dinding dapat melebar (aneurisma) dan bahkan mengalami ruptur dengan menimbulkan perdarahan yang berbahaya ke jaringan sekitar.1,3. Lesi-lesi aterosklerotik biasanya berkembang pada segmen epikardial proksimal dari arteri koronaria, yaitu pada tempat lengkungan yang tajam, percabangan, atau perlekatan. 4 FAKTOR RISIKO Aterosklerosis bukan semata-mata karena penuaan. Timbulnya bercak-bercak lemak pada dinding arteri koronaria bahkan sejak masa kanak -kanak sudah merupakan fenomena alamiah dan tidak selalu harus menjadi lesi aterosklerotik. Faktor risiko yang tak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Penyakit yang serius jarang terjadi sebelum usia 40 tahun. Tetapi hubungan antara usia dan penyaakit ini mungkin hanya mencerminkan lama paparan yang lebih panjang terhadap faktor-faktor aterogenik. Wanita lebih kebal sampai setelah menopause, dan kemudian menjadi sama rentannya dengan pria. Efek perlindungan estrogen dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas ini. Orang Amerika-Afrika lebih rentan terhadap aterosklerosis daripada orang kulit putih. Akhirnya, riwayat keluarga yang positif terhadap PJK yang menderita penyakit ini sebelum 50 tahun meningkatkan kemungkinan timbulnya atrosklerosis premature. Besarnya pengaruh genetik dan lingkungan belum diketahui. Komponen genetik dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk aterosklerosis yang nyata, atau yang cepat berkembangnya, seperti pada gangguan lipid familial. Faktor risiko tambahan lain yang masih dapat diubah yang termasuk golongan mayor adalah:1,2,3,4 peningkatan kadar lipid serum(hiperlipidemia) kadar kolestrol serum >265 mg/dl pada orang berusia 35-40 tahun meningkatkan risiko jantung koroner hinggan 5 kali lipat dibandingkan dengan kadar<220 mg/dl. Sekitar 70% dari kolestrol ini akan ditranspor dalam bentuk LDL . hipertensi:meningkatkan infiltrasi LDL dengan meningkatkan tekanan hidrostatik dan perusakan endothelial. merokok: adanya pengaruh nikotin terhadap pelepasan katekolamin oleh sistem saraf otonom. Tetapi efek nikotin tidak kumulatif. Merokok dapat merangsang pergantian O2 dalam Hb dengan CO, peningkatan daya lekat trombosit dan peningkatan permeabilitas endotel yang dirangsang oleh unsur pokok dalam rokok. Merokok juga dapat meningkatkan oksidasi LDL dan inflamasi dinding arteri. Merokok 1 bungkus sehari akan meningkatkan risiko IHD 3 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok. gangguan toleransi glukosa/DM: berhubungan juga dengan hipertensi, kelainan pembekuan, adhesi trombosit serta meningkatkan stress oksidatif dan disfungsi endotel. diet tinggi lemak jenuh, kolesterol dan kalori/obesitas:obesitas meningkatkan beban kerja jantung dan kebutuhan akan O2. Yang termasuk golongan minor adalah gaya hidup, stress, dan tipe kepribadian.4
Bentuk akibat dari arterosklerosis adalah: angina pectoris stabil dan tidak stabil, infark miokardium, dan sudden death akibat vibrilasi dari ventrikel.3 ANGINA PEKTORIS STABIL5,6 Angina pektoris adalah rasa nyeri yang timbul karena iskemia miokardium. Biasanya mempunyai karakteristik tertentu : - Lokasinya biasanya di dada, substernal atau sedikit di kirinya, dengan penjalaran ke leher, rahang, bahu kiri sampai dengan lengan dan jari-jari bagian ulnar, punggung/pundak kiri. - Kualitas nyeri biasanya merupakan nyeri yang tumpul seperti rasa tertindih/berat di dada, rasa desakan yang kuat dari dalam atau dari bawah diafragma, seperti diremas-remas dan pada keadaan yang berat biasanya disertai keringat dingin. Nyeri berhubungan dengan aktivitas, stres fisik ataupun emosional, dan hilang dengan istirahat. - Kuantitas : Nyeri yang pertama sekali timbul biasanya agak nyata, dari beberapa menit sampai kurang dari 20 menit. Nyeri tidak terus menerus, tapi hilang timbul dengan intensitas yang makin bertambah atau makin berkurang sampai terkontrol. Pada angina pektoris stabil, nyeri dada yang awalnya agak berat, berangsur-angsur turun kuantitas dan intensitasnya dengan atau tanpa pengobatan, kemudian menetap (misalnya beberapa hari sekali, atau baru timbul pada beban/stres yang tertentu atau lebih berat dari sehari-harinya). Angina pektoris stabil biasanya disebabkan oleh penyempitan aterosklerotik tetap (biasanya 75% atau lebih) satu atau lebih arteri koronaria. Peningkatan tahanan proksimal ini masih dapat diatasi oleh dilatasi arteriol, yaitu reduksi tahanan perifer di cabang-cabang intramiokardial dari arteri koronaria. Dengan demikian aliran koroner dapat memenuhi kebutuhan normal. Pemeriksaan penunjang - Foto toraks dapat melihat kalsifikasi koroner ataupun katup jantung. - Ekokardiografi untuk memperlihatkan ada tidaknya aterosklerosis yang signifikan atau kardiomiopati hipertrofik. Selain itu dapat pula menentukan luasnya iskemia bila dilakukan saat nyeri dada sedang berlangsung. - Angiografi koroner bermanfaat untuk stratifikasi prognostik, yang berkorelasi dengan jumlah pembuluh darah yang mengalami stenosis. Penatalaksanaan : Tujuan pengobatan terutama adalah mencegah kematian dan terjadinya serangan jantung (infark). Sedangkan yang lainnya adalah mengontrol serangan angina sehingga memperbaiki kualitas hidup. Penatalaksanaan terdiri dari : Non farmakologis yaitu : penurunan BB, perubahan life style (seperti berhenti merokok), lahraga teratur, penyesuaian diet. Farmakologis : - Pengobatan Kolesterol. Penurunan secara agresif dari Low-density Lipoprotein (LDL) atau colesterol jahat dapat memperlambat, menghentikan atau me-reverse pembentukan deposit lemak dalam pembuluh darah arteri. Meningkatkan High-density Lipoprotein (HDL) atau colesterol yang baik juga akan membantu perbaikan pembuluh arteri dari penumpukan/deposit lemak. Dokter akan memilih jenis pengobatan colesterol untuk seperti obat dari jenis Statin dan Fibrat. - Aspirin. Penggunaan aspirin atau pengencer darah lainnya setiap hari dapat mengurangi tendensi butir darah untuk menggumpal/membeku yang mana hal ini akan mencegah penyumbatan pembuluh darah arteri koroner. Apabila mengalami serangan jantung maka aspirin dapat membantu mencegah serangan jantung ulangan.
- Beta-Blocker. Jenis obat ini akan memperlambat denyutan jantung dan akan menurunkan tekanan tinggi sehingga akan menurunkan kebutuhan akan oksigen dari jantung. Apabila mendapat serangan jantung, Beta-Bloker juga akan mencegah serangan jantung ulangan. - Nitrogliserin. Tablet, spray atau plester Nitrogliserin dapat mengontrol nyeri dada dengan cara melebarkan pembuluh darah koroner sehingga akan menurunkan kebutuhan jantung akan oksigen. - Angiotensin-Converting Enzyme (ACE). Obat ini akan menurunkan tekanan darah tinggi dan dapat menolong mencegah progresivitas penyakit jantung koroner. Apabila mendapat serangan jantung, penghambat ACE ini akan mencegah resiko serangan jantung ulangan. - Antagonis Ca atau nitrat jangka panjang dan kombinasinya untuk tambahan beta blocker apabila ada kontraindikasi atau efek samping yang tidak dapat ditolelir. Reperfusi miokardium : Intervensi koroner dengan balon dan pemakaian stent sampai operasi CABG. ANGINA PEKTORIS TAK STABIL.7 Gejala klinik dari angina pektoris tidak stabil yaitu : - Pasien dengan angina yang masih baru dalam 2 bulan, dimana angina cukup berat dan frekuensi cukup sering, lebih dari 3 kali/hari. - Pasien dengan angina stabil yang makin bertambah berat, lalu serangan angina timbul lebih sering, lebih berat. - Pasien dengan serangan angina pada waktu istirahat. - Dapat disertai mual, muntah, kadang disertai keringat dingin. Patogenesis - ruptur plak Ruptur dari plak aterosklerotik dianggap penyebab terpenting dari angina pektoris tak stabil, sehingga tiba-tiba terjadi oklusi subtotal atau total dari pembuluh koroner yang sebelumnya mempunyai penyempitan yang minimal. Plak yang tidak stabil terdiri dari inti yang banyak mengandung lemak dan adanya infiltrasi sel makrofag. Kadang-kadang keretakan terjadi pada dinding plak yang paling lemah karena adanya enzim protease yang dihasilkan makrofag dan secara enzimatik melemahkan dinding plak (fibrous cap). Terjadinya ruptur menyebabkan aktivasi, adhesi, dan agregasi platelet dan menyebabkan aktivasi terbentuknya trombus. Bila trombus menutup pembuluh darah 100% akan terjadi infark dengan elevasi segmen ST, sedangkan bila trombus tidak menyumbat 100%, dan hanya menimbulkan stenosis yang berat akan terjadi angina tidak stabil. - Trombosis dan agregasi trombosit Terjadinya trombosis setelah plak terganggu disebabkan karena interaksi yang terjadi antara lemak, sel otot polos, makrofag, dan kolagen. Sebagai reaksi terhadap gangguan faal endotel, terjadi agregasi platelet dan platelet mengeluarkan isi granulasi sehingga memicu agregasi yang lebih luas, vasokonstriksi dan pembentukan trombus. Faktor sistemik dan inflamasi ikut berperan dalam perubahan terjadinya hemostase dan koagulasi dan berperan dalam memulai trombosis yang intermitten, pada angina tidak stabil. - Vasospasme Diperkirakan adanya disfungsi endotel dan bahan vasoaktif yang diproduksi oleh platelet berperan dalam perubahan tonus pembuluh darah dan menyebabkan spasme. Adanya spasme seringkali terjadi pada plak yang tidak stabil dan mempunyai peran dalam pembentukan trombus.
- Erosi pada plak tanpa ruptur Adanya perubahan bentuk dan lesi karena bertambahnya sel otot polos dapat menimbulkan penyempitan pembuluh dengan cepat dan keluhan iskemia. Pemeriksaan penunjang - Exercise test Pasien yang menunjukkan risiko lebih tinggi perlu pemeriksaan exercise test dengan alat treadmill. Bila hasilnya negatif maka prognosis baik. Sedangkan bila hasilnya positif, terlebih jika didapatkan depresi segmen ST yang dalam, dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan angiografi koroner, untuk menilai keadaan pembuluh koronernya apakah memerlukan tindakan revaskularisasi. - Ekokardiografi Pemeriksaan ini sebenarnya tidak memberikan data untuk diagnosis angina tak stabil secara langsung. Tetapi bila tampak adanya gangguan faal ventrikel kiri, adanya mitral insufisiensi dan abnormalitas gerakan dinding regional jantung, menandakan prognosis yang kurang baik. - EKG Gambaran EKG saat istirahat dan bukan pada saat serangan angina sering masih normal. Gambaran EKG dapat menunjukkan bahwa pasien pernah mendapat infark miokard di masa lampau. Kadang-kadang menunjukkan pembesaran ventrikel kiri. Dapat pula menunjukkan perubahan segmen ST dan gelombang T yang tidak khas. Pada saat serangan, EKG akan menunjukkan depresi segmen ST dan gelombang T dapat menjadi negatif. - Pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan troponin T atau I, dan pemeriksaan CK-MB merupakan petanda paling penting. Penatalaksanaan Tindakan umum : pasien perlu perawatan di rumah sakit, diistirahatkan (bed rest), diberi penenang dan oksigen. Pemberian morfin atau petidin perlu pada pasien yang masih merasakan sakit dada walaupun sudah mendapat nitrogliserin. Terapi farmakologi : - Obat anti iskemia a. nitrat menyebabkan vasodilatasi pembuluh vena dan arteriol perifer, dengan efek mengurangi preload dan afterload sehingga dapat mengurangi wall stress dan kebutuhan oksigen. Nitrat juga menambah suplai oksigen dengan vasodilatasi pembuluh koroner dan memperbaiki aliran darah kolateral. Pembuluh darah kolateral memberikan rute alternatif perfusi miokard bila arteri koroner epikard mayor mengalami stenosis atau oklusi. Saluran ini dorman dalam keadaan normal namun dalam beberapa jam kolateral yang ada mengalami dilatasi dan mengembangkan karakteristik pembuluh darah matur. b. beta blocker menurunkan kebutuhan oksigen miokatdium melalui efek penurunan denyut jantung dan daya kontraksi miokardium. Contoh : propanolol, metoprolol, atenolol. c. antagonis kalsium vasodilatasi koroner dan menurunkan tekanan darah - Obat antiagregasi trombosit a. aspirin mengurangi kematian jantung dan mengurangi infark fatal maupun nonfatal pada pasien dengan angina tidak stabil.
b. tiklopidin merupakan obat lini kedua jika pasien tidak tahan aspirin, efek sama. c. klopidogrel menghambat agregasi platelet, mengurangi stroke, infark, dan kematian kardiovaskular. d. glikoprotein Iib/IIIa inhibitor ikatan fibrinogen dengan reseptor GP IIb/IIIa pada platelet ialah ikatan terakhir pada proses agregasi platelet. Karena GP IIb/IIIa inhibitor menduduki reseptor tadi maka ikatan platelet dengan fibrinogen dapat dihalangi dan agregasi platelet tidak terjadi. - Obat antitrombin a. Unfractionated heparin bersifat antikoagulan b. Low molecular weight Heparin (LMWH) antikoagulan, dibuat melalui depolarisasi rantai polisakarida heparin. - Direct thrombin inhibitors : bekerja langsung mencegah pembentukan pembekuan darah Tindakan revaskularisasi pembuluh koroner : Tindakan operasi bypass (CABG), angioplasti dan pemasangan stent (Percutaneous Coronary Revascularization), coronary brachytherapy, dan laser revascularization. INFARK MIOKARD Kebutuhan akan oksigen yang melebihi kapasitas suplai oksigen oleh pembuluh yang terserang penyakit menyebabkan iskemia miokardium lokal. Iskemia menyebabkan perubahan jalur metabolic gangguan fungsi ventrikel kirikekuatan kontraksi berkurangperbesaran ventrikel dan peningkatan tekanan jantung kiri. Iskemia miokardium secara khas ditandai oleh perubahan EKG akibat perubahan elektrofisiologi seluler, yaitu gelombang T terbalik dan aadanya depresi segmen ST. Elevasi segmen ST dikaitkan dengan sejenis angina yang dikenal dengan nama angina Prinzmetal. Serangan iskemia biasanya mereda dalam beberapa menit dan semua perubahan yang terjadi bersifat reversible. Iskemia yang berlangsung lebih dari 30-45 menit akan menyebabkan kerusakan seluler yang irreversible dan kematian otot atau nekrosis. Bagian miokardium yang mengalami infark akan berhenti berkontraksi secara permanen. Infark miokard biasa terjadi di ventrikel kiri, baik infark transmural maupun subendokordial. 4 INFARK MIOKARD AKUT DENGAN ELEVASI ST (STEMI)8 Patofisiologi STEMI umumnya terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak setelah oklusi thrombus pada plak arterosklerosis yang sudah ada sebelumnya. STEMI terjadi jika thrombus arteri koroner terjadi secara cepat pada lokasi injuri vaskuler, dimana injuri ini dicetuskan oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid. Pada sebagian kasus, infark terjadi jika plak aterosklerosis mengalami fisur, ruptur, atau ulserasi dan jika kondisi lokal atau sistemik memicu trombogenesis, sehingga terjadi trombus mural pada lokasi ruptur yang mengakibatkan oklusi arteri koroner. Penelitian histologis menunjukkan plak koroner cenderung mengalami rupture jika mempunyai fibrous cap yang
tipis dan inti kaya lipid (lipid rich core). Pada STEMI gambaran patologis klasik terdiri dari fibrin rich red thrombus. Selanjutnya pada lokasi rupture plak, berbagai agonis (kolagen, ADP, epinefrin, serotonin) memicu aktivasi trombosit, yang selanjutnya akan memproduksi dan melepaskan tromboksan A2 (vasokontriktor lokal yang poten). Selain itu, aktivasi trombosit memicu perubahan konformasi reseptor glikoprotein IIb/IIIa. Setelah mengalami konversi fungsinya, reseptor mempunyai afinitas tinggi terhadap sekuen asam amino pada protein adhesi yang larut seperti faktor von Willebrand (vWF) dan fibrinogen, dimana keduanya adalah molekul multivalent yang dapat mengikat 2 platelet yang berbeda secara simultan, menghasilkan ikatan silang platelet dan agregasi. Kaskade koagulasi diaktivasi oleh pajanan tissue factor pada sel endotel yang rusak. Faktor VII dan X diaktivasi, mengakibatkan konversi protrombin menjadi thrombin, yang akan mengkonversi fibrinogen menjadi fibrin. Arteri koroner yang terlihat kemudian akan mengalami oklusi oleh thrombus yang terdiri dari agregasi trombosit dan fibrin. Diagnosis Diagnosis IMA dengan elevasi ST ditegakkan berdasarkan anamnesis nyeri dada yang khas dan gambaran EKG adanya elevasi ST> 2 mm, minimal pada 2 sadapan prekordial yang berdampingan atau>1mm pada sadapan ekstremitas. Pemeriksaan enzim jantung, terutama troponin T yang meningkat memperkuat diagnosis. Nyeri Dada Nyeri dada (angina) merupakan gejala kardinal pasien IMA. Sifat nyeri dada angina sebagai berikut: Lokasi: substernal, retrosternal, dan prekordial Sifat nyeri:rasa sakit, seperti ditekan, rasa terbakar, ditindih benda berat seperti:ditusuk, diperas, atau dipelintir Penjalaran:biasanya ke lengan kiri, dapat juga ke leher, rahang bawah, gigi, punggung/interskapula, perut dan dapat juga ke lengan kanan. Nyeri membaik atau hilang dengan istirahat atau obat nitrat. Faktor pencetus:latihan fisik, stress emosi, udara dingin, sesudah makan. Gejala yang menyertai:mual, muntah, sulit bernapas, keringat dingin, cemas, dan lemas. Diagnosis Banding Perikarditis akut, emboli paru, diseksi aorta akut, kostokondritis dan gangguan GI. STEMI tanpa nyeri lebih sering pada DM dan usia lanjut. Pemeriksaan Fisik Sebagian besar pasien cemas dan tidak bisa istirahat (gelisah). Seringkali ekstremitas pucat dengan keringat dingin. Kombinasi nyeri dada substernal >30 menit dan banyak keringat dicurigai kuat. Tanda fisis lain adalah penurunan intensitas bunyi jantung pertama dan murmur midsistolik yang bersifat sementara. Peningkatan suhu sampai 38C dapat dijumpai dalam minggu pertama pasca STEMI. Pemeriksaan EKG Sebagian besar pasien dengan presentasi awal elevasi segmen ST mengalami evolusi menjadi gelombang Q pada EKG yang akhirnya didiagnosis infark miokard gelombang Q.
Reaksi non spesifik terhadap injuri miokard adalah leukositosis polimorfonuklear yang dapat terjadi dalam beberapa jam setelah onset nyeri dan menetap selama 3-7 hari. Leukosit dapat mencapai 12000-15000/ul. Komplikasi STEMI Disfungsi ventricular, aritmia pasca STEMI, gangguan hemodinamik, ekstrasistol ventrikel, edema paru, takikardi dan fibrilasi atrium dan ventrikel, syok kardiogenik, bradikardi dan blok, infark ventrikel kanan.
INFARK MIOKARD AKUT TANPA ELEVASI ST (NSTEMI)9 Patofisiologi NSTEMI dapat disebabkan oleh penurunan suplai oksigen dan atau peningkatan kebutuhan oksigen miokard yang diperberat oleh obstruksi koroner. NSTEMI terjadi karena trombosis akut atau vasokontriksi koroner. Trombosis akut pada arteri koroner diawali dengan adanya ruptur plak yang tak stabil. Plak yang tidak stabil ini biasanya mempunyai inti yang besar, densitas otot polos yang rendah, fibrous cap yang tipis dan konsentrasi faktor jaringan yang tinggi. Inti lemak yang cenderung ruptur mempunyai ester kolesterol dengan proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Pada lokasi ruptur plak dapat dijumpai sel makrofag, dan limfosit T yang menunjukkan adanya proses inflamasi. Sel-sel ini akan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti TNF- dan IL-6. Gejala Klinik Nyeri dada dengan lokasi substernal dan kadangkala di epigastrium dengan ciri seperti diperas, perasaan seperti diikat, perasaan terbakar, nyeri tumpul, rasa penuh, berat atau tertekan. Gejala tidak khas seperti dyspneu, mual, diaphoresis, sinkop, atau nyeri di lengan, epigastrium, bahu atas atau leher lebih dijumpai pada usia diatas 65 th. Pemeriksaan EKG dan Lab Gambaran EKG secara spesifik berupa deviasi segmen ST merupakan hal penting untuk menentukan risiko pasien. Adanya depresi segmen ST baru sebanyak 0,05 mV merupakan predictor outcome yang buruk. Begitu juga dengan adanya perubahan pada troponin T. PENATALAKSANAAN INFARK MIOKARD5,6 Umum: penjelasan penyakit, penyesuaian aktivitas fisik, pengendalian faktor risiko, pencegahan sekunder. Mengatasi iskemia:medikamentosa dan revaskulerisasi Terapi Farmakologi a. Terapi antiiskemia: nitrogliserin (sublingual/intravena) dan penyekat beta. b. Terapi antiplatelet: aspirin, klopidigrei, antagonis platelet GP IIb/IIIa. c. Terapi antikoagulan: UFH (unfractinionated heparin), LMWH (Low Molecular Weigth heparin) Terapi invasif: kateterisasi dan/atau revaskulerisasipemakaian trombolitik, non operatif yaitu melebarkan a.koronaria dengan balon, dan dengan operasi. KOMPLIKASI ISKEMIA DAN INFARK4 Komplikasi iskemia dan infark antara lain gagal jantung kongestif, syok kardiogenik, disfungsi otot papilaris defek septum ventrikel, rupture jantung (dinding nekrotik yang tipis
pecahperdarahan masif di kantong pericardiumtamponade jantung), aneurisme ventrikel, tromboembolisme, perikarditis, Sindrom Dressler, dan aritmia. Aritmia adalah jenis komplikasi yang yang paling sering terjadi pada infark miokardium, dimana insidensnya sekitar 90%. Aritmia timbul akibat perubahan elektrofisiologi sel-sel miokardium. Kelainan irama jantung dapat digolongkan sesuai dengan mekanisme dasar berikut: kelainan otomatisitas, kelainan konduksi, atau keduanya. Karena kecepatan denyut jantung adalah penentu utama curah jantung, maka pengurangan atau peningkatan berlebihan pada kecepatan denyut jantung dapat mengurangi curah jantung. Setiap impuls jantung yang berasal dari luar nodus sinus dianggap abnormal dan dikenal dengan nama denyut ektopik. Denyut ektopik dapat berasal dari atrium , perbatasan atrioventrikular, atau ventrikel dengan dua syarat :kegagalan ataupun terjadi perlambatan berlebihan dari nodus sinus dan pengaktifan prematur daerah jantung lain. Daftar Pustaka 1. Slibernagl, S dan Lang, F. Teks dan Atlas Berwarna Patofisiologi. Jakarta: EGC. 2000. h.236-239. 2. Boudi, F.B. Atherosclerosis. Diunduh dari www.emedicine.com. ( 10 Februari 2009). 3. Runge, M.S and Patterson, C. Coronary Atherosclerosis in Netters Cardiology. 1st edition. Carlstadt: Icon learning Systems. 2004. P.18-28. 4. Price, S.A dan Wilson, L.M. Fisiologi Proses-Proses Penyakit. Edisi 4. Jakarta: EGC. 1995. h.528-540. 5. Rahman, AM. Angina Pektoris Stabil dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 4 jilid III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 2006. h. 1626-1628. 6. Hanafiah, Asikin. Angina Pektoris dalam Buku Ajar Kardiologi. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. 2004. h.166-167. 7. Trisnohadi, Hanafi B. Angina Pektoris Tak Stabil dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 4 jilid III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 2006. h. 1621-1623. 8. Alwi, Idrus. Tatalaksana Infark Miokard Akut dengan Elevasi ST dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 4 jilid III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 2006. h. 1630-1640. 9. Harun, S. Alwi, I. Infark Miokard Akut Tanpa Elevasi ST dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Edisi 4 jilid III. Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI. 2006. h. 1641-1650. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Cor (jantung) adalah organ yang sangat penting bagi kehidupan karena berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Walaupun banyak berisi darah, cor tidak mampu menyerap nutrisi dari darah tersebut. Nutrisi cor disuplai oleh arteri coronaria yang merupakan cabang pertama dari aorta ascendens. Kelainan pada arteri ini dapat mengganggu aktivitas cor bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada cor tersebut. Banyak penyakit yang menyerang cor, berikut ini tujuh penyakit cor terpenting : 1. Penyakit jantung koroner (penyebab 80% kematian yang disebabkan penyakit jantung) 2. Penyakit jantung akibat hipertensi (9%) 3. Penyakit jantung rernatik (2-3%)
4. Penyakit jantung kongenital (2%) 5. Endokarditis bakterialis (1-2%) 6. Penyakit jantung sifilitik (1%) 7. Cor pulmonale (1%), 8. dan lain-lain (5%) (Santoso dan Setiawan; 2005). Pada tahun 1997, penyakit jantung koroner (PJK) menyebabkan 466.101 kematian dan sampai saat ini tetap merupakan penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Begitu pula di Indonesia, diperkirakan jumlahnya akan bertambah dari tahun ke tahun. Melihat fakta tersebut, sangat dibutuhkan untuk mengetahui kriteria diagnostik PJK agar dapat menegakkan diagnosis dengan tepat. B. Definisi Kasus Laki-laki 40 tahun dengan keluhan utama nyeri dada. Pada anamnesis tidak didapatkan sesak napas, lekas capek, maupun dada berdebar. Pasien adalah perokok 2 bungkus perhari, jarang olahraga, tidak DM, dan ayahnya menderita PJK. Pada pemeriksaan fisik : kesadaran compos mentis, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 x/menit, irama reguler, isian cukup, RR 18 x/menit, JVP tidak meningkat. Inspeksi : tidak ada heaving, apeks di linea medioclavikularis sinistra SIC IV. Palpasi : apeks di linea medioclavicularis sinistra SIC IV, tidak ada thrill. Perkusi : pinggang jantung normal, apeks di linea mediovlacicularis sinistra SIC IV. Auskultasi : BJ 1 normal, BJ 2 normal, splitting normal, bising -, gallop -, ronkhi -. Pemeriksaan laboratorium normal, EKG normal, foto thorax : CTR = 0,49, vascularisasi perifer normal, aorta tidak menonjol, pinggang jantung normal, apex tidak bergeser, exercise test normal, echo cardiografi normal. C. Tujuan Penulisan Dengan tulisan ini diharapkan agar dapat mempermudah dalam menegakkan diagnosis PJK berdasar data-data dan dapat menetapkan pemeriksaan penunjang lainnya. D. Hipotesis Pasien pada contoh kasus di atas, memiliki jantung yang normal. INJAUAN PUSTAKA Anatomi dan Fisiologi Cor Cor terdiri atas (1) endocardium, (2) miokardium, (3) epicardium yang melipat keluar menjadi pericardium, (4) sistem konduksi khusus yang terdiri atas nodus sinoatriaum (NSA) dan nodus atrioventrikel (NVA), berkas his, dan serat purkinje. Cor terdidi dari empat ruang, yaitu atrium dextrum, ventricel dexter, atrium sinistrum, dan ventricel sinister. Antara kedua atrium dipisahkan oleh septum interatriale, dan antara kedua ventricel dipisahkan oleh septum interventriculare. Antara atrium dan ventricel terdapat lubang yang ditutupi oleh katup, yaitu antara atrium dextrum dan ventricel dexter oleh valva tricuspidalis dan valva mitralis membatasi atrium sinistrum dan ventricel sinister. Ventricel dexter merupakan pangkal dari a. pulmonalis dengan katupnya valva semilunaris pulmonalis, sedang ventricel sinister pangkal dari aorta dengan katupnya valva aortae (Budianto, 2005; Chandrasoma, 2006).
Impuls cor (sebagai sistem konduksi) berasal dari NSA yang terletak di dinding posterior atrium dextrum, disebut juga sebagai pace maker. Impuls kemudian menyebar menuju jalur konduksi khusus atrium dan ke otot atrium. Impuls kemudian mencapai NVA yang terletak di sebelah kanan interatrial dalam atrium dextrum. Penghantaran menjadi diperlambat karena tipisnya serat di daerah ini dan konsentrasi taut selisih yang rendah. Perlambatan ini berguna agar pengisian ventricel lebih optimal. Kemudian impuls dilanjutkan ke berkas his dan bercabang menjadi serabut kanan dan kiri. Berkas ini kemudian menjadi serabut purkinje. Serabut kiri berjalan melalui septum interventriculare dan bercabang menjadi bagian anterior dan posterior. Penyebaran hantaran melalui serabut purkinje dimulai dari permukaan endocardium, lalu ke miokardium, kemudian berlanjut ke epicardium. Struktur ini menyebabkan aktivasi segera dan kontraksi ventricel yang terjadi hampir bersamaan (Linda dan Lilavati, 2009; Price dan Wilson, 2005). Efisiensi cor sebagai pompa bergantung pada nutrisi dan oksigenasi otot cor melalui sirkulasi koroner. A. coronaria merupakan percabangan pertama dari aorta. A. coronaria bercabang menjadi a. coronaria dextra dan a. coronaria sinistra. A. coronaria dextra mempercabangkan r. nodi sinoatrialis, r. coni arteriosi, r. artrialis, r. marginalis dextra, dan r. interventricularis posterior. Sedangkan a. coronaria sinistra memparcabangkan r sircumflexus (rr marginalis, rr arterialis, r interventricularis septalis, r atrioventricularis) dan r interventricularis anterior (r interventricularis septalis, r lateralis) (Linda dan Lilavati, 2009). Etiologi Penyakit Jantung Koroner Penyakit jantung koroner dapat disebabkan oleh beberapa hal : 1. penyempitan (stenosis) dan penciutan (spasme) a coronaria, akan tetapi penyempitan bertahap akan memungkinkan berkembangnya kolateral yang cukup sebagai pengganti. 2. aterosklerosis, menyebabkan sekitar 98% kasus PJK. 3. penyempitan a coronaria pada sifilis, aortitis takayasu, berbagai jenis arteritis yang mengenai a coronaria, dll. (Chandrasoma, 2006; Kusmana dan Hanafi, 2003). Faktor Risiko Faktor risiko ada yang dapat dimodifikasi dan ada yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko penting yang dapat dimodifikasi adalah merokok, hiperlipoproteinemia dan hiperkolesterolemia, hipertensi, diabetes melitus, dan obesitas. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan aterosklerotik (Kusmana dan Hanafi, 2003). Risiko aterosklerosis koroner meningkat dengan bertambahnya usia; penyakit yang serius jarang terjadi sebelum usia 40 tahun. Tetapi hubungan antara usia dan timbulnya penyakit mungkin hanya mencerminkan lebih panjangnya lama paparan terhadap faktor- faktor aterogenik. Wanita agaknya relatif kebal terhadap penyakit ini sampai menopause, dan kemudian menjadi sama rentannya seperti pria; diduga oleh adanya efek perlindungan estrogen. Orang Amerika-Afrika lebih rentan terhadap ateros-klerosis daripada orang kulit putih. Riwayat keluarga yang positif terhadap penyakit jantung koroner (saudara atau orang tua yang menderita penyakit ini sebelum usia 50 tahun) meningkatkan kemungkinan timbulnya aterosklerosis prematur. Pentingnya pengaruh genetik dan lingkungan masih belum diketahui. Komponen genetik dapat diduga pada beberapa bentuk aterosklerosis yang
nyata, atau yang cepat per-kembangannya, seperti pada gangguan lipid familial. Tetapi, riwayat keluarga dapat pula mencerminkan komponen lingkungan yang kuat, seperti misalnya gaya hidup yang menimbulkan stres atau obesitas (Santoso dan Setiawan, 2005). Merokok dapat merangsang proses ateriosklerosis karena efek langsung terhadap dinding arteri, karbon monoksida menyebabkan hipoksia arteri, nikotin menyebabkan mobilisasi katekolamin yang dapat menimbulkan reaksi trombosit, glikoprotein tembakau dapat menimbulkan reaksi hipersensitifitas dinding arteri. DM, obesitas, dan hiperlipoproteinemia berhubungan dengan pengendapan lemak. Hipertensi merupakan beban tekanan dinding arteri (Kusmana dan Hanafi, 2003). Patofisiologi 1. Penyakit jantung aterosklerotik Pembuluh arteri mengikuti proses penuaan yang karakteristik seperti penebalan tunika intima, berkurangnya elastisitas, penumpukan kalsium terutama di arteri-arteri besa menyebabkan fibrosis yang merata menyebabkan aliran darah lambat laun berkurang. Manifestasi penyakit jantung koroner disebabkan ketidak seimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dengan suplai yang masuk. Masuknya oksigen untuk miokardium sebetulnya tergantung dari oksigen dalam darah dan arteria koronaria. Di kenal dua keadaan ketidakseimbangan masukan terhadap kebutuhan oksigen yaitu : hipoksemi (iskemi) yang ditimbulkan oleh kelainan vaskular dan hipoksi (anoksi) yang disebabkan kekurangan oksigen dalam darah. Perbedaannya ialah pada iskemi terdapat kelainan vaskular sehingga perfusi ke jaringan berkurang dan eleminasi metabolit yang ditimbulkannya menurun juga, sehingga gejalanya akan lebih cepat muncul. 2. Angina pektoris Penyebab angina pektoris adalah suplai oksigen yang tidak adekuat ke sel-sel miokardium dibandingkan kebutuhan. Jika beban kerja suatu jaringan meningkat maka kebutuhan oksigen juga meningkat; pada jantung yang sehat, arteria koroner berdilatasi dan mengalirkan lebih banyak darah dan oksigen ke otot jantung; namun jika arteria koroner mengalami kekakuan atau menyempit (akibat arterosklerosis, dll.) dan tidak dapat berdilatasi sebagai respon peningkatan kebutuhan akan oksigen, maka terjadi iskemi miokardium; sel-sel miokardium mulai menggunakan glikolisis anaerob untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Cara ini tidak efisien dan menyebabkan terbentuknya asam laktat. Asam laktat menurunkan pH miokardium dan menimbulkan nyeri yang berkaitan dengan angina pektoris. Apabila kebutuhan energi sel-sel jantung berkurang, maka suplai oksigen menjadi adekuat dan sel-sel otot kembali ke proses fosforilasi oksidatif untuk membentuk energi. Proses ini tidak menghasilkan asam laktat. Dengan hilangnya penimbunan asam laktat, maka nyeri ang ina pektoris mereda. Dengan demikian, angina pektoris merupakan suatu keadaan yang berlangsung singkat. 3. Infark miokardium Infark miokardium adalah nekrosis miokard akibat gangguan aliran darah ke otot jantung. Infark miokard biasanya disebabkan oleh trombus arteri koroner; prosesnya mula-mula berawal dari rupturnya plak yang kemudian diikuti oleh pembentukan trombus oleh
trombosit. Lokasi dan luasnya infark miokard tergantung pada jenis arteri yang oklusi dan aliran darah kolateral. Gambaran Klinis, Laboratorium, dan Pemeriksaan Penunjang 1. Penyakit jantung aterosklerotik Sesak napas yang makin lama makin bertambah, sekalipun melakukan aktivitas ringan; nyeri dan keram di ekstremitas bawah, terjadi selama atau setelah olah raga. Laboratorium : kadar kolesterol di atas 180 mg/dl pada orang yang berusia 30 tahun atau kurang, atau di atas 200 mg/dl untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun, dianggap beresiko khusus mengidap penyakit arteri koroner. 2. Angina pektoris Nyeri dada di daerah sternum, substernal atau dada sebelah kiri dan kadang-kadang menjalar ke lengan kiri, punggung, rahang, leher, atau ke lengan kanan; dapat timbul di tempat lain seperti di daerah epigastrium, leher, rahang, gigi, bahu. Nyeri dada biasanya seperti tertekan benda berat, atau seperti di peras atau terasa panas, kadang-kadang hanya mengeluh perasaan tidak enak di dada. Nyeri timbul pada saat melakukan aktivitas dan mereda bila aktivitas dihentikan. Lamanya nyeri dada biasanya berlangsung 1-5 menit. Gambaran EKG saat istirahat dan bukan pada saat serangan angina sering masih normal. Foto rontgen dada sering menunjukkan bentuk jantung yang normal. Perlu dilakukan exercise test, positif bila EKG menunjukkan depresi segmen ST dan gelombang T dapat terbalik. 3. Infark miokardium Nyeri dada kiri seperti ditusuk-tusuk atau diiris-iris menjalar ke lengan kiri, lebih intensif dan lama serta tidak sepenuhnya hilang dengan istirahat ataupun pemberian nitrogliserin. Pada EKG terdapat elevasi segmen ST diikuti dengan perubahan sampai inversi gelombang T; kemudian muncul peningkatan gelombang Q minimal di 2 sadapan. Peningkatan kadar enzim atau isoenzim merupakan indikator spesifik infark miokard akut yaitu kreatinin fosfoskinase (CPK/CK), SGOT, LDH, alfa hidroksi butirat dehidrogenase, dan isoenzim CK-MB. Yang paling awal meningkat adalah CPK tetapi paling cepat turun. Penatalaksanaan Dibagi menjadi 2 : umum dan mengatasi iskemia. Penatalaksanaan umum meliputi edukasi pada pasien seperti penjelasan mengenai penyakit, aktivitas yang harus dihindari, pengendalian faktor risiko, pencegahan sekunder (cth : memberi penghambat aterosklerosis), pemberian oksigen bila perlu. Penatalaksanaan iskemia dengan memberi nitrat, berbagai jenis penyekat beta, antagonis kalsium, untuk revaskularisasi diberi trombolitik, operasi. Angina Pektoris, penatalaksanaannya : pengobatan pada serangan akut : nitrogliserin pencegahan serangan lanjutan : Long acting nitrate, Beta blocker, Calcium antagonist; mengobati faktor presdiposisi dan faktor pencetus, memberi penjelasan perlunya aktivitas sehari-hari untuk meningkatkan kemampuan jantung. Infark Miokardium, penatalaksanaannya : istirahat total, diet makanan lunak serta rendah garam, pasang infus dekstrosa 5 % emergency, atasi nyeri : morfin 2,5 5 mg iv atau petidin; lain - lain: nitrat , antagonis kalsium; oksigen 2 4 liter/menit; sedatif sedang seperti
diazepam; antikoagulan : heparin 20000 40000 U/24 jam; diteruskan dengan asetakumarol, streptokinase / trombolisis (Santoso dan Setiawan, 2005). PEMBAHASAN Pada kasus di atas didapatkan seorang laki-laki berumur 40 tahun dengan keluhan utama nyeri dada. Dia khawatir terkena penyakit jantung koroner karena ayahnya dengan keluhan yang sama dinyatakan menderita PJK. Beberapa tahun yang lalu, kebanyakan pasien takut menderita tuberkulosis bila merasa sakit dalam dadanya. Namun, sekarang yang lebih ditakutkan adalah penyakit jantung. Kertohoesodo (1987) mengatakan bahwa nyeri dada dapat disebabkan oleh berbagai macam penyakit seperti flu, salah tidur, ketegangan batin, penyakit pada tulang rusuk, pada otot dan atau saraf sela iga, bronkhitis, pleuritis, perikarditis, dan lain-lain. Masing-masing penyakit tersebut menimbulkan manifestasi nyeri dada dengan sifat yang berbeda-beda. Pada angina dan infark miokard sudah dijelaskan di atas. Pada pleuritis, nyeri dirasakan saat inspirasi dan batuk. Perikarditis, nyeri dengan lokasi di tengah dada, menusuk ke belakang dan ke pinggir trapezius. Chandrasoma dan Taylor (2006) mengatakan bahwa nyeri dada pada penyakit jantung diyakini disebabkan oleh stimulasi ujung-ujung saraf oleh asam laktat yang dihasilkan selama glikolisis anaerobik. Pada kasus, sifat nyeri dada tidak disebutkan, kemungkinan nyeri dada tidak bersifat khas. Pasien juga tidak memilki keluhan penyerta seperti sesak napas, lekas capek, maupun dada berdebar (palpitasi). Rakhman (2003) mengatakan bahwa sesak napas memberikan petunjuk adanya gangguan pada sistem respirasi. Pada penyakit jantung menunjukan bahwa gangguan juga mengenai paru, contohnya pada stenosis mitral, infark miokard. Lekas capek terjadi bila suplai nutrisi dan oksigen tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Palpitasi (dada berdebar, merasakan denyut jantung sendiri) terjadi karena perubahan kecepatan, keteraturan, atau kekuatan kontraksi jantung. Karena keluhan tersebut tidak ada pada pasien berarti penyakit pasien cenderung tidak mengenai paru, tidak terjadi hambatan distribusi nutrisi dan oksigen, serta tidak terjadi perubahan denyut jantung. Berdasar hasil anamnesis, pasien meiliki beberapa faktor risiko PJK, yaitu merokok 2 bungkus sehari, jarang olahraga, dan riwayat keluarga (ayah) menderita PJK. Berarti dalam kasus ini, pasien berisiko besar menderita PJK. Dari hasil pemeriksaan fisik (keadaan umum) didapatkan data bahwa kesadaran, teka nan darah, denyut nadi, irama, isian sekuncup, frekuensi napas, dan JVP, pada pasien semuanya normal. Tekanan darah yang tinggi (hipertensi) juga merupakan faktor risiko PJK. Denyut nadi menggambarkan aktivitas pompa jantung maupun keadaan pembuluh darah itu sendiri. Bila pada penderita penyakit jantung mengalami bradikardi, denyut nadi perlu dicocokan dengan denyut jantung karena kemungkinan jantung berdenyut lebih sering dari pada nadi. Hal ini terjadi pada isian sekuncup yang kecil. Bila isian cukup maka selisih denyut nadi dan jantung sangat sedikit bahkan tidak ada. Peningkatan frekuensi napas (takipneu) merupakan pertanda gagal jantung dan asidosis karena penyakit jantung sianotik. JVP memberikan gambaran tentang aktivitas (faal) jantung bagian kanan. Bila terdapat bendungan, tekanan vena jugularis akan meningkat. Dengan demikian berdasarkan pemeriksaan keadaan umum, jantung pasien sementara ini adalah normal.
Begitu pula pada pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, hasilnya adalah normal. Hal mana tidak ditemukan heaving, pemebesaran jantung, thrill, bising, gallop, maupun ronkhi. Letak apex cor, bunyi jantung I dan II, serta splitting adalah normal. Heaving adalah getaran jantung yang teraba seperti gelombang atau kursi goyang, ditemukan pada hipertrofi ventricel dexter. Thrill adalah getaran dinding thorax di daerah prekordial yang terjadi karena adanya aliran turbulensi, ditemukan pada penyempitan katup, dilatasi segmen arteri. Bising adalah desiran yang berlangsung lebih lama dari suatu bunyi, penyebab sama seperti pada thrill. Gallop ialah bunyi kembar dari bunyi jantung yang terdengar berurutan seperti derap kaki kuda, ditemukan pada bundle branche blok, dekompensasi cor dengan hipertrofi venrticel sinister. Ronkhi ditemukan pada kelainan saluran napas. Pada pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, EKG, foto thorax, exercise stress test, echocardiografi, pemeriksaan vascularisasi perifer, juga didapatkan hasil yang normal. Pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan rutin dan spesifik. Pemeriksaan laboratorium rutin meliputi 2 unsur, yaitu pemeriksaan darah rutin dan urin. Pemeriksaan darah tepi seperti hemoglobin, hematokrit, apus darah tepi, ureum, gula darah, laju endap darah, merupakan pemeriksaan rutin yang penting dan efektif. Pemeriksaan analisis urin rutin untuk mendeteksi dan memantau kelainan intrinsik dari ginjal, saluran kencing, atau perubahan sekunder akibat penyakit lain. Hematuria dapat merupakan petunjuk adanya infark ginjal yang terjadi sekunder akibat emboli dari jantung bagian kiri atau suatu endokarditis bakterialis. Proteinurea atau urobilinogen dalam urin ditemukan pada gagal jantung. Pemeriksaan laboratorium spesifik hanya dilakukan pada penyakit jantung untuk menegakan diagnosis. Beberapa pemeriksaan yang dilakukan adalah memeriksa enzim jantung, CK, isoenzim CK-MB, troponin T, SGOT, LDH, alfa HBDH, CRP, ASTO, tes fungsi hati, sistem koagulasi, kultur darah, kadar digitalis dalam darah, pemeriksaan CES, dan lain-lain. Pemeriksaan tersebut disesuaikan dengan indikasi suatu penyakit untuk menegakkan diagnosis. Elektrokardiogram (EKG) adalah suatu alat pencatat grafis aktivitas listrik jantung yang direkam pada permukaan tubuh melalui elektroda. EKG memberikan informasi yang berguna untuk penilaian hipertrofi jantung, aritmia dan hambatan konduksi, iskemia dan infark mikard, penyakit perikardium, dan kelainan elektrolit dan beberapa efek obat. EKG normal belum tentu menyingkirkan adanya suatu angina. EKG pada angina biasanya memperlihatkan kelainan khas berupa elvasi segmen ST. Sedangkan pada infark miokard, timbul gelombang Q yang besar, elevasi segmen ST, dan inversi gelombang T. Pada foto thorax, kontur jantung sangat kontras dengan paru yang terisi udara yang berwarna radiolusen. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui pembesaran jantung secara umum, pembesaran lokal salah satu ruang jantung, kalsifikasi katup atau arteri coronaria, kongesti vena pulmonalis. Jota (2002) mengatakan bahwa metode yang lazim dipakai untuk mengetahui adanya pembesaran jantung adalah dengan Cardiothoracic ratio (CTR), yaitu perbandingan antara lebar maksimal jantung dengan thorax, normalnya < 0,5. Exercise stress test ialah suatu tes dengan cara memberikan beban pada jantung sehingga kebutuhan oksigen otot jantung meningkat, bila terjadi insufisiensi koroner akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut yang dapat direkam dengan EKG berupa perubahan segmen ST.
Echokardiografi adalah suatu pemriksaan dengan menggunakan alat yang dapat membangkitkan suara ultrasound dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu > 20.000 Hz. Pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui informasi tentang anatomi, morfologi, serta fungsi ruang jantung, dinding jantung, katup-katup, dan pembuluh darah besar. Setelah menganalisis semua hasil pemeriksaan, didapatkan bahwa hasilnya normal semua. Dengan demikian, jantung pasien dalam keadaan normal. Namun, bila memungkinkan dapat dilakukan pemeriksaan tambahan seperti skintigrafi talium-201 dan angiografi koroner. Walaupun saat ini jantung pasien masih dalam keadaan normal, pasien memiliki kemungkinan besar dapat terkena PJK. Hal ini dikarenakan pasien memiliki beberapa faktor risiko. Oleh karena itu, salah satu penatalaksanaan pada pasien ini adalah memberikan edukasi pada pasien agar dapat mengurangi faktor risiko dengan berhenti merokok, melakukan olahraga yang rutin dan teratur, serta mengatur pola makan. Selain itu, pasien diberi koborantia atau vitamin.
PENUTUP
KESIMPULAN 1. Penyakit jantung koroner (PJK) adalah penyakit yang menyerang arteri coronaria dengan tiga kelompok utama, yaitu penyakit aterosklerotik, angina pektoris, dan infark miokard. 2. Penyakit aterosklerotik coroner dapat ditegakan diagnosis apabila sesak napas yang makin lama makin bertambah, sekalipun melakukan aktivitas ringan; nyeri dan keram di ekstremitas bawah, terjadi selama atau setelah olah raga. Laboratorium : kadar kolesterol di atas 180 mg/dl pada orang yang berusia 30 tahun atau kurang, atau di atas 200 mg/dl untuk mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. 3. Nyeri dada di daerah sternum, substernal atau dada sebelah kiri dan kadang -kadang menjalar ke lengan kiri, punggung, rahang, leher, atau ke lengan kanan.Gambaran EKG, foto rontgen dada, exercise stress test positif adalah gambaran pada angina pektoris. 4. Untuk menegakan diagnosis infark miokard berikut ini gambarannya. Nyeri dada kiri seperti ditusuk-tusuk atau diiris-iris menjalar ke lengan kiri, lebih intensif dan lama serta tidak sepenuhnya hilang dengan istirahat ataupun pemberian nitrogliserin. Pada EKG terdapat elevasi segmen ST diikuti dengan perubahan sampai inversi gelombang T; kemudian muncul peningkatan gelombang Q minimal di 2 sadapan. Peningkatan kadar enzim atau isoenzim merupakan indikator spesifik infark miokard akut yaitu kreatinin fosfoskinase (CPK/CK), SGOT, LDH, alfa hidroksi butirat dehidrogenase, dan isoenzim CK-MB. Yang paling awal meningkat adalah CPK tetapi paling cepat turun. 5. Pasien pada kasus ini memiliki jantung yang normal berdasar hasil pemeriksaan, baik itu dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Walaupun begitu, pasien memiliki kemungkinan besar terkena PJK, mengingat pasien memiliki beberapa faktor risiko terkena PJK. 6. Penatalaksanaan pada pasien tersebut adalah memberikan edukasi dan memberi vitamin. SARAN
1. Mengingat PJK adalah penyakit pertama yang menimbulkan kematian, dan salah satu sebabnya adalah rokok, hal mana rokok adalah faktor risiko yang dapat dihindari. Maka sebaiknya setiap orang harus mau untuk tidak merokok. 2. Selain itu, sebaiknya setiap orang mengatur pola makan dan mengurangi makanan yang mengandung terlalu banyak lemak dan kolesterol. DAFTAR PUSTAKA 1. Budianto, Anang. 2005. Guidance to Anatomy II. Surakarta : Keluarga Besar Asisten Anatomi FKUNS. 2. Chandrasoma dan Taylor. 2006. Ringkasan Patologi Anatomi. Ed: ke-2. Jakarta : EGC. 3. Joto, Santa. 2001. Diagnosis Penyakit Jantung. Jakarta : Penerbit Widya Medika. 4. Kertohoesodo, Soeharto. 1987. Pengantar Kardiologi. Jakarta : Penerbit UI. 5. Kusmana dan Hanafi. 2003. Patofisiologi Penyakit Jantung Koroner. Dalam : Buku Ajar Kardiologi. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. 6. Linda dan Lilavati. 2009. Hanout Anatomi Blok Cardiovasculer. Surakarta : Keluarga Besar Asisten Anatomi FKUNS. 7. Price dan Wilson. 2006. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Ed: Ke6. Jakarta: EGC. 8. Rakhman, Otte. 2003. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik pada Penyakit Jantung. Dalam : Buku Ajar Kardiologi. Jakarta : Balai Penerbit FKUI. 9. Santoso dan Setiawan. 2005. Penyakit Jantung Koroner. Jakarta : Cermin Dunia Kedokteran.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)