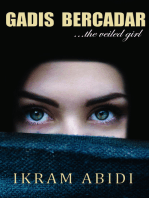Pengiriman Cerpen Rian Harahap
Diunggah oleh
Rian HarahapHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Pengiriman Cerpen Rian Harahap
Diunggah oleh
Rian HarahapHak Cipta:
Format Tersedia
LAMTIUR Senja menyemut pemandanganku di tepi laut Cina Selatan. Perhiasan langit menyapa dengan senyum tiada henti.
Desas desus riak gelombang menghentak bibir kesunyian pantai. Sudah lama aku tidak seperti ini, bersemayam kamar-kamar kosong yang menyatu dengan alam. Senja berkabut yang mencumbu bau tubuhku. Aku terbuai lama dengan memori masa silam. Saat masih aku berkuliah dan menghabiskan waktuku di Medan. Ya Medan, kota yang cukup besar di pulau Sumatra. Kota yang mendidikku selama lima tahun dengan penuh realita kehidupan. Aku tidak habis pikir kini aku menjadi seorang direktur kaya yang memiliki satu rumah mewah dan lima mobil yang tak sempat kupakai satu per satu. Kini aku jadi teringat kehidupan itu, kota yang sudah lama yang kutinggalkan dan kujanjikan untuk tidak mengingatnya lagi. Begitu traumanya jika aku mengingat kota itu. Bukan karena kota itu keras atau sama dengan ibukota tapi kota itu selalu mengantarkanku pada sebuah nama seorang gadis. Lamtiur, namanya jelas menunjukkan bahwa ia adalah gadis batak tulen dari keturunannya lalu pun masih tinggal di pedalaman sumatera utara. Lamtiur, gadis yang kukenal ketika masih kuliah kerja nyata di daerah Tarutung. Lamtiur seorang gadis yang tersenyum menyambut kami rombongan mahasiswa dari universitas. Kami datang ke kampung itu pagi sekali. Disambut nyanyian dan gendang tradisional seakan kami tamu jauh dari luar kampung. Padahal kami hanya mahasiswa dari Medan. Dentuman musik tradisi itu riuh sekali membahana mengisi kekosongan letih kami di perjalanan tadi. Terlihat seorang gadis mungil di balut ulos tersenyum di pinggiran baris warga. Aku penasaran, apa masih ada perempuan semanis itu di pedalaman seperti ini ? pikirku. Maklumlah daerah ini harus menempuh jalan satu jam lagi dari kota dan melewati jalan berlubang. Senyum itu masih saja membuat rasa penasaranku tak penat mencari namanya. Sudah lama kami dijamu, akupun harus beristirahat dan masih penasaran. Lalu kuberanikan diri bertanya pada seorang bocah nama gadis itu. Meski aku harus mengeluarkan komisi pada bocah itu, gawat kecil-kecil sudah mengerti duit. Lamtiur bang namanya, sebut bocah itu. Aku pun merekah dalam senyum yang tak terucap. Lamtiur nama yang indah untuk gadis mungil yang juga indah.
Aku harus memberanikan diri padanya untuk menyapanya esok hari. Belum pernah aku melihat gadis mungil yang sering tersenyum seperti dia. Esok hari akan kujemput dia di rumah sebelah kebun jeruk, kata bocah itu rumahnya disana. Semerbak parfum dari kota sudah kupersiapkan untuk esok. Aku menjadi orang yang terbius senyuman. Hei, hei mandi kau. Sudah sore jangan melamun, panggil seorang mahasiswa dari belakang. Wewangian sudah siap menyetubuhiku. Lamtiur akan menyambutku pasti dengan senyuman khasnya. Terang saja sebab aku masih wangi dibanding pemuda lain di desa ini, pikirku agak bangga. Kami bertemu di warung nasi di rumahnya. Aku mencoba mendekati lewat kepura-puraan membeli nasi di warungnya. Aku sudah terkejut dibuat wajahnya yang kurasa lebih wangi dari wewangianku tadi. Ia ramah dan sangat bersahabat. Aku semakin jatuh hati padanya. Ia mengajak untuk pergi ke sungai hari minggu nanti. Ia berjanji akan menunjukkan sebuah tempat yang begitu indah di kampungnya. Aku langsung menanggapi dengan anggukan kepala penuh harap. Sontak saja benar yang ia janjikan. Aku dibawanya melihat sebuah air terjun yang begitu indahnya. Ia malah mengatakan jika kita melihat air tejun ini dengan orang yang kita sayang maka cinta kita akan abadi. Aku pun percaya pada hal itu dan langsung mengucap kata cinta padanya di bawah rerintihan air terjun. Senyumnya telah meramu hidupku beberapa hari ini. Namun ada yang aneh ketika ia tidak lagi kulihat setelah itu. Ia tidak ada kabar dan aku pun tidak boleh menanyakan kabarnya sebab kami berjanji hubungan ini tidak boleh ada yang tahu. Makanya aku lebih baik diam dan menunggu dia yang mengabariku. Tapi itu belum juga hadir dan menyapaku. Aku tidak lagi bisa melihatnya meramu senyum di bawah air terjun kami. Ia menghilang begitu saja dalam keramaian hatiku. Gurau-gurau menjelma menjadi pilu yang tak kunjung habis. Jika aku menjadi mentari aku belum bisa cerah hari ini. Mentari akan mendung dalam larutnya senja. Kegembiraan mencibirku dari dekat. Lamunanku tetap saja berlalu. Kembali aku mengerjakan tugas-tugasku di desa ini. Selalu mengerjakannya dan tiap itu kusudahi dengan lamunan seperti biasa di pinggir jendela kamar. Berharap akan ada sebuah rekah senyum gadis manis yang kunanti. Lalu aku memanggilnya dan bercakap-cakap dengannnya dengan pesona yang tak mampu kuumbar dengan kata-kata. Tapi itu hanya menjadi sebuah pedoman mimpi dan lamunan yang pilu. Aku harus menanti sampai menanti lagi tapi itu belum saja terjadi.
Sudah hampir sebulan aku disini dan ini hari terakhirku bertugas. Mungkin sudah saatnya aku pulang dan menemui dosenku dan melaporkan apa yang kudapat untuk ditransfer menjadi nilai dan angka. Ya itulah yang dosenku minta dari kegiatan disini. Tapi aku masih dalam bungkus penasaran yang meronta-ronta. Aku belum lagi bisa bertemu dengannya setela pertemuan kami yang lalu ketika aku masih baru disini. Ia tidak pernah lagi terlihat dalam balut senyum yang menggemaskan. Bumi mungkin tidak merestui pertemuanku dengannya. Ya, sejak pertama kali aku menjumpanya itu merupakan takdir yang menyalah menurutku. Hari ini aku terkejut saja. Kenapa tiba-tiba kampung ini ramai sekali. Mereka memakai pakaian adat seperti ada acara besar saja. Bingung dalam hati tapi aku tidak menorehkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi itulah aku tetap saja menjadi rikuh jika dalam hingar bingar ini aku tidak tahu apa-apa. Ada apa ya pak ? , tanyaku pada seorang bapak yang berdiri tepat di depan rumah kami. Ini si Lamtiur menikah . Aku terperanjat seketika. Ingin saja aku mati dalam sekejap mata, biar tiada yang tahu kemana jasad busukku ini. Gadis yang aku cintai harus menikah tanpa mengabari sebait kabar. Petir menyambar ubun-ubunku pagi ini. Kuterobos saja kerumunan tadi hanya untuk melihata apa tatp matanya masih sama melihatku dan tertawa dalam balut lukaku. Belum lagi habis darah yang mengucur tadi sudah kembali lukaku disayat. Ya, pria yang disandingkan dengannya tidak lain dan bukan ialah Profesor Hutomo. Ia adalah dosenku untuk mata kuliah ini. Ada yang menangis ada yang tertawa. Ada yang lahir ada yang mati. Ada yang tersenyum ada yang berkabut duka. Ada kubangan cinta ada kubangan lara. Aku harus menyetubuh dengan wewangian lara bertumpuk kesunyian air terjun yang tak ingin bemuara. Percuma mencinta sebab kupikir kita sama dalam kata tapi tidak dalam cinta.
*Penulis adalah mahasiswa Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UMSU dan bergiat di KONTAN dan Teater SISI .
Anda mungkin juga menyukai
- Mimpi Yang NyataDokumen4 halamanMimpi Yang NyataRaihan AbyzarBelum ada peringkat
- MonicaDokumen5 halamanMonicaTitin Widyawati 6Belum ada peringkat
- Bias Pelangi SenjaDokumen6 halamanBias Pelangi SenjaMuhammad IkhsanBelum ada peringkat
- CintaDokumen4 halamanCintacarmynahBelum ada peringkat
- Bunga BerteoriDokumen2 halamanBunga BerteoriIndana AlyaBelum ada peringkat
- Kedai Kopi DaratDokumen23 halamanKedai Kopi DaratFauzan AhmadBelum ada peringkat
- Bab IDokumen3 halamanBab IdadarahahoBelum ada peringkat
- Cerpen Rian HarahapDokumen3 halamanCerpen Rian HarahapRian Harahap100% (1)
- Perpisahan Termanis MoronsDokumen3 halamanPerpisahan Termanis MoronsPiter MoronBelum ada peringkat
- Cerpen BellaDokumen15 halamanCerpen BellaAgustina SyaputriBelum ada peringkat
- Tak Sempat TerucapDokumen10 halamanTak Sempat TerucapKholiq MoteckarBelum ada peringkat
- Gadis Kursi RodaDokumen7 halamanGadis Kursi Rodayusrizal yusufBelum ada peringkat
- Badai Pasti BerlaluDokumen110 halamanBadai Pasti BerlaluAnis Najwa0% (1)
- KISAH REMBULANDokumen3 halamanKISAH REMBULANSilvia NurBelum ada peringkat
- Aku Tergoda OlehnyaDokumen6 halamanAku Tergoda OlehnyaAyu WulanBelum ada peringkat
- JarakDokumen3 halamanJarakDatang YaBelum ada peringkat
- IlpoverelloDokumen7 halamanIlpoverellovalentino elvisBelum ada peringkat
- Surga Yang DekatDokumen5 halamanSurga Yang DekatNatasha HadiwinataBelum ada peringkat
- MenikahDokumen5 halamanMenikahiffah WahidBelum ada peringkat
- Adam N HawaKompilasiDokumen56 halamanAdam N HawaKompilasimyumarBelum ada peringkat
- Cerpen Kelompok 3Dokumen10 halamanCerpen Kelompok 3Muhammad NurBelum ada peringkat
- Aku Ingin Bercinta Tapi....Dokumen17 halamanAku Ingin Bercinta Tapi....Amalina Ismail100% (2)
- Persahabatan yang BermulaDokumen8 halamanPersahabatan yang BermulaputudesiirawanBelum ada peringkat
- Hujan & SenjaDokumen3 halamanHujan & SenjaShahfa Rizkya Ananda 2105134662Belum ada peringkat
- Misteri - Debora Natalia Ndaparoka - Frans Dan Pulau Palue - 082139599126Dokumen6 halamanMisteri - Debora Natalia Ndaparoka - Frans Dan Pulau Palue - 082139599126Debora NdaparokaBelum ada peringkat
- Cerpen 1Dokumen3 halamanCerpen 1Agus Juniarta I WayanBelum ada peringkat
- Kibo No Uta - ParthenaDokumen19 halamanKibo No Uta - ParthenaChingkyBelum ada peringkat
- Kumpulan Cerpen AbsurdDokumen66 halamanKumpulan Cerpen AbsurdHendra Bangkit PramanaBelum ada peringkat
- Jodoh Takdir TuhanDokumen6 halamanJodoh Takdir TuhanIqbal NmBelum ada peringkat
- SesalDokumen10 halamanSesalMiranda RiskiBelum ada peringkat
- BERSAMA SENJADokumen4 halamanBERSAMA SENJAMahardika Gilang Aditya100% (1)
- Indahnya HujanDokumen5 halamanIndahnya HujanliliyatiBelum ada peringkat
- Setangkai Cinta EdelweisDokumen4 halamanSetangkai Cinta EdelweisLindaBelum ada peringkat
- 4 Cerpen Sastra BandinganDokumen11 halaman4 Cerpen Sastra BandinganIrvan dermawanBelum ada peringkat
- Keindahan Kejora di Pantai SantoloDokumen8 halamanKeindahan Kejora di Pantai SantoloRetno Dyah PekertiBelum ada peringkat
- Cintaku Tertinggal Di Lombok TengahDokumen2 halamanCintaku Tertinggal Di Lombok TengahFerry AgusmansyahBelum ada peringkat
- Desa Coklat yang HidupDokumen12 halamanDesa Coklat yang HidupAll GameBelum ada peringkat
- Contoh Cerpen RemajaDokumen15 halamanContoh Cerpen RemajaDyah Ayu50% (2)
- CerpenDokumen3 halamanCerpenChelsi SetyaningrumBelum ada peringkat
- Cerpen Nastiti-1Dokumen5 halamanCerpen Nastiti-1faiq elfBelum ada peringkat
- Link 2 Thalia 13-12-2023Dokumen12 halamanLink 2 Thalia 13-12-2023admin iranesiaBelum ada peringkat
- Amalia Risky Fitrayanti - Good Bye Moccacino, Hello Vanilla LatteDokumen9 halamanAmalia Risky Fitrayanti - Good Bye Moccacino, Hello Vanilla LatteAmalia Risky FitrayantiBelum ada peringkat
- Cerpen - Taksi Menuju Horizon - Minerva AzaleaDokumen6 halamanCerpen - Taksi Menuju Horizon - Minerva AzaleaecaBelum ada peringkat
- Aku Duduk Terdiam Dan TerpakuDokumen5 halamanAku Duduk Terdiam Dan TerpakuAnugrah N HadiBelum ada peringkat
- BANGKITDokumen8 halamanBANGKITJoseph Simorangkir57% (7)
- Cerpen NASHRUL HANIFDokumen11 halamanCerpen NASHRUL HANIFIqbal Hamdan Habibi100% (1)
- Cerpen CintaDokumen4 halamanCerpen CintaDaniella FarencyBelum ada peringkat
- SENJADokumen5 halamanSENJAMuhammad DzulaemyBelum ada peringkat
- Pertemuan Wanita SenjaDokumen20 halamanPertemuan Wanita SenjaRidho SaputraBelum ada peringkat
- Hujan Di Malam ItuDokumen5 halamanHujan Di Malam ItuMEI RINJANINGRUM MAHARANI Ushuluddin dan FilsafatBelum ada peringkat
- Kisah Surga di BumiDokumen39 halamanKisah Surga di BumiimacatpersonBelum ada peringkat
- SECANGKIR KOPI IN STORYDokumen11 halamanSECANGKIR KOPI IN STORYGalillea LalaBelum ada peringkat
- SenjaAirmataDokumen4 halamanSenjaAirmataDewii Irmaa RscmgBelum ada peringkat
- Mimpiku Berakhir Pada Temaram Kala Itu RhevanaDokumen12 halamanMimpiku Berakhir Pada Temaram Kala Itu RhevanaRheva VanavaniBelum ada peringkat
- Hi Day at 2Dokumen169 halamanHi Day at 2Hidayat KusamantoBelum ada peringkat
- Satu Hari BersamamuDokumen15 halamanSatu Hari BersamamuHijrianti Suharna100% (1)
- Cerpen: Utusan KasihDokumen9 halamanCerpen: Utusan KasihonemahmudBelum ada peringkat
- My Friend's Wife: Serena: Seri Selingkuh dengan Istri TemanDari EverandMy Friend's Wife: Serena: Seri Selingkuh dengan Istri TemanPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (16)
- Tugas Kelompok Pendidikan Berbasis Masyarakat (Pak Diah) - TutDokumen20 halamanTugas Kelompok Pendidikan Berbasis Masyarakat (Pak Diah) - TutRian HarahapBelum ada peringkat
- Dongeng Domba-Domba (Cerpen)Dokumen5 halamanDongeng Domba-Domba (Cerpen)Rian HarahapBelum ada peringkat
- Puisi-Peluk Aku Dengan TatapmuDokumen9 halamanPuisi-Peluk Aku Dengan TatapmuRian HarahapBelum ada peringkat
- (Artikel) Antara Bengkel Teater Dan Burung CamarDokumen4 halaman(Artikel) Antara Bengkel Teater Dan Burung CamarRian HarahapBelum ada peringkat
- Sign Thing#2Dokumen6 halamanSign Thing#2Rian HarahapBelum ada peringkat
- Contoh Surat Lamaran Kerja (FIX)Dokumen3 halamanContoh Surat Lamaran Kerja (FIX)Rian HarahapBelum ada peringkat
- Melihat Indonesia Dari 14 InchDokumen2 halamanMelihat Indonesia Dari 14 InchRian HarahapBelum ada peringkat
- Cerpen Rian (Rubaini)Dokumen4 halamanCerpen Rian (Rubaini)Rian HarahapBelum ada peringkat
- Mira's ReturnDokumen4 halamanMira's ReturnRian HarahapBelum ada peringkat
- Cerpen Rian HarahapDokumen3 halamanCerpen Rian HarahapRian Harahap100% (1)
- (Artikel) Teater Tradisional Sumatera Yang Belum Termakan ZamanDokumen5 halaman(Artikel) Teater Tradisional Sumatera Yang Belum Termakan ZamanRian HarahapBelum ada peringkat
- JEPANG 10 MARET 2011Dokumen2 halamanJEPANG 10 MARET 2011Rian HarahapBelum ada peringkat
- Tujuh Puluh TigaDokumen1 halamanTujuh Puluh TigaRian HarahapBelum ada peringkat
- 10 Maret Di JepangDokumen3 halaman10 Maret Di JepangRian HarahapBelum ada peringkat
- Surat Buat Om GayusDokumen2 halamanSurat Buat Om GayusRian HarahapBelum ada peringkat