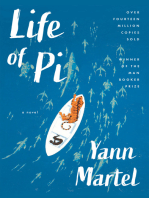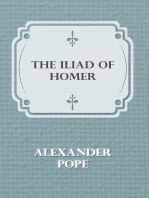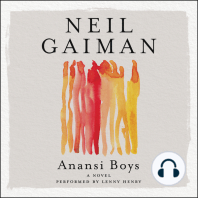Resensi April 08
Diunggah oleh
Muzni AlamsyahJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Resensi April 08
Diunggah oleh
Muzni AlamsyahHak Cipta:
Format Tersedia
WACANA, VOL. 10 RESENSI BUKU NO.
1, APRIL 2008 (161189)
161
RESENSI BUKU
Susan Blackburn, Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2007, xviii + 256 hlm. ISBN 979-461-507-2. Harga: Rp63.750,00 (soft cover). Thera Widyastuti Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia therabega2002@yahoo.com Susan Blackburn adalah Profesor di Universitas Monash, Melbourne Australia yang mempunyai minat pada masalah sosial politik Asia Tenggara khususnya Indonesia. Pada tahun 1993, ia menemukan salinan dari laporan-laporan mengenai Kongres Perempuan Pertama di Perpustakaan Nasional Jakarta. Ia merasa terpanggil untuk menerbitkan ulang isi dari edisi perdana majalah Isteri yang memuat pidato-pidato Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Kedudukan perempuan di tengah masyarakat, pada masa itu, belum setara karena dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat kuat. Sistem patriarki tradisional yang dianut oleh hampir sebagian besar bangsa Indonesia (kecuali suku Minang, Bugis, dan Makassar), pada masa itu membuat ruang gerak kaum perempuan terbatas. Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan di Mataram Yogyakarta. Gagasan penyelenggaraan kongres tersebut adalah untuk membangunkan kesadaran kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan keberhasilan kaum perempuan meneruskan apa yang sudah dicapai oleh pendahulu mereka. Kongres tersebut digagas oleh tiga orang perempuan Indonesia, yaitu Soejatin, Nyi Hadjar Dewantoro, dan R.A. Soekonto. Semangat ketiga perempuan pencetus kongres tersebut memperlihatkan nasionalisme yang tinggi dalam mendukung perjuangan pergerakan nasionalisme Indonesia (hlm. xiii). Pentingnya kongres tersebut terlihat dengan disepakatinya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, bahkan pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Besar Nasional (hlm. xii).
162
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
Dalam kongres tersebut hadir limabelas pembicara yang berasal dari sepuluh organisasi yang berbeda. Hampir sebagian besar adalah organisasi yang sudah sangat mapan dan terkenal pada masa itu. Peserta kongres adalah utusan dari 23 organisasi yang berlandaskan agama Islam, Katolik, dan non-agama. Meskipun mayoritas pembicara dalam kongres itu berasal dari Jawa Sentris, ada satu orang pembicara berasal dari Sumatera (Tabel 1, hlm. xxv). Keanekaragaman organisasi yang terlibat dalam kongres tersebut memperlihatkan bahwa semangat berorganisasi kaum perempuan pada saat itu sudah sangat tinggi. Buku ini secara cukup terperinci menjelaskan aspek-aspek kesetaraan gender dan pemahaman cara pandang kaum perempuan tentang normanorma yang berlaku di masyarakat. Teks-teks pidato setiap pembicara kongres yang dibacakan pada saat berlangsungnya kongres juga terlampir terperinci (hlm. xxxv). Topik-topik yang diangkat meliputi masalah domestik, seperti perkawinan, poligami, westernisasi, dan pendidikan. Beberapa judul pidato di dalam kongres tersebut, antara lain, Kewadjiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia, Deradjat Perempoean, Doedoeknja Perempoean di Kehidoepan Sama-sama, Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini dan Bagaimanakah Kelak?. Pidato Kewadjiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia disampaikan oleh Sdr. Sitti Soendari. Dalam pidatonya ia tidak menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Jawa, melainkan bahasa Indonesia (ada juga pembicara yang menggunakan bahasa Jawa dalam berpidato). Menurut Sitti Soendari, ini dilakukannya untuk mendukung Kongres Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang dicanangkan di Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Ia mengingatkan hadirin mengenai keputusan Kongres Sumpah Pemuda tersebut, yaitu hendak berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, hendak bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, dan hendak menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut salah satu kutipan pidato tersebut.
Kalau kita kaum perempuan tahu kewajiban kita, kalau para isteri tidak melupakan kewajiban sebagai isteri, kalau putri mengenali kewajiban putri, barulah tumbuh hak kaum ibu yang sesungguhnya. Hak ini bertopang pada pengakuan kaum perempuan sendiri dan bersendi pada kewajiban yang jelas bagi laki-laki dan perempuan. (hlm. 182).
Pidato tersebut cukup panjang dan sangat berani mengritik isu gender yang sebelumnya tidak pernah diangkat ke permukaan secara terbuka. Peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat turut dibahas, terutama bagaimana perempuan menghargai dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan membina keluarga yang harmonis. Pidato Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini dan Bagaimanakah Kelak? yang disampaikan oleh Tien Sastrowirjo membahas cara pandang kaum perempuan, baik mengenai kebebasan perempuan untuk mengemukakan pendapat dan penghargaan yang diberikan kepada mereka
RESENSI BUKU
163
atas keberhasilan yang telah mereka capai dengan susah payah. Berikut salah satu kutipan pidato tersebut.
Kamu perempuan, apa yang kamu lakukan? Kaum laki-laki menjadi apa pun pasti panjang langkahnya, tetapi perempuan selamanya ribut saja karena kainnya. Walaupun bisa apapun juga, perempuan toh harus masuk dapur. Kalau sudah bisa masak, itu sudah cukup bagi perempuan. Semua ini menunjukkan bahwa ia tak senang bekerja sama, bahwa ia tidak setuju kalau kita maju, kalau kita masuk sekolah tinggi dan lain-lainnya. (hlm.195).
Isu kesetaraan gender terutama mengenai hak dan kewajiban kaum perempuan yang dirasakannya sangat tidak adil diangkat oleh pembicara, juga mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya suku bangsa Jawa, yang dianggap memihak laki-laki. Keadilan dalam hak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki juga disoroti. Perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa jauh lebih baik daripada perempuan berpendidikan rendah. Dikemukakan pula tujuh ilmu yang harus dihargai tinggi oleh kaum perempuan untuk memenuhi kewajiban, yaitu: (1) mengurus rumah tangga, (2) pengetahuan untuk mengurus anak, (3) memelihara dan mendidik anak, (4) pendidikan kewarganegaraan, (5) ilmu etika, (6) pengetahuan umum, dan (7) kebutuhan kaum perempuan. Apabila ketujuh ilmu tersebut sudah dikuasai perempuan, maka manfaat dan hasilnya dapat membantu perempuan untuk membangun rumah tangga ideal dan kelak bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, kuat, teguh, berani, pandai, dan maju. Bangsa lain mau berteman, menjadi sahabat, akhirnya tanah tumpah darah Indonesia menjadi termasyhur. Ketertarikan perempuan berbicara di depan umum mengenai masalah mereka merupakan dampak dari emansipasi perempuan yang mulai berkembang di Pulau Jawa. Banyak perempuan yang sudah menyadari bahwa selain kewajiban, mereka juga memiliki hak yang harus diperjuangkan. Mereka sadar bahwa sudah saatnya kaum perempuan memikirkan diri mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk membangun bangsa, diperlukan pilar yang kokoh dan kaum perempuan dapat menyiapkan pilar yang kokoh tersebut dengan mendidik generasi penerus bangsa sebaik mungkin. Kongres Perempuan Pertama menjadi cambuk bagi perempuan di Indonesia untuk lebih bergiat memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pengaruh barat sedikit banyak telah memengaruhi pandangan hidup bangsa Indonesia dan turut memberi dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan kaum feminis. Perlu diketahui bahwa mayoritas peserta kongres yang berjumlah sekitar 1.000 orang adalah kaum perempuan yang berasal dari golongan bangsawan, berumur muda (berusia sekitar duapuluhan), dan mengenyam pendidikan formal modern di barat, baik itu di Belanda maupun Perancis, yaitu negeri-negeri yang
164
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
feminismenya sudah sangat berkembang. Pengaruh gelombang feminisme pertama di Eropa tanpa disadari telah masuk ke Indonesia. Keberanian kaum perempuan Indonesia untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk diri mereka merupakan sebuah langkah maju. Bangsa Indonesia yang masih dipengaruhi tradisi dan norma-norma timur perlu mengkaji ulang pengaruhpengaruh barat yang masuk ke Indonesia. Nilai-nilai timur yang memang patut dilestarikan harus dipertahankan agar anak cucu kita dapat mengetahui akar keberadaan mereka. Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan mutu generasi penerus bangsa. Kehadiran buku ini sangat penting dan perlu disambut dengan semangat tinggi sehingga dapat melanjutkan perjuangan aktivis-aktivis perempuan di tahun 1920-an yang sudah mengawali pergerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Gagasan mereka sangat mulia dan berharga untuk seluruh bangsa Indonesia. Setelah pembaca menyelesaikan membaca buku ini diharapkan ada tertinggal semangat untuk terus berjuang memajukan bangsa. Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Asia lainnya dalam mengantisipasi kemajuan di segala bidang. -------------------------------------Xu Ziliang dan Wu Renfu. (Metode praktis bagi pengajaran bahasa cina sebagai bahasa asing). Beijing: Peking University Press, 2005, 228 hlm. ISBN 7-301-08092-1. Harga: RMB 22.00 (soft cover). Lilysagita Tjahjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia lilisagita_t@yahoo.com Banyak orang ingin mengantisipasi peran aktif Cina dalam era globalisasi dengan mulai membuka diri untuk mempelajari bahasa Cina. Namun, banyak pemelajar yang merasa bahwa bahasa Cina amatlah sulit dipelajari, sehingga pemelajar hanya bersemangat di awal pemelajaran saja. Agar pengajaran dapat efektif dan tidak menimbulkan kejenuhan pada pemelajar bahasa Cina tersebut, pengajar perlu mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau pengajaran bahasa asing mempunyai prinsip pengajaran yang berbeda dengan pengajaran bahasa pertama. Pengajaran bahasa pertama menekankan keterampilan Membaca dan Menulis, mengabaikan keterampilan
RESENSI BUKU
165
Berbicara. Sebaliknya, pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing, pada tahap awal pemelajaran, meskipun memberikan porsi latihan lebih besar pada keterampilan Mendengarkan dan Berbicara, namun tidaklah mengabaikan pengembangan keterampilan Membaca dan Menulis. Xu Ziliang dan Wu Renfu penulis buku Metode praktis bagi pengajaran bahasa cina sebagai bahasa asing menyatakan dalam Bab III, bahwa pengajaran bahasa harus didistribusikan ke dalam empat keterampilan, yaitu Mendengarkan, Berbicara, Membaca, dan Menulis, sehingga pemelajar mempunyai keterampilan berbahasa yang menyeluruh dan lengkap. Buku Metode praktis yang ditulis dalam bahasa Cina oleh Xu dan Wu ini terdiri atas sepuluh bab. Buku ini ditulis dengan landasan teori pengajaran bahasa Inggris yang diterapkan ke dalam bahasa Cina. Buku yang diterbitkan pada tahun 2005 di Beijing ini, merupakan buku pegangan pengajar yang memfokuskan pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Selain mengarahkan pengajaran pada prinsip-prinsip pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing, buku ini juga memperkenalkan metode pengajaran mutakhir, yaitu pengajaran berbasis kompetensi komunikatif. Terlihat jelas bahwa metode yang disajikan sangat berbeda dari metode pengajaran gramatikal yang diperkenalkan pada tahun 50-an. Jika pembahasan pengajaran gramatikal hanya terfokus pada struktur bahasa semata-mata, keunggulan buku ini adalah menyajikan pengajaran bahasa secara komprehensif yaitu, pembahasan empat keterampilan mencakup unsur linguistik serta sosial budaya bahasa Cina, tanpa mengabaikan struktur bahasa. Pelatihan setiap keterampilan menyajikan pengajaran unsur linguistik - seperti fonetik, sintaksis, kosakata, dan aksara Cina - dengan menyisipkan aspek sosial dan budaya bahasa Cina sebagai satu kesatuan. Setiap paparan keterampilan menyajikan Landasan Teori, Sasaran Pelatihan, dan Cara-Cara Pelatihan. Secara teoritis, Xu dan Wu juga memasukkan pembahasan aspek psikologis yang berkaitan dengan unsur kejiwaan dan proses kejiwaan yang terkait dengan perasaan, memori, pikiran dan nalar, serta motivasi. Buku tersebut juga membahas prinsip-prinsip psikologi pendidikan serta prinsipprinsip pendidikan itu sendiri. Dalam pembahasan teori ini dinyatakan bahwa pembentukan bahasa tergantung pada aspek psikologis. Yang dimaksud dengan aspek psikologis adalah sebelum seseorang terampil menggunakan bahasa, orang tersebut harus meniru atau menerima asupan simbol-simbol bahasa terlebih dahulu. Sasaran Pelatihan setiap keterampilan yang diuraikan dalam buku ini menyajikan isi dari pengajaran dan cara menggunakan bahasa tersebut untuk tujuan komunikasi tiap-tiap keterampilan. Setiap keterampilan mempunyai sasaran pelatihan yang berbeda. Pada keterampilan Mendengarkan, sasaran pelatihan diarahkan pada pemahaman isi dialog atau teks yang diperdengarkan oleh pengajar lewat rekaman. Pemelajar dilatih agar mempunyai ketajaman memahami dialog atau teks yang diperdengarkan oleh pengajar. Sasaran pelatihan ini berbeda dari latihan keterampilan Berbicara, yang menekankan latihan bercerita atau berdialog yang dilakukan oleh pemelajar. Dalam latihan
166
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
berbicara, pemelajar dilatih agar berani mengungkapkan pendapat. Dalam berbicara diperlukan pula strategi berkomunikasi dan mempertahankan komunikasi. Pengajar memberikan kesempatan pemelajar berbicara, kemudian memperbaiki lafal pemelajar. Dalam hal ini pemelajar dituntut berperan aktif di dalam kelas. Dalam keterampilan Membaca dijelaskan bahwa sasaran pelatihan diarahkan kepada pendekatan pemahaman teks secara kontekstual, dan menangkap ide utama dari teks bacaan yang dibaca. Pemelajar dilatih pula membaca nyaring dengan lafal yang benar dan memperhatikan jeda serta penggalan kata. Selain itu, pemelajar dibiasakan pula membaca tanpa mengeluarkan suara, untuk melatih konsentrasi membaca. Pada keterampilan Menulis, sasaran pelatihan diarahkan kepada cara-cara menulis. Cara-cara menulis ini bermula dari menyusun kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dan dari paragraf menjadi sebuah karangan. Salah satu aspek menarik dari buku ini adalah buku ini tidak hanya menyajikan aspek teoritis, tetapi juga memberi contoh latihan setiap keterampilan. Contoh latihan ini sangat bermanfaat untuk digunakan di dalam latihan di kelas. Dengan adanya contoh-contoh latihan, pengajar dapat menggunakan modul tersebut untuk mengembangkan dan memperluas bentuk latihan secara variatif, sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal. Buku ini juga menarik dan variatif karena memuat metode-metode pengajaran yang sangat bermanfaat. Metode-metode ini dikelompokkan ke dalam empat aliran besar, yaitu (1) Aliran Kognitif, yang memperkenalkan Metode Terjemahan Struktur (Gramatical Translation Method). Metode ini merupakan metode yang menitik-beratkan pengajaran struktur. Metode ini diusulkan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Heinrich Ollenderff pada sekitar abad ke-19. Ollenderff beranggapan bahwa bahasa dapat dipelajari dengan cara menerjemahkan struktur bahasa Ibu ke dalam bahasa sasaran; (2) Aliran Pengalaman-Menghasilkan-Kebiasaan. Aliran ini memperkenalkan Metode Langsung (Direct Teaching). Metode ini memperkenalkan pengajaran yang langsung menggunakan bahasa sasaran, dan menghindarkan penjelasan dengan bahasa Ibu. Metode ini dilandasi kepercayaan bahwa bahasa dapat dipelajari lewat pengalaman; karena mengalami maka menjadi mahir. Proses pelatihan metode tersebut adalah dengan cara mengulang dan meniru serta langsung mengenal benda sesungguhnya, agar dapat mempertajam pengenalan dan perasaan pemelajar terhadap bahasa yang sedang dipelajari. Metode ini diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Jerman, yaitu Berlitz, pada abad ke-19; (3) Aliran Meliput Gerakan Tubuh dan Perasaan (Total Physical Response). Aliran ini memperkenalkan pelatihan yang disertai dengan perbuatan, seperti Metode Belajar Secara Berkelompok, Metode Diam; (4) Aliran Fungsi Komunikatif (Communicative Approach), yang diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Inggris bernama Wilkins, pada tahun 70-an abad ke-20. Aliran ini memperkenalkan Metode Komunikatif yang menekankan proses pemelajaran secara fungsional. Metode ini dilandasi keyakinan bahwa bahasa tidak mengandalkan struktur semata-mata, melainkan mengandalkan
RESENSI BUKU
167
kemampuan seseorang menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan fungsi komunikasi. Xu dan Wu memperkenalkan pula cara melakukan evaluasi yang dapat diandalkan (Bab X). Dengan paparan dari pengarang tentang cara mengevaluasi kelas, pengajar dapat memberi penilaian kelas secara lebih sahih dan andal. Pada dasarnya, prinsip evaluasi adalah mengukur sebagian hasil belajar suatu kelas. Cara mengukur hasil belajar tersebut dilakukan melalui testing. Agar testing tersebut dilaksanakan secara sistematis, penguji harus terlebih dahulu mengkaji beberapa hal di bawah ini sebelum melakukan testing. 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan testing. (hlm. 219). Sasaran dan ruang lingkup materi yang akan diujikan. (hlm. 219). Rancangan testing. (hlm. 220). Indikator yang akan digunakan. (hlm. 220). Penilaian. (hlm. 221).
Dikatakan pula oleh Xu dan Wu bahwa testing yang baik adalah yang memiliki kesahihan1 dan keterandalan2, serta memiliki pula tingkat kesulitan dan keragaman yang jelas. Bab V dari buku ini menyajikan perangkat silabus dari suatu kegiatan belajar mengajar di kelas dalam satu periode. Dijabarkan bahwa dalam silabus, sebaiknya, terdapat rancangan proses pengajaran. Proses pengajaran tersebut berupa apa yang akan diajarkan, pendistribusian waktu, dan langkah-langkah yang dilakukan. Selain silabus, buku ini juga menyajikan rancangan persiapan pengajaran untuk pengajar. Di dalam rancangan persiapan pengajaran tersebut terdapat satuan Tujuan dan Harapan Pengajaran, Pendistribusian Waktu, Sasaran dan Kesulitan Pengajaran, Metode Pengajaran, Pengulangan, Prapenyampaian Materi Baru, Penjelasan Materi Baru, Latihan Materi Baru, dan Pekerjaan Rumah. Rancangan pengajaran ini sangat diperlukan baik oleh lembaga pengajaran maupun pengajar bahasa, karena rancangan silabus tersebut merupakan refleksi dari kegiatan di kelas. Seiring dengan peran aktif Cina dalam era globalisasi, bahasa Cina menjadi sarana dan jembatan yang amat penting, maka tidak mengherankan jika banyak orang mulai mengantisipasi keadaan tersebut di atas dengan mulai memelajari bahasa Cina. Namun untuk mengajarkan bahasa Cina secara efektif, tentunya diperlukan metode yang tepat. Buku ini adalah buku yang dapat dijadikan bahan acuan pengajar untuk mengajar bahasa Cina sebagai bahasa asing secara efektif. Buku ini dapat menuntun pengajar agar dapat mengajar di kelas secara sistematis dan terarah dengan tuntunan baik secara teoritis maupun praktis. Dengan mengikuti pedoman-pedoman yang terdapat di dalam buku tersebut, pengajar akan memiliki cara-cara pengajaran
1
diukur.
2
Sebuah tes memiliki kesahihan bila tes tersebut mengukur keahlian yang seharusnya Sebuah tes memiliki keandalan bila hasil tes tersebut konsisten.
168
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
di kelas yang dapat diandalkan. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan menjadi efektif. -------------------------------------B. Herry Priyono, Anthony Giddens: suatu pengantar. Cetakan kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003, 98 hlm. (Cetakan pertama 2002). ISBN 979-9023-85-8. Harga: Rp15.000,00 (soft cover). Diah Madubrangti Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia diahjiro@yahoo.com Dualitas struktur dan pelaku menunjukkan bahwa pelaku dikepung struktur. Sebaliknya, sangatlah sulit untuk memahami bahwa struktur mengandalkan pelaku. Itulah salah satu paparan yang dikemukakan oleh Herry Priyono, penulis buku saku Anthony Giddens: suatu pengantar. Dalam buku tersebut, ia ingin memetakan pemikiran dasar Giddens yang luas, tetapi hanya dalam bentuk buku saku. Ia menulis buku saku ini karena terkesan pada Giddens yang mengajarinya tidak ada aksi tanpa teori. Sebagai mahasiswa program doktor bidang Ekonomi-Politik dan Sosiologi yang pada waktu itu dosennya adalah Anthony Giddens, Priyono berusaha memahami sosok Giddens sebagai seorang teoritikus yang tidak pernah memisahkan tindakan dari teori. Pemetaan pemikiran dasar Giddens ini ditulis oleh Priyono dalam tiga bagian, yaitu pertama, refleksi diri Giddens terhadap teori lain, kedua, beberapa terobosan teori Giddens, dan ketiga, ringkasan penerapan teorinya. Priyono menguraikan cara pandang Giddens dalam mengelompokkan struktur pada halaman 24-26. Pertama, struktur signifikasi (signification), yaitu struktur yang berhubungan dengan pengelompokan dalam simbol, pemaknaan dan wacana. Kedua, struktur penguasaan (domination), yaitu struktur mencakup penguasaan orang dalam pengertian penguasaan politik dan ekonomi. Ketiga, struktur legitimasi (legitimation), yaitu struktur yang berkaitan dengan peraturan normatif yang terdapat dalam tata hukum. Uraiannya diungkapkan dalam bentuk tabel dan contoh-contoh dengan mengambil situasi yang ada pada masa Orde Baru. Kerangka berpikir Giddens dalam bidang ilmu-ilmu sosial berbeda dengan kerangka berpikir para teoritikus ilmu-ilmu sosial seperti Talcott Parsons, Karl Marx, dan Levi- Strauss, walaupun sebenarnya kerangka berpikir Giddens dibangun berdasarkan pemahaman Giddens melalui kritikan-kritikan terhadap teori fungsionalisme, marxisme, dan strukturalisme. Menurut
RESENSI BUKU
169
Giddens (1984: 12-20) dalam perspektif ilmu-ilmu sosial pemahaman dinamika masyarakat selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu, dan pelaku dan tindakan pelaku . Pandangan Erving Goffman dan Talcott Parsons tentang pengertian pelaku dan tindakan pelaku diuraikan oleh Priyono, bahwa setiap anggota masyarakat adalah pelaksana peran sosial tertentu yang membentuk satu sistem sosial dan setiap sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Priyono (hlm. 9-10) dalam memaparkan pandangan Giddens mengungkapkan bahwa Giddens ingin menghapus istilah fungsi (function) dari ilmu-ilmu sosial dan ingin mengembangkan teori strukturasi sebagai suatu manifesto contra fungsionalism karena Giddens tidak bisa menerima pandangan pada teori fungsionalisme yang mengatakan bahwa sebuah sistem sosial mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan pada teori fungsionalime mempunyai syarat fungsional yang harus dipenuhi, yaitu goal tujuan, adaptation adaptasi, intergration integrasi, dan latency tuntutan. Giddens membedakan dimensi ruang dan waktu dalam menjelaskan gejala sosial. Hubungan antara ruang dan waktu bersifat kodrati dan menyangkut makna serta hakikat tindakan itu sendiri, karena pelaku dan tindakan tidak dapat dipisahkan. Priyono memberikan contoh, bahwa tindakan dosen berbicara di ruang kelas pada jam-jam tertentu disebut berkuliah (hlm. 37). Maksudnya, ia ingin memetakan pernyataan Giddens bahwa tanpa ruang dan waktu tidak ada tindakan, sedangkan dalam pandangan Talcott Parsons, tindakan dalam bentuk apapun merupakan pelaksana peran-peran sosial tertentu. Selain itu, setiap tatanan masyarakat selalu dikaitkan dengan peran sosial dan fungsi (function). Giddens tidak menyetujui dengan pernyataan Parsons bahwa di dalam sistem sosial terdapat fungsi. Menurut Giddens, sistem sosial tidak mempunyai kebutuhan apapun terhadap pelaku. Yang mempunyai kebutuhan adalah para pelaku itu sendiri, karena pelaku adalah peran sosial. Pada sistem sosial, ada nilai (value) yang mengikat tindakan setiap individu sebagai anggota masyarakat dalam peran sosialnya, entah sebagai seorang guru, buruh, murid ataupun manajer. Terhadap pernyataan ini, Priyono (hlm. 12) mengungkapkan kritikan Giddens dengan cara membuat tabel logika terhadap bagian dan keseluruhan konsepsi dasar fungsionalisme dan strukturasi. Dalam marxisme klasik, untuk memahami dinamika masyarakat, pandangan berbagai segi kehidupan masyarakat dikaitkan dengan sistem kapitalis. Priyono (hal. 32-39), lebih banyak memaparkan kritikan Giddens terhadap pemikiran Karl Marx mengenai sistem kapitalisme. Menurut Giddens, dinamika masyarakat terjadi bukan pada reduksi struktur dominasi pada penguasaan alokatif ekonomi, tetapi terjadi karena proses stukturasi dalam bentuk reproduksi praktik sosial dan sistem kapitalisme. Yang dimaksud struktur dominasi pada penguasaan alokatif ekonomi oleh Priyono, sebenarnya mengacu pada hubungan sosial pada tataran struktur dengan kekuasaan yang berhubungan dengan kapasitas keterlibatan dalam hubungan
170
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
sosial itu. Kapitalisme membutuhkan teknologi dan inovasi teknologi. Hal ini dikoordinasi dalam praktik sosial yang berlangsung melalui ruang dan waktu (lihat Giddens 1984). Dalam gagasan marxisme, pelaku dan struktur bersifat fungsional karena perubahan terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat melalui kontradiksi sistem yang satu dengan sistem yang lain. Menurut Marx (hlm. 33), perubahan terjadi melalui mobilisasi struktur dominasi, maksudnya terbentuk dalam dan melalui penguasaan alokatif terhadap barang dan penguasaan otoritatif terhadap orang. Menurut Giddens, dalam logika strukturasinya, dikatakan bahwa perubahan terjadi melalui transformasi yang muncul secara periodik. Struktur tidak mengkoordinasi suatu interaksi sosial yang baru, tetapi mengoordinasi perubahan yang terjadi dalam interaksi sosial. Setiap perubahan terjadi pada struktur dalam sistem sosial dan berkembang sangat cepat seiring perjalanan zamannya. Strukturalisme yang dipelopori oleh Ferdinant de Saussure diterapkan dalam analisis bahasa oleh Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss cenderung menyingkirkan subjek dengan menempatkan sifat manasuka (arbitrary) dan perbedaan (difference) sebagai pembentuk identitas. Giddens selalu melihat fakta dan perbedaan sebagai subjek yang selalu dikaitkan dengan perbedaan dalam fakta, misalnya perbedaan antara bahasa (langue) dan ujaran (parole), the agent pelaku dan agency tindakan pelaku, structure dan structuration (lihat Giddens 1984). Priyono memberi contoh mengenai fakta dan perbedaan yang ada pada sistem kekuatan militer pada zaman Soeharto, tetapi uraian yang disampaikan oleh Priyono hanya bersifat informatif. Dikatakannya bahwa negara dan bangsa pada masa itu menunjukkan prinsip strutural dalam konteks militerisme. Militer mengkoordinasi praktik kontrol atas peran sosial (hlm. 43-44). Giddens lebih dapat memahami pemikiran kaum strukturalisme daripada fungsionalisme, walaupun keduanya menunjukkan adanya penyingkiran subjek. Giddens lebih menaruh simpati pada beberapa aspek strukturalisme daripada fungsionalisme, karena kehadiran subjek dalam strukturalisme masih tetap ada. Priyono menuliskan penjelasan waktu dan ruang berdasarkan teori Giddens, yaitu teori strukturasi, bukan strukturalisme. Strukturasi berarti kelangsungan suatu proses hubungan antara pelaku tindakan dan struktur. Ia memberi contoh kehidupan masyarakat tradisional di daerah Jawa Tengah yang melakukan transaksi jual-beli tanpa ditentukan oleh kesatuan ruang dan waktu. Seseorang membeli barang di Wonosari, dan menjualnya di Kota Gede (hlm. 40). Proses jual-beli yang berulang kali memakai keterikatan waktu dan ruang dalam konteks manajemen modern, menurut Priyono tidak sesuai bila menggunakan teori strukturasi. Menurut Giddens (hlm. 43), ada empat gugus reflektivitas-institusional yang membentuk dan menyangga modernitas, yaitu kapitalisme (capitalism), negara-bangsa (nation-state), kekuatan militer (military power), dan pembangunan (created environment).
RESENSI BUKU
171
Priyono menjelaskan juga konsep-konsep Giddens (hlm. 40-49), antara lain konsep relasi dualitas Giddens, yaitu konsep yang menguraikan hubungan pelaku dan struktur, serta hubungan ruang dan waktu. Kedua hubungan ini saling terkait dan membentuk pola hubungan dalam praktik sosial, karena melalui peristiwa yang terjadi berulang kali akan terpola hubungan dalam praktik sosial. Priyono juga menjelaskan konsep objektivitas struktur yang dikatakan oleh Giddens tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktik sosial. Priyono menyampaikan bahwa objektivitas struktur dalam strukturasi berbeda dengan struktur dalam fungsionalisme dan strukturalisme. Konsep hermeneutika ganda tidak terlepas dari ilmu-ilmu sosial dan objek kajiannya. Giddens mengatakan, bahwa hermeneutika ganda (double hermeneutic) adalah arus timbal balik antara dunia sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan wacana ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan sosial (hlm. 52). Hal ini dipahami Priyono sebagai transformasi yang dibawa oleh sains dan teknologi, kemudian melalui praktik sosial, peran dualitas pelaku dan struktur melibatkan konsep-konsep dan teori oleh ilmuwan sosial. Kaitan ilmu sosial dan praktik sosial merupakan hubungan timbal balik antara yang dikaji oleh para ilmuwan sosial. Bentuk (form) dan isi (content) dalam praktik sosial merupakan prasarana yang diperlukan.dalam menghadapi modernitas. Modernitas menghasilkan sejumlah profesional dalam sains dan teknologi. Berdasarkan konsep-konsep Giddens, Priyono berusaha memaparkan pemahaman teori Giddens dalam tiga kategori struktur, yaitu struktur penandaan, struktur penguasaan, dan struktur pembenaran. Dijelaskan oleh Priyono, bahwa penggunaan istilah kekuasaan perlu dibedakan dengan istilah dominasi pada tataran struktur. Dalam teori strukturasi Giddens, kekuasaan bukan gejala yang terkait dengan struktur atau sistem, melainkan tergantung dari kemampuan pelaku (subjek) dalam paktik sosial atau interaksi sosial. Perubahan kemampuan pelaku selalu terjadi dalam proses strukturasi. Di dalam kesimpulannya, Priyono mengatakan bahwa teori strukturasi mencerminkan kerangka pemikiran karya-karya Giddens. Dikatakan pula bahwa Giddens menyadari bahwa teori struturasi ada kelemahannya dan masih jauh lebih memadai daripada lainnya. Priyono menilai sebagai orang yang ingin menunjukkan adanya keseimbangan antara analisis makro dan mikronya. Priyono mengklasifikasikan konsep-konsep dan teori Giddens dengan membuat skema tentang signifikasi (signification), dominasi (domination), dan legitimasi (legitimation) (hlm. 25). Selain itu, ia juga membuat tabel mengenai stuktur sosial, sistem sosial, dan praktek sosial (hlm. 32). Dari uraiannya, gagasan-gagasan yang menjadi kerangka berpikir Giddens dapat digunakan dalam berbagai masalah, baik mengenai negara, bangsa, modernitas, globalisasi, maupun identitas diri. Melalui buku saku ini, Priyono memperlihatkan usaha untuk memaparkan pemikiran Giddens dengan memperkenalkan teori strukturasi kepada pembaca. Dari segi isi, paparan teori sebagai sintesis baru sudah cukup jelas, walaupun dari segi keterbacaan banyak kalimat yang sulit dicerna maknanya.
172
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
Misalnya, penggunaan istilah strukturasi (structuration), yang berarti menunjukkan hubungan pelaku dengan struktur sebagai relasi dualitas, atau penggunaan istilah pencabutan (disembedding), yang berarti pemisahan antara ruang dan waktu. Hal ini membuat pembaca harus berulang kali membacanya. Secara keseluruhan, buku ini dapat direkomendasikan untuk dibaca sebagai buku saku yang memuat informasi awal untuk mengetahui pemetaan kerangka berpikir Giddens. Walaupun penjelasannya tidak gamblang, pembaca mudah mengenal teori strukturasi dengan sintesis baru yang menguraikan kinerja subjek dalam peran sosialnya. Buku ini menyajikan terobosan sintesis baru Giddens mengenai dualitas pelaku dan struktur dengan mengangkat pelaku sebagai subjek tindakan.
Daftar Pustaka
Anthony Giddens. 1984. Constitution of Society (Outline of the Theory of Structuration). Berkeley, LA: University of California Press. -------------------------------------Yasraf Amir Piliang. Hiper-moralitas; Mengadili Bayang-Bayang. Yogyakarta: Belukar, 2003, iv + 176 hlm. ISBN 979-96572-0-2. Harga: Rp20.000,00 (soft cover). Selu Margaretha Kushendrawati Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia boendamargie@yahoo.com Pemahaman filosofis tentang dunia yang serba hiper merupakan sebuah ciri khas dari pemikiran pascastrukturalis. Para filsuf pascamodernis ini sangat antusias dengan perubahan revolusioner yang terjadi di dunia. Perubahan itu, di mata mereka, dibaca sebagai keadaan yang serba tidak beraturan (chaos), indeterministis, dan kemajuan atau progresitas yang tidak terkendali, simulasi, banalitas, kemubaziran segala hal dan hilangnya pemaknaan. Pada titik yang ekstrem, pandangan seperti ini akan sampai pada kehampaan. Menghadapi tatanan sosial dan perkembangan teknologi serta media komunikasi yang berlari di luar jangkauan kontrol akal sehat manusia, sebagian dari pemikir kontemporer melihat bahwa di ujung dari perkembangan tersebut terdapat kehampaan makna. Di Indonesia tema-tema seperti itu antara lain dapat ditemukan dalam Hiper-moralitas; Mengadili Bayang-bayang dari Yasraf Amir Piliang. Melalui kumpulan tulisan dosen tamatan Central Saint Martins College of Art
RESENSI BUKU
173
& Design dari London ini, pembaca diajak untuk mengeksplorasi dunia kekinian dengan kacamata pemikiran yang penuh dengan nuansa kekacauan, pemutarbalikan, dan indeterminisme. Buku Hiper-moralitas ini merupakan sebuah buku menarik karena isinya langsung berkaitan dengan situasi nyata yang dialami bangsa Indonesia pascakejatuhan Soeharto tahun 1998. Maksudnya, meskipun rezim orde baru secara de jure telah runtuh dan Soeharto sendiri telah lengser, secara de facto berbagai kecurigaan tentang kejahatan ekonomi, politik dan idelogi seakan-akan tetap tak tersentuh oleh hukum dan keadilan hingga saat ini. Kata hiper-moralitas dalam judul buku ini sebenarnya istilah khas Jean Baudrillard. Namun, dalam buku ini Yasraf rupanya mengacu pada konsep hypermorality dari George Bataille, konsep krisis legitimasi dari Jrgen Habermas, dan konsep abjeksi atau moralitas mengambang dari Julia Kristeva (hlm. 20-21). Buku yang berupa bunga rampai 30 artikel lepas, yang pernah diterbitkan di harian Kompas dari bulan April 1998 sampai dengan Januari 2001 ini disusun dalam lima bagian ditambah dengan prolog sebagai pendahuluan dan epilog sebagai penutup. Kecuali prolog dan epilog yang masing-masing berupa sebuah artikel, kelima bagian lain dari buku ini terdiri dari berbagai artikel. Pada Prolog, artikel yang dipakai Yasraf adalah Post-chaotic Society. Pada bagian Pertama yang berjudul The Perfect Crime: Realitas-Realitas Hiper terdapat lima artikel, yakni Hiper-moralitas, Hiper-kriminalitas, Hiperdemokrasi, Hiper-otonomi, dan The Perfect Crime: Hiper-realitas Timor Timur. Bagian Kedua yang berjudul Justice Game: Bahasa Politik Kekuasaan diisi dengan tiga artikel, yakni: Justice Game: Mengadili Bayang-bayang, Horrocracy: Politik Menjemput Maut, dan Libidosophy: Revolusi Mentalitas Bangsa. Bagian Ketiga yang berjudul Terorisme Virtual: Mesin-Mesin Horor terdapat enam artikel, yakni Horrosophy, Terorisme Virtual, Chaosophy, Mikro-Fasisme: Mesin-mesin Antidemokrasi, Parasit Politik, dan Pseudosophy: Mesin-mesin Kepalsuan. Bagian Keempat yang berjudul The Positive Chaos: Bangkit dari Kegelapan terdapat enam artikel, yakni The Positive Chaos: Masa Depan Pluralitas Bangsa, Dekonstruksi Kultural dan Masa Depan Bangsa, Geo-politik, Demokrasi Dialogis, Heteronomi, dan Harapan Positif, Membangun Imajinasi Kolektif Bangsa. Bagian Kelima yang berjudul Pornokitsch: Kebudayaan di Akhir Milenium terdapat tiga artikel, yakni Centraphobia: Refleksi menjelang Akhir Abad ke-21, Mitos Milenium Ketiga, dan Pornokitsch. Pada Epilog Yasraf menempatkan sebuah artikel berjudul Milenium Ketiga dan matinya Pascamodernisme. Melalui buku ini Yasraf mencoba menerapkan berbagai pemikiran Baudrillard dan para pemikir postmodern lainnya untuk menganalisis situasi masyarakat Indonesia, khususnya di era pascakejatuhan Soeharto. Yasraf seakan menemukan sebuah miniatur realitas yang sedikit banyak cocok dengan apa yang didengungkan oleh para pemikir kontemporer seperti Baudrillard. Realitas yang dimaksud adalah situasi chaos yang dialami bangsa Indonesia setelah keluar dari dunia otoriter, serba seragam, dan sentralistis ala Soeharto. Munculnya berbagai krisis multidimensi, termasuk
174
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
di dalamnya krisis moralitas yang menimpa bangsa Indonesia, dibaca oleh Yasraf sebagai petanda yang cocok dengan pemikiran pascastrukturalis. Walaupun pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Baudrillard, Yasraf berusaha menghindari jebakan nihilisme sebagaimana yang dialami oleh Baudrillard, yang mengajarkan bahwa menghadapi perkembangan dunia yang supercepat dan di luar kendali manusia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal ini Yasraf masih sedikit optimis dengan menawarkan semacam solusi (hlm. 15-16). Solusi tersebut adalah ketidakberaturan (chaos) yang menyatu dengan keteraturan (cosmos). Untuk itu, ia memperkenalkan konsep kemanunggalan chaos dan cosmos. Perpaduan antara cosmos dan chaos ini sudah terbaca sejak bagian Prolog dari bukunya. Di bagian ini ia membuat dikotomi antara pemerintahan Gus Dur - yang serba tidak menentu, tidak berarah, indeterministis, membawa masyarakat dalam kegalauan, dan diwarnai ritus-ritus kekerasan sebagai buah dari kebebasan yang berlebihan - dan pemerintahan Megawati yang dibacanya sebagai pemerintahan yang mulai menanamkan benih-benih keteraturan (hlm. 15). Pada bagian Pertama ini Yasraf seakan menemukan contoh arah yang baru dalam menerapkan pemikiran kritis kaum pascastrukturalis. Jika para pendahulunya berkaca dari realitas kontemporer dengan kemajuan tak terkendali yang melekat dalam kapitalisme global, maka Yasraf mencoba menerapkan pemikiran tersebut untuk memahami efek-efek negatif (bahkan kemunduran) dari kapitalisme global, khususnya yang menimpa bangsa Indonesia di akhir 1990-an. Yasraf berhasil menerapkan berbagai konsep serba hiper (hiper-moralitas, hiperkriminalitas, hiperrealitas dan sebagainya) dalam konteks realitas kebangsaan Indonesia. Dengan konsep hiperkriminalitas ini Yasraf seakan mengajak pembaca untuk melupakan kejahatan Soeharto, bukan karena alasan kemanusiaan, tetapi karena sedemikian sempurnanya kejahatan yang dilakukan tersebut sehingga tidak satu pun yang dapat mengungkapkannya. Dalam bagian Kedua, dalam sebuah artikel yang berjudul Justice Game: Mengadili Bayang-Bayang Yasraf mencoba untuk kembali memakai jasa pisau analisis pascastrukturalis untuk menganalisis berbagai kesemuan (kebohongan) yang secara kasat mata terjadi di Indonesia (khususnya di era pascakejatuhan Soeharto). Baginya, fenomena reformasi atau seruan perubahan di berbagai bidang oleh berbagai elemen masyarakat pascakejatuhan Soeharto dapat dianalisis pula dengan konsep dekonstruksi ala Jacques Derrida. Dengan konsep itu Yasraf melihat reformasi sebagai sebuah dekonstruksi atas oposisi biner yang melekat dalam politik dan budaya Orde Baru (hlm. 116). Selain pemikiran Baudrillard dan Derrida, beberapa artikel dalam buku ini juga melibatkan pemikiran Julia Kristeva untuk mendiagnosisnya. Perspektif pascastrukturalis yang cenderung menentang sistem yang stagnan (status quo) yang terbaca dari tulisan-tulisan Yasraf dalam buku ini, tampak sangat cocok untuk memahami realitas kebangsaan di Indonesia akhirakhir ini. Jika para pemikir-pemikir besar seperti Baudrillard memakai latar situasi kapitalisme global dengan segala kemajuannya, maka Yasraf justru
RESENSI BUKU
175
mengambil potret-potret kemunduran dan stagnasi ekonomi dan bidang kehidupan sosial lainnya sebagai realitas yang dijadikan acuannya. Ada satu artikel yang juga menarik di dalam buku ini, khususnya dalam bagian akhir atau Epilog (hlm. 165-171), yang membahas tentang milenium ketiga dan matinya pascamodernisme. Dengan bercermin pada anomali yang terjadi di Asia belakangan ini, yang ditandai dengan krisis ekonomi yang mewabah, Yasraf kemudian mempertanyakan grand narrative manakah yang layak ketika tiga pemain besar atau tatanan sebelumnya telah gagal menciptakan dunia yang ideal. Ketiga tatanan yang dimaksud adalah agama, militer, dan ekonomi pasar. Menurut Yasraf, pada masa lalu ketika agama mendominasi, dunia diperkenalkan pada kedamaian dan persatuan seluruh umat manusia. Akan tetapi agama gagal menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Lalu, ketika militer yang berkuasa, bahasa kekuasaan merembes ke dalam setiap pola relasi dan kehidupan masyarakat, dunia mengalami perkembangan inovasi teknologi yang pesat. Pada akhirnya, ketika kekuatan ekonomi yang mendominasi, kehidupan masyarakat dikalkulasi dalam prinsip untung-rugi dengan pasar global sebagai media komunikasi yang dapat menyatukan bangsa-bangsa. Dalam tulisan Yasraf ada kecenderungan untuk mereduksi segala permasalahan yang ada ke dalam solusi-solusi eskatologis agama. Di samping berbagai usaha reformasi yang lain, usaha yang paling layak untuk dimajukan dalam mengatasi masalah yang dikemukakan Yasraf dalam buku ini adalah melalui penguatan masyarakat sipil (civil society) yang cerdas dan mampu berpikir secara kritis. Dengan meningkatkan komunikasi aktif serta masyarakat sipil sebagai motor penggeraknya maka hiperkriminalitas, simulasi, banalitas, dan hiperrealitas akan mendapat lawan yang seimbang. Hanya manusia yang sadar dan kritislah yang berani mengatakan tidak kepada berbagai permasalahan tersebut. Yang menarik dan patut diapresiasi dari buku ini adalah gaya tulisannya yang cenderung menciptakan kemudahan pemahaman bagi para pembaca, terutama bagi para pembaca yang agak asing dengan dunia filsafat. --------------------------------------
176
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
Fabrice Thumerel, La critique littraire. Cetakan kedua. Paris: Armand Colin, 2002, 184 hlm. (Cetakan pertama tahun 2000). ISBN 2-200-26355-4. Soft cover. Talha Bachmid Fakultas Ilmu Pengetahuan Buadaya Universitas Indonesia tbachmid@yahoo.fr Buku yang disusun oleh seorang kritikus sastra Prancis ini sebenarnya ditujukan kepada mahasiswa tetapi juga sangat bermanfaat bagi mereka yang tertarik akan kritik sastra. Di dalam pengantarnya Thumerel mulai dengan sejumlah pertanyaan seperti: apakah kritik sastra dapat dianggap sebagai genre sastra tersendiri ataukah suatu meta wacana sastra, apakah kritik sastra harus masuk ke dalam wilayah kesusastraan atau berada di wilayah tepi kesusastraan, dan sejumlah pertanyaan lain, yang dijawabnya melalui empat bab, yaitu (a) apa kritik sastra itu, (b) sejarah perkembangan kritik sastra, (c) tiga jenis kritik sastra, dan (d) metode-metode kritik sastra. Jawaban atas pertanyaan apa kritik sastra itu beragam tergantung pada zaman, filsafat atau ideologi yang mendasari aliran-aliran kritik maupun penulisnya. Beberapa definisi diajukan mulai dari definisi paling sederhana hingga suatu definisi terinci sebagai berikut: kritik sastra adalah (1) seni menilai karya, (2) seni menikmati karya, dan (3) kemampuan menjelaskan karya. Dalam menilai karya, kritik sastra, sesuai etimologinya, adalah seni melihat kelebihan dan kekurangan karya-karya utama. Sebagai penilai karya, seorang kritikus dapat melakukan kritik yang bersifat a priori, artinya ia merumuskan norma-norma, membuat klasifikasi, dan kaidah-kaidah genre bagi pengarang dan karyanya dan kemudian menentukan bahwa yang disebut mahakarya adalah hanya yang mengikuti norma dan kaidah genre. Atau kritik yang bersifat a posteriori, yaitu yang mengabstraksikan kesan-kesan pribadi guna menilai kelebihan serta orisinalitas sebuah karya dalam konteks horison sosial budaya. Sebagai seni menikmati karya, kritikus memusatkan perhatiannya pada pengarang dan berusaha membangun lingkungan artistik pengarang. Kritik ini dibagi dalam kritik identifikasi dan kritik impresionis. Sedangkan dalam upaya menjelaskan karya, seorang kritikus bisa bersikap menolak kemungkinan seseorang merambahi misteri seni, atau sebaliknya, menganggap bahwa proses kreatif dapat dijelaskan (aliran positivisme). Dua tabel yang sangat membantu pembaca memahami rumitnya kritik sastra, yaitu yang berusaha memetakannya dalam pemilahan cukup sederhana, diletakkan dalam subab 2 dengan judul tipologi-tipologi dan
RESENSI BUKU
177
tabel sinoptik. Melalui dua tabel ini pembaca kemudian dapat memilih jenis kritik sastra yang ingin didalaminya, dan melanjutkan keingintahuannya melalui daftar pustaka yang sangat lengkap. Pada bagian terakhir bab ini dibicarakan batas-batas kritik dalam empat subbab, yaitu (1) tentang perkembangan kritik sastra dari kritik murni hingga ke anti-kritik, yaitu yang mempertanyakan kembali tradisi dan makna-makna yang sudah mapan; (2) hubungan antara kritik sastra dengan ilmu (pada abad ke-19, istilah ilmu kesusastraan diperkenalkan); (3) pendapat-pendapat tentang hubungan di antara keduanya; dan (4) masalah subjektivitas dan objektivitas dalam kritik sastra. Bab ini diakhiri dengan masalah objektivitas dan subjektivitas dalam kritik sastra yang dibahas dengan mengutip pendapat-pendapat berbagai kritikus maupun sastrawan. Kritik yang bersifat subjektif ditunjukkan melalui beberapa contoh, dengan penekanan pada upaya memihak, menunjukkan kedekatan erat dengan karya serta bersifat politis; demikian pula kritik yang disebut objektif ditunjukkan melalui sudut pandang kritikus yang mempertahankan pentingnya objektivitas. Mungkin di sinilah kita menemukan kesulitan dalam memanfaatkan buku ini, karena terlalu banyak kutipan dari kritikus, sastrawan dan penulis yang sebagian besar tidak dikenal di Indonesia. Namun, tentunya itu seharusnya mendorong pembaca mencari tahu dengan mencari sumber aslinya atau paling tidak mencari informasi tambahan. Keingintahuan adalah dorongan paling ampuh untuk memperluas wawasan. Dalam Bab Kedua, sejarah panjang kritik sastra di Prancis ditelusuri melalui empat subbab: asalmula kritik sastra, kritik sastra abad ke-19, era perubahan, dan kritik sastra dari kejayaan hingga ke krisisnya. Dalam subbab pertama, dipaparkan sejarah kritik sastra yang berawal dari pemikiran Aristoteles. Dimulai dengan Aristoteles, kemudian dilanjutkan dengan kritik dogmatik, kejayaan ideologi normatif, lalu dengan kritik estetik yang otonom sifatnya, dan diakhiri dengan uraian ringkas tentang filologi, kritik sejarah dan kritik jurnalistik. Dalam subbab kedua mengenai kritik sastra pada abad ke-19, mulamula dibahas dua jenis kritik, yaitu kritik ideologis dan kritik ilmiah. Kemudian dijabarkan kritik sejarah yang terdiri dari sejarah sastra pada masa Romantisme, sejarah sastra yang berwawasan ilmiah, dan pembaharuan filologi. Setelah itu, dipaparkan berkembangnya kritik jurnalistik dengan pesat serta kritik akademis atau yang disebutnya kritik oleh para pengajar. Subbab ketiga berisi perubahan atau, meminjam istilah penulis, mutasi, khususnya pada paruh pertama abad ke-20. Di sini dibahas apa yang disebut kritik berdasarkan penelitian yang terdiri dari konsep Lanson yang disebut lansonisme, kritik filologi modern, dan kritik biografi. Dari topik-topik perubahan yang terjadi pada awal abad ke-20 ini, mungkin yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah kenyataan bahwa perubahan-perubahan itu sejalan dengan terjadinya keterputusan dengan teori-teori besar. Sejarah kritik sastra bergerak seiring dengan sejarah kesusastraan, mengikuti konflikkonflik antara tradisi dan inovasi, menjadi cermin perkembangan sosial dan
178
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
pemikiran seperti tradisi Yunani-Romawi, pemikiran abad pencerahan (abad ke-18), positivisme, pemikiran Freud, eksistensialisme, pemikiran Saussure, dan dekonstruksi. Sementara kritik masa klasisisme menentukan modelmodel genre yang dianggap abadi, abad ke-19 menghasilkan pengarangpengarang produk zamannya, dan abad ke-20 menciptakan teks-teks yang diproduksi oleh ketidaksadaran atau oleh subjek plural dan dihubungkan dengan berbagai interteks sosiobudaya maupun sastra. Di akhir Bab Kedua ini, sedikit dijabarkan masa postmodern yang ditandai dengan krisis kritik sastra, hidupnya kembali kritik sejarahan, dan kritik plural atau juga disebut kritik total yang menggabungkan kritik sejarahan, kritik estetik, kritik akademis. Diharapkan kritik semacam itu mampu memperkecil jarak antara kritikus dengan pembaca dan dengan karya. Memang ada kritikus yang tidak setuju dengan kritik plural itu dan mengusulkan kritik dialogis yaitu yang tidak berbicara mengenai karya tetapi kepada atau dengan karya. Namun, kritik semacam itu hanya mungkin kalau kita menganggap karya sastra menyampaikan nilai-nilai, tetapi tidak membawa kebenaran sejarah; kritik tidak bersembunyi di balik objektivitas semu tetapi mengambil pihak karena kritik sastra adalah juga pencarian kebenaran dan nilai-nilai Tiga macam kritik sastra yang dijabarkan di dalam Bab Ketiga adalah kritik jurnalistik, kritik akademis, dan kritik oleh pengarang. Tujuan instruksionalnya adalah bahwa mahasiswa mendalami perbedaan-perbedaan yang dibahas tentang ketiga jenis kritik sastra itu, dan mengenal karya-karya kritik akademis maupun kritik oleh pengarang yang diakui terkenal dan menarik. Mengenai kritik jurnalistik, sebenarnya telah cukup dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan di dalam subbab ini ditunjukkan apa saja kegiatan kritikus-wartawan, apa saja tujuan-tujuannya dan kekurangankekurangannya. Mula-mula ditunjukkan bahwa status wartawan beragam tergantung medianya, apakah audiovisual atau media cetak, di surat kabar berskala nasional atau regional, atau di majalah. Tujuan profesi ini antara lain menjadi jembatan antara pengarang dan pembaca dan memperdengarkan suara yang lebih orisinal di tengah-tengah meriahnya suara media massa yang cenderung melayani komsumsi massa (Eric Faye dalam majalah La Quinzaine littraire 1997). Selain itu beberapa pengarang terkenal mengecam profesi itu dengan menyatakan antara lain bahwa jurnalisme mengetengahkan apa yang menarik hari ini tetapi kurang menarik esok; atau komentar seperti membuat ringkasan atau pujian terhadap karya yang terbit di pasaran, bukanlah kritik sastra, melainkan hanya dapat disebut kronik karya-karya yang terbit, dengan tujuan mengiklankan, atau mendorong orang membacanya. Tujuh dosa kritik jurnalistik dipaparkan di sini, yaitu bahwa, pertama kritikus cenderung memiliki sifat-sifat buruk seperti kikir (tidak membeli bukunya), iri hati (karena tidak bisa mencipta sendiri), angkuh (merasa sangat dibutuhkan oleh pengarang), dan malas (sering tidak membaca buku secara keseluruhan atau dengan terlalu cepat). Dosa kedua adalah yang disebut kesetiaan kepada komunitas sehingga wartawan-kritikus sering terlibat
RESENSI BUKU
179
kolusi dengan penerbit dan pers, sedangkan dosa ketiga adalah kedangkalan kritik mereka karena oleh keinginan untuk menilai kebaruan sebuah karya, mereka agak memaksa tanpa penelitian sebelumnya. Tujuan utamanya adalah menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Dosa keempat adalah keberpihakan kepada ideologi tertentu dan sistematisme yang menyebabkan mereka bersikap konservatif dan normatif; pengarang sering dimasukkan ke dalam kotak tertentu. Dosa kelima adalah kurangnya pendidikan kritikuswartawan pada umumnya, yaitu tidak mengenyam pendidikan tinggi dan tidak mengenal kesusastraan Prancis dengan baik. Itu menyebabkan seringnya kritikus membandingkan beberapa karya atau penulis yang tidak sama dan tidak bisa dibandingkan. Dosa keenam, yaitu rendahnya selera serta penilaian mereka, misalnya ketika mereka memilih karya best-seller untuk dipuji-puji tetapi mengabaikan karya yang justru tinggi nilai sastranya. Dosa terakhir adalah penggunaan bahasa yang sering mereduksi gagasan penting sebuah karya. Kritikus-wartawan dianggap menciptakan kosa kata tersendiri tetapi kekhasan itu justru merusak bahasa, seperti yang ditunjukkan lewat sebuah buku yang menjadi parodi kritik jurnalistik (Le Journalisme sans peine karangan M.-A Burnier dan P. Rambaud 1999). Dalam subbab dua dibicarakan kritik akademis, yaitu karya yang ditulis oleh para pengajar perguruan tinggi. Bourdieu membedakan pengajar tersebut menurut usia, kepakaran, ijazah yang dimiliki, tempat bekerja dan pengakuan yang mereka terima secara intern maupun ekstern. Juga dibedakan antara pengajar-peneliti dan pengajar yang berupaya menerapkan teori-teori yang dipelajari demi untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Di dalam artikelnya yang berjudul Homo academicus Bourdieu menjelaskan sifat akademisme kritik sastra yang dihasilkan oleh para pengajar itu, dan yang disebutnya kritik universiter pedagogis. Kegiatan menghasilkan karya kritik sastra merupakan semacam penghargaan (distinction) bagi seorang pengajar dan sering memberinya kewenangan untuk melakukan banyak hal. Pada akhir bab ini dibahas kritik yang ditulis oleh sastrawan. Sejak Corneille, pengarang drama abad ke-17, pengarang sering bereaksi terhadap tulisan kritikus terhadapnya dan reaksi itu sering dapat dianggap sebagai sebuah karya kritik pula. Dalam subbab ini dibahas beberapa hal, yaitu tema-tema serta protes mereka, ragam dan bentuk kritik sastrawan, dan beberapa penuliskritikus ternama. Mengenai tema serta protes pengarang, tercatat kecaman keras terhadap kritikus yang disebut penulis gagal yang mengritik penulis-penulis yang berhasil, dan ejekan terhadap kritikus sebagai orang-orang yang tidak mampu mencipta. Pengarang-pengarang tertentu bahkan membandingkan kritikus dengan hewan, seperti lebah yang hanya bisa berdengung (Flaubert), kuda nil yang memperlihatkan bobot sangat berat tetapi berkulit tipis (Gombrowics), atau seekor anjing yang masih hidup dibandingkan dengan pengarang yang bagaikan seekor singa yang telah mati, karena kritikus sering menilai karya pengarang yang sudah meninggal (Sartre). Bab Keempat, yaitu metode-metode kritik terdiri dari tiga subbab, yaitu (1) metode penelitian (critique erudite), (2) kritik hermeneutik, dan (3) kritik
180
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
tematik. Beberapa kritik hermeneutik dijabarkan, seperti sosiologi sastra, kritik psikoanalisa, kritik tematik dan kritik hermeneutik Paul Ricoeur. Sosiologi sastra diulas melalui tiga perspektif, yaitu penciptaan (Lucien Goldmann), teks (sosiokritik, Mikhail Bakhtine dan sosiosemiotik, Pierre Zima), dan pembaca (Jauss). Kritik hermeneutik Paul Ricoeur dijabarkan dengan agak panjang mungkin karena posisi Risoeur yang memang penting dalam pemikiran Prancis. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa buku ini bernilai khusus bagi mereka yang belajar kesusastraan, selain karena dilengkapi dengan tujuan instruksional khusus pada awal setiap bab. Juga di akhir setiap babnya diusulkan sejumlah topik yang dapat dikerjakan mahasiswa, misalnya dalam Bab Pertama sebagai berikut: Apakah kritik sastra harus berpihak? atau di Bab Kedua: Beri komentar terhadap pernyataan Todorov dalam Critique de la critique (1984): kritik sastra tidak harus membatasi diri pada pembahasan tentang karya, pada gilirannya kemudian, kritik harus menyatakan pendapatnya tentang kehidupan. Selain itu, dalam setiap bab disajikan satu atau dua contoh ulasan karya penulis Prancis terkenal, menurut aliran kritik tertentu. Kalau isi buku yang ditulis dalam bahasa Prancis ini terlalu padat, sehingga ada kesan semua informasi tentang kritik sastra berjejalan, di lain pihak, banyaknya kutipan dan acuan berupa namanama kritikus dan ahli sastra menjadi dorongan khusus bagi pembaca untuk segera melihat daftar pustaka yang sangat lengkap untuk bidang ini. Sangat diharapkan ada pengajar atau peneliti sastra yang kemudian berminat untuk menyederhanakan salah satu atau bahkan beberapa bagian buku ini sehingga lebih banyak lagi pembaca Indonesia yang dapat menikmatinya. -------------------------------------Firman Lubis, Jakarta 1950-an; Kenangan Semasa Remaja. Depok: Masup Jakarta, 2008, xxi + 329 hlm. ISBN 978-979-15706-3-3. Harga: Rp60.000,00 (soft cover). Achmad Sunjayadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia achmad.sunjayadi@ui.edu Jakarta menyimpan banyak cerita dan kenangan baik bagi para pendatang maupun penduduknya. Namun, cerita dan kenangan itu akan lenyap bila orang yang memiliki cerita dan kenangan itu telah tiada. Ditambah lagi tak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menuliskan kenangannya.
RESENSI BUKU
181
Generasi berikut sangat beruntung jika cerita dan kenangan tersebut dapat direkam, misalnya dalam bentuk tulisan maupun gambar (foto). Memang tidak semua kenangan dapat direkam. Namun, setidaknya potongan gambaran masa lalu dapat diketahui oleh generasi berikut. Salah satu upaya itu diwujudkan dalam Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja, tulisan Firman Lubis. Tahun 50-an merupakan masa peralihan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ke pemerintah Indonesia yang ketika itu masih balita. Tentu banyak cerita menarik seputar tahun 50-an yang tak kalah dengan gegap gempitanya masa revolusi. Oleh karena itu, kita berharap banyak munculnya cerita unik dan menarik dalam buku ini. Apalagi jika melalui kaca mata seorang remaja yang penuh gejolak dan semangat petualangan. Harapan itu hampir menjadi kenyataan. Lubis menceritakan cerita unik khas remaja, Misalnya cerita becak komplit, transportasi umum murah untuk rakyat yang juga berfungsi sebagai tempat bermesraan (hlm. 127), bermain layang-layang di atas atap rumah tanpa khawatir terkena setrum listrik (hlm. 243), mode celana pendek ketat yang ujungnya hanya sedikit di bawah pangkal paha (hlm. 251), razia celana ketat dan blue jeans yang ketika itu disebut celana jengki (dari kata yankee) oleh polisi dan tentara. Cara menentukan celana itu sempit atau tidak adalah dengan menggunakan botol. Celana dianggap ketat jika botol tidak dapat dimasukkan ke dalam kaki celana. Jika dianggap ketat maka celana akan digunting. Sedangkan celana blue jeans tanpa ampun langsung digunting (hlm. 252). Lalu cerita tentang gaya rambut ala Tony Curtis, gaya rambut tanpa belahan dengan jambul tinggi di tengah yang ditarik ke depan. Bagian kiri dan kanan rambut disisir ke belakang. Supaya tatanan rambut tidak cepat rusak karena angin dan tahan lama maka harus digunakan minyak rambut. Minyak rambut yang dipakai berbahan dasar vaseline pekat diberi minyak wangi menyengat. Salah satu merek terkenal adalah Lavender yang bisa dibeli di kaki lima (hlm. 253). Kenangan yang tak kalah menariknya adalah cerita tentang buku dan majalah porno yang ternyata sudah beredar pada masa itu. Menurut Lubis, buku-buku berbau porno itu berukuran saku dan kualitas cetakannya kurang bagus. Harganya pun lumayan mahal untuk kantong remaja. Biasanya buku porno itu tidak selalu berisi gambar yang merangsang tetapi dalam bentuk cerita. Misalnya buku serial Serikat 128 yang menceritakan sebuah organisasi rahasia yang membongkar dan melawan kejahatan. Cerita kriminal itu sering diselingi dengan cerita adegan porno yang merangsang birahi remaja (hlm. 274). Begitu pula dengan kisah si Jaim, tukang catut (calo) karcis bioskop Metropole atau Menteng. Anak kampung Pedurenan ini marah jika dipanggil si Jaim. Pria besar yang juga jagoan ini hanya mau dipanggil Eddy (hlm. 262). Namun, cerita-cerita menarik itu tidak langsung dapat kita baca. Pada bab-bab awal kita disuguhi dengan biografi penulisnya serta cerita-cerita yang mengacu pada peristiwa-peristiwa penting menjelang 1950-an seperti
182
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan serta perang revolusi. Firman Lubis menjelaskan alasannya menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang tentunya ditujukan bagi orang awam bukan sejarawan di bagian penutup. Bagi yang ingin langsung mengetahui cerita-cerita unik khas remaja tahun 1950-an tentu cerita peristiwa-peristiwa penting itu agak membosankan. Ditulisnya kenangan tahun 1950-an pada masa yang berbeda (tahun 2000an) tentu memiliki konsekuensi. Seperti yang terjadi pada buku ini. Pandangan penulis pada masa kini yang telah memiliki pengalaman tentu berbeda jika kenangan itu dituliskan, misalnya pada 1960-an. Pandangan polos remaja tentu berbeda dengan pandangan arif dewasa yang telah banyak makan asam garam. Misalnya kritik penulis terhadap dunia pendidikan (hlm. 228-229), lingkungan (Bab VI), status sosial (hlm. 113). Firman Lubis, si anak Menteng bukanlah seorang sejarawan. Ia adalah seorang guru besar FKUI bidang kedokteran komunitas dan pencegahan yang memiliki hobi pada sejarah. Hal itu terlihat dalam bacaannya yang luas tentang sejarah yang ia jadikan referensi untuk beberapa peristiwa penting. Sehingga bagi mereka yang ingin lebih mendalami peristiwa atau pokok masalah tertentu dapat membaca buku-buku yang disarankan olehnya. Buku yang dilengkapi dengan ilustrasi foto meski cukup membingungkan mana yang koleksi pribadi dan mana yang bukan serta tanpa disertai indeks cukup menarik untuk dibaca. Setidaknya bagi mereka yang seusia dengan Firman Lubis dapat mengenang masa lalu sedangkan bagi generasi sesudahnya dapat mengetahui masa lalu. Bagi sejarawan, buku ini juga layak dijadikan sumber data sejarah sosial Jakarta masa 50-an. Namun tentu harus didukung dengan data lain serta penelitian lebih lanjut. Mengingat kalimat-kalimat meragukan yang digunakan penulisnya seperti kalau tidak salah , seingat saya , dari yang pernah saya dengar . Satu hal yang bisa dijadikan pelajaran dari buku ini adalah setiap orang dapat menuliskan sejarahnya (baca: kenangannya) yang mungkin saja kelak dapat berguna untuk orang lain. Tidak perlu menunggu masa depan seperti yang dikhayalkan oleh Firman Lubis: jika dapat hidup kembali ke masa 1950-an hal pertama yang ia lakukan adalah memotret berbagai keadaan dan kehidupan di Jakarta pada masa itu. --------------------------------------
RESENSI BUKU
183
Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, xii + 713 pp. ISBN 979-22-2447-5. Price: IDR 170.000,00 (hard cover). Dick van der Meij Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dickvdm@yahoo.com Indonesian is a complex and rich language, but many authors and speakers are incapable of using it in its full richness by lack of knowledge and also because a proper thesaurus of the language was not available. This situation has now drastically changed and no one can use the unavailability of a dictionary any longer as an excuse not to write proper Indonesian. The thesaurus under discussion is quite rightfully not called a book of synonyms. Notwithstanding the fact that many words seemingly mean the same and are therefore called synonyms, in actual fact real one to one synonymy rarely, if ever, exists. Even though words might superficially mean the same, they may not be used interchangeably because there is a semantic, social, psychological, generational, local, or contextual difference or even a combination of any number of them. For instance, enak means tasteful but its use is not the same as lezat or sedap which have a more advertisement feeling. A young girl in Indonesian is cewek or gadis but the use of either word depends on the context. Cewek has a big-city ring to it and is therefore now used all over the country while gadis sounds old fashioned to most ears and is now confined to literature and old folks. The first may be used pejoratively as well while that would seem far fetched and highly unusual for the second. The book under discussion is rich, very rich indeed and shows once again that the Indonesian lexical reality is complex and extensive. Indonesia has hundreds of languages spoken within its borders and each influences local forms of Indonesian. Javanese, with the largest number of speakers influences the language most profoundly while the language spoken in a far-off islet out in the far eastern part of the archipelago might perhaps have no influence on the modern language at all. The metropolitan melting pot Jakarta is a hotchpotch of all these languages combined with modern English, Arabic, Chinese and many other languages. The use of the language of this metropolis is distributed all over the country through soap operas which are extremely popular and any modern word finds its way to the most remote part of the archipelago through SMS and email messages. The bibliography lists works that have been consulted or have been used as data sources, but they are not distinguished as such so that it is impossible to find out what book was used for what purpose, although it would seem
184
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
logical to assume that English language books were not used for data. The data sources consist mainly of dictionaries and wordlists and no literary works are listed at all. I think this may have seriously limited the number of literary idiom listed in the book. As a result there is also no designation provided for words which may be restricted to literary usage. The entries are followed by their equivalents in strict alphabetical order. This has been done for consistencies sake. However, it carries the danger that a rare and hardly ever used synonym that directly follows the entry might therefore mistakenly be considered the best equivalent, which it often is not. No mention of frequency is provided so that a word used all over the place all the time is not distinguished from others that may be extremely rare. Hyponyms have been excluded in the dictionary since they are not the same as synonyms. This means that under the entry ayah and ibu the hyponym orang tua is not mentioned as it is not synonymous with either of them. The introduction claims that full circularity has been adopted. This means that all the words considered synonymous with the entry are themselves found as main entry as well. Thus, in the example above, gadis is entered as follows: gadis n bikir (kl), cewek (cak), dara, dayang (kl), kuntum (ki), perawan, putri. If full circularity would have been maintained, all synonyms would have been entered as entries. However, if we consult cewek the word dayang has been left out. The entry dara however adds perempuan and wanita (muda) which are not found with the rest. When consulting the entry bibit, (anak) has been added to dara, but then also the compounds anak wanita and anak perempuan might have been possibilities and what happened to perempuan and wanita (muda)? In short, the dictionary may be up for some revisions in this particular aspect. At times I wonder if we can speak of synonymy at all. For instance the entry abad n daur, era, kala, kurun, masa, periode, zaman. Abad is a period of one hundred years and none of the synonyms refer to any period with a specific length of time so I wonder what is meant here. Full circularity has also not been maintained with this word as daur adds siklus, but leaves out zaman, etcetera. The Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 and 2000) have been used as source materials but the word publik is not mentioned under hadirin and under publik the meaning of hadirin is left out while this word is found in the Kamus Besar and I doubt whether this is the only example. It has therefore not become clear to me what precisely was considered data and how the sources have been used. Other aspects of the dictionary give rise to questions as well. Abai is apparently not a synonym of masa bodoh since it is not mentioned as such, but mengabaikan is synonymous with memasabodohkan. I find it puzzling that two derivatives can be synonymous but the stems not? Abbreviated forms of everyday words have also not been recognized as entries in their own right or are not mentioned at all. Tidak does not mention tak, while tapi is referred to tetapi but not mentioned under that entry and the
RESENSI BUKU
185
abbreviated form nak for anak is not mentioned at all. Information about the regional origins of the words has not been maintained throughout, which of course would have been impossible given the sources used, but sometimes I am puzzled at everyday words that are omitted. Under the entry kucing meong is mentioned but where is pus which is used in everyday Jakarta parlance and far beyond? Despite of what I said above, the dictionary is a joy. It gives many possibilities to make Indonesian an enjoyable language and the number of synonyms the author put together is enormous. My criticism is therefore mainly concerned with presentation and consistency. Some issues I would have done differently, such as the list of abbreviations which is now departmentalized and would better have been one list. Consulting it means five times browsing. The dictionary also gives rise to laughter. Under the entry marah we find for instance makan bawang which sound funny and after checking none of my Indonesian friends had ever heard but found equally amusing. However, people who have no or restricted knowledge of Indonesian need to use the dictionary with care. Many words cannot be used in place of another and have specific meanings which need to be fully grasped before the word can be used. It is therefore in the first place an extremely useful tool for Indonesian native speakers. -------------------------------------Susi Moeimam en Hein Steinhauer. Met medewerking van Nurhayu W. Santoso en met bijdragen van Ewald F. Ebing, Nederlands-Indonesisch Woordenboek. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004, xxviii + 1125 pp. ISBN 90-6718227-3. Price: EUR 49.90 (hard cover). Susi Moeimam dan Hein Steinhauer. Dengan bantuan Nurhayu W. Santoso dan sumbangan dari Ewald F. Ebing, Kamus Belanda-Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, KITLV-Jakarta, 2005, xliv + 1265 pp. ISBN 979-221498-4. Price: IDR 325.000,00 (hard cover). Dick van der Meij Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dickvdm@yahoo.com More than twenty years ago I took care of two large groups of Indonesian students in the Netherlands. They were sent to Holland to study regular university courses at any of the thirteen Dutch universities
186
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
of their choice. Of course the language of instruction at Dutch universities was Dutch which the students had to learn in a very short time. At the time the much needed upgraded versions of A. Teeuws excellent Indonesian-Dutch dictionary had not yet seen the light and I found it unfair that the students were required to be able to learn Dutch quickly while good IndonesianDutch dictionaries had to be purchased from second hand bookshops and a high-quality Dutch-Indonesian dictionary did not exist at all. Unfortunately, suggestions to have such a dictionary made fell on deaf ears at the time. Luckily these are things of the past. Teeuw was able to update his old 1950s dictionary which has now seen four reprints since 1990 and is a publication of the KITLV. The problem of the unavailability of a high-quality DutchIndonesian dictionary has now been solved because of the books under discussion. We are actually concerned here with two versions of what is basically the same dictionary. The first version - which was also published firstly - is a productive Dutch-Indonesian dictionary meant for a Dutchspeaking audience who wishes to produce Indonesian translations of modern written Dutch. The second is a receptive dictionary for Indonesian-speakers wanting to understand modern, written Dutch. Because both groups originate from different backgrounds, they have different needs which are addressed in the two dictionaries. For the speakers of Dutch all kinds of lexical and grammatical features of Dutch do not need to be explained, but for Indonesians they are crucial for without these explanations Dutch would be much harder to learn and to translate. The other way around, some peculiarities of Indonesian need to be explained in the dictionary meant for the Dutch audience, which do not have to be explained for an Indonesian readership. Curiously no mention is made in the introductions to both dictionaries that they are also highly valuable tools for those who wish to learn the modern Indonesian or Dutch spoken languages, especially since many sample sentences in the books clearly refer to spoken language as well. The project to make these dictionaries was a co-operation between Leiden University and Universitas Indonesia in Depok/Jakarta. Both institutions provided the two authors with the opportunity to spend five years of their time to work on the dictionaries. The project was moreover sponsored by what is now known as the ALVV, the Adviescommissie voor Lexicografische Vertaalvoorzieningen (Advisory Committee for the Provision of Lexical Translations Aids) founded by the Dutch and Flemish Ministries of Education who acted as the main sponsors of the project. Other financial and infrastructural assistance came from the Royal Dutch Academy of Sciences (KNAW), the International Institute for Asian Studies (IIAS) at Leiden and especially Leiden University itself. The project was called DIDIC (Dutch Indonesian Dictionary) and was executed at Leiden University. The Dutch entries came mostly from the digitalized Referentiebestand Nederlands (Reference File Dutch) while the OMBI dictionary program (OMkeerbaar BIlinguaal Bestand, Reversible Bilingual File) of ALVVs predecessor CLVV (Adviescommissie voor Lexicographische Vertaalvoorzieningen: Advice Commission for Lexical
RESENSI BUKU
187
Translation Aids) was used as the software to produce the dictionaries. The first dictionary is said to comprise around 46.000 entries with 60.000 distinct meanings while also 55.000 sample sentences were added. The dictionary proper is preceded by a (very) short user guide and grammatical compendium containing the most basic grammatical information needed in order to be able to evaluate the Indonesian translations provided in the dictionary indicating that they are often a choice of the available translations possibilities. Due to differences in grammar and especially in morphology one to one translations of the sample sentences are often impossible and through browsing the grammatical compendium the reader may more easily understand this. The second dictionary meant for an Indonesian audience contains around 50.000 entries with 60.000 distinct meanings while 55.000 example sentences, expressions and idioms were added. A much more extensive grammatical compendium of Dutch has been added for speakers of Indonesian. This dictionary is preceded by a much larger introduction. The user guide is extremely useful for Indonesian users and may be considered a useful tool in itself even without reference to the dictionary. The receptive dictionary is larger because many derivatives have been included which are superfluous for the productive one. Irregular plurals of nouns, archaic inflected forms of nouns, and irregular forms of singular present tense of most auxiliaries have been included with references to their corresponding counterparts. It is useful that the irregular past forms of verbs have been added in a separate appendix but I feel it would have been advisable to have had them included as separate entries in the dictionary as well with references to the corresponding infinitives. I feel that doing this for the irregular forms of singular present tense and not for these other irregular forms is somewhat inconsistent. It might have been especially useful for people just starting to learn Dutch who might have no idea they are looking at a verb to begin with. The same holds for the verbs with irregular perfect tense. The enumeration of the complete list of morphemes that may be syntactically separated from larger singular lexical units (verbal derivational prefixes) is extremely useful and was for me as a Dutch native speaker never even thinking about this also very interesting. It is indeed for most native speakers of Indonesian a difficult grammatical trait of Dutch because the distance between the various parts of the verb can be rather great and the list is a useful aid for them. See for instance the verb: binnenlopen (to enter or to pay a short visit) Je moet niet steeds bij hem binnenlopen Ik liep gisteren even bij hem binnen Ik was even bij hem binnengelopen Ik loop straks misschien wel even bij hem binnen Dont visit him all the time. I paid him a short visit yesterday. I paid him just a short visit. I might drop in at his place.
188
WACANA VOL. 10 NO. 1, APRIL 2008
Some criticism is of course unavoidable and short browsing the dictionaries gives rise to some remarks. I think for instance that some entries may prove to continue to be a problem for the uninitiated user because no translation is provided of the actual lexical entry but only sample sentences are given. For instance the adverb dan which is used in many Dutch sentences and most Dutch native speakers themselves would have problems explaining what it exactly means. It usually provides emphasis to a statement of part thereof. As it is treated now it is hard to see what part in the translation of the sample sentences refers to the word dan. Some indication of the translation of the word in the sample sentence, for instance by putting them in italics might have given the user some inclination of where the word is translated. Sometimes entries would seem to have been incompletely explained for instance: aangedaan [aan-][adj nonadv] pilu, terharu, but it is also the participium perfectum of aandoen1 (mampir, singgah, etcetera) and aandoen2 (berkesan) which is not mentioned; and other examples such as aangestoken [aan-][adj nonadv] menular, which is also the participium perfectum of aansteken (menyulut, menulari) and other examples such as aangeslagen - aanslaan. Sometimes the number of translational possibilities has been insufficiently explored for instance in translations of a word as geldigheidsduur which is translated as lama berlakunya, but may also be translated as masa berlaku. At other times I find the translations to academic and not idiomatic such as: ongenade [-na-][n][de] bij iemand in ongenade vallen = meninggalkan kesan yg tidak baik pada sso. I think a translation such as tidak disenangi lagi oleh sso. might more effectively have added to understanding. Dutch breuk is often used in the sense of hernia and the translation turun berok and burut might have been added under that entry. Does anyone ever use the expression memekak telinga voor oorverdovend or do they simply use berisik sekali? At occasions the sociolinguistic scope of the translations is rather limited. Nadat, for instance, is in much journalistic jargon in Indonesia seusai, and in normal, everyday language it may simply be translated with habis, both of which are not mentioned. Zeggen may also be translated by menuturkan, mengujarkan, mengucapkan, bersabda and probably by some more, dependent of the context. I am aware that having had to add synonyms might have made the production of this book even more time consuming and expensive, but it may be good for future editions to bear this in mind. Admirable work has been done by Susi Moeimam and Hein Steinhauer and their two coworkers. We are now in the happy circumstances that we can use two different, albeit closely related dictionaries Dutch-Indonesian. I might add to my admiration that the receptive dictionary is also highly usable for a Dutch audience. The details provided with the entries such as gender, the kind of article to use and the word classes of the words are highly usable for Dutch students as well. No need anymore to consult a Dutch-Dutch dictionary for these kinds of details while we are working on our Indonesian skills. These books will hopefully add to enhanced Dutch-Indonesian relations and will finally enable students of both countries to learn each others language with
RESENSI BUKU
189
much more ease and comfort. I would like to end by urging users to convey their remarks to the authors or to the publishers so that future editions are even more perfect than the present one. Lastly, the present dictionary is too limited to be useful for older Dutch texts, especially from colonial times and pertaining to colonial situations and culture. It is to be hoped that the authors will be given the possibility to either add to the present dictionaries or to compile a dictionary of historic Dutch which might be extremely useful for Indonesian students of Indonesias history which is to the present for them still a largely inaccessible past.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20020)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
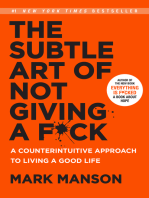






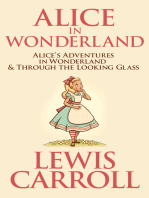






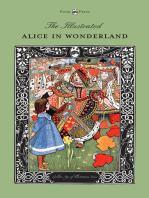

![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)