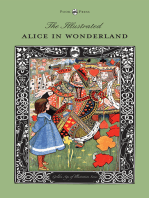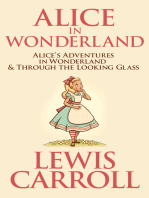Amartya Sen
Diunggah oleh
V Mencret SatuHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Amartya Sen
Diunggah oleh
V Mencret SatuHak Cipta:
Format Tersedia
20 Oktober 1998 Muhammad Chatib Basri
Amartya Sen
Amartya Sen, nama orang India itu, mungkin belum dikenal luas di negeri ini. Tapi, agaknya sebentar lagi akan populer. Sebagai ekonom, ia memang tak setenar Millon Freidman atau Paul Krugman, yang selalu menimbulkan kontroversi dengan ide-idenya. Tetapi, Sen, yang lahir di Bengal, India, pada 1933, telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat besar dalam soal kemiskinan dan kelaparan (poverty and famine). Karena itu, ia berhak atas posisi terhormat: pemenang Nobel Ekonomi 1998. Konsepnya mengenai entitlement (keberkahan) dianggap sebagai suatu terobosan besar dalam pembahasan tentang kemiskinan dan keadilan. Sen mencoba menjembatani dua kutub perseteruan teoretis antara Robert Nozick (Anarchy State and Utopia) dan John Rawls (A Theory of Justice). Nozick disebut sebagai pemikir kaum Libertarian, yang percaya mekanisme pasar akan memberikan hasil yang optimal dalam soal equality. Pasar memberikan balas jasa sesuai dengan kontribusi yang diberikan seseorang. Sedangkan John Rawls melihat bahwa dalam masalah keadilan, negara harus melakukan pemihakan kepada kelompok yang lemah. Dengan kata lain, tujuan kesejahteraan harus diarahkan kepada upaya meningkatkan kepuasan kelompok yang minim (the least well-off). Dengan demikian, ada perseteruan teoretis yang tajam di sini. Sen mencoba menjembatani dua pemikiran ini dengan memajukan konsep yang ia sebut sebagai: human diversity. Di sini, di satu sisi ia mengakui pentingnya otonomi individu, tetapi orang Asia pertama pemenang Nobel ini juga melihat bahwa secara alami manusia berbeda satu dengan yang lain, baik dalam hal fisik maupun kepemilikan aset. Karena itu, menurut Sen, equality harus dipahami dalam konteks bagaimana ia mampu meningkatkan kapabilitas untuk memperoleh hidup yang layak (well being). Di sini elemen kebebasan menjadi sangat penting karena--seperti yang dijelaskan dengan sangat teknis oleh Sen--kapabilitas harus merefleksikan kebebasan untuk memperoleh satu kehidupan yang lebih baik. Pemikiran Sen ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia, terutama ketika isu redistribusi aset mulai hangat dibicarakan hari-hari ini. Dari sisi ini kita melihat bahwa redistribusi aset adalah suatu hal yang dapat dibenarkan, tapi satu hal yang patut dicatat: ia harus tetap bisa menjamin hak otonomi individu. Artinya, redistribusi aset harus dijalankan dalam perspektif mekanisme pasar dan bukan sekadar pengalihan aset atau confiscation. Di sini, mekanisme pajak menjadi instrumen yang amat penting. Konsep availability yang dikembangkan oleh Sen juga mencoba menjawab persoalan klasik dalam ilmu ekonomi mengenai masalah kurang pangan (famine). Lewat buku Poverty and Famines: An essay on entitlement and deprivation, ia menjawab bahaya dari suatu hal yang disebutnya "Optimisme Malthusian". Dalam konsep Malthus dikatakan bahwa kelaparan akan terjadi jika jumlah makanan lebih sedikit daripada jumlah penduduk. Karena itu, indikator
reproduksi pangan per kapita seperti yang kerap disampaikan pemerintah kita menodai indikator yang sangat penting. Namun, studi Sen menunjukkan, dalam kasus India, kurang pangan terjadi justru ketika jumlah produksi pangan per kapita meningkat, seperti juga yang terjadi di Cina. Sen menunjukkan bahwa soalnya bukanlah pada jumlah produksi pangan per kapita, tetapi lebih pada soal akses terhadap makanan itu sendiri. Kelaparan adalah kondisi di mana orang tidak bisa memiliki makanan dan bukan hanya kondisi tidak adanya makanan. Dalam kasus Cina, misalnya, sistem pemerintahan yang otoriter turut bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan orang. Sebab, kritik terhadap kesalahan kebijakan pemerintah dalam hal pangan menjadi muskil dalam sistem otoriter. Itulah sebabnya aspek kebebasan--suatu hal yang begitu mahal di negeri ini--menjadi sangat penting dalam masalah kemiskinan dan kelaparan. Di republik ini sendiri pemerintah kerap, dengan bangganya, memaparkan parade angka-angka keberhasilan pembangunan seperti yang ditandai oleh meningkatnya produksi telur per kapita atau makanan lain per kapita, tetapi--seperti temuan Sen--tidak ada jaminan bahwa masalah kurang pangan otomatis terhindari karena ia harus mencakup soal apakah harganya terjangkau atau apakah ia bisa diperoleh karena distribusinya yang baik. Dalam kasus beras, misalnya, walaupun pemerintah menyatakan bahwa suplai beras telah berlebih, banyak masyarakat masih mengeluh soal mahalnya harga beras. Di sinilah pentingnya masalah aksesibilitas. Bagi kelompok yang memang tidak memiliki factor endowment untuk mempertahan hidupnya, pemihakan seperti Rawls memiliki justifikasinya. Dalam konteks ini, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses kebutuhan pokok, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Wacana pemikiran seperti inilah yang agaknya dibutuhkan oleh negeri ini, terutama ketika dataran perdebatan mengenai kemiskinan seperti mengalami stagnasi dan melebar pada pelbagai embel-embel ideologis seperti "prorakyat" atau "ekonomi kerakyatan". Mantan Presiden Masyarakat Ekonometri Amerika Serikat ini memang mencoba masuk dalam satu kajian "wilayah terlarang" seperti sosial, politik, dan filsafat, yang oleh banyak ekonom kerap ditabukan. Tapi justru di situlah kontribusinya menjadi relevan dalam wacana kemiskinan. *Penulis staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20011)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2565)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6513)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3271)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2306)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
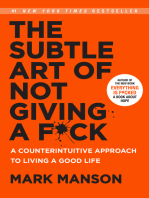





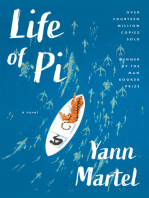







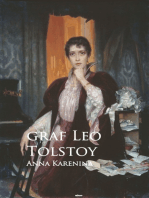


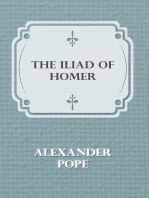






![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)