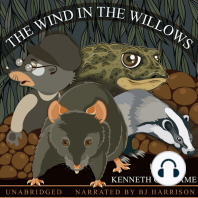Bab 2
Bab 2
Diunggah oleh
Rizz You RizzHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab 2
Bab 2
Diunggah oleh
Rizz You RizzHak Cipta:
Format Tersedia
2.
1 Pre Eklamsi
2.1.1 Pengertian
Hipertensi disertai proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah
usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. (Wibowo dan
Rachimhadi, 2006)
2.1.2 KlasiIikasi
Pre eklamsi dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :
1) Pre eklamsi ringan, bila disertai keadaan sebagai berikut :
a. Tekanan darah sistolik antara 140-160 mmHg dan tekanan darah
b. diastolik 90-110 mmHg
c. Proteinuria minimal ( 2g/L/24 jam)
d. Tidak disertai gangguan Iungsi organ (Wibowo dan
Rachimhadi, 2006)
2) Pre eklamsi berat, bila disertai keadaan sebagai berikut :
a. Tekanan darah sistolik ~ 160 mmHg atau tekanan darah
diastolik ~ 110 mmHg
b. Proteinuria (~ 5 g/L/24 jam) atau positiI 3 atau 4 pada
pemeriksaan kuantitatiI
c. Bisa disertai dengan :
O liguria (urine _ 400 mL/24jam)
O Keluhan serebral, gangguan penglihatan
O yeri abdomen pada kuadran kanan atas atau daerah
epigastrium
O angguan Iungsi hati dengan hiperbilirubinemia
O Edema pulmonum, sianosis
O angguan perkembangan intrauterine
O icroangiopathic hemolytic anemia, trombositopenia.
(Wibowo dan Rachimhadi, 2006)
2.1.3 Etiologi
1) Peran Prostasiklin dan Tromboksan
Pada preeklamsia/eklamsia didapatkan kerusakan pada endotel
vaskuler, sehingga terjadi penurunan produksi prostasiklin (P2)
yang pada kehamilan normal meningkat, aktivasi penggumpalan dan
Iibrinolisis, yang kemudian akan diganti dengan trombin dan
plasmin. Trombin akan mengkonsumsi antitrombin sehingga
terjadi deposit Iibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan
tromboksan (TxA2) dan serotonin, sehingga terjadi vasospasme dan
kerusakan endotel.
2) Peran Faktor munologis
Preeklamsia/eklamsia sering terjadi pada kehamilan pertama dan
tidak timbul lagi pada kehamilan berikutnya. Hal ini dapat
diterangkan bahwa pada kehamilan pertama pembentukan blocking
antibodies terhadap antigen plasenta tidak sempurna, yang semakin
sempurna pada kehamilan berikutnya. Fierlie F.. (1992)
mendapatkan beberapa data yang mendukung adanya sistem imun
pada penderita preeklamsia/eklamsia:
a) Beberapa wanita dengan preeklamsia/eklamsia mempunyai
kompleks imun dalam serum.
b) Beberapa studi juga mendapatkan adanya aktivasi sistem
komplemen pada preeklamsia/eklamsia diikuti dengan
proteinuria.
c) Peran Faktor enetik/Iamilial
d) Beberapa bukti yang menunjukkan peran Iaktor genetik pada
kejadian preeklamsia/eklamsia antara lain:
O Preeklamsia/eklamsia hanya terjadi pada manusia.
O Terdapatnya kecenderungan meningkatnya Irekuensi
preeklamsia/eklamsia pada anak-anak dari ibu yang menderita
preeklamsia/eklamsia.
O Kecenderungan meningkatnya Irekuensi preeklamsia/eklamsia
pada anak dan cucu ibu hamil dengan riwayat
preeklamsia/eklamsia dan bukan pada ipar mereka.
O Peran Renin-Angiotensin-Aldosteron System (RAAS) .
(Sudhabrata K, 2001)
2.1.4 Komplikasi
1) Eklamsi
2) Solusio plasenta
3) HipoIibrinogenemia
4) Hemolisis
5) Perdarahan otak
6) Kelainan mata
) Edema paru-paru
8) ekrosis hati
9) Sindroma HELLP yaitu haemolysis, elevated liver en:ymes dan low
Platelet
10)Kelainan ginjal
11)Komplikasi lain: Lidah tergigit, trauma dan Iraktur karena jatuh
akibat kejangkejang pneumonia aspirasi dan D
12)Prematuritas
13)&R
14)awat janin
15)&FD. (Wibowo dan Rachimhadi, 2006)
2.1.5 Penanganan
1) Pre Eklamsi Ringan
a. Kehamilan kurang dari 3 minggu
O Pantau tekanan darah, urine (untuk proteinuria), reIlex dan
kondisi janin.
O Konseling pasien dengan keluarganya tentang tanda-tanda
bahaya preeklamsia dan eklamsia.
O Lebih banyak istirahat.
O Diet biasa (tidak perlu diet rendah garam).
O Tidak perlu diberi obat-obatan.
O ika rawat jalan tidak mungkin, rawat di rumah sakit:
4 Diet biasa.
4 Pantau tekanan darah 2 kali sehari, dan urine (untuk
proteinuria) sehari sekali.
4 Tidak perlu obat-obatan.
4 Tidak perlu diuretik, kecuali jika terdapat edema
paru, dekompensatio kordis atau gagal ginjal akut.
4 ika tekanan diastolic turun sampai normal pasien
dapat dipulangkan.
4 ika tidak ada tanda perbaikan, tetap dirawat.
Lanjutkan penanganan dan observasi kesehatan
janin.
4 ika terdapat tanda-tanda pertumbuhan janin
terhambat, pertimbangkan terminasi kehamilan. ika
tidak, rawat sampai aterm.
4 ika proteinuria meningkat, tangani sebagai
preeklamsia berat.
b) Kehamilan lebih dari 3 minggu
O ika serviks matang, pecahkan ketuban dan induksi
persalinan dengan oksitoksin atau prostaglandin.
O ika serviks belum matang, lakukan pematangan dengan
prostaglandin atau kateter Iolley atau lakukan seksio sesaria.
(SaiIuddin, 2002)
2) Pre Eklamsi Berat
Penanganan preeklamsia berat dan eklamsia sama, kecuali bahwa
persalinan harus berlangsung dalam 12 jam setelah timbulnya kejang
pada eklamsia. Semua kasus preeklamsia berat harus ditangani
secara aktiI. Penanganan konservatiI dan gangguan penglihatan
sering tidak sahih.
Perawatan konservatiI (usia kehamilan 36 minggu)
a. Tirah baring.
b. nIus D5:RL 3:1.
c. Diet rendah garam dan tinggi protein (diet preeklamsia)
d. Pasang kateter tetap (bila perlu).
e. edikamentosa:
O Anti konvulsan gS4.
O Anti hipertensi iIedipine 10 mg sublingual, dilanjutkan
dengan 10 mg q 8 jam.
O Kortikosteroid (radexon i.m. 2 kali 10 mg) untuk kehamilan
36 minggu.
O Antibiotikum, diuretikum dan kardiotonikum hanya diberikan
atas indikasi.
Perawatan aktiI (terminasi kehamilan), yaitu pada keadaan-keadaan di
bawah ini:
a. &mur kehamilan ~36 minggu.
b. Terdapat tanda-tanda impending eklamsia atau eklamsia
c. awat janin.
d. Sindroma HELLP.
e. Kegagalan perawatan konservatiI, yakni setelah 6 jam perawatan
tidak terlihat tanda-tanda perbaikan penyakit. (SaiIuddin, 2002)
2.2 Eklamsi
2.2.1 Pengertian Eklamsia
Eklamsi adalah gejala preeklamsia berat disertai dengan kejang dan
diikuti dengan koma (anuaba, 200)
2.2.2 Tanda dan ejala
1) Perdarahan subkapsular
2) Perdarahan periportal sistem dan inIark liver
3) Edema parenkim liver
4) Peningkatan pengeluaran enzim liver
5) Tekanan darah dapat meningkat sehingga menimbulkan kegagalan
dari kemampuan sistem otonom aliran darah sistem saraI pusat (ke
otak) dan menimbulkan berbagai bentuk kelainan patologis sebagai
berikut (anuaba, 200) :
O Edema otak karena permeabilitas kapiler bertambah
O skemia yang menimbulkan inIark serebal
O Edema dan perdarahan menimbulkan nekrosis
O Edema dan perdarahan pada batang otak dan retina
O Dapat terjadi herniasi batang otak yang menekan pusat vital
medulla blongata
2.2.3 Etiologi
Pada umumnya disahului oleh makin memburuknya preeklamsia dan
terjadinya gejala-gejala nyeri kepala Irontal, gangguan penglihatan, mua
keras, nyeri epigastrium, dan hiperreIleksia. Bila keadaan ini tidak dikenal
dan diobati sgera, akan timbul kejang, terutama pada persalinan bahaya ini
besar. (Sarwono, 200)
2.2.4 Komplikasi
1. Solusio Plasenta
2. HipoIibrinogenemia
3. Hemolisis
4. Perdarahan otak
5. Kelainan mata
6. Edema paru-paru
. ekrosis hati
8. Sindrome HELLP
9. Komplikasi lain
10.Prematuritas, dismaturitas, dan kematian janin intra uteriin
(Sarwono, 200)
2.2.5 Penanganan
Penanganan preeklamsia berat dan eklamsia sama, kecuali bahwa
persalinan harus berlangsung dalam 12 jam setelah timbulnya kejang pada
eklamsia. Semua kasus preeklamsia berat harus ditangani secara aktiI.
Penanganan konservatiI dan gangguan penglihatan sering tidak sahih.
Perawatan konservatiI (usia kehamilan 36 minggu)
a. Tirah baring.
b. nIus D5:RL 3:1.
c. Diet rendah garam dan tinggi protein (diet preeklamsia)
d. Pasang kateter tetap (bila perlu).
e. edikamentosa:
O Anti konvulsan gS4.
O Anti hipertensi iIedipine 10 mg sublingual, dilanjutkan dengan
10 mg q 8 jam.
O Kortikosteroid (radexon i.m. 2 kali 10 mg) untuk kehamilan 36
minggu.
O Antibiotikum, diuretikum dan kardiotonikum hanya diberikan
atas indikasi.
Perawatan aktiI (terminasi kehamilan), yaitu pada keadaan-keadaan di
bawah ini:
a. &mur kehamilan ~36 minggu.
b. awat janin.
c. Sindroma HELLP.
d. Kegagalan perawatan konservatiI, yakni setelah 6 jam perawatan
tidak terlihat tanda-tanda perbaikan penyakit
e. Tirah baring, diet preeklamsia atau per sonde (bila pasien dalam
keadaan koma).
O nIus D5:RL 3:1.
O Pasang kateter tetap.
O Kepala direndahkan, isap lendir oroIaring.
O Pasang sudip lidah untuk mencegah lidah tergigit bila pasien
kejang.
O edikamentosa. (SaiIuddin, 2002)
DAFTAR PUSTAKA
Bobak, Lowdermik, ensen. 2004. Buku ajar keperawatan maternitas.
akarta: E
Boswick, ohn A. 199. Perawatan Gawat Darurat. akarta : E
Derek Lewellyn-jones, Dasar-dasar obstetric dan ginekologi, Alih
bahasa;Hadyanto, Ed.6 akarta, 2001
Hacker . F., 2001. Esensial Obstetri dan Ginekologi. akarta : Hipokrates
ansjoer, AriI . 2000. Kapita selekta kedokteran. akarta: edia
Aaesculapius
anuaba, . B. ., 200. Pengantar Kuliah Obstetri. akarta : E
anuaba, da Bagus de. 2010. Ilmu kebidanan, penyakit kandungan, dan
KB untuk pendidikan bidan. akarta: E
SaiIuddin, dkk, 2002. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal. akarta : YBPSP
Sinclair, ostance. 2010. Buku Saku Kebidanan. akarta: E
Sudhabrata K., 2001. Profil Penderita Preeklampsia-Eklampsia di RSU
Tarakan Kaltim.
Sullivan, Amanda. 2009. Panduan Pemeriksaan Antenatal. akarta: E
Varney, Helen. 2001. Buku saku kebidanan. akarta: E
Varney, Helen. 2008. Buku afar Asuhan kebidanan. akarta:E
Wibowo B., Rachimhadi T., 2006. Preeklampsia dan Eklampsia, dalam .
Ilmu Kebidanan. Edisi III. akarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono
Prawirohardjo
Wiknjosastro, HaniIa. 2006. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan
Maternal dan Neonatal.
Winkjosastro, haniIa. 200. Ilmu Kebidanan. akarta: Yayasan Bina Pustaka
Yulaikhah, Lily. 2009. Serie Asuhan Kehamilan. akarta: E
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20099)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12955)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)