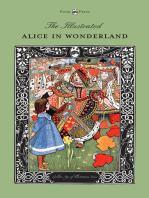Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia
Diunggah oleh
GusPiit97%(65)97% menganggap dokumen ini bermanfaat (65 suara)
12K tayangan5 halamanSepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam.
Judul Asli
HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA
Hak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniSepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
97%(65)97% menganggap dokumen ini bermanfaat (65 suara)
12K tayangan5 halamanHukum Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia
Diunggah oleh
GusPiitSepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam.
Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Oleh Yusril Ihza Mahendra
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk ikut berpartisipasi dalam seminar tentang Hukum Islam di
Asia Tenggara yang diselenggarakan mulai hari ini. Saya tidak
dapat mengatakan bahwa saya adalah ahli di bidang Hukum
Islam, mengingat fokus kajian akademis saya adalah hukum
tatanegara. Namun mengingat topik seminar ini adalah
transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional, maka titik
singgungnya dengan hukum tata negara, sejarah hukum, sosiologi
hukum dan filsafat hukum kiranya jelas keterkaitannya. Bidang-
bidang terakhir ini juga menjadi minat kajian akademis saya
selama ini. Sebab itulah, saya memberanikan diri untuk ikut
berpartisipasi dalam seminar ini, dengan harapan, sayapun akan
dapat belajar dari para pemakalah yang lain dan para peserta
seminar ini. Saya bukan pura-pura tawaddhu’, karena saya yakin
sayapun dapat berguru menimba ilmu dengan mereka.
Akar Historis dan Sosiologis Hukum Islam
Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka
nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu,
hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-
tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum
Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang
disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk
dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang
hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab,
yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum
Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi
Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi
bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin
mempunyai Al-Ahkamul Fuqoha, dan kaum Muhammadiyin
mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hassan dari
Persis, Soal Jawab, dibaca orang sampai ke negara-negara
tetangga.
Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama
lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya
dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni
Al-Qur’an dan al-Hadith. Dalam menjalankan kehidupan sehari-
hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota
masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada
aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu
mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar
kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kompisi besar-
kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam
diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh
mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam
memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-
hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.
Jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan
Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan
ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak
mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama,
tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para
sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan
kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di
masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di
Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate
dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten
dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah
memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam.
Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau
kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya
di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum
positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun
masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya
kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.
Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan
para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat,
kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang
mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah
sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan
kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini
berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang
menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai
penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan
hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula
komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India
Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di
kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.
Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal
orang Betawi di masa kemudian.Pada umumnya mereka
beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka,
mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa
Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan
Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang
yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk
menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa
di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung
halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia
karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih
hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu
komunitas yang baru.
Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar
tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda
Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa
hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian
melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya
mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang
terkenal itu. Saya masih menyimpan buku antik Compendium
Freijer itu yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu
tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini
tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum
keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab
fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek
yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek
masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum
Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu
sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-
perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah
Jawa.
Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten
mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai
mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian
pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di
mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram,
yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta,
masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi
negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi
koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke
desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan
pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya.
Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara
hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum
kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum
perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan
dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan
hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan
benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah
terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.
Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya
tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan ituterjadi
hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju
harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama
kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari
“langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum
adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju
harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan
hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang
hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat.
Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh
pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan
perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat,
termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-
asasnya.
Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan
politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus
memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan,
atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan
kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et
impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-
kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam
satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada
hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan
Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas
menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku
tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan
Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan
India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula
hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir
pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra
yang beragama Kristen.
Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali
hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang
berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam.
Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori
iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di
kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia
sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang
keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu
tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena
merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah
Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI,
tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia
merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya,
seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945,
walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari
setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan
Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan
UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus
berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di
era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi
politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam
konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah …
(Bersambung…)
Sumber : http://yusril.ihzamahendra.com
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20018)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)



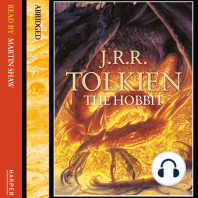




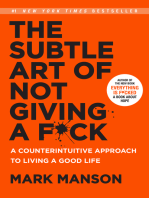

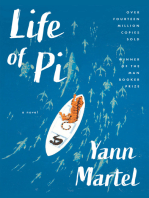
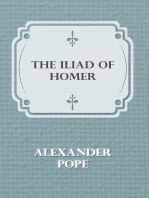








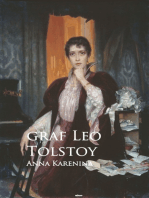
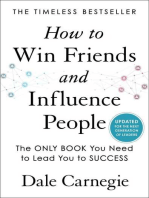


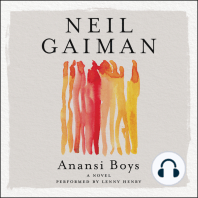
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)