Natural Law 78-91
Diunggah oleh
subhanscribdHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Natural Law 78-91
Diunggah oleh
subhanscribdHak Cipta:
Format Tersedia
Pemikiran tentang hukum alam telah menempati peran yang penting dalam dunia etika, politik dan hukum
sejak masa peradaban yunani. Pada beberapa masa, daya tarik mengenai hukum alam tersebut memang lebih condong ke arah keagamaan atau gaib, namun dalam era modern, pemikiran tentang hukum alam telah membentuk senjata penting dalam ideology politik dan hukum, terutama dalam upayanya untuk memberi landasan moral terhadap sistem sosial, ekonomi dan sistem hukum mereka. Dengan menyatakan bahwa hukum positif yang berlaku didasarkan pada hukum yang lebih tinggi, yang merupakan hukum yang seharusnya, dengan demikian, maka hukum positif dianggap telah mendapatkan dasar pembenarnya yang membuatnya menjadi tidak terbantahkan. Pemikiran tentang hukum alam mengalami keredupan pada abad ke Sembilan belas. Sebagai reaksi terhadap kekuatan konservatif yang berusaha untuk menempatkan hak atas kepemilikan sebagai hak manusia yang paling mendasar bahkan melampaui hak untuk hidup, maka diam-diam bangkit gagasan mengenai hak-hak alamiah manusia yang menekankan pada persamaan antar manusia sebagai hak paling mendasar. Gagasan tersebut telah terbukti dalam Pernyataan Kemerdekaaan Amerika Serikat dan akhirnya menjelma dengan nyata dalam pecahnya revolusi perancis. Namun demikian, pemikiran tentang hukum alam bangkit kembali pada abad ke dua puluh, terutama sejak pecahnya perang dunia ke-II, bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, ketertarikan terhadap pemikiran hukum alam kembali bangkit dalam teori-teori besar mengenai hukum, politik dan moral. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN HUKUM ALAM? Dengan sejarah selama dua ribu lima ratus tahun, tidaklah mengherankan, pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan hukum alam memicu timbulnya banyaknya jawaban yang berbedabeda. Walaupun ungkapan tentang hukum alam terus berkesinambungan, namun tidak berarti bahwa konsep mengenai hukum alam tetap statis. Sebaliknya, dalam perkembangannya, pemikiran tentang hukum alam telah mempunyai arti yang sangat berbeda dan digunakan untuk maksud yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan oleh DEntreves banyaknya ambiguitas tentang konsep hukum alam, haruslah dianggap berasal dari ambiguitas tentang konsep mengenai alam kodrat yang menjadi dasar dari pemikiran tersebut. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa doktrin yang berbeda mengenai hukum alam. Dalam masyarakat romawi kuno dimana tidak dikenal mengenai hak-hak alamiah, maka mereka tidak
memberikan hubungan antara hukum positif dengan hukum alam sebagaimana orang-orang sesudah zamannya. Pandangan masyarakat masa pertengahan dan masa modern mengenai hukum alam pun hanya sedikit memiliki persamaan. Namun demikian, terlepas dari berbagai perbedaan konsep tersebut, satu hal yang tetap tidak berubah adalah adanya kesamaan pandangan bahwa terdapat prinsipprinsip dasar mengenai hukum alam. Pandangan mengenai kandungan dari prinsip-prinsip dasar tersebut terkadang disimpangkan atau mengalami pembiasan, namun inti pemikiran dari hukum alam dapat dikatakan tetap berada dalam pemahaman yang sama bahwa pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip moral yang objektif yang bersumber pada kodrat alam semesta dan dapat ditemukan dengan menggunakan logika berpikir. Prinsip-prinsip dasar inilah yang membentuk hukum alam. Hukum alam dipercaya sebagai landasan rasional untuk menentukan penilaian moral. Para ahli hukum alam menerima kenyataan bahwa prinsip-prinsip hukum alam mungkin tidak mempunyai pengaruh seperti yang mereka inginkan, namun mereka tetap bertahan bahwa prinsip-prinsip tersebut tetap ada walaupun dalam kenyataannya mereka diacuhkan, disalahartikan bahkan disimpangkan, atau bahkan disanggap dalam pemikiran pragmatis. Hukum alam merupakan sebuah bentuk kepastian matematika mengenai nilai-nilai kebaikan, walaupun disalahartikan ataupun belum ditemukan. Salah satu halangan mendasar yang dihadapi oleh hukum alam adalah mengenai pertanyaan apakah gagasan moral selalu dapat ditarik dari fakta yang ada, apakah yang seharusnya dapat disimpulkan dari yang nyatanya. Finnis menolak anggapan bahwa hukum alam berpendirian bahwa hal yang demikian dimungkinkan. Sebaliknya, Finnis menerima dan mengartikan kembali teori dualism dari Hume. Menjembatani antara yang nyatanya dengan yang seharusnya tetap merupakan pertanyaan penting. Tentu, dapat dimengerti mengapa para sarjana hukum alam menginginkan untuk menarik sebuah gagasan moral dari fakta yang ada. Fakta bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat misalnya, selalu dapat diuji kebenarannya. Penilaian moral, bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang pantas bagi pembunuhan misalnya, tidak dapat dibuktikan. Jadi bila gagasan moral dapat ditarik dari fakta yang ada, kita akan dapat merumuskan sebuah kebenaran moral yang tentu saja memerlukan sebuah kesepakatan umum. Banyak perhatian telah diberikan oleh para sarjana hukum alam untuk menjawab pertanyaan bagaimana menarik yang nyatanya kepada yang seharusnya tanpa menghasilkan sebuah kesimpulan yang justru tidak dapat diterima oleh logika.
Salah satu cara yang ditawarkan oleh para sarjana hukum alam adalah dengan bertahan bahwa apabila terdapat hukum alam bagi manusia untuk bertindak dalam sebuah pola perilaku tertentu (yang dapat ditemukan melalui proses pengamatan terhadap pola perilaku manusia tersebut), maka manusia tersebut secara moral akan bertindak sesuai dengan pola perilaku tersebut. Sebagai contoh, merupakan hukum alam bagi manusia untuk menghasilkan keturunannya, oleh karenanya manusia cenderung akan berlaku demikian, sehingga apabila manusia tidak berupaya untuk menghasilkan keturunan maka hal tersebut akan bertentangan dengan hukum alam. Dengan menggunakan perspektif ini, sangat mudah untuk menarik kesimpulan bahwa alat pencegahan kehamilan dan aborsi adalah bertentangan dengan kepatutan moral, Para penganut aliran positivis berpendapat bahwa perspektif tersebut hanya akan menghasilkan kebingungan mengenai hukum ilmiah (yang menjabarkan mengenai aturan tentang apa yang dalam kenyataannya terjadi) dengan nilai moral (yang menjabarkan mengenai apa yang seharusnya terjadi). Dalam kenyataannya, fakta yang tidak diragukan lagi. bahwa manusia pada umumnya menghasilkan keturunan, tidak dapat disamartikan dengan ada sebagian manusia yang merasa terikat dengan kewajiban moral untuk menghasilkan keturunan. Beberapa sarjana hukum alam mungkin akan mencoba menjawab pertanyaan ini, dengan berpendapat bahwa hukum ilmiah (seperti misalnya, hukum gravitasi) menjabarkan mengenai sifat yang harus dimiliki oleh setiap benda, dengan demikian gagasan ini menawarkan ide bahwa Sang pencipta telah menundukkan segala sesuatu ke dalam hukum. Kepalsuan dari gagasan ini terdapat pada pendapat mereka yang menyatakan bahwa belum dapat dibuktikan mengenai adanya hukum ilmiah ini semata-mata terletak pada belum mampunya para ilmuwan untuk dapat secara akurat menemukan apa yang sejatinya ditentukan oleh Sang pencipta sebagai hukum bagi segala sesuatu tersebut. Pandangan ini tidak sepenuhnya menyangkut kebingungan antara hukum ilmiah dengan hukum moral, namun lebih dalam dari itu, menyangkut bukti mengenai keberadaan Tuhan, yang sampai saat ini merupakan sebuah masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan. Cara lain yang digunakan untuk membenarkan pandangan hukum ilmiah ini adalah anggapan bahwa terdapat norma dan nilai yang kokoh dan tidak tergoyahkan sebagai kodrat dari segala sesuatu, yang kemudian dipandang sebagai teologi mengenai alam semesta. Bagi Aristoteles dan para pengikutnya, proses alam cenderung menuju kepada kesudahan yang sudah ditentukan sebelumnya., seperti halnya biji pohon oak berupa menjadi pohon oak. Dengan cara ini segala sesuatu memenuhi fungsinya masing-masing yang ditentukan oleh alam. Manusia, menurut pandangan ini, juga mempunyai fungsinya
yang dapat ditemukan melalui proses berpikir dan logika. Pandangan ini memberikan kita gagasan mengenai Kesempurnaan. Kesempurnaan untuk setiap mahluk adalam mencapai kesudahannya apabila perkembangannya tidak mendapat halang rintang. Dengan demikian, Segala sesuatu hanya dapat dimengerti dengan melihat fungsi dan kontribusinya di dalam alam semesta. Pandangan ini dikembangkan oleh Aquinas pada abad ke tiga belas dari sudut pandang dunia kekristenan. Kebaikan diungkapkan oleh alam barasal dari Lex Aeterna, yaitu rencana Tuhan bagi alam semesta yang dapat ditemukan oleh manusia melalui proses pewahyuan (the lex divina) dan menggunakan akal pikirannya (the lex naturalis). Tradisi ini juga terjabarkan dalam karya terbaru Finnis. Menurut Finnis, terdapat kebutuhan mendasar bagi bagi manusia, nilainilai objektif, yang diterima oleh setiap manusia yang berakal sebagai kebutuhan yang harus dikejar dalam hidup manusia. Kebutuhankebutuhan ini hanya dapat dilihat dalam komunitas, karena hanya dalam komunitaslah terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan manusia untuk mengejar kebutuhan dasarnya. Pandangan teologikal melihat manusia sebagai mahluk yang mempunyai tujuan yang dapat diketahui dengan melihat kodratnya dan kebutuhannya. Salah satu sudut pandang ini adalah mengenai pertanyaan, siapakah yang memberikan manusia tujuan hidupnya. Hal ini akan membawa kita kembali dalam pertanyaan mengenai Ketuhanan. Bahkan apabila terdapat penjelasan yang memuaskan mengenai keberadaan Tuhan, namun teori yang didasarkan pada keberadannya mungkin akan mengecewakan. Lagipula, salah satu daya tarik dari paham hukum alam adalah anggapan bahwa kita dapat menggapai hakikat moral dari menggunakan logika murni. Pembelaan memungkinkan lainnya mengenai sudut pandang teologi dari hukum alam adalah dengan mengutarakan gagasan bahwa mahluk rasional memiliki kehendak bebas. Karena manusia mempunyai kehendak bebas, maka hanya menentukan apa yang harus dilakukan namun tidak selalu dapat meramalkan mengenai apa yang terjadi dalam kenyataannya. Namun perdebatan mengenai kehendak bebas tersebut menimbulkan permasalahan mendasar. Bila seseorang mempunyai kehendak bebas, bagaimana mungkin ia diwajibkan untuk melakukan sesuatu? Pertanyaan ini mengharuskan kita untuk memposisikan beberapa perilaku sebagai berasal dari kehendak bebas si pelaku sendiri atau atas dasar kehendak kekuasan yang lebih tinggi dari dirinya, sebagaimana kehendak Tuhan. Apabila kita menerima pandangan yang terakhir, maka kekuatan mengikat dari hukum alam dilandaskan pada anggapan, sebagaimana dinyatakan oleh Pufendorf, bahwa hukum alam tersebut merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan.
Bagaimana pun juga, untuk menjabarkan moralitas sebagai kehendak Tuhan akan menuai beberapa keberatan. Bagaimana jika kita ternyata diciptakan oleh tuhan yang jahat untuk tujuan jahat. Jawaban terhadap pertanyaan ini, yang mungkin diberikan oleh para sarjana hukum alam, adalah bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang baik. Pandangan bahwa moralitas merupakan kehendak Tuhan beranjak dari pemahaman kaum yahudi dan Kristen bahwa Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kesempurnaan moral, sehingga penyangkalan terhadap sifat baik dari Tuhan, pada dasarnya merupakan penyangkalan terhadap entitas Tuhan itu sendiri. Dengan mengatakan bahwa Tuhan layak atas kepatuhan kita karena Ia sempurna dari sisi moral, hanya dapat masuk akal apabila kita mengerti mengenai gagasan tentang hakikat moral itu sendiri, sebelum kita menghubungkannya dengan Tuhan. Kita harus menggunakan standar logika yang mandiri untuk menilai dari sisi moral tentang mengapa kita harus menghargai Tuhan, sebagaimana kita diajarkan untuk mempercayainya. Kita tidak boleh mengabaikan penilaian moral yang mandiri. Bukanlah kedigdayaan Tuhan yang membuat sebuah perilaku sebagai apa yang benar, melainkan alasan yang dapat diberikan oleh tuhan, atau apa yang dijabarkan sebagai kebaikan, terhadap perilaku tersebut. Para sarjana hukum alam seperti Suarez dan Grotius di abad ketujuh belas, menyadari hal ini. Bagi mereka, hukum alam awalnya dikehendaki oleh Tuhan, namun diinginkan oleh Tuhan karena hukum tersebut secara rasional mengandung kebaikan, bukan sebalikanya, yaitu hukum tersebut dipandang baik hanya karena hal tersebut diinginkan oleh Tuhan. Hence Grotius dapat menyimpulkan bahwa hukum alam akan tetap mengandung kebaikan, walaupun tidak ada tuhan. Hukum awal tidak menyangkal keberadaan bahkan diperlukannya hukum positif. Dalam pandangan para sarjana hukum alam berpendapat bahwa hukum positif seharusnya merupakan perwujudan dari hukum alam. Namun penadangan tersebut tidak selamanya benar. Dalam banyak hal, para sarjana hukum alam bersikap apatis terhadap hukum positif. Hal ini tidak berarti bahwa hukum alam tidak perduli apakah ada yang disebut sebagai hukum positif, hanya saja, penguasa manusia yang memiliki kehendak bebas dapat saja menghasilkan hukum yang tidak adil. Selanjutnya kita harus kembali ke pertanyaan awal, yaitu bagaimana norma dan nilai moral dapat terbentuk. Pendirian lainnya adalah gagasan bahwa hukum alam sebagai kenyataan tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Hal ini, tentu saja merupakan kemunduran dari pandangan bahwa hukum alam dapat dibuktikan. Walaupun demikian, keraguan masih saja timbul terhadap pandangan ini. Pernyataan seperti
perbudakan adalah salah atau adalah salah untuk membunuh mungkin saja tidak diragukan lagi oleh kita, tapi Orang yunani, untuk contohnya, menerima perbudakan sebagai suatu lembaga yang benar dari sisi moral. Selain itu, juga terdapat permasalahan mengenai konsep tentang apa yang disebut perbudakan atau pembunuhan. Walaupun semua masyarakat sepertinya melarang pembunuhan, namun tidak ada kesamaan pandangan mengenai dalam hal apakah pembunuhan dikatakan melawan hukum atau dapat dibenarkan. Salah satu upaya abad ke duapuluh untuk menyelamatkan hukum alam dari masalah ini, yang seringkali dihubungkan dengan pendapat Stammler, adalah terori bahwa hukum alam mempunyai kandungan yang dapat dipengaruhi dari luar. Menurut pandangan ini, nilai-nilai yang ideal tentang keadilan bersifat absolute, namun penerapannya, harus disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaannya. Namun kita tidak boleh melupakan fakta bahwa terdapatnya keberagaman dalam penerapannya, adalah karena terdapat perbedaan dari pandangan moral yang dianut oleh suatu masyarakat. Masyarakat Yunani tidak memandang perbudakan sebagai sebuah kesalahan, namun kita menganggap sebaliknya. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa kandungan hukum alam dapat dipengaruhi oleh perbedaan sosial, sama saja artinya dengan mengakui kegagalan untuk membentuk norma dan nilai yang obyektif. Upaya lainnya untuk menyelamatkan hukum alam dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan dari sarjana hukum positif yang terkemuka, Hart. Pandangannya mengenai kandungan minimal dari hukum alam didasarkan pada pada anggapan-anggapan di dunia biologi dan psikologi. Menurut Hart, manusia dalam kodratnya merupakan mahluk yang rentan terhadap bahaya dan mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mementingkan orang lain. Ia menyatakan bahwa kita semua mempunyai kemauan untuk bertahan hidup, sehingga kita dapat membuat seperangkat prinsip yang dapat menjawab kebutuhan kita dan meningkatkan kesempatan kita untuk bertahan hidup. Dua permasalahan dari ditarik dari pernyataan ini. Pertama, yang Hart coba untuk lakukan adalah menarik kesimpulan tentang prinsip moral dan norma hukum dari kenyataan. Kedua, dapat dikatakan bahwa dengan kandungan minimal hanya membekali kita dengan sangat sedikit panduan. Panduan tersebut mengatakan bahwa kita perlu melarang kekerasan, pengakuan terhadap hak milik pribadi, namun kandungan minimal tersebut tidak akan membawa kita lebih jauh lagi. Sebuah pemikiran kembali dari konsep hukum alam yang juga penting untuk dikemukakan adalah konsep Finnis tentang hukum alam dan hak-hak alamiah. Finnis menolak bahwa tujuan hukum alam bertujuan untuk menarik yang seharusnya dari yang senyatanya. Pemikiran
Finnis yang merupakan penafsiran kembali terhadap tulisan-tulisan Aquinas, pada dasarnya menyatakan bahwa Logika berpikir praktis dimulai bukan dengan berupaya untuk memahami alam kodrati dari luar, dengan menggunakan sudut pandang psikologis, antropologis, pengamatan metafisika dan penilaian mengenai sifat-sifat manusia, namun melihat dari dalam, dengan cara mengalami langsung, menghayati kodratnya sendiri sebagai manusia, di dalam bentuk naluriahnya sendiri. Menurut Fennis, hal ini tidak dapat diperoleh dengan cara hanya menduga-duga saja. DAYA TARIK DARI ALIRAN HUKUM ALAM Selama sejarah peradaban, manusia telah berusaha keras untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari yang mereka temukan didalam hukum dan kelembagaan yang telah ada. Selama sistem hukum yang ada tidak sempurna, selama masih dirasakan bentuk ketidakadilan, pencarian terhadap sistem hukum yang ideal akan terus berlangsung. Dari jaman nabi-nabi perjanjian lama sampai dengan pembelaan antigone yang berapi-api di dalam drama Sophocle, sampai dengan argumentasi penuntut umum dihadapan pengadilan perang Nuremberg, hal yang dikemukakan tetaplah sama, yaitu bahwa ada kewajiban yang lebih penting, nilai-nilai yang lebih tinggi, daripada sekedar mematuhi hukum posited dari suatu negara. Hal ini menimbulkan tiga pertanyaan penting. Pertama, terdapat permasalahan dalam menjabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan ketidakadilan. Menurut Aquinas, kekuatan dari hukum tergantung pada derajat keadilan yang dikandungnya, yang dapat dimengerti melalui logika. Namun logika yang paling utama adalah hukum alam. Dengan demikian, hukum manusia hanya akan mempunyai kodratnya sebagai hukum tergantung seberapa jauh ia mengandung nilai-nilai hukum alam, namun bila hukum yang berlaku tersebut memisahkan dirinya dari hukum alam, maka ia bukanlah hukum lagi, melainkan hukum yang sesat. Sengat jelas bahwa pandangan Aquinas ini dihasilkan saat hukum manusia mencermikankan keadilan, melayani kemaslahatan orang banyak, mendistrubusikan beban secara adil, mengandung nilai-nila agama dan mencakup juga kekuasaan dari pembentuk undang-undang. Semua konsep ini tentu saja sangat sarat akan nilai dan memerlukan penafsiran. Banyak pendapat muncul, bukan saja mengenai apakah yang dimaksud dengan kemaslahatan orang banyak namun bahkan apakah memang ada apa yang dinamakan kemaslahatan orang banyak tersebut. Menurut konsep ini, ketidakadilan terjadi bukan karena mengikuti hukum, namun karena menerapkan secara tidak adil.
Kedua, timbul pertanyaan mengenai siapa yang menentukan mengenai apakah hukum telah sangat melanggar prinsip-prinsip keadilan sehingga ia tidak layak lagi mendapat predikat sebagai hukum? Apakah keputusan ini diserahkan begitu saja pada hati nurani setiap orang, atau hanya dapat diambil oleh para professional, hakim atau sarjana hukum, menurut kriteria yang mereka anggap sebagai prinsipil dan bermoral? Bila dasar dari penilaian tersebut adalah logika, maka akan sangat sulit bagi setiap orang untuk menolak keputusan ini. Ketiga, apakah konsekuensi dari memutuskan bahwa sebuah hukum tidak harus dihargai sebagai sebuah hukum? Aquinas tanpa raguragu menyatakan bahwa hukum yang sesat tidak dapat mengikat hati nurani dan moral manusia dan dapat saja diabaikan namun pembahasan mengenai hal ini harus dilakukan dengan sangat hatihati. Hukum harus dipatuhi saat pelanggaran terhadap ketentuannya akan menimbulkan skandal atau gangguan terhadap tatana kehidupan di masyarakat. Dengan kata lain, Aquinas membandingkan antara konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap hukum yang tidak adil dengan dampak yang mengganggu, yang mungkin ditimbulkan dari tetap membiarkan berlakunya hukum yang sesat tersebut. Pendapat Finnis mengenal hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat Aquinas. Menurut Finnis, warga negara yang baik, secara moral tetap diharuskan untuk tetap tunduk terhadap ketentuan yang tidak adil dalam jangkauan yang diperlukan untuk menghindari melemahnya hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Namun, karena pembuat hukum seharusnya mencabut hukum yang demikian daripada tetap memberlakukannya, maka ia tidak punya hak untuk mengharapkan bahwa masyarakat harus tetap mematuhi hukum tersebut. Dari pendapat ini dapat disimpulkan, bahwa walaupun Finnis tidak menunjuk secara langsung, namun ia tetap berpendapat bahwa orang yang tidak patuh terhadap hukum harus tetap diberi sanksi. Finnis juga menyampaikan dilemma yang ditimbulkan dari adanya hukum yang sesat tersebbut bagi para penegak hukum seperti halnya hakim. Apakah hakim haris tetap menegakkan hukum yang tidak adil. Mengenai ini timbul pendapat, sebagaimana dapat dilihat dalam konsep hukum yang dikemukakan oleh Hart, bahwa memilih untuk tidak menegakkan hukum yang demikian akan justru melanggar prinsip keadilan. Dengan demikian apakah yang harus dilakukan oleh hakim? Hal ini bersandar kepada konteks politiknya. Kebebasan apa yang dimiliki hakim tersebut? Atau apakah ia sebetulnya hanya boneka dari rezim yang berkuasa? Apabila ia hanya ditanam oleh rezim yang berkuasa untuk tetap mempertahankan kehormatan rezim tersebut dengan memakai nama baiknya dalam proses pengadilan mereka,
maka tidak terbayangkan kesulitan yang dihadapi seorang hakim dalam situasi ini. Kegagalan untuk menerapkan hukum yang tidak adil dalam keadaan ini mungkin saja akan menimbulkan dampak yang kurang menyebangkan bagi diri si Hakim, namun ia tidak akan dianggap melanggar prinsip-prinsip moral. Kewajibannya untuk menjunjung tinggi hukum dikalahkan dengan latar belakang penunjukkan dirinya tersebut. Bahkan di dalam sistem yang demoktratik tetap ditemukan keadaan dimana seorang hakim, atau seorang penegak hukum, tidak dianggap telah melanggar tugasnya untuk menjunjung tinggi hukum, saat ia menolak untuk menerapkan hukum yang tidak adil. Sebagaimana layaknya kewajiban seorang prajurit untuk tunduk terhadap perintah, tidak berlaku saat ia diperintahkan untuk menembak seorang warga sipil yang tidak bersenjata, demikian juga kewajiban seorang hakim untuk menerapkan hukum tetap mempunyai batasn-batasan moral. Batasan-batasan moral ini bersandar pada kadar hukumnya, konteks sosial dan politik dan untung rugi dari tetap menerapkan hukum tersebut daripada tidak menerapkannya. Dilema moral yang dihadapi oleh hakim tersebut memicu banyak pertanyaan dan kontroversi di Afrika Selatan saat sistem apartheid masih berlaku. Seorang penegak hukum mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Namun terdapat suatu ikatan moral di dalam kewajiban ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam hal seorang hakim menemukan bahwa hukum yang harus ia terapkan ternyata tidak bermoral, harus mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bergabung dengan kaum revolusioner? Seorang hakim mungkin saja berpikir bahwa terdapat banyak alasan bagi dirinya untuk tetap bertahan dalam posisinya tersebut. Pertama, Ia mungkin saja berpikir bahwa kebanyakan hukum pada umumnya adalah adil (seberapa persentasenya bahwa hukum yang dibuat oleh Nazi atau hukum apartheid di Afrika selatan telah derpolusi oleh isu rasisme?) sehingga, sebagian besar keputusannya tetap ada di dalam batasan moral yang netral. Kedua, ia mungkin saja percaya bahwa terdapat kesempatan bagia dirinya untuk menafsirkan hukum tersebut dengan menggunakan nilia-nilai kemanusiaan, bahkan memberinya untuk mengkesampingkan maksud dari pembentuk undang-undang yang dianggapnya tidak mengandung moral. Dan yang ketiga, terdapat juga pemahaman dan nalurinya bahwa, apabila ia mengundurkan diri, maka posisinya tersebut dapat juga digantikan oleh seseorang hakim yang jutsru lebih tidak bermoral. Reaksi selanjutnya dapat dari penganut aliran positivis. Hart, sebagai contohnya, berpendirian bahwa peraturan yang bersifat terbuka (lentur) (dan banyak dari hukum yang bersifat diskriminatif yang
biasanya dicirikan dengan ketidakjelasannya, masuk dalam katagori ini) akan memberikan hakim celah untuk membentuk hukum dan mengambil prinsip-prinsip moral untuk mencapai putusannya. Dengan penafsiran hukum, membuka kesempatan yang luas bagi hakim untuk menerapkan kewenangan diskresinya terhadap apa yang ia pandang baik. Tentu saja, kaum liberal di Afrika selatan akan berusaha untuk memperlihatkan bahwa terdapat celah di dalam hukum yang tidak adil, yang memungkinkan digunakannya penafsiran dari sisi nilai-nilai kemanausiaan. Hal ini juga merupakan tanggapan dari Dworkin. Menurut Dworkin, hakim harus menganggap bahwa dirinya tidak sedang menyuarakan keyakinan moral pribadinya sendiri, melainkan sebagai pengarang dalam rangkaian sistem hukum common law. Menurut Dworkin, solusi terbaik terhadap dilemma moral yang dihadapi oleh hakim adalah dengan cara seorang hakim harus berbohong karena ia tidak akan dapat membantu kecuali ia sendiri mengerti , sebagaimana ungkapan, dalam perannya yang diberikan oleh undang-undang, bahwa peraturan hukum yang berlaku adalah berbeda dengan apa yang ia sendiri yakini Pemahaman Dworkin mengenai proses pengambilan keputusan oleh hakim ini didasarkan pada konsep penafsiran konstruktif yang merupakan penjabaran dari pandangan bahwa hukum merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam pandangan hukum sebagai satu kesatuan, proses keputusan oleh hakim tidak sematamata terbatas pada dimensi waktu dan tempat saat itu saja, melainkan untuk mencari apa yang dipandang benar maka bukan saja apa yang secara moral dianggap terbaik dalam proses pengambilan keputusan saat itu saja, namun ia juga harus sesuai dengan sejarah kelembagaannya. Dalam taraf ini, hakim merupakan saluran untuk menurunkan nilai-nilai yang kekal yang bertahan dalam sistem hukum. Saat nilai-nilai yang telah terlembaga tersebut tidak adil, maka hukum yang akan putusan yang akan diterapkan dalam kasus nyatapun akan melibatkan hukum yang tidak adil. Dalam pandangan Dworkin, apabila menghadapi dilemma ini, maka hakim harus berbohong. Hal ini tentu saja berarti menempatkan kesetiaan terhadap keadilan diatas kesetiaannya terhadap hukum, namun untuk dapat melakukan ini, seorang hakim terpaksa harus melembagakan kebohongan. Namun apakah hakim yang melakukan hal ini akan tetap bertahan? Dan apabila ia tetap bertahan, bukankah kompetensinya, integritasnya tidak menjadi diragukan? Bagi mereka yang mengadopsi prinsip naturalisme, melihat terdapat daya tarik lainnya di dalam hukum alam.DEntreves mencatat bahwa bagian dari pencarian manusia yang tidak pernah selesai adalah
mengenai upaya untuk menarik nilai-nilai yang lebih tinggi dari sekedar kata-kata yang tercantum dalam hukum ke dalam dunia roh. Pandangan ini merupakan koreksi yang sangat berguna terhadap kecenderungan untuk melebih-lebihkan pandangan sejarah bahwa hukum terjadi secara kebetulan. Pandangan tersebut juga dapat menjelaskan mengenai hukum positif mempunyai kekuatan mengikat, bahkan saat prinsip-prinsip hukum alam tidak dapat disimpulkan dari hukum tersebut. Hal tersebut dapat memberikan kepada kita pandangan mengenai mengapa hukum dibentuk, mengingat, seperti halnya lembaga sosial lainnya, hukum hanya akan dapat sepenuhnya dipahami di dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang harus mereka sadari, seperti misalnya keadilan dan kemaslahatan orang banyak. Mungkin saja, walaupun daya tarik yang paling utama dari aliran hukum alam bagi para mahasiswa hukum adalah karena ilmu hukum alam memberikan pemikiran yang berbeda dengan alur pikiran para positivis, hukum alam kemudian juga memperluas cakupan dari ilmu hukum secara keseluruhan. Kita harus sepakat dengan Finnis bahwa seorang teoritis tidak dapat memberikan penjabaran dari segi teori dan analisa terhadap fakta sosial, kecuali ia sendiri terjun langsung sebagai participant di dalam kegiatan penilaiannya, dalam pemahamannya mengenai apa yang sungguh-sungguh baik baik manusia dan apa yang sebenarnya diminta oleh logika berpikir yang praktis.Para sarjana hukum positif, juga memberikan kita penjabaran dan analisa mengenai hukum sebagai lembaga sosial, namun penjbaran dan analisa yang diberika cenderung bersifat legalistic, menganggapnya sebagai sebuah entitas yang terpisah. Bidang pembahasan dari para sarjana hukum adal;ah hukum , namun bagaimana ia dapat menentukan apa yang dipandang sebagai hukum sebagai landasan dari pemikiran mereka tersebut.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20024)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3277)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5508)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12947)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)

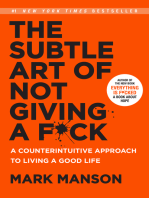










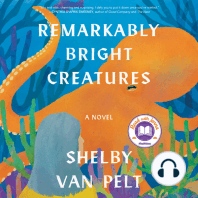
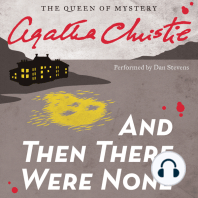






![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)





