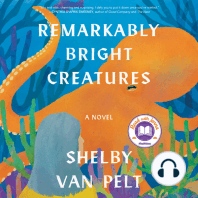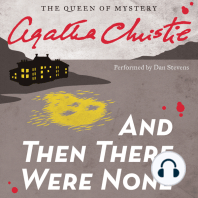Nietzsche
Diunggah oleh
Fazli Al SyiraziHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Nietzsche
Diunggah oleh
Fazli Al SyiraziHak Cipta:
Format Tersedia
Nietzsche, Derrida dan Dekonstruksi Satu bag.
dari buku,' Nietzsche' , penerbit Kanisius, Jogjakarta
Abdul Hakim, Director of Center for Islam and State Studies Indonesia
Dalam tradisi filsafat Barat modern, Nietzsche (1844-1900) menempati posisi yang khas, karena kritiknya terhadap metafisika Barat. Nietzsche dikenal berfilsafat dengan palu; ia menghantam dengan keras segala keyakinan, kepercayaan, dogma dan pengetahuan yang mendasarkan dirinya pada suatu fondasi yang tak tergoyahkan. Ia menggugat metafisika yang membicarakan palungpalung kenyataan, dan hakikat di balik seluruh realitas, dan dengan tanpa ampun ia mempreteli apa yang disebut kebenaran. Nietzsche, sekali lagi, mengingatkan bahwa ambisi filsafat untuk menemukan hakikat kebenaran adalah racun yang membunuh dirinya sendiri. Apa yang diusung oleh Nietzsche hampir lebih satu abad yang lalu dirayakan di hari ini dalam tradisi filsafat kontemporer. Panji-panji filsafat kontemporer yang menggemakan ulang apa yang pernah disuarakan Nietzsche di masa lalu mendapatkan bentuknya pada Martin Heidegger dengan destruksi atas metafisika, dialektika negatif pada Adorno, dan dekonstruksi pada Jacques Derrida. Dalam pengantar Being and Time, Heidegger mengemukakan kegelisahannya akan krisis pengetahuan zaman ini, yang ia sebut dengan krisis fondasi, krisis tersebut bersumber dari kelupaan akan Ada. Dan dengan dialektika negatif, Adorno menyatakan konsep adalah sumber kekerasan; dalam berfikir selalu terjadi identifikasi, kategorisasi, sistematisasi, dan segala anasir yang partikular, nonidentitas dileburkan dalam sintesis ala Hegel. Melalui dekonstruksi Derrida ingin menarik filsafat ke garis perbatasannya, yaitu meninggalkan nostalgia filsafat akan Ada sebagai kehadiran.[1] Jacques Derrida melanjutkan proyek yang dilakukan oleh Heidegger, terutama proyek Heidegger yang tak pernah diselesaikannya dalam Being and Time yang hendak melakukan destruksi atas sejarah metafisika. Dan dalam banyak hal, Derrida dan Adorno menggarap tema yang sama, yaitu melakukan kritik terhadap filsafat Barat yang berpusat pada fondasi. Adorno dapat dianggap sebagai sang proto-dekonstruksionis. Namun berbeda dengan Heidegger yang melakukan perlawanannya terhadap metafisika Barat dengan jalan membangun ontologi fundamental, atau Adorno dengan dialektika warisan Idealisme Jerman, dekonstruksi Derrida justru mendapatkan senjatanya melalui filsafat bahasa Dekonstruksi Atas Metode Kata metode berasal dari kata Yunani meta, berarti dari sesuatu, atau sesudah sesuatu, dan hodos, yang berarti perjalanan. Secara etimologis, metode merujuk pada perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain; metode dipahami sebagai jalan menuju pengetahuan.[2] Donald Polkinghorne, di dalam Method for the Human Sciences (1983), mendefinisikan metode sebagai sejenis aktivitas yang bertujuan untuk mencapai hasil penelitian. Dengan kata lain,
metode merujuk pada perencanaan yang terorganisasi secara terperinci dan logis dengan bantuan metode itu dapat meraih pengetahuan. Metode berarti suatu prosedur logis dan sudut pandang yang digunakan untuk mendapatkan serangkaian informasi dari proses penelitian terhadap objek.[3] Sementara dekonstruksi mempersoalkan orientasi meraih hasil dan analisis sistematik dari prinsip-prinsip metode pengetahuan. Derrida mengkritik metode tradisional yang berupaya menggambarkan objeknya dari sudut tertentu dengan menyingkirkan sisi-sisi yang dianggap tidak relevan bagi kepentingan suatu penelitian terhadap objek. Sebaliknya, dekonstruksi bermaksud mendekati objeknya dari posisi objek itu sendiri, dan bukan berdasarkan pada pengandaian tertentu untuk menentukan bagaimana objek itu menyingkapkan dirinya. Melalui seperangkat metode dan pengandaian tertentu atas objek, seakan ada jarak yang memisahkan antara peneliti dengan objek yang diteliti. Derrida hendak meleburkan batas antara peneliti dan objek yang ditelitinya, bahkan pembaca dan teks. Karakter dasar dari dekonstruksi ialah perhatiannya pada teks, sistem konseptual, dan linguistik dengan terus mempertautkan interioritas dan eksterioritas. Teks tidak mungkin sepenuhnya bersifat eksternal terhadap pembaca, dalam proses pemahaman diandaikan terjadi internalisasi diri, untuk menjadikan teks sebagai miliknya. Dengan demikian strategi pembacaan dekonstruksi tidak berikhtiar untuk menemukan makna tertentu atau ide utama sebuah teks, tetapi menelisik bagaimana teks melahirkan beragam makna yang mungkin bertentangan satu sama lain. Dalam konteks pembacaan ini pula, dekonstruksi berseberangan dengan hermeneutika. Hermeneutika berupaya merekonstruksi makna yang dimaksud oleh pengarang, menyempurnakan teks dengan bertumpu pada konteks yang membentuk sebuah teks, bukan untuk memperlihatkan kontradiksi internal yang selalu menandai teks, sebagaimana strategi dekonstruksi. Sebaliknya, dekonstruksi menghindari upaya melengkapi, mengklarifikasi, atau mendamaikan kontradiksi di dalam teks dalam rangka menemukan titik tolak dan ruang bagi munculnya interpretasi baru.[4] Dekonstruksi bukanlah metode yang siap digunakan dan dipakai di mana pun dan kapan pun terhadap semua teks, setiap teks sudah mengandung kemungkinan dekonstruksi. Derrida menggambarkan dekonstruksi seperti, menulis dengan dua tangan, sebagai peristiwa, inskripsi atau percabangan tekstual. Dekonstruksi membuka ruang bagi perbedaan, konflik, ragam makna, diseminasi, dan konteks tanpa batas serta memusatkan diri pada permainan perbedaan tekstual untuk menggoyahkan pemikiran yang diliputi petanda transendental. Strategi dekonstruksi Derrida dapat dilihat dalam dua langkah simultan berikut; pertama, bertujuan untuk memahami teks, dengan bertolak dari teks itu sendiri sebagaimana teks itu menyingkapkan dirinya; kedua, ikhtiar memahami teks secara non-logosentris, suatu pembacaan teks yang hendak melawan dominasi petanda transendental, sentrum makna, bahkan tema yang mengikat keseluruhan teks, serta berkonsentrasi pada permainan perbedaan dan tekstualitas yang terdapat di dalam teks. Strategi pembacaan dekonstruksi hanya memusatkan perhatiannya pada teks itu sendiri, pada ketegangan dan ambiguitas yang dikandung oleh teks, dekonstruksi tidak berminat untuk mengungkapkan maksud pengarang, sebaliknya berupaya mengungkapkan apa yang tidak dimaksudkan, disembunyikan, disingkirkan, atau direpresi oleh sang pengarang. Berbeda dengan
hermeneutika yang masih berupaya mengungkapkan makna yang dimaksudkan oleh teks. Hermeneutika dan dekonstruksi dibedakan oleh konsepsi keduanya atas bahasa; yang pertama berupaya merengkuh makna transendental yang berada di seberang bahasa, hermeneutika masih meyakini ada sentrum makna yang mengikat keseluruhan teks, makna yang mengikat dan menjadi sentrum teks. Sebaliknya dekonstruksi mempersoalkan eksistensi petanda transendental, dan berkonsentrasi pada ketegangan, ambiguitas, dan antinomi teks. Apa yang dilakukan oleh Derrida sesungguhnya bertolak dari pengertian tertentu atas bahasa dan makna, bukan tanpa pengandaian dan kepentingan diri.[5] Dekonstruksi Sebagai Tulisan-Ganda Dekonstruksi meneruskan proyek filsafat Nietzsche dan Heidegger dalam rangka mengkritik metafisika Barat, dan dengan dekonstruksi Derrida tidak hanya melakukan kritik terhadap tradisi filosofis an sich, tetapi juga pemikiran dan bahasa sehari-hari. Pemikiran Barat, demikian Derrida, selalu telah distrukturkan dalam kerangka dikotomi atau polaritas; baik dan buruk, ada dan ketiadaan, kehadiran dan ketidakhadiran, benar dan salah, identitas dan perbedaan, pikiran dan tindakan, lelaki dan wanita, jiwa dan tubuh, kehidupan dan kematian, natur dan kultur, wicara dan tulisan. Dua kutub yang berlawanan ini, sayangnya tidak terdiri secara bebas satu sama lain, dan bukan dua entitas yang setara. Kutub yang kedua selalu merupakan suplemen, kurang bermakna, dan sekunder berhadapan dengan kutub pertama. Dengan kata lain, dikotomi ini tidak mencerminkan makna yang saling berlawanan satu sama lain, tetapi telah ditentukan secara hierarkis, di mana yang pertama selalu mendapatkan prioritas baik secara temporal maupun makna kualitatif kata tersebut. Menurut Derrida, hierarki oposisi biner ini mengukuhkan privelese kesatuan, identitas, imediasi, dan kehadiran spasio-temporal terhadap perbedaan, penundaan, jarak, dan keragaman. Sebagai pencarian jawaban dari pertanyaan mengenai Ada, filsafat Barat sesunggguhnya selalu menganggap Ada sebagai kehadiran.[6] Derrida juga melakukan kritik terhadap metafisika Barat yang memberi privelese bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Bahasa lisan selalu diberi nilai lebih tinggi daripada bahasa tulisan, karena dalam bahasa lisan atau wicara diandaikan sang pembicara dan pendengar hadir dalam pembicaraan secara simultan, tidak ada jarak spasio-temporal antara pembicara, pembicaraan, dan pendengar, karena pembicara dan pendengar diandaikan berjumpa dalam satu momen pembicaraan di mana pembicara dan pendengar mendengarkan satu sama lain. Ini sekaligus meneguhkan anggapan bahwa dalam bahasa lisan kita tahu apa yang kita maksudkan, memahami apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita inginkan, serta mengetahui apa yang telah kita katakan. Citra mengenai makna yang hadir secara penuh ini, menurut Derrida, merupakan ideal yang mendasari kebudayaan Barat. Derrida memberi istilah logosentrisme terhadap keyakinan akan kepenuhan-diri makna ini, berasal dari bahasa Yunani Kuno, kata Logos berarti wicara, logika, rasio, sabda Tuhan.[7] Tulisan, di sisi lain, dalam sistem logosentris dianggap hanya sebagai representasi dari wicara, sebagai pengganti wicara yang bersifat sekunder jika wicara tak memungkinkan. Tulisan diletakkan dalam posisi yang sekunder berhadapan dengan wicara, tulisan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengatasi jarak; pemikir menuangkan pikiran-pikirannya dalam tulisan di atas kertas, berjarak dengan dirinya sendiri, bertransformasi menjadi sesuatu yang
dapat dibaca oleh orang lain yang jauh dari sang penulis, bahkan setelah wafatnya. Inklusi kematian, jarak, dan perbedaan pikiran telah merusak kehadiran penuh makna . Logosentrisme mengandaikan bahwa bahasa merupakan medium yang cukup-diri dalam rangka ekspresi bahasa atau komunikasi makna dapat dijelaskan dalam kerangka tindak pemberian makna dari subjek yang sadar. Dengan kata lain, esensi atau makna murni, yang dalam bahasa Saussure disebut dengan petanda adalah primer. Sementara tanda, baik itu sebagai bunyi maupun inskripsi, adalah sekunder, derivatif, dan semata kendaraan bagi pikiran.[8] Dengan melakukan kritik terhadap hierarki oposisi biner yang mendasari pemikiran filsafat Barat ini, Derrida sesungguhnya tidak sesederhana hendak membalikkan oposisi tersebut seperti sediakala, dengan mengatakan bahwa tulisan lebih utama ketimbang wicara. Lebih jauh, Derrida hendak mengatakan bahwa seluruh oposisi yang bertumpu pada sistem biner yang berbasiskan kehadiran dan ketidakhadiran, atau imediasi dan representasi merupakan ilusi. Karena wicara selalu sudah distrukturkan oleh perbedaan dan jarak sebagaimana juga tulisan. Dengan menilik ulang hierarki oposisi biner yang mendasari pemikiran Barat sebenarnya Derrida hendak melikuidasi logosentrisme yang menjadi ciri penting pemikiran Barat sejak Plato. Dengan mengambil ilham dari Nietszche, Derrida berusaha meradikalkan konsep interpretasi, perspektif, evaluasi, perbedaan. Dan Nietzsche telah melakukan liberasi atas petanda dari derivasinya dan ketergantungan terhadap logos dan hubungannya dengan konsep kebenaran atau makna primer.[9] Dengan pernyataan ini, menjadi jelas bahwa Nietzsche mencurigai apa kita sebut dengan nilai dan rezim kebenaran, makna, atau Ada, bahkan makna Ada itu sendiri. Nietzsche telah menegaskan suatu rangkaian tanda yang terus menerus tanpa henti, tanpa dasar dan kebenaran. Dari sini kita mendapatkan kaitan erat antara proyek Of Grammatology Derrida dan interpretasi Nietzsche mengenai sistem nilai sebagai tekstualitas tak terbatas dan melihat kesinambungan antara uraian Derrida mengenai valuasi negatif dalam hierarki tulisanlisan dengan genealogi Nietzsche. Di sinilah letak perbedaan Heidegger dan Derrida melihat posisi Nietzsche dalam sejarah metafisika Barat. Heidegger menempatkan Nietzsche sebagai metafisikus terakhir dalam sejarah pemikiran Barat. Karena bagi Heidegger, metafisikus adalah seseorang yang masih mempersoalkan Apa itu hakikat kenyataan?. Dan bagi Heidegger, Nietzsche menjawab bahwa hakikat kenyataan itu adalah kehendak untuk berkuasa. Tampaknya Heidegger menganggap Nietzsche sebagai filsuf yang lupa akan Ada. Derrida, justru menegaskan sebaliknya, Nietzsche adalah filsuf yang telah beringsut dari nostalgia akan asal-usul, dan kelupaan Nietzsche adalah kelupaan yang aktif. Menempatkan Nietzsche sebagai filsuf yang masih bergulat dengan pertanyaan mengenai hakikat kenyataan sesungguhnya sangat problematis, karena Nietzsche menganggap tak ada totalitas kenyataan, tak ada evaluasi eksistensi manusia yang dapat dibuat berkenaan dengan sesuatu yang tidak ada. Selain itu, menurut Derrida, Heidegger mengabaikan kenyataan pluralitas gaya tulisan Nietzsche. Bagi Heidegger, Nietzsche tetap sang metafisikus yang mempertanyakan Ada, dan tidak mempertanyakan pertanyaan itu sendiri. Alih-alih mendestruksi metafisika, Heidegger justru meneguhkan kembali logos dan kebenaran sebagai primum signatum: petanda transendental, transendental dalam pengertian filsafat abad pertengahan sebagai; ens, unum, verum, bonum,
yang berimplikasi terhadap semua kategori dan signifikansi. Dengan melepaskan tanda dari makna, dan kaitan antara petanda dengan penanda yang bersifat arbitrer secara absolut berarti Derrida menyingkap sejarah logos, tidak ada lagi makna di luar teks.[10] Di dalam beberapa konteks yang berbeda, Derrida menggambarkan dekonstruksi sebagai tulisan ganda (double-writing), gerakan ganda, dan pengertian-ganda (double-science).[11]Tulisanganda digunakan oleh Derrida untuk menunjukkan strategi dekonstruksi terhadap apa yang ia sebut hierarki oposisi biner yang menjadi ciri dari pemikiran metafisika Barat. Melalui hierarki oposisi biner ini hendak ditunjukkan bahwa pasangan-pasangan konseptual tidak pernah berdiri sejajar satu sama lain, melainkan menegaskan yang pertama sebagai bernilai dan fundamental dibanding yang kedua atau lawannya. Di sisi lain, dekonstruksi sebagai gerakan ganda merujuk pada upaya untuk memutarbalikkan dan melampaui hierarki oposisi biner yang mendasari setiap pemikiran Barat dengan membongkar pasangan-pasangan konseptual yang berlawanan dengan mengintroduksi konsep baru, sebuah konsep yang tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam konsep sebelumnya.[12] Konsep baru ini, disebut Derrida dengan ketidakmungkinan untuk diputuskan (undcidables). Konsep baru ini tidak lagi dapat dimasukkan dalam skema hierarki oposisi biner meskipun konsep tersebut mendiami, meresistensi, dan mendisorganisasikan oposisi filsafat.[13] Menurut Gasch, dua pergerakan dekonstruksi dapat dilukiskan sebagai berikut: pertama, pembalikan hierarki tradisional oposisi konseptual; kedua, reinskripsi istilah dan konsep baru yang tidak lagi identik dengan konsep sebelumnya.[14] Dekonstruksi atas hierarki oposisi biner atas konsep filsafat tradisional ini niscaya, tegas Derrida. Filsafat tradisional telah melakukan pensejajaran konseptual, misalnya, tubuh/kesadaran, alam/budaya, petanda/penanda, tulisan/ujaran. Pensejajaran ini bukanlah suatu koeksistensi damai oposisi konseptual tetapi hierarki kekerasan, ketika salah satunya mendominasi dan mensubordinasikan yang lain.[15] Dekonstruksi berupaya membalikkan oposisi biner untuk menemukan perspektif baru dalam mengkaji relasi konseptual yang saling dilawankan itu. Perspektif baru tidak mungkin diraih bila oposisi biner dipertahankan, bahkan hanya akan terjebak di dalam pensejajaran dualistik tersebut. Dekonstruksi mengintroduksi cara baru dalam memahami perlawanan konseptual dalam filsafat, yaitu dengan mengubah pengertian hierarki pasangan yang saling berlawanan. Dekonstruksi melampaui fondasi dan asal-usul. Apa struktur yang menyokong fondasi, asal-usul, dan definisi mengenai yang aktual sebagai fondasi dasar? Dan apa yang menentukan lawannya sebagai nonaktual? Apa itu fondasi atau asal-usul suatu fondasi? Suatu fondasi dasar dianggap sebagai fondasi karena relasinya dan ditentukan oleh pengandaian adanya yang asali dan bukan asali. Dasar dan bukan dasar, fondasi dan non-fondasi. Dengan istilah ketidakmungkinan untuk diputuskan (undecidable), Derrida menegaskan kemungkinan untuk tidak terjebak dalam oposisi dan sistem yang disokong oleh hierarki oposisi biner, bahkan ketika membongkar pasangan konseptual yang berlawanan pun, konsep baru ini akan melengkapi yang sebelumnya.[16] Derrida menelisik teks-teks Rousseau di dalam Of Grammatology sebagai eksemplar dari dekonstruksi atas hierarki oposisi biner dalam tradisi pemikiran Barat. Rousseau, menurut Derrida, di dalam teks-teksnya telah menyajikan perangkat nilai yang menempatkan ujaran lebih nyata dan asali dalam relasinya dengan tulisan, termasuk alam dianggap lebih primer ketimbang kultur. Derrida memperlihatkan melalui teks-teks Rousseau bagaimana konstruksi hierarki oposisi biner telah melahirkan kekerasan atas yang lain, dengan mendedahkan kembali istilah
suplemen (supplment) dan substitusi yang digunakan oleh Rousseau. Dalam rangka menggambarkan pengalaman asali, Rousseau melawankannya dengan istilah suplemen untuk melukiskan pengalaman yang tidak otentik dan tambahan atas yang asali. Bagi Derrida istilah suplemen adalah diffrance, tidak dapat diputuskan pengertiannya. Derrida hendak menunjukkan tugas dekonstruksi mengungkapkan hubungan antara yang asali dan sekunder, fondasi dan bukan fondasi, otentik dan artifisial, alamiah dan suplemen dikonstruksi secara arbitrer di dalam filsafat. Hubungan antara yang alamiah dan suplemen (misalnya, tulisan, representasi atau imaji) atas yang alamiah inilah yang diperlihatkan Derrida di dalam teks Rousseau sebagai hubungan yang problematik. Intensi dekonstruksi ialah memperlihatkan ketidakmungkinan untuk diputuskannya suatu pengertian konseptual karena dilawankan dengan yang lain. Hugh J. Silverman menyatakan bahwa dekonstruksi telah memberi ruang bagi perbedaan di dalam teks, mengangkat apa yang terlupakan di dalam teks, sesuatu yang diangkat itu memang sudah mendiami teks dan bukan di luar teks.[17] Feminisme Prancis menggunakan dekonstruksi sebagai tulisan ganda dalam rangka membongkar hierarki oposisi biner relasi pria dan wanita. Sesungguhnya, feminis Prancis seperti Simone de Beauvoir telah lama sebelum Derrida menggugat logika hierarki biner dalam rangka pembelaannya atas perempuan melalui karya The Second Sex (1949). Menurutnya, wanita telah didefinisikan sebagai yang lain dari pria. Pria dianggap subjek yang aktif dan wanita subjek yang pasif. Dengan kata lain, wanita secara historis ditentukan oleh hierarki oposisi biner, di mana wanita ditempatkan secara rendah dibanding pria. De Beauvoir mempertanyakan genealogi historis hierarki ini serta bagaimana hierarki ini dimantapkan di dalam sejarah dan adakah latarbelakang biologis atas hierarki ini? Membongkar hubungan hierarkis antara pria dan wanita menghajatkan pengakuan resiprositas antara jenis kelamin yang berbeda. Ia menampilkan sederet eksemplar yang menegaskan bahwa pria sebagai subjek yang aktif turut menentukan definisi wanita sebagai subjek yang pasif. Ia menunjukkan salah satu akar dari hierarki antara pria dan wanita ini ialah pembagian tradisional peran pria dan wanita dalam sejarah. Pria dianggap lebih mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah terutama di wilayah-wilayah sosial sementara wanita hanya ditempatkan di rumah dan bekerja di rumah semata.[18] Konsekuensi lebih mengerikan dari hierarki antara pria dan wanita ini, pria dianggap lebih manusia ketimbang wanita, meski wanita otonom, tetapi tetap bergantung dan terikat dengan pria. Ia menampilkan pandangan dekonstruktif atas hubungan pria dan wanita ini dengan menegaskan perbedaan kelamin sesuatu yang tidak dapat diubah, tetapi pembagian peran berdasarkan kelamin dapat digugat dan dipersoalkan sebagai biang keladi subordinasi atas perempuan di dalam sejarah. Dengan kata lain, ia sedang membongkar hierarki pria dan wanita yang sudah mapan dalam sejarah dengan menyatakan bahwa pembagian peran dan kerja antara pria dan wanita tidak pernah alamiah, tetapi dibentuk oleh kuasa dan sejarah kaum lelaki. Feminisme post-strukturalis Prancis membangun analisa hubungan pria dan wanita berdasarkan warisan De Beauvoir. Tulisan-tulisan Hlne Cixous tampak dipengaruhi oleh Derrida. Menurut Cixous sistem oposisi-hierarkis di dalam sejarah pemikiran Barat bertumpu pada dualisme seks yang kemudian berimbas pada sistem nilai patriarkis. Maskulinitas dilihat di dalam kerangka yang positif, sementara femininitas dilihat secara negatif dan pasif sekaligus. Cixous
menunjukkan hubungan hierarkis ini dengan jelas dengan memperlihatkan daftar kelompok kata oposisi biner yang didasarkan pada jukstaposisi hierarkis antara jenis kelamin.[19]
Masculine/Feminine active/passive sun/moon culture/nature day/night father/mother head/feelings intellectual/emotional logos/pathos Menurut Cixous, oposisi yang berpasangan sebaiknya dilihat dengan bertolak dari heterogenitas diffrance. Maskulinitas dan femininitas termasuk oposisi yang berpasangan lainnya dipahami sebagai plural. Heterogenitas perbedaan merujuk pada kenyataan bahwa kewanitaan, misalnya, ditentukan tidak hanya oleh relasinya dengan kepriaan, tetapi ditentukan oleh hubungan dengan sekian banyak pria dan wanita yang berbeda, termasuk etnik dan budaya yang beragam. Definisi ini juga terus berkembang dan berubah sepanjang waktu tergantung dengan perubahan relasi yang kompleks satu sama lain. Di dalam sebuah wawancara Christine McDonald dengan Derrida, kemudian dipublikasikan dengan judul, Choreographies (1982), Derrida mengajukan sikap yang sama dengan Cixous untuk mengatasi hierarki oposisi biner mengenai konsep gender. Menurutnya, kategori gender semestinya dipahami sebagai suara polifonik, beragam suara yang menandai gender bukan hanya semata dua kategori gender. Dekonstruksi sebagai tulisan ganda juga dioperasikan untuk menggugat pandangan hierarkis atas minoritas etnis, politik, agama dan seksual. Gayatri Spivak menelisik minoritas yang berada di pinggiran berdasarkan dekonstruksi Derrida. Spivak mendekonstruksi kategori pusat dan pinggiran, arus utama budaya dan budaya minoritas. Ia mengkritik penerapan secara universal feminisme Eropa dan Anglo-Amerika, termasuk gagasan mengenai kesetaraan untuk mengangkat posisi perempuan di Dunia Ketiga. Untuk meningkatkan harkat perempuan di Dunia Ketiga diperlukan nilai-nilai, pandangan dan konsep yang berbeda dengan apa yang terjadi dan dihayati sebagai kesetaraan di Dunia Barat. Dengan cara yang sama dapat dilakukan di dalam kajian mengenai post-kolonialisme. Postkolonialisme mengungkapkan perbedaan antara hegemoni yang berkuasa dengan koloni
yang dikuasai dalam sistem nilai hierarki biner. Di sisi lain, berupaya untuk mendekonstruksi nilai-nilai yang hegemonik dan dominasi pusat atas wilayah pinggiran dan marginalia. Sasaran utama analisis dekonstruksi, kritik feminis dan analisis akan budaya pinggiran dan minoritas adalah reevaluasi nilai-nilai secara umum, serta memperlihatkan bagaimana kuasa turut berperan kuat dalam mengeksklusi yang lain dan segala carut-marut perbedaan di luar pusat. Simon Crithley mengintroduksi istilah pembacaan ganda (double reading) dalam The Ethic of Deconstruction (1992). Menurutnya, pembacaan dengan menggunakan strategi dekonstruksi berbeda dengan jenis pembacaan lainnya. Pembacaan ganda ini dengan dua langkah berikut: pertama, pembacaan dan interpretasi atas teks sesuai dengan apa yang diungkapkan teks secara jelas dan terang benderang, sementara pembacaan kedua, menyadari konflik yang terdapat di dalam teks agar pengertian yang kita temukan terbuka terhadap yang lain. Crithley senada dengan Derrida di dalam Positions bahwa dekonstruksi atas filsafat secara meyakinkan memeriksa genealogi konsep-konsep filsafat, namun pada saat yang sama menentukan dari sudut eksterior tertentu sesuatu yang belum lengkap atau dinamai oleh filsafat, yaitu apa yang diabaikan oleh sejarah filsafat dengan menyingkapkan represi yang berlangsung di dalam teksteks filsafat.[20] Melalui pembacaan ganda ini pula sesungguhnya Derrida mendedahkan strategi pembacaan teks filsafat dengan mengikuti logika internal, secara simultan menelisik tepi dan batas-batas filsafat, agar teks dapat dibaca dari posisi luaran. Dekonstruksi bergerak di garis batas logosentrime ini. Kita tidak dapat melangkah keluar dari logosentrisme sepenuhnya, karena tidak ada tempat di luar logosentrisme atau metafisika kehadiran. Dengan kata lain, membaca secara dekonstruktif berarti membaca tepian dan batas-batas tradisi, dengan tetap berusaha memahami setepat mungkin pemikiran dan teks yang dianggap mapan di dalam kerangka tradisi tersebut namun secara cermat juga mengungkapkan apa yang dieksklusikan oleh tradisi. Tradisi tidak dipahami sebagai keseluruhan yang konsisten apalagi seragam, tradisi memuat konflik dan ketegangan yang membuka kemungkinan bagi dekonstruksi. Pembacaan tepi dan batas tradisi ini memiliki hubungan erat dengan destruksi (Destruktion) Heidegger. Dekonstruksi merupakan penerapan dan penterjemahan istilah Heidegger. Melalui destruksi pula, Heidegger membaca tepi dan batas tradisi metafisika Barat untuk membongkar tradisi dan pemikiran dimungkinkan.[21] Menurut Crithley, pembacaan ganda bersifat etis, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi yang lain (otherness) yang dikandung oleh filsafat dan konsep logosentris, dan dari dalam tradisi itu yang lain mendekonstruksi konsep-konsep logosentris. Tujuan dekonstruksi ialah menyingkapkan interpretasi yang seakan terlihat konsisten lalu memperlihatkan batas-batasnya agar terjadi perubahan di dalam interpretasi tradisional. Lalu apakah yang lain itu? Apa tepi dan batas-batas teks? Pertanyaan ini patut diajukan untuk memahami apa yang dimaksud Derrida bahwa yang lain itu mendiami teks dan tradisi. Yang lain (otherness) adalah istilah filsafat Emmanuel Levinas. Menurutnya, yang lain ialah sesuatu yang tidak mungkin dipahami dari sudut kesadaran: yang lain tidak mungkin ditangkap oleh semua pendekatan kognitif.[22]Jika yang lain tidak dapat direngkuh oleh kesadaran, bagaimana yang lain itu muncul di dalam teks dan dapat dipahami? Bagi Derrida yang lain itu muncul di dalam pengertian dan makna yang memanifestasikan diri sebagai jejak (trace) atau diffrance. Konsekuensinya, makna tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai kehadiran penuh, tetapi selalu merucut dan terus menerus terlepas dari setiap upaya memastikannya. Teks tidak pernah merujuk pada referensi yang stabil,
makna selalu berubah dalam relasinya dengan pembaca dan situasi pembacaan yang beragam. Makna dibentuk oleh wilayah ketegangan yang berbeda yang selalu dapat diubah tanpa rujukan yang tetap. Karena itu yang lain dapat dimengerti sebagai karakter dasar dari teks dan semua tanda linguistik. Lalu bagaimana yang lain itu memanifestasikan diri di dalam teks? Setiap teks memuat blind spots dan elipsis, titik-titik yang tidak disadari oleh sang pengarang. Setiap pembacaan kritis atas teks selalu melahirkan struktur penandaan teks, sehingga setiap pembacaan memperlihatkan apa yang dimaksud oleh sang pengarang sekaligus mengungkapkan apa yang tidak ia maksudkan dari pola-pola bahasa yang digunakan sang pengarang.[23] Sebagai contoh, demikian Derrida, konsep suplemen dalam teks-teks Rousseau merupakan serangkaian blind spots yang mengaburkan kejelasan teks. Blind spots merupakan titik-titik yang di mana penulis tidak dapat sepenuhnya mengontrol bahasa yang digunakan atau ketika ketegangan internal pemikiran turut menghantui teks. Blind spots inilah yang mengaburkan kejelasan teks dan pada saat yang sama membuka sudut pandang baru ke dalam teks. Dekonstruksi bermula dari pembacaan cermat atas konflik, paradoks, diskotinuitas, dan aporia yang menjadi ciri argumentasi, konseptualisasi dan diskursus filsafat. Ketegangan, aporia, dan diskontinuitas yang memanifestasikan diri di dalam teks juga dapat disebut sebagai tanda akan yang lain, sudut pandang berbeda dan logika yang tersembunyi di dalam teks.[24] Selanjutnya, dekonstruksi beroperasi untuk menemukan terma ikat-pisah (hinge term) seperti engsel yang menghubungkan, mengikat sekaligus memisahkan pintu dengan dinding. Teks selalu terdiri dari dua tingkatan; jelas dan tersembunyi sekaligus. Pengarang teks mengendalikan salah satu, tetapi mengabaikan yang lain: menyatakan yang satu dan menyembunyikan yang lain, satu metafisika dan yang lain bukan; yang satu bentuk dan yang lain isi; yang satu prinsipil dan yang lain praktis. Kedua tingkatan ini terhubung satu sama lain, kejelasan salah satunya akan diikuti oleh ketersembunyian yang lain. Teks, dengan demikian, ditandai oleh terma penghubung atau terma ikat-pisah yang secara simultan menghubungkan dua tingkatan teks dan memainkan peran ganda. Tugas dekonstruksi ialah menemukan terma ikat-pisah dan mengungkapkan hubungan kedua tingkatan teks. Terma ikat-pisah tidak menyatukan tingkatan teks yang berbeda, tetapi membuka kemungkinan interpretasi yang berbeda dan pergantian perspektif.[25] terma ikat-pisah tidak dapat dipastikan pengertiannya meski muncul di dalam kedua level teks sebagai elemen yang bertegangan satu sama lain. terma ikat-pisah akan melahirkan ketegangan logis di dalam teks sehingga teks tidak akan dapat sepenuhnya dimengerti secara solid dan koheren. Ekonomi kehadiran dan ketidakhadiran yang disebabkan oleh terma ikat-pisah ini akan selalu membuat teks menjadi terbuka, tanpa finalitas, tanpa kejelasan absolut, dan interpretasi tanpa akhir.[26] Teks Rousseau sebagaimana dilukiskan Derrida di dalam Of Grammatology dapat ditafsirkan sebentuk pencarian akan terma ikat-pisah dan blind spots yang mendiami teks Rousseau. Rousseau menggunakan kata subtitusi dan suplemen dalam tegangan yang tidak dapat dipastikan pengertiannya. Pada level tekstual, Rousseau menggunakan kata subtitusi secara sekunder, misalnya, kebudayaan dianggap substitusi atas alam, inang sebagai subtitusi atas ibu yang melahirkan, tulisan atas ujaran, tetapi pada saat yang sama subtitusi yang dianggap sekunder itu justru mendapatkan pengertiannya dan hanya mungkin dipahami karena relasinya dengan yang pertama, lebih asali dari substitusinya. Ikhtiar menemukan terma ikat-pisah ini
pula dapat dilihat di dalam pembacaan Derrida terhadap teks Plato. Di dalam Dissemination, Derrida menelisik pandangan Plato mengenai tulisan sebagai obat sekaligus racun (pharmakon), kata pharmakon merupakan terma ikat-pisah yang melahirkan ketegangan antara apa yang hendak dinyatakan Plato dan apa yang hendak dihindarinya. Plato mengklaim di dalam tulisannya bahwa tulisan adalah racun bagi pemikiran karena manusia tidak perlu mengingat sesuatu ketika mampu bertumpu pada teks tertulis. Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa tulisan adalah obat karena mampu mengawetkan eksistensi pemikiran dari kealpaan. Di dalam pandangan Plato ini mengenai tulisan sebagai racun sekaligus obat ini terdapat level teks yang berbeda dan ketegangan interpretasi yang dapat dilihat secara berkesinambungan. Tujuan dekonstruksi, dengan demikian, mendedahkan ketegangan yang dilahirkan oleh level teks yang berbeda dan mengungkapkan logika dan konstruksi teks tersebut. Dengan cara ini pula perspektif dekonstruksi dapat melahirkan perubahan interpretasi. Hugh J. Silverman di dalam Inscriptions (1987) menegaskan bahwa dekonstruksi sebagai praxis yang beroperasi di dalam pergerakan menuju batas, tepi, dan melalui dekonstruksi perbedaan dimengerti sebagai tulisan-asali (arch-writing). Maka dekonstruksi dapat berperan sebagai titik penghubung antara kejelasan dan ketersembunyian, filsafat dan nonfilsafat. Silverman mengembangkan gagasan terma ikat-pisah ini dengan menunjukkan indikator-indikator dekonstruksi. Baginya, terdapat sekian indikator dekonstruksi di dalam teks. Indikator-indikator ini menunjukkan tempat di mana strategi dekonstruksi dapat berlangsung. Seperti pada jejak, tanda, pinggiran, rujukan, tepi, batas, dan seterusnya. Indikator-indikator dekonstruksi ini terkadang berada di luar dan di dalam teks . Indikator-indikator ini berfungsi sebagai terma ikat-pisah: menghubungkan dan memisahkan keduanya sekaligus.[27] Munculnya yang lain di dalam teks juga dapat ditafsirkan sebagai ekspresi ketidaksadaran teks. Dekonstruksi dapat dikatakan sejenis psikoanalisa atas sejarah filsafat. Derrida tampaknya telah membawa psikoanalisa ke dalam sejarah filsafat. Dengan kata lain, dekonstruksi hendak mengungkapkan represi dan ketidaksadaran teks. Meskipun Derrida menampik untuk mensejajarkan dekonstruksi filsafat dan psikoanalisa atas sejarah filsafat. Kemiripan ini terjadi karena Derrida menggunakan istilah represi dan ketidaksadaran. Konsep represi yang digunakan Derrida dalam hubungannya dengan dekonstruksi logosentrisme berbeda dengan istilah represi dan ketidaksadaran dalam psikoanalisa Freud. Istilah represi dan ketidaksadaran dalam psikoanalisa Freud, tegas Derrida, masih terjebak dalam sejarah metafisika Barat, serta memuat implikasi-implikasi metafisis. Istilah ketidaksadaran dalam psikoanalisa Freud terkait-erat dengan kehadiran kesadaran di dalam metafisika. Sebaliknya, bagi Derrida, ketidaksadaran tidak bersifat sekunder terhadap kesadaran, ketidaksadaran menandai yang lain yang sepenuhnya tersembunyi, dan melalui dekonstruksi ketidaksadaran teks dapat ditampilkan. Ketidasadaran tidak pernah sepenuhnya dapat ditampilkan atau dipahami, melalui wilayah kesadaran sebagaimana dalam psikoanalisa Freud, sebaliknya ketidaksadaran hanya mungkin ditampilkan melalui jalan melingkar, lewat inskripsi dan tulisan.[28] Akhirnya, dekonstruksi sebagai tulisan ganda (double writing) dan pembacaan ganda (double reading) menemukan bentuk yang beranekaragam tergantung pada teks. Perbedaan itu dapat muncul sebagai blind spots, elipsis, ketegangan, aporia, terma ikat-pisah, pinggiran atau tepi
dari teks, judul, bahkan tanda tangan pengarang sekalipun. Karena itu, dekonstruksi dapat dipahami dalam beragam bentuk, tidak semata pembacaan ganda dan tulisan ganda. Inskripsi dan PercabanganTekstual. Istilah percabangan tekstual (textual grafting) digunakan oleh Derrida pertama kali di dalam Dissemination (1972). Di dalam bahasa Prancis kata la greffe (graft: bahasa Inggris) merujuk pada cabang sebuah pohon, tetapi Derrida juga mengaitkannya dengan kata le graphe (graph: Inggris). Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani graphion yang berarti alat tulis, alat menggambar, ujung pena.[29] Dengan istilah ini Derrida ingin menunjukkan bahwa pemikiran mengenai teks layaknya tanaman atau pohon yang terdiri dari dahan-dahan tekstual. Percabangan tekstual ini dekat dan terkait-erat dengan intertektualitas. Berbeda dengan intertekstualitas, percabangan tektstual merujuk pada penggabungan teks. Maka penggabungan antarteks menghidupi dirinya di dalam konteks teks yang baru dan tidak lagi perlu menghubungkan diri, serta merujuk pada teks sebelumnya. Gagasan mengenai percabangan tekstual berhubungan dengan konsep umum mengenai konteks sebuah teks. Menurut Derrida, tidak ada konteks yang paling benar bagi sebuah teks, teks dapat dibaca di dalam konteks yang berbeda. Intensi pengarang dan konteks yang menyertainya bersifat tidak terbatas. Konteks sebuah teks dapat didekati tetapi tidak dapat sepenuhnya ditentukan dan dipastikan. Maka atas alasan ini pula, sebuah teks selalu terbuka terhadap konteks yang berbeda dan dapat dibaca dengan beraneka ragam cara. Teks-teks filsafat, misalnya, dapat dibaca di dalam konteks psikoanalisa atau feminis.[30] Di dalam Dissemination, Derrida menegaskan pembacaan dekonstruksi sebagai percabangan tekstual. Pembacaan atas teks bukan untuk menemukan makna yang paling sahih atau konteks yang paling benar, termasuk menemukan maksud dan konteks sang pengarang. Sebaliknya, pembacaan dekonstruksi berusaha mencari titik persilangan dan intertekstualitas di antara teks-teks yang berbeda. Percabangan tekstual juga dapat dilakukan dalam rangka studi terhadap etimologi kata di dalam teks, biasanya disebut oleh Derrida dengan paleonymy. Paleonymy adalah penyelidikan makna kuno (palaois) sebuah kata (nomen), dan melalui investigasi paleonymy ini akan ditemukan makna baru.[31] Istilah paleonymy, demikian Derrida, berbeda dengan istilah etimologi yang masih di dalam rangka metafisika. Kata etymology berasal dari bahasa Yunani etymos, berarti nyata dan benar, sementara logos, berarti sabda, alasan, atau rasio. Maka istilah etimologi merujuk pada yang nyata, asali, makna kata yang benar. Para filsuf biasanya mengklarifikasi asal-usul makna kata dengan menelusuri etiomologinya. Heidegger, misalnya, melakukan destruksi terhadap tradisi pemikiran Barat dengan menelisik makna-makna etimologis konsep filsafat tradisional, seperti Ada dan kebenaran. Heidegger bermaksud menyegarkan kembali makna sebuah kata dengan menelusuri asal-usulnya hingga ke tradisi filsafat antik agar dapat dipahami dalam konteks kekinian. Heidegger memiliki tendensi untuk memahami asal-usul makna sebuah kata melalui penyelidikan etimologis sebagai makna asali dan aktual.[32] Sebaliknya, melalui paleonymy, Derrida melepaskan ikhtiar untuk mencari makna literal dan jelas (propre) atau makna asali kata, melainkan hendak menerangi ambiguitas kata, konsep dan pengertian. Jonathan Culler menganggap Derrida menggunakan teknik puisi ke dalam teknik pembacaan teks dengan meninggalkan kelaziman cara pemahaman. Tidak heran bila Derrida memiliki
perhatian lebih terhadap morfologi, fonetik, grafik, dan hubungan semantik atau etimologis istilah tertentu dalam filsafat. Derrida tanpa sungkan mentransformasikan istilah kesusastraan ke dalam istilah filsafat. Di dalam Signponge, misalnya, Derrida mentransformasikan metafor dan imaji puitik Francis Ponge secara tidak konvensional dan lalu mengadaptasinya ke dalam konsep filsafat, dan melalui metafor Ponge ia melukiskan proses pembentukan makna serta bahasa. Derrida, misalnya, menggunakan metafor Ponge mengenai mesin cuci untuk menggambarkan peristiwa tulisan, lalu mentransformasikannya ke dalam istilah filsafat. Penulis, bagi Derrida dengan meminjam istilah Ponge, ibarat mesin cuci yang membersihkan pakaian (pakaian adalah metafor untuk kata). Kata-kata adalah pakaian kotor yang akan memiliki makna otentik dan unik ketika dicuci. Analisis Derrida dalam buku ini bercampur-baur dengan teks Ponge, sehingga sulit dibedakan lagi antara pemikiran Derrida dan pemikiran Ponge. Melalui teks Francis Ponge ini, Derrida hendak menegaskan kaburnya batas-batas antara pembaca dan teks, tidak sebagaimana yang terjadi dalam riset ilmiah yang berupaya memisahkan secara tegas antara peneliti dan objek yang ditelitinya agar dapat meraih penjelasan objektif atas realitas. Derrida sama sekali menampik pemisahan yang sudah mapan di dalam tradisi sains ini. Karya-karya akhir Derrida, khususnya Glas, Signpong, dan Post Card bukanlah karya-karya ilmiah ala sains atau filsafat pada umumnya, tetapi peleburan gaya penulisan filsafat dan kesusastraan. Baginya, teks tidak akan pernah bersifat eksternal terhadap pembaca, karena setelah sebuah teks selesai dituliskan, ia hanya akan bertahan secara historis dan hidup di dalam dunia batin pembaca sepanjang hayat. Dekonstruksi, Skeptisisme, dan Permainan Michel Haar dalam tafsirnya mengenai Nietzsche dan Derrida mengungkapkan bahwa elemen penting yang diradikalkan oleh Derrida dari Nietzsche adalah konsep main. Filsafat mendapatkan energinya kembali justru pada kemampuannya untuk menggunakan tulisan sebagai permainan. Dua strategi yang dilakukan Derrida; pertama membalik oposisi metafisis, kedua bermain melalui bahasa. Kedua pembalikan ini membawa kita ke titik yang paling ekstrim, yaitu destabilisasi tanpa batas. Derrida membalik metafisika Barat sebagi sistem-sistem oposisi tidak dengan menghadapkannya pada yang non-metafisis. Tetapi Derrida menandaskan fakta bahwa tidak ada konsep yang dalam dirinya sendiri bersifat metafisis, dalam kata-kata Derrida:Tidak ada sesuatu yang disebut sebagai konsep metafisika. Tidak ada sesuatu yang disebut dengan nama metafisika. Metafisika merupakan suatu determinasi atau arah yang diambil oleh sebuah mata rantai. Seseorang tak dapat menghadapkannya pada sebuah konsep, tetapi pada suatu proses kerja tekstual atau perangkaian yang lain.[33] Strategi yang perlu diambil, demikian Derrida, adalah memasukan loxos ke dalam logos. Dekonstruksi dengan demikian, membiarkan ekuivokalitas, ketidakpastian makna, ambiguitas dalam logika pembalikan tersebut. Nietzsche telah membawa kita lepas dari dasar, asal-usul, dan kebenaran yang menjadi pencarian filosofis sepanjang masa. Ia telah melepaskan dalam bahasa Derrida- derivasi makna dari logos. Nietzsche mencabut akar logos dari keterpautan alamiahnya dengan makna. Tanda tidak lagi memuat secara alamiah makna, karenanya bahasa dan kebenaran hanya soal interpretasi, soal tafsir, yang tak bebas dari proses pembentukan bersama yang bersifat abitrer dan sementara.
Bersama Nietzsche, kita menemukan kembali semangat permainan yang telah dilupakan oleh filsafat. Filsafat yang hendak bertumpu pada rigorisitas, ketat, logis dan transparan bagi Nietzsche dan juga Derrida hanya ilusi pikiran. Seakan-akan terdapat korespondensi langsung antara pikiran dan kenyataan. Apa yang kita sebut kebenaran adalah hasil konstruksi melalui bahasa, dan bila bahasa telah dilepaskan dari klaimnya sebagai medium ungkapan kehadiran penuh makna, yang tersisa kemudian adalah suatu permainan, sebagaimana bermain catur di atas papan tanpa dasar.[34] Melalui Nietzsche, Derrida mengembalikan skeptisisme dan kritisisme sebagai semangat awal modernitas yang terlupakan. Dekonstruksi menanggalkan kepercayaan Kantian bahwa kesadaran merupakan representasi akurat dunia eksternal di seberang sana, kepercayaan yang terus dipeluk oleh filsafat bahasa mutakhir. Dekonstruksi menginterogasi kepercayaan demikian. Derrida mengkritik klaim filosofis representasionalisme dan referensi linguistik yang meretakkan korespondensi antara kata dan benda. Dekonstruksi Derrida merupakan versi klasik skeptisisme linguistik, sehingga tidaklah aneh, kalau dikatakan filsafat Derrida adalah sebentuk imanensi linguistik; sebagai konsekuensi lepasnya hubungan langsung subjek dengan dunia di luar dirinya.[35] Ketidakpastian makna atau juga disebut dengan permainan bebas penanda biasanya dianggap sebagai konsekuensi dari destruksi terhadap pijakan referensial bahasa, karena bahasa telah diputus hubungan korespondensialnya dengan dunia eksternal, sehingga tak ada lagi yang internal, tak ada privelese atas makna, atau penanda guna menjamin stabilitas makna. Jika skeptisisme Derrida berarti melepaskan referensi, dan jika bahasa tidak lagi stabil sebagaimana korespondensi Kantian, maka makna mendiseminasi ke segala arah. Diseminasi tanpa batas ini terkait erat dengan kritik Derrida terhadap representasi. Namun pada saat yang bersamaan kritik terhadap representasi yang mendorong kesadaran subjek masuk ke dalam perangakp tekstualitas. Kita semua terperangkap di dalam teks dan di dalam interpretasi kita terhadapnya. Interpretasi yang menempatkan dekonstruksi sebagai bentuk skeptisisme linguistik juga tidak hanya menunjukkan ketidakmungkinan pengetahuan di dalam kerangka filsafat Derrida, tetapi juga tak dapat dielakkan, subjek yang berbicara terperangkap dalam imanensi ruang tekstual. Bagi yang mempercayai dekonstruksi, ini bukan mengarah pada halusinasi atau mimpi, tetapi masuk ke dalam permainan bebas tanda.[36] Di sisi lain, Derrida melepaskan ikhtiar filsafat untuk mencari jawab. Derrida ingin mengembalikan tugas filsafat yang terus-menerus mengajukan pertanyaan, menginterogasi dan menggoyang posisi-posisi. Derrida mempersoalkan teks, mempertanyakan tulisan, menggugat subordinasi ontologis, menyoal marginalia, dan mempermasalahkan metafor. Seseorang yang hendak mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan Derrida terhadap persoalan tersebut di atas akan putus asa dan kebingungan. Mengharap jawab dari Derrida adalah naif. Derrida menggugat pengandaian bahwa dalam setiap persoalan terdapat jawaban. Derrida tidak pernah menjawab berbagai soal yang diajukannya, karena ia percaya semua itu tak ada jawab. Persoalan ini terlihat elementer, tetapi sesungguhnya sangat krusial. Di dalam, Genesis and Structure and Phenomenology, Derrida menyatakan : pertanyaan mengenai kemungkinan reduksi
transendental tidak terjawab. Dalam teks lain, pada kalimat-kalimat awal dari Of an Apocaliptic Tone Newly Adopted in Philosophy, Derrida mengatakan: Tetapi saya harus mengingatkan saudara sekarang; sejarah atau teka-teki dari yang saya bicarakan,..........saya yakin tanpa solusi dan jalan keluar.[37] Beberapa bagian yang dikutip di atas menunjukkan bahwa Derrida sendiri menegaskan klaimnya mengenai persoalan yang diajukannya tanpa perlu atau tak ada jawab. Bahkan mungkin bila kita menjelajahi pemikiran Derrida dari satu karya ke karya lainnya, kita tak akan menemukan bahwa pertanyaan dan problematik yang diajukannya terjawab atau terpecahkan. Dekonstruksi atas problem filsafat bukan berarti memecahkan problem tersebut. Skeptisisme sebagai semangat dasar filsafat Derrida menegaskan bahwa problem filosofis harus terus-menerus diperiksa tanpa henti, sekalipun tak ada jawab yang akan diraih. Dalam, Violence and Metaphysics, Derrida mengemukakan pertanyaan mengenai kematian filsafat, dan sekalipun pertanyaan ini tak terjawab, hal ini harus terus-menerus diperiksa dan dipersoalkan ulang oleh komunitas filsafat, yang ia sebut sebagai, sebuah komunitas yang mempertanyakan kemungkinan pertanyaan.[38] Dengan mengajukan pertanyaan tanpa henti, elaborasi dan mengurai kerumitannya, dekonstruksi merupakan sejenis cara bertanya. Sejak awal karya sampai hari ini, Derrida menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah mengajukan pertanyaan atau menginterogasi teks, kata, posisi filosofis. Dekonstruksi problem filosofis bukan untuk memecahkan masalah tersebut atau sejenisnya, atau juga dekonstruksi sebuah teks bukan untuk menolak teks atau sebuah posisi. Dekonstruksi konsep, kata, dan argumen bukan untuk menempatkan pengertian baru dalam sebuah teks, konsep dan kata tersebut. Dekonstruksi adalah cara khusus untuk menyoal suatu pokok masalah, teks, posisi, konsep, kata dan pokok soal filosofis tertentu. Dekonstruksi justru hendak mengungkapkan antinomi, aporia, paradoks-paradoks, pergantian dan ketidakterputusan makna teks filsafat serta intensi filosofis yang menyertainya. Tugas dekonstruksi adalah memperlihatkan bahwa makna dalam teks-teks filsafat tidak seperti yang dimaksudkan penulisnya, bahkan tidak ada makna yang baku secara keseluruhan. Teks-teks filsafat yang mendasarkan klaimnya pada kepastian yang tak tergoyahkan sesungguhnya sudah mengandung ketegangan, kontradiksi, dan antinomi internal yang mensubversi klaim-klaim kebenarannya sendiri. Setiap upaya untuk menjadikan bahasa sebagai jalan menemukan kebenaran translinguistik, transkultural, transhistoris, atau dalam bahasa Derrida disebut dengan makna transendental, adalah suatu kosakata platonis yang berada di luar kebudayaan. Bahasa merupakan cermin yang retak bagi realitas yang hendak dipantulkannya. Filsafat yang berintensi meraih kebenaran universal, dalam kenyatannya, tak dapat dilepaskan dari gravitasi bahasa partikular. Tak ada jalan keluar dari permainan bahasa. Makna tidak lagi tersungkup di balik teks dan kita tinggal menjemputnya, makna lahir dari struktur perbedaan yang inheren dalam setiap teks. Lebih jauh, dekonstruksi Derrida menolak tirani totalitas dan esensi yang mendominasi tradisi filsafat sejak lama. Gagasan mengenai totalitas, yaitu bahwa realitas itu satu dan sebagai akibatnya mensubordinasi segala keragaman dan kontradiksi ke dalam satu sistem. Totalitas seakan menyerap begitu saja keragaman, perbedaan dan multiplisitas yang menjadi karakter kenyataan. Totalisasi, sebagaimana kita mafhum, bukan hanya soal pikiran, tetapi juga memuat kecenderungan pada totalitarianisme politik; totalisasi atas masyarakat juga ekuivalen dengan
impian sains modern. Peristiwa holocaust, pembunuhan antaraetnis, dan pengusiran terhadap kaum imigran, dalam arti tertentu, merupakan konsekuensi dari resapan berpikir dalam kerangka totalitas, totalitas emoh terhadap perbedaan, pluralitas, dan menyingkirkan anasir yang tak dapat dikategorisasi dan diidentifikasi. Dengan kata lain, kelainan (otherness) merupakan penyakit yang harus disingkirkan. Dekonstruksi memperhatikan yang sebaliknya; partikularitas dan perbedaan, keragaman, heterogenitas, yang marjinal, fragmen-fragmen. Dalam kenyataan, pluralisme merupakan kondisi yang niscaya bagi terwujudnya prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Selanjutnya, menurut Derrida, esensi juga bersifat opresif. Esensi merupakan gagasan yang mendasari filsafat sains, yang klaim-kalim saintifiknya runtuh tanpa esensi. Sains dan pengetahuan perdefinisi merupakan kegiatan mengetahui sesuatu. Asumsi metafisis yang mendasari ikhtiar epistemik ini adalah bahwa suatu benda itu secara persis demikian dan bukan yang lain; esensialisme berdiri di atas prinsip identitas dan menjadi pijakan dasar logosentrisme. Sebagaimana yang dinyatakan Nietzsche, apa yang dikatakan oleh masyarakat di masa lalu menjadi terkanonisasi dan mengalami fikasasi. Esensi adalah fiksasi yang terpenjara dalam keadaan stagnan, baku, dan lepas dari hukum perubahan. Pembelaan terhadap yang partikular, marjinal, atau kontradiksi bukanlah semudah memilih merek baju atau menu makanan. Merayakan perbedaan berarti menunda terus-menerus hasrat kepastian, dan masuk dalam semangat permainan. Ketika filasafat dilucuti makna transendentalnya, maka yang tersisa adalah permainan kata yang tidak lagi merujuk pada realitas di luar dirinya, kata berkait-erat dengan kata lain secara tak terbatas, suatu intertekstualitas. Makna selalu tertunda, tanpa batas, dan diseminasi ketidakpastian makna; sebuah labirin tanpa ujung di mana kita dikutuk untuk berkelana tanpa arah. Absennya makna transendental memperluas wilayah dan permainan signifikansi tanpa batas, di mana-mana hanya perbedaan dan permainan jejak dari jejak.[39] Keterbukaan Pada Rahasia Derrida sebagaimana Nietzsche dan Heidegger telah menyodorkan pengertian baru mengenai apa itu pemikiran yang secara khas beroperasi tanpa metode. Pemikiran yang secara khas beroperasi tanpa metode ini oleh Heidegger disebut dengan pemikiran meditatif. Pemikiran tidak dapat direduksikan semata pada teknik, metode, dan seperangkat aturan ilmiah ala sains. Dengan kata lain, pemikiran radikal tidak akan muncul dari pengetahuan yang sudah tersedia, tetapi terletak pada kemampuannya untuk mempersoalkan tanpa henti fondasi dan rejim pengetahuan yang sudah ada, termasuk filsafat. Pemikiran radikal dapat menyajikan sudut pandang baru pada tradisi, bahkan mentransformasikan dasar-dasar pemahaman. Karenanya, sudut pandang dekonstruksi berbeda dengan pemikiran filsafat pada umumnya, misalnya filsafat perenial yang berusaha menemukan dan mengukuhkan pengertian universal. Dari sudut dekonstruksi, filsafat tampil sebagai pemikiran kreatif dan proses yang tak pernah sudah untuk menciptakan pengertian tekstual baru, khususnya lewat persilangan konteks, kuasi-konsep, dan menggantikan gagasan-gagasan lama. Menurut Derrida, filsafat tidak tumbuh dan berkembang secara linier menuju kesempurnaan, melainkan dibentuk oleh perjumpaan teks dan konsep yang lahir dalam kurun waktu yang
berbeda. Pemikiran filsafat yang kreatif artinya bahwa tulisan atau pemikiran tekstual melahirkan cara baru dalam melihat dunia yang tidak ditemukan sebelum invensi dan deskripsi tekstual. Dengan demikian, filsafat tidak hanya melukiskan berbagai cara berada universal di mana keragaman deskripsi hanya menyajikan metafor yang berbeda untuk objek yang sama. Filsafat bertolak dari pengandaian bahwa dunia berubah secara historis dan pengertian historis baru akan turut mengubah dunia. Metafor filsafat, kuasi-konsep, dan neologisme menciptakan objek-objek baru pengetahuan dan cara memahami dunia. Dekonstruksi bukanlah sebuah metode dalam arti tradisional yaitu seperangkat aturan ilmiah yang siap digunakan untuk mendapatkan pengetahuan sistematik dalam penelitian sebuah objek. Derrida menampik konsep tradisional mengenai metode, terutama mempersoalkan metode pembacaan atas teks dengan seperangkat pendekatan konseptual yang sistematik. Derrida menggugat anggapan mengenai koherensi teks, karena setiap teks ditandai ketegangan internal, diskontinuitas, dan entitas intertekstual di dalam jaringan permainan perbedaan. Dekonstruksi tidak bertolak dari pembaca, karena teks itu sendiri di dalam dirinya bersifat dekonstruktif. Dekonstruksi bukanlah metode yang siap diterapkan terhadap teks, ia merupakan ciri pokok semua teks dan tekstualitas. Stategi dekonstruksi sebagai tulisan ganda atau pembacaan ganda terhadap teks adalah strategi dekonstruksi yang paling dikenal luas, sebagaimana digambarkan oleh Derrida di dalam Positions. Tulisan ganda dimaksudkan untuk membongkar struktur hierarki oposisi biner pemikiran Barat. Sebagai tulisan ganda, dekonstruksi beroperasi dalam dua langkah sekaligus: memahami secara teliti sebuah teks dari dalam teks itu sendiri dan merekonstruksi maksud pengarang serta kandungan teks, kemudian mendekonstruksi makna sentral sebuah teks dari posisi luaran tertentu, dan mencermati titik buta yang dimuat oleh teks agar sudut pandang dekonstruksi dimungkinkan.[40] Dekonstruksi sebagai percabangan tekstual berupaya menelisik intertekstualitas di dalam teks untuk memperluas dan mendiseminasi pemahaman. Salah satu ciri pokok dari strategi pembacaan dekonstruksi ialah penolakan terhadap kemungkinan makna final, tetap dan stabil melainkan mendesak terus-menerus perbatasan teks untuk menggoyang segala pengertian yang sudah dimapankan, diekslusikan, dan disembunyikan oleh teks itu sendiri. Dekonstruksi bertolak belakang dengan pembacaan umumnya terhadap teks yang bemaksud memahami teks sebagai keseluruhan yang solid dan koheren, serta memperbaiki kontradiksi yang terkandung di dalam teks dengan model interpretasi tertentu, serta mencari petanda transendental atau sesuatu-padadirinya sendiri di balik teks. Derrida juga menolak sebuah sistem normatif mengenai dekonstruksi yang diturunkan dari analisis historis atas apa yang telah dikemukakan di dalam karya-karyanya, sistem normatif semacam itu hanya akan mengaburkan motivasi dasar dekonstruksi sebagai jawaban terhadap panggilan akan yang lain. Di dalam Force de loi Derrida menegaskan bahwa dekonstruksi, Beroperasi berdasarkan gagasan mengenai keadilan yang tidak berhingga. Tidak terbatas dalam arti tidak dapat direduksikan, ketidakmungkinan untuk direduksikan karena terikat dan berhutang pada yang lain, bertanggungjawab atas yang lain sebelum berbagai perjanjian dan kontrak, karena ia telah datang, kedatangan yang lain dalam singularitasnya selalu sebagai yang lain. Dekonstruksi, dengan demikian, paralel dengan apa yang
dikemukakan Heidegger sebagai keterbukaan pada rahasia, atau frase filsafat Levinas mengenai keterbukaan pada yang lain sebagai sepenuhnya yang lain.[41] Filsafat tidak lagi beroperasi di atas klaim absolutisme dan kebenaran, dalam bahasa Rorty, filsafat dewasa ini hanya sejenis tulisan, bahkan genre dari fiksi. Ketika segala sesuatu menjadi tekstualitas dan intertekstualitas, tak ada lagi dunia yang sesungguhnya di seberang teks, kita semua masuk ke dalam lubang hitam di mana penanda-penanda bebas mengambang. Ini merupakan nihilisme; nihilisme yang menggembirakan dan membebaskan. Derrida sesungguhnya tidaklah melantunkan sesuatu yang baru, ia hanya membawa kegembiraan Nietzsche; pengetahuan yang menggembirakan sebagai titik tolak untuk menggugat metafisika kehadiran yang merembesi seluruh pemikiran Barat sejak Plato. Derrida melanjutkan proyek Nietzsche yang tak lagi bernostalgia akan esensi, substansi, kebenaran atau bahkan Tuhan sebagai pengikat yang mendasari dunia makna. Sebagaimana Nietzsche, Derrida berhasrat melepaskan sentrum, agar pluralitas kenyataan kembali terhampar seperti sediakala, dan perbedaan terus dirayakan. Dekonstruksi Derrida terhadap metafisika Barat menguatkan pernyataan Nietzsche bahwa: Kebenaran adalah sepasukan metafor dan metonimi, antropomorfisme,.......kebenaran adalah fiksi yang kita lupa bahwa ia adalah fiksi. Derrida mengungkapkan kembali kegelisahan Nietzsche satu abad yang lalu itu dengan mengatakan, Sejarah metafisika, sebagaimana sejarah Barat, adalah sejarah metafor dan metonimi. Tidak ada yang mengejutkan pada Nietzsche dan Derrida, apalagi mencemaskan. Nietzsche dan Derrida hanya mengingatkan kita akan kefanaan, yang menjadi karakter penting hakikat Dasein.[42]
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20024)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3277)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5508)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)








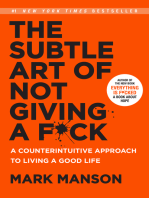



![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)