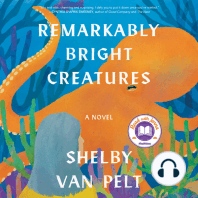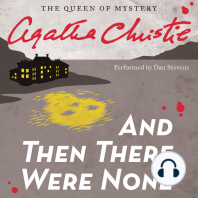Bahan Lomba Debat Rechstaat Asas Retroaktif
Diunggah oleh
Garrisha RissaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bahan Lomba Debat Rechstaat Asas Retroaktif
Diunggah oleh
Garrisha RissaHak Cipta:
Format Tersedia
Penerapan asas retroaktif dari sisi pengetahuan hukum, pemberlakuan asas retroaktif dapat dipahami sepanjang diberlakukan secara
rigid dan darurat limitatif sifatnya, artinya apabila negara dalam keadaan darurat (abnormal) dengan prinsip-prinsip hukum darurat (abnormaal recht), karena itu penempatan asas ini hanya bersifat temporer dan dalam wilayah hukum yang amat limit, dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terkontaminasi unsur-unsur yang dapat dikategorikan abuse of power. Adapun alasan utama dikenai prinsip hukum retroaktif apabila kejahatan yang diketegorikan sebagai kejahatan luar biasa. Sebagai contoh, Urgensi Asas Retroaktif Pemberlakuan Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 tidak terlepas dari berbagai masalah yang menyertai keberadaannya dalam sistem hukum pidana. Memang sejak awal diundangkannya terjadi pro-kontra sebagai instrumen hukum pidana dalam kasus Bom Bali yang telah menewaskan lebih kurang 200 (dua ratus) orang dari berbagai latar kewarganegaraan. Penolakan atas diberlakukannya Perpu No. 1 dan 2 tahun 2002 tersebut dikarenakan Perpu tersebut menerapkan asas retroaktif (berlaku surut) bagi para pelaku bom Bali di mana hal ini dianggap tidak sesuai dengan asas legalitas pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan ini pun dianggap melanggar prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang. Aspek yuridis yang umum dikemukakan oleh mereka yang menolak diberlakukannya Perpu No. 1 dan No. 2 tahun 2002 tersebut adalah Pasal 28 I ayat 1 Amandemen ke-4 UUD 1945 yang berbunyi: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari pasal ini jelas sesungguhnya penerapan asas retroaktif diperbolehkan khususnya untuk penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan. Semangat untuk memberlakukan eksistensi asas retroaktif kini bisa dianggap sebagai kemunduran jika dikaitkan dengan asas lex tallionis sebagai sumber primaritas, tetapi semangat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi bagi pelaku yang telah menikmati hasil korupsi di masa lalu bukan sebagai semangat "tallionis", tetapi merupakan tindakan pemulihan dan penyelamatan harta kekayaan negara yang telah diselewengkan pelaku korupsi yang tidak bertanggung jawab. Pemberlakuan asas retroaktif untuk kejahatan korupsi yang kami anggap sebagai kejahatan terhadap masyarakat (crimes against society) adalah suatu hal dimungkinkan selain dapat mematahkan upaya-upaya impunity, juga agar dapat menyelesaikan secara tuntas dan adil tiap kejahatan korupsi yang telah menyengsarakan masyarakat. Persoalan penggunaan asas retroaktif ini akan menjadi semakin sulit apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materiil terhadap UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang menurut para pemohonnya bertentangan dengan Pasal 28i Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena memberlakukan asas retroaktif. Apabila ini terjadi berarti Mahkamah Konstitusi telah berpendirian, asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana Noellun Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lega Poenali sama sekali tidak dapat disimpangi tuntutan keadilan masyarakat. Kalau kembali menggunakan asas legalitas seperti dalam Pasal 1 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana), maka produk hukum tidak bisa berlaku surut. Tidak boleh ada satu perbuatan yang didakwakan sebelum ada peraturannya. Artinya, perbuatan yang terjadi sebelum ada undang-undangnya, itu tidak bisa diberlakukan. Inilah prinsip hukum yang digunakan di Indonesia sampai sekarang. Munculnya asas retroaktif sebenarnya dimulai dari misteriusnya Amandemen UUD (Pasal 28 i ayat 1) yang kemudian disusul lahirnya UU Pengadilan HAM. Pada hal proses pembuatan dua dokumen penting yang kontraversial tersebut terjadi di suatu kompleks bangunan MPR-DPR yang jaraknya hanya satu langkah. III) Apalagi semua anggota DPR berdasarkan UUD 1945 adalah juga anggota MPR. Mengapa kedua lembaga negara tersebut melahirkan peraturan perundang-undangan yang isinya bertolak belakang. MPR menciptakan
Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945, yang melarang azas Retroaktif, sedang DPR menciptakan UU Pengadilan HAM, yang memperbolehkan asas Retroaktif. Yang juga mengherankan adalah tidak adanya kegiatan atau gerakan menentang RANCANGAN Amandemen yang menghasilkan Pasal 28 (i) ayat 1 tersebut ketika itu. Sepertinya lembaga-lembaga pembela HAM, pakar-pakar hukum peduli keadilan semuanya kena obat bius, teler dan tidak melihat keanehan yang muncul di lapangan hukum di Indonesia. Padahal Pasal 28 (i) ayat 1 UUD 1945 secara riil bisa diterapkan untuk menghadang agar kasus pelanggaran HAM masa lalu (Pembunuhan dan penahanan massal 1965-66, kasus Trisakti, kasus Tanjung Priok, Kasus Jl. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan bersamaan dengan itu impunity terus berdominasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tentu saja rambu-rambu yuridis dari Pasal 28 (i) ayat 1 tersebut harus diletakkan pada posisi demi keadilan, sepanjang menyangkut masalah pelanggaran HAM BERAT. Maka perlu usaha gebrakan untuk mengadakan amandemen terhadap pasal 28 (i) ayat 1 tersebut: cukup dengan penambahan kata-kata "kecuali mengenai pelanggaran HAM berat, yang diatur selanjutnya dalam UU". Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara UUD (Pasal 28 (i) ayat 1) dan UU Pengadilan HAM ad Hoc dalam masalah asas retroaktif. Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 Magna Charta (1215) di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence (1776) di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan. Pandangan inilah yang akhirnya dibawa ke Perancis oleh seorang sahabat dekat George Washington, Marquis de Lafayette. Ketentuan mengenai "tiada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undangundang yang sudah ada sebelumnya" tercantum dalam Declaration des Droits de lHomme et du Citoyen (1789). Gagasan itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda dan akhirnya Indonesia yang mengaturnya dalam Pasal 1 KUHP. Tujuan yang ingin dicapai asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh rule of law (Muladi, 2002). Asas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, tapi dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespons pesatnya perkembangan kejahatan. Dan, ini dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan mendasar. Oleh karena itu, E Utrecht (1966) mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingankepentingan kolektif (collectieve belangen), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep mala in prohibita (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan mala in se (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela). Dengan kelemahan asas legalitas itu, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif setidak-tidaknya untuk (1) menegakkan prinsip-prinsip keadilan; (2) mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama; (3) mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan; dan (4) mencegah terjadinya kekosongan hukum. Dengan empat alasan tersebut, asas legalitas yang sering mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan realitas dapat disimpangi secara selektif. Menurut mantan jaksa penuntut dalam International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY), Marie Tuma (2001), asas retroaktif dapat diterapkan terhadap situasi kekacauan yang menghancurkan manusia. Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika (1) menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan
perbuatan yang dapat dipidana; dan (2) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal HAM). Asas tersebut bisa mengakibatkan seseorang dapat dipidana dengan alasan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperhitungkan atau tidak diketahui akan membawanya pada pertanggungjawaban pidana. Pendukung asas ini mendasarkan diri pada asas ignorantia juris neminem excusat (ketidaktahuan hukum tidak membebaskan apa pun). Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State (1973) mengatakan, "Retroactive laws are considered to be objectionable and undesirable because it hurts our feeling of justice to inflict a sanction, especially a punishment, upon an individual because of an action or omission of which this individual could not know that it would entail this sanction." Kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang tidak diperhitungkan dan tidak diketahui oleh pelakunya akan membawa pada pertanggungjawaban hukum inilah yang menjadi keberatan ahli lain terhadap keberadaan asas retroaktif. Keberatan terhadap asas retroaktif semakin nyata setelah larangan penerapan hukum yang berlaku surut dicantumkan dalam konstitusi suatu negara sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Tidak hanya itu, sebagaimana terbaca dalam putusan MK, asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apa pun tidak dikehendaki karena dianggap dapat menimbulkan suatu bias hukum, mengabaikan kepastian hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan, dan akhirnya akan menimbulkan political revenge (balas dendam politik). Inilah yang disebut bahwa asas retroaktif merupakan cerminan lex talionios (balas dendam). Asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif: (1) kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya; (2) peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional; (3) peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan permanen; dan (4) keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya. Untuk membicarakan tentang tindak pidana atau delik korupsi, maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui asal-ususl istilah korupsi itu sendiri. Korupsi berasal dari bahasa Latin :Corruptio atau Coroptus yang kemudian muncul pula dalam perbendaharaan bahsa Indonesia : Korupsi. Istilah korupsi berasal dari perkataan corruptio, yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat : Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang corruptio (rusak). Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi yang disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan. Perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam peraturan pengusa militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Dalam konsiderans peraturan ini dikatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya. Dari uraian di atas, kemudian kalau kita meninjau kamus-kamus mengenai korupsi itu, baik yang Inggris-Inggris, maupun yang Inggris Indonesia, akan didapati bahwa arti korupsi itu adalah busuk, kuruk, bejat, dapat digosok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada penyuapan saja, yang kemudian menjadi luas. Dalam Encykioedia American disebutkan korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi dalam bidang polikitk, keuangan, material. Korupsi dalam bidang politik termasuk penyalahgunaan alat resmi dan dana negara untuk kepentingan kampanye partainya. Contohnya : skandal Watergate, alat-alat resmi dipakai semata-mata dan menyadap pembicaraan di gedung lawan yaitu di waterage. (Muladi dan Arief, 1992;133). Korupsi adalah suatu pengertian perbuatan melawan hukum yang ada sangkut pautnya dengan jabatan atau kewengan atau kekuasaan yang menempel pada si pelaku. Bahwa dengan perbuatannya
tersebut maka keuangan negara atau perekonomian dapat menderiata kerugian (Moegono, 1983;77) Menurut Andi Hamzah, SH kata korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptio atau Corruptus yang secara harfiah mempunyai arti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 1991;7) whistle blower adalah setiap orang lazimnya korban yang kemudian bersaksi memberikan keterangan kepada penyidik mengenai seluk beluk tindak pidana yang ia ketahui dan dengar sendiri bahkan ia alami sendiri. Dengan itu dia mendapatkan jaminan perlindungan atas keamanan (fisik) di bawah supervisi kepolisian.Caranya dengan mengubah identitas, menempatkan di suatu lokasi tertentu dan berada d bawah pengawasan superketat dari pihak intelijen kepolisian. Tujuan dari keberadaan whistle blower adalah memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada intelectual-dader dan pimpinan organisasi kejahatan. Sementara justice collaboratoradalah setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparatur hukum untuk bekerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif. Perlindungan hukum terhadap whistle blower berbeda dengan justice collaborator. Perlindungan hukum terhadap whistle blower sebatas perlindungan fisik sedangkan perlindungan terhadap justice collaborator tidak sebatas fisik melainkan juga keringanankeringanan yang bisa ditawarkan. Keringanan itu baik dalam menentukan besarnya tuntutan penuntut atau hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim di persidangan atau bahkan kemungkinan untuk dibebaskan dari penuntutan. Keringanan-keringanan bagi justice collaborator telah diatur dalam Konvensi PBB Antikkorupsi 2003 dan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi 2000 yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam RUU Tipikor 2011, justice collaborator telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1):Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jikaiadapatmembantumengungkap tindak pidana korupsi tersebut.Pasal 52 ayat (2): Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang pernannya ringan dalam tindak pidana korupsi ....maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya. Namun dalam Hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai baik whistle blowermaupun justice collaborator kecuali UURINomor13 Tahun2006tentang Perlindungan Saksi/Korban. UU ini pun tidak memberikan hak istimewakepada seorang justice collaborator, kecuali peniup peluit. Persamaan whistle blower dan justice collaborator adalah keduanya bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan. Dalam konteks ini, kasus korupsi di Indonesia yang tidak pernah dilakukan sendirian melainkan bersifat kolektif, keberadaan ketentuan whistle blower dan justice collaborator merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Namun demikian celah hukum bagi baik whistle blower dan justice collaborator bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang fair and impartial sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan mengail di air keruhatau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkanhaltersebut. Dalam konteks ini kebijakan Menkumham memberikan bebas bersyarat (VI) lebih awal (Mei 2012) dari seharusnya waktu pembebasan bersyarat bagi MRM bulan November 2012 tidak terlepas dari dua kemungkinan risiko tersebut di atas. Penetapan justice collaborator harus dikaji secara mendalam karena tiga alasan.Pertama, kasus korupsi telah dipahami masyarakatluassebagaikejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Kedua, paham bahwa tujuan hukum pidana adalah penghukuman semata-mata masih melekat kuat baik pada masyarakat maupun pada aparatur hukum sekalipun tidak benar menurut doktrin maupun hukum acara pidana (KUHAP). Ketiga, keterlibatan tokoh partai politik dalam kasus korupsi telah dipahami
masyarakatsebagaibentukpengkhianatan dari janji kampanye Tahun 2009 yang lampau. Atas dasar hal tersebut maka penetapan seseorang tersangka menjadi justice collaborator seharusnya diatur dalam UU bukan dengan peraturan di bawah UU.Karena penetapan justice collaborator dan hak istimewanya merupakan terobosan hukum terhadap UU Pemasyarakatan dan juga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan politik. Kebijakan Menkumham mempercepat pemberian bebas bersyarat daripada batas waktu seharusnya terhadap MRM mencerminkan inkonsistensi dan diskriminasi perlakuan terhadap terpidana korupsi lainnya. Misalnya terhadap Paskah Suzetta dkk yang telah ditunda secara lisan pembebasan bersyarat dengan alasan perketatan terhadap terpidana korupsi sekalipun telah memenuhi syarat materiil maupun formil sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengaturan Hak Warga Binaan. Sekalipun pemberian hak istimewaterhadap MRM yang dianggap justice collaborator adalah wewenang Menkumham, tetapi KPK seharusnya menyampaikan sikap resmi mengenai kebenaran pertimbangan Menkumham mengenai hal tersebut kepada publik.
Harapannya agar tidak muncul simpang siur penafsiran terhadap kebijakan Menkumham tersebut.Apalagi PP Nomor 28 Tahun 2006 tidak mengatur percepatan pemberian remisi dan bebas bersyaratterhadap justice collaborator sekalipun terpidana korupsi. ROMLI ATMASASMITA Guru Besar Emeritus Hukum Pidana Internasional, Anggota Dewan Pakar Partai NasDem. Pengaturan Pembuktian Terbalik Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada tahun 1971 telah dibentuk UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian pada tahun 1999 diundangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik terbatas yang terdapat dalam Pasal 37 yang memungkinkan diterapkannya pembuktian terbalik yang terbatas terhadap harta benda tertentu dan mengenai perampasan harta hasil korupsi. UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 pada asasnya tetap mempergunakan teori pembuktian negative, kemudian di UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni berupa Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dan Berimbang. Yang mengatur pembuktian terbalik secara lebih jelas yaitu pada Pasal 12 B, 12 C, 37, 37A, 38 A, dan 38 B. Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Didalam pasal tersebut dinyatakan : ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum pemerintahan (algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain. Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur di dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (Lex specialis derogate Legi Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Pada KUHP Tindak Pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi terdapat di dalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435 KUHP). Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan Tindak Pidana Korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelakupelakunya. Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem Eropa Kontinental maupun AngloSaxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam certain cases (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai Reversal of Burden Proof (Omkering van Bewijslast). Itu pun tidak dilakukan secara overall, tetapi memiliki batasbatas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/ Terdakwa. Penjelasan umum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni : terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata bersifat terbatas didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata berimbang dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output atau dengan kata lain input lebih kecil dari output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut (misalnya rumah-rumah, mobil-mobil, saham-saham, simpanan dolar dalam rekening bank, dan lain-lainnya) adalah hasil perolehan dari tidak pidana korupsi yang didakwakan. Jadi, dalam pembuktian delik korupsi dianut dua teori pembuktian, yakni : 1) Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa Teori bebas sebagaimana tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta berwujud dalam, hal-hal sebagai tercantum dalam pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut: a) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. b) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
c) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. d) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber panambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. e) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. 2) Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh penuntut umum. Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tersirat dalam pasal 183 KUHAP, yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sistem pembuktian terbalik adalah sistem dimana beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan dimungkinkannya dilakukan pemeriksaan tambahan atau khusus jika dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi namun hal tersebut belum didakwakan. Bahkan jika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya.
Asas Pembuktian Terbalik dalam KUHAP
Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi : a. alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.
b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan tersangka (pasal 188 ayat 2 KUHAP). Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam pasal 188 ayat 2 KUHAP, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 26 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu : a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP. Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur. Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya, melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim. Istilah pembuktian terbalik telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat, dari sisi bahasa dikenal sebagai omkering van het bewijslat atau reversal burden of proof yang bila diterjemahkan secara bebas menjadi pembalikan beban pembuktian. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang universalis terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembuktian terbalik
Kalimat tersebut sungguh tepat karena tanpa meletakan kata beban maka makna yang terjadi akan berlainan. Pembuktian terbalik tanpa kata beban dapat ditafsirkan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa sehingga secara harfiah hanya melihat tata urutan alat bukti saja. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian, yaitu: a. Beban Pembuktian pada Penuntut Umum Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitornya. Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena penuntut umum masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri. Teori beban pembuktian ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Beban pembuktian seperti ini dapat dikategorisasikan beban pembuktian biasa atau konvensional. b. Beban Pembuktian pada Terdakwa Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada asasnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori Pembalikan Beban Pembuktian (Omkering van het Bewijslast atau Shifting of Burden of Proof/ Onus of Proof). Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu: 1) Untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHP, yang menentukan bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. Terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. 2) Ia berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suami (jika terdakwa
adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak. Perolehan/ pelepasan hak itu mengenai kapan; bagaimana; dan siapa-siapa saja, yang terlibat dalam perolehan/ pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi. Dikaji dari perspektif teoritis dan praktik teori beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (limited burden of proof). Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. c. Beban Pembuktian Berimbang Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian berimbang. Apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut dikaji dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi yaitu: a. Sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan undang-undang. Kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. b. Teori pembalikan beban pembuktian yang dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut atau murni bahwa terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian terdakwa dan Penuntut saling membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20024)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3277)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5508)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1107)








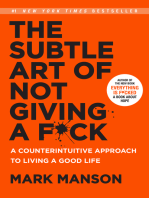



![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)