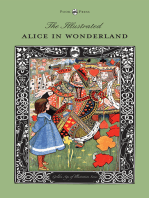Problematika Penegakan Keadilan Substantif
Diunggah oleh
Daus MbolHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Problematika Penegakan Keadilan Substantif
Diunggah oleh
Daus MbolHak Cipta:
Format Tersedia
PROBLEMATIKA PENEGAKAN KEADILAN SUBSTANTIF
A. PENDAHULUAN Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih debatable. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan seyogyianya hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong undang-undang). Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undangundang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
B. KEADILAN SUBSTANTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL Permasalahan sebagaimana tergambar pada bagian pendahuluan di atas agaknya tidak dapat dilepaskan dari dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan procedural. Keadilan substantif di dalam Blacks Law Dictionary 7th Edition dimaknai sebagai : Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors
Not Affecting The Litigants substantive Rights. (Blacks Law Dictionary, 7th Edition, p. 869) [Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat]. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Sebaliknya, merujuk pada definisi yang diberikan oleh Wikipedia, procedural justice atau keadilan prosedural adalah : Refers to the idea of fairness in the processes that resolve disputes and allocate resources. One aspect of procedural justice is related to discussions of the administration of justice and legal proceedings. This sense of procedural justice is connected to due process (US), fundamental justice (Canada), procedural fairness (Australia) and natural justice (other common law jurisdictions), but the idea of procedural justice can also be applied to nonlegal contexts in which some process is employed to resolve or divide benefits or burdens. Procedural justice concern the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with distributive justice (fairness in the distribution of rights or resources),and retributive justice (fairness in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterised as procedurally fair. Some theories of procedural justice hol that fair procedural leads to equitable outcomes, even if the requirements of distributive or corrective justice are not met.
Terjemahan : Keadilan prosedural menunjuk pada gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan
keadilan dalam proses hukum. Makna keadilan procedural yang seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia), dan keadilan alamiah (Negara-negara Comon Law lainnya), namun gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagibagi keuntungan atau beban. Dengan merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumber daya), dan keadilan distributir (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syaratsyarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.
C. POSITIVISTIK ATAU MORALISTIK? Guna membedah dikotomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural dalam proses penegakan hukum, kiranya perlu dilakukan review terhadap akar filosofis dari penegakan hukum itu sendiri. Mencermati pendapat Hans Kelsen, penegakan hukum oleh hakim itu terikat pada teori positivisme, yaitu bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia. Dalam hal ini, Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai. Hakim terikat dengan hukum positif yang sudah ada, berdasarkan paham legisme dalam konsep positivisme, hakim hanya sebagai corong undang-undang, artinya mau tidak mau hakim harus benar-benar menerapkan suatu kejadian berdasarkan konsep hukum yang sudah ada. Dalam praktiknya, konsep positivisme dalam penegakan hukum ini ternyata sangat jauh dari keadilan, karena sering sekali hukum positif itu ketinggalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, sehingga dalam penerapan teori positivisme tidak bisa
serta merta dilaksanakan dengan paham legisme. Hakim boleh menerapkan teori ini pada kasus yang aturan hukumnya jelas, sehingga tinggal menerapkan saja pada peristiwa konkret, namun dalam hal peristiwa yang tidak ada aturan hukumnya hakim harus menemukan dan menggunakan analogi untuk penemuan hukum. Hukumnya harus diupayakan dengan cara menelusuri peraturan yang mengatur peristiwa khusus yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicari hukumnya dengan jalan argumentasi (argumentum a contrario atau argumentum per analogiam). Kalau peristiwanya tidak diatur sama sekali dalam undang-undang, maka hakim berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 .wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hakim dalam memberikan keadilan kepada pencari keadilan, harus mempunyai iktikad baik, yaitu keyakinan hakim dengan alat bukti yang cukup untuk memutuskan suatu perkara sehingga dapat memberikan suatu keadilan dan kebahagiaan kepada para pihak dengan mengindahkan kode etik dan prosedural yang benar dalam praktiknya di pengadilan. Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, dan keikhlasan inilah yang menjadi barometer keadilan dalam penegakan hukum oleh hakim. Selama ini, banyak pihak menurut hakim agar lebih berpihak pada perwujudan keadilan substantif daripada keadilan prosedural semata. Namun, tuntutan itu memang bisa diterima secara teoritis daripada praktis karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural diyakini hanya mengacu pada bunyi undang-undang an sich. Sehingga, sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebijakan (virtue) bagi banyak pihak? Para penegak keadilan prosedural tidak mempedulikannya. Mereka, para penegak keadilan prosedural itu, biasanya tergolong kaum yang berorientasi positivistik. Bagi kaum positivistik, keputusan-keputusan hukum itu dapat dibuat dengan terlebih dahulu mendeduksikan secara logis peraturan-peraturan yang sudah ada tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebajikan, serta moralitas. Betapapun tidak adilnya dan
terbatasnya bunyi undang-undang yang ada. Hukum adalah perintah undang-undang, dan dari situ kepastian hukum bisa ditegakkan. Pandangan positivistik tersebut ditentang oleh kalangan yang berpandangan bahwa prinsip kebajikan dan moralitas mesti harus dipertimbangkan pula dalam mengukur validitas hukum. Penganut hukum moralis itu berprinsip bahwa hukum harus mencerminkan moralitas. Karena itu, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas, bahkan bertentangan dengan moralitas, boleh atau bisa tidak ditaati berdasar suatu hak moral (moral right). Indonesia adalah Negara yang menganut civil law system, yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. Alhasil, para hakimnya ialah pelaksana undangundang, bukan pencipta undang-undang (baca: hukum), sebagaimana yang dilakukan para hakim di Inggris yang menganut sistem common law. Alhasil, pakem yang masih berlaku di negeri ini adalah bahwa meskipun para hakim di Indonesia dapat melakukan penemuan hokum (rechtsvinding) melalui putusannya, mereka tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
D. MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEADILAN SUBSTANTIF MK dalam berbagai kesempatan telah menegaskan posisinya bahwa lembaga ini akan menegakkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural semata-mata. Dalam arti, sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak akan terpaku pada undang-undang jika undang-undang a quo dinilai keluar dari tujuan hukum sendiri. Pilihan paradigmatik ini didasari pada keyakinan bahwa dalam posisinya sebagai pengawal konstitusi, demokrasi, dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus mencari keadilan substansial, sebab, selain hal ini dibenarkan oleh UUD 1945 juga dimuat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar UUD Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
Pasal itu menyebutkan, bukti dan keyakinan hakim harus menjadi dasar putusan untuk menegakkan keadilan substantif, apalagi jika pihak yang berperkara jelas-jelas meminta ex aequo et bono (putusan adil). Pada irah-irah tiap putusan juga selalu ditegaskan, putusan dibuat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang. Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski-jika terpaksa-melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan. Ada yang mempersoalkan, hal itu sulit dilakukan karena tiadanya kriteria pasti untuk menentukan keadilan itu. Berbeda dengan bunyi undang-undang yang isinya pasti. Atas masalah itu perlu ditegaskan, keadilan tidak selalu dapat dipastikan lebih dahulu karena dalam banyak kasus justru harus disikapi sesuai karakter masing-masing. Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun hakim dengan menilai satu per satu bukti yang diajukan di persidangan untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat vonis. Meski demikian, tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang. Dengan kata lain, para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) di masyarakat dari pada terbelenggu ketentuan undang-undang (procedural justice). Yang hendak ditekankan adalah prinsip bahwa berdasarkan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, hakim diperbolehkan membuat putusan yang keluar dari undang-undang jika undang-undang itu membelenggunya dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. Selain itu, pilihan paradigmatik pada keadilan substantif juga dilatarbelakangi derasnya tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang memberikan solusi hikum atas ketidak pastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat terjadi kekosongan hokum. Demikian pula halnya dalam perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi bergerak menjadi pengadilan yang menegakkan keadilan substantif dan bukan
sekedar pengadilan perselisihan penghitungan atau yang sering disebut sebagai pengadilan kalkulator. Pergerakan atau pergeseran tersebut terjadi bukan karena kehendak para hakim konstitusi untuk memperluas kompetensi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi semata-mata untuk menegakkan konstitusi dan memenuhi tuntutan keadilan substantif. Hasil pemilu adalah manifestasi suara rakyat. Oleh karenanya, untuk menjamin hal itu harus dipastikan bahwa hasil pemilu harus didapatkan dengan cara yang benar, jujur, dan adil, serta dihitung dengan benar pula sesuai dengan prinsip one man, one vote, one value. Oleh Karena itu, perselisihan hasil pemilu tidak dapat dilihat secara sempit sebagai perselisihan di atas kertas, tetapi harus melihat bagaimana suara itu diperoleh. Suara yang diperoleh dengan cara melanggar prinsip jujur dan adil tentu tidak dapat dibiarkan karena sama halnya dengan membiarkan terjadinya ketidakadilan, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih itu sendiri. Menutup mata terhadap pemilu yang melanggar prinsip jujur dan adil sama halnya dengan membiarkan terbentuknya pemerintahan yang bukan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Pemilu hanya akan menjadi prosedur memperoleh kekuasaan semata. Jika terjadi demikian, hal itu akan menjadi awal dari malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria (tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain). Maknanya adalah bahwa tidak boleh ada pembiaran pelanggaran terstruktur dan masif. Dengan pilihan ini pelanggar dan orang-orang yang curang tidak justru diuntungkan kembali dan pihak yang dicurangi merasa dilindungi dan tidak kembali dirugikan dengan pelanggaran dan tanpa perlindungan. Hakim konstitusi adalah penentu terlaksananya wewenang konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, segenap organisasi Mahkamah Konstitusi diorientasikan untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan tanggung jawab hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dukungan administrasi umum
dan justisial diberikan untuk mendukung kinerja hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan hukum dan keadilan serta menjamin bahwa masyarakat mendapatkan keadilan dalam proses berperkara. Jika layanan administrasi tidak diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di lembaga peradilan, dapat dipastikan masyarakat telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif sejak pendaftaran perkara hingga proses untuk memperoleh putusan pengadilan. Pada saat administrasi peradilan sudah dijalankan secara diskriminatif dan tidak adil, putusan yang adilpun sulit dicapai. Bahkan, putusan yang adil pun dapat kehilangan makna apabila diputus dalam waktu yang lama dan tidak dapat segera diakses oleh masyarakat yang berhak (justice delayed, justice denied). Oleh karena itu, untuk dapat memutus sesuai dengan nilai dan rasa keadilan substantif, dukungan administrasi umum dan justisial diperlukan agar hakim konstitusi dapat dengan mudah dan cepat memeriksa dan menilai permohonan alat bukti, serta keterangan saksi dan ahli sebagai bahan pertimbangan hukum putusan majelis hakim. Untuk itu disusun mekanisme dan prosedur administrasi yang tepat dan cepat, apalagi untuk perkara PHPU yang harus diputus dengan cepat sesuai dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang. Di samping layanan terhadap hakim konstitusi, administrasi umum dan justisial juga memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada penerimaan permohonan yang dilakukan secara professional, tetapi juga memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh masyarakat untuk memperoleh keadilan sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Hal itu diperlukan agar semakin banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan cukup untuk dapat menggunakan hak berperkara di Mahakamah Konstitusi sehingga mendorong terwujudnya persamaan dihadapan hukum dan peradilan (equality before the law court). Peran tersebut juga diniatkan untuk memberikan dan memudahkan masyarakat memperoleh haknya mendapatkan keadilan (access ti justice) melalui pengadilan konstitusi (access to court). Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma keadilan substantif. Dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan
kesalahan tersebut bersifat tolerable, maka dapat dinyatakan tidak salah. Betapapun jika suatu ketentuan undang-undang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali-kali tentuklah dapat dikatakan intolerable dan mengandung ketidakadilan. Sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada Negara dan masyarakat. Perlu ditekankan juga bahwa pilihan paradigmatik Mahkamah Konstitusi atas penegakkan keadilan substantif bukan berarti mahkamah harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Dalam mengimplementasikan paradigma ini Mahkamah Konstitusi dapat keluar atau mengabaikan bunyi undang-undang tetapi tidak harus selalu mengabaikan atau keluar dari bunyi undang-undang. Selama bunyi undang-undang memberi rasa keadilan, maka Mahkamah Konstitusi akan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan putusan; sebaliknya jika penerapan bunyi undang-undang tidak dapat memberi keadilan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mengabaikannya untuk kemudian membuat putusan sendiri. Inilah inti hukum progresif atau hukum responsif yang dipahami dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan paradigma tersebut, maka dalam menangani sengketa hasil pemilu mahkamah tidak hanya menilai kebenaran kuantitatif dalam penetapan hasil pemilu, seperti menghitung kebenaran penetapan jumlah suara yang diperoleh parpol atau kontestan dalam pemilu, melainkan sekaligus menilai proses pelaksanaan pemilu untuk mencari kebenaran secara kualitatif. Oleh sebab itu, jika dalam proses pemilu terjadi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, yang mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan, tanpa harus memastikan kepastian penetapan jumlah (kualitatif) yang salah dalam penetapannya, maka Mahkamah Konstitusi dapat menentukan putusan atau sanksi tersendiri demi tegaknya keadilan, sekaligus untuk pembelajaran dan pendidikan agar pada pemilu-pemilu berikutnya pelanggaran semacam itu tidak terjadi lagi. Meskipun begitu, agar dalam menegakkan keadilan tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas dan diterima oleh common sense publik, maka kesalahan kualitatif proses pemilu
yang dapat dijatuhi sanski (condemnatoir) oleh Mahkamah Konstitusi adalah pelanggaranpelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif, dan masif.
E. PROBLEMATIKA PENEGAKAN KEADILAN SUBSTANTIF Meskipun secara konseptual idealisme yang terkandung dalam keadilan substantif sebagaimana keyakinan paradigmatik Mahkamah Konstitusi itu lebih adiluhung (bahasa Jawa) atau malebbi (bahasa Bugis) daripada yang terkandung dalam keadilan prosedural, namun upaya mewujudkan keadilan substantif lazim berbenturan dengan problematika kepastian hukum (equality). Contohnya ialah putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara pelanggaran pemilihan kepada daerah tidak diatur. Namun, karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa mereka menemukan bukti adanya pelanggaran pilkada, Mahkamah Konstitusi berhak mengambil keputusan tentang pelanggaran itu sekalipun harus menabrak UU Mahkamah Konstitusi sendiri. Sebagai justifikasi untuk kesiapan MK menabrak undang-undang, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud, M.D. menggunakan argumentasi dengan kalimat, Karena itu, kita bikin terobosan. Tidak lagi melaksanakan undang-undang, tetapi melaksanakan UUD 1945, yaitu menjamin tegaknya demokrasi dan hukum, (Jawa Pos, 3/12/2008). Permasalahannya kemudian adalah apakah penafsiran dan keputusan hukum MK itu legitimate? Ini merupakan pertanyaan yang debatable. Merujuk pada kenyataan hukum bahwa putusan MK adalah final dan mengikat (final and binding), apapun keputusan hukumnya akan menjadi legitimate karena tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubahnya. Alahasil, banyak pihak menilai MK sebagai lembaga superbodi, tidak ada lembaga lain yang bisa mengontrol keputusan-keputusannya. Sekalipun menabrak kepastian hukum.
Kepastian hukum pun makin rancu. Sebab, putusan MK itu bisa menjadi preseden bahwa pelanggaran pilkada di masa datang bisa langsung dikirimkan ke MK, menjadi bagian dari materi yang bisa diajukan gugatan (legal action) ke MK. Tak perlu lagi melalui jalur panwaslu untuk diproses di pengadilan negeri. Lalu, bagaimana dengan kepastian hukum UU Pemilu? Belum lagi problem sosial ikutan dari keputusan MK itu, misalnya penyediaan anggaran lagi untuk pilkada susulan, suasana ketegangan sosial yang dimunculkan darinya, dan kerepotan aparat keamanan untuk terus berada dari kondisi siaga satu ke siaga satu lagi. Juga, dari pihak yang kalah dan pendukungnya. Upaya hukum apa lagi yang bisa ditempuh? Karena pintu upaya hukum sudah tertutup, pintu yang terbuka adalah protes sosial yang berpotensi pada kerusuhan sosial. Biaya-biaya sosial tersebut barangkali memang tak terhitung, ketika hakim Mahkamah Konstitusi lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Menegakkan keadilan atau memilih kepastian hukum memang persoalan antinomi yang berlarut-larut dalam menentukan tujuan hukum. Para pakar hukum memang terbagi antara memilih keadilan atau kepastian hukum. Banyak di antara mereka memilih kepastian hukum karena lebih menjamin ketertiban hukum dan social. Pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memilih perwujudan keadilan substantive itu, dalam menyelesaikan perkara Pemilukada, pemilu legislatif, maupun pemilu presiden dan wakil presiden merupakan batu uji bagi kedigdayaan keyakinan paradigmatik Mahkamah Konstitusi. F. KESIMPULAN Sejatinya, perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang (keadilan substantif), merupakan isu klasik. Sebab pada kenyataannya, kini, sudah tidak ada lagi garis antara tradisi civil law yang menjadikan hakim hanya sebagai corong undang-undang dan tradisi common law yang menjadi hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus melanggar undang-undang. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi.
Berdasar UUD 1945 hasil amandemen, di Indonesia kedua hal itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jadi, tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Saat konstitusi diamandemen, prinsip itu ditekankan dalam UUD 1945 karena di masa lalu, upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam undang-undang. Padahal saat itu, banyak undang-undang yang berwatak konservatif, elitis, dan positivistik-instrumentalistik. Atas pertimbangan tersebut, pilihan paradigmatik untuk lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan proseduralformal merupakan pilihan yang paling logis dan tepat untuk era dewasa ini.`
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20018)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)







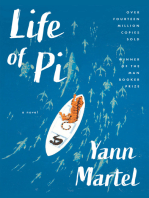
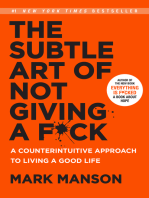





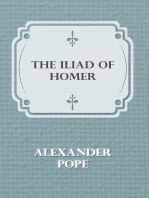





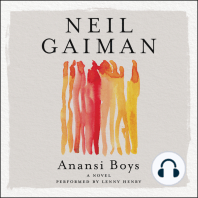

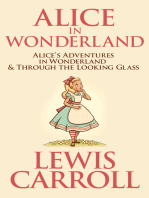



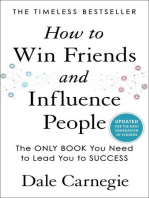
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)