Module 1 2011
Diunggah oleh
Aruan DosmauliJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Module 1 2011
Diunggah oleh
Aruan DosmauliHak Cipta:
Format Tersedia
SOSIOLOGI PERTANIAN:
Koentjaraningrat
Masyarakat Pedesaan Indonesia
Lab. Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Email : dl@ub.ac.id Tujuan Pembelajaran 1. Pendahuluan 2. Becocok Tanam di Ladang 3. Bercocok Tanam Menetap di Jawa, Madura dan Bali 4. Fragmentasi Sawah di Jawa, Madura dan Bali 5. Involusi Pertanian (Konsep Geertz ) 6. Mobilitas Komunitas Desa 7. Komunitas Desa dan Dunia di Luar Desa Pertanyaan Diskusi
MODUL
Tujuan Pembelajaran
1 2 3
4 5
Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa akan mampu : Menjelaskan pengertian komunitas desa dengan lengkap dan jelas. Menjelaskan penggolongan komunitas desa menurut teknologi usahatani. Menyebutkan dan menjelaskan unsur2/komponen2 komunitas desa dan kaitannya satu sama lain (hubungan fungsional, disfungsional antar unsur ) dengan benar Menjelaskan perbedaan antara komunitas desa berbasis lahan sawah dan lahan kering. Menyebutkan dan menjelaskan bahwa komunitas desa juga dipengaruhi oleh dunia luar(faktor ekternal) dengan baik.
1
SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT (SPEED)
PENDAHULUAN Menurut statistik sensus pertanian 1963, di Indonesia terdapat lebih dari 41.000 komunitas desa, di antaranya lebih dari 21.000 terdapat
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
di Jawa.1 Ke-41.000 komunitas desa itu didiami oleh lebih dari 80 juta penduduk, yaitu lebih-kurang 80 persen dari seluruh penduduk pada waktu itu, yang berarti bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian (termasuk peternakan dan perikanan). Walaupun demikian dalam angka statistik ada kecondongan menurun, yang menunjukkan bahwa dalam waktu sepuluh tahun penduduk Indonesia yang aktif secara ekonomis (artinya, tak terhitung yang menganggur dan setengah menganggur) dalam sektor pertanian turun dari 71,9 persen dalam tahun 1961 menjadi 63,2 persen dalam tahun 1971 (King 1973 : Tabel 1). Ke-41.000 komunitas desa tersebut dapat kita bagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan teknologi usaha taninya, menjadi dua golongan: (1) desa-desa yang berdasarkan cocok-tanam di ladang, dan (2) desa-desa yang berdasarkan cocok-tanam di sawah. Desa-desa golongan pertama terletak di sebagian besar Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian dan Timor, dengan perkecualian beberapa daerah di Sumatera Utara dan Barat, daerah pantai Kalimantan, daerah Sulawesi Selatan serta Minahasa, dan beberapa daerah terbatas yang terpencar di Nusa Tenggara dan Maluku. Desa-desa yang termasuk golongan kedua terutama terletak di Jawa, Madura, Bali dan Lombok, dan merupakan tempat bermukim dan hampir 65 persen dari seluruh penduduk Indonesia (lebih dari 85 juta menurut Sensus 1971); sedangkan areal tempat desa-desa itu hanya meliputi 7 persen dari seluruh wilayah negara kita ini. BERCOCOK TANAM DI LADANG Teknologi bercocok tanam di ladang menyebabkan suatu komunitas desa berpindahpindah yang sangat berbeda dengan komunitas desa menetap yang didasarkan pada teknologi bercocok tanam di sawah. Teknologi bercocok tanam di ladang memerlukan tanah yang luas di suatu daerah yang masih merupakan hutan rimba yang sedapat mungkin masih perawan. Para petani mulai membuka suatu ladang dengan membersihkan belukar bawah di suatu bagian tertentu dari hutan, kemudian menebang pohon-pohon besar. Batang-batang, cabang-cabang, dahan-dahan serta daun-daun dibakar, dan dengan demikian terbukalah suatu ladang yang kemudian ditanami dengan bermacam tanaman tanpa pengolahan tanah yang berarti, yaitu tanpa dicangkul, diberi air atau pupuk secara khusus. Abu yang berasal dan pembakaran pohon cukup untuk memberi kesuburan pada tanaman. Air pun hanya yang berasal dari hujan saja, tanpa suatu sistem irigasi yang mengaturnya. Metode penanaman biji tanaman juga sangatlan sederhana, yaitu hanya dengan menggunakan tongkat tugal berupa tongkat yang berujung runcing yang diberati dengan batu, dekat pada ujungnya yang runcing itu. Dengan tongkat itulah para petani pria menusuk lubang ke dalam tanah, di mana biji-biji tanaman dimasukkan, pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Pekerjaan selanjutnya ialah membersihkan ladang dari tanaman liar, dan menjaganya terhadap serangan babi hutan, tikus dan hama lainnya. Teknik bercocok-tanam seperti itu menyebabkan adanya sebutan slash and burn agriculture, atau "bercocok-tanam menebang dan membakar", yang seringkali diberikan oleh para ahli kepadanya; sedangkan sebutan yang lain adalah shifting cultivation, atau "pertanian
1
Angka-angka itu saya kutip dari karangan A.T. Birowo (1973 : Tabel I). Dalam sebuah karangan L. Adam dari tahun 1924, tercantum keterangan bahwa di Jawa dan Madura pada waktu itu ada 23.024 buah desa, walaupun pengarang itu juga mencantumkan dua buah angka statistik desa lain, yaitu 22.000 dan 21.800 untuk tahun 1923 (Adam 1924 him. 10). Page 2 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
berpindah-pindah", yang menggambarkan keadaan bahwa setiap kali setelah suatu ladang terpakai sebanyak dua atau tiga kali panen, tanah yang tak digarap dulu serta tak disuburkan dengan pupuk dan air secara teratur itu, lama-lama akan kehabisan zat hara dan tidak akan menghasilkan lagi. Akibatnya ialah bahwa para petaninya harus meninggalkannya dan membuka ladang baru dengan teknik yang sama, yaitu menebang dan membakar bagian yang baru dari hutan. Petani ladang meninggalkan ladangnya setiap dua-tiga kali panen, dan dalam waktu sepuluh tahun sudah berpindah tempat sebanyak lima-enam kali. Dalam waktu itu ladang yang pertama sudah kembali menjadi hutan, yang kemudian ditempati lagi. Walaupun demikian kita dapat membayangkan bahwa rangkaian ladang baru yang dibuka oleh para petani ladang itu makin jauh letaknya dari komunitas desa pemukimannya. Oleh karena itu para petani seringkali mendirikan gubuk-gubuk sementara dekat ladang yang mereka kerjakan, di mana mereka dapat tinggal selama musim sibuk dalam lingkaran usaha tani mereka. Hanya dalam musim-musim tatkala kesibukan bercocok-tanam mengendur mereka pulang ke desa induk mereka untuk melakukan pesta-pesta dan upacara bersama warga komunitas yang lain. Tidak jarang terjadi bahwa sekelompok gubuk tempat mereka itu tinggal sementara pada waktu-waktu sibuk, menjadi suatu pusat pemukiman baru, dengan suatu identitas tersendiri, sehingga dapat memisahkan diri dari desa induknya dan membentuk suatu desa yang baru. Mudah dapat dimengerti bahwa suatu cara bercocok-tanam seperti terurai di atas memerlukan tanah yang luas. Karena itu cara itu hanya dapat dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduknya masih rendah, seperti misalnya di Sumatera yang dalam tahun 1971 padatnya rata-rata sekitar 38 orang tiap kilometer persegi, di Kalimantan dengan ratarata 9 orang tiap kilometer persegi, atau di Sulawesi dengan rata-rata 37 orang tiap kilometer persegi. Di Jawa atau Bali, di mana padat penduduknya dalam tahun itu juga secara respektif adalah 565 dan 377 tiap kilometer persegi, tidak mungkin dilaksanakan cocok-tanam di ladang. Cara bercocok-tanam di daerah-daerah ini sebagian besar memang dilakukan dengan irigasi di tanah basah, atau sawah. BERCOCOK TANAM MENETAP DI JAWA, MADURA DAN BALI Tipe-tipe Penggunaan Tanah Seorang petani di Jawa, Madura atau di Bali, dalam kenyataan menggarap tiga macam tanah pertanian, yaitu: (1) kebun kecil di sekitar rumahnya; (2) tanah pertanian kering yang digarap dengan menetap, tetapi tanpa irigasi, dan (3) tanah pertanian basah yang diirigasi. Di tanah kebun kecil sekitar rumah, yang di Jawa Tengah dan Timur, dan juga di Bali, disebut pekarangan, seorang petani menanam kelapa, buah-buahan, sayur-mayur, bumbubumbu dan lain-lain, yang diperlukannya dalam kehidupan rumah-tangganya sehari-hari. Di antara pohon buah-buahan terdapat jenis-jenis pohon tinggi yang berumur panjang, seperti bermacam jenis pohon nangka dan sukun; jenis-jenis pohon setengah tinggi seperti berbagai jenis pohon jambu, lamtoro dan lain-lain; jenis-jenis pohon yang berumur pendek seperti pepaya dan pisang; dan jenis-jenis yang tumbuh dekat di tanah, atau yang berupa belukar, seperti nenas, salak, atau jeruk. Di antara tanaman bumbu-bumbu banyak yang berupa belukar, tetapi ada pula yang dipergunakan untuk meramu obat-obatan tradisional. Pekarangan tentu juga mengandung tanaman yang berupa umbi-umbian dan akar-akaran seperti berbagai jenis ubi dan singkong. Tak dapat dilupakan, bahwa di pekarangan sering ada pula kolam ikan yang selain untuk tempat pemeliharaan berbagai jenis ikan, tidak jarang pula dipakai sebagai tempat buang air. Hasil pekarangan sebagian besar dipergunakan untuk
Page 3 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
konsumsi sendiri, walaupun tidak sedikit pula yang dijual di pasar desa atau kepada para tengkulak kelapa dan buah-buahan. 2 Di tanah pertanian kering, yang di Jawa biasanya disebut tegalan, petani-petani menanam serangkaian tanaman yang kebanyakan dijual di pasar atau kepada tengkulak. Tanaman itu adalah antara lain jagung, kacang kedele, berbagai jenis kacang, tembakau, singkong, umbi-umbian, tetapi juga padi yang dapat tumbuh tanpa irigasi. Walaupun tidak diirigasi, tanah tegalan biasanya digarap secara intensif, dan tanaman-tanamannya dipupuk dan disiram dengan teratur. Tanah yang menjadi tegalan adalah tanah yang kurang cocok untuk dijadikan tanah basah, karena kemampuannya yang rendah untuk mengandung air, atau tanah yang letaknya di lereng-lereng gunung yang terjal sehingga memerlukan investasi tenaga untuk membangun sistem irigasi yang terlampau tinggi. Proporsi tanah pertanian di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berupa tegalan (lihat Tabel III-l) adalah cukup tinggi, yaitu hampir 40 persen, yang berarti sama dengan proporsi tanah pertanian yang berupa tanah basah. Bercocok tanam di tanah basah atau sawah itu, seperti tersebut di atas memang merupakan usaha tani yang paling pokok dan paling penting bagi para petani di Jawa dan Bali sejak beberapa abad lamanya. Dengan teknik penggarapan tanah yang intensif dan dengan cara-cara pemupukan dan irigasi yang tradisional, para petani tersebut menanam tanaman tunggal, yaitu padi. Berbeda dengan cocok tanam di ladang, maka cocok-tanam di sawah dapat dilakukan di suatu bidang tanah yang terbatas secara terus-menerus, tanpa menghabiskan zat-zat hara yang terkandung di dalamnya.
Tabel 1: Proporsi Berbagai Tipe Penggunaan Lahan di Jawa
Propinsi Proporsi tanah pertanian terhadap seluruh tanah Ladan g Proporsi Berbagai Tipe Tanah (%) Pekaran Tegalan gan Pemakaian Sawah Lain
Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur
52,8 61,4 44,8
3,0 8,8 1,7
11,4 3,6 10,7
39,8 59,6 42,8
43,1 28,4 42,4
2,7 2,6 2,4
SUMBER: Sensus Pertanian, EPS, 1963.
Tahap-tahap Produksi Bercocok-Tanam di Sawah Bercocok-tanam di sawah sangat tergantung kepada pengaturan air, yang dilakukan dengan suatu sistem irigasi yang kompleks. Agar sawah dapat digenangi air, maka
2
Suatu studi yang luas mengenai pertanian pekarangan ini pernah dilakukan oleh ahli-ahli pertanian Belanda E. de Vries (1927) dan GJ.A. Terra (1932; 1932-a). Page 4 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
permukaannya harus mendatar sama sekali, dan dikelilingi oleh suatu pematang yang tingginya 20 sampai 25 sentimeter. Itulah sebabnya membuat sawah di lereng gunung me merlukan pembentukan susunan bertangga yang, seperti telah dikata-kan di atas, memerlukan investasi tenaga kerja yang tinggi. Namun, di daerah dataran rendah pun bercocok-tanam di sawah memerlukan banyak tenaga kerja di semua tahap produksinya. Rangkaian tahap-tahap produksi dalam hal bercocok-tanam di sawah itu dimulai pada akhir musim kering, yang menurut teori jatuh pada bulan Oktober atau November. Dalam kenyataan, banyak petani di Jawa menentukan sendiri saat mereka memulai rangkaian tahaptahap produksi tersebut, yang biasanya banyak dipengaruhi oleh cara-cara perhitungan tradisional seperti yang terdapat dalam buku-buku ilmu dukun yang disebut primbon. Tiap lingkaran tahap-tahap pekerjaan bercocok-tanam itu biasanya dimulai dengan memperbaiki bagian-bagian dari sistem irigasi, misalnya pematang, saluran dan pipa-pipa bambu, dan kadang-kadang juga bendungan yang merupakan sumber dari sistem irigasi bagi sekelompok sawah sekitar desa. Pekerjaan ini adalah khusus pekerjaan laki-laki. Langkah selanjutnya adalah membuka saluran-saluran air sehingga air dapat mengalir dari bagian sungai yang dibendung ke sawah-sawah hingga merata. Pembagian air ke sawah di desa-desa di daerah pegunungan di Jawa biasanya mudah, karena air dengan mudah dapat mengalir dari sawah-sawah yang letaknya tinggi ke sawah-sawah yang letaknya rendah. Sebaliknya, di desa-desa yang letaknya rendah, pengaliran dan distribusi air ke sawah-sawah yang jauh letaknya adalah lebih sukar. Agar supaya pembagian air ke sawah-sawah itu dapat berlangsung lancar dan adil, maka desa-desa di tanah yang rendah itu seringkali mempunyai seorang anggota pamong desa yang tugasnya khusus mengurus soal irigasi ini. Anggota pamong desa ini antara lain disebut ulu-ulu. Di Bali soal-soal irigasi pembagian air, pertengkaran mengenai distribusi air irigasi dan sebagainya, diurus oleh suatu organisasi yang bemama subak. Organisasi ini tidak terikat sebagai bagian dari organisasi dari suatu perkampungan di Bali, yang disebut banjar, tetapi selalu terikat kepada suatu kompleks atau sistem bendungan tertentu. Bendunganbendungan ini memberi air melalui suatu sistem saluran dan pipa-pipa yang luas kepada sejumlah sawah yang tertentu juga, sedangkan pemilik sawah-sawah tadi mungkin saja terdiri dari warga-warga berbagai banjar yang berlainan. Sebaliknya, tidak jarang pula terjadi bahwa ada warga dalam suatu banjar itu menjadi anggota dari beberapa subak yang berbeda-beda karena memiliki berbagai sawah yang tergantung kepada sistem bendungan sumber air yang berbeda-beda. Solidaritas para anggota subak tidak ditentukan oleh solidaritas kewargaan banjar, melainkan oleh suatu sistem pura (yaitu tempat-tempat pemujaan serta aktivitas upacara, seperti odalan dan sebagainya) dalam rangka sistem pura itu. Sebagai contoh kita bisa melihat hubungan yang khas itu antara beberapa subak dengan banjar-banjar yang terletak di daerah Tihingan di Suapraja Klungkung (Bali Selatan). Sawah digenangi air selama beberapa waktu, yaitu antara satu hingga dua minggu. Sementara itu sisa-sisa tanaman padi sebelumnya dan tumbuh-tumbuhan lain di sawah dibersihkan. Setelah itu tanah dicangkul atau dibajak (di banyak daerah di Jawa membajak disebut meluku) yang kadang-kadang dikerjakan oleh orang, tetapi kadang-kadang pula oleh kerbau atau sapi. Sawah-sawah yang tanahnya diolah dengan bajak, seringkali mempunyai bagian-bagian yang tak terjangkau oleh bajak sehingga masih harus diolah dengan cangkul juga. Sementara itu sudah disiapkan juga tempat-tempat untuk menyebarkan benih. Pesemaian-pesemaian itu berupa bidang-bidang kecil pada bagian-bagian sawah yang mudah diberi air, yang sebelumnya telah diolah dengan cangkul dan diratakan. Untuk kedua kalinya sawah diolah dengan bajak dan cangkul, serta dibiarkan lagi terendam air selama beberapa hari. Pematang-pematang pun sudah diperbaiki. Biasanya bajak yang dipergunakan untuk mengolah tanah adalah milik bersama dari sekelompok
Page 5 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
petani. Demikian juga binatang yang menghela bajak itu. Bajak dan kerbau atau sapi itu dipakai secara bergantian oleh para petani yang memilikinya. Bajak yang tidak ditarik oleh binatang, biasanya menggunakan tenaga manusia yang disewa. Cangkul merupakan alat yang biasanya dimiliki oleh setiap petani atau buruh tani. Tanah yang sudah diolah untuk kedua kalinya, dan digenangi air selama satu hingga dua minggu itu, kemudian diratakan dengan garu, yang ditarik oleh kerbau atau sapi, tetapi seringkali juga oleh manusia. Setelah pekerjaan ini selesai, maka sawah siap untuk ditanami dengan tunas-tunas padi yang sementara itu sudah tumbuh di pesemaian. Pekerjaan menanam dilakukan oleh tenaga wanita. Tata urut pekerjaan itu adalah sebagai berikut: mula-mula tunas-tunas muda itu dicabut dengan hati-hati dari pesemaian, lalu diikat menjadi beberapa ikatan yang dibagi-bagikan secara merata di tiap petak sawah. Lalu mulailah tunas-tunas itu ditanam satu demi satu dengan tangan, menjadi deretanderetan yang panjang dan teratur. Selama tumbuh, para petani harus memelihara dan menjaga tanaman mereka dari berbagai tumbuh-tumbuhan liar (matun) yang dilakukan oleh wanita, dan apabila padi sudah mulai berbuah, serangan-serangan biasanya datang dari burung, tikus, serangga dan sebagainya. Untuk pekerjaan ini para petani seringkali harus mengerahkan tenaga tambahan. Berapa lamanya padi berbuah dan masak, tergantung pada jenis padi dan berbagai faktor lain. Ada jenis padi yang sudah dapat dipotong setelah berusia empat bulan, tetapi ada pula jenis-jenis lain yang baru dapat dipanen setelah enam bulan atau lebih. Panen selalu dikerjakan oleh wanita, dengan menggunakan pisau kecil yang disebut ani-ani, untuk memotong tangkai-tangkai padi itu satu demi satu. Oleh karena itu cara panen semacam itu sangat banyak membutuhkan tenaga tambahan, yang diperoleh dengan menyewanya dengan upah berupa bagian dari padi yang dipotong. Sebelum panen, sering diadakan upacara slametan yang dipimpin oleh seorang dukun. Tiga atau empat bulan setelah panen, sementara menunggu penanaman padi yang berikutnya, para petani menanam bermacam tanaman lain, seperti ubi-ubian, singkong, berbagai kacang, kedele, jagung, juga padi gaga (yaitu padi kering), sayur-mayur, tembakau, kadang-kadang juga tebu, dan bumbu-bumbu, yang jumlahnya ada lebih dari 20 macam. Tanaman sekunder ini oleh orang Jawa disebut palawija. Penanaman palawija dalam sistem bercocok-tanam di sawah adalah suatu perkembangan yang baru berlangsung kira-kira satu abad lamanya di Jawa. Singkong atau jagung sejak lama memang menjadi tanaman utama di daerah-daerah di Jawa dan Madura yang tidak dapat ditumbuhi padi dengan baik, 3 tetapi berbagai jenis tanaman lain yang termasuk golongan palawija itu sekarang secara berangsur-angsur rupa-rupanya telah diterima juga oleh rakyat desa, dan sudah mulai diintegrasikan ke dalam sistem bercocoktanam di sawah-sawah. Pengerahan Tenaga Pada Cocok-Tanam di Sawah Salah satu cara untuk mengerahkan tenaga tambahan untuk pekerjaan bercocoktanam secara tradisional dalam komunitas pedesaan adalah sistem bantu-membantu yang di Indonesia kita kenal dengan istilah "gotong-royong". Sistem pengerahan tenaga seperti itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga di tempat-tempat lain di dunia, di mana produksi bercocok-tanam secara tradisional masih dominan, yaitu di komunitas-komunitas pedesaan suku-suku-bangsa penduduk Afrika, Asia, dan Oseania, dan penduduk pribumi di Amerika
Dalam bukunya The History of Java (1830: 1, him. 134) misalnya, Raffles menyatakan bahwa sudah dalam tahun 1817 "in the more populous parts of Java ... Where the sawahs do not afford sufficient supply of rice," jagung menjadi tanaman utama. Singkong katanya tersebar di Jawa baru setelah kira-kira tahun 1850. Mengenai hal ini lihatlah karangan A.J. Koens, dalam buku De Landbouw in den Indischen Archipel redaksi C.J.J. Hall dan C. van de Kop-pel (1946: HA, him. 163-240). Page 6 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
Latin. Sistem gotong-royong sampai masa kini bahkan masih terdapat juga di beberapa tempat di Eropa. Di Indonesia, dan khususnya di Jawa, aktivitas gotong-royong biasanya tidak hanya menyangkut lapangan bercocok-tanam saja, tetapi juga menyangkut lapangan kehidupan sosial lainnya seperti: 1. Dalam hal kematian, sakit, atau kecelakaan, di mana keluarga yang sedang menderita itu mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangganya dan orang-orang lain sedesa. 2. Dalam hal pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya memperbaiki atap rumah, mengganti dinding rumah, membersihkan rumah dari hama tikus, menggali sumur, dan sebagainya, untuk mana pemilik rumah dapat minta bantuan tetangga-tetangganya yang dekat, dengan memberi jamuan makan. 3. Dalam hal pesta-pesta, misalnya pada waktu mengawinkan anaknya, bantuan tidak hanya dapat diminta dari kaum kerabatnya, tetapi juga dari tetangga-tetangganya, untuk persiapan dan penyelenggaraan pestanya. 4. Dalam mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum dalam masyarakat desa, seperti memperbaiki jalan, jembatan, bendungan irigasi, bangunan umum dan sebagainya, untuk mana penduduk desa dapat tergerak untuk bekerja bakti atas perintah dari kepala desa. Dalam pertanian di Jawa, sistem gotong-royong biasanya hanya dilakukan untuk pekerjaan yang meliputi perbaikan pematang dan saluran air, mencangkul dan membajak, menanam dan membersihkan sawah dari tumbuh-tumbuhan liar (matun). Untuk pekerjaan memotong padi dipergunakan tenaga buruh tani wanita dan anak-anak yang diberi upah. Di banyak daerah pedesaan di Jawa sistem gotong-royong dalam lapangan bercocok-tanam juga berkurang, dan diganti dengan sistem memburuh. Upah untuk membayar tenaga buruh da pat berupa (i) upah secara adat, dan (ii) upah berupa uang. Upah secara adat dibayar dengan sebagian dari hasil pertanian, dan jumlahnya tergantung keadaan. Di daerah-daerah di mana penawaran tenaga buruh besar, maka upahnya tentu menjadi lebih kecil. Di Jawa, misalnya, sistem upah buruh tani dilakukan untuk memotong padi, yaitu yang disebut sistem bawon. Dalam keadaan biasa, wanita-wanita buruh itu sudah harus puas dengan hanya 1/25 dari hasil yang dipetiknya. Sistem-sistem pembayaran buruh tani secara adat ini bisa mempunyai akibat yang baik, karena para buruh tani dengan demikian berusaha untuk bekerja segiat-giatnya, agar dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya, sehingga upahnya pun dapat bertambah banyak. Upah berupa uang adalah suatu cara membayar buruh tani yang sudah lazim juga di seluruh Indonesia. Walaupun cara ini merupakan suatu sistem yang relatif baru di Indonesia, di Jawa sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-19 yang lalu. Para petani sering memiliki bantuan tenaga buruh yang tetap, yang memberi bantuan dalam pertanian pada waktu-waktu sibuk, dan yang juga membantu dalam rumah tangga pada waktu-waktu senggang. Pembantu-pembantu serupa itu biasanya menumpang (mondok) di rumah keluarga tani bersangkutan, ikut makan, mendapat pakaian, dan biasanya juga mendapat sekedar upah berupa uang. Buruh tani yang paling lazim adalah buruh tani yang memburuhkan tenaganya untuk pekerjaan tertentu, tetapi tidak pada satu keluarga tani saja. Buruh semacam ini dapat disewa secara borongan, dapat juga secara harian. Tarif upah buruh tani di Indonesia tentu
Page 7 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
berbeda-beda menurut daerahnya, yang tentu erat pula kaitannya dengan besar-kecilnya penawaran tenaga buruh. Masa kini, terutama dalam produksi bercocok-tanam terjadi proses pergeseran dari cara pengarahan tenaga bantuan di luar rumah-tangga dengan gotong-royong ke cara dengan menyewa buruh. Proses pergeseran itu dalam bercocok-tanam di Jawa menurut para ahli pertanian Belanda sudah dimulai dalam tahun 30-an (Kolff, 1937) dan penelitian saya sendiri terhadap masalah pengerahan tenaga kerja dalam komunitas desa di daerah Bagelen di Jawa Tengah bagian Selatan, juga mengobservasi proses yang sedang terjadi di sana dalam tahun 50-an (Koentjaraningrat 1961: 1977). Tabel III-2 menunjukkan jumlah rata-rata jam kerja bagi tiap individu petani aktif dalam satu panen pada satu hektar sawah di daerah Bagelen dalam tahun 1958. Dalam tabel itu juga tercantum jumlah rata-rata jam kerja bagi tiap individu, yang didasarkan atas sistem gotong-royong maupun yang didasarkan kerja buruh. Tabel 2 Jumlah Rata-rata Jam Kerja Bagi Tiap Individu Pada Satu Hektar Sawah di Daerah Begelen (1958) Aktivitas Produksi Mempersiapkan sawah System irigasi Mempersiapkan tempat persemian Menanam biji Membajak mencangkul sawah (dua kali) Menggaru sawah (dua kali) Mempersiapkan benih Menanam benih Matun Menuai Total Sumber : Penelitian Lapangan Koentjaraningrat
Data dikumpulkan dengan cara mengobservasi 10 kasus. * Datadikumpulkan dari mulut informan yang memiliki 36 kesatuan tanah untuk usaha-tani, seluruhnya seluas 21 hektar lebih.
Tenaga gotong royong Pria Wanita Anak 70 25 2 40 51 188 43 205 59 300 607 12 12 -
Tenag Tenaga a hewan buruh 42 42 81 44 92 54 162 350 125
Akhir-akhir ini malahan timbul keadaan yang lebih gawat lagi. Di banyak tempat di Jawa adat para petani pemilik tanah untuk membagi hasil panen mereka dengan buruh tani mulai mencapai batas kemampuannya. Memang, kalau kita bepergian dengan kereta api di Pulau Jawa dalam bulan-bulan April atau Mei, yaitu pada waktu musim panen, kita sering dapat melihat padi yang sudah menguning yang sedang dipotong oleh berpuluh-puluh manusia beraneka-warna. Pandangan yang lebih mengkhusus pada sebidang sawah tertentu dengan taksiran terhadap jumlah manusia yang sedang sibuk memotong padi di sana, menemukan bahwa di suatu bidang sawah yang luasnya kira-kira seperlima hektar itu bekerja tidak kurang dari 40 orang! Empatpuluh hingga limapuluh tahun yang lampau jumlah pemotong padi yang beramai-ramai datang untuk membantu menuai padi tidak pernah lebih dari 15 orang. Mereka membantu dengan semangat gotong-royong, dan menurut adat boleh membawa pulang sebagian dari jumlah padi yang mereka potong. Kerabat-kerabat dan para teman
Page 8 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
dekat yang turut membantu seringkali menerima seperenam sampai seperlima bagian; tetangga atau kenalan jauh menerima seperdelapan sampai sepersepuluh bagian; dan wanita-wanita yang pekerjaannya memang buruh pemotong padi dan yang setiap musim panen berkeliling dari desa yang satu ke desa lain untuk memotong padi, menerima sekitar sepersepuluh bagian dari hasil yang mereka potong. Bagian yang diperoleh para kerabat, tetangga, dan buruh pemotong tadi disebut dengan istilah adat Jawa, bawon. Pada zaman sekarang, di mana jumlah kerabat, tetangga, kenalan dan buruh yang datang membantu memotong padi itu sudah sekitar 40 orang, tentu sangat berat bagi petani pemilik sawah itu untuk mempertahankan adat berdasarkan sistem gotong-royong bawon itu. Oleh karena itu buruh wanita pemotong padi sekarang tidak menerima lebih dari seperduapuluh bagian dari padi yang berhasil mereka potong. Walaupun demikian, jumlah buruh tani seperti itu tetap saja bertambah banyak jumlahnya di masyarakat pedesaan di Jawa. Secara sangat radikal, sejak kira-kira sepuluh tahun yang lalu, di banyak tempat di Jawa telah timbul sistem pengerahan tenaga panen yang baru, yang dengan cepat telah mulai menghapuskan adat panen berdasarkan gotong-royong yang disebut adat bawon terurai di atas. Menurut sistem baru yang disebut sistem tebasan itu, seorang petani pemilik usaha tani menjual sebagian besar padinya yang sudah menguning kepada seorang pedagang dari luar desa yang akan mengusahakan pemotongan padinya. Pedagang yang juga disebut penebas ini akan datang pada waktunya dengan buruh pemotong padinya sendiri yang juga berasal dari desa lain, yang jumlahnya tidak lebih dari empat-lima orang. Mereka membabat padi di sawah dengan sangat efisien4 dengan menggunakari arit atau sabit.5 Contoh lain dari proses tergesernya adat gotong-royong oleh sistem baru dengan menyewa buruh tani wanita adalah adat menumbuk padi secara tradisional. Kira-kira sepuluh tahun yang lalu seorang petani akan meminta pertolongan para isteri tetangga atau kenalankenalannya untuk menumbuk padinya. Mereka itu akan menerima sebagian dari padi yang mereka tumbuk sebagai kompensasi atas bantuan mereka. Juga sejak kira-kira sepuluh tahun yang lalu masyarakat desa di Indonesia mulai mengenal mesin huller, yaitu mesin kecil penggiling padi yang dapat dibeli oleh petani-petani yang kaya. Para petani ini tidak hanya memakai mesin seperti itu untuk keperluan mereka sendiri, tetapi sering juga menyewakannya kepada petani-petani lain. Dengan menggunakan mesin huller itu padi dapat digiling secara efisien, tetapi sebaliknya para isteri tetangga dan buruh tani wanita yang biasanya diminta atau dipanggil untuk membantu menggiling padi itu dengan adanya mesin itu kehilangan suatu mata pencaharian tambahan. 6 Proses pergeseran dari cara pengerahan tenaga tani dan sistem gotong-royong menjadi sistem menyewa buruh tani, antara lain terdorong oleh murahnya tenaga buruh tani, terutama di Jawa. Dalam contoh terakhir, adat pengerahan tenaga pembantu dalam produksi pangan tergeser oleh teknologi baru, namun pada umumnya proses penggeseran cara pengerahan tenaga tani dan gotong-royong menjadi menyewa buruh tani itu, antara lain disebabkan karena tenaga buruh tani itu menjadi sangat murah. Oleh karena itu jauh lebih mudah dan
4
Deskripsi mengenai sistem tebasan terdapat dalam karangan Collier, Gunawan Wiradi dan Soentoro (1973) dan karangan Collier, Soentoro, Gunawan Wiradi dan Makali (1974). Sebenarnya sistem tebasan bukan suatu sistem memo-tong padi yang baru. Dalam tahun 1911 telah ada suatu deskripsi mengenai sistem itu dalam buku berkala Adatrechtbundeh (1911: II, him. 128-130, 248). 5 Menurut cara adat, seorang petani Jawa sebenarnya harus memakai ani-ani, yaitu pisau kecil yang hanya dapat memotong padi setangkai demi setangkai.
6
Seorang ahli antropologi, dosen Universitas Gadjah Mada, peman meneliti dan menulis tentang masalah pengaruh mesin penggiling padi terhadap kehidupan sosial ekonomi para wanita buruh penumbuk padi tadi (Kasniyah 1978: him. 161-172). Page 9 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
murah untuk menyewa tenaga bantuan daripada melaksanakan adat lama yang penuh tatacara sopan-santun, dan yang akhirnya toh tidak tanpa biaya itu. Biaya yang diperlukan pada adat pengerahan tenaga tani secara tradisional biasanya adalah untuk menjamu para tetangga yang datang untuk membantu itu Biaya itu kadang-kadang sangat tinggi, karena tidak jarang ada unsur "gengsi" dalam menjamu tetangga itu. Adapun sangat murahnya biaya menyewa buruh tani itu disebabkan karena makin bertambahnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah, atau petani yang hanya memiliki tanah yang sangat kecil sehingga tidak cukup menghasilkan untuk memberi makan satu keluarga Jawa sepanjang musim. Mereka ini memerlukan suatu mata pencaharian yang hanya bisa berupa memburuhkan tenaga. Semua hal terurai di atas itu mempunyai sebab yang lebih dasar yaitu bertambahnya penduduk Indonesia dengan sangat cepat tiap tahun (lihat Bab II). Fragmentasi Sawah di Jawa, Madura dan Bali Laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat itu, terutama di Jawa memang merupakan sebab utama dari proses makin kecilnya usaha tani secara rata-rata. Menurut sensus pertanian 1963, tanah milik petani di Jawa dan Madura adalah rata-rata 0,7 hektar. Tanah pertanian berupa sawah atau tegalan yang sudah demikian kecilnya itu pada umumnya kemudian dipecah-pecah lebih lanjut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Fragmentasi yang sifatnya ekstrim seperti itu terjadi karena petani pemiliknya membagi-bagi tanahnya untuk digarap oleh sejumlah petani lain dengan berbagai macam cara. Di antaranya ada cara yang paling tradisional, yaitu ketiga adat bagi-hasil: maro, mertelu dan merpat. Pada adat maro, petani yang menggarap tanah akan menerima separuh dari hasilnya, dan pajak tanah ditanggung oleh pemiliknya, sedangkan biaya produksi oleh si penggarap. Pada adat mertelu, perjanjian pembagian hasil adalah duapertiga bagi si pemilik tanah dan sepertiga bagi penggarap, dan mengenai biaya-biayanya perjanjiannya adalah sama seperti pada adat maro. Pada adat merpat, pemilik tanah memperoleh tigaperempat bagian tetapi harus membayar pajak tanah dan menanggung sebagian dari biaya produksi, dan penggarap hanya menerima seperempat bagian dari hasil, dan membayar sisa dari biaya produksi. Yang termasuk biaya produksi adalah pembelian bibit dan pupuk. Penggarap juga menanggung biaya untuk membayar tenaga buruh dan untuk menyewa alat-alat pertanian seperti bajak dan alat penggaru serta hewan untuk menariknya. Dengan meningkatnya jumlah petani yang tidak memiliki tanah, merpat sekarang menjadi adat bagi-hasil yang paling lazim di Jawa, sedangkan adat maro sekarang hanya dilaksanakan antara para petani yang masih ada hubungan kerabat dekat, misalnya antara ayah dan anak-anaknya atau antara saudara-saudara sekandung. Fragmentasi sekarang juga terjadi karena di samping membagi hasil bagian-bagian dari tanahnya kepada sejumlah petani lain, seorang petani pemilik seringkali juga menyewakan beberapa bagian dari tanahnya, sehingga dengan demikian ia tidak hanya menerima pendapatan berupa hasil bumi tetapi juga berupa uang tunai. Pada masa kini banyak petani pemilik tanah juga sering menggadaikan bagian-bagian tertentu dari tanahnya selama satu atau dua kali panen. Orang yang menggarap tanahnya itu meminjamkan uang tunai sebagai gantinya, dan hasilnya adalah seluruhnya bagi yang menggarap. Sesuai dengan perjanjian, setelah satu atau dua panen uang yang dipinjam oleh pemilik tanah itu dikembalikan kepada si penggarap, dengan mendapatkan kembali juga tanahnya. Hasil bumi yang diambil oleh penggarap merupakan bunga dari uang yang telah dipinjamkan kepada pemilik tanah itu. Proses fragmentasi tanah di Jawa dan Madura memang berjalan terus, dan dengan demikian maka tanah pertanian milik para petani itu menjadi semakin kecil juga. Sensus
Page 10 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
pertanian 1963 juga menunjukkan bahwa dari 7,94 juta unit tanah milik petani di Jawa dan Madura, hanyalah 1,43 juta digarap sebagai kesatuan yang utuh; 5,11 juta unit tanah milik petani terpecah untuk penggarapannya menjadi dua sampai tiga bagian; 1,07 juta terpecah ke dalam empat sampai lima bagian; 0,3 juta ke dalam enam sampai sembilan bagian; dan 0,02 juta bahkan terpecah ke dalam sepuluh bagian atau lebih (Brand 1969: hlm. 315). Perlu diperhatikan bahwa proses fragmentasi tanah pertanian garapan di Jawa, Madura dan Bali yang menjadi semakin ekstrem ini, yang disebabkan karena penambahan penduduk yang sangat cepat, dibarengi dengan proses lain yang sebenarnya bertentangan, yaitu proses konsentrasi pemilikan ke dalam tangan dari sejumlah petani kaya yang terbatas jumlahnya. Proses yang tersebut kedua antara lain merupakan akibat dari proses meningkatnya kemiskman di daerah pedesaan, walaupun ada beberapa sebab lain juga, seperti terlihat dari beberapa penelitian mengenai masalah itu, yang terutamaa dilakukan di Jawa Barat. 7 Sejumlah penelitian lain yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan bahwa proses konsentrasi milik tanah ke dalam tangan beberapa orang petani kaya juga terjadi, sedangkan di samping itu proses fragmentasi penggarapan tanah juga berlangsung terus. 8 Dengan demikian memang cukup banyak data konkret mengenai proses melebarnya jurang antara petani kaya dan petani miskin, dan lebih banyak pula penelitian mendetail mengeni kemiskinan di antara penduduk pedesaan di Jawa, misalnya penelitian D.H. Penny dan M. Singarimbun mengenai masalah tekanan penduduk dan kemiskinan di desa Sriharjo dekat Yogya (Penny, Singarimbun 1973), atau oleh A. Harts-Broekhuis dan H. Palte-Grooszen (1977) di desa Jambidan, juga dekat Yogya. Hal itu perlu supaya kita memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai bagaimana petani miskin di Jawa berhasil menyesuaikan diri dengan keadaannya agar dapat hidup langsung. Involusi Pertanian (Konsep Geertz ) Ahli antropologi terkenal, C. Geertz, yang pernah melakukan penelitian mengenai sejarah ekonomi pertanian di Jawa, pernah mengembangkan konsep "involusi pertanian", atau agricultural involutin, yang dipakainya untuk menggambarkan proses sejarah pertanian di Jawa sampai dasawarsa 50-an yang lalu. Uraian mengenai konsep itu termaktub dalam bukunya yang menjadi sangat terkenal, yaitu Agricultural Involution (1963). Pada halaman 80
7
Suatu penelitian yang penting sekali mengenai hal itu, yang sering dikutip ahli-ahli dan penelitipeneliti lain adalah penelitian oleh ahli pertanian Belanda H. ten Dam, di desa Cibodas, Bogor (Dam 1956). Penelitian lain adalah oleh ahli pertanian Adiwilaga di desa Cipagalo dekat Bandung (1954). Ten Dam melaporkan bahwa sudah sebelum Perang Dunia II, 44 persen dari keluarga-keluarga petani di desa Cibodas tak memiliki tanah, hanya 25 persen memiliki tanah pekarangan, sedangkan 23 persen memiliki tanah kering dari ukuran kurang dari satu hektar (Dam 1956: hlm. 91-92). Hal itu berarti bahwa semua tanah yang baik menjadi milik dari hanya 8 persen dari jumlah petani.
Lihat misalnya laporan penelitian oleh Soemardjo Hadiwignjo mengenai masalah pengangguran terselubung di daerah pedesaan dekat Yogya (1950); laporan penelitian D.C. Bennet mengenai tekanan penduduk di tiga desa di Jawa Timur dan pengaruhnya terhadap keadaan gizi dalam makanan, pengangguran dalam pertanian untuk ekspor di Klaten (1958); laporan penelitian Pandam Guritmo mengenai penelitiannya di Marangan dekat Yogyakarta (1958); karangan P. Jay mengenai penelitian antropologinya di Tamansari dekat Pare, Jawa Timur (1969: him 262-267); laporan penelitian M. Timmer mengenai tekanan penduduk di daerah pedesaan dekat Yogyakarta (1961); dan buku W. Roll mengenai masalah milik tanah di Klaten (1976) : him. 55-61). Karangan saya sendiri mengenai adat gotong-royong di dua desa di Bagelen, Jawa Tengah, juga mengandung beberapa keterangan mengenai fragmentasi tanah garapan ini (Koentjaraningrat 1961: him. 21; 1967: him. 250-151). Di antara 1145 penduduk desa Celapar di daerah pegunungan di Bagellen, hanya 259 memiliki tanah. Sebagian besar memiliki antara satu sampai dua setengah hektar tanah kering (tegalan), ditambah dengan 0,2 sampai 1,5 hektar tanah sawah. Hanya 22 orang saja memiliki tanah tegalan sekitar 2,5 hektar, dan hanya tujuh orang memiliki tanah sawah seluas 1,5" hektar. Mereka membagi-bagi tanahnya kepada tiga sampai lima petani penggarap berdasarkan sewa tanah atau bagi-hasil, dan beberapa yang memiliki 2,5 hektar malahan ada yang membagi-bagi tanahnya kepada sebanyak sepuluh orang petani. Page 11 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
dari buku itu Geertz merumuskan definisi yang berbunyi sebagai berikut: "Wet-rice cultivation, with its extraordinary ability to maintain levels of marginal productivity by always managing to work one more man in without a serious fall in percapita income, soaked up almost the whole of the additional population that Western intrusion created, at least indirectly. It is this ultimately self-defeating process that I have proposed to call agricultural involution." Definisi tersebut memang kurang jelas, tetapi dari uraiannya lebih lanjut dalam babbab berikutnya dalam buku itu, tampak bahwa Geertz membayangkan perkembangan pertanian sawah di Jawa sebagai suatu keadaan di mana para petani yang menggarap bidang-bidang tanah yang memang sudah kecil dan tak dapat dijadikan lebih besar lagi itu, toh masih terkena tekanan pertambahan penduduk secara terus-menerus. Walaupun demikian, kemiskinan di Jawa tidak bertambah secara cepat serta secara besar-besaran, karena dengan makin bertambamnya intensitas penggarapan bidang-bidang sawah yang kecil itu,maka banyak pula tenaga kerja dapat tertampung. Hal itu makin memperbesar hasil pertanian, dan hasil pertanian yang makin bertambah itu menyebabkan selalu tersedianya makan bagi penduduk yang makin banyak jumlahnya itu. Jadi walaupun tingkat kemakmuran para petani di Jawa dan Bali tidak pernah akan dapat meningkat, namun intensifikasi kerja tadi itulah yang menambah hasil panen, dan bukan karena cara kerja yang lebih keras yang dilakukan para petani itu, melainkan cara kerjasama, yang dilakukan oleh tenaga petani yang lebih banyak jumlahnya. Tambahan itu memang tidak banyak, namun dapat dinikmati secara rata. Dengan merasakan kemiskinan bersama (shared poverty) itulah penderitaan dapat dikurangi. Secara teori hal itu berarti bahwa produksi naik apabila ditinjau dari aspek tanah dan dihitung per hektar tanah, tetapi konstan atau bahkan turun bila ditinjau dari aspek tenaga dan dihitung per individu. Dengan demikian suatu kelebihan hasil produksi tidak pernah akan mungkin tertimbun, sehingga dapat terbentuk suatu surplus ekonomi yang dapat dipakai sebagai modal untuk berkembang dan membangun. Dengan itu tidak ada perkembangan yang sifatnya membesar keluar, melainkan suatu perkembangan yang sifatnya makin kompleks-mendetail-mendalam.9 Proses inilah yang oleh Geertz dicoba digambarkan dengan istilah "involusi" itu. Untuk menguraikan konsepnya, Geertz antara lain memakai proses makin terpecah-pecahnya tanah petani Jawa itu akibat pemberian bagian-bagian dari tanahnya oleh para petani yang kecukupan kepada petani-petani kecil, dengan cara-cara seperti menyewakan, membagihasilkan, atau menggadaikan, sebagai contoh-contoh yang penting (Geertz, 1963:100-101). Di samping mendapat perhatian yang besar, buku Geertz tersebut di atas juga mendapat banyak kecaman, tetapi kecaman-kecaman itu umumnya tidak mengenai azas permasalahannya,10 kecuali kecaman yang berasal dari ahli antropologi Belanda, O.D. Van den Muijzenberg, yang mencoba menerapkan konsep Geertz untuk menganalisa suatu daerah pertanian sawah kecil yang terpecah-pecah, yang juga terkena tekanan penduduk yang bertambah. Hanya saja letak daerah yang dibicarakannya itu tidak di Indonesia, melain kan di Pulau Luzon Tengah, Filipina. Laporan dari analisa itu tercantum dalam karangan Involution or Evolution in Central Luzon (1975).11 Dalam karangannya itu Van den Muijzenberg
9
Geertz mengatakan: ". . . inward over elatoration of detail." (1963: him. 82).
10
Sebuah daftar dari sejumlah tinjauan buku terhadap buku Geertz termaktub dalam buku saya mengenai ilmu antropologi di Indonesia (Koentjaraningrat 1975: him. 202).
11
Karangan itu juga disebut oleh W.L. Collier dalam karangan mengenai turunnya penggunaan tenaga kerja dalam produksi bercocok-tanam di sawah (Collier 1979). Page 12 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
melancarkan dua kecaman pokok, ialah bahwa: (1) konsep Geertz mengenai involusi kebudayaan terlalu kabur, karena tidak membedakan secara tajam antara aspek produksi dan aspek konsumsi; (2) gambaran Geertz tentang involusi pertanian mengabaikan kenyataan bahwa para petani di Jawa, seperti juga di Luzon, banyak mendapat penghasilan tambahan dari sumber lain di luar pertanian.12 Van den Muijzenberg menyarankan bahwa dalam menganalisa proses perkembangan pertanian di bidang-bidang tanah sawah yang kecil dengan adanya unsur tekanan penduduk yang makin besar jumlahnya seperti di Luzon Tengah atau di Jawa, seorang peneliti sebaiknya membedakan secara tajam antara aspek produksi dan aspek konsumsi. Dalam produksi petani seringkali dapat meningkatkan hasil panen dengan mempekerjakan lebih banyak tenaga manusia dalam prosesnya. Untuk menyebut aspek yang mengenai aspek produksi ini Van den Muijzenberg menerima istilah Geertz agricultural involution. Namun, hasil panen yang bertambah sebagai akibat intensifikasi penggarapan tanah tadi, dibagi rata antara para petani yang juga bertambah jumlahnya. Untuk menyebut aspek mengenai konsumsi ini, Van den Muijzenberg menyarankan untuk mempergu-nakan istilah Geertz yang kedua yaitu shared poverty. Dengan demikian Van den Muijzenberg berusaha mempertajam konsep cultural involution dengan memisahkannya dari konsep shared poverty. Dalam konsepsi Geertz, perbedaan yang tajam itu tidak ada. Kecaman Van den Muijzenberg bahwa Geertz sama sekali mengabaikan fakta bahwa sebagian besar petani kecil di Jawa, seperti juga halnya di Luzon, banyak mempunyai sumber mata pencahanan di luar pertanian, memang merupakan kecaman yang tepat. Petani-petani di Jawa masa kini biasanya memang banyak mempunyai sumber-sumber mata pencarian lain di luar pertanian. Kecuali berdagang atau berjualan di desa, mereka juga berdagang atau berjualan di kota-kota yang dekat maupun yang cukup jauh dari desa tempat tinggal mereka. Di samping itu mereka sering bekerja sebagai buruh musiman pada waktu-waktu mereka tidak sibuk dalam sektor pertanian, atau bilamana pekerjaan dapat diserahkan kepada isteri atau buruh tani. Untuk menjadi buruh musiman mereka pergi ke kota-kota yang letaknya seringkali cukup jauh dari desa mereka, dan bekerja sebagai kuli atau buruh kasar di berbagai macam proyek pembangunan yang akhir-akhir ini ada di hampir semua kota di Jawa. Kecuali itu kita juga mengetahui bahwa banyak petani pergi ke kota-kota secara musiman untuk bekerja sebagai tukang becak, dan yang tidak dapat dilupakan tetapi tidak cukup mendapat perhatian dari Geertz, ialah bahwa rumah tangga petani di Jawa juga dapat memperoleh penghasilan tambahan dari berbagai macam kegiatan dan usaha yang dilakukan para isteri dan anggota wanita 13 dalam rumah tangga, serta dari aktivitas-aktivitas anakanaknya.14 MOBILITAS KOMUNITAS DESA
12
Khusus mengenai penghasilan petani dari sumber-sumber lain di luar pertanian, lihat karangan saya (Koentjaraningrat 1974).
13
Mengenai berbagai kegiatan dan usaha wanita dalam rumah tangga wanita di Jawa, lihat misalnya karangan A. Staler dalam majalah Masyarakat Indonesia (1975; 1977). 14 Mengenai masalah arti ekonomi anak dalam rumah-tangga petani di Jawa, lihat disertasi serta karangan-karangan B. White (1973; 1975; 1976; 1976-a) dan him. 144-166 di bawah.
Page 13 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Mata Pencaharian Petani di Luar Sektor Pertanian
Brawijaya University 2011
Walaupun penduduk desa biasanya terlibat dalam sektor pertanian, dalam tiap komunitas desa di seluruh Indonesia sudah jelas banyak terdapat sumber mata pencaharian hidup yang lain. Penduduk desa pada umumnya juga terlibat dalam bermacam-macam pekerjaan di luar sektor pertanian, dan mengerjakan kedua sektor tersebut pada waktu yang bersamaan, sebagai pekerjaan primer dan sekunder. Tetapi banyak pula desa-desa, terutama di Jawa, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di luar sektor pertanian. Meskipun demikian kepada pegawai sensus, petugas survai KB, atau kepada para peneliti ilmu sosial, mereka itu biasanya mengidentifikasikan dirinya sebagai petani. Bagi seorang peneliti memang sulit untuk menentukan perbedaan antara petani dan non-petani dan juga antara pekerjaan primer dan sekunder itu, hanya berdasarkan atas pernyataan mereka saja. Seorang petani yang memiliki sebidang tanah yang cukup luas yang juga memiliki sebuah warung yang dijaga oleh ibunya pada awal musim bercocok-tanam, mungkin menerima penghasilan yang lebih banyak dari warungnya daripada dari hasil kebun pekarangannya yang dijual isterinya di pasar desa. Petani itu sendiri tentu saja sibuk di sawahnya, di sawah tetangganya di mana ia memberikan tenaganya berdasarkan adat gotong-royong, dan juga di pekarangan-nya sendiri, untuk memetik buah-buahan yang kemudian dijualnya sendiri menyusuri jalan-jalan di kota kecamatan terdekat, yang jaraknya bisa mencapai kurang-lebih sepuluh kilometer dari desanya. Dengan demikian seorang petani bersama keluarganya sebenarnya sama sibuknya dalam sektor pertanian maupun dalam sektor perdagangan. Apabila musim panen tiba, maka isterinya akan sibuk mengurus para buruh bawon di sawahnya, membantu bawon di sawah tetangga, dan sementara itu petani itu sendiri masih sibuk menjual buah-buahan di kota dan harus segera kembali lagi ke desa untuk menjual sebagian dari hasil padinya kepada para tengkulak dan BUUD. Selama berlangsungnya kegiatan itu seorang petani sebenarnya adalah seorang pedagang; baru apabila ia mulai menanam palawija di sawahnya, ia mulai aktif lagi dalam sektor pertanian. Seorang petani yang tidak memiliki tanah mungkin juga memiliki sebuah warung yang diusahakan oleh isterinya, sedangkan ia sendiri pada awal musim bercocok-tanam sibuk bekerja sebagai buruh tani pada petani-petani lain yang biasanya berasal dari desa lain. Sering juga petani yang tidak memiliki tanah itu menjadi buruh pekerja jalan atau pekerja bangunan selama suatu jangka waktu yang pendek, yaitu misalnya selama tiga bulan, berdasarkan suatu kontrak. Mungkin juga ia pergi ke kota untuk bekerja sebagai tukang becak. Jadi walaupun ia masih cukup aktif dalam sektor pertanian, seorang petani yang tidak memiliki tanah itu tidak menyebut dirinya seorang petani. Ia juga tidak atau jarang menyebut dirinya buruh pekerja jalan atau buruh bangunan, tetapi lebih sering menamakan dirinya pemilik warung, walaupun penghasilannya dari sektor itu tidak banyak. Menjadi tukang warung dirasakannya lebih menaikkan gengsinya daripada menjadi buruh tani, pekerja jalan, buruh pabrik, atau pun tukang becak. Dalam hampir semua komunitas desa, semua anggota pamong desa dan para guru desa, pasti memiiki tanah sawah dan tegalan. Sebagian dari tanah itu mereka sewakan, mereka dibagi-hasilkan, atau mereka gadaikan kepada petani lainnya, tetapi sebagian lagi selalu mereka kerjakan sendiri. Dengan demikian mereka lebih seringg berada di sawah atau tegalan mereka daripada di belakang meja tulis atau ruang kelas. Meskipun demikian mereka lebih senang mengidentifikasi dirinya sebagai pegawai pamong praja karena dalam kebudayaan Indonesia pada umumnya, dan kebudayaan petani Jawa pada khususnya, menjadi pegawai membuatnya lebih gengsi daripada menjadi petani. Desa-desa di Jawa yang ada di sepanjang jalan-jalan raya dekat pabrik-pabrik pusat industri atau dekat kota-kota kecil atau besar, biasanya kurang-lebih terpengaruh oleh gaya hidup kota. Banyak penduduk desa dengan lokasi seperti tersebut di atas itu memiliki atau
Page 14 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
berhasrat memiliki rumah gaya kota, lengkap dengan lantai tegel atau setidak-tidaknya lantai semen, jendela kaca, atap seng atau genting dan perabot rumah seperti yang dimiliki orang kota. Kecuali mereka sudah merasakan perlunya memiliki radio transistor, sepeda motor, dan sekarang malahan juga pesawat televisi. Gaya hidup seperti itu telah menumbuhkan kebutuhan akan keahlian spesiasasi tertentu, seperti tukang kayu, tukang batu, montir sepeda motor, montir radio dan TV dsb. Menjadi tukang di dalam komunitas desa di Jawa tidak merupakan hal yang dipandang rendah. Sejak dahulu kala seorang pandai basi misalnya, dianggap sebagai seorang tokoh masyarakat yang sangat terhormat, bahkan seringgkali dianggap memiliki sifat-sifat keramat. Mobilitas Geografis Pola-pola, mata pencaharian dan aktivitas pekerjaan di luar sektor pertanian tersebut di atas tentu menyebabkan terjadinya suatu mobilitas geografikal yang sangat ekstensif dalam masyarakat pedesaan di Indonesia, dan khususnya di Jawa. Hal ini telah dilukiskan dalam suatu laporan penelitian mengenai kehidupan komunitas-komunitas desa sekitar Jakarta (Koentjaraningrat 1975), yang juga termuat dalam bagian ke III dari buku bunga rampai ini. Dalam bagian yang khusus memuat karangan-karangan mengenai migrasi, transmigrasi dan urbanisasi itu, masalah mobilitas geografikal dari penduduk komunitas desa di Indonesia akan dibahas lebih mendalam. KOMUNITAS DESA DAN DUNIA DI LUAR DESA Sepanjang masa, sebagian besar komunitas desa di Indonesia, dari daerah Aceh hingga Irian Jaya, telah didominasi oleh suatu kekuasaan pusat tertentu. Banyak di antaranya telah mengalami dominasi itu sejak zaman kejayaan kerajaan-kerajaan tradisional; banyak yang mengalaminya sejak zaman penjajahan Belanda atau Inggris, dan banyak pula lainnya yang baru mengalaminya sejak beberapa waktu terakhir ini. Dengan demikian, juga karena makin berkembangnya kesempatan dan prasarana untuk suatu gaya hidup dengan mobilitas geografikal yang tinggi, pada waktu sekarang ini hampir tidak ada lagi komunitas desa bersahaja yang terisolasi di negara kita ini, yaitu desa dengan penduduk yang tidak sadar akan adanya dunia di luar desa itu. Dalam pada itu terhadap banyak komunitas desa di Indonesia kita dapat menerapkan konsep Redfield mengenai masyarakat petani yang warganya berupa " . . . . orang pedesaan, bagian dari peradaban-peradaban kuno, .... yang menggarap tanah mereka sebagai mata pencaharian hidup dan sebagai suatu cara hidup tradisional. Mereka itu berorientasi terhadap serta terpengaruh oleh suatu golongan priyayi di kota-kota dengan cara hidup yang sama seperti mereka walaupun dalam bentuk yang lebih beradab."15 Walaupun demikian kesadaran akan adanya suatu dunia luas di luar komunitas desa sendiri perlu dianalisa, lepas dari jangkauan hubungan dari para petani pedesaan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu di dunia luar itu tadi, sedangkan kesadaran tadi itu juga belum berarti bahwa para petani pedesaan itu juga mempunyai perhatian dan pengertian yang luas dari dunia luar itu. Seorang petani pedesaan tertentu mungkin mempunyai kesadaran akan adanya suatu dunia yang luas di luar batas komunitasnya sendiri; ia malahan mungkin mempunyai perhatian serta pengertian besar
15
Redfield raengatakan: " ... rural people in old civilizations, ... who control and cultivate their land for subsistence and as part of a traditional way of life and who look to and are influenced by gentry or townspeople whose way of life is like theirs but in a more civilized form. " (1956: him. 20). Page 15 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
mengenai beberapa masalah yang ada di dunia luar tadi, padahal ruang lingkup hubungannya dengan individu-individu atau kelompok-kelompok di kota terbatas sekali. Sebaliknya, seorang petani tetangganya, walaupun juga memiliki kesadaran tadi, mungkin saja tidak mempunyai perhatian banyak serta pengertian mengenai dunia di luar desanya, meskipun ia mungkin mengenal banyak orang di kota, bahkan di beberapa kota lain yang jauh letaknya. Pada hemat saya, suatu konsep yang sangat cocok untuk menganalisa perbedaan antara kesadaran dan pengertian dari para petani pedesaan mengenai dunia di luar batas komunitas itu, serta ruang lingkup hubungan sosialnya di sana, adalah konsep yang dikembangkan oleh ahli antropologi-sosial J.A. Barnes mengenai "lapangan lapangan sosial" atau social fields (1954). Menurut konsep itu, petani desa pun dalam kehidupan sosialnya dapat bergerak dalam "lapangan-lapangan sosial" yang berbeda-beda, menurut keadaannya yang berbeda-beda dan dalam waktu yang berbeda-beda. Karena itu banyak petani di Indonesia pada umumnya mempunyai hubungan sosialnya dalam "lapangan hidup" pertanian. Dalam hubungan sosial ini termasuk kerabatnya yang terdekat, tetangganya, kenalankenalannya yang memiliki tanah pertanian dekat pada tanah pertaniannya sendiri, penduduk dukuh-dukuh lain yang juga menjadi anggota organisasi irigasi subak yang sama, para pemilik tanah yang tanahnya sedang digarap atas dasar bagi-hasil, dan para buruh tani yang berasal dari desa-desa lain pada musim panen. Banyak di antara para petani mempunyai mata pencaharian tambahan sebagai penjaja buah-buahan atau sayur-mayur, atau menjadi pedagang barang kerajinan tangan atau kebutuhan rumah tangga di pasar. Kecuali kaum kerabatnya, tetangga-tetangganya, dan teman-temannya, para petani dari golongan ini juga mempunyai hubungan dalam lapangan sosial para pembelinya dan langganannya, yang biasanya berasal dari desa lain, atau dengan para tengkulak yang memang mungkin berasal dari desanya sendiri, tetapi lebih lazim dari desa dan bahkan kota lain. Para petani yang dalam bulan-bulan sewaktu kesibukan produksi pertanian sedang menurun, seringkali pergi merantau secara musiman untuk bekerja menjadi buruh pekerjaan umum dalam proyek-proyek pemugaran atau pembangunan jalan raya, jembatan, bendungan serta saluran irigasi, atau untuk menjadi buruh bangunan dalam proyek-proyek penamahan di kota-kota, atau menjadi tukang becak di kota-kota. Mereka ini biasanya mempunyai hubungan yang lebih ekstensif lagi, dan yang melingkupi lapangan-lapangan sosial yang lebih luas. Dengan mempergunakan konsep "lapangan sosial" sebagai jaringan-jaringan hubungan para petani pedesaan, seorang peneliti dengan demikian dapat membuat suatu deskripsi kongkrit secara kualitatif dan kuantitatif tentang berbagai macam pola dari lapanganlapangan sosial para petani yang berdasarkan sifat, ruang lingkup, intensitas, serta frekuensi dari hubungan-hubungannya. Loyalitas para petani terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu ditentukan oleh perhatian mereka terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok itu. Perhatian itu sebaliknya ditentukan oleh sifat dari "lapangan sosial" yang menjadi lapangan hidup serta lapangan orientasi mereka. Dalam tahun 50-an, ketika G.W. Skinner dan beberapa ahli antropologi Amerika meneliti daerah pedesaan di beberapa tempat di Indonesia, dan berdasarkan observasi mereka telah menulis karangan-karangan mengenai Local, Ethnic and National Loyaltiesdn Village Indonesia (1959), ternyata bahwa loyalitas orang desa di negeri kita masih sangat terorientasi terhadap orang-orang dan kelompokkelompok dalam lingkungan masyarakat desanya sendiri. Data yang diajukan dalam karangan-karangan tersebut memang menunjukkan bahwa ruang lingkup pola-pola "lapangan sosial" para petani Indonesia waktu itu rupa-rupanya masih terbatas kepada lingkungan lokal, dan perhatian para petani terhadap masalah-masalah nasional belum berkembang. Jika para ahli antropologi tadi mengadakan pengamatan mereka sekarang, dalam dasawarsa 70-an ini,
Page 16 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
mereka mungkin akan melihat bahwa perhatian terhadap masalah-masalah di luar lokalitas desa mereka sudah banyak, dan karena itu pola-pola "lapangan sosial" orang desa sudah mempunyai ruang-lingkup yang jauh lebih luas. Sebaliknya, masalah apakah loyalitas nasional para petani di berbagai daerah pedesaan di Indonesia juga sudah berkembang adalah hal yang memang masih perlu diteliti lebih mendalam. Loyalitas etnik adalah masalah yang lain lagi. Semua penduduk pedesaan di Indonesia secara primordial tentu sudah memiliki loyalitas etnik terhadap suku-bangsanya masingmasing, karena sejak kecil mereka disosialisasikan dan dibudayakan dalam kebudayaan suku bangsa itu. Komunitas pedesaan di Indonesia biasanya dihuni oleh penduduk dari satu sukubangsa tertentu; apabila ada warga suku-bangsa lain, maka mereka itu akan merupakan minoritas dalam masyarakat desa itu. Dengan demikian, dalam masyarakat desa seperti yang juga akan diuraikan pada halaman lain, hubungan antara suku-bangsa jarang menimbulkan masalah. Hanya dalam masyarakat kota, di mana bermukim berbagai suku-bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, untuk bersaing dalam memperoleh kesempatan pendidikan, kerja dan politik, maka masalah hubungan antar suku bangsa itu timbul. Usaha yang penting dari para perencana pembangunan masyarakat desa adalah untuk selalu menyediakan dan menciptakan adanya kepentingan-kepentingan lokal, yang dapat mengembangkan "lapangan-lapangan sosial" dengan ruang-lingkup lokal. Dengan demikian kecenderungan orang-orang desa untuk pindah ke kota dapat terjaga. Juga usaha pengembangan loyalitas nasional pada penduduk desa di Indonesia sebaiknya merupakan usaha pengembangan lebih lanjut dari perhatian mereka terhadap masalah-masalah lokal. Dalam hal ini loyalitas nasional merupakan ekstensi dari loyalitas lokal. BIBLIOGRAFI Adam, L. 1924 De Autonomie van het Indonesische Corp. Amersfoort, S.W. Melchior (Dissertasi Universitas Leiden). Adiwilaga 1954 Land Tenure in the Village ofTjipagalo. Bandung, Kantor Perantjang Tata Bumi Barnes, J.A. 1954 Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations, VII, him. 39-58. Bennet, D.C. 1957 Population Pressure in East Java. Syracuse, N.Y. (Naskah ketik dissertasi untuk Universitas Syracuse). Birowo, A.T. 1973 Aspek Kesempatan Kerja Dalam Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Prisma, II-4: him. 3-15. Collier, W.L. 1979 Policy Implications of Declining Labor Absorption in Javanese Rice Production. Kuala Lumpur (Makalah untuk Southeast Asia's Third Biennial Meeting of the Agricultural Economic Society). Collier, W.L., Gunawan Wiradi, dan Soentoro 1973 Recent Changes in Rice Harvesting Methods. Bulletin of Indonesian Economic Studies, IX: him. 36-45. Collier, W.L., Soentoro, Gunawan Wiradi, dan Makali 1974 Agricultural Technology and Institutional Change: An Example in Java. Food Research Institute Studies in Agricultural Economics, Trade and Development, Stanford University. Dam, H. ten 1956 Coopereren Vanuit het Gezichtspunt der Desastructuur in Desa Tjibodas, Indonesian, IX: him. 89-116. Terjemahannya dalam bahasa Inggeris dengan judul "Cooperation and Social Structure in the Village of Tjibodas" diterbitkan dalam Indonesian Economics. The
Page 17 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
Hague, W. van Hoeve. Selected Studies on Indonesia by Dutch Scholars, VI. him. 345382. Djojopranoto, R. Ng. A., 1958 Persaingan Tanaman Perdagangan di Daerah Surakarta Dan Sekitarnja. Chusus-nja Daerah Klaten. Teknik Pertanian, XI-12: him. 517. Guritno Pandam . 1958 Masjarakat Marangan. Jogyakarta, Panitya Social Research, Universitas Gadjah Mada (Naskah roneo). Harts-Broekhuis, A., dan H.Palte-Gooszen 1977 Demografische Aspekten van Armoede in een Javaans Dorp, Jambidan, D.I.Y. Utrecht, Geografisch Instituut Rijksuniversiteit te Utreecht. Jay, R.R. 1969 Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjohuto. Cambridge, Mass., The M.I.T. Press. Kasniyah, N. 1978 Pengaruh Mesin Penggiling Padi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Wanita Buruh Tumbuk Padi. Masyarakat Indonesia, V/2: halaman 161-172. King, D.Y. 1973 Social Development in Indonesia: A Macro Analysis. Jakarta, Biro Pusat Statistic Koentjaraningrat 1961 Some Social-Anthropological Observations on Gotong-Royong Practices in Two Villages of Central Java. Ithaca, N.Y. Cornell University Modern Indonesia Project. Monograph Series. 1967 Tjelapar: A Village in South Central Java, Villages in Indonesia. Koentjaraningrat editor. Ithaca, N.Y., Cornell Univesity Press. 1974 Non-Farming Occupations in Village Communities. Masyarakat Indonesia, I: him. 45-61. 1975 Anthropology in Indonesia: A Bibliographical Review. 'sGravenhage, Martinus Nijhooff. 1977 Sistem Gotong Royong Dan Jiwa Gotong Royong. Berita Antropologi IX/30: him. 4-16. Kolff, G.H. van der 1937 De Historische Ontwikkeling van de Arbeidsverhoudingen bij de Rijstcultuur in een Afgelegen Streek op Java: Voorlopige Resultaten van Plaatselijk Onderzoek, Volkskredietwezen: hlm. 3-70. Kuntowijoyo 1971 Economic and Religious Attitudes of Entrepreneurs in a Village Industry: Notes on the Community of Batur. Translate by N. Nakamura. Indonesia, XII: hlm. 47-55. Muijzenberg, D.D. van den 1976 Involution or Evolution in Central Luzon, Cultural Anthropology in the Netherlands. P. Kloos, HJ.M. Claessens editors. Rotterdam, Nederlandsche Sociolo-gische en Antropologische Verenjging. Afdeling Culturele Antropologie/Niet-Westersche Sociologie. Penny, D.H., M. Singarimbun 1973 Population and Poverty in Rural Java : Some Economic Arithmatic From Shihardjo, Ithaca, N.Y.: Dept. of Agricultural Economics, Cornell University. Redield, R. 1956 Peasant Society and Culture, Chicago: Chicago University Press. Roll, W. 1977 Die Agrarische Grndbezit Vergassung uin Raume Surakarta: Untersuchungen zur Agrar und Sozial-struktur Zentral-Javas, Website Institut fur. Asienkunde, Hamburg. Skinner, G.W. (editor) 1959 Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium, New Haven: Yale University Southeast Asia Studies. Soemardjo Hadiwidnjo 1950 Desa Tjandi, Kelurahan Purwobmangun. Jogyakarta. Panitya Social Research, Universitas Gadjah Mada (Naskah roneo). Terra, G.J.A
Page 18 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
1952 Tuinbouw in Indonesia 'sGravenhage: W. van Hoeve 1932-a De Voeding der Bevolking en de Erfcultuur, Kolomale Studien, XVI. hlm. 593. Tiken, J. 1976. Guru Desa Een Sociologisch-Anthropologische Benadering van de Sociale Posi-tie van Onderwijzend Personeel en Zijn Rol in de Dorpssamenleving van Midden-java Amsterdam: Universiteit van Amsterdam (Naskah skripsi Sarana Universitas Amsterdam). Timmer, M. 1961 Chld Mortality and Population Pressure in D.I. Jogyakarta, Java, Indonesia. Rotterdam: Bronder Offset. Vries, E. de 1927 On twikkling van de Erfucltuur, De Indische Culturen : hlm. 496-656. White, B. 1973 Peranan Anak Dalam Ekonomi Desa, Prisma, II-4: hlm. 44-59 1985 The Economic Importance of Children in Jaanese Village, Population and Social Organization, Moni Nag editor. The Hague. Mouton. 1976 Production and Reproduction in a Javanese Village, New York (Dissertasi Ph.D. Antropologi, Universitas coulombia). 1976 Problems of Estimating the Value of Work in Peasant Houshold Economics: An Example from Rural Java. Bogor (Naskah roneo).
Pertanyaan Diskusi 1 2 3 4 5 Jelaskan pengertian komunitas desa dengan contoh kasus desa lahan kering/lahan sawah, ladang berpindah! Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur komunitas desa di Indonesia serta hubungan antar unsur-unsur komunitas desa tersebut Sebutkan dan jelaskan perbedaan komunitas desa pertanian ladang berpindah dengan pertanian menetap! Sebutkan dan jelaskan perbedaan komunitas desa lahan kering dan lahan sawah! Bagaimana proses/mekanisme faktor eksternal mempengaruhi komunitas desa? Unsurunsur komunitas desa apa yang terkena pengaruh faktor ekternal tersebut? Jelaskan dengan menggunakan Teori Medan Sosial Redfield
Page 19 of 20
Mata Kuliah / MateriKuliah
Brawijaya University 2011
SOAL KUIS 1 : Kerjakan satu di antara beberapa soal berikut ini: 1. Ada dua (2) macam pertanian di Indonesia, yaitu pertanian ladang berpindah ( shifting cultivation) dan pertanian menetap. Tunjukkan dan jelaskan beberapa ciri-ciri komunitas desa dengan sistem pertanian ladang berpindah dan pertanian menetap. 2. Komunitas desa di Indonesia senantiasa berinteraksi dengan dunia luar. Adakah pengaruh dunia luar terhadap kondisi internal komunitas desa? Jelaskan! 3. Dalam setiap komunitas, yang warganya hidup bersama pasti memiliki kebudayaan tertentu. Sebutkan kebudayaan yang dijumpai pada komunitas desa dengan basis lahan sawah dan lahan kering!
Page 20 of 20
Anda mungkin juga menyukai
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1108)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5795)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (728)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20026)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3278)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5511)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12948)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)














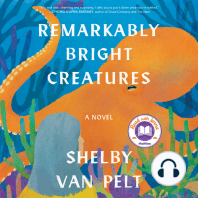






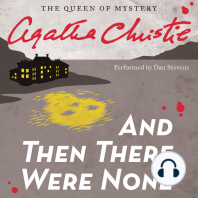

![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)



