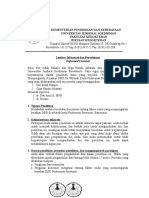Gastroesofageal Refluks Disease
Gastroesofageal Refluks Disease
Diunggah oleh
Giga Hasabi AlkaraniHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Gastroesofageal Refluks Disease
Gastroesofageal Refluks Disease
Diunggah oleh
Giga Hasabi AlkaraniHak Cipta:
Format Tersedia
Gastroesofageal Refluks Disease (GERD)
1. Definisi GERD
Refluks gastroesofagus adalah peristiwa masuknya isi lambung ke
dalam esofagus yang terjadi secara intermiten pada setiap orang, terutama
setelah makan. Refluks yang terjadi tanpa menimbulkan gejala dan perubahan
histologik mukosa esofagus, disebut refluks gastroesofagus fisiologik. Bila
refluks terjadi berulang-ulang, sehingga timbul gejala dan komplikasi, disebut
refluks gastroesofagus patologik atau penyakit refluks gastroesofagus, suatu
istilah yang meliputi refluks esofagitis dan refluks simtomatis (Mariyana,
2001).
2. Etiologi GERD
Penyakit gastroesofageal bersifat multifaktorial. Keadaan yang harus
dijumpai agar episode refluks terjadi adalah isi lambung harus siap untuk
refluks dan mekanisme anti refluks pada sphincter gastroesophagus harus
menurun. Faktor-faktor yang dapat menurunkan tonus sphincter
gastroesophagus adalah ( Makmun, 2009) :
a. Adanya hiatus hernia
b. Panjang sphincter gastroesophagus ( makin pendek, makin rendah
tonusnya)
c. Obat-obatan seperti antikolinergik, beta adrenergik, theofilin, dll
d. Faktor hormonal (kehamilan).
e. Makanan yang berlemak, merokok dan minuman dengan kandungan
xantin yang tinggi (teh, kopi).
Sebagian besar pasien GERD, ternyata mempunyai tonus sphincter
gastroesophagus yang normal. Pada kasus ini, yang berperan dalam
terjadinya proses refluks ini adalah transient LES relaxation, yaitu relaksasi
sphincter gastroesophagus yang bersifat spontan (Makmun, 2009).
3. Penegakkan Diagnosis GERD
a. Anamnesis
1) Faktor risiko:
Penyakit hiatus hernia, konsumsi obat-obatan seperti antikolinergik,
beta adrenergik, dll, kehamilan, obesitas, rokok, alkohol dan minum
dengan kandungan xantin yang tinggi (Makmun, 2009).
2) Tanda dan Gejala
Gejala klinik yang khas dari GERD adalah nyeri atau rasa tidak enak
di epigastrium atau retrosternal bagian bawah, kadang-kadang
bercampur dengan disfagia, mual atau regurgitasi dan rasa pahit di
lidah. Odinofagia bisa timbul jika sudah terjadi ulserasi esofagus yang
berat. GERD juga dapat menimbulkan manifestasi gejala esktra
esophageal yang atipik dan sangat bervariasi mulai dari nyeri dada non
cardiac, suara serak, laringitis, dan batuk. Gejala GERD biasanya
berjalan perlahan-lahan ( Makmun, 2009).
b. Pemeriksaan Penunjang (Makmun, 2009) :
1) Endoskopi saluran cerna atas
Pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas merupakan standar baku
untuk diagnosis GERD dengan ditemukannya mucosal break di
esofagus. Dengan pemeriksaan endoskopi dapat dinilai perubahan
makroskopik dari mukosa esofagus. Jika tidak ditemukan mucosal
break pada pemeriksaan endoskopi saluran cerna atas pada pasien
dengan gejala khas GERD, keadaan ini disebut non erosive reflux
disease (NERD)
2) Esofagografi dengan barium
Pemeriksaan kurang peka dan seringkali tidak menunjukkan kelainan.
3) Radiologi
Pada keadaan yang lebih berat, gambar radiologi dapat berupa
penebalan dinding dan lipatan mukosa, ulkus atau penyempitan lumen.
4) Pemantauan pH 24 jam
Episode refluks menimbulkan asidifikasi bagian distal esofagus. PH di
bawah 4 pada jarak 5 cm di atas sphincter gastroesophageal dianggap
diagnostik untuk GERD.
5) Tes Bernstein
Tes ini mengukur sensitivitas mukosa dengan menggunakan larutan 0,
1 M dan NaCL. Bila larutan HCL menimbulkan nyeri sepeti yang
biasanya dialami pasien, sedangkan larutan NaCL tidak menimbulkan
rasa nyeri, maka test ini dianggap positif.
6) Manometri esofagus
Tes manometri akan memberikan manfaat yang berarti jika pada
pasien-pasien dengan gejala nyeri epigstrium dan regurgitasi yang
nyata didapatkan esofagografi barium dan endoskopi yang normal.
7) Histopatologi
Pemeriksaan untuk menilai adanya metaplasia, displasia atau
keganasan. Tetapi bukan untuk memastikan NERD.
4. Penatalaksanaan GERD
Pada prinsipnya, penatalaksanaan GERD terdiri dari modifikasi gaya
hidup, terapi medikamentosa, terapi bedah serta akhir-akhir ini mulai
dilakukan terapi endoskopik. Target penatalaksanaan GERD adalah
menyembuhkan lesi esophagus, menghilangkan gejala/keluhan, mencegah
kekambuhan, memperbaiki kualitas hidup, dan mencegah timbulnya
komplikasi (Makmun, 2009).
a. Non-medikamentosa
Modifikasi gaya hidup merupakan salah satu bagian dari
penatalaksanaan GERD, namun bukan merupakan pengobatan primer.
Walaupun belum ada studi yang dapat memperlihatkan kemaknaannya,
namun pada dasarnya usaha ini bertujuan untuk mengurangi frekuensi
refluks serta mencegah kekambuhan (Makmun, 2009). Hal-hal yang
perlu dilakukan dalam modifikasi gaya hidup, yaitu (Makmun, 2009) :
1) Meninggikan posisi kepala pada saat tidur serta menghindari makan
sebelum tidur dengan tujuan untuk meningkatkan bersihan asam
selama tidur serta mencegah refluks asam dari lambung ke
esophagus.
2) Berhenti merokok dan mengkonsumsi alkohol karena keduanya
dapat menurunkan tonus LES sehingga secara langsung
mempengaruhi sel-sel epitel.
3) Mengurangi konsumsi lemak serta mengurangi jumlah makanan
yang dimakan karena keduanya dapat menimbulkan distensi
lambung.
4) Menurunkan berat badan pada pasien kegemukan serta menghindari
pakaian ketat sehingga dapat mengurangi tekanan intraabdomen.
5) Menghindari makanan/minuman seperti coklat, teh, peppermint,
kopi dan minuman bersoda karena dapat menstimulasi sekresi asam.
6) Jika memungkinkan menghindari obat-obat yang dapat menurunkan
tonus LES seperti antikolinergik, teofilin, diazepam, opiate,
antagonis kalsium, agonis beta adrenergic, progesteron.
b. Medikamentosa
Berikut adalah obat-obatan yang dapat digunakan dalam terapi
medikamentosa GERD :
1) Penghambat pompa proton (Proton Pump Inhhibitor/PPI)
Golongan obat ini merupakan drug of choice dalam
pengobatan GERD. Golongan obat-obatan ini bekerja langsung
pada pompa proton sel parietal dengan mempengaruhi enzim H, K
ATP-ase yang dianggap sebagai tahap akhir proses pembentukan
asam lambung. Dosis yang diberikan untuk GERD adalah dosis
penuh yaitu: omeprazole 2x20mg, lansoprazole 2x30mg,
pantoprazole 2x40mg, rabeprazole 2x10mg dan esomeprazole
2x40mg (Makmun, 2009).
2) Antasid
Golongan obat ini cukup efektif dan aman dalam
menghilangkan gejala GERD tetapi tidak menyembuhkan lesi
esofagitis. Selain sebagai buffer terhadap HCl, obat ini dapat
memperkuat tekanan sfingter esophagus bagian bawah. Kelemahan
obat golongan ini adalah rasanya kurang menyenangkan, dapat
menimbulkan diare terutama yang mengandung magnesium serta
konstipasi terutama antasid yang mengandung aluminium,
penggunaannya sangat terbatas pada pasien dengan gangguan
fungsi ginjal. Dosis sehari 4 x 1 sendok makan (Makmun, 2009).
3) Antagonis reseptor H2
Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah simetidin,
ranitidine, famotidin, dan nizatidin. Sebagai penekan sekresi asam,
golongan obat ini efektif dalam pengobatan penyakit refluks
gastroesofageal jika diberikan dosis 2 kali lebih tinggi dan dosis
untuk terapi ulkus. Golongan obat ini hanya efektif pada
pengobatan esofagitis derajat ringan sampai sedang serta tanpa
komplikasi. Dosis pemberian simetidin 2x800mg atau 4x400mg,
ranitidin 4x150mg, famotidin 2x20mg, nizatidin 2x150mg
(Makmun, 2009).
4) Obat-obatan prokinetik
Secara teoritis, obat ini paling sesuai untuk pengobatan
GERD karena penyakit ini lebih condong kearah gangguan
motilitas. Namun, pada prakteknya, pengobatan GERD sangat
bergantung pada penekanan sekresi asam. Beberapa dari obat obat
prokinetik :
a) Metoklopramid
Obat ini bekerja sebagai antagonis reseptor dopamine.
Efektivitasnya rendah dalam mengurangi gejala serta tidak
berperan dalam penyembuhan lesi di esophagus kecuali dalam
kombinasi dengan antagonis reseptor H2 atau penghambat
pompa proton. Karena melalui sawar darah otak, maka dapat
timbul efek terhadap susunan saraf pusat berupa mengantuk,
pusing, agitasi, tremor, dan diskinesia. Dosis 3x10mg
(Makmun, 2009).
b) Domperidon
Golongan obat ini adalah antagonis reseptor dopamine dengan
efek samping yang lebih jarang dibanding metoklopramid
karena tidak melalui sawar darah otak. Walaupun efektivitasnya
dalam mengurangi keluhan dan penyembuhan lesi esophageal
belum banyak dilaporkan, golongan obat ini diketahui dapat
meningkatkan tonus LES serta mempercepat pengosongan
lambung. Dosis 3x10-20mg sehari (Makmun, 2009).
c) Cisapride
Sebagai suatu antagonis reseptor 5 HT4, obat ini dapat
mempercepat pengosongan lambung serta meningkatkan
tekanan tonus LES. Efektivitasnya dalam menghilangkan gejala
serta penyembuhan lesi esophagus lebih baik dibandingkan
dengan domperidon. Dosis 3x10mg sehari (Makmun, 2009).
5) Sukralfat (Aluminium hidroksida + sukrosa oktasulfat)
Berbeda dengan antasid dan penekan sekresi asam, obat ini
tidak memiliki efek langsung terhadap asam lambung. Obat ini
bekerja dengan cara meningkatkan pertahanan mukosa esophagus,
sebagai buffer terhadap HCl di eesofagus serta dapat mengikat
pepsin dan garam empedu. Golongan obat ini cukup aman diberikan
karena bekerja secara topikal (sitoproteksi). Dosis 4x1gram
(Makmun, 2009).
DAFTAR PUSTAKA
Makmun D. 2009. Penyakit Refluks Gastroesofageal. Dalam : Sudoyo AW, Setiohadi
B. Ilmu Penyakit Dalam Jilid 1. Jakarta: EGC.
Mariana Y. 2001. Penyakit Refluks Gastroesofagus. Dalam : Efiaty AS, Nurbaiti I.
Buku Ajar Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, Leher Edisi
5. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
Anda mungkin juga menyukai
- Moreen Higiene CTHDokumen13 halamanMoreen Higiene CTHGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- Kuesioner DBDDokumen13 halamanKuesioner DBDGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- CoverDokumen2 halamanCoverGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- Tatalaksana Airway ManagementDokumen14 halamanTatalaksana Airway ManagementGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- Jurnal BPDokumen10 halamanJurnal BPGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- CTH PartografDokumen10 halamanCTH PartografGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- CTH PartografDokumen10 halamanCTH PartografGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka PemfigusDokumen8 halamanTinjauan Pustaka PemfigusGiga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat
- Modul SPSS Besral 2013Dokumen139 halamanModul SPSS Besral 2013Giga Hasabi AlkaraniBelum ada peringkat