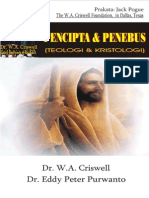Iman Tidak Pernah Amin Steve Gasperz
Diunggah oleh
Nusye Bastov Manuputty0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
175 tayangan152 halamanBuku
Judul Asli
Iman Tidak pernah Amin Steve Gasperz
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniBuku
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
175 tayangan152 halamanIman Tidak Pernah Amin Steve Gasperz
Diunggah oleh
Nusye Bastov ManuputtyBuku
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 152
of. John Titaley, Th.D
a UKSW Salatiga
Menjadi Kristen & Menjadi Indonesia
Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen & Menjadi Indonesia
Copyright © 2009 oleh Steve Gaspersz
Diterbitkan olen PT BPK Gunung Mulia
Ji. Kwitang 22-23, Jakarta 10420
E-mail: publishing@bpkgm.com
Website: www:bpkgm.com
Anggota IKAPI
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Cetakan ke-1: 2009
Penyunting: Eko Y.A. Fangohoy, Irayati Tampubolon, Anton Sulistiyanto
Tata Letake: Panjibudi
Desain Sampul: Hendry
Katalog dalam Terbitan (KDT)
Gaspersz, Steve
Iman tidak pernah amin: menjadi Kristen & menjadi Indonesia /
oleh Steve Garpersz; - Cet. 1.— Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009
xvi + 204 him. ; 14x 21 em
1, Renungan
1 Judul
261
ISBN 978-979-687-666-2
Daftar Isi
Kata Pengantar
Benang Merah. xi
DAEs? scencnsrmunwonmnrenunwnmananannanenanas xv
Bagian | - Indonesia dalam Ceritaku
1.__Avatar 3
2. ML 9
3.__Ayat-ayat Cinta untuk Siapa: 17
4. _Menjadi Indonesia: Masihkah Realistis? 23
5.__Indonesia Raya atau Indonesia Rawa?, Sf
6. Pilpres: Menyorot dari Lekuk yang Lain 36
Z._Ke Sekolah - Ke Mana?... 43
8. Sepak Bola dan Rasisme. 48
9. Satpol PP: Solusi atau Masalah 55
10; Pérenipuatt-nincnonianacnnnamnananmmmnarce 61
Bagian Il - Beragama dalam Indonesiaku
11. Agama-agama dan HIV/AIDS 69
12. Membidik yang Salah atau Salah Membidik: 74
13. Beragama yang Repot... 80
14. 86
15. Mencari yang Tersentuh dan Bebas: Teologi Feminis
Indonesia Pasca~Marianne Katoppo 90
xv
16. Lectio Divin: 94
17. Banjir..... 100
18. Mengasihi Musuh? Capek Deh 105
19. Anakku Sekolah! ....
20. Idul Fitri bagi Seorang Kristen......c..seessecssseesenesesneeeenneese 116
Bagian Ill - Beriman dalam Budayaku
21. Marinyo dan Andarinyo 123
22. Gereja Puing-puing. 127
23. Gereja dan Adat. 136
24. Saat Ambon Pecah Lagi 149
25. Nol Kilometer: Sekelumit Catatan tentang Kit: 156
26. Reformasi Misi Gereja: Apa Lagi?...... 161
27. Signifikansi Praksis Gerakan Keesaan Gereja
dalam Konteks Polemik Ideologi Politik di Indonesia 170
28. Maarif Award untuk Rakyat Maluku 180
29. Palestina-Israel: Secuil Pandangan 185
30. Mena Muria: Sebuah Tafsir Simbol Budaya .. 191
31. Daniel Sahuleka: The Legend..............-:100-s0essesseeeeeseeees 196
Catatan ....... 200
Tentang Penulis 204
xvi
Iman Tidak Pernah Amin
BAGIAN | i
INDONESIA DALAM $j}
CERITAKU __
Avatar
Am kami, Kainalu, terpincut berat dengan film animasi
Avatar”. Hampir setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah,
ia memaksa agar diizinkan menonton film itu sampai selesai.
Akibatnya, beberapa kali ia terlambat ke sekolah. Yah, susahnya film
anak-anak diputar sepagi itu. Semula kami merasa berat dengan
kebiasaan menontonnya ini, tetapi lama-kelamaan kami terdorong
oleh rasa ingin tahu: apa sebenarnya yang diceritakan film itu.
Beberapa kali kami menyempatkan diri untuk menontonnya. Wow,
ternyata film animasi Avatar itu sarat ajaran kebijaksanaan Timur
yang dikemas dengan menarik. Sekarang bukan hanya Kainalu, kami
pun orangtuanya ketagihan menikmati alur cerita dan ungkapan
hikmat (wise words) yang kerap muncul dalam adegan-adegan
Avatar. Kendati episodenya diulang-ulang, namun rasanya kami tak
kunjung bosan menikmati ceritanya. Malah, kami sampai hafal alur
ceritanya.
image
not
available
image
not
available
menyabot tanah warga; banyak anggota DPR yang marah karena
tidak mendapat fasilitas hidup ala konglomerat sebagai konsekuensi
mewakili rakyat yang hidup melarat; anak-anak sekolah yang marah
karena temannya diejek anak-anak dari sekolah lain; warga miskin
yang marah karena gubuk-gubuk mereka digusur tanpa ampun;
para pengacara yang marah karena kliennya dituduh sembarangan;
kaum beragama yang marah karena ada kelompok beragama lain
yang mendompleng nama agamanya padahal praktiknya dianggap
menyimpang; polisi marah kepada tentara, tentara marah kepada
polisi; dan seribu kemarahan lainya. Negeri kita benar-benar
sedang menjadi pabrik raksasa yang memproduksi aneka produk
kemarahan. Tinggal pilih: mau marah yang rasa apa—rasa caci-
maki, rasa bogem, rasa pentungan kayu, rasa buldoser, atau bahkan
rasa arsenik (seperti yang dialami sahabat kita, Munir).
Menuju Habitus Baru?
Mengapa kita tampaknya begitu menikmati energi kemarahan?
Jawabannya bisa bermacam-macam, bergantung pada siapa yang
menjawabnya. Saya sendiri tidak tahu jawabannya. Akan tetapi,
rasanya sayang sekali jika bangsa yang begini besar dengan kejamakan
(bahasa, etnis, agama, budaya) terkuras habis energinya hanya untuk
marah-marah. Energi kemarahan yang menampak dalam berbagai
tampilan bangsa kita ini sebenarnya bisa dimaknai sebagai energi luar
biasa jika itu diarahkan bagi pengembangan kesadaran berbangsa
secara positif.
Tentu saja proses membangun kesadaran positif dengan energi
tersebut bukanlah sesuatu yang gampang bin mudah. Justru saya
melihat bahwa sekarang ini kita tidak membutuhkan negasi terhadap
energi sosial itu, tetapi membutuhkan habitus baru yang mampu
mewadakinya. Wadak itu adalah ”kita’, bangsa ini, dengan segala
kemajemukannya. Spirit itu adalah komitmen dan konsensus untuk
6 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
mereka asal jiplak (aspak) alias asal mangap (asma) alias asal bunyi
(asbun). Kalau mereka mau protes, harus jelas dong argumentasi,
logika, korelasi logis dengan variabel-variabel yang mereka ajukan.
Kalau cuma menyoroti judulnya, itu si# namanya sentimen belaka,
bukan argumen. Menurut produsernya, film ini memang lebih
menguak persoalan free-sex yang sudah semakin biasa dan terbuka
di masyarakat kita (Indonesia). Dulu, mungkin kita tidak terbiasa
berbicara secara blak-blakan soal free-sex; soal itu terselip diam-
diam dan menjadi kebiasaan bisu masyarakat kita: dilakukan oleh
banyak orang, tetapi disimpan agar hanya diketahui segelintir orang.
Sekarang yang dilakukan adalah sebaliknya: dilakukan oleh banyak
orang dan diketahui oleh semua orang. Itulah yang dikatakan
produsernya yang sempat saya rekam sepintas. Ia juga mengakui
bahwa film ini lebih merupakan media melakukan sex-education
kepada para remaja.
Saya sih—yang bukan artis dan produser film—melihat feno-
mena ini biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah respons orang atau
kelompok tertentu yang rupanya terusik dengan judul film itu—lagi-
lagi hanya judulnya. Sejauh pengamatan saya, mereka sama sekali
tidak mengutak-atik alur film itu: pesan apa yang ingin disampaikan
oleh suatu media. Jika seluruh ckspresi estetis hanya dipahami
dalam cakrawala pemikiran yang sempit semacam itu, dalam hal ini
hanya terpesona atau terusik oleh yang kelihatan sambil melupakan
pemaknaannya, saya jadi cemas juga, sebab jangan-jangan masyarakat
kita sudah mati rasa dalam menikmati ekspresi seni nan estetis.
Kita ribut dengan apa yang kelihatan tetapi abai pada pesan yang
terkandung di dalamnya.
Benarkah seperti itu? Rasanya tidak juga. Karena ternyata dalam
banyak hal masyarakat kita malah cenderung mendiamkan apa yang
kelihatan dan ribut dengan yang tidak kelihatan. Mau contohnya?
Kita cenderung mendiamkan ketidakdisiplinan berlalu-lintas yang
nyata-nyata terjadi setiap hari di depan batang hidung kita dan
10 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Namun, sayang seribu sayang, dari hari ke hari kita mendapati
wilayah negara kita semakin disesaki oleh orang-orang miskin.
Mereka bukan hanya tidak punya uang tetapi kehilangan kualitas
hidup; mereka bukan hanya tidak bisa makan tetapi tidak mampu
lagi membayangkan apa yang bisa dimakan; mereka bukan hanya
putus sekolah tetapi frustrasi apakah bisa sekolah dan untuk apa
sekolah; mereka bukan hanya menjadi pengangguran tetapi tidak
mampu memperoleh pekerjaan seperti apa yang bisa dimasuki jika
semuanya sudah dikuasai jaringan koneksi orang dalam; mereka
bukan hanya menjadi preman karena desakan hidup tetapi menjadi
pilihan sadar, karena aparat negara pun sudah berlagak layaknya
preman berseragam; mereka bukan hanya kehilangan rumah tetapi
juga hak-hak atas tempat tinggal di sejumput tanah Indonesia Raya
ini; dan masih banyak ML-ML jenis ini. Kita tidak tahu harus
menghadapi situasi ini dengan cara apa. Namun, Prof. Muhammad
Yunus, peraih Nobel Ekonomi, mengatakan: "Saya ingin menjadi
murid orang-orang miskin. Mereka adalah profesor saya.”
Something was wrong. Why did my university courses not reflect
the reality of Sufiya’ life? I was angry, angry at myself, angry
at my economic department and the thousands of intelligent
professors who had not tried to address this problem and solve it
[Muhammad Yunus, Banker to the Poor, PublicAffairs 2003,
him. 48].
Oleh karena itu, ia menanggalkan seluruh prestisenya sebagai
profesor ekonomi dan berempati untuk belajar dari orang miskin di
negaranya. Hanya dengan cara itulah kemiskinan dapat dipahami
akarnya dan dicari solusinya.
\4 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
Ayat-ayat Cinta
untuk Siapa?
ada tahun 2008, ada hari libur panjang selama empat hari. Hari-
hariliburitucukup memberikan kesempatan untuk meregangkan
otot dan urat syaraf. Apalagi liburan tersebut berkaitan dengan
perayaan dua hari keagamaan, yakni Maulid Nabi Muhammad
SAW (20 Maret) dan Wafat Yesus Kristus (21 Maret). Akan tetapi,
begitulah, rupanya metabolisme tubuh sudah sedemikian terbentuk
oleh iklim kepadatan kerja dan kemacetan lalu-lintas Jakarta
sehingga rasanya tidak enak juga kalau terlalu lama berleha-leha.
Pada hari terakhir libur, hari Minggu, saya membeli koran Kompas
(Minggu, 23 Maret 2008). Sembari membalik-balik halamannya,
mata saya terpaku pada satu kolom bertajuk Kagumi Orang Muda,
Jusuf Kalla Menonton "Ayat-ayat Cinta”. Jujur saja, ketertarikan saya
membaca kolom tersebut sebenarnya lebih didorong rasa ingin tahu
apa alur cerita film itu—maklum, waktu itu tanggal tua sehingga
hasrat nonton saya belum kesampaian. Namun, setelah membaca
dua kali, saya agak menyesal karena tidak menemukan apa impresi
Wapres Jusuf Kalla (JK) mengenai alur cerita film tersebut.
Membaca kolom tersebut, saya malah menemukan beberapa
plot narasi berita yang sedikit saja kena~-mengena dengan judul
kolomnya. Saya hanya ingin mengambil tiga bagian yang menarik
untuk dicermati:
Satu. ”Wapres ingin menonton film itu karena kagum dengan anak-
anak muda yang bergiat di balik film yang mencetak rekorjumlah
penonton hingga tiga juta.” Jika dapat ditafsir, bagian ini hendak
menyatakan secara tidak langsung bahwa JK lebih terdorong
menonton film itu karena kagum dengan jumlah penonton yang
mencapai angka tiga juta, dan oleh karena itu memberi apresiasi
pada kinesja para sineas muda yang menggarapnya. Mari lihat
apa kata JK tentang itu: ’Saya terus terang kagum dengan anak-
anak muda yang ada di balik film itu. Mereka semua kreatif dan
semua berusia di bawah 35 tahun”. Substansi dan makna film
itu sendiri yang diterima JK sebagai penonton [ternyata] tidak
muncul atau direkam dalam kolom berita tersebut.
Kedua. Benarkah JK tidak memberikan impresi sama sekali atas film
18
itu? Ternyata tidak. JK tetap memberikan impresinya, dan ini
yang unik: "Ini menandakan pertumbuhan kita sedang terjadi
dan belum pernah terjadi sebelumnya setidaknya dalam 10
tahun terakhir. Ini sering luput kita lihat.” Efek dari menonton
film itu bagi JK ternyata bukan pada alur narasinya atau pesan
apa yang hendak dikomunikasikan oleh para pembuat film
itu kepada penikmatnya. Di sini ada semacam ambiguitas
pemaknaan, apakah indikator pertumbuhan [ekonomi?] negara
ini bertumpu pada tampilnya sineas-sineas muda ataukah pada
rekor angka tiga juta penontonnya. Lebih lanjut, agak naifrasanya
jika indikator kreativitas orang-orang muda hanya dipaku pada
Iman Tidak Pernah Amin
tampilnya segelintir para selebriti muda yang membentuk kelas
sosial baru dalam masyarakat kita. Pasalnya, kelas sosial baru
ini lahir dan bertumbuh dalam suatu dunia kenyamanan yang
menyediakan kepada mereka fasilitas melimpah-ruah untuk
bereksperimen dalam kreativitas yang mahal ini—apalagi
sampai mempekerjakan artis yang berwarganegara dan sudah
pasti berwajah "asing”. Sementara itu, di sebelah lain kehidupan
kita, yang luput dari penglihatan kita adalah kinerja kaum muda
progresif yang memberi makna berindonesia dengan model
kreativitas mereka sendiri, yang jauh dari sorotan lampu kamera
‘wartawan atau rekaman media massa.
Ketiga. Film ini bagi JK, melahirkan sebentuk tafsir sosial tersendiri
sebagaimana dikutip berikut ini: "Wapres mengakui, meskipun
pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 6,3 persen, kemiskinan
masih tinggi. Dengan terus tumbuhnya ckonomi, Wapres
berharap kemiskinan makin terkikis dan jumlah rakyat miskin
berkurang.” Sungguh, saya yang bodoh dalam soal ekonomi
dan hitung-hitungan matematis mikro/makroekonomi ini
merasa sesak dengan tafsir JK tersebut. Dalam pengamatan
saya, perspektif JK tersebut memperlihatkan bahwa perspektif
pembangunan kebangsaan negara ini masih dilihat dalam
kerangkakerjaevolusioner-alamidanlineardimanapertumbuhan
ekonomi yang tinggi—yang kerap menjadi indikator kemajuan
atau modernisasi—dilihat sebagai unsur yang dengan sendirinya
akan membenahi atau mendorong kemajuan pada bidang-
bidang kehidupan rakyat lainnya. Padahal, kita semua saat ini
sedang berada pada puncak kemacetan membangun kebudayaan
bangsa dan sedang mengalami degradasi kultural, jika bukan
sosial-politik, yang sedang membawa republik ini terpuruk.
Ayat-ayat Cinta untuk Siapa? 9
image
not
available
image
not
available
”ayat” menjadi ”adat” (aspek budayawi) kemanusiaan. Jika demikian
halnya, bukanlah mustahil ”ayat-ayat cinta” menggairahkan seluruh
energi sosial kita kepada ”adat-adat cinta” di mana cinta~mencintai
dalam artinya yang hakiki (ontologis - Tillich) menjadi tradisi dalam
kehidupan bersama kita di republik ini. "Ayat-ayat cinta” menjadi
kebudayaan mencinta, di mana Sang Tuhan tampil dalam gairah
cinta universal yang membongkar tembok-tembok primordialisme
dan fanatisme semu, termasuk atas nama Tuhan itu sendiri. Jadi,
Pak Wapres, menikmati "Ayat-ayat Cinta” jangan melulu dilihat
dalam grafik pertumbuhan ekonomi, karena sebagai suatu karya
seni ”Ayat-ayat Cinta” mesti disimak dalam kacamata tafsir simbolis
kebudayaan dan karenanya berpesan tentang sesuatu yang tak
terukur oleh rumus-rumus matematis. Kalau jumlah penikmat film
itu menembus angka tiga juta, itu semata-mata rakyat kita sedang
haus dengan sentuhan kebijakan penuh cinta. Rakyat sudah jenuh
dan sumpek dengan dagelan keadilan, sandiwara kemakmuran, horor
penggusuran, thriller kekerasan, dalam reality show keseharian. Kami,
rakyat Indonesia, sedang mimpi hidup dalam tatanan sosial-politik-
budaya yang penuh cinta, karena agama-agama kami memang ingin
agar kami—yang mengaku beragama—tampil sebagai para pelaku
cinta.
2 Iman Tidak Pernah Amin
4
Menjadi Indonesia:
Masihkah Realistis?
ertanyaan di atas terbuka bagi siapa saja. Tentu, banyak ragam
jawaban dan interpretasi yang akan muncul menanggapi soal ter-
sebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegelisahan untuk melanjutkan
pembangunan bangsa ini sekarang makin menguat dan menggumpal
dalam sikap fatalistis: apakah kita masih bisa terus berjalan dalam
komitmen kebangsaan yang bernama Indonesia? Kegundahan itu
bukannya tidak beralasan bila kita melihat eskalasi suhu politik
tanah air yang akhir-akhir ini semakin memanas. Banyak faktor yang
memicu munculnya gejolak tersebut. Suatu kenyataan bahwa gejolak
internal berdampak sangat signifikan bagi upaya pemulihan situasi
sosial Indonesia yang untuk sementara waktu sedang tertatih-tatih.
Kita memang sedang membangun kembali infra~ maupun
suprastruktur negara kita yang sudah terpuruk selama beberapa
tahun terakhir ini akibat disorientasi penataan sistem bernegara di
segala bidang. Tentu saja, pembangunan yang dimaksud tidak hanya
23
dalam arti fisik semata, melainkan lebih pada rekonstruksi struktur
kesadaran dan mentalitas kebangsaan yang dilandaskan pada ideologi
nasional yang disepakati bersama. Kesepakatan ideologis itulah yang
sebenarnya memberikan roh bagi eksistensi dan daya tahan hidup
suatu bangsa. Inilah sebenarnya makna hakiki dari apa yang sering
disebut nation building.
Karakter nation building itu sendiri bukanlah wahyu ilahi yang
jatuh dari surga, tetapi produk pergulatan manusia memaknai inter-
relasi dengan sesamanya dalam wujud simbol-simbol kebudayaan
tertentu. Simbol-simbol kebudayaan ini, meskipun merupakan pan-
tulan refleksi manusia universal, tetap merupakan suatu ekspresi
yang terkungkung dalam batasan-batasan berdimensi temporal.
Apalagi ketika simbol-simbol kultural tersebut mengalami proses
institusionalisasi, yang berarti ia makin memperoleh legitimasi sosial
dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain, sebagai
simbol-simbol kebudayaan, karakter tersebut tidak bersifat perenial,
tetapi selalu mengalami metamorfosis—baik secara natural maupun
artifisial. Iru semua terjadi karena setiap manusia memiliki perbedaan
persepsi mengenai eksistensi kediriannya di dalam konteks hidup
masing-masing. Jadi, manusia itu sendiri tidak bebas nilai karena
dikurung dalam "sangkar” tradisi, bahasa, kekerabatan, adat-istiadat,
religiositas, pandangan dunia, dan pengetahuannya.
Kendati demikian, manusia tidak tenggelam dalam kenisbian
kultural tersebut.Sebagai makhluk yang selalu menjadi atau berproses,
manusia terus-menerus memberi makna kepada dunianya dalam
kerangka membangun suatu peradaban yang lebih maju daripada
yang sudah ada. Oleh karena itu, manusia mesti bersosialisasi, sebab
peradaban itu sendiri mesti dibangun bersama-sama. Sosialisasi ini
merupakan lompatan keluar dari kurungan kebudayaannya untuk
berjumpa dengan mereka yang lain, yang juga melompat keluar dari
kurungan yang sama meskipun konteksnya berbeda. Pada saat itulah
4 Iman Tidak Pernah Amin
terjadi perjumpaan kreatif yang mendorong terciptanya kehidupan
baru dengan spektrum yang lebih kompleks dan berwarna-warni.
Karakter nation building adalah suatu bentuk lompatan keluar
untuk bertemu sebagai manusia-~manusia yang berkehendak secara
sadar melakukan dialog komunikatif di dalam suatu tatanan sosial
yang beradab. Implikasi pengertian ini mencuat dalam aspek eksternal
dan internal. Secara internal, tatanan sosial yang disebut masyarakat
itu secara kontinyu bergerak dengan aturan mainnya sendiri. Secara
eksternal, masyarakat itu juga meretas kebuntuan komunikasi dengan
masyarakat lainnya sehingga mereka bisa membentuk masyarakat
dengan identitas yang lebih makro. Pada titik inilah sebenarnya kita
bisa memahami makna globalisasi.
Jadi, karakter nation building itu sendiri merupakan perpaduan
dinamis antara apa yang internal dan eksternal, lokal dan global.
Fenomena itu sudah berlangsung berabad-abad, meski intensitas
globalisasi (eksternal) lebih terasa selama beberapa dekade akhir
abad ke-20 dan awal abad ke-21. Itu disebabkan oleh gebrakan
teknologi komunikasi dan informasi yang memperlancar akselerasi
relasional antarmanusia, antarbangsa, antarperadaban.
Benturan Peradaban
Prof. Samuel Huntington, guru besar ilmu politik internasional dari
Universitas Harvard, Amerika Serikat, pernah mengajukan tesis
mengenai benturan peradaban (clash of civilization). la mencermati
bahwa pasca-Perang Dingin akan terjadi suatu pergeseran besar
dalam peta kekuatan politik global yang lebih banyak dimotori
oleh perubahan-perubahan mendasar dalam kepentingan politik
internasional dari kedua negara superpower Amerika Serikat dan
Uni Soviet. Sejarah mencatat bahwa dalam dinamika hubungan
internasional yang fluktuatif dan kadang-kadang memanas, Uni
Soviet tidak mampu lagi survive dengan ideologi Marxis-Leninisme
Menjadi Indonesia: Masihkan Realistis? 25
sehingga ambruk dan terpecah menjadi negara-negara kecil yang
sampai hari ini masih terus diguncang perang saudara. Amerika
Serikat (AS), simbolisasi kekuatan kapitalisme dunia, seolah-olah
muncul sebagai pemenang. Itu juga berarti AS menjadi satu-satunya
negara adikuasa.
Kenyataan ini telah menggiring AS untuk menempatkan diri
sebagai satu-satunya negara supermodern yang paling berpengaruh
di dunia. Justru di situ soalnya: AS tidak lagi memiliki musuh
utama yang mampu menjadi rival sekaligus kontrol atas segala
kiprahnya. Dengan demikian, AS bebas menanamkan cakarnya di
segala bidang (pertahanan, ekonomi, politik, pendidikan, teknologi,
dan sebagainya). Hampir di semua negara, AS menjadi kekuatan
imperialisme baru yang menciptakan "musuh-musuh” ideologis baru
dalam suatu jejaring global.
Bagi sementara pihak, kenyataan ini menimbulkan persoalan
karena AS memberlakukan double standard: menjadi kiblat mo-
dernitas sebagai garda utama kebebasan manusia (HAM), sekaligus
kekuasaan yang represif. Pemberlakuan standar ganda ini paling
jelas tampak dari keterlibatan AS dalam konflik Palestina-Israel.
Bagi AS sendiri, sulit melepaskan citra sebagai ”pihak yang selalu
mengalah” ketika berhadapan dengan Israel yang "keras kepala”
dalam kasus ini (sudah menjadi rahasia umum bahwa posisi-
posisi vital di pemerintahan AS didominasi oleh kelompok Yahudi
perantauan). Meski sebenarnya lebih bernuansa politis, namun di
lingkungan internasional, konflik Palestina-Israel telah berkembang
secara manipulatif menjadi konflik agama (Yahudi vs Islam). Akan
tetapi, karena Yahudi secara salah kaprah selalu dikaitkan dengan
Kristen maka jadilah konflik segitiga: Yahudi—Islam—Kristen.
Pada momentum inilah, menurut saya, sedang terjadi suatu benturan
kebudayaan yang luar biasa hebatnya karena sudah mengalami bias ke
ranah paling sensitif: agama. Apakah ini yang dimaksud Huntington
sebagai benturan peradaban? Saya kurang yakin. Sebab saya percaya
26 Iman Tidak Pernah Amin
Huntington tidak akan mengabaikan konflik Inggris-Irlandia Utara
yang juga sarat dengan muatan konflik agama (Protestan vs Katolik);
atau India-Pakistan (Hindu vs Islam).
Apa yang bisa dikatakan secara singkat hanyalah bahwa
pada dasarnya tidak ada satu konflik pun yang disebabkan oleh
perbedaan agama. Seluruh konflik yang terjadi sebenarnya hanya
memperebutkan satu: KEKUASAAN. Siapa yang menguasai siapa
dan apa yang bisa dipakai untuk menguasai orang lain. Di sinilah
sebenarnya agama pada tampilan wajahnya yang lain menunjukkan
potensi dimanipulasi sebagai "senjata” untuk melumpuhkan, me-
matahkan kekuasaan pihak lain dan menguasainya. Agama telah
menjadi fenomena sosial yang sangat ideologis. Dalam wacana ini
pula, "Tuhan” sebagai Realitas Ultim-Transenden bergerak secara
antropomorfis menjadi ”panglima perang” yang memberangus
musuh-musuh-Nya (atau musuh manusia?). Betapa mengerikan bila
kekuasaan Tuhan sebagai Realitas Ultim takluk di bawah kekuasaan
manusia yang terbatas dan definit. Kalau sudah begitu, siapa yang
menjadi "tuhan”? Tuhan per se dalam misteri adikodrati-Nya atau
manusia yang menuhankan dan mentransendensikan kekuasaannya
sendiri?
Indonesia: di Persimpangan Jalan
Pasca-peristiwa 11 September 2001, ketegangan meruncing antara
AS dengan kelompok teroris [?] yang selama ini sudah beberapa
kali melakukan aksi teror dalam berbagai bentuk di AS (mungkin
juga di negara-negara lain sekutu AS). Banyak analisis yang melihat
pertautan antara aksi vandalis di World Trade Center New York dan
Markas Pentagon Washington DC dengan kekecewaan kelompok-
kelompok perjuangan nasional pembebasan Palestina atas sikap AS
yang ambivalen terhadap konflik Palestina-Israel. Ada pula yang
melihat bahwa rangkaian peristiwa teror ini tidak dapat dilepaskan
Menjadi Indonesia: Masihkan Realistis? 27
image
not
available
image
not
available
mayoritas; mereka juga tidak memilih Republik Islam” meskipun
mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, mereka memilih
nama baru “Indonesia” yang memberi ruang hidup bagi segenap
manusia dengan kekayaan ekspresi kulturalnya masing-masing. Se-
lain pluralitas, kesetaraan di antara manusianya juga dijamin secara
konsekuen. Dengan demikian, Indonesia sebagai realitas politik baru
(lahir 17 Agustus 1945) menjadi suatu tempat yang di dalamnya
perjumpaan kemanusiaan terjadi dan terus berlangsung. Sekali lagi,
ini jika kita mau tetap setia pada komitmen para pendiri bangsa ini
untuk membentuk suatu negara modern yang berwawasan humanis,
bukan sektarian atau primordial.
Indonesia seperti itu pada hakikatnya memberikan suatu ke-
longgaran bagi pendewasaan berdemokrasi yang santun tanpa
mesti terperangkap dalam segmen-segmen primordialisme yang
vulgar, Namun, kalau ternyata sepanjang perjalanan sejarahnya kita
melihat bahwa untuk menjadi bangsa yang dewasa membutuhkan
proses jatuh-bangun—sejauh itu mendorong pemerdekaan setiap
warga negara—itu harus dipacu dan dipertahankan. Sebaliknya, bila
ternyata komitmen untuk menjadi bangsa yang majemuk dengan
wawasan modern tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis yang
mengikat, dan pada akhirnya menciptakan polarisasi yang semakin
mengerucut, maka kita perlu melakukan re-visi: masih relevankah
kita menyebut diri orang Indonesia tanpa suatu keterbukaan untuk
menerima kehadiran orang lain secara setara? Atau kesadaran historis
kita sudah menjadi begitu pejal sehingga seperti orang linglung yang
lupa daratan? Atau mungkin yang lebih spesifik: masih realistiskah
untuk menjadi Indonesia?
30 Iman Tidak Pernah Amin
3
Indonesia Raya
atau
Indonesia Rawa?
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku
Disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku
Indonesia hebangsaanku, bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru Indonesia bersatu
Hiduplah tanabku, hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku, semuanya
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya
Indonesia Raya merdeka, merdeka
Tanabku, negeriku yang kucinta
Indonesia Raya merdeka, merdeka
Hiduplab Indonesia Raya
3
image
not
available
image
not
available
Jalu perhelatan akbar di Gelora Bung Karno, dengan tarian-tarian
massal dan komentar-komentar basi tentang Indonesia. Berapa biaya
yang terkuras untuk acara boong-boongan seperti itu? Tak tahulah.
Yang pasti lebih besar dari anggaran Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk orang miskin se-Jakarta Utara (soalnya, saya tinggal
di wilayah itu yang konon paling banyak MaMi-nya—maksudnya
*masyarakat miskin”). Itu memang cuma acara boong-boongan,
karena usai acara yang ”katanya” membangkitkan nasionalisme kita,
kita malah disuguhi realitas pahit bahwa para pemimpin negeri
ini sama sekali telah kehilangan roh nasionalisme. Mulut mereka
menyemburkan uap busuk nasionalisme untuk dihirup oleh rakyat
yang sudah sempoyongan sekarat.
Nasionalisme kita—setelah 100 tahun KitNas—ternyata ber-
hasil menciptakan gen sosial baru yang disebut "masyarakat miskin’.
Jika Alvin Toffler pernah mengidentifikasi gelombang perubahan dari
"masyarakat agraris” ke "masyarakat industri”, lalu peradaban Barat
melanjutkannya dengan "masyarakat teknologi”, kita di Indonesia
juga tidak mau kalah dengan menciptakan gen "masyarakat miskin”
(MaMi). Jika dulu era agraris ditinggalkan dan orang berbondong-
bondong masuk ke dunia industri, kita kini bersemangat berbondong-
bondong mendaftarkan diri sebagai masyarakat yang telah mengidap
gen MaMi. Semua rame-rame bikin kartu miskin, termasuk yang
sebenarnya tidak miskin.
Jauh sebelum gejala gen MaMi semakin tampak—dengan infus
BLI—embrionya sudah hidup dan makin meluas menghancurkan
puluhan desa, merendam habis ribuan hektar tanah pertanian,
menendang keluar penduduk yang atap rumahnya pun tak tampak
karena tercelup lumpur panas, yang hingga kini tak jelas pe-
nanganannya selain membuat tanggul yang semakin tinggi. Kini,
gen MaMi makin diformalkan sebagai identitas baru Indonesia
Raya. Nasionalisme kita memang semakin tenggelam dalam lumpur
dan rawa. Pemimpin negara berbicara sesuka hati, mengumbar
34 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
dan program-program kerja yang akan dilakukannya, tetapi tanpa
kepekaan, bisa jadi seluruh uraian programnya hanya mengawang,
tidak menggawang.
Spiritualitas Politik
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang cerdas. Itu pasti. Namun
kecerdasan tidaklah cuma terukur pada kemampuan membaca teks-
teks teori sehingga menampilkannya bak ensiklopedi berjalan, atau
pada gelar akademik yang disandang. Lebih jauh, ia juga semestinya
mampu membaca konteks secara cermat dengan kepekaan nurani
yang tajam. Kepekaan nurani tidak lahir dalam ruang-ruang kelas
kuliah di kampus-kampus atau di ruang-ruang seminar.
Kepekaan nurani lahir dari pergolakan batin yang menatap ke-
nistaan dan penderitaan manusia sebagai sebuah penghinaan bagi
kemuliaan Tuhan, Sang Pencipta. Artinya, kesadaran itu hanya
terbentuk dalam realitas ”jalanan”, di mana seluruh jejaring kompleks
aktivitas riil manusia berlangsung secara telanjang. Dalam lingkup
pemahaman demikian, eksplorasi keberagamaan menjadi salah satu
kunci utama dalam prospek kepemimpinan di republik ini.
Jika dibahasakan secara lain, seorang pemimpin semestinya
memiliki visi teologis yang membentuk seluruh konstruksi
kesadaran dan moralitasnya, sebagai pertanggungjawaban amanah
kepemimpinannya kepada rakyat dan Tuhannya. Visi teologis seorang
negarawan menjadi penting, karena melaluinya seorang pemimpin
bangsa menyadari batas-batas kekuasaannya sebagai manusia. Ini
merupakan refleksi dari kemahatakterbatasan Sang Tuhan, sehingga
ia tidak mencoba-coba menuhankan dirinya melalui eksperimentasi
kekuasaan-tanpa-batas.
Konstatasi itu tidak hendak menempatkan “agama” sekadar
kumpulan simbol-simbol khusus atau ritual-ritual tertentu, tetapi
menaruhnya dalam bingkai sistem nilai dan rujukan moralitas yang
38 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
dalamnya setiap warga negara merasa hidup di dalamnya dan meng-
hidupi Pancasila itu sendiri.
Pancasila memang bukan ”agama’” dalam arti tradisional. Akan
tetapi, Pancasila tentu sah-sah saja jika diperlakukan sebagai sebuah
kredo politik sejauh urgensinya diletakkan secara proporsional.
Artinya, konteks kemajemukan Indonesia tentu tidak bisa hanya
direduksi pada rujukan sistem nilai primordial budaya atau agama
tertentu saja.
Indonesia dihidupi oleh kemajemukannya, dan itu berarti di-
butuhkan sebuah kesepakatan nilai-nilai berbangsa yang memberi
ruang bagi setiap orang tanpa tersekat dalam ikatan primordialnya,
untuk berekspresi secara santun dan cerdas. Setiap orang berhak
memberi makna dalam gerak "menjadi Indonesia”. Dengan de-
milian, Indonesia sebenarnya sclalu berada dalam proses menjadi,
dan belum usai.
42 Iman Tidak Pernah Amin
Ke Sekolah -
Ke Mana?
ada pertengahan tahun 2008, kami mengantar anak kami
Kainalu untuk mencari sekolahnya yang baru. Tersisa beberapa
bulan ke depan, Kainalu menghabiskan kegiatan bermain dan
belajamnya di jenjang taman kanak-kanak (TK). Pihak TK sudah
mengundang rapat orangtua murid untuk membicarakan tahap akhir
kegiatan "mabel” (main-belajar) dan sudah menyepakati soal waktu
dan tempat perpisahan. Mengingat waktu yang terus bergulir, kami
mempertimbangkan untuk segera mencari sekolah dasar sebelum
masa pendaftaran murid baru ditutup.
Ini soal yang gampang-gampang susah. Gampang, karena
banyak sekolah yang bertebaran di sekitar kompleks rumah kami.
Susah, karena dalam menentukan pilihan kami mempunyai standar
tertentu sehingga dari yang banyak itu kami harus memilih mana
yang—menurut kami, orangtua—cocok untuk Kainalu. Maklumlah,
mendengar dan menyimak berita-berita yang beredar tentang ma-
43
raknya tindakan kekerasan terbuka/terselubung di sekolah-sekolah,
baik oleh para guru maupun teman-teman sebaya, membuat kami
benar-benar harus selektif. Selain itu, faktor yang tidak bisa diabaikan
ialah pertimbangan mutu sekolah itu sendiri. Masalah dana tentu
juga diperhitungkan, tetapi untuk sementara mesti diabaikan karena
di mana lagi sih di Jakarta ini bisa mendapatkan sekolah yang di
dalamnya uang pendaftarannya murah tetapi bermutu? Rasanya
sudah dimaklumi oleh publik bahwa yang murah itu selalu identik
dengan murahan, dan mahal itu sudah pasti bermutu. Meskipun
saya sendiri menganggapnya nisbi, karena saya mengakui bahwa
ukuran-ukuran sumir semacam itu tetap perlu diuji kesahihannya.
Akan tetapi, lagi-lagi, kami harus tunduk pada hukum sosial bahwa
citra yang berkembang atau dikembangkan oleh khalayak itulah
yang cenderung menjadi ukuran.
Sekelumit pengalaman itu tiba-tiba menyentakkan kesadaran
dalam diri saya, betapa sulitnya orangtua saya dahulu ketika harus
mencari sekolah yang baru. Untunglah, pada masa saya masih
bersekolah dasar di Malang, jarak antara rumah-sekolah tidak terlalu
jauh sehingga dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki atau
bersepeda. Lalu lintas kota pun tak terlalu sibuk sehingga tidak terlalu
mengkhawatirkan orangtua kami. Yang cukup meringankan, saya
kira, adalah pertimbangan soal mutu "sekolah negeri” dan "sekolah
swasta” yang tidak terlampau mencolok sehingga orangtua kami pun
tidak terlalu ekstrem dalam menentukan pilihan. Meskipun, saya
tahu, faktor itu pun tak luput dari perhitungan mereka. Siapa sih
orangtua yang mau melihat anaknya dididik dalam sebuah lembaga
pendidikan yang tak jelas program dan output-nya? Sekarang, itulah
yang kami rasakan.
Kalau dulu, saya melihat sekolah tak lebih dari suatu mekanisme
alamiah yang mesti dilakukan dalam perkembangan hidup seseorang
sejak ia masih anak hingga mencapai jenjang usia dewasa. Namun,
seiring dengan berjalannya waktu serta tempaan pengalaman, saya
Ah Iman Tidak Pernah Amin
makin menyadari bahwa sekolah bukanlah melulu "mekanisme’”,
melainkan tanda "organisme” yang berproses dalam pembentukan
jati diri dan karakter. Jika dulu sekolah hanya saya pahami sebagai
pengasahan kemampuan berpikir kognitif, kini saya sadar bahwa
saya keliru. Sekolah bukan tempat berpikir” semata, melainkan
suatu sistem pembentukan karakter yang utuh dari setiap anak.
Keprihatinan terhadap semakin sulitnya mencari sekolah yang
bermutu—dalam kategori characters building—itulah yang membuat
kami merasa harus semakin jeli dalam menentukan pilihan sekolah
bagi anak kami. Mutu suatu sekolah tentu tidak hanya diukur dari
ketersediaan fasilitas yang wah”, tetapi juga pada visi-misi sckolah
tersebut. Selain itu, kapasitas gurunya pun mesti teruji, bukan dengan
sederet gelar di depan dan/atau di belakang namanya, melainkan
dari kemampuan mereka menjadi teladan yang pada gilirannya turut
menanamkan suatu citra model pemimpin yang ideal bagi anak
didik.
Persoalan keteladanan ini tidak bisa dianggap basi karena bagi
saya itulah esensi dari sekolah. Saya tidak bisa membayangkan diri
saya seperti sekarang ini jika sejak jenjang SD hingga perguruan
tinggi hanya dicekoki dengan seabrek ilmu, tanpa merujuk pada
karakter kepemimpinan yang diperlihatkan oleh guru-guru saya—
hanya berlomba membentuk manusia yang otaknya pintar, tetapi
kepribadiannya rapuh. Dengan segala plus-minusnya, saya tetap
respek terhadap pola pembentukan disiplin diri melalui upacara
bendera setiap hari Senin; pemeriksaan rambut dan kuku; sepatu
sekolah yang harus sama warna dan merek—supaya yang kaya
tidak perlu pamer dan yang miskin tidak harus minder; buku-buku
harus disampul dengan kertas berwarna coklat; mengikuti kegiatan
pramuka untuk mengasah solidaritas dan keterampilan survive di
tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Wah, masih banyak lagi.
Bernostalgia memang mengasyikkan. Namun, kini saya tak
punya cukup waktu untuk melakukannya. Zaman sudah berubah.
Ke Sekolah - Ke Mana? 45
Saya kini mempunyai anak yang harus melanjutkan sekolahnya
di tengah krisis karakter yang melanda sekolah-sekolah kita. Saya
tidak hendak menimpakan semua kesalahan di pundak para guru,
karena mereka juga bergelut di tengah impitan hidup yang makin
susah. Ingin membela murid malah dituduh membocorkan soal.
Ingin menanamkan disiplin dituding melakukan kekerasan. Ingin
membantu siswa dianggap mencari tambahan yang tidak pantas.
Macam-macamlah. Padahal, berapa sib penghasilan seorang guru
sekarang? Apalagi dengan kenaikan harga barang-barang yang jauh
dari penghargaan kepada manusia.
Tak heran jika sekolah kita kini semakin kedodoran dalam
pembinaan dan penguatan karakter anak didik. Idealisme ’pahlawan
tanpa tanda jasa” sudah tidak laku lagi di tengah-tengah tuntutan
hidup zaman sekarang. Mau apa dengan model ”pahlawan” seperti
itu, kalau ternyata yang diclu-clukan sebagai ”pahlawan” sekarang
adalah orang-orang yang menuntut jasa besar alias uang upeti? Lihat
saja, mister-mister yang duduk nyaman di Senayan yang "atas nama
rakyat” berkoar-koar mengaku pahlawan pembela rakyat. Apakah
mereka mau melakukan tugas-tugas mewakili rakyat tanpa "tanda
jasa”?
Masih kental dalam ingatan saya, ketika pada suatu waktu, saya
dan istri saya, Nancy, menjadi fasilitator dan narasumber dalam
kegiatan Retret Guru-guru Kristen se-Kecamatan Jatinegara. Saya
menyaksikan betapa tangguhnya manusia-manusia yang mengabdi-
kan dan mendedikasikan hidupnya menjadi guru. Kami menyebut
mereka manusia tangguh—rasanya lebih pas ketimbang pahlawan
tanpa tanda jasa—karena dalam segala keterbatasan mereka, baik
yang tidak disengaja maupun disengaja, mereka tetap bersedia
menjalani panggilan tugas ini. Belum lagi harus menangani berbagai
persoalan di dalam keluarga mereka sendiri.
Dalam hati kecil, kami tetap bermimpi bahwa dengan terus
bersekolah Kainalu dapat menimba banyak pengalaman dan terus-
46 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
topi untuk Guus Hiddink yang memoles Rusia hingga mampu
menggilas Belanda 3-1 dengan 2 gol yang dicetak pada injury time.
Padahal Belanda masuk ke perempat final sebagai juara grup yang
tak terkalahkan. Mentalitas tempur ”beruang kutub” yang luar biasa.
Menikmati sepak bola tanpa ikatan emosional sebagai fans ternyata
menyuguhkan kenikmatan tersendiri.
Namun, apa yang selalu menjadi perhatian saya setiap kali me-
nonton tayangan Euro 2008 justru adalah sebuah papan iklan di
pinggir lapangan. Papan iklan? Ya, papan iklan bertuliskan "NO TO.
RACISM”. Ungkapan itu cukup menggelitik karena dipasang di
pinggir lapangan sepak bola yang dapat dilihat oleh semua penonton
distadion maupun tertangkap semua kamera televisi. Tentu ungkapan
itu bukan sekadar iklan produk barang. Ungkapan itu merupakan
suatu produk ideologie dan historis dalam pergulatan bangea-bangea
di Eropa selama berabad-abad. Membaca sejenak scjarah Eropa,
saya dicengangkan oleh begitu banyak warisan ideologis yang
menghancurkan sebagian komunitas manusia. Ideologi ras memang
pernah berjaya di daratan Eropa dengan dampak menghancurkan
yang luar biasa,
Perasaan unggul atausuperior sebagai peninggalan Enlightenment
telah membawa ras Eropa (Barat) pada puncak arogansi kultural
dengan implikasi lahirnya berbagai bentuk diskriminasi terhadap
kelompok-kelompok marjinal yang ”bukan putih” dan ”bukan Eropa
(Barat)”. Dan, celakanya, agama pun (baca: gereja) terjerembab
dalam lumpur diskriminasi ras yang mengerikan. Gereja menjadi
sarana legitimasi teologis yang memberikan pembenaran terhadap
superioritas sekelompok manusia berdasarkan rasnya. Sikap gereja
tersebut telah menimbulkan kekecewaan mendalam bagi sebagian
kalangan masyarakat Eropa, sehingga mereka menjadi apatis
terhadap gereja. Bahkan rasionalisme telah membawa kebanyakan
orang Eropa menjadi anti-agama atau anti-gereja. Gereja bagi me-
reka telah menjadi tempat berkubang orang-orang oportunis yang
50 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
para pejabat negeri ini. Kejenuhan yang tidak terorganisasi itu akan
meledak dalam tindakan-tindakan anarkis suporter sepak bola yang
tidak melihat sepak bola sebagai spiritualitas baru untuk keluar dari
kemacetan berpolitik dan berdialog secara terbuka dan sportif.
Saya teringat pada perjalanan bersama keluarga Ulis Tahamata-
Sapulete—adik Simon Tahamata pemain Ajax Amsterdam era
1970-an—berkeliling sehari di stadion ArenA Amsterdam, yang
juga disebut The World of Ajax. Suatu pengelolaan organisasi yang
nyaris sempurna, yang memperhitungkan setiap detail sehingga
sepak bola tidak lagi menjadi sekadar olahraga tetapi bisnis raksasa
yang semakin gemerlap. Lihat saja, misalnya, untuk menghindari
bentrokan antarsuporter, stadion ArenA mempunyai fasilitas yang
menghubungkan tempat duduk suporter tamu secara langsung
dengan akses keluar ke stasiun kereta api. Masuk ke kabin, para
investor seperti berada dalam kamar hotel bintang lima. Di kabin
inilah mereka membicarakan masa depan klub, advertising, transfer
pemain, pelatih, dan sebagainya. Di bawah lapangan rumput, sistem
pengairan sudah diinstalasi sehingga rumput lapangan tidak perlu
disiram air dari atas. Wow, masih banyak lagi hal yang terlalu
fantastis bagi saya yang kampungan ini. Namun, fo/ saya tetap orang
Indonesia yang bermimpi bahwa Indonesia suatu saat akan berjaya
di lapangan rumput internasional. Atau, saya cuma bangga dengan
rumput sendiri? Walahualam....
4 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Jadi, di manakah sebenarnya batasan fungsi dan tugas antara
”polisi” pamong praja dan "polisi” Republik Indonesia? Jika istilah
”polisi” dapat dimaknai sebagai ”mengamankan folicy” dari pihak pe-
merintah, tidak cukupkah kesatuan Polisi Republik Indonesia untuk
melakukannya? Padahal, pemisahan Polri dan TNI, pada hemat
saya, sudah cukup memberikan ruang bagi polisi untuk melakukan
capacity building dan ekspansi kewenangannya pada aspek-aspek
sipil dan non-militeristik. To, faktanya pemerintah kita masih
membutuhkan "polisi” yang lain—polisi pamong praja.
Ketidakjelasan fungsi dan tugas di antara dua unsur "polisi”
tersebut nyata dalam komentar seorang aparat polisi (Polri) ketika
diwawancarai oleh reporter salah satu stasiun televisi. Dengan
entengnya, ia menjawab "tidak tahu”. Padahal, setiap aksi penertiban
(baca: penggusuran) oleh Satpol PP selalu harus didampingi oleh
kesatuan Polri untuk mengantisipasi bentrokan dengan pihak yang
menolak digusur. Respons seadanya tersebut mengindikasikan
dengan jelas bahwa tidak ada koordinasi di antara dua instansi
”polisi” tersebut. Ataukah ada suatu koordinasi "pembiaran’?
Bukan tidak mungkin terjadi proses pembiaran atau cuci
tangan supaya mereka tidak kecipratan getahnya. Mahasiswa yang
ingin berdemonstrasi saja harus memiliki izin dan dikawal; bagai-
mana mungkin suatu peristiwa yang rentan terhadap bentrokan
antarkelompok masyarakat tidak diketahui dan diantisipasi dengan
pengawalan?
Kebijakan pemerintah kota untuk menertibkan sejumlah ka-
wasan tentu sudah menjadi kewajibannya, meskipun hal tersebut
sering kali dilakukan secara tidak manusiawi. Namun, kalau sudah
sampai ke tingkat tawuran yang disasarkan pada satu gedung yang
merepresentasikan eksistensi dan privasi suatu organisasi—yang tak
ada sangkut-paut langsung dengan aksi penertiban—tentu sudah
soal lain. Apa pun alasannya, kantor PGI adalah aset organisasi
keagamaan yang sama vitalnya dengan kantor-kantor organisasi
58 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Namun, mengapa begitu sampai pada isu perempuan yang
menjadi “babu” di tanah orang—lalu mengalami penindasan dan
pemerkosaan—seolah-olah hanya sebuah berita yang biasa-biasa
saja? Sangat berbeda dengan sikap dan militansi perlawanan kita
terhadap isu ”Palestina”, ”korupsi”, atau "pornografi”. Bukan berarti
itu tidak penting. Akan tetapi, sungguh bebal jika kita melayangkan
pandangan kita dan berkoar-koar meneriakkan keadilan dan
kemanusiaan terhadap sesuatu yang jauh di sana; sementara pada saat
yang sama kita juga menyadari bahwa kehidupan dan kemanusiaan
perempuan-perempuan Indonesia—mungkin ibu kita, mungkin
saudara perempuan kita, mungkin istri kita—dicabik-cabik oleh
angkara syahwat para majikan sonfoloyo di negara lain. Jangan bicara
keadilan, jangan bicara agama, jangan bicara kesejahteraan, jangan
bicara martabat bangsa. Semua itu hanya uap mulut yang berbau
busuk karena bangsa lain tetap akan melihat kita sebagai "kacung”
dan "babu” yang hanya mampu menghibur diri dengan kemolekan
kampungan, tetapi tetap mau diinjak-injak sebagai keset bangsa lain.
Martabat bangsa kita sesungguhnya tidaklah terletak pada diplomasi
licin para elite politik, atau pesona basi para pejabat negara, atau debat
palsu undang-undang negara yang sarat manipulasi kepentingan
jabatan dan uang. Martabat bangsa kita ini sesungguhnya terletak
pada kaum tangguh dan rentan yang kita panggil ”perempuan’.
Yesus dan Perempuan Samaria
Saya teringat cerita dalam Injil Yohanes 4:1-42 tentang percakapan
Yesus dengan perempuan Samaria. Sebuah perikop yang cukup
panjang, yang menarasikan dialog Yesus dan perempuan itu.
Perempuan itu tak bernama. Identitasnya hanya ditentukan oleh
representasi lokalitasnya—Samaria. Sungguh ironis, bahkan dalam
Injil-injil pun, banyak perempuan yang tak bernama. Padahal
mereka sering disebutkan sebagai orang-orang tangguh yang
62 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
: _BAGIAN I! | Hl |
BERAGAMA TAM
INDONESIAKU
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Teologi AIDS, Thealogia Religionum
HIV/AIDS tentu bukan masalah satu agama saja, tetapi masalah
kemanusiaan universal. Sebagai yang demikian, agama-agama tidak
bisa tinggal diam. Ada beberapa alasan mengapa agama-agama
sangat berperan penting dalam memerangi HIV/AIDS: (1) agama-
agama memiliki mandat spiritual; (2) agama-agama berjangkauan
luas lintas kategorisasi sosial; (3) agama-agama memiliki tradisi
keterlibatan komunitas; (4) agama-agama memiliki daya tahan
yang lama. Mandat spiritual merupakan alasan pertama dan utama
karena menyangkut teologi suatu agama. Kontribusi signifikan
agama-agama dalam konteks HIV/AIDS hanya dapat terjadi ketika
teologinya mampu membuka perspektif religiositas sebagai bagian
dari pergumulan sosial. Oleh karena itu, memang dibutuhkan suatu
reinterpretasi teologis secara kontckstual dalam menyikapi realitas
penderitaan kemanusiaan yang disebabkan HIV/AIDS.
Tidaklah berlebihan jika dalam konteks HIV/AIDS agama-
agama perlu merumuskan ulang secara bersama-sama Teologi
AIDS sebagai bagian dari matra teologi agama-agama (theologia
religionum). Axrtinya, setiap komunitas beragama terbuka untuk
menggali kembali nilai-nilai teologis dan moralitas dalam perspektif
yang bersifat relasional, bukan lagi doktrinal. Dari sanalah pertautan
relasi agama-agama tidak lagi terperangkap dalam perdebatan "siapa
yang paling benar’, tetapi bersama-sama menemukan kebenaran
transendental yang saling menghidupkan. Tidak lagi terjerat pada
argumentasi "keselamatan surgawi”, tetapi bersama-sama membuka
diri dalam sebuah gerak menyelamatkan "sejarah” masa depan ke-
manusiaan.
Jadi, berdasar keempat alasan esensial tersebut, agama-agama
diharapkan mampu membangun suatu kesadaran dan sikap kritis
yang lahir dari pendasaran teologis yang kokoh. Dimulai dari proses
penyadaran komunitasnya sendiri dalam menyikapi HIV/AIDS,
2 Iman Tidak Pernah Amin
image
not
available
image
not
available
image
not
available
image
not
available
image
not
available
image
not
available
image
not
available
13
Beragama yang
Repot
Px; suatu pagi di bulan Juni 2008, perjalanan saya ke kantor
terhambat karena iring-iringan sepeda motor dan bus metro-
mini yang mengangkut orang-orang yang akan berunjuk rasa di
Monas. Saya tidak tahu mereka dari kelompok mana. Hanya jelas
terbaca tulisan-tulisan pada spanduk-spanduk yang dibentangkan
dan kertas-kertas kecil yang ditempelkan di kaca depan bus
metromini. Tulisannya singkat: "Bubarkan Ahmadiyah! Bebaskan
Habieb Rizieq!” Semua pengunjuk rasa mengenakan pakaian putih-
putih. Dari tulisan itu jelas bahwa kelompok ini terkait atau sengaja
mengaitkan diri dengan insiden kekerasan pada 1 Juni 2008 di Monas.
Aksi kekerasan dilakukan tepat pada hari lahirnya Pancasila.
Pada hari itu, saya masih menyempatkan diri mengintip sejenak
weblog untuk membaca peristiwa apa yang pernah terjadi di dunia
ini pada suatu waktu dan tempat. Saya terkesan dengan kutipan hari
ini dari ucapan Anna Sewell (1820-1878), seorang penulis Inggris,
80
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Dekonstruksi kitab suci, menurut saya, harus dilakukan secara
konsisten. Dekonstruksi di sini tidak dalam arti desakralisasi
sebagaimana yang ingin dilakukan oleh kaum humanis. Tidak.
Agama tetap membutuhkan sebuah landasan tradisi yang menjadi
dasar eksistensinya dalam berbagai perubahan yang terjadi saat
ini. Dekonstruksi yang saya maksud adalah suatu keterbukaan
dan keberanian untuk membaca dan menafsir kitab suci bukan
sebagai "kata-kata Allah”, melainkan sebagai refleksi iman orang-
orang yang menuliskan kitab-kitab dalam kitab suci. Orang-orang
tersebut adalah manusia biasa yang berpikir, bertutur, bertindak,
sesuai dengan pola pikir budaya mereka. Sementara itu, kita yang
hidup dalam konteks yang berbeda dengan mereka mempunyai pola
pikir budaya yang jauh berbeda. Dekonstruksi interpretatif terhadap
teles-teks kitab euci diperlukan agar kita justru menemukan esensi
kemanusiaan dalam kitab suci. Kita tidak terpesona terhadap Allah”,
tetapi melupakan pesona ”kemanusiaan” kita. Allah hanya mewujud
secara paripurna ketika kita mengakui bahwa kita perlu menjaga
keutuhan kemanusiaan bersama.
NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Katolik, Protestan, Buddha
Mahayana, Hindu, Konghucu, Kakehan, Aluk Todolo, Kejawen, dan
sebagainya, merupakan penampakan dari kreativitas kemanusiaan
dalam mencerap Sang Misteri. Apakah Sang Misteri itu mampu
dikenal secara paripurna? Tentu tidak. Yang bisa kita tangkap paling-
paling hanyalah bayangan kebesaran-Nya atau sepercik kemuliaan-
Nya saja. Bayangan kebesaran dan percik kemuliaan Sang Misteri itu
dalam arti sepenuhnya dapat kita temukan dalam suatu re/ational-
faith (iman yang membangun relasi) antarmanusia. Relational-faith
adalah kesadaran beriman untuk menempatkan sang /iyan dalam
relasi "Aku-Engkau” (J-¢hou), bukan "Aku-Benda” (I-it), seperti
yang dikatakan oleh filsuf Martin Buber. Bagaimana mungkin
saya memahami Sang Misteri atau Allah jika pada saat yang sama
saya mengabaikan manusia yang lain? Bagaimana mungkin saya
84 Iman Tidak Pernah Amin
mengasihi manusia jika saya tidak menyadari bahwa Sang Misteri
itu hidup dalam hubungan-hubungan kemanusiaan yang utuh di
bumi ini? Bagaimanakah iman saya menjadi bermakna jika tindakan
saya justru merendahkan dan melecehkan Allah, dengan cara-cara
yang kita imani tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah itu, yang penuh
rahmat bagi seluruh ciptaan?
Relational-faith adalah suatu pengakuan bahwa tidak ada satu
agama pun yang berasal dari surga atau nirwana. Agama hanyalah
konstruksi kontekstual teologis manusia. Dengan kesadaran itu,
"beragama” adalah sebuah cita-cita untuk memulihkan harkat dan
martabat kemanusiaan sebagai imago Dei. Jika beragama hanyalah
suatu kosmetik kesalehan dengan polesan hipokrisi, beragama
seperti itu justru menghina kemuliaan Sang Misteri. Jika beragama
hanya berujung pada penghancuran imago Dei, justru di situlah
letak kesesatan beragama, yakni agama direduksi menjadi "senjata”
untuk menghancurkan kemanusiaan orang lain. Jika beragama
hanya menumbuhkan arogansi dan prasangka yang mengarah pada
penghakiman orang lain, beragama semacam itu tidak lebih dari
kemaksiatan dan mencabuli kemuliaan Sang Misteri dengan nafsu-
nafsu egoisme sendiri.
Jadi beragama seperti apa yang sekarang hendak kita pamer-
kan?
Beragama yang Repot = 85
14
Oprah Menyangkal
Yesus— So What?
eorang teman saya pernah meneruskan e-mail yang berisi tulisan
bertajuk "Oprah Menyangkal Yesus”. Tulisan itu lebih kurang
berisi tentang pandangan sejumlah orang terhadap pendapat-
pendapat Oprah di berbagai media, termasuk Oprah Winfrey Show.
Sebenarnya saya agak malas membaca dan menanggapinya, tetapi
setelah melihat beberapa komentar yang masuk, saya jadi terusik juga
untuk ikut nimbrung. Ini bukan analisis panjang lebar, melainkan
semacam pandangan pribadi yang ringkas atas tulisan itu.
Kadang-kadang saya jadi berpikir betapa egoisnya keberaga-
maan kita sampai-sampai Yesus pun kita klaim sebagai milik kita
saja dan seluruh pemahaman tentang Yesus hanya boleh dilakukan
oleh "kita”. Interpretasi terhadap siapa Yesus itu sudah berkembang
selama ribuan tahun dengan beraneka corak media—mulai dari yang
tradisional sampai yang "net-nct”-an.
86
Soal Oprah menyangkali Yesus—menurut saya—itu hanyalah
bentuk ketidakpahaman kita terhadap perspektif kristologis Oprah.
Perspektif kita sendiri tentang Yesus juga tak luput dari keterbatasan
kita dalam menafsir siapa Yesus. Kalau kita mengklaim "Oprah
menyangkal Yesus”, "Yesus”-nya kita sendiri apakah memang sudah
(paling] benar? Lalu, kalau kita bilang "paling benar”, dari mana
sumberkebenaran” itu sendiri? Dari Alkitab? Lha, kita sendiri sudah
mafhum bahwa Alkitab adalah sebuah produk tafsir manusia yang
berlangsung dalam sejarah peradaban manusia yang cukup panjang.
Dari ajaran Kristen? Kristen yang mana dulu? Lha, sekarang ini
tidak kurang banyak pihak yang menyebut dirinya Kristen dengan
versi yang berbeda-beda.
Jika Oprah menyatakan pendapatnya seperti itu—entah mau
dikategorikan sebagai new age atau apa saja—mari kita melihatnya
sebagai berubahnya mindset seseorang yang dipengaruhi oleh
*pengalaman-pengalaman” hidupnya. Bukankah di dalam ”penga-
laman-pengalaman” hidup itu seseorang—baik Oprah maupun
kita—sebenarnya sedang berada dalam pencarian "kehendak”
Tuhan? Kita tidak sedang mencari Tuhan, karena untuk apa Tuhan
dicari? Saya tidak melihat Tuhan sebagai "sosok” yang "duduk manis
di singgasana surga yang nyaman, adem, hening”. Saya—mengikuti
John Robinson dalam Honest to God dan Paul Tillich dalam Courage
To Be—lebih melihat Tuhan sebagai The Ground of our being.” Dia”
tidak ada di luar pengalaman manusia. Dia hidup dan menjelajah
di dalam pengalaman-pengalaman kemanusiaan. Dalam hal ini,
saya lebih cenderung pada John Cobb, Jr. yang merumuskan teologi
proses. Cobb sendiri sangat dipengaruhi oleh filsuf Alfred North
Whitehead yang memperkenalkan filsafat proses—yang berakar
dalam pandangan filsafat Yunani klasik eyang Herakleitos dengan
gagasan panta-rei: semua mengalir.
Kalau kita membekukan Oprah dalam freezer teologis kita
sendiri, saya melihat ini justru memperlihatkan keengganan kita
Oprah Menyangkal Yesus—So What? 87
image
not
available
image
not
available
image
not
available
image
not
available
Kendati ada keinginan berdiskusi dengan MK, hingga ke-
pergiannya menjumpai Sang Tuhan yang diempukannya, saya belum
pernah sekali pun mendapatkan kesempatan itu. Yah, sudahlah.
Namun, saya makin menyadari makna pepatah "gajah mati me-
ninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”—betapa
pentingnya meninggalkan "warisan” pemikiran yang terartikulasi
dalam wujud buku.Tanpa fisik MK, saya ternyata menjumpai dirinya
dalam kritik-kritiknya, diksi-diksinya, yang cerdas dalam bukunya—
dan ternyata MK tetap “hidup”.
Perempuan 3D
MK menyadari bahwa ketika ia berteologi, ia selalu akan berada
dalam daya gravitasi tiga dimensi (3D): Asia-Kristen-Perempuan.
Pada titik itulah MK melakukan petualangan-petualangan teologis
yang liar dan keluar dari pakem-pakem (mainstream) tradisional,
baik dalam dunia teologi maupun sastra. Perspektif 3D itu pula yang
membuat feminisme MK menjadi kontekstual dan menggairahkan.
Feminisme MK "garang” bukan karena dielaborasi dalam theoretical
framework yang Barat; melainkan karena dengan berani membedah
"kanker” kebisuan dalam ranah kultural perempuan pada tiga
dimensi itu.
Tidak sulit mencari perempuan Asia-Kristen yang pintar
dan bergelar, tetapi menurut saya sulit mencari Perempuan-Asia-
Kristen setangguh MK. Ja tangguh bukan karena mampu menguasai
10 bahasa asing, tetapi karena ia menyelami hidupnya dengan
petualangan-petualangan intelektual lintas budaya. Ia tangguh
bukan karena pernah belajar dan berkarya di luar negeri, tetapi ia
menghayati identitasnya sebagai perempuan serta memberi makna
”yang lain” (others) di tengah-tengah wacana identitas multikultural.
Dia tangguh karena memilih menjadi dirinya sendiri, perempuan
92 Iman Tidak Pernah Amin
merdeka yang menolak dideterminasi oleh ”gelar” dan "status
sosial”.
Mengenang MK dengan seluruh sepak-terjangnya di dunia
feminisme global pada saat yang sama adalah juga mengajukan
pertanyaan: ke mana arah feminisme (teologi Kristen) Indonesia?
Saya tahu bahwa banyak teologiwati Indonesia—beraliran feminisme
radikal—yang cukup garang menyuarakan kritik sosial terhadap
penindasan perempuan dalam arti luas.
Sayangnya,menurut saya, mereka lebih banyak tenggelam dalam
retorika teologis yang tidak berakar pada gulatan-gulatan lumpur
Indonesia. Bacaan-bacaan mereka "berat”, tetapi "kurus” dalam eks-
plorasi keperempuanan yang ”menyentuh dan membebaskan”. Pen-
dapat-pendapat mereka kritis, tetapi dengan mudah ditepis karena
tidak dibangun di atas kerangka epistemologis yang andal. Banyak
yang merujuk feminis-feminis Barat, tetapi terpuruk ketika mesti
menyebut perempuan-perempuan biasa di tanah sendiri, padahal
mereka juga melakukan banyak hal yang luar biasa.
Saya mendengar bahwa PERSETIA bekerja sama dengan Pusat
Studi Feminis (PSF) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)
Yogyakarta dalam merealisasikan penulisan buku teologi feminis
Indonesia yang disaring dari sekolah-sekolah teologi di Indonesia.
Mungkin inilah waktunya untuk mengerahkan dan mengarahkan
energi perempuan 3D dalam kurikulum sekolah-sekolah teologi di
Indonesia. Marianne Katoppo, perempuan 3D itu, telah pergi. Akan
tetapi, saya, laki-laki biasa, percaya bahwa kerangka feminisme
MK dapat menjadi spektrum yang menerobos kebekuan dan
kekeluan teologis dalam kurikulum sekolah-sekolah teologi ketika
mesti berbicara tentang perempuan. Saya, laki-laki biasa, berharap
momentum wacana teologi feminis oleh PERSETIA dan UKDW
Yogyakarta dapat menjadi proses lingkaran hermeneutis yang
mengajak setiap orang—perempuan dan laki-laki— "tersentuh dan
bebas”.
Mencari yang Tersentuh dan Bebas 93
image
not
available
harus bermuara pada agree for disagree. Toh, itu juga merupakan
sebuah kekayaan dalam spiritualitas ber-Tuhan (teisme).
Entah mengapa, saat menyaksikan tayangan berita mengenai
gelombang protes terhadap film Fitna karya Geert Wilders, saya
jadi teringat sahabat saya itu. Dulu, kami sering berdebat sengit,
bahkan saling melancarkan kritik. Namun, dalam kritik, ternyata
saya tidak hanya semakin mencintai iman kristiani saya, tetapi juga
semakin menghayati iman islami sahabat saya itu. Demikian juga
sebaliknya. Ia menyimpan sajadahnya di kamar saya supaya ia bisa
tetap melaksanakan sholat jika sedang berada di situ. Ketika kami
berpisah, barang yang saya minta darinya sebagai kenang-kenangan
adalah sajadahnya itu.
Saya tidak ingin mengomentari soal film Fitna, karena sudah
banyak kajian kritis yang diarahkan terhadap film itu, termasuk
mengenai Geert Wilders sendiri. Saya justru tertarik untuk melihat
bahwa kedangkalan Wilders dalam memahami Alquran justru
bermula dari kedangkalannya memahami Alkitab (tentu, jika sampai
saat ini ia masih mengaku ”Kristen”).
Iman yang Mencari Pengertian
Memahami dan menghayati Alquran dan Alkitab (juga kitab-kitab
suci lainnya) tidak bisa dilakukan dalam suatu kerangka pengertian
yang sains-ilmiah. Dalam ranah religiositas, iman tidaklah bermula
dari pengetahuan melainkan dari pengalaman-pengalamanadikodrati
yang mengangkat eksistensi manusia ke suatu suasana batiniah yang
transendental. Pada titik itulah manusia mengkreasi simbol-simbol
alamiah dalam pertautan eksistensial dengan kehadiran Sang Tuhan
(omnipresence). Tuhan hadir dalam segalanya, tetapi segalanya tidak
bisa dituhankan. Tuhan menampak dalam guntur, kilat, petir, badai,
tetapi juga dalam keheningan, semilir angin sepoi-sepoi. Keagungan
Tuhan disimbolisasikan seperti burung rajawali yang mampu terbang
Lectio Divina 95
di antara gunung-gunung batu, tetapi juga dipahami sebagai yang
tak bernama—Aku adalah Aku!
Alkitab (dan juga kitab-kitab suci lainnya) merupakan buku
yang sarat dengan simbol—bentuk huruf, kata, kalimat, ungkapan,
intonasi, alegori, dan sebagainya. Membaca Alkitab (dan kitab-kitab
suci lainnya) serta-merta adalah membaca simbol dan menafsir
makna. Simbol itu sendiri bukanlah suatu entitas linguistik yang
baku dan kaku, melainkan terbuka dan dinamis sehingga ketika
dibaca akan membuka ranah tafsir yang luas dan multibentuk.
Terlepas dari kepentingan apa yang melatari Geert Wilders
membuat dan menyebarluaskan film Fitna, tetapi Wilders sudah
memberi contoh bagaimana Alquran sebagai simbol keberimanan
yang menjadi hakikat religiositas keislaman telah ditekuk hanya
menjadi bacaan picisan. "Kekerasan” adalah suatu bahasa simbolik
dari ambisi manusia untuk berkuasa dengan mengabaikan hidup
orang lain. Wilders rupanya sengaja lupa [atau memang tidak
tahu karena tak tuntas membaca Alkitab] bahwa di dalam Alkitab
juga sarat dengan kisah dan anjuran berjiwa kekerasan. Bahkan,
Allah pun digambarkan sebagai Allah yang murka, marah, dan
mendendam. Namun, teks-teks kekerasan dalam Alkitab juga mesti
dipahami sebagai model realitas kemanusiaan yang tak urung lepas
dari akar-akar kekerasan. Dalam kerangka itu, membaca Alkitab
harus dipahami sebagai upaya mengarungi lautan makna simbol-
simbol yang [pernah] menjadi bagian dari sejarah sosiologis suatu
komunitas.
Lectio Divina
Lantas, apakah teks-teks kekerasan dalam Alkitab harus dibuang?
Untuk apa? Tidak perlu. Kesucian Alkitab tidaklah terletak pada arti
harfiah teks-teks di dalamnya melainkan pada kehendak setiap orang
yang membacanya, tenggelam dalam permenungan yang terarah
96 Iman Tidak Pernah Amin
bukan hanya untuk mengenal Tuhan tetapi juga mendengar suara-
Nya. Kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya yang
tertulis dalam Alkitab adalah pantulan realitas kemanusiaan vis-a-
vis transendensi Allah. Penghadapan yang imanen dan transenden
justru hendak mengingatkan bahwa di dalam diri setiap manusia
tepercik citra ilahi untuk mendatangkan kebaikan dan rahmat bagi
semua ciptaan. Pada titik itulah, Alkitab (dan kitab suci lainnya)
menjadi /ectio divina (bacaan suci, sacred reading).
Dalam tradisi spiritualitas kristiani, lectio divina adalah cara
membaca secara batiniah yang terdiri dari empat langkah:
Lectio = pemilihan atau bacaan
Meditatio = merenungkan makna atau meditasi
Oratio = berbicara atau berdoa
Contemplatio = permenungan atau kontemplasi
Lectio. Lectio tidak sama artinya dengan membaca koran, tabloid,
atau kertas ujian. Lectio adalah membaca dengan pelan-tenang-
mendalam-tenggelam dalam Allah. Kalau dalam Penelaahan Alkitab
kita mencoba mengetabui lebih banyak tentang Allah, lectio mengajak
kita mendengar lebih banyak dari Allah. Ini tidak mudah, karena kita
terbiasa dengan yang serba cepat, instan, asal jadi. Lectio juga adalah
soal cita rasa dalam menikmati bacaan Alkitab: berulang-ulang,
perlahan-lahan, tenang, fokus pada kata, kalimat, dan paragraf.
‘Tidak usah dipikirkan apa maknanya; tidak usah dibayangkan apa
konteksnya. Dengan Jectio kita diajak untuk akrab dengan teks
Alkitab, meresapkannya dalam jiwa. Tidak usah pusing dengan
maknanya, dengarkan saja teks itu. Alami teks itu.
Meditatio. Kata "meditasi” muncul sekitar 15 kali dalam PL
(tidak muncul dalam PB). Kata itu muncul 14 kali dalam Mazmur,
6 kali dalam Mazmur 119; juga Yosua 1:2-8—’renungkanlah itu
siang dan malam...”. Kata Ibrani untuk ”meditasi” adalah hagah, yang
lectio Diving = 97
1?
Banjir
ulit melupakan peristiwa serbuan "air bah” yang sering meng-
gempur Jakarta (misalnya pada 2 Februari 2007). Hanya dalam
hitungan jam, seantero wilayah Jakarta lumpuh total dan serbuan
tersebut membentuk peta Jakarta layaknya danau raksasa. Kata
orang—dan juga para pejabat yang sok tahu—ini merupakan
bencana lima tahunan. Perhitungan itu hanya didasarkan pada
petistiwa banjir bandang’ tohun 2002, lalu disimpullan secara
simplistis sebagai ”peristiwa lima tahunan”.
Asumsi yang dangkal dan sok tahu itu pun runtuh ketika
ternyata baru genap setahun, yaitu 1 Februari 2008, Jakarta kembali
rontok-merontok” karena lagi-lagi diterjang air bah yang bingung
mencari jalan keluar. Malah, kali ini boleh dibilang lebih parah.
Bayangkan saja, bandara bertaraf internasional "Soekarno-Hatta”
tergolek lesu tak berdaya terkepung air, schingga pemerintah harus
{00
dan sesat—sampai bisa mengeluarkan fatwa "aliran sesat”’—bisa
nggak ya dikeluarkan fatwa tentang aliran-aliran air yang "tersesat”
masuk ke jalan-jalan dan permukiman penduduk (kampung-
kampung) di seantero Jakarta?
Fatwa itu saya kira lebih universal karena keselamatan manusia
dan lingkungan hidup yang menjadi dasar teologisnya. Dasar teologis?
Ya, bukankah hubungan kita dengan Realitas Ultim yang kita sebut
"Tuhan” itu tidak hanya tampak dalam ritual-ritual keagamaan
kita, tetapi juga harus mewujud dalam etika hidup bersama dengan
seluruh matra semesta—masyarakat dan lingkungan hidup?
Dengan demikian, bangsa yang religius tidak sekadar pamer
kemegahan tempat-tempat ibadah yang menjulang tinggi dan jor-
joran membangun rumah ibadah pada setiap jengkal tanah kosong
tanpa peduli pada ketentuan izin mendirikan bangunan. Bangsa yang
religius adalah bangsa yang sadar bahwa ibadah yang sejati adalah
penghormatan yang tulus atas relasi-relasi kemanusiaan dengan
siapa saja dan juga dengan lingkungan hidup.
Hormat pada yang kelihatan tentu saja akan menentukan
ketulusan rasa hormat pada yang tidak kelihatan—Tuhan, Dalam
kekristenan, Yesus mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu—"barang
siapa menghormati saudaraku yang paling hina, dia menghormati
Aku’.
Saya makin berandai-andai dengan tautan kontroversi seputar
”pemaafan’atas kesalahan Soeharto,presiden ke-2 RepublikIndonesia
yang pernah berjaya dengan segala prestasi dan kepongahan kuasa
despotiknya selama 32 tahun. Pernyataan tersebut bisa bermakna
ganda:
Soeharto bagi lawan-lawan politiknya dianggap “hina”
TETAPI ia mesti dihormati;
Para korban politik semasa Orde Baru diperlakukan "hina”
TETAPI mereka juga harus dihormati.
{02 Iman Tidak Pernah Amin
Jika banjir terjadi karena aliran air yang tersesat, tentu masalahnya
bukan pada airnya, tetapi pada saluran-saluran air yang tersumbat
oleh beraneka sampah yang tak terurai (non-organik). Bisa jadi,
"aliran{-aliran]” keagamaan yang tidak sepaham dengan kelompok
keagamaan dominan [lalu dicap "tersesat”], masalahnya bukan pada
aliran[-aliran] itu tetapi pada saluran komunikasi antarkomunitas
beriman yang mungkin saja tersumbat”sampah-sampah’ sejarah, tafsir
doktrinal yang dangkal, arogansi spiritual, persekongkolan agama-
politik/politik-agama, sehingga aliran-aliran tertentu mencari jalan
sendiri dan menyimpang dari ”arus utama”. Penyimpangan itu pun
dianggap ”bencana” namun tak mampu diatasi secara komprehensif.
Sumbatan komunikasi hanya bisa dibuka jika seluruh agama
(khususnya, teistik) memahami bahwa sentrum agama adalah
*manusia”, yang dalam sejarah peradabannya mencoba menggapai
kebenaran dalam kemahaluasan Realitas Ultim, yang kemudian
dibahasakan dalam nama "Tuhan’.
Penggagasan teologis semacam ini mau tidak mau harus me-
langkah pada titian humanisme yang terus-menerus menjaga
agar tidak terjerumus pada jurang ekstremitas humanistik di kiri
dan teistik di kanan. Beragama tanpa Tuhan (humanisme) hanya
menarik manusia ke dalam medan magnet keperkasaan manusia
yang semu (ddber-mensch) yang abai pada dorongan-dorongan
kebaikan eksistensial yang inheren pada kemanusiaannya. Sebaliknya,
beragama tanpa manusia akan menyedot manusia ke dalam medan
magnet utopia tentang akhirat” atau "surga”, yang pada gilirannya
menciptakan manusia-manusia asketik ahistoris.
Ttulah manusia-manusia yang syahwat sosiologisnya impoten
dan hanya asyik-masyuk dalam mimpi dengan "tuhan-tuhan”-nya
yang manis tetapi tidak pernah mampu merangkul Sang Tuhan itu
karena kesulitan menggauli Sang Tuhan dalam wujud kebertubuhan
sosial. Iman membutuhkan tubuh sosial agama. Tubuh sosial itu
pada gilirannya tak lebih dari mayat” jika tidak dihidupi oleh iman
Banjir (03
image
not
available
18
Mengasihi Musuh?
Capek Deh....
ahabat saya, Pdt. Elifas Maspaitella, menulis satu artikel menarik
di blognya bertajuk "Susahnya Mengampuni”. Saya tidak tahu
konteks apa yang menginspirasinya untuk membuat tulisan tersebut.
Namun, okelah, soal ackground tulisan itu, biarlah cuma ia yang
tahu. Akan tetapi, setidaknya tulisan tersebut telah membawa saya
pada percik permenungan yang lain, tentu dari sudut pandang yang
berbeda, mengenai tautan wacana ”pengampunan”. [mpuls imajinatif
saya mendadak sontak nyanto/ pada satu pernyataan Yesus dalam
Injil Lukas 6:27-36 (nanti baca saja sendiri; soalnya kutipannya
terlalu panjang kalau dimuat seluruhnya di sini). Saya hanya ingin
mengutip pernyataan yang paling dikenal saja: "Kasihilah musuhmu,
berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu; mintalah
berkat bagi orang yang mengutuk kamu; berdoalah bagi orang yang
mencaci kamu...”.
105
Topik”mengasihi musuh”, saya kira, merupakan topik yang paling
tidak populer bagi setiap orang. Topik ini sering dihindari dalam
banyak percakapan, diskusi gerejawi dan bahkan khotbah-khotbah
di gereja. Kutipan pernyataan Yesus di atas kemudian bermuara pada
apa yang disebut "kaidah emas’ (go/den rule):”Dan sebagaimana kamu
kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian
kepada mereka” (ayat 31). Pernyataan serupa terungkap pula dalam
Matius 7:12: "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang
perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah
isi seluruh Hukum Taurat dan kitab para nabi.” Artinya, menurut
Matius, Yesus sungguh-sungguh membangun etika pelayanan-Nya
di atas dasar pemahaman keagamaan-Nya (Yahudi). Yesus tidak
anti-Taurat tetapi terus-menerus hendak menanamkan pengertian
baru yang lebih segar dan relevan daripada yang diajarkan sebagai
rutinisme oleh para ahli Taurat sezaman.
Mengapa topik ini tidak populer bagi banyak orang? Setidaknya
ada dua alasan: [1] sejak masa Pencerahan, manusia tersiram cahaya
rasionalitas bahwa kebebasan untuk berpikir tentang dirinya dan
dunianya tidak lagi dibatasi oleh pagar norma-norma keagamaan
(teologis) yang dibangun olch institusi keagamaan (gereja). Sejak
saat itulah ajaran-ajaran [berbau] agama dianggap sebagai spam
karena dianggap hanya menawarkan ekstase akhirat tanpa bergulat
dalam realitas konkret kemanusiaan yang berlepotan dengan sejuta
problem tak berjawab. "Mengasihi musuh”, antara lain, dianggap
sebagai utopia karena dunia justru sedang mengarah pada ”perang”,
baik secara fisik maupun ideologis yang tentu beralchir pada polarisasi
”pemenang-pecundang” (winner and /ooser); [2] Pada dasarnya dalam
diri manusia terdapat dorongan-dorongan untuk mencari kepuasan
intrinsik yang kemudian dipahami sebagai "kehendak bebas” (free
will), yang kerap mewujud dalam tindakan-tindakan melawan
aturan atau hukum sosial.
106 Iman Tidak Pernah Amin
Dua alasan di atas mempunyai efek yang luas (sosial, ekonomi,
budaya, teknologi, teologi). Namun, bukankah semua itu adalah
konsekuensi historis dari sebuah perkembangan zaman? Mengapa
harus dicurigai? Sebenarnya, jika hendak menempatkan pernyataan
Yesus dalam konteks hidup kita sekarang, [si]apakah musuh kita?
Bisa jadi, ketika mendengar pertanyaan tentang "musuh”,
imajinasi kita langsung menerawang pada gambaran “orang” yang
bermuka masam, cemberut, marah-marah pada kita atau yang
sering membuat kita tersinggung dan sakit hati. Namun, pernahkah
kita membayangkan wajah "musuh” justru sebaliknya: murah
senyum, [seolah-olah] bersahabat, memberi kita kenikmatan [yang
menjerumuskan], membuat kita mabuk, dan sebagainya?
Kebudayaan global dengan segala tampilannya saat ini telah
menawarkan kepada kita suatu ekstase gaya hidup yang ”nyaman’,
tetapi bukan berarti tanpa risiko. Itulah sebentuk ”ideologi” yang
sekarang sedang merasuki kehidupan masyarakat kita dan menggiring
kita ke arah tujuan yang tak menentu. Memang, perubahan paling
radikal dalam sebuah konstruksi sosial masyarakat agaknya justru
sedang berlangsung dengan cara paling damai, nyaman, diam-diam,
tanpa gejolak: tiba-tiba saja, masyarakat tercerabut dari aras tertentu
dan lalu perubahan dalam arti riil yang dicita-Citakan bersama tak
diperlukan lagi.
"Ideologi” yang baru merasuk tidak lewat indoktrinasi kaku,
pamflet, propaganda, pidato, penataran dan sejenisnya, tetapi lewat
gemerlap iklan, sihir program-program televisi, tawaran gaya hidup
yang “wah”, yang kemudian mendekonstruksi atau mengubah
kebudayaan bersama maknanya yang selama ini dikenal orang
pada kajian baru. Saat ini sedang terjadi "perang” massif, semboyan
besar-besaran, untuk mendewakan kekuatan materi atau uang;
orang berlomba-lomba dalam keserakahan mengejar kekayaan
lalu menumpuknya; orang menyangkal realitas kemiskinan dengan
Nengasthi Musuh? Capek Deh... 107
polesan tampilan flamboyan ala selebriti bertabur berlian—hanya
supaya dicap orang kaya”.
Kalau dulu, sebagian orang merasa’tidak perlu” pamer kekayaan
dan cenderung tampil modes¢ meskipun kaya, kini apa gunanya kaya
kalau tidak dinikmati habis-habisan? Kaya itu enak dan perlu. Lalu
apa yang membatasinya? Hanya langit.
Welcome to McD’s World!
Mari kita intip contoh McDonald’s. Di Oak Brook, Illinois, daerah
pinggiran kota Chicago, berdiri dan tersebar bangunan besar kantor,
plaza, universitas, hotel, selain hutan dan danau yang tampak
dilestarikan. Di situlah "markas besar” McDonald’s, usaha waralaba
(franchising) yang bergerak di penjualan hamburger dengan restoran
yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Melihat "mabes”
McDonald’s, kita akan menyadari bahwa di balik struktur organisasi
dan pengendalian usahanya terbingkai suatu "ideologi”: McDonald’s
tidak hanya membuat makanan tetapi "mencetak manusia
[hamburger]”, tidak menciptakan hamburger tetapi kebudayaan,
bukan hanya mengurusi masalah perut tetapi juga gaya hidup. Seperti
halnya Levi-Strauss meroket dalam popularitas global dengan 4/ue-
Jeans, yang terjadi sebenarnya adalah proses produksi yang mengikuti
desain kebudayaan berupa standarisasi dalam skala global.
Untuk menyebarkan ideologi”manusia hamburger”,McDonald’s
mendirikan Hamburger University di Oak Brook.Merekasadarbahwa
bukan makanan yang mereka proses, tetapi konsumen. Apa yang
distandarisasi bukan hanya makanannya, tetapi juga konsumennya.
Dengan demikian, mengonsumsi produk McDonald’s bukan
hanya untuk kenyang, tetapi juga untuk peningkatan kebahagiaan
manusia yang sadar akan makanan dan kebiasaan makan yang schat.
Clive Bloom melukiskan kekuatan McDonald’s sebagai penetrasi
"ideologi Amerika”. Sebuah dunia yang nyaman, enak, bersahabat
108 Iman Tidak Pernah Amin
dan pas untuk konsumsi domestik. Memasuki dunia McDonald's,
Coca-Cola, Levi 501s, Anda tak perlu memikirkan dunia yang kian
ruwet. Masa Perang Dingin telah usai. Penetrasi”ideologi” tidak lagi
lewat paksaan moncong senjata dan infiltrasi spionase, melainkan
tawaran yang adem, damai, nyaman, atau kata orang Amerika: have
fun. Lagipula, tidak ada kata” gagal” dalam kamus McDonald’s. Batas
karier seseorang di McDonald’s cuma langit.
Kalau begitu, apa yang salah dengannya? Mengapa kita harus
melihatnya sebagai ancaman atau musuh? Kita sudah tentu tidak
bisa menghindarinya karena tsunami kebudayaan massal ini sedang
menerjang sendi-sendi kehidupan kita: mulai dari urusan rambut
sampai kuku kaki. Apa yang bisa kita lakukan paling-paling hanya
mengenalinya agar, semoga, tidak tergulung oleh gelombang dan
jungkir-balik tanpa arah, yang akhirnya menghempaskan kita pada
batu karang realitas yang membinasakan kemanusiaan dan ekosistem
bumi.
Apa yang hendak kita refleksikan di sini ialah "kehati-hatian”
atau "kritik ideologi” terhadap gaya hidup yang scbenarnya sedang
menjerumuskan kemanusiaan kita pada keterasingan (alienation).
Ketika manusia turun nilainya menjadi "komoditas”, maka lambat-
Jaun atau segera pandangan kita terhadap diri sendiri dan sesama akan
ditentukan oleh komoditas tempelan yang disandangnya (parfum,
busana, sepatu, tongkrongannya, konsumsi, tujuan wisata, merek HP,
dan sebagainya). Hubungan kita tidak lagi terbangun secara genuine
sebagai hubungan kemanusiaan. Mengasihi musuh adalah suatu
tindakan radikal yang berarti "menerima segala perkembangan yang
penuh risiko tanpa kehilangan sikap kritis [keberanian berjarak]
dengannya”. Pada titik irulah letak kesulitannya yang lagi-lagi oleh
Yesus disebut sebagai keberanian untuk menyangkal diri.
Anda mungkin menganggapnya sebagai "cerita besat” (grand-
narrative). Tak apalah. Namun, ini bukan bualan besar karena cerita
besar ini sedang menjadi cerita kita bersama, yang menggulung kita
Mengasihi Musuh? Capek Deh.. (09
dalam alur narasi hidup bersama sejagat, baik yang hidup di kota-
kota megapolitan hingga ke desa-desa paling ndeso di titik-titik
peta dunia yang selalu tak menarik untuk diperhatikan. Kita semua
sedang ditelan ke dalam situasi yang sempoyongan dengan ekstase
gaya hidup.
Seandainya Yesus hidup pada abad ini, saya percaya Yesus pun
akan bergaya hip-hop, menenteng HP Nokia Nseries 3G, atau Dia
duduk di Mal Senayan City mengajar orang banyak sambil membawa
mereka berkeliling untuk shopping, kalau lapar, Dia mungkin tidak
sempat singgah di rumah Zakeus [yang nangkring di plafon koridor
bus Transjakarta], melainkan nongkrong di McDonald’s, KFC, atau
Pizza Hut. Kan lebih asyik. Adem lagi.
Akan tetapi, saya percaya bahwa Yesus postmodern pun masih
punya waktu dan energi untuk bekerja bagi pelayanan kaum miskin
tergusur—entah oleh banjir atau satpol PP—bukan karena mereka
miskin-papa, melainkan karena mereka adalah sesama manusia yang
harkat-martabatnya tidak lebih dan tidak kurang dibandingkan
kaum berduit dengan tunggangan Mercedes Benz atau BMW.
Saya percaya Yesus postmodern juga tetap punya konsistensi
dan resistensi dalam perubahan sosial yang makin merakyatkan
kemelaratan, termasuk perlawanan terhadap pelecehan kaum pe-
rempuan dalam sweeping PSK yang tidak manusiawi dan penuh
kemunafikan. Dalam karya klasiknya Love, Power and Justice, Paul
Tillich menyatakan bahwa urusan "mengasihi” bukanlah urusan
personal-emosional semata, melainkan masalah ontologis yang
terikat dan terkait dengan soal keadilan dan kekuasaan. Wuaaahh...,
capek deb!
iio Iman Tidak Pernah Amin
19
Anakku Sekolah!
enin, 14 Juli 2008, adalah hari pertama Kainalu di Sekolah
Dasar Katolik Don Bosco 1 Kelapa Gading. Bagi saya, ini
adalah hari yang bersejarah. Sama pentingnya dengan saat seorang
anak dilahirkan dari rahim ibunya. Sebuah proses peralihan yang
juga menyertakan pergeseran cara berpikir (mindset), yang pada
gilirannya membentuk suatu gaya hidup yang berbeda dengan
sebelumnya. Begitu pentingnya schingga saya lebih memilih absen
dari kantor untuk mengantarkannya ke sekolah, dan memperhatikan
seluruh proses pembelajaran dari luar ruang kelas. Ah, saya jadi
teringat pada masa saya masih kecil ketika baru masuk SD dulu di
Malang. Nancy, istri saya, sedang bertugas ke luar Jakarta. Jadi, hanya
saya yang mengantarkan Kainalu.
Memperhatikan Kainalu di dalam kelas membuat imajinasi saya
melayang-layang—mengenang kembali saat-saat harus beradaptasi
dengan lingkungan sekolah yang baru. Terpisah dengan teman-
teman waktu di taman kanak-kanak memang sangat menyedihkan.
Memang,di SD, kita berkenalan dengan teman-teman baru, tetapi fob
seperti ada sesuatu yang hilang—keakraban, keceriaan, pengenalan.
Namun, apa mau dikata? Proses semacam ini harus dialami oleh
setiap orang. Suatu diskontinuitas, untuk menjalani kontinuitas yang
baru, tidak hanya dalam bentuk tetapi juga kualitas.
Jujur saja, rasa "terputus” (diskontinuitas) itu tidak hanya
dirasakan oleh anak, tetapi sekarang juga oleh saya yang sudah
menjadi orangtua. Senang melihat anak bertumbuh sehat dan cerdas,
tetapi juga terselip rasa kesendirian. Semakin besar anak, semakin
longgar ikatan ketergantungan dengan orangtuanya. Kita ingin
terus memperlakukannya dengan manja tetapi serta-merta tersadar
bahwa anak sudah semakin besar dan mandiri. Melihat Kainalu
belajar di kelas, saya menjadi semakin sadar bahwa hidup kita
terus bergerak dalam fragmen-fragmen diskontinuitas/kontinuitas.
Sebuah keterputusan transformatif yang membawa kita pada realitas
ruang dan waktu yang berbeda, dan pada akhirnya membuat kita
memang harus terus berada dalam aliran sejarah yang senantiasa
memunculkan varian-varian kehidupan yang tak terduga tetapi
harus dijalani.
Momen semacam itu mengingatkan saya pada cerita tentang
Yesus dalam Bait Allah ketika Dia berumur 12 tahun (Luk. 2:41-
52). Ketika berada di Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah,
orangtua Yesus tidak menyadari bahwa Yesus sudah tidak bersama
mereka dalam rombongan. Mereka menyangka Yesus berjalan
dengan teman-teman sebayanya. Ketika sadar Yesus tidak ada dalam
rombongan, Yusuf dan Maria pun mulai mencari Yesus. Tiga hari
mereka mencari Yesus. Wow, bayangkan betapa paniknya Yusuf dan
Maria—harus mencari Yesus di antara begitu banyak orang. Apalagi,
pada waktu itu belum ada Aandphone atau kendaraan bermotor yang
bisa dipakai mondar-mandir.
2 Iman Tidak Pernah Amin
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
aa
You have either reached a page that is unavailable for viewing or reached your viewing limit for this
book.
Diangkat dari catatan-catatan pribadin
kapi berbagai persoalan yang dijumpai
hari—dari
Daniel Sal
Dengan gaya bahasa lincah menggelitik, ia men
pengalaman tersebut dan bersama-sama menemukan pesan bagi kita dan
uleka.
ak kita merefleksikan
kembali upaya untuk
e oleh
g, terutama dalam meraj
Indonesia. Inilah iman yang menolak di
suatu Iman yang
pernal
sikap dogmatis terten
Melalui buku ini, Steve Gaspersz membuktikan dirinya sebagai seorang teolog muda
Indonesia yang dapat diandalkan. Tulisan-tulisannya menampakkan kepekaan sosial
dan kepiawaian literer merangkai gagasan-gagasan iman Kristen dalam konteks
aktual Indonesia berlatar Maluku.
Dr. Zakaria Ngelow, Teolog, Sejarawan Gereja, Aktivis Kemanusiaan dan Pluralisme
Bagaimana mungkin sembilan kualitas unggul sebagai kritikus, pluralis, nasionalis,
penulis, pembelajar, budayawan, teolog, pendeta, bahkan filsuf dimiliki sekaligus
oleh satu orang bernama Steve Gaspersz. Tetapi, tulisan-tulisan bernas dalam buku
ini membuktikannya!
Edy Zaqeus, Penulis Bestseller, Trainer, Writer Coach, Writing & Publishing Consultant
Pendiri/Editor AndaLuarBiasa.com dan BukuKenangan.com
Iman Tidak Pernah Amin ISBN 978-979-687-666-2
PT BPK GUNUNGMULIA™ | | | |
www.bpkgm.com 1007141300 9117897961876662
Rohani
——"
Anda mungkin juga menyukai
- Tetap Percaya Tuhan Yesus BaikDokumen2 halamanTetap Percaya Tuhan Yesus BaikNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- MEMBANGUN HUBUNGANDokumen6 halamanMEMBANGUN HUBUNGANNusye Bastov Manuputty0% (1)
- Contoh Pedoman-Monev-KurikulumDokumen23 halamanContoh Pedoman-Monev-KurikulumNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Curriculum VitaeDokumen1 halamanCurriculum VitaeNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Kisah Lukas Tentang Pelayanan Paulus Di Roma Menegaskan Pemenuhan Janji AllahDokumen3 halamanKisah Lukas Tentang Pelayanan Paulus Di Roma Menegaskan Pemenuhan Janji AllahNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Green, Dennis. Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama.Dokumen114 halamanGreen, Dennis. Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama.Nusye Bastov Manuputty96% (45)
- MujizatInjilDokumen2 halamanMujizatInjilNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Tetap Percaya Tuhan Yesus BaikDokumen2 halamanTetap Percaya Tuhan Yesus BaikNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Renungan PagiDokumen2 halamanRenungan PagiNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Lasor, W.S Et Al. Pengantar Perjanjian Lama. 2.Dokumen233 halamanLasor, W.S Et Al. Pengantar Perjanjian Lama. 2.Nusye Bastov Manuputty92% (24)
- Bab 1Dokumen15 halamanBab 1Nusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Laporan Baca Teologi MisiDokumen2 halamanLaporan Baca Teologi MisiNusye Bastov Manuputty100% (1)
- Khotbah Kaum Muda BersyukurDokumen1 halamanKhotbah Kaum Muda BersyukurNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- OPTIMALKAN BISNIS PELAYANANDokumen4 halamanOPTIMALKAN BISNIS PELAYANANNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Doktrin KeselamatanDokumen8 halamanDoktrin KeselamatanNusye Bastov Manuputty100% (1)
- Sejarah Gereja KristenDokumen14 halamanSejarah Gereja KristenNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Hip Hop Christmas 2Dokumen1 halamanHip Hop Christmas 2Nusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- IntroDokumen9 halamanIntroNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Hip Hop Christmas 2Dokumen1 halamanHip Hop Christmas 2Nusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Hip Hop Christmas 2Dokumen1 halamanHip Hop Christmas 2Nusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Penulisan Karya IlmiaDokumen4 halamanPenulisan Karya IlmiaNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- IntroDokumen9 halamanIntroNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- PWJDokumen2 halamanPWJNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Tugas Kris .KorintusDokumen1 halamanTugas Kris .KorintusNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Ipi 283963Dokumen23 halamanIpi 283963Nusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- Buku KristologiDokumen180 halamanBuku KristologiBao383100% (3)
- Laporan BacaDokumen3 halamanLaporan BacaNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat
- 3-Sebuah Tinjauan Eksegesis-Fery YangDokumen25 halaman3-Sebuah Tinjauan Eksegesis-Fery YangNusye Bastov ManuputtyBelum ada peringkat