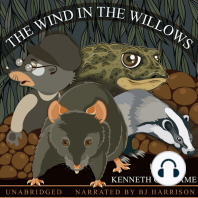Makalah Epid TRUE-rubah Umur
Makalah Epid TRUE-rubah Umur
Diunggah oleh
averdyHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Makalah Epid TRUE-rubah Umur
Makalah Epid TRUE-rubah Umur
Diunggah oleh
averdyHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Epidemiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang
penyebaran penyakit dan faktor yang menentukan terjadinya penyakit pada
manusia (Azwar, 1999). Penyebaran penyakit yang dipelajari dalam epidemiologi
adalah karakteristik penyebaran penyakit menurut sifat orang, tempat, dan waktu.
Epidemiologi tidak hanya mempelajari tentang siapa yang terkena penyakit, tetapi
juga membahas mengenai dimana dan bagaimana suatu penyakit dapat menyebar.
Hasil dari penelitian epidemiologis adalah data mengenai jumlah penderita dari
suatu jenis penyakit, jenis kelamin penderita, lokasi dimana penderita tinggal,
bagaimana penyakit dapat menginfeksi penderita, dan kapan penyakit sering
muncul (Bustan dan Arsunan, 1997).
Epidemiologi secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kategori,
yaitu epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik.. Kedua studi ini memiliki
manfaat/keuntungan dan kerugian masing-masing dan digunakan sesuai dengan
tujuan peneliti dalam melaksanaan penelitian (Azwar, 1999).
Studi epidemiologi deskriptif adalah suatu studi yang menggambarkan
pola-pola kejadian penyakit, atau pola-pola pemaparan dalam kaitannya dengan
variabel orang (populasi), tempat (letak geografis), dan waktu (Subaris dkk,
2004). Studi epidemiologi deskriptif disebut juga studi prevalensi atau studi
pendahuluan dari studi analitik yang dapat dilakukan pada suatu saat atau suatu
periode tertentu. Studi epidemiologi deskriptif hanya bertujuan untuk memberi
gambaran masalah yang ada di masyarakat, bukan mencari penyebab dan
menentukan hubungan antarvariabel (Kasjono dan Kristiawan, 2009). Penjelasan
mengenai studi epidemiologi deskriptif beserta contoh penelitian yang
menggunakan studi epidemiologi deskriptif pada bidang kesehatan reproduksi
akan dibahas pada makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah definisi dari studi epidemiologi deskriptif?
2. Apakah tujuan studi epidemiologi deskriptif?
3. Apakah perbedaan studi epidemiologi deskriptif dengan epidemiologi
analitik?
4. Apa saja karakteristik variabel studi epidemiologi deskriptif?
5. Bagaimanakah ciri-ciri studi epidemiologi deskriptif?
6. Apa sajakah kegunaan studi epidemiologi deskriptif?
7. Bagaimanakah kategori studi epidemiologi deskriptif?
8. Bagaimana langkah-langkah studi epidemiologi deskriptif?
9. Apa sajakah keuntungan dan kerugian studi epidemiologi deskriptif?
10. Bagaimana interpretasi hasil studi epidemiologi deskriptif?
11. Bagaimana contoh penelitian dengan studi epidemiologi deskriptif pada
bidang kesehatan reproduksi?
1.3 Tujuan
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui tentang studi epidemiologi deskriptif
1.3.2
Tujuan Khusus
1. Mengetahui definisi dari studi epidemiologi deskriptif.
2. Mengetahui tujuan dari studi epidemiologi deskriptif.
3. Mengetahui perbedaan studi epidemiologi deskriptif
dengan
epidemiologi analitik.
4. Mengetahui karakteristik variabel studi epidemiologi deskriptif.
5. Mengetahui ciri-ciri studi epidemiologi deskriptif.
6. Mengetahui kegunaan studi epidemiologi deskriptif.
7. Mengetahui kategori studi epidemiologi deskriptif.
8. Mengetahui langkah-langkah studi epidemiologi deskriptif.
9. Mengetahui keuntungan dan kerugian studi epidemiologi deskriptif.
10. Mengetahui interpretasi hasil studi epidemiologi deskriptif.
11. Mengetahui contoh penelitian yang menggunakan studi epidemiologi
deskriptif pada bidang kesehatan reproduksi.
1.4 Manfaat
1.4.1 Manfaat Teoritis
Makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta
sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan,
serta dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi untuk melakukan
pembelajaran dan bahan bacaan.
1.4.2
Manfaat Praktis
Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa
dalam memilih studi yang tepat bagi penelitian tesisnya maupun karya ilmiah
lainnya.
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Studi Epidemiologi Deskriptif
Studi epidemiologi deskriptif adalah suatu studi yang menggambarkan
pola-pola kejadian penyakit, atau pola-pola pemaparan dalam kaitannya dengan
variabel orang (populasi), tempat (letak geografis), dan waktu (Subaris dkk,
2004). Sedangkan menurut Azwar, studi epidemiologi deskriptif merupakan studi
yang hanya mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan
saja, tanpa memandang perlu mencarikan jawaban terhadap faktor-faktor
penyebab yang mempengaruhi frekuensi, penyebaran, dan atau munculnya
masalah kesehatan tersebut (Azwar, 1999).
Studi epidemiologi deskriptif disebut juga studi prevalensi atau studi
pendahuluan dari studi analitik yang dapat dilakukan pada suatu saat atau suatu
periode tertentu (Kasjono dan Kristiawan, 2009). Studi epidemiologi deskriptif
yang ditujukan pada sekelompok masyarakat tertentu yang mempunyai masalah
kesehatan disebut dengan studi kasus, tetapi jika ditujukan untuk pengamatan
secara berkelanjutan maka disebutlah dengan surveilans, serta apabila ditujukan
untuk menganalisis faktor penyebab atau risiko maupun akibatnya maka disebut
dengan studi potong lintang atau cross sectional (Murti, 2011).
Epidemiologi deskriptif umumnya dilaksanakan jika tersedia sedikit
informasi yang diketahui mengenai kejadian, riwayat alamiah dan faktor yang
berhubungan dengan penyakit. Upaya mencari frekuensi distribusi penyakit
berdasarkan epidemiologi deskriptif dilakukan dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan mengenai: siapa yang terkena, bilamana hal tersebut terjadi,
bagaimana terjadinya, dimana kejadian tersebut, berapa jumlah orang yang
terkena, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena
(Noor, 1997).
Selain itu, epidemiologi deskriptif juga ditujukan untuk menjawab 4
pertanyaan berikut (Noor, 1997):
1. What, yaitu apa masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan berapa
besarnya masalah kesehatan masyarakat tersebut. Jawaban pertanyaan ini
akan mengukur masalah kesehatan.
2. Who, yaitu siapa yang terkena masalah kesehatan. Who yang dimaksudkan
adalah masyarakat atau sekelompok manusia (man) yang menjadi host
penyakit. Man yang akan diteliti dan dibahas adalah variabel pada
karakteristiknya, meliputi: jenis kelamin, usia, paritas, agama, ras,
genetika, tingkat pendidikan, penghasilan, jenis pekerjaan, jumlah
keluarga,dan berbagai variabel lainnya.
3. Where, yaitu dimana masyarakat yang terkena masalah kesehatan.
Jawabannya akan menjelaskan tempat (place) dengan karakteristik tempat
tinggal, batas geografis, desa-kota, batas administrative, dan berbagai
karakteristik tempat lainnya.
4. When, yaitu kapan masyarakat terkena masalah kesehatan. Jawaban
pertanyaan ini akan menjelaskan waktu (time) dengan karakteristik periode
penyakit atau gangguan kesehatan jangka pendek (ukurannya detik, menit,
jam, hari, minggu), jangka panjang (bulan, tahun), atau periode musiman.
2.2 Tujuan Studi Epidemiologi Deskriptif
Tujuan dilakukannya studi epidemiologi deskriptif adalah (Kasjono dan
Kristiawan, 2009):
1. Untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan menurut
karakteristik tertentu, seperti: umur, gender, ras, strata sosial, pekerjaan,
daerah geografik, dan lainnya sehingga dapat diduga kelompok mana di
masyarakat yang paling banyak terserang.
2. Untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai
kelompok.
3. Untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan
terhadap masalah kesehatan (menjadi dasar suatu formulasi hipotesis untuk
dilanjutkan dengan studi analitik atau intervensi).
4. Menyediakan data dasar bagi perencanaan, penyediaan dan penilaian
upaya pelayanan kesehatan di suatu populasi.
2.3 Perbedaan Sudi Epidemiologi Deskriptif dengan Epidemiologi Analitik
Secara umum, studi epidemiologi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu
(Budiarto dan Anggraeni, 2002):
1. Studi yang ditujukan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan
distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan
waktu. Studi ini disebut studi epidemiologi deskriptif.
2. Studi epidemiologi yang ditujukan untuk mencari faktor-faktor penyebab
timbulnya peyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi yang tinggi
atau rendahnya frekuensi penyakit pada berbagai kelompok individu. Studi
epidemiologi ini dikenal sebagai epidemiologi analtik.
Epidemiologi deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi
penyakit dan kecenderungan (trend) penyakit pada populasi. Sedangkan
epidemiologi
analitik
bertujuan
untuk
mempelajari
determinan/faktor
resiko/penyebab penyakit. Epidemiologi deskriptif berguna untuk memahami
distribusi dan mengetahui besarnya masalah kesehatan pada populasi.
Epidemiologi analitik berguna untuk memahami penyebab penyakit, menjelaskan
dan meramalkan kecenderungan penyakit, dan menemukan strategi yang efektif
untuk mencegah dan mengendalikan penyakit (Murti, 2011).
2.4 Karakteristik Variabel Studi Epidemiologi Deskriptif
Ruang lingkup kajian studi epidemiologi deskriptif mencakup kajian
terhadap variabel-variabel pada karakteristik orang, tempat, dan waktu (Lapau,
2009). Berikut penjelasan dari masing-masing variabel.
2.4.1 Orang (Person)
Banyak fokus epidemiologi yang ditujukan pada karakteristik orang,
dalam hal penyakit, ketidakmampuan, cedera, dan kematian. Studi epidemiologi
umumnya berfokus pada beberapa karakteristik demografi utama dari aspek
manusia, yaitu: umur, jenis kelamin, kelas sosial, jenis pekerjaan, penghasilan,
golongan etnis, status perkawinan, besarnya keluarga, struktur keluarga, dan
1.
paritas.
Umur
Variabel umur memiliki pengaruh yang paling besar dibandingkan
dengan variabel sifat manusia yang lain dalam hal membantu memastikan
hubungan sebab-akibat penyakit infeksi, cedera, penyakit kronis, dan penyakit
lain. Variabel umur merupakan hal yang penting karena semua rate morbiditas
dan rate mortalitas yang dilaporkan hampir selalu berkaitkan dengan umur
(Budiarto dan Anggraeni, 2002).
Hampir semua penyakit dapat menyerang semua kelompok usia, tetapi
penyakit tertentu lebih sering terjadi pada umur tertentu. Pernyataan ini sesuai
khususnya untuk penyakit kronis, karena penyakit kronis membutuhkan waktu
untuk berkembang, sehingga penyakit kronis akan lebih sering muncul pada
usia lanjut. Beberapa contoh pentingnya variabel umur dalam studi
epidemiologi deskriptif, antara lain (Budiarto dan Anggraeni, 2002):
a. Hubungan Umur Dengan Mortalitas
Walaupun secara umum kematian dapat terjadi pada setiap golongan
umur, tetapi dari berbagai data, diketahui bahwa frekuensi kematian pada
setiap golongan umur berbeda-beda. Kematian tertinggi terjadi pada golongan
umur 0-5 tahun dan kematian terendah terletak pada golongan umur15-25
tahun, dan akan meningkat lagi pada umur 40 tahun ke atas (Budiarto dan
Anggraeni, 2002).
b. Hubungan Umur Dengan Morbiditas
Pada umumnya, suatu penyakit dapat menyerang setiap orang pada
semua golongan umur, tetapi terdapat penyakit tertentu yang lebih banyak
menyerang golongan umur tertentu.
Penyakit kronis mempunyai
kecenderungan
meningkat
seiring
pertambahan umur, sedangkan penyakit-penyakit akut tidak mempunyai suatu
kecenderungan yang jelas. Penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung
koroner, dan karsinoma lebih banyak menyerang orang dewasa dan lanjut usia,
sedangkan penyakit kelamin, AIDS, kecelakaan lalulintas, penyalahgunaan
obat terlarang lebih banyak terjadi pada golongan umur produktif, yaitu remaja
dan dewasa (Budiarto dan Anggraeni, 2002).
Anak berumur 1-5 tahun lebih banyak terkena infeksi saluran
pernapasan atas (ISPA). Hal ini disebabkan imunitas yang diperoleh dari ibu
hanya bertahan sampai umur 6 bulan setelah dilahirkan. Setelah umur 6 bulan,
imunitas ini menghilang dan ISPA mulai menunjukkan peningkatan (Harlan,
2006).
Hubungan antara umur dan penyakit tidak hanya pada frekuensinya
saja, tetapi juga pada tingkat beratnya penyakit. Misalnya, infeksi oleh
Staphylococcus sp. dan Eschericia coli akan lebih berat apabila menyerang
bayi dibandingkan golongan umur lain, karena bayi masih sangat rentan
2.
terhadap penyakit (Budiarto, 2004).
Jenis Kelamin
Selain umur, jenis kelamin atau gender merupakan determinan
perbedaan kedua yang paling signifikan di dalam peristiwa kesehatan atau
dalam faktor resiko suatu penyakit. Angka-angka dari luar negeri menunjukkan
bahwa angka kesakitan lebih tinggi pada kalangan wanita, sedangkan angka
kematian lebih tinggi pada pria pada semua golongan umur. Perbedaan angka
kematian ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor intrinsik yang diduga
meliputi: perbedaan fisiologis atau perbedaan hormonal, genetik, perbedaan
tekanan emosional, kebiasaan individu, faktor-faktor lingkungan (misalnya,
lebih
banyak
pria
merokok,
kecanduan
alkohol,
bekerja
berat,dan
ketergantungan narkotika), dan pelayanan medik (Lapau, 2009).
Data juga menunjukkan adanya perbedaan kejadian penyakit antara pria
dan wanita, antara lain: kanker paru dan ulkus pepticum lebih sering terjadi
pada pria, sedangkan tyrotoksikosis dan kolesistitis lebih sering terjadi pada
wanita (Lapau, 2009).
3.
Kelas Sosial
Kelas sosial juga merupakan variabel yang sering dilihat hubungannya
dengan angka kesakitan atau kematian. Variabel ini menggambarkan tingkat
kehidupan
seseorang,
yang
ditentukan
oleh:
pendidikan,
pekerjaan,
penghasilan, dan tempat tinggal atau pemukiman. Tingkat kehidupan ini dapat
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemeliharaan kesehatan
sehingga terdapat perbedaan dalam angka kesakitan atau kematian antara
4.
berbagai kelas sosial (Harlan, 2006).
Jenis Pekerjaan
Jenis pekerjaan tertentu juga dapat berperan dalam timbulnya penyakit
melalui berbagai cara, antara lain (Rajab, 2012):
1. Adanya faktor-faktor lingkungan yang langsung dapat menimbulkan
kesakitan, seperti: bahan kimia, gas beracun, radiasi, dan benda-benda fisik
yang dapat menimbulkan kecelakaan.
2. Situasi pekerjaan yang penuh dengan stress, dapat memicu timbulnya
hipertensi dan gangguan lambung.
3. Ada tidaknya gerak badan dalam pekerjaan. Data di Amerika Serikat
menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner sering ditemukan pada
pekerja yang kurang gerak.
4. Luas tempat kerja. Penularan penyakit akan lebih mudah terjadi diantara
para pekerja apabila pekerja berada pada satu tempat kerja yang relatif
sempit.
5. Penyakit karena cacing tambang telah lama diketahui terkait dengan
5.
pekerjaan di pertambangan.
Penghasilan
Penghasilan dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan fasilitas
pelayanan kesehatan maupun pencegahan. Penghasilan yang kurang diduga
akan mengurangi pula penggunaan fasilitas kesehatan. Contohnya, seseorang
kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada dikarenakan tidak
mempunyai cukup uang untuk membeli obat atau membayar transport (Rajab,
2012).
6.
Etnis
Perbedaan golongan etnis berperan dalam adanya perbedaan kebiasaan
makan, susunan genetika, daya hidup, dan berbagai perbedaan lain yang dapat
mengakibatkan perbedaan di dalam angka kesakitan dan kematian. Perbedaan
genetik ini dapat berpengaruh terhadap kecenderungan suatu etnis atau ras
tertentu menderita suatu penyakit (Lapau, 2009).
Misalnya, ras Negro secara genetik mempunyai sel darah merah yang
berbentuk oval sehingga ras Negro disebut menderita sickle cell anemia. Ras
Negro juga secara sosio-ekonomis termasuk golongan berpendapatan rendah
sehingga mereka rentan untuk menderita penyakit infeksi seperti tuberculosis
(Lapau, 2009).
7.
Status Perkawinan
Berdasarkan data, diketahui bahwa angka kesakitan dan kematian lebih
tinggi pada orang yang tidak menikah dibandingkan dengan yang sudah
menikah. Hal ini kemungkinan diakibatkan adanya kebiasaan kurang sehat dari
orang-orang yang tidak menikah atau karena adanya perbedaan gaya hidup
yang berhubungan secara kausal dengan penyebab penyakit tertentu (Kasjono
dan Kristiawan, 2009).
Janda atau orang yang belum menikah juga lebih sering menderita
penyakit karena faktor tekanan fisiologis atau psikologis. Namun disertai pula
10
dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah, yang juga merangsang terjadinya
penyakit (Lapau, 2009).
8.
Besarnya Keluarga
Di dalam keluarga besar dengan penghasilan yang rendah, anak-anak
lebih mudah mengidap penyakit karena status gizi dan imunitas yang rendah.
Hal ini dikarenakan penghasilan yang sedikit dan masih harus dibagi-bagi
untuk memenuhi kebutuhan banyak anggota keluarga sehingga tidak
mencukupi kebutuhan nutrisi (Bustan dan Arsunan, 1997).
Struktur keluarga juga dapat mempunyai pengaruh terhadap timbulnya
penyakit dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Suatu keluarga besar karena
besarnya tanggungan secara relatif mungkin harus tinggal berdesak-desakan di
dalam rumah yang luasnya terbatas sehingga memudahkan penularan penyakit
menular (Bustan dan Arsunan, 1997).
9. Paritas
Tingkat paritas telah diteliti dalam kaitannya dengan hubungan
kesehatan ibu maupun anak. Berdasarkan data, terdapat kecenderungan
kesehatan ibu yang berparitas rendah lebih baik dari ibu berparitas tinggi,
terdapat asosiasi antara tingkat paritas dan penyakit-penyakit tertentu seperti
asma, ulcus pepticum, pyloric stenosis, dan preeklamsia. Akan tetapi,
kebenaran data-data ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut (Harlan,
2006).
10. Agama atau Budaya
Dalam beberapa hal terdapat hubungan antara kebudayaan masyarakat
atau agama dengan frekuensi penyakit tertentu. Misalnya (Lapau, 2009):
1. Balanitis, karsinoma penis banyak terjadi pada orang yang tidak
melakukan sirkumsisi disertai dengan hygiene perorangan yang jelek
2. Trisinensis jarang terdapat pada orang Islam dan Yahudi karena mereka
tidak memakan daging babi.
11. Golongan Darah ABO
Golongan darah juga dapat mempengaruhi insiden suatu penyakit. Data
yang didapatkan dari penelitian di Jepang menunjukkan bahwa orang dengan
golongan darah A meningkatkan resiko terserang karsinoma lambung,
sedangkan golongan darah O lebih banyak menderita ulkus duodeni (Kasjono
dan Kristiawan, 2009).
2.4.2 Tempat (Place)
11
Pengetahuan mengenai distribusi penyakit berguna untuk perencanaan
pelayanan kesehatan dan dapat memberikan penjelasan mengenai etiologi
penyakit. Hal yang sangat berguna dalam penelitian epidemiologi adalah
penempatan penyakit, kondisi, pengklasterannya pada peta, serta perangkat
lainnya untuk menempatkan berbagai kasus penyakit. Hal tersebut penting, karena
Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit tidak dapat terhenti total apabila host
berpindah-pindah tempat. Setiap kasus dan sumber harus ditentukan letaknya
(Budiarto dan Anggraeni, 2002).
Perbandingan pola penyakit sering dilakukan diantara: batas-batas daerah
pemerintahan, kota dan pedesaan, daerah atau tempat berdasarkan batas-batas
alam (pegunungan, sungai, laut, atau padang pasir), negara, dan regional (Lapau,
2009). Untuk kepentingan mendapatkan pengertian tentang etiologi penyakit,
perbandingan menurut batas-batas alam lebih berguna daripada batas-batas
administrasi pemerintahan.
Hal-hal yang memberikan kekhususan pola penyakit di suatu daerah
dengan batas-batas alam ialah: 1) keadaan lingkungan yang khusus, seperti:
temperatur, kelembaban, curah hujan, ketinggian di atas permukaan laut, keadaan
tanah, sumber air; 2) derajat isolasi terhadap pengaruh luar yang tergambar dalam
tingkat kemajuan ekonomi, pendidikan, industri, pelayanan kesehatan, adanya
tradisi-tradisi yang menjadi hambatan pembangunan, faktor-faktor sosial budaya
yang tidak menguntungkan kesehatan atau pengembangan kesehatan; 3) sifat-sifat
lingkungan biologis (ada tidaknya vektor penyakit menular tertentu, reservoir
penyakit menular tertentu, dan susunan genetika) (Harlan, 2006).
Contoh adanya kekhususan penyakit di suatu daerah dengan batas-batas
alam adalah penyakit demam kuning (yellow fever) di Amerika Latin. Distribusi
penyakit ini disebabkan oleh adanya reservoir infeksi (manusia atau kera), vektor
(Aedes aegypty), penduduk yang rentan, dan keadaan iklim yang memungkinkan
suburnya agen penyebab penyakit.
Pentingnya pengetahuan mengenai tempat dalam mempelajari etiologi
suatu penyakit dapat digambarkan dengan jelas pada penyelidikan suatu wabah
dan pada penyelidikan kaum migran. Variasi geografis pada terjadinya beberapa
penyakit atau keadaan lain mungkin berhubungan dengan beberapa faktor sebagai
berikut (Budiarto dan Anggraeni, 2002):
12
a. Lingkungan fisik, kemis, biologis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda
dari satu tempat ke tempat lainnya.
b. Konstitusi genetis dan etnis dari penduduk yang berbeda dan bervariasi,
seperti karakterisitik demografi.
c. Variasi kultural, misalnya terjadi perbedaan dalam kebiasaan, pekerjaan,
keluarga, praktek higiene perorangan, dan bahkan persepsi tentang sakit
atau sehat.
d. Variasi administratif, termasuk faktor-faktor seperti tersedianya dan efisiensi
pelayanan medis, program higiene (sanitasi), dan variasi administratif
lainnya.
2.4.3 Waktu (Time)
Mempelajari hubungan antara waktu dan penyakit merupakan kebutuhan
dasar di dalam analisis epidemiologis, karena perubahan-perubahan penyakit
menurut waktu menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor etiologis (Noor,
1997).
Dilihat dari panjangnya waktu di mana terjadi perubahan angka kesakitan,
maka waktu dibedakan menjadi:
a. Tren Jangka Pendek (Fluktuasi Jangka Pendek)
Pola perubahan angka kesakitan berlangsung hanya dalam
beberapa jam, hari, minggu, dan bulan. Pola perubahan kesakitan ini
terlihat pada epidemi, misalnya pada epidemi karena keracunan makanan
(beberapa jam), epidemi influenza (beberapa hari atau minggu), epidemi
cacar (beberapa bulan) (Timmreck, 2004).
Fluktuasi jangka pendek atau epidemi ini memberikan petunjuk
bahwa (Timmreck, 2004):
1) Penderita terserang penyakit yang sama dalam waktu bersamaan atau
hampir bersamaan.
2) Waktu inkubasi pada umumnya pendek
b. Tren Siklus
Tren jangka pendek dan tren jangka panjang beberapa penyakit
ternyata
membentuk
siklus, dimana
perubahan-perubahan angka
kesakitan terjadi secara berulang dengan selang antara beberapa hari,
beberapa bulan (musiman), tahunan, atau beberapa tahun. Peristiwa
13
semacam ini dapat terjadi, baik pada penyakit infeksi maupun penyakit
bukan infeksi (Lapau, 2009).
Beberapa siklus penyakit bersifat musiman, beberapa yang lain
mungkin dikendalikan oleh faktor siklus lain, seperti: tahun ajaran
sekolah, pola migrasi, durasi dan perjalanan penyakit, penempatan
militer, dan perang (Lapau, 2009).
Timbulnya atau memuncaknya angka kesakitan atau kematian
suatu penyakit yang ditularkan melalui vektor secara siklus ini
berhubungan dengan (Lapau, 2009):
a. Ada tidaknya keadaan yang memungkinkan transmisi penyakit oleh
vektor yang bersangkutan, yaitu apakah terdapat temperatur atau
kelembaban yang memungkinkan transmisi.
b. Adanya tempat perkembangbiakan alami dari vektor yang menjamin
kepadatan vektor yang diperlukan dalam transmisi.
c. Selalu adanya kerentanan.
d. Adanya kegiatan berkala dari orang yang rentan yang menyebabkan
mereka terserang oleh vector borne disease tertentu.
e. Kemampuan agen infektif untuk menimbulkan penyakit tetap tinggi.
f. Adanya faktor-faktor lain yang belum diketahui.
Hilangnya atau berubahnya siklus berarti terdapat perubahan dari
salah satu atau lebih hal-hal tersebut di atas.
c. Tren Sekuler (Jangka Panjang)
Yaitu, terjadinya perubahan angka kesakitan yang berlangsung
dalam periode waktu yang panjang atau dalam waktu yang lama,
bertahun-tahun, atau berpuluh tahun. Kecenderungan sekuler dapat
terjadi pada penyakit menular maupun penyakit infeksi non menular.
Misalnya, terjadinya pergeseran pola penyakit menular ke penyakit tidak
menular di negara maju pada dasawarsa terakhir (Kasjono dan
Kristiawan, 2009).
d. Variasi dan Tren Musiman
Pola yang konsisten dapat dilihat pada beberapa penyakit atau
kondisi yang terjadi dalam satu tahun. Peningkatan insiden penyakit atau
kondisi pada bulan-bulan tertentu, dengan variasi siklus berdasarkan
tahun dan musim memperlihatkan adanya tren musiman pada suatu
penyakit (Kasjono dan Kristiawan, 2009).
14
Variasi ini dihubungkan dengan perubahan secara musiman dari
produksi, distribusi, dan konsumsi dari bahan-bahan makanan yang
mengandung bahan yang dibutuhkan untuk pemeliharaan gizi, maupun
keadaan kesehatan individu, terutama dalam hubungan dengan penyakit
infeksi (Kasjono dan Kristiawan, 2009).
e. Variasi dan Tren Random
Yaitu terjadinya
epidemi
yang
tidak
dapat
diramalkan
sebelumnya, misalnya epidemi yang tejadi karena adanya bencana alam
seperti banjir, tsunami, atau gempa bumi (Subaris dkk, 2004).
2.5 Ciri-Ciri Studi Epidemiologi Deskriptif
Secara umum, ciri-ciri studi epidemiologi deskriptif adalah sebagai berikut
(Murti, 2011):
1. Bertujuan untuk menggambarkan.
2. Tidak terdapat kelompok pembanding.
3. Hubungan sebab akibat hanya merupakan suatu perkiraan ataau semacam
asumsi.
4. Hasil penelitiannya berupa formula hipotesis.
5. Merupakan studi pendahuluan untuk studi yang mendalam.
2.6 Kegunaan Studi Epidemiologi Deskriptif
Hasil penelitian studi epidemiologi deskriptif dapat digunakan untuk
(Subaris dkk, 2004):
1. Untuk menyusun perencanaan pelayanan kesehatan.
2. Untuk menentukan dan menilai program pemberantasan penyakit yang
telah dilaksanakan.
3. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitain lebih lanjut.
4. Untuk membandingkan frekuensi distribusi morbiditas atau mortalitas
antara wilayah atau satu wilayah dalam waktu yang berbeda.
2.7 Kategori Studi Epidemiologi Deskriptif
Berdasarkan unit pengamatan, epidemiologi deskriptif dibagi menjadi 2
kategori, yaitu studi populasi dan studi individu.
2.7.1 Studi Populasi
Studi populasi terdiri dari studi ekologis/korelasi yang merupakan studi
awal dengan seluruh populasi sebagai unit, dan studi rangkaian berkala (time
15
series) terhadap populasi. Karakteristik dari populasi yang akan diteliti biasanya
tergantung pada minat seorang peneliti, misalnya: jenis kelamin, umur, kebiasaan
mengkonsumsi makanan tertentu, obat-obatan, rokok, aktivitas, tempat tinggal,
atau variabel lainnya (Murti, 2011).
2.7.2 Studi Individu
Studi individu terdiri dari: laporan kasus (case report), rangkaian kasus
(case series), dan studi potong lintang (cross-sectional).
1.
Case series
Case series merupakan serangkaian laporan pasien (serangkaian case
report) yang mencakup pengobatan yang diberikan. Case series berisi data diri
pasien yang meliputi informasi demografis (usia, seks, etnis) dan informasi
tentang diagnosis, pengobatan, perawatan, sampai dengan tindak lanjut setelahnya
(Budiarto, 2004).
Case series digunakan ketika penyakit yang diteliti bukan penyakit biasa
dan disebabkan oleh pajanan eksklusif atau hampir eksklusif (seperti vinyl
chloride dengan angiosarcoma). Hal ini merupakan hal pertama yang bisa
dilakukan untuk menemukan petunjuk dalam identifikasi sebuah penyakit baru
dan untuk melihat dampak pajanan bagi kesehatan (Budiarto, 2004).
Karena merupakan laporan per pasien tanpa populasi kontrol sebagai
perbandingan, case series tidak memiliki validitas statistik. Case series berguna
untuk mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan klinis,
dan prognosis kasus. Case series banyak dijumpai dalam literatur kedokteran
klinik. Tetapi desain studi ini lemah untuk memberikan bukti kausal, sebab pada
case series tidak dilakukan perbandingan kasus dengan non-kasus. Case series
dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dengan desain studi
analitik (Budiarto, 2004).
2.
Case report
Merupakan laporan kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan
manifestasi klinis, perjalanan klinis, dan prognosis kasus. Laporan kasus
merupakan rancangan studi yang menggambarkan kejadian satu kasus baru yang
menarik. Misalnya, terjadinya kasus keracunan methyl mercury di Teluk
16
Minamata, Jepang. Case report mendeskripsikan cara klinisi mendiagnosis dan
memberi terapi kepada kasus, dan hasil klinis yang diperoleh. Selain tidak
terdapat kasus pembanding, hasil klinis yang diperoleh mencerminkan variasi
biologis yang lebar dari sebuah kasus, sehingga case report kurang reliabel untuk
memberikan bukti empiris tentang gambaran klinis penyakit (Subaris dkk, 2004).
3.
Cross sectional (studi potong lintang)
Cross sectional meliputi studi prevalensi dan survei epidemiologi yang
berguna untuk mendeskripsikan penyakit dan paparan pada populasi pada satu
titik waktu tertentu. Data yang dihasilkan dari studi potong lintang adalah data
prevalensi. Studi potong lintang juga dapat digunakan untuk meneliti hubungan
paparan-penyakit sekalipun bukti yang dihasilkan tidak kuat untuk menarik
kesimpulan kausal antara paparan dan penyakit, karena dengan desain studi ini
tidak dapat dipastikan bahwa paparan mendahului penyakit (Murti, 2011).
Studi cross sectional adalah sebuah studi deskriptif tentang penyakit dan
status paparan, dimana keduanya diukur secara bersamaan dalam sebuah populasi
tertentu. Studi ini mempelajari hubungan penyakit dengan paparan secara acak
terhadap satu individu dimana faktor pencetus dan status penyakit diteliti pada
waktu yang sama (Murti, 2011).
Studi cross sectional bertujuan menyediakan sebuah gambaran frekuensi
dan karakteristik dari penyakit di populasi pada suatu titik dalam waktu tertentu.
Data yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai prevalensi dari kondisi akut
atau kronis di sebuah populasi (Murti, 2011).
2.8 Langkah-Langkah Studi Epidemiologi Deskriptif
Penelitian dengan studi epidemiologi deskriptif mempunyai langkah
penting seperti berikut:
1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan
2.
3.
4.
5.
melalui metode deskriptif.
Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
Menentukan kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian dan atau
hipotesis penelitian deskriptif.
17
6. Mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal
ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen,
mengumpulkan data, dan menganalisis data.
7. Mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan
menggunakan teknik statistika deskriptif yang relevan.
8. Melakukan pengolahan dan analisis data deskriptif.
9. Menyajikan data.
10. Membuat laporan penelitian.
2.9 Keuntungan dan Kerugian Studi Epidemiologi Deskriptif
2.9.1 Keuntungan dan Kerugian Secara Umum
Beberapa keuntungan dari studi epidemiologi deskriptif adalah (Subaris
dkk, 2004):
1. Mudah dilakukan dan relatif murah daripada studi epidemiologi analitik.
2. Memberikan masukan tentang pengalokasian sumber daya dalam rangka
perencanaan yang efisien.
3. Dapat memberikan gambaran
mengenai
pola
penyakit
dan
kecenderungan terjadinya penyakit berdasarkan karakteristik orang,
tempat, dan waktu.
4. Dapat memberikan informasi penting mengenai potensi penting dan
faktor risiko, seperti: umur, jenis kelamin, dan letak geografis untuk
keperluan perbandingan terhadap prevalensi suatu penyakit dan
pembuatan suatu formula hipotesis pada studi analisis.
5. Merupakan informasi dasar untuk keperluan perencanaan, pelayanan, dan
evaluasi program pelayanan kesehatan pada masyarakat.
6. Memberikan petunjuk awal untuk merumuskan hipotesis bahwa suatu
variabel merupakan faktor risiko penyakit.
Sedangkan kerugian studi epidemiologi deskriptif adalah (Subaris dkk,
2004):
1. Tidak dapat digunakan untuk uji etiologi hipotesis karena tidak ada
kelompok kontrol atau kelompok pembanding.
2. Tidak dapat menentukan adanya asosiasi atau hubungan antara faktor
risiko dengan masalah kesehatan atau penyakit.
18
2.9.2 Keuntungan dan Kerugian Dari Setiap Jenis Studi Epidemiologi
Deskriptif
Secara khusus keuntungan dan kerugian pada setiap jenis penelitian
epidemiologi deskriptif adalah sebagai berikut:
1.
Studi ekologi/korelasi
Kelebihan dari studi korelasi adalah sangat tepat bila digunakan sebagai
dasar penelitian untuk melihat hubungan antara fakor paparan dengan penyakit,
karena mudah dilakukan dengan informasi yang tersedia sehingga dapat muncul
hipotesis kausal dan selanjutnya dapat diuji dengan rancangan studi epidemiologi
analitik (Timmreck, 2004).
Kelemahan dari studi korelasi adalah studi korelasi mengacu pada populasi
(kelompok), sehingga tidak dapat mengidentifikasikan kondisi per individu dalam
kelompok tersebut. Selain itu, dalam studi korelasi juga tidak dapat mengontrol
faktor perancu yang potensial (Timmreck, 2004).
2.
Case Series dan Case Report
Kelebihan atau keuntungan studi ini adalah (Timmreck, 2004):
a. Sebagai langkah awal untuk mempelajari suatu penyakit.
b. Sebagai penghubung antara penelitian klinis dan penelitian epidemiologi.
c. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dengan melihat
adanya kelompok yang berisiko tinggi.
d. Dapat merumuskan hipotesis yang akan diuji dengan desain studi analitik.
e. Dapat mendeskripsikan spektrum penyakit, manifestasi klinis, perjalanan
klinis, dan prognosis kasus.
f. Case report mendeskripsikan cara klinisi mendiagnosis dan memberi terapi
kepada kasus, dan hasil klinis yang diperoleh.
Kelemahan atau kerugiannya adalah (Timmreck, 2004):
a. Case series tidak memiliki validitas statistik.
b. Case series lemah untuk memberikan bukti kausal.
c. Case report kurang reliabel untuk memberikan bukti empiris tentang
gambaran klinis penyakit.
d. Tidak memiliki grup kontrol.
e. Tidak dapat dilakukan studi hipotesis
3.
Cross sectional
19
Keuntungan atau kekuatan penelitian cross sectional adalah sebagai
berikut (Murti, 2011):
a. Studi
cross
sectional
memungkinkan
penggunaan
populasi
dari
masyarakat umum, tidak hanya para pasien yang mencari pengobatan,
b.
c.
d.
e.
sehingga generalisasinya cukup memadai.
Relatif murah dan hasilnya cepat diperoleh.
Dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus.
Jarang terancam loss to follow-up (drop out).
Dapat dimasukkan ke dalam tahapan pertama suatu penelitian kohort atau
eksperimen, tanpa atau dengan sedikit sekali menambah biaya.
f. Dapat dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang bersifat
lebih konklusif.
g. Membangun hipotesis dari hasil analisis.
Sedangkan kerugian atau kelemahan penelitian cross sectional adalah
sebagai berikut (Murti, 2011):
a. Sulit untuk menentukan sebab akibat karena pengambilan data risiko dan
efek dilakukan pada saat yang bersamaan.
b. Studi prevalen lebih banyak menjaring subyek yang mempunyai masa sakit
yang panjang daripada yang mempunyai masa sakit yang pendek karena
inidividu yang cepat sembuh atau cepat meninggal mempunyai kesempatan
yang lebih kecil untuk terjaring dalam studi.
c. Dibutuhkan jumlah subyek yang cukup banyak, terutama apabila variabel
d.
e.
f.
g.
yang dipelajari banyak.
Tidak menggambarkan perjalanan penyakit, insidensi maupun prognosis.
Tidak praktis untuk meneliti kasus yang jarang.
Hanya akurat apabila dilaksanakan pada individu yang representatif.
Tidak tepat untuk meneliti hubungan kausal antara penyakit dengan
pemicunya karena penelitian dilakukan pada satu waktu.
h. Tidak dapat dilaksanakan pada semua kasus.
2.10 Interpretasi Hasil Studi Epidemiologi Deskriptif
Analisis
dan
interpretasi
hasil
penelitian
epidemiologi
semakin
berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu matematika dan ilmu statistik.
Untuk menginterpretasikan dan menyajikan data dari hasil studi epidemiologi
deskriptif dapat dilakukan, antara lain, dengan menggunakan perhitungan statistik
deskriptif (Budiarto dan Anggraeni, 2002).
20
Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk mengumpulan, menyajikan,
dan menganalisis data dalam bentuk narasi, tabulasi, atau diagram, serta untuk
menghitung persentase, nilai rata-rata, standar deviasi, dan berbagai perhitungan
dari data sampel, tanpa perlu meramalkan atau membuktikan hasil statistik
terhadap grup data yang lebih luas atau populasi (Budiarto dan Anggraeni, 2002).
Data dari hasil studi epidemiologi deskriptif akan diolah sehingga data
akan dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, diagram, serta dapat disajikan
dalam distribusi frekuensi, prevalensi, nilai rata-rata, standar deviasi, dan berbagai
perhitungan statistik lainnya.
2.11Contoh Penelitian yang Menggunakan Studi Epidemiologi Deskriptif
dalam Bidang Kesehatan Reproduksi
Suatu penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nur Djannah dan Ika Sukma
Arianti pada tahun 2009, ditujukan untuk mengetahui gambaran epidemiologi
kejadian preeklamsia/eklamsia di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun
2007-2009.
Populasi
pada
penelitian
ini
adalah
seluruh
kejadian
preeklamsia/eklampia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun
20072009. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik
totality sampling, yaitu seluruh kejadian preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 20072009, sebanyak 118 kasus. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan
dokumen- dokumen resmi RS PKU Muhammadiyah. Dokumen-dokumen yang
digunakan dalam penelitian ini berupa buku registrasi pasien dan berkas rekam
medis (medical record). Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari pencatatan rekam
medis (medical record) pasien yang dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammdiyah
Yogyakarta tahun 20072009. Data rekam medis ini memuat keadaan umum
pasien, yang berisi keterangan tentang nama, nomor rekam medis, jenis
kelamin, umur, alamat, serta diagnosis sekunder. Dari data rekam medis yang
diperoleh, kemudian dilakukan analisis data rekam medis (medical record), yang
meliputi (Djannah dan Arianti, 2010):
a. Editing: memeriksa kelengkapan data dan mencocokkan dengan
21
hasil dari buku rawat inap.
b. Scoring: menghitung jumlah dan persentase tentang karakteristik yang
diteliti.
c. Tabulating: data disajikan dalam bentuk tabel/grafik menggunakan sistem
komputerisasi kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif.
d. Analisis: melakukan analisis deskriptif berdasarkan hasil tabulasi.
Pada penelitian ini, variabel yang diteliti dan dideskripsikan pada sampel
meliputi:
1. Karakteristik Orang
a.
Usia
Pada penelitian deskriptif kejadian preeklamsia/eklamsia ini, sampel
yang diambil adalah semua ibu penderita preeklamsia/eklamsia di Rumah
Sakit
PKU
Muhammadiyah
Yogyakarta
tahun
20072009
tanpa
mengelompokkan umur ibu sehingga data variabel umur merupakan data
dengan skala rasio. Berikut tabel hasil dari penelitian tersebut.
22
Tabel 1. Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Usia Ibu
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
JUMLAH
USIA IBU
16 tahun
17 tahun
19 tahun
20 tahun
21 tahun
22 tahun
23 tahun
24 tahun
25 tahun
27 tahun
28 tahun
29 tahun
30 tahun
31 tahun
33 tahun
34 tahun
35 tahun
37 tahun
38 tahun
JUMLAH
1
3
7
5
4
4
6
3
4
5
7
11
5
8
7
11
13
7
7
118
PERSENTASE
0,85
2,54
5,93
4,24
3,39
3,39
5,08
2,54
3,39
4,24
5,93
9,32
4,24
6,78
5,93
9,32
11,03
5,93
5,93
100
Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat distribusi frekuensi penderita
preeklamsia/eklamsia berdasarkan usia ibu. Kemudian, berdasarkan data dari
tabel dapat dihitung:
a. Mean = 28,95 tahun dengan standar deviasi = 6,16 tahun.
Rata-rata umur ibu penderita preeklamsia/eklamsia di Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 20072009 adalah
28,95 tahun.
b. Modus = 35 tahun. Berdasarkan data usia ibu, penderita
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah
Yogyakarta tahun 20072009 terbanyak adalah usia 35 tahun
dengan jumlah penderita sebanyak 13 orang atau 11,03% dari
seluruh penderita.
c. Median = 29 tahun dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal
38 tahun.
23
Median atau nilai tengah dari data yang didapatkan terletak
pada pada ke-59, yaitu pada usia 29 tahun.
b. Paritas
Pada proses scoring untuk mendeskripsikan paritas pada penelitian
ini, data mengenai paritas sampel dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu:
primigravida dan multigravida sehingga variabel paritas memiliki skala data
ordinal. Berikut tabel hasil dari penelitian tersebut.
Tabel 2 Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Paritas
NO.
KELOMPOK
JUMLAH
PERSENTASE
USIA
1.
Primigravida
2.
Multigravida
JUMLAH
Dari penelitian tersebut
dapat
82
36
118
dilihat
bahwa
69,5
30,5
100
kejadian
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
pada tahun 20072009 terbesar, yaitu pada kelompok ibu primigravida
dengan jumlah 82 orang (69,5 persen), dan angka terendah terjadi pada
kelompok multigravida dengan jumlah 36 orang (30,5 persen).
c. Tingkat ANC (Ante Natal Care)
Pada proses scoring untuk mendeskripsikan tingkat ANC pada
penelitian ini, data sampel dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu: ibu
hamil yang melakukan ANC < 4 kali dan yang melakukan ANC 4 kali .
Berikut tabel hasil dari penelitian tersebut.
Tabel 3 Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Tingkat ANC
NO.
1.
2.
JUMLAH
TINGKAT ANC
JUMLAH
< 4 kali
4 kali
Berdasarkan
tabel
PERSENTASE
90
28
118
3
dapat
dilihat
76,3
23,7
100
bahwa
kejadian
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
24
pada tahun 20072009 berdasarkan tingkat ANC ibu lebih didominasi oleh
penderita yang melakukan ANC kurang dari 4 kali dengan jumlah 90 orang
(76,3 persen), dan angka terendah terjadi pada kelompok penderita yang
melakukan ANC lebih dari atau sama dengan 4 kali ( 4 kali) dengan jumlah
28 orang (23,7 persen).
d. Riwayat Hipertesi
Pada proses scoring untuk mendeskripsikan riwayat hipertensi pada
penelitian ini, data sampel dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu: ibu
hamil yang ada riwayat hipertensi dan yang tidak ada riwayat hipertensi
sehingga variabel riwayat hipertensi memiliki skala data ordinal. Berikut
tabel hasil dari penelitian tersebut.
Tabel 4 Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Riwayat
Hipertensi
NO.
RIWAYAT
JUMLAH
PERSENTASE
HIPERTENSI
1.
2.
JUMLAH
Ada
Tidak ada
Berdasarkan
tabel
19
99
118
4
dapat
dilihat
16,1
83,9
100
bahwa
kejadian
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
pada tahun 20072009 berdasarkan riwayat hipertensi lebih didominasi
oleh kelompok penderita yang tidak memiliki riwayat hipertensi dengan
jumlah 99 orang (83,9 persen), dan 19 orang (16,1 persen) terjadi pada
kelompok yang tidak memiliki riwayat hipertensi.
e. Tingkat Pendidikan
Pada proses scoring untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan pada
penelitian ini, data sampel dikelompokkan dalam 5 kelompok menurut tingkat
pendidikan sehingga variabel tingkat pendidikan memiliki skala data ordinal.
Berikut tabel hasil dari penelitian tersebut.
25
Tabel 5 Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Tingkat
Pendidikan
NO.
KELOMPOK
JUMLAH
PERSENTASE
USIA
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH
Tidak Sekolah
SD
SLTP
SLTA
PT
23
8
15
47
35
118
19,5
6,8
12,7
39,8
21,2
100
Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa distribusi kejadian
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada
tahun 20132015 berdasarkan tingkat pendidikan lebih didominasi oleh
kelompok dengan tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 47 orang (39,8
persen), dan angka terendah terjadi pada kelompok dengan tingkat
pendidikan SD dengan jumlah 8 orang (6,8 persen).
f. Jenis Pekerjaan
Pada proses scoring untuk mendeskripsikan jenis pekerjaan pada
penelitian ini, data sampel dikelompokkan dalam 5 kelompok sehingga
variabel jenis pekerjaan memiliki skala data ordinal. Berikut tabel hasil dari
penelitian tersebut.
Tabel 6 Data Penderita Preeklamsia/Eklamsia Menurut Jenis Pekerjaan
NO.
JENIS
JUMLAH
PERSENTASE
PEKERJAAN
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH
Buruh
Wiraswasta
PNS
Tani
Tidak bekerja
1
31
9
2
75
118
0,8
26,3
7,6
1,7
63,5
100
26
Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa distribusi kejadian
preeklamsia/eklamsia di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
pada tahun 20072009 berdasarkan jenis pekerjaan didomonasi oleh
kelompok penderita yang tidak bekerja dengan jumlah 75 orang (63,5 persen),
dan angka terendah justru terjadi pada kelompok yang memiliki jenis
pekerjaan sebagai buruh yaitu sebanyak 1 orang (0,8 persen).
2.
Karakteristik Tempat
Penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
dimana menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Rumah Sakit
PKU Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu rumah sakit dengan
penderita preeklamsia/eklamsia yang tinggi dan merupakan rumah sakit rujukan
tingkat 2.
3. Karakteristik Waktu
Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 20072009 dimana pada tahun
tersebut didapatkan data rekam medis penderita preeklamsia/eklamsia di Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta cukup banyak.
27
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Studi epidemiologi deskriptif adalah suatu studi yang menggambarkan
pola-pola kejadian penyakit, atau pola-pola pemaparan dalam kaitannya
dengan variabel orang (populasi), tempat (letak geografis), dan waktu.
2. Epidemiologi deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan distribusi
penyakit dan kecenderungan (trend) penyakit pada populasi serta
memahami distribusi dan mengetahui besarnya masalah kesehatan pada
populasi. Sedangkan epidemiologi analitik bertujuan untuk mempelajari
determinan/faktor resiko/penyebab penyakit dan menemukan strategi yang
efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit.
3. Data dari hasil studi epidemiologi deskriptif disajikan dalam bentuk narasi,
tabel, diagram, serta dapat berupa perhitungan statistik, seperti: distribusi
frekuensi, prevalensi, nilai rata-rata, dan standar deviasi.
4. Keuntungan dari penggunaan desain studi epidemiologi deskriptif antara
lain adalah mudah dilakukan, relatif murah, serta dapat memberikan
informasi dasar untuk keperluan perencanaan, pelayanan, dan evaluasi
program pelayanan kesehatan pada masyarakat.
5. Kerugian studi epidemiologi deskriptif adalah tidak dapat digunakan untuk
uji hipotesis dan tidak dapat menentukan adanya asosiasi atau hubungan
antara faktor risiko dengan masalah kesehatan.
3.2 Saran
Semua praktisi kesehatan, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan
disarankan untuk memiliki pengetahuan tentang studi epidemiologi deskriptif
karena data yang disajikan dari hasil studi epidemiologi deskriptif merupakan data
mentah dan real pada populasi serta dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai
kebijakan, terutama kebijakan di bidang kesehatan.
28
DAFTAR PUSTAKA
Azwar, Azrul. 1999. Pengantar Epidemiologi. Jakarta. Binarupa Aksara.
Budiarto, Eko. 2004. Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah Pengantar.
Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Budiarto, E., dan Anggraeni, D. 2002. Pengantar Epidemiologi Edisi 2. Jakarta.
Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Bustan, M.N., dan Arsunan, A. 1997. Pengantar Epidemiologi. Jakarta. PT.
Rineka Cipta.
Djannah, S.N., Arianti, I.S. 2010. Gambaran Epidemiologi Kejadian
Preeklamsia/Eklamsia di RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun
2007-2009. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Volume 13 Nomor 4
Oktober 2010:378-385
Harlan, Johan. 2006. Epidemiologi Kebidanan. Jakarta. Universitas Gunadarma.
Kasjono, H.H.S., dan Kristiawan, H.B. 2009. Intisari Epidemiologi. Yogyakarta.
Mitra Cendikia Press.
Lapau, Buchari. 2009. Prinsip dan Metode Epidemiologi. Jakarta. Universitas
Indonesia
Murti, Bhisma. 2011. Desain Studi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
Noor, N.Nasri. 1997. Dasar Epidemiologi. Jakarta. PT Rineka Cipta
Rajab, Wahyudin. 2012. Buku Ajar Epidemiologi Untuk Mahasiswa Kebidanan.
Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Subaris, H., Aritonang, I., Riwidigdo, H., Palestin, B., Winarti, S.A. 2004.
Manajemen Epidemiologi. Yogyakarta. Politeknik Kesehatan Yogyakarta.
29
Timmreck, Thomas C. 2004. Epidemiologi: Suatu Pengantar. Jakarta. Penerbit
Buku Kedokteran EGC.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5813)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2327)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20098)
- The Wind in the Willows: Classic Tales EditionDari EverandThe Wind in the Willows: Classic Tales EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3464)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3310)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6538)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2571)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12954)