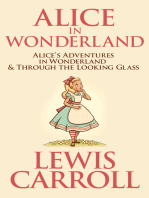Beragama Untuk Manusia
Diunggah oleh
Ahmad Syarif0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
4 tayangan2 halamanAgama, Tuhan, dan manusia
Judul Asli
BERAGAMA UNTUK MANUSIA
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniAgama, Tuhan, dan manusia
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
4 tayangan2 halamanBeragama Untuk Manusia
Diunggah oleh
Ahmad SyarifAgama, Tuhan, dan manusia
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
BERAGAMA UNTUK MANUSIA
Oleh
Ahmad Syarif H
(Penikmat Islamic Studies, dan Pengajar di UIN Raden Fatah
Palembang)
Adalah fakta bahwa kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan,
ketertindasan, ketidakadilan, dan semacamnya hingga tingkat
tertentu masih merupakan realitas keseharian sebagian besar umat Islam di banyak belahan
dunia, tak terkecuali di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Banyak hal bisa dituding
sebagai sebab, baik berupa anasir absolut maupun struktural-sistemik. Namun, terlepas
apapun penyebab utama dari realitas dimaksud, impotensi umat Islam menghadapi kenyataan
ini tentu ironis demi menyadari betapa sesungguhnya Islam sarat akan spirit revolusioner
yakni nilai-nilai moral yang membebaskan, yang mendorong ke arah terciptanya tatanan
hidup yang lebih baik, layak, dan manusiawi.
Banyak alasan yang bisa disebut mengapa ketakberdayaan itu berlarut. Salah satunya ialah
ketiadaan motivasi religius. Sejauh menyangkut lan-vital ajaran Islam sendiri, fakta
ketakberdayaan umat itu memang berkait rekat dengan ketiadaan motivasi religius yang
mampu berperan sebagai motivator perubahan, yang berperan transformatif dan
menggerakkan mereka untuk membebaskan diri dari semrawut realitas sosial tak
mengenakkan. Ketiadaan motivasi religius itu membuat apa yang kita sebut transformasi
sosial secara total nyaris tak pernah berlangsung secara signifikan di dunia Islam, termasuk di
tengah umat islam di negeri ini.
Lalu bagaimana mencari motivasi religious bervisi revolusioner-transformatif tersebut?
jika kita melihat lebih mendalam terkait sikap umum umat islam yang terkesan pasrah akan
nasib dan keadaan serta jauh dari semangat juang untuk hidup lebih layak dan berkemajuan,
setidaknya hal tersebut dipengaruhi oleh pola pemahaman teologis yang sangat bersifat
teosentris. Artinya pola pemahaman keagamaan umat islam sangat didominasi oleh hal-hal
yang bersifat vertical (hal-hal yang hanya berhubungan dengan Tuhan). Aspek ibadah dan
pemahaman akan konsep-konsep taqwa, iman, islam dan ihsan serta kesalehan dan ketaatan
sangat didominasi oleh pola pikir melangit ini. Sehingga kemudian hal-hal keduniawian
yang merupakan fakta yang sedang dihadapi dan dirasakan dalam kehidupan mereka
sekarang seakan terlepas dari unsur-unsur religiusitas (doktrin keagamaan). Fakta ini terlihat
misalkan dari mewabahnya pemahaman yang masih sangat dalam melekat pada setiap umat
islam di negeri ini yang menganggap bahwa barometer kesalehan dan atau ketaqwaan
seseorang sangat ditentukan oleh seberapa sering seorang muslim pergi ke masjid, ke
Mekkah, atau melakukan ibadah ritual lainnya. Sangat jarang ,untuk mengatakan tidak,
penilaian kesalehan dan ketaqwaan tersebut ditujukan pada mereka yang peduli lingkungan,
peduli anak yatim, atau kepada para aktivis pembela keadilan dan pembela hak-hak manusia
yang sedang dizalimi.
Hemat penulis, pola pemahaman keagamaan serta konsep-konsep teologis yang mendasari
pemikiran teosentris di atas perlu dirumus ulang agar sejalan dengan semangat pembebasan.
Pada prinsipnya, reformulasi ini merupakan suatu proses reflektif-kritis secara teologis yang
berlandaskan hasil pemaknaan teks (al-Quran dan hadits) dan pemahaman konteks kekinian
(realitas aktual-faktual). Dalam hal itu, setidaknya, terdapat tiga konsep teologis yang
mendesak untuk dirumus-ulang dalam kerangka paradigma transformatif yang berpihak pada
kepentingan pembelaan pembebasan kaum mustadlafn (orang-orang yang belum beruntung
secara sosial dan ekonomi).
Pertama, konsep Tawhd. Pada dasarnya konsep ini merupakan doktrin pokok dalam
keseluruhan teologi Islam klasik. Dalam konteks pembebasan, tawhd harus dipahami dan
diyakini sebagai penggambaran adanya unity of godhead, kesatuan ketuhanan. Keyakinan
atasnya menurunkan konsep penegas adanya unity of creation, kesatuan penciptaan. Dalam
konteks sosial-horisontal, kesatuan penciptaan itu memberi suatu keyakinan adanya unity of
mankind, kesatuan kemanusiaan. Kesadaran teologis akan kesatuan kemanusiaan menegaskan
bahwa tawhd menolak segenap bentuk penindasan atas kemanusiaan. Dalam konteks Islam,
kesatuan kemanusiaan itu menghendaki adanya unity of guidance (kesatuan pedoman hidup;
al-Quran dan hadits) bagi orang-orang Mukmin. Dengan demikian tawhd secara konseptual
memberi arahan kepada adanya unity of purpose of life (kesatuan tujuan hidup), bergerak
menuju muara tunggal, Allah swt.
Pemahaman tawhd sedemikian tidak hanya diarahkan secara vertikal untuk membebaskan
manusia dari ketersesatan dalam bertuhan, tapi juga secara sosial-horisontal dikehendaki
berperan sebagai teologi yang membebaskan manusia agar terlepas dari seluruh anasir
penindasan. Cita pembebasan manusia dari ketertindasan, merupakan salah satu aqdah
ilhiyah. Elaborasi lebih jauh dari pemahaman tawhd semacam ini menuntut pula redefinisi
terhadap entitas makna mn, nilai kufr dan sebutan kfir, dan pada akhirnya reposisi entitas
makna Islam dan Muslim searah dengan kepentingan praksis pembebasan.
Kedua, konsep Keadilan Sosial. Pengedepanan konsep ini bertolak dari kesadaran bahwa
ketidakadilan sosial (kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, eksploitasi, diskriminasi, dan
dehumanisasi) merupakan produk dari suatu proses sosial via struktur dan sistem yang tidak
adil, yang terjadi lantaran proses sejarah manusia. Artinya, realitas sosial yang tidak adil
bukanlah taqdir Tuhan, melainkan hasil dari proses sejarah yang disengaja. Bukan pula
semata akibat ada yang salah dalam bangunan mentalitas-budaya manusia, melainkan imbas
langsung dari diselenggarakannya sistem dan struktur yang tidak adil, eksploitatif, dan
menindas.
Ketiga, konsep Spiritualitas Pembebasan. Konsep ini merupakan konkretisasi dari proses
refleksi kritis atas realitas di satu sisi, dan atas fungsi utama ajaran Islam sebagai agama
pembebasan di sisi lain. Proses reflektif itu bermuara pada satu titik: spiritualitas
pembebasan. Ialah yang sesungguhnya mewarnai seluruh bangunan paradigmatik teologi
Islam yang transformatif dan membebaskan ini. Pembebasan dalam kerangka spiritualitas
tidak hanya diarahkan pada struktur-sistem yang menindas, tapi juga ia harus diarahkan pada
upaya membebaskan manusia dari hegemoni wacana tertentu seperti ia harus mengambil
tempat dan peran aktif dalam proses kontekstualisasi teks-teks keagamaan atas konteks
kekinian.
Dengan berteologi seperti tersebut di atas kita bisa berharap munculnya realitas sosial
kemanusiaan yang lebih menggembirakan. Dalam pada itu Islam sebagai entitas nilai maupun
agama (organized religion) akan benar-benar hadir sebagaimana spirit aslinya sebagai agama
yang membebaskan. Sebab, di sana ia mengemuka lebih sebagai verb daripada sebagai noun,
yang bergerak dinamis-inspiratif mengarah pada upaya perwujudan-pemenuhan keadilan
sosial. Melalui rekonstruksi teologi itu, Islam sebagai entitas ajaran harus mengambil jalan
mengubah dunia untuk mengubah manusia dan bukan mengubah manusia untuk
mengubah dunia. Dan, yang pasti, dengan cara berteologi demikian iman kita akan menjadi
iman yang hidup, dinamis. Sementara di sisi berbarengan, diharapkan silang-sengkarut tema-
tema perdebatan kalm Abad Pertengahan tidak lagi menguras habis energi umat, tapi secara
kreatif beralih mendorong pada pengembangan suatu pemikiran teologis yang lebih aktual
dan peduli pada derita kemanusiaan. Kiranya degan mereformulasi pemahaman teologis
keberislaman seperti tersebut di atas, kesadaran akan betapa beragama itu sebenarnya adalah
untuk manusia dan bukan untuk Tuhan seperti yang selama ini kita yakini, akan segera
terwujud dan mewujud dalam perilaku kita sehari-hari. Wallahu Alamu []
Anda mungkin juga menyukai
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20022)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3276)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)


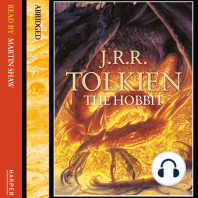
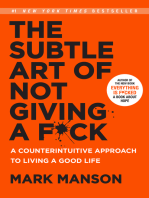







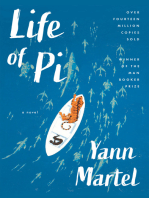







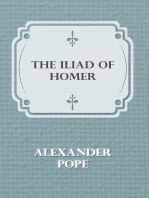



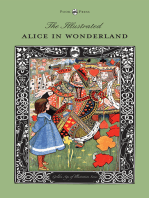

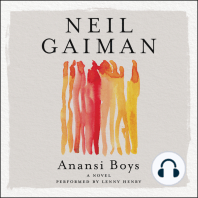
![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)