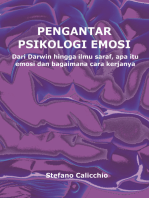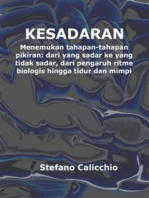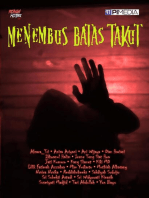Materi Bagian Dua
Diunggah oleh
Anonymous c5PUo7WHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Materi Bagian Dua
Diunggah oleh
Anonymous c5PUo7WHak Cipta:
Format Tersedia
MATERI BAGIAN DUA
EPISTEMOLOGI
PENELITIAN KEBUDAYAAN
A. OBYEKTIVITAS DAN SUBYEKTIVITAS
1. Paham Interpretasi dan Etnografi Imajinasi
Masalah pelik yang sering menghantui peneliti budaya adalah
ihwal obyektivitas dan subyektivitas. Persoalan ini, kadang-
kadan~ menjadi perbincangan yang tak ada ujung pangkalnya di
kalangar penelitian budaya. Karena, banyak pihak selalu
berpendapat bahwa penelitian budaya yang cenderung memanfaatkan
penelitian kualitatif dianggap kurang objektif. Berbeda dengan
paradigama penelitian kuantitatif yang serba ilmiah dan
terkontrol. Hal ini pun oleh para peneliti budaya tidak ditolak.
Penelitian budaya sedikit mengabaikan prinsip obyektivitas jika
istilah objektif sebagai batasan penelitian yang harus terukur,
adz keberulangan, dan perilaku yang dapat diramalkan. Umumnya
penelit budaya tidak berpikir demikian, karena budaya
berhubungan dengar manusia, tentu saja subyektivitas tetap
memiliki peranan tersendiri Studi budaya yang menerapkan
pendekatan subyektivitas, biasany, disebut studi humanistik.
Paham ini berpandangan bahwa buday, bukan harga mati, melainkan
wilayah interpretatif.
Menurut pandangan subyektivitas, alih-alih rasional, teratur
atau sistematik, perilaku manusia bersifat kontekstual
berdasarkai makna yang diberikan di lingkungannya. Kalau ilmu di
luar huma niora lebih ke arah sebuah "kedisiplinan", humaniora
justru ke aral interpretasi alternatif. Posisi ilmu humaniora,
termasuk budaya, adalah pada "siapa" menentukan "apa yang
dilihat". Menurut paham ini realitas budaya termasuk fenomena
yang cair dan mudah berubah.
Fenomena ini bersifat polisemik yang memerlukan penafsiran.
Jadi, penelitian budaya selalu bergerak pada "koma-koma", bukan
pada "titik" (berhenti).
Ihwal objektivitas-ilmiah dan subjektivitas-tidak ilmiah di
atas, memang telah lama merambah dunia penelitian budaya,
terutama dengan hadirnya peneliti budaya tafsir. Hadirnya
penelitian tafsir budaya, telah memunculkan beberapa keberatan,
jika dikaitkan dengan ihwal objektivitas dan subjekvititas.
Tidak hanya Keesing yang berkeberatan, namun juga ahli-ahli lain
seperti Bleicher (1982:64) yang mempersoalkan kesahihan budaya
tafsir (hermeneutik). Kendati frame dia adalah sosiologi, namun
cukup memberikan ketajaman pikiran kita terhadap pandangan yang
selalu mengklaim objektivitas - selalu dikembalikan kepada ilmu
alam.
Padahal, ilmu sosial dan budaya tentu memiliki karakteristik
tersendiri. Karena itu, subjektivitas interpreter yang sering
memasukkan resepsi, kepekaan, akal sehat, dan pelukisan budaya
yang terbuka, mestinya tidak harus sama persis dengan 'self-
understanding'. Itulah sebabnya, objektivitas dalam ilmu sosial
dan humaniora tidak bisa absolut. Karena itu, untuk mencapai
objektivitas, Bleicher menyarankan adanya proses intersubjektif.
Melalui pandangan antar pemilik budaya dan peneliti,
objektivitas peneliti baru akan ditemukan.
Memang gejala barn, terutama karya etnografi sebagai karya
sastra, akan menghadirkan dilematis bagi peneliti budaya itu
sendiri. Yakni, hasil penelitian budaya itu sebuah ilmu atau
seni (science or art?). Kalau etnografi dipandang sebagai
sastra, lantas sampai dimana kita memperlakukannya sebagai
sumber data untuk membangun teori yang "objektif ' tentunya.
Kenyataan ini lalu menumbuhkan kesadaran baru peneliti budaya
dan menjadi salah satu ciri postmodernisme, yaitu bahwa
representasi, suatu penyajian dalam sebuah etnografi mengenai
kebudayaan suatu bangsa, pada dasarnya tidak pernah melukiskan
"sebagaimana adanya suatu ("reality out there"). Penyajian telah
dibungkus dalam kemasan tertentu. Kebudayaan sebagai teks,
memang tidak pernah tampil sebagaimana adanya. Dia telah
mengalami "distorsi" tertentu setelah melalui proses tafsir dan
kemudian disajikan.
Tafsir kebudayaan selalu dalam kerangka berpikir tertentu, tidak
bisa bebas. Oleh karena itu tidak pernah bisa "objektif',
sebagaimana adanya. Lantas, apa artinya kebenaran ilmiah? Kebe-
naran ilmiah bersifat relatif, kondisional dan tergantung pada
konsensus. Tak ada kebenaran mutlak. Benar dan salah adalah soal
konsensus. Karena itu, setiap ilmuwan budaya harus siap menerima
kritik atas kekurang-tepatan analisisnya. Relativitas dan
pluralitas, adalah dua ciri postmodernisme yang tetap perlu
diperhitungkan dalam kajian ilmiah budaya.
Dalam kaitan itu, Adorno (Jackson, 1996:22), berkomentar tentang
subyektivitas dan obyektivitas: "If the object lacked the moment
of subjectivity, its own objektivity would become nonsensical".
Maksudnya, jika objek tidak memiliki subjektivitas, objektivitas
itu tidak akan berguna. Dengan menyingkirkan subyek dari wacana
kebudayaan, berarti akan menyingkirkan kita dari lokasi budaya
itu sendiri.
Pendek kata, riset budaya perlu melaporkan segala yang ada, yang
mengitari budaya tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan Abu
Lughod, bahwa etnografer dapat menyusun kesadaran `subyek-
tivitas' yang selanjutnya diarahkan pada penulisan biografi
individu. Etnografi individu ini digambarkan melalui ceritera
seorang individu tentang keunikan kehidupannya.
Anggapan modern tentang subyektivitas, menurut Jackson (1996)
berasal dari Descartes, karena filsuf kondang ini menunjukkan
cogito sebagai titik tolak bagi filsafat. Kata ini tampak
diterjemahkan "aku berpikir" menjadi "aku menyadari". Tampaknya,
strukturalisme tidak menyukai kesadaran ini.
Subyektivitas seolah-olah telah dibongkar dan digusur, didirikan
bangunan baru lewat konsep linguistik struktural. Karena, temuan
Levi-Strauss telah mempergunakan `sistem' sebagai acuan. Sistem
mendapat prioritas, bukan "aku" yang berbicara-ada yang bicara
dalam "aku" (it speaks in me): sistem.
Hal tersebut telah dilakukan oleh Geertz dalam bukunya After the
Fact (1998). Melalui tulisan dia itu, berarti persoalan objektif
ilmiah dan subjektif-tidak ilmiah tak perlu diperdebatkan. Oleh
karena, menurut Geertz, dalam riset budaya kedua hal itu pasti
ada dan sulit terhindarkan.
Karena itu, kehadiran tafsir kebudayaan yang sering dikatakan
terlalu longgar, terlalu melebih-lebihkan, semakin menjauhkan
peneliti budaya dari fakta, tidak selalu tepat. Geertz pernah
berterus terang bahwa pada saat datang ke Indonesia, di UGM,
oleh para mahasiswa dianggap membuat bising (mengganggu). Lalu,
dia naik bus ke timur, tanpa tujuan. Akhirnya turun di Pare
(Mojokuto) dan dia anggap disitu tepat untuk diteliti. Lalu,
ketika datang ke UGM lagi, ia sampaikan hal yang ditemui, justru
mahasiswa UGM mengatakan: senang, daripada mengganggu.
Akhirnya, ia mampu menghasilkan Abangan, Santri, dan Priyayi
yang mungkin objektivitasnya bagi golongan tertentu diragukan,
namun bagi sebagian orang (terutama negara Geertz), karya dia
cukup memberi arti baru. Bahkan Knauff (1990:21) juga
mengomentari pribadi Geertz, yang telah menghasilkan banyak
karya lapangan dalam studi etnografi. Geertz dalam beretnografi
memiliki kelebihan dan lebih refleksif.
Begitu pula apa yang dilakukan Malinowski, pada saat bukunya
(catatan harian) diterbitkan isterinya, setelah dia meninggal,
juga sempat mengundang kecaman di kalangan peneliti budaya.
Setidaknya, dari buku harian itu, akan terlihat kejujuran
Malinovski ketika meneliti, ia harus berpura-pura "makan, minum"
dan sejumlah kegiatan yang lain, yang sebenarnya dia tidak suka.
Ada, peneliti budaya dianggap tidak jujur dan melebih-lebihkan.
Peneliti budaya dianggap main-main dalam sistem metodologisnya.
Jika semacam ini, apakah karya Malinowski lantas bebas dari
objektivitas, tentu saja tidak hams demikian. Sebab,
subyektivitas itu sendiri sebenarnya mengandung objektivitas.
Subjektivitas dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1)
sebagai pusat integrasi segala proses fisiologik, (2) penampilan
pribadi yang membawa konteks dan sejarah hidup pribadi dari
waktu yang lalu sampai saat mendatang, (3) dapat mengambil jarak
dari tubuh dan melihatnya sebagai obyek dalam aspeknya yang
meruang.
2. Mengambil Jarak dan Diskotinuitas Budaya
Manakala subjektivitas itu mampu meinasuki konteks dengan
mengambil jarak, sesungguhnya objektivitas pun akan ada juga.
Terlebih lagi, Anderson (1976:30) menyatakan bahwa: "We shall
define meaning, then, as, the place of a thing in a context;
when we grasp the place of a thing in context, we "understand"
it.
Memang diakui Bruner (1993:1-3) bahwa dalam konteks etnografi
tradisional, etnografer berpandangan harus objektif, memiliki
otoritas, netral dengan politik dan selalu mengamati dengan
pilar putih di dalam teks. Padahal, budaya itu selalu berubah
dan diproduksi terus, akibatnya makna bisa plural, selalu
terbuka dan sangat mungkin terkait dengan ihwal politik.
Persoalan pemahaman seseorang dan budaya, memang sangat menarik,
seperti halnya harus memahami ihwal perbedaan antara subjektif
dan objektif, menurut observer dan orang yang diamati.
Permasalahan ini akan terkait pula dengan soal ilmiah dan tidak
ilmiah dan juga humanistik atau science, akademik atau puistis,
ilmiah atau bernada sastra. Peneliti budaya yang menolak oposisi
semacam ini, lalu semua itu harus dikembalika ke perkecualian
individual.
Gagasan "scientifik", juga objektif, tergantung bagaimana
individu melaporkan hasil observasinya. Itulah sebabnya, The
Nuer karya Evans-Pritchard ada yang berpandangan lebih objektif.
Subjektivitas dimungkinkan terjadi manakala ada monografi yang
berupa ucapan terima kasih, kata pengantar, pendahuluan singkat,
dan otobiografi.
Jika begitu, kita bisa acung jempol kalau Bourdie (Jackson, '
1996:20-23) sejak semula telah mengejek objektivisme, karena
objektivitas telah mengubah lembaga menjadi aktivitas otomatis
yang mengikuti aturan teoritis. Bourdie menolak tentang
observasi yang berdiri terpisah dari tindakan manusia hanya
semata-mata untuk menjaga objektivitas, namun juba tidak benar
jika pengamatan dilakukan terlalu terlibat dalam situasi yang
diamati.
Dengan kata lain, ia menghindari adanya jebakan ke arah
irrasionalisme yang terpusat pada subjek, dan juga tidak setuju
terhadap jebakan ke arah objektivitas yang melihat sesuatu
secara mekanis. Menghadapi pernyataan semacam itu, Jackson cukup
bijaksana dalam menyikapi subjektivitas dan obektivitas, yakni
istilah ini akan selesai asalkan kita menyadari bahwa kita
sering sebagai `pembuat dunia' dan juga sering `diperbuat oleh
dunia'.
Atas dasar hal-hal tersebut, layak jika Barthes (1970:414)
berkomentar bahwa subyektivitas dan obyektivitas memang tidak
bisa dilihat seperti masa jaya jayanya positivisme. Dalam
strukturalisme yang bertekat ingin menjadi "penulis", tentunya
yang tidak menerapkan "gaya halus", tidak tertutup kemungkinan
ditemukan objektivitas. Lebih-lebih jika strukturalis itu
berupaya menemukan masalah penting dalam setiap ungkapan bahasa
dan bukan terjebak pada alam khayalan realis, melainkan selalu
berpegang teguh pada bahasa sebagai alat pemikiran.
Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan Hastrub (199:61-76)
bahwa peneliti budaya (etnografi) boleh disajikan melalui bahasa
khayal (imajinasi), seperti halnya metafora. Peneliti budaya
imajinasi memang tidak mempersoalkan standar keilmiahan dari
pemaparan etnografi. Namun, lebih menekankan angin baru ke arah
kreativitas penulisan etnografi yang artistik dan fantastik.
Akhirnya, kita memang tidak bisa menutup mata terhadap pandangan
ilmuwan kita dalam riset harus `objektif-ilmiah', namun hal ini
akan terbentur pada realitas itu sendiri. Artinya, apakah
kehadiran Anna Tsing dalam melukiskan marginalitas Dayak Meratus
atas fenomena politis itu, dengan gaya sastra, harus dicap
kurang objektif? Padahal, Strathern (1992:167) juga telah
mensugestikan bahwa budaya pada saatnya akan mengalami
diskontinuitas. Budaya akan mengalamai transformasi yang sulit
diramalkan. Ini adalah pekerjaan rumah dari para ilmuwan budaya
untuk berpikir lebih jernih.
Ihwal objektif dan subyektif ini secara rinci dapat dapat
dilihat pada pokok-pokok persoalan dalam penelitian budaya.
Pokok-pokok penelitian budaya yang sering dianggap menjadi biang
keladi obyektivitas dan subyektivitas adalah sebagai berikut.
Pokok-pokok objektif Subjektif
tian budaya
peneli
Hubungan Peneliti sebagai Hubungan
peneliti dan otonom, terpisah, interaktif,
antara
penelitian pengamat
tidak harus relatif
berjangkaakrab,
lama
subjek berjarak,
berjangka pendek ada
d timbal
Tujuan berkotak hal-hal setaraf
Menanganilangsung Menangani
balik,
untuk yang khusus,
penelitian umum,
diambil secara persoalan
yang diambil
generalisasi, oleh dan
terikat sampel kecil
terikat
acak, tidak budaya
secara
Analisis Bersifat
sampel Bersifat
konteks
setelah waktu data oleh
menenrus konteks
tidak
data purposif,
deduktif, biasanya terkumpul
kap, induktif,
terkumpul leng waktu
menunggu data
perhitungan model,
Metode dilakukan
menggunakan
Deskriptif analisis
lengkap, terus
Deskriptif,
data statistik
struktur), kategorisasi,
terstruktur,
pengambilan (wawancara ber- mencari
wawancara tak
mencari ran
dan tema serta,
survei,
ri pengamatan
hubungan studi kasus
kolerasional, analisis
eksperimen,
kausal berpe
menca dokumen,
Dari tabel itu, tampak bahwa penelitian budaya yang sering
dipandang bernilai subyektif kurang ilmiah sebenarnya tidak
selamanya benar. Penelitian budaya tetap mengedepankan aspek-
aspek kebenaran tertentu, sejalan dengan tujuan, metode,
hubungan peneliti dengan yang diteliti, dan analisis yang
berwawasan lain dengan pendekatan objektif. Perbedaan ini tidak
berarti bahwa penelitian budaya hanya asal-asalan saja,
melainkan berusaha memahami fenomena lewat subyektivitas yang
tidak mungkin terpahami melalui obyektivitas.
B. LOGIKA DAN KEBENARAN
Salah satu cibiran terhadap penelitian budaya, adalah tentang
ihwal kebenaran. Penelitian budaya yang sering memanfaatkan
penalaran subyektif dan paradigma kualitatif, mengakibatkan pada
pemojokkan dan penilaian yang naif terhadap hasil kajian. Yakni,
penelitian budaya disinyalir kurang memiliki kebenaran pada
tingkat tertentu. Kebenaran penelitian budaya dianggap terlalu
mengada-ada, mencari-cari, dan khayal.
Tentu saja asumsi demikian tidak selalu benar dan tidak akan
mengecilkan hati para peneliti budaya. Namun, peneliti budaya
seyogyanya juga berusaha keras untuk meyakinkan orang lain bahwa
kajian budaya tetap memiliki kadar logika dan kebenaran.
Kalaupun masih tetap ada ejekan-ejekan tentang hal ini, mustinya
diterima saja sebagai cambuk agar peneliti budaya mampu
membuktikan diri secara akurat.
Sesungguhnya, logika dan kebenaran dalam penelitian budaya, juga
tidak berbeda dengan penelitian lain. Logika tetap menjadi
wahana untuk mencari kebenaran. Memang harus diakui bahwa ada
bermacam-macam logika untuk mencari kebenaran, namun tidak
semuanya relevan bagi penelitian kebudayaan.
Macam-macam logika itu adalah:
(a) logika formil, artinya upaya pencarian kebenaran dengan
mencari relasi antar proposisi, dengan tujuan untuk gene-
ralisasi, hal ini jelas kurang relevan bagi penelitian budaya.
Karena, penelitian budaya tak memburu generalisasi, melainkan
transferabilitas;
(b) logika matematik, artinya pencarian kebenaran dengan mencari
relasi proposisi menurut kebenaran materiil; logika semacam ini
didukung oleh rerata yang pasti dan terukur. Andalan logika ini
adalah adanya dalil, aturan, dan rumus-rumus pasti. Logika ini
pun, hanya berlaku bagi peneliti budaya yang menganut paham
positivistik. Peneliti serupa amat jarang dalam kancah
penelitian budaya;
(c) logika reflektif, yaitu cara berpikir dengan sangat cepat,
untuk mengabstraksikan dan penjabaran. Tentunya, logika ini
berlangsung cepat kilat dan bisa memanfaatkan daya intuisi yang
tinggi;
(d) logika kualitatif, artinya pencarian kebenaran berdasaran
paparan deskriptif data di lapangan, kualitas kebenaran
didasarkan pada realita yang ada; (e) logika linguistik, artinya
pencarian kebenaran berdasarkan pemaknaan bahasa, logika ini
sering diminati oleh peneliti budaya tafsir.Dari macam-macam
logika demikian, tampaknya penelitian budaya cenderung
memanfaatkan logika kualitatif dan logika linguistik.
Hal ini tergantung fenomena budaya yang diteliti. Jika
memungkinkan juga menggunakan logika reflektif, khususnya pada
model interaksionis simbolik. Sedangkan penelitian model
etnografis, biasanya memanfaatkan logika kualitatif. Logika
linguistik banyak diminati oleh peneliti budaya tafsir. Jadi,
berdasarkan kecenderungan pemakaian logika tersebut, jelas
kurang benar apabila penelitian budaya kurang atau tidak
memenuhi standar logika dan kebenaran.
Penelitian budaya yang cenderung memanfaatkan logika kualitatif,
biasanya digunakan dalam lingkup kebenaran yang terbatas.
Maksudnya, kebenaran yang dicapai bukan sebuah wacana yang
berlaku universal, melainkan hanya pada tingkat lokal atau kasus
tertentu saja.
Itulah sebabnya, kebenaran yang bersifat kualitatif memang lebih
spesifik dan tidak menghendaki adanya regularitas. Melalui
logika kualitatif, mungkin sekali salah satu kebudayaan ketika
diamati atau diteliti oleh orang berbeda, hasilnya akan berbeda
pula. Hal ini tidak berarti kebenaran kualitatif bisa dipandang
remeh atau lemah, namun tetap menggunakan argumen berdasarkan
realita.
Tentu saja, perkembangan penelitian budaya yang ke arah post-
modernisme telah meninggalkan permainan logika di atas. Postmo-
dernisme kadang-kadang keluar dari rel logika tradisi, dan ingin
mencari kebenaran baru yang lebih orisinil. Kendati pendapat
semacam ini dalam penelitian budaya belum banyak dikembangkan,
namun beberapa penelitian telah mencoba mengarah ke sana. Dalam
kaitan ini kebenaran yang dilandasi argumen, imajinasi, dan
common sense (akal sehat) akan dianut oleh kaum postmodernisme.
Menurut peneliti budaya postmodernisme, kebenaran bersifat
plural dan bebas.
Kaum postmodernisme, biasanya lebih suka pada kenisbian dan atau
relativitas kebenaran. Kebenaran sebuah penelitian budaya selalu
menganut hukum probabilitas yang serba mungkin. Titik tolak kaum
postmomodern adalah kebenaran kreatif, cerdas, dan tidak harus
konsisten. Hal semacam ini, tentu saja kurang disetujui oleh
peneliti-peneliti yang taat pada kebenaran matematik. Namun,
kenyataan juga sulit dipungkiri bahwa kebenaran kreatif pun akan
mampu mewadahi aspirasi kebenaran yang kecil-kecil.
Yakni, kebenaran yang mungkin jarang teradopsi oleh pengamatan
awam.Yang patut dipertimbangkan, baik oleh peneliti budaya
modern maupun postmodernisme adalah fenomena manusia itu
sendiri. Manusia sebagai issu sentral budaya memang cukup unik.
Manusia sebagai obyek pokok (core) penelitian budaya, pada
dasarnya sering mengalami bias (Kaplan dan Manner, 1999:32).
Karena itu, tuntutan kebenaran dan atau obyektivitas hendaknya
dicari bukan seperti fenomena alam. Jika fenomena alam ada hal-
hal yang secara fisik teramati, terulang, dan teratur - fenomena
budaya mungkin bisa demikian dan juga tidak. Fenomena budaya
biasanya jarang yang mengikuti gejala alam sepenuhnya.
Pada dasarnya, manusia sebagai obyek sentral budaya selalu bias.
Tingkat bias ini hanya mampu ditampilkan menjadi objektif
apabila dilukiskan secara verstehen (mudah terpahami). Jika
fenomena yang tergambarkan dari hasil penelitian budaya cukup
bisa dimengerti oleh orang lain, berarti ada kejelasan.
Kejelasan inilah inti kebenaran penelitian budaya. Mungkin, akan
lebih tepat kebenaran dalam penelitian budaya diberi "tanda
petik". Jika hal ini dilakukan pun, sebenarnya tidak akan
mengurangi kredibilitas penelitian itu sendiri. Karena, setiap
ragam penelitian memiliki kebenaran masing-masing.
Jadi, kalau kebenaran objektif lebih menyukai penjelasan
(explanatory) logis, penelitian budaya juga menyajikan
penjelasan yang berisi penafsiran. Asumsi dasar peneliti budaya
adalah pengetahuan kebenaran itu bersifat interpretatif. Kalau
kebenaran objektif ingin melihat pembakuan pengamatan yang
terukur, penelitian budaya ke arah pengamatan humanistik yang
kreatif.
Dengan kata lain, kebenaran penelitian budaya lebih menitik
beratkan pada aspek-aspek humanistik manusia. Aspek-aspek ini
akan menyiratkan pengertian bahwa fenomena budaya adalah unik,
artinya manusia satu dan yang lain tidak harus sama, sehingga
tidak memiliki hubungan kausal yang jelas. Itulah sebabnya,
kebenaran penelitian budaya tidak harus relasional yang
memungkinkan kontrol proposisi lain.
Dengan demikian, penafsiran logik yang kadang-kadang bercampur
dengan intuisi, imajinasi, dan kreativitas pun dalam penelitian
budaya tetap sah. Oleh karena, melalui penafsiran demikian
justru lebih mampu memasuki sisi-sisi "gelap" perilaku manusia.
Kebenaran bukan hal yang diadakan atau dirancang ada, melainkan
harus dicari dalam konteks. Peneliti hanya bertugas menata,
mengorganisir, mengklasifikasikan, dan membuat tema-tema budaya
untuk keperluan pemahaman. Logika dan kebenaran lebih banyak
didukung oleh orisinalitas data di lapangan. Itulah sebabnya
tataran logika dan kebenaran lebih banyak dipengaruhi kondisi
pemilik budaya. Jika pemilik budaya mampu memberikan keterangan
sejelas jelasnya, memahami yang dilakukan, dan proses budaya
juga bisa dimengerti, tentu kebenaran akan tercapai.
C. INDUKTIF DAN DEDUKTIF
Penelitian budaya sering direpotkan ketika harus membuat
kesimpulan hasil. Bahkan pada saat proses penelitian pun, telah
tampak arah penelitian itu mau kemana. Maksudnya, cenderung ke
arah induktif atau deduktif. Dua paham penelitian ini, secara
etimologis memang bertolak belakang. Keduanya memiliki implikasi
metodologis yang berbeda. Padahal, keduanya pula dapat dan tidak
dimanfatkan oleh peneliti budaya.
Induksi adalah sebuah penalaran dalam penelitian. Penalaran
tersebut dibangun dari hal-hal khusus atau contoh-contoh
partikular ke kesimpulan umum. Yang menjadi problem, penelitian
budaya sadar atau tidak sering memanfaatkan penalaran induktif
ini, dibanding penalaran deduktif. Hanya saja, induktif yang
digunakan bukan untuk menggeneralisasi sebuah gejala budaya,
melainkan untuk menata pemikiran yang dimungkinkan sebuah budaya
dapat ditransfer ke budaya lain.
Kajian budaya memang lazim terjun ke dalam advokasi verstehen
(pemahaman), penuh dengan penafsiran dan sedikit meninggalkan
eksplanatori (penjelasan). Pemahaman budaya akan bergerak dari
kontak pengalaman langsung dengan fenomena dan diramu dengan
kenangan pengalaman peneliti sendiri. Keduanya sering rancu,
sehingga kapan harus menggunakan deduktif maupun induktif juga
kurang jernih.
Dengan demikian, kapan penalaran induktif dan deduktif digunakan
tergantung harapan yang akan dicapai dari kajian budaya itu
sendiri. Jika peneliti hendak memperoleh gambaran kebudayaan
baru, hendak membangun teori baru, dan memperoleh informasi-
informasi baru, kiranya penalaran induktif lebih cocok
digunakan. Dari sini, peneliti justru tak terpaku lagi pada
teori-teori dan hipotesis atau asumsi-asumsi dasar yang pernah
dibangun sebelumnya. Bahkan peneliti tak perlu membangun
hipotesis sebelum masuk ke lapangan. Jadi, kesimpulan hasil
benar-benar didasarkan pada data yang ada di lapangan.
Sebaliknya, jika peneliti hendak mencocokkan teori atau
hipotesis yang telah dibangun terlebih dahulu, berarti harus
menggunakan penalaran deduktif. Penalaran ini, rupa-rupanya amat
sempit dan membatasi diri pada kondisi lapangan. Akibatnya,
peneliti hanya terpaku oleh asumsi-asumsi dasar dan sejumlah
teori yang telah dibaca sebelumnya. Karena itu, hasil penelitian
pun seringkali telah dapat diramalkan. Dari sini, tampak bahwa
penalaran deduktif memiliki kelemahan, yaitu kurang menghargai
fenomena dan realitas.
Pemakaian induksi dalam penelitian kualitatif budaya, menurut
Moleong (2001:5) ada beberapa alasan:
(1) proses induksi lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan
ganda sebagai yang terdapat dalam data;
(2) lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi
eksplisit, dapat dikenal, dan akontabel;
(3) lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat
keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan kepada
suatu latar lainnya;
(4) lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam
hubungan-hubungan, dan analisis juga dapat memperhitungkan
nilai-nilai eksplisit. Dari alasan ini, dapat dinayatakan bahwa
analisis induktif lebih realistis dan meyakinkan.
Dilihat dari ragamnya, menurut Brannen (1997:13-T4) induksi dua
macam yaitu induksi enumeratif dan induksi analitik.
Induksi enumeratif yaitu suatu penalaran mengambil kesimpulan
hasil penelitian berdasarkan perhitungan angka-angka.
Ini biasanya digunakan oleh ilmu-ilmu eksata, meskipun kajian
budaya pun tak menolaknya.
Sedangkan induksi analitik, adalah penalaran yang didasarkan
pada data tanpa memanfaatkan angka-angka. Kesimpulan hasil
didasarkan pada deskripsi kata-kata semata.
Dari dua macam induksi tersebut, tampak sekali bahwa penelitian
budaya cenderung menggunakan induksi analitik. Terlebih lagi
penelitian budaya yang cenderung menggunakan model etnografis,
penalaran induksi analitik sangat penting. Oleh karena, peneliti
selalu melakukan analisis data terus-menerus baik ketika di
lapangan maupun setelah kembali ke meja. Kekuatan induksi
analitik adalah pada kemampuan peneliti membuat kategorisasi dan
abstraksi fenomena budaya.
Suatu persyaratan induksi analitik dalam kajian budaya yaitu
berpegang teguh pada data di lapangan. Data yang banyak
berbicara dan menentukan induksi. Karena itu, peneliti budaya
diharapkan mampu melukiskan fenomena budaya dan sejumlah kasus
secara proporsional. Dalam kaitan ini, penelitian budaya tak
lagi generalisasi, meskipun melakukan analisis induktif.
Anda mungkin juga menyukai
- FENOMENOLOGI BUDAYADokumen27 halamanFENOMENOLOGI BUDAYAMeandus Agundong100% (1)
- FENOMENOLOGI BUDAYADokumen27 halamanFENOMENOLOGI BUDAYANurhalimah Febrianti100% (1)
- KEBUDAYAAN-REFLEKSIDokumen22 halamanKEBUDAYAAN-REFLEKSIZhar KasyiBelum ada peringkat
- Makalah Rangkuman EKM MasinambowDokumen4 halamanMakalah Rangkuman EKM MasinambowFebri Taufiqurrahman100% (1)
- FenomologiDokumen10 halamanFenomologiGregorio Antonny BaniBelum ada peringkat
- Gudeg YogyakartaDokumen20 halamanGudeg YogyakartaDebora LinaningrumBelum ada peringkat
- Budaya DinamisDokumen276 halamanBudaya Dinamisachonx_eri100% (2)
- Metodologi Sejarah MeresumeDokumen3 halamanMetodologi Sejarah MeresumeSri wahyuniBelum ada peringkat
- RMK EtnografiDokumen7 halamanRMK Etnografisalsa100% (2)
- KEBUDAYAAN DAN KONSEPDokumen8 halamanKEBUDAYAAN DAN KONSEPriana auliaBelum ada peringkat
- 1 SM4Dokumen26 halaman1 SM4Sulaiman nasutionBelum ada peringkat
- Tugas 1 Metodologi PenelitianDokumen6 halamanTugas 1 Metodologi PenelitianIgnasius GeraldiBelum ada peringkat
- Review BukuDokumen8 halamanReview BukuNajwa AmaliaBelum ada peringkat
- Filsafat Sejarah Collingwood - Jusuf Nikolas: Ringkasan Yan NurcahyaDokumen6 halamanFilsafat Sejarah Collingwood - Jusuf Nikolas: Ringkasan Yan NurcahyaYAN NURCAHYABelum ada peringkat
- Perspektif Baru Budaya Kontemporer & Pencarian Identitas Dalam Atmosfer HipermodernismeDokumen18 halamanPerspektif Baru Budaya Kontemporer & Pencarian Identitas Dalam Atmosfer HipermodernismeAntonius Galih PrasetyoBelum ada peringkat
- Makalah Meti Nurhidayanti - Teori KebudayaanDokumen6 halamanMakalah Meti Nurhidayanti - Teori KebudayaanNurlin SahabBelum ada peringkat
- Positivistik Ilmu Sejarah Di IndonesiaDokumen6 halamanPositivistik Ilmu Sejarah Di IndonesiaYudhi AndoniBelum ada peringkat
- Konsepsi-Konsepsi Budaya - Evolusi Menuju Definisi Yang Bersifat SemiotisDokumen16 halamanKonsepsi-Konsepsi Budaya - Evolusi Menuju Definisi Yang Bersifat Semiotisp_syahrieBelum ada peringkat
- ID Filsafat Kebudayaan Dan Sastra Dalam Per PDFDokumen7 halamanID Filsafat Kebudayaan Dan Sastra Dalam Per PDFfarid naufalBelum ada peringkat
- Pengetahuan Lokal Dalam Epistemologi RelasionalDokumen9 halamanPengetahuan Lokal Dalam Epistemologi RelasionalPanji DewantoroBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Antropologi SosialDokumen3 halamanKonsep Dasar Antropologi SosiallusiBelum ada peringkat
- TEORI DIALOGDokumen6 halamanTEORI DIALOGTak Pernah AdaBelum ada peringkat
- Teori Budaya 2Dokumen14 halamanTeori Budaya 2Vania Vera Larastika100% (1)
- Makalah EtnografiDokumen11 halamanMakalah EtnografiDintia Zarkasih75% (4)
- SEJARAHBUDAYADokumen3 halamanSEJARAHBUDAYASyazwanie SuhaimiBelum ada peringkat
- Biografi SejarahDokumen24 halamanBiografi SejarahEskasinagaBelum ada peringkat
- Etnografi PanduanDokumen5 halamanEtnografi PanduanFadhiilah FatmasariBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Kalimat EfektifDokumen15 halamanTugas Kelompok Kalimat EfektifDaniel Ganda ChristiantoBelum ada peringkat
- Makalah Bulan BahasaDokumen25 halamanMakalah Bulan BahasaIrwan Cungkring67% (3)
- Objektivitas Dan Subjektivitas Dalam Penulisan SejarahDokumen11 halamanObjektivitas Dan Subjektivitas Dalam Penulisan Sejarahbinbinadi100% (1)
- Sastra Inggris dan BudayaDokumen14 halamanSastra Inggris dan BudayaDaniel Ganda ChristiantoBelum ada peringkat
- 171-Article Text-370-1-10-20180202Dokumen13 halaman171-Article Text-370-1-10-20180202Rani DyanaaBelum ada peringkat
- OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFDokumen11 halamanOBJEKTIF DAN SUBJEKTIFfebriani rahayu putriBelum ada peringkat
- Teori-BudayaDokumen14 halamanTeori-BudayaZo RoBelum ada peringkat
- Review Clifford Geertz: Tafsir KebudayaanDokumen10 halamanReview Clifford Geertz: Tafsir Kebudayaanelka purwasito92% (13)
- UAS - Metpen Kualitatif EtnografiDokumen30 halamanUAS - Metpen Kualitatif Etnografilale ariniagit100% (1)
- Pendekatan SastraDokumen6 halamanPendekatan SastraUnassBelum ada peringkat
- Ringkasan Buku Tafsir Kebudayaan: Pseudo-Ilmu Yang Juga Sudah Muncul Pada Gelora Awal KemashyurannyaDokumen20 halamanRingkasan Buku Tafsir Kebudayaan: Pseudo-Ilmu Yang Juga Sudah Muncul Pada Gelora Awal KemashyurannyaNicodemus SihalohoBelum ada peringkat
- Antropologi SosialDokumen6 halamanAntropologi SosialErminaBelum ada peringkat
- SNA2010 - Seminar - PM Laksono - Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam AntropologiDokumen12 halamanSNA2010 - Seminar - PM Laksono - Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam AntropologiBintang Y. SoepoetroBelum ada peringkat
- UAS Antropologi BudayaDokumen3 halamanUAS Antropologi BudayaAl BaihakiBelum ada peringkat
- MPS chp.2Dokumen6 halamanMPS chp.2diana_sandyaBelum ada peringkat
- Definisi Antropologi SosialDokumen8 halamanDefinisi Antropologi Sosialbikeindo20Belum ada peringkat
- BAB IV Dan Bab V Sos SastraDokumen13 halamanBAB IV Dan Bab V Sos Sastra5. SABHAN ABDILLAH RASYIDBelum ada peringkat
- Paradigma Metode Penelitian Kualitatif PDFDokumen267 halamanParadigma Metode Penelitian Kualitatif PDFVietha Ntue Alay Angetz0% (1)
- Cultural Studies SemiotikaDokumen13 halamanCultural Studies SemiotikaTriana Nur Laela0% (1)
- Digital - 132572 T 27748 Sejarah Nuswantara PendahuluanDokumen14 halamanDigital - 132572 T 27748 Sejarah Nuswantara PendahuluanNur Anis NabilaBelum ada peringkat
- Teori Teori Tentang Budaya PDFDokumen29 halamanTeori Teori Tentang Budaya PDFRyan Kuncoro Harry WicaksonoBelum ada peringkat
- Sejarah IntelektualDokumen14 halamanSejarah IntelektualLa Raman100% (1)
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Sejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniDari EverandSejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniBelum ada peringkat
- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Kesadaran: Menemukan tahapan-tahapan pikiran: dari yang sadar ke yang tidak sadar, dari pengaruh ritme biologis hingga tidur dan mimpiDari EverandKesadaran: Menemukan tahapan-tahapan pikiran: dari yang sadar ke yang tidak sadar, dari pengaruh ritme biologis hingga tidur dan mimpiBelum ada peringkat
- Kepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaDari EverandKepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1)
- Semua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Dari EverandSemua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (4)
- Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baruDari EverandFizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baruPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- STRATEGI PELAKSANAAN IPV (Modul IPV Gabungan)Dokumen48 halamanSTRATEGI PELAKSANAAN IPV (Modul IPV Gabungan)Anonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Bap 2013Dokumen2 halamanBap 2013Anonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Kata Pengantar Juknis Intro MR - GTDokumen2 halamanKata Pengantar Juknis Intro MR - GTAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Rencana SDM Prov ADokumen7 halamanRencana SDM Prov AVtrock The'IlectraBelum ada peringkat
- Anjab PromkesDokumen4 halamanAnjab PromkesAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Bon Nota KeluarDokumen1 halamanBon Nota KeluarAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Anjab KapusDokumen4 halamanAnjab KapusAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Tahunan 2014Dokumen1 halamanTahunan 2014Anonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Form Rs - DRSP - KirimDokumen14 halamanForm Rs - DRSP - KirimrspbatuBelum ada peringkat
- Daftar HadirDokumen1 halamanDaftar HadirAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Rumah SakitDokumen1 halamanRumah SakitimaBelum ada peringkat
- Bon Nota KeluarDokumen1 halamanBon Nota KeluarAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- PMK Keselamatan PasienDokumen2 halamanPMK Keselamatan PasienAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Grafik SuhuDokumen3 halamanGrafik SuhuAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Terbaru ImunisasiDokumen6 halamanTerbaru ImunisasiAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- 2.6.1. (6) Lampiran SK PJ KendaraanDokumen1 halaman2.6.1. (6) Lampiran SK PJ KendaraanAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- ETIKETDokumen1 halamanETIKETAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- 2.6.1. (1) Lampiran SK PJ Pengadaan BarangDokumen2 halaman2.6.1. (1) Lampiran SK PJ Pengadaan BarangAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Bab 8 PenutupDokumen1 halamanBab 8 PenutupmarlinaBelum ada peringkat
- 2.6.1 (1) SK Pengelola Pengadaan Barang Bandung 2018Dokumen2 halaman2.6.1 (1) SK Pengelola Pengadaan Barang Bandung 2018Anonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- 2.6.1. (8) Lampiran SK PJ KendaraanDokumen1 halaman2.6.1. (8) Lampiran SK PJ KendaraanAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Denah RuanganDokumen1 halamanDenah RuanganAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Format Visum BulananDokumen1 halamanFormat Visum BulananAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Surat Keterangan KewirausahaanDokumen1 halamanSurat Keterangan KewirausahaanAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Indri 2Dokumen1 halamanIndri 2Anonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- PERHATIANDokumen1 halamanPERHATIANAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Surat Perjanjian Antara Bidan Dan Dukun Desa CiagelDokumen2 halamanSurat Perjanjian Antara Bidan Dan Dukun Desa CiagelAnonymous c5PUo7W100% (1)
- Ruk Jiwa Dan KeswaDokumen4 halamanRuk Jiwa Dan KeswaAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Diagram Alir PerizinanDokumen4 halamanDiagram Alir PerizinanAnonymous c5PUo7WBelum ada peringkat
- Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035Dokumen470 halamanProyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (3)