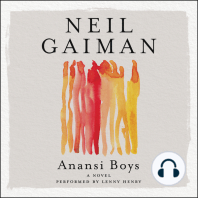Gus Dur Dan Pendidikan Perdamaian
Diunggah oleh
fajaraquinoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Gus Dur Dan Pendidikan Perdamaian
Diunggah oleh
fajaraquinoHak Cipta:
Format Tersedia
Gus Dur dan Pendidikan Perdamaian
Oleh: Ahmad Nurcholish
Mencermati pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memang menarik sekaligus menyulitkan.
Menarik karena gagasan-gagasannya sangat sederhana, tetapi dinilai banyak kalangan mampu
memberikan wawasan tersediri dalam menganalisis persoalan, baik di Indonesia maupun di ranah
internasional. Menyulitkan karena pemikirannya terkadang keluar dari kultur lingkungan yang
membesarkannya, yakni NU dan pesantren.
Namun demikian, secara umum ide-ide Gus Dur telah menjadi wacana public yang terus menggulir
dan dipahami serta ditafsir oleh sejumlah kalangan sesuai latar belakang disiplin intelektual mereka.
Kali ini, saya tertarik untuk mengulas Gus Dur dan gagasan pendidikan perdamaiannya.
Indonesia merupakan Negara dan bangsa yang majemuk (plural, bhineka). Kondisi tersebut
menuntuk sikap toleran yang tinggi dari setiap warga Negara. Sikap toleransi tersebut harus dapat
diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuk sebuah tatanan
masyarakat yang kompak, bersatu dalam keragaman sehingga kaya akan gagasan-gagasan
baru. Toleransi inilah yang menjadi dasar utama bagi terwujudnya perdamaian dalam sebuah
masyarakat, bangsa dan Negara.
Toleransi yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Gus Dur tidak sekedar menghormati dan
menghargai keyakinan atau pendirian orang lain dari agama yang berbeda, tetapi juga disertai
adanya kesediaan menerima ajaran-ajaran yang baik dari agama lain. Dalam sebuah tulisannya
berjudul Intelektual di Tengah Eksklusifisme, Wahid memaparkan:
“…Saya membaca, menguasai, menerapkan al-Qur’an, al-Hadits, dan kitab-kitab Kuning tidak
dikhususkan bagi orang Islam. Saya bersedia memakai yang mana pun asal benar dan cocok sesuai
hati nurani. Saya tidak memedulikan apakah kutipan dari Injil, Bhagawad Gita, kalau bernas kita
terima. Dalam masalah bangsa, ayat al-Qur’an kita pakai secara fungsional, bukannya untuk diyakini
secar teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi adalah soal
penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis, melainkan sudah menjadi
masalah pemikiran.” (Gus Dur, 2010: 2014)
Wahid tidak hanya dapat menerima kebenaran yang berasal dari ajaran agama lain, tetapi juga
menganggap penganutnya sebagai saudara. Persaudaraan sesame manusia meski berbeda agama
inilah yang menjadi salah satu pilar perdamaian. Dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27
Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta, misalnya, Gus Dur menuturkan:
“Saya adalah seorang yang menyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak menghalangi saya untuk
merasa bersaudara dengan orang yang beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesame umat
beragama. Sejak kecil itu saya rasakan. Walaupun saya tinggal di lingkungan pesantren, hidup di
kalangan keluarga kiai, tak pernah sedikitpun saya merasa berbeda dengan yang lain.” (Rumadi,
2002: 144)
Pernyataan Gus Dur tersebut menandaskan bahwa dirinya tak pernah merasakan berbeda dengan
penganut agama lain. Bagi Wahid, perbedaan keyakinan seyogyanya tidak membatasi atau melarang
kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal-hal yang menyangkut
kepentingan umat manusia. Penerimaan Islam akan kerjasama itu tentunya akan dapat diwujudkan
dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar-agama.
Dengan ungkapan lain, prinsip pemenuhan klebutuhan berlaku dalam hal ini, seperti adagium ushul
fiqh (teori legal hukum Islam): “Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwujud
tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun)”.
Kerjasama tidak akan terlaksana tanpa didahului dengan adanya dialog. Oleh karena itu dialog antar
agama juga menjadi kewajiban. (Gus Dur, 2002: 133-134)
Dalam hal kemajemukan, kebhinekaan atau pluralitas, aebagai tercantum dalam QS. Al-Hujarat [49]:
13, menurut Wahid, ayat tersebut menunjuk kepada perbedaan yang senantiasa ada antara laki-laki
dan perempuan serta antar berbagai bangsa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan
merupakan sebuah hal yang diakui dalam Islam. Sebaliknya, yang dilarang adalah adanya
perpecahan dan keterpisahan yang dibarengi sikap permusuhan.
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa definisi sekaligus konsepsi pendidikan perdamaian
menurut Gus Dur adalah adanya toleransi yang ditandai dengan penerimaan atas keberadaan orang
atau peganut agama lain yang berbeda dibarengi dengan sikap menghormati dan menghargai
sebagai sesama manusia. Konsep inilah yang dapat direalisasikan dan diaplikasikan dalam
pembelajaran baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal agar peserta didik saling
toleransi, menghargai dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujud perdamaian.
Jika ditelusuri secara mendalam, konsep pendidikan perdamaian Gus Dur yang kemudian
mengantarkannya menjadi seorang humanis adalah pengaruh para kiai yang mendidik dan
membimbingnya sejak ia remaja hingga dewasa. Ia meneladani kisah tentang Kiai Fatah dari Tambak
Beras, KH. Ali Ma’sum dari Krapyak dan Kiai Chudhori dari Tegalrejo telah membuat pribadi Gus Dur
menjadi orang yang sangat peka pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Seseorang dapat
menjunjung perdamaian karena memiliki sikap humanitarian, kecintaan kepada manusia yang
membuatnya memunyai sikap menghormati kepada yang lain yang berbeda.
Dari lacakan epistimologis, Gus Dur bukanlah seorang yang eksistensialis, melainkan seorang yang
beragama dan percaya pada konsep wahyu, tetapi ia gabungkan dengan pemikiran modern. Ia
menyakini adanya Tuhan Allah Sang Pencipta semesta, menyakini adanya wahyu dan kitab suci,
tetapi juga menyakini adanya pengetahuan obyektif yang lahir dari beragam disiplin ilmu
pengetahuan. Kebebasan, toleransi, serta persamaan antar manusia menjadi kata kunci bagi
bangunan pemikiran pendidikan perdamaian dalam persepektif Gus Dur.
Toleransi yang menjadi basis utama pendidikan perdamaian Gus Dur tidak lahir dengan mudah
begitu saja. Ia terbentuk oleh ekspedisi intelektualnya yang panjang. Wahid tumbuh di lingkungan
pesantrenm tradisional Tebuireng Jombang, Krapyak Yogyakarta, dan Tegalrejo Magelang. Dari
ketiga pesantren tersebut, Gus Dur menimba disiplin keilmuan Islam tradisional seperti fiqih, tafsir
al-Qur’an, hadits, tasawuf, dan sebagainya. Dalam pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) pada
umumnya, toleransi merupakan ajaran yang kerap disuguhkan oleh para kiai sehingga tertanam di
hati para santri sebagai peserta didik. (Irwan Masduqi, 2011: 135)
Wahid menemukan prinsip toleransi yang diserap dari hadits Nabi bahwa pencari kebenaran
hukum akan mendapatkan dua pahala jika benar dan mendapatkan satu pahala jika salah (man
ijtahada fa asaaba fa lahu ajrani fa man ijtahada fa akhta’a fa lahu ajrun wahidan). Pencari
kebenaran diberika reward oleh Tuhan meskipun dia salah. Oleh karena itu, semua pendapat
atau pemahaman keagamaan harus dihargai dan tidak boleh diberangus, apalagi dinilai sesat
dan menyesatkan.
Pendidikan pesantren mengajarkan kepada Gus Dur jargon toleransi Al-Syaf’i: “Pendapat kami benar
tetapi mungkin salah, sedangkan pendapat kalian salah tetapi mungkin benar.” (ra’yuna sawabun
yahtamilu al-khata’ wa ra’yu ghayrina khata’un yahtamilu al-sawab). Ungkapan Imam Syafi’I ini
menandaskan bahwa kebenaran pemikiran manusia tidaklah absolut, karena itu tidak boleh merasa
benar sendiri sembari menyesatkan pendapat orang lain. Gus Dur sangat tidak suka dengan sikap
dogmatis dan fanatic yang – meminjam istilahnya – sering “main mutlak-mutlakan”.
Nampaknya Gus Dur belajar banyak dari Al-Syafi’i tentang prinsip toleransi yang terbangun dari
kerendahan hati yang di dalamnya terdapat pengakuan kemungkinan salah pada diri sendiri.
Selain disiplin fiqih, sufisme juga menempati posisi sentral yang mengajarkan budaya toleransi di
lingkungan pesantren. Nuansa sufistik yang kental di pesantren juga memengaruhi pandangan
pluralistic dan toleran Wahid. Sufisme mengajarkan toleransi, moderatisme, koeksistensi, dan nilai-
nilai humanistic lainnya. Hal ini karena pandangan metafisik dalam sufieme mengimplikasikan
bahwa terdapat kesatuan di antara semua hal yang eksis.
Sedangkan perbedaan, kebhinekaan, dan pertentangan antara kelompok manusia dan semua hal
yang eksis hanyalah ilusi. Jika keragaman hanyalah ilusi, maka perbedaan di antara manusia, adat
sistiadat, dan budaya juga bersifat superfisial. Oleh sebab itu, sufisme mengajarkan sikap rendah hati
dan menghormati perbedaan. (Masduqi: 135-136). Penghormatan terhadap perbedaan inilah yang
menjadi basis kedua dalam pendidikan perdamaian ala Gus Dur.
Sikap-sikap toleran dan pluralis Gus Dur berakar dari penghayatan terhadap teks-teks inklusif al-
Qur’an, Allah berfirman bahwa “Tidak ada paksaan dalam agama.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).
“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” (QS. Al-Kafirun [109]: 6). “Jikalau Tuhanmu
menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa
berselisih pendapat.” (QS. Hud [11]: 119). Ayat-ayat toleransi ini kerap dikutip oleh Gus Dur
dalam esai-esai dan ceramah-ceramahnya.
Dalam hal pendidikan perdamaian itu sendiri ayat paling fundamental yang kerap dikutip oleh Gus
Dur adalah QS. Al-Hujarat [49]: 13 yang juga menjadi spirit multikulturalisme dalam al-Qur’an. Entah
sudah berapa kali Gus Dur mengulang-ulang ayat ini dalam berbagai ceramahnya. Ia begitu
menghayati ayat ini secara mendalam dan semakin yakin bahwa kebhinekaan suku dan bangsa
bukan untuk saling berperang, melainkan untuk saling mengenal dalam dialog antarbudaya dan
peradaban.
Ayat tersebut ditafsirkan oleh Gus Dur sebagai prinsip Bhineka Tunggal Ika. Prinsip ini pulalah yang
menjadi basis ketiga bagi pendidikan perdamaian Sang Guru Bangsa yang telah meninggalkan kita
enam tahun silam.
Ahmad Nurcholish, penulis buku “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur” (Elexmedia,
2015)
Tulisan ini pernah dimuat di icrp-online.org pada 3 Desember 2015
Pendidikan perdamaian seperti digagas oleh Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,
Pendidikan Perdamaian bukan saja soal perdamaian itu sendiri sebagai konsep,
sebagai ide melainkan bagaimana gagasan dan konsep tentang perdamaian itu
disebarkan, ditanam, dipupuk, dan ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat.
Sebab, segala sesuatu memang harus dirawat, sebagaimana tumbuhan yang ada di
kebun atau taman kita tak akan tumbuh dan besar manakala kita biarkan tanpa
perawatan dan kepedulian, begitu juga nilai, sikap dan prilaku. kesemuanya itu tak
akan tumbuh jika tidak disebarkan melalui pendidikan. (Ulil Abshar Abdallah, Ketua
Umum ICRP)
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5796)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7771)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2314)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20036)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4611)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3282)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4347)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12948)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6523)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2568)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)






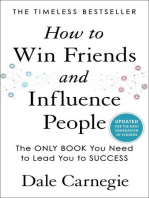







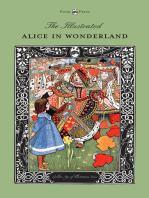
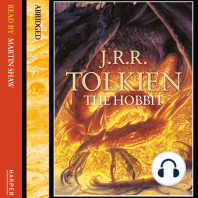











![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)