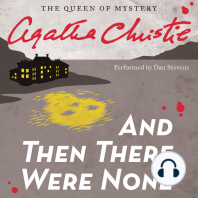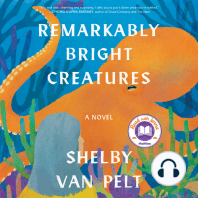Grahadyan Romansa Kertas Hitam 2018 PDF
Diunggah oleh
H'dyan Farrel0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan3 halamanJudul Asli
Grahadyan; Romansa Kertas Hitam; 2018.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan3 halamanGrahadyan Romansa Kertas Hitam 2018 PDF
Diunggah oleh
H'dyan FarrelHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
Romansa Kertas Hitam
(Hadyan Farrel Nugraha; 16 Februari 2018)
Aku ingat betul bagaimana hari terakhir yang mengerikan itu terus menggelayuti
pikiranku. Perempuan bergaun hitam renda dengan tatapan matanya yang lemah itu sepertinya
sudah menandakan bahwa waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Aku masih menyimpan
rahasia terbesar bahwa aku masih ingin menghabiskan waktu dengannya lebih lama, dan
mengajaknya untuk mengikatkan janji untuk hidup bersama. Saat itu kulitnya yang putih
melebihi gading gajah terpendar oleh cahaya jingga yang merayap perlahan bersamaan dengan
suara serangga musim panas yang saling berbalas irama. Bibirnya yang tipis dengan sedikit
lengkungan itu akhirnya tersenyum sambil melambaikan tangannya sesaat matahari senja ikut
tertelan oleh sambutan malam. Aku tahu, ia sudah pergi untuk selamanya. Rambut hitamnya
yang tergerai itu terkibas oleh angin yang searah denganku yang sedang terpaku menatap
pemandangan yang memilukan. Kekasihku itu, hanya bayangan sekarang. Ia sudah pergi.
Aku melamun cukup lama sembari membiarkan tinta penaku kering. Secarik kertas yang
lusuh dengan noda-noda merah mediaku menulis memang menyedihkan. Kursi cokelat lapuk
dengan ujungnya yang melengkung dan diukir, menjadi sandaran ketika aku mulai kehabisan
kata-kata untuk menuliskan sebuah mahakarya. Alunan musik Renaisans dari Pierre de La
Rue−berjudul Masses−yang gaya musiknya sangat aku sukai mengalun dari Gramofon cokelat
yang antik sekaligus menarik. Pierre memang menyukai nada rendah, sehingga saat itu Requiem
adalah karyanya yang paling gemilang. Salah satu karyanya yang paling aku sukai adalah Masses.
Aku memperhatikan lukisan Aleena, perempuan yang pernah mengisi relung hati
kosong nan sepi saat jiwaku benar-benar kehilangan arah untuk hidup. Aku selalu memandang
lukisan dirinya yang terpampang di dinding ruangan bercat putih pudar dengan kurangnya
cahaya matahari sehingga segala ornamen berwarna cokelat di sini menjadikannya terbilang
kuno sekali. Dalam lukisan itu Aleena memperlihatkan senyuman tipisnya dengan rambut hitam
yang digerai. Wajahnya sangat begitu nyata, bola mata yang bulat dan indah itu terkadang
seakan mengikutiku ke mana pun aku pergi di ruangan ini. Dan hatinya meski sudah melebur
dengan tanah masih aku rasakan sampai saat ini. Seringkali suaranya yang lembut itu pun masih
terdengar di sela-sela musik Pierre yang aku gemari.
Sampai empat malam berlalu aku masih selalu terpikir akan Aleena. Aku sedang
berkiprah di dunia tulisan−maksudnya Novel, yang sedang populer di kota ini. Selain banyak
penulis Novel, kota ini digandrungi pula oleh penyair muda. Bahkan tidak sedikit dari mereka
yang menjadi penyanyi kafe di kota yang bergaya Medieval ini. Aku hanyalah penduduk miskin
yang menyedihkan sekarang dan penyambung hidupku hanyalah Novel yang aku tulis. Novel ini
nantinya akan dijual ke pusat baca yang didirikan khusus oleh kerajaan di kota ini. Nominal yang
diberikan memang lumayan besar, dan aku sempat mendapatkan bayaran dua kali lipat dari
pihak istana. Namun, semua itu terkadang habis hanya untuk membayar hutang-hutang yang
ditinggalkan oleh kedua orangtuaku yang sudah bersama Aleena di surga. Harta warisanku
nyaris habis, dan rumah ini adalah satu-satunya harta yang aku miliki.
“Bisakah aku menulisnya untuk Aleena? Jiwanya masih selalu menghantui pikiranku,
bahkan aku tidak mampu untuk menuliskan satu kata pun untuknya.. aku tidak tahu bagaimana
lagi caranya hidup”
Dan sungguh ketika itu aku benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa selain meratapi
segala kemalangan yang menimpaku. Aku berniat untuk menjadi pengamen, untuk Aleenaku,
agar ia tidak melihatku menyedihkan. Namun itu mustahil, aku bahkan tidak memiliki bakat
musik!
Tirai kamar yang bergoyang karena angin membuyarkan lamunanku. Lantas aku pikir
lebih baik jalan-jalan ke luar sebentar untuk membeli makanan−karena bubur sumsum bekas
pemberian temanku yang sekarang sedang sibuk dengan syairnya itu sudah habis sekarang. Aku
akan membeli gandum hitam yang lebih murah ketimbang gandum normal yang harganya pasti
jauh lebih mahal. Dan parahnya saat ini Novelku belum juga selesai karena selalu memikirkan
Aleena.
Aku sudah hancur, jauh lebih hancur dari bubur sumsum yang aku makan. Aleena sudah
tidak bisa memberikan apapun selain kengiluan yang aku rasakan sebagai pria yang paling
menyedihkan. Seketika, aku menangis. Benar-benar menangis hingga emosiku yang selama ini
berkecamuk di dalam hati dilampiaskan pada meja yang penuh dengan kertas berisi tulisan
karanganku yang belum selesai−atau tidak pernah selesai. Aku sangat berdosa karena tidak
mampu berbuat apa-apa.
Lukisan besar itu, Aleena, bergerak dengan tidak sabaran di dinding hingga suara
gemeretaknya terdengar dengan jelas. Aku memperhatikannya dengan perasaan kagum
sekaligus takut. Dari matanya muncul cairan merah kental yang membuatku tertegun sambil
merasakan badanku yang gemetar bukan main.
Bibirku kalut marut menyebut namanya, “A..A..Aleena, kau kah itu?”
Sosok yang selalu aku pikirkan itu sekarang muncul di hadapanku dengan tatapan yang
tajam. Ia bukan lagi Aleena yang manis dengan senyumnya yang membuatku selalu terpana oleh
kecantikannya. Sekarang, ia benar-benar marah. Sangat marah, sehingga aku tidak dapat
bergerak dan terjatuh di lantai kusam yang dipenuhi oleh kertas-kertas yang bertinta hitam.
“Aleena.. ALEENA!!!” aku berteriak hingga histeris melandaku yang gembira sekaligus
takut. Aku tidak tahu harus apa.. pada Aleena.
“Hentikan!! Jangan hina dirimu karena orang yang sudah mati. Aku menjerit setiap kali
kau memikirkanku!!!” dan aku tidak percaya Aleena begitu marah kepadaku. Karena memang
aku selalu memikirkannya, bahkan menganggap dirinya masih hidup. Tapi aku tidak menyangka
ini malah membuatnya tersiksa di dimensi yang berbeda denganku.
Sesaat Aleena tersungut-sungut dengan matanya yang membulat lebar, lukisan dirinya
terjatuh di lantai dan menimbulkan retak yang cukup parah. Bersamaan dengan itu, Aleena
menghilang dengan debu pekat berwarna hitam. Aku masih mengatur napasku, keringat yang
membasahi dahiku sudah tidak dapat lagi aku bendung. Keinginan Aleena adalah agar aku
melupakannya dan bisa menulis sebuah karya Novel seperti biasa, untuk menyambung hidupku.
Keesokan harinya setelah kejadian itu, aku pergi ke bukit di belakang rumahku dan
membakar lukisan Aleena. Ada perasaan berat sekaligus lega mengingat aku sekarang benar-
benar akan melupakan Aleena, perempuan yang sangat aku cintai, dan dengan ketenangan
jiwanya sekarang aku dapat pula meneruskan keinginanku untuk menjadi penulis terkenal di
kota.
Hingga nanti suatu hari, aku dapat merasakan apa artinya gemilang hidup
sesungguhnya. Dan aku sangat yakin, Aleena akan bahagia melihatku yang sudah beranjak dari
kepiluan yang selama ini membuatku tersiksa. Hidupku bukan hanya bernuansa romansa,
hidupku bergantung kepada apa yang harus aku lakukan ke depan. Pena hitam dan secarik kertas
putih bersih ini akan menjadi awal baru, untukku.
FIN
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20026)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5795)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3278)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12948)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (728)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1108)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5511)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)














![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)