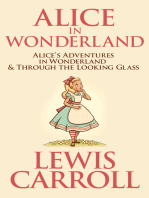CerpenMF2019 - Putri Refinda Yuan - SMA - Bunda, Bolehkah Aku Membencimu
CerpenMF2019 - Putri Refinda Yuan - SMA - Bunda, Bolehkah Aku Membencimu
Diunggah oleh
Ire Yuano0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1 tayangan7 halamancerpen genre slice of life
Judul Asli
CerpenMF2019_Putri Refinda Yuan_SMA_Bunda, Bolehkah Aku Membencimu
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inicerpen genre slice of life
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1 tayangan7 halamanCerpenMF2019 - Putri Refinda Yuan - SMA - Bunda, Bolehkah Aku Membencimu
CerpenMF2019 - Putri Refinda Yuan - SMA - Bunda, Bolehkah Aku Membencimu
Diunggah oleh
Ire Yuanocerpen genre slice of life
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 7
Assalamualaikum, Nareswaranya Bunda.
Saat kertas penuh coretan Bunda sudah dibaca oleh
Swara. Artinya, Bunda sudah sampai di ibukota. Jangan coba-
coba mengingkari satu janji pun, atau Bunda tidak akan
menemui Swara.
Masih ingat dua janji Swara, kan? Ingatlah selalu itu.
Percaya pada Bunda, anak Bunda bisa menepati janjinya.
**
“Bunda, kalau Swara gak bisa nepatin salah satu dari janji itu,
Bunda gak bakal nemui Swara, dong.”
Suara katak bernyanyi bersahutan, nyanyian pujian atas
datangnya hujan meredam volume suaraku yang merajuk pada
Bunda. Aku terus merengek agar Bunda mau melupakan janji
yang sekrang jauh dari jangkauan. Tidak ada jawaban atau
pertanyaan balik karena Bunda memang tidak mendengarku.
Malam sepenuhnya gelap. Sedikitpun tidak memberi
ruang bagi bulan atau bintang untuk berpendar. Meski waktu
isya telah berlalu tiga jam yang lalu, manik mata ini belum
bosan jua menatap langit. Semilir angin malam membawa
hawa dingin, menubruk semua benda yang menghalangi
lajunya. Menusuk pelan, menembus lapisan kulit, menyebar,
lalu membuat tubuh menggigil. Asa mendapat rengkuhan
hangat keluarga hanya sebatas bayangan pelupuk mata.
Ratusan malam berlalu membawa tubuh yang haus akan
kehangatan. nun apalah adanya hanya angin yang
merengkuhku. Menghilangkan kehangatan yang pernah
dikenal oleh indera perabaku.
Mata ini mulai memanas. Memburam. Embun-embun
hangat itu akan sempurna mengalir dan menetes jatuh sebentar
lagi. Tidak akan ada yang menahannya. Apa lagi? Keinginan
itu berada di ujung tebing. Pilihannya hanya satu, menunggu
kesempatan lain untuk menepati janji yang akan membawaku
pada Bunda, dan itu bukanlah pilihan.
“Masih ingat dua janji Swara, kan?”
Urung. Suara lembut menenangkan itu menggema,
memenuhi ruang pada indera pendengaranku. Rangkaian kata
yang selalu Bunda katakan di kala aku mengeluh. Di saat aku
memaki-maki takdir dan menyalahkan kepergian Ayah.
Rangkaian kata itu sama persis dengan sepotong kalimat yang
Bunda tuliskan di sepucuk surat.
“Swara ingat, sangat ingat. Bukankah Bunda menyuruh
Swara untuk percaya pada Bunda?”
Aku menunduk, tidak ingin memejamkan mata. Takut
kalau bulir bening ini mencuri kesempatan untuk keluar
melalui celah tersempit sekalipun. Pandangan ini tanpa
sengaja merekam aksi diamnya jajaran sandal di bawah sana,
di depan pintu gedung asrama berwarna jingga itu. Berbaris
rapi berpasang-pasang. Bahkan sepasang alas kaki yang
kodratnya hanya untuk diinjakpun tidak pernah sendiri,
apalagi merasakan kesepian. Kembali, aku memandangi langit
yanag masih enggan menyingkap tabir. Mendongak. Hawa
dingin menampar pipiku seketika.
“Bunda, kenapa sih Bunda harus kerja di Ibukota. Kan,
kalau begini Swara jadi susah untuk nepatin janji. Paskibraka
Nasional gak gampang buat Swara.”
Satu persatu rasa yang asing oleh lidah, mulai mengisi
satu ruang yang Allah ciptakan khusus untuknya. Perasaan
rindu yang tidak akan pernah tersampaikan. Perasaan takut
yang tidak beralasan. Perasaan kosong ketika rasa penyesalan
tentang betapa cerobohnya aku kembali muncul. Tanpa segan
ia mengundang ingatan malangku untuk memutar memori
pada tempo itu. Siang yang berangin di kantin sekolah
membuatku ingin angkat tangan atas penantian sendu ini. Dan
tabir siang yang memberiku sebuah arti final. Sebenarnya,
selepas pengajian pagi aku kehilangan semangat sekolah.
Gairahku benar-benar hancur. Sampai pada jam kesekian,
nama Nareswara Arendra terdengar di seluruh penjuru
pesantren putri setelah nama Paku Nalabela disebutkan. Pada
detik-detik itulah rona hatiku berputar ke lain titik derajat.
“Tapi, aku masih tidak percaya. Bisa-bisanya kamu
dikirim untuk menjalani karantina dengan Nala si modelnya
pesantren itu! Kalau dibandingkan dengan kamu, kamu punya
apa?” Imbuh Ragil sarkasme.
Memang aku sempat heran. Dibandingkan dengan
Nalabela sang model yang wajah ayunya sering tercetak di
brosur dan banner. Aku jelas lewat. Apalagi dia yang notabene
seorang mantan Ketua Paskibraka semasa SMP. Sudah dapat
dipastikan keahliannya berdasarkan pengalaman yang ia miliki.
Satu kesimpulan yang dapat aku tarik, aku beruntung. Surat
berstempel ini semakin mendekap anganku akan seorang
paskibraka yang penuh kharisma melenggang tegap
mengiringi bendera merah putih. Istimewanya, ada Bunda
yang akan merengkuh paskibraka itu.
“Simpan dulu, Neng. Biar ndak kusut” Sindir Ragil
menanggapi tingkahku yang memberlakukan surat dari Pihak
Penyeleksi Paskibraka Nasional layaknya surat cinta. Tanpa ia
sindir pun sebenarnya aku sudah berniat untuk
memasukkannya kembali kedalam amplop tempatnya berasal.
Sayangnya, jikalau aku tidak terhanyut dalam timangan
anganku, mungkin aku bisa menyimpannya untuk waktu yang
lebih lama. Apalah adanya, semua sudah terjadi begitu cepat
di depan mataku. Aku mengingat semuanya dengan lekang,
dan aku menyesalinya.
Kertas berkop itu membelah jadi dua secara perlahan,
sesaat setelah sadar kertas itu tidak kupegang lagi. Nafasku
tertahan. Mataku membulat. Aku kaget, bahkan tidak sempat
menyadari mengenai kehadiran seseorang di sampingku. Dia
dengan santainya menyobek pelan kertasku. Seorang gadis
anggun setinggi 160 sentimeter. Lebih tinggi tiga senti dariku.
Dialah Nalabela.
“Eh, kok ada kop resminya, ya? Upppss, sepertinya ini
berharga untukmu” aku terdiam memandangi surat itu. Ia
menyeringai licik serambi melempar surat itu ke wajahku.
“Maaf ya” Lanjutnya dengan nada yang dibuat sok
bersalah.
Habis kesabaran Ragil. Tanpa seperizinanku dia berdiri
dari duduknya, disusul suara gebrakan meja ulah sepasang
telapak tangannya yang mengeras akibat luapan emosi. Ragil
yang temperamental tidak bisa mengontrol rasa kesalnya.
Kegaduhan tidak terelakkan. Semua berantakan. Menjadi
kusut, sekusut kertas berkop tadi yang sekarang melayang lalu
meringkuk kesepian. Pasalnya, ia sudah terlepas dari masalah.
Sedangkan untukku, masalah itu malah menjerat kuat. Aku
yang semula tidak ingin terlibat ujung-ujungnya terseret ke
depan meja dewan kepesantrenan. Satu kasus yang sudah aku
ketahui benar apa konsekuesinya.
”Kalian bertiga. Saya tidak tahu alibi kalian. Semuanya
akan mendapat hukuman yang sama. Kamu, Nareswara!
Karena satu kesalahan kamu, kami pihak kepesantrenan
membatalkan karantinamu sebagai peserta Paskibraka.”
Ucapan Ustaz yang menduduki posisi dewan
kepesantrenan itu kurekam dengan jelas dalam kompilasi
album sedih yang kutata rapi di rak kenanganku. Kisah yang
aku angan-angan penuh warna, tentang pembuktian sebuah
kepercayaan. Tidak seindah perealisasiannya. Kisah
selanjutnya begitu buram. Seburam cermin tua yang
terbengkalai di sudut kamarku.
Aura malam semakin mencekam. Hawa dingin yang
semula memeluk menggigilkan berubah haluan menjadi
mencengkeram membekukan. Aku masih berdiri pada
posisiku. Menjadikan pagar balkon kamarku sebagai tumpuan
kedua lengan yang tidak bertenaga.
Tidak biasanya aku merenung terlampau lama. Semua
rasa yang mengisi ruang khusus itu semakin absurd. Hanya
tertinggal nanas putus asa, membuat dadaku penuh sesak.
“Bunda, apa Allah lupa dengan Swara? Bukankah janji
Allah bakal nyata?” suaraku mengecil.
“Apa Swara kurang percaya pada Bunda? Semenjak
mendapatkan surat itu. Swara semakin percaya, janji ini gak
sia-sia. Swara akan mengibarkan bendera Merah Putih di
Istana Negara. Di tempat itu akan teramat mudah untuk
memelukmu. Masa bodoh dengan janji yang kedua”. Kembali,
aku menahan suaraku agar tidak berucap lagi. Pelan, aku
berusaha mengeja apa yang hatiku tuliskan. Menjaga agar janji
itu tetap tekontrol oleh sistem otakku.
”Bunda, Tujuh kali lagi bertemu malam. Maka Swara
tidak bisa lagi bertemu denganmu. Apakah ini nyata, Bunda?”
Kilatan cahaya putih melukisi kanvas langit malam ini.
Air jatuh untuk kesekian kali. Langit malam pun
menumpahkan kesedihan, menguraikan semua beban miliknya
selama menemani Bumi. Lalu, kapan aku bisa seperti langit?
Pagi ini, langit masih terbawa suram. Seakan mengerti
lebih tentang perasaanku yang semakin buram dari pandangan
bahagia. Ditambah lagi dengan keberadaan seorang laki-laki
di depanku yang mengaku sebagai ayahku.
“Swara?”
“Diam!!!” potongku tegas.
Pikiranku kalut, perasaanku kacau. Hilang semua ilmu
tentang etika yang selama ini aku jaga. Apa maksud sang
takdir pada jalan hidupku. Aku sudah menganggapnya tidak
pernah ada. Karena dia, Bunda harus pergi ke ibukota. Karena
dia juga, terpetik janji itu. Lalu untuk apa dia sekarang datang,
di saat Bunda sudah benar-benar tidak akan menemuiku.
Abaikan janji keduaku pada Bunda. Biarlah, aku terlanjur
membencinya.
“Tunggu, jangan potong ucapan Ayah. Semua tidak
seperti yang Swara pikirkan. Swara harus tahu sesuatu” Aku
terdiam mendengarkan suaranya yang teramat dirindukan oleh
indera pendengaranku dalam menyebut namaku. Aku
mengamatinya, gerakannya ketika mengambil sepucuk kertas
dari saku kemeja.
“Baca sekarang juga. Ayah harap Swara mengerti”. Aku
menerima kertas yang ia sodorkan padaku. Kertas ini seperti
tidak asing bagiku. Kertas ini sama dengan surat Bunda yang
berada di kantong jubahku.
Aku membukanya pelan, mengamati sekilas. Manik
mataku bergetar. Retina ini menangkapnya, tulisan Bunda
yang lain. Apa mungkin...
“Itu potongan surat dari Bunda untukmu. Ayah
menemukannya di lantai rumah. Mungkin terjatuh.”
Aku membungkam mulutku. Menunduk, memandangi lamat
kertas di tanganku. Sebuah kenyataan yang baru terungkap
untukku. Ayahku seorang non-muslim, dan Bunda mualaf
ketika usiaku menginjak 10 tahun. Jelas sekali alasan mereka
berpisah dan tidak bisa kembali bersama. Hukum fasakh1
berlaku untuk Bunda, dan untuk masalah ini Bunda
menyembunyikannya. Seharusnya janjiku bukan untuk tidak
membenci ayah, melainkan untuk membencimu.
“Ayah, bawa Swara pada Bunda?” Ucapku akhirnya,
wajahnya pias.
“Ayo, ikut Ayah”
Mobil Avanza Hitam yang aku tumpangi berhenti
mengeluarkan bunyi erangan. Di jendela kaca, terlihat
pemandangan yang tidak pernah ingin aku lihat. Tanpa
menunggu dipersilahkan, aku membuka knop mobil. Turun
dengan tergesa dan berlari secepat yang tenagaku bisa
keluarkan. Di sana, di bawah pohon kamboja yang sedang
berguguran bunga kuningnya. Titik fokusku terkunci pada satu
objek mati.
Aku tersungkur, mengabaikan jubah putihku yang
nantinya kotor karena tanah. Aku memeluknya, takdir
membiarkanku memeluknya.
“Bunda, Swara menuntut atas kepercayaan yang Swara
berikan pada Bunda. Bangun Bunda... Semua janji itu omong
kosong. Kenapa Bunda diam, ayo jelaskan Bunda!”
Perkataan Ayah saat di mobil kembali
terngiang.“Bundamu kecelakaan dalam perjalanan ke
Ibukota”. Pipi ini basah oleh embun yang menetes dari
pelupuk mataku. Aku menangis. Melepaskan janji yang
pernah kubuat dengan Bunda. Melepaskan Bunda yang pernah
membuat janji bersamaku.
“Bolehkah Swara membencimu, Bunda?”
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5819)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20105)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDari EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2340)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20479)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3313)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7503)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2559)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2487)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2572)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2508)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6700)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12956)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5734)