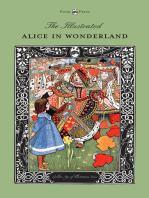Demokrasi Tanpa Negara
Diunggah oleh
Bima Satria Putra0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
8 tayangan5 halamanTulisan singkat mengenai kritik atas demokrasi negara
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniTulisan singkat mengenai kritik atas demokrasi negara
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
8 tayangan5 halamanDemokrasi Tanpa Negara
Diunggah oleh
Bima Satria PutraTulisan singkat mengenai kritik atas demokrasi negara
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Demokrasi Tanpa Negara
oleh Bima Satria Putra
Noam Chomsky, seorang cendikiawan anarkis Amerika, menjelaskan bahwa
segala istilah politik mengandung dua makna, yaitu literal dan doktrinal. Sebagai
contoh adalah demokrasi. Demokrasi adalah ketika semua orang punya kesempatan
yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam mengatur hubungan-hubungan sosial.
Namun ini adalah makna yang definisinya bisa dengan mudah kita dapatkan di
dalam kamus-kamus. Kenyataannya?
Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa etos konsumsi yang menjadi
kultur modern dari dampak langsung keberadaan kapitalisme telah membuat kita
semua menyibukkan diri dalam rutinitas pekerjaan yang menjemukan. Kita dituntut
untuk lebih banyak bekerja, untuk dapat lebih banyak merasa ‘hidup’. Pada
kenyataan, kita melihat bahwa hal ini justru semakin kontra-produktif karena ia
mencerabut individu yang sehat dari mengurus keluarganya, apalagi mengurus
komunitas, dan dalam skala yang lebih luas, terkadang kepada politik. Apa yang
kita saksikan adalah lahirnya orang-orang gila kerja dan tidak peduli, dan
seandainya peduli, kita menyaksikan bagaimana mereka mengalami hambatan
untuk merealisasikan kepeduliannya itu. Mereka hanya mampu melaksanakan hal-
hal remeh, dan menganggap bahwa itulah kontribusi terbaik yang bisa ia berikan.
Padahal, kemampuan dan intelegensia kita bisa mencapai suatu ukuran yang
mungkin tidak dapat kita bayangkan, dari sekedar membuang sampah pada
tempatnya, membantu nenek menyebrangi jalan raya, mengikuti pemilihan umum
dan berdiskusi mengenai kontestasi politik nasional saat ini di warung-warung kopi.
Apa yang tersisa bagi kita hanyalah remah-remah, dan sialnya, kita bahkan
bersyukur bahwa kita telah berpartisipasi secara pasif, saking pasifnya, sebenarnya
hal tersebut bahkan sama sekali tidak dapat disebut sebagai partisipasi. Sistem
kenegaraan telah mengerdilkan warga menjadi sekedar “pembayar pajak”,
“pemberi suara” dan “konstituen”, seolah-olah mereka terlalu muda atau tidak
mampu untuk mengelola urusan-urusan publik mereka sendiri. Segala administrasi
menjadi bersifat sangat profesional, membuat rumit banyak proses pertimbangan
pengambilan keputusan, sehingga kita membutuhkan bidang ilmu tersendiri untuk
mempelajarinya, dan membuat rakyat menjadi semakin pusing dan lebih pasif lagi.
Pada akhirnya, pengambilan keputusan tetap terjadi secara tersentralisir dan
kemudian lahirlah kebijakan publik yang sangat buruk. Upaya kita untuk
mempengaruhinya sangat sulit, seperti menghancurkan tank dengan melempar
kerikil. Seribu protes digelar, dan seribu petisi disebar, namun semua hanya
berujung kepada kegagalan dan kekalahan. Seandainya berhasil, ada rangkaian
kebijakan buruk lain yang harus kita upayakan untuk dirubah. Alhasil, politik tampak
seperti kegiatan ritual menyembah setan.
Sekarang, kita menyaksikan bahwa urusan-urusan publik diatur hanya oleh
segelintir elit. Tentu saja, tidak semua politisi itu buruk. Namun politisi yang baik
hanya masuk ke dalam kandang singa. Artinya, politisi baik masuk ke dalam
“kandang” yang buruk dan dikelilingi oleh politisi “singa” buruk yang lain. Seidealis
apapun motivasi ia untuk terjun ke dunia politik, mereka hanya menjadi bagian dari
sistem interaksi kekuasaan yang perintah-perintahnya telah berkuasa atas diri
mereka. Asumsi dasar kebanyakan orang adalah percaya bahwa jika kita memilih
dengan tepat, maka penguasa yang baik akan memberikan dan menjamin hak-hak
kita. Bukankah ini konyol, mengingat tidak ada satu manusia pun yang sempurna di
dunia, dan karena penguasa adalah manusia, maka dengan demikian tidak ada
hasil yang sempurna pula dari penguasa yang tidak sempurna tersebut? Namun
mereka malah mentolerir hal ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar
dan layak diterima, tanpa mempertimbangkan adanya pilihan-pilihan lain yang
sebenarnya jauh lebih masuk akal dan manusiawi. “Pemilu itu bukan untuk memilih
yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa,” ujar Frans Magnis
Suseno, yang dengan lancang mengeluarkan pernyataan kompromis macam ini. Jika
demikian, apalagi yang dibutuhkan dari penguasa jika mereka memang tidak
mungkin memberikan yang asasi dari setiap manusia, yaitu kebebasan?
Di sisi lain, banyak orang mengira bahwa permasalahannya terletak pada
politikus yang bodoh. Hingga batas tertentu, hal ini ada benarnya. Namun saya
harap ini tidak mengaburkan akar permasalahannya yang sebenarnya. Kebutuhan
akan politikus yang cerdas, pemimpin negara dan kementrian yang sesuai dengan
latar belakangnya, atau yang bijak, adalah kebutuhan untuk membuat massa tetap
bodoh. Kapitalisme telah menghasilkan spesialisasi, artinya, ada pembagian kerja
yang berlebihan atas seseorang untuk hanya menekuni satu bidang tersebut.
Negara memastikan bahwa mereka yang terlibat didalamnya adalah para
profesional, para ahli kenegaraan saja. Nah, kalau sudah demikian, apa fungsi
partisipasi sipil? Bagaimana mungkin demokrasi bisa dilangsungkan dalam negara?
Memilih politikus yang baik dan bermoral saja tidak cukup. Apalagi hanya
sekedar cerdas. Permasalahan politik kita melampaui hal ini, ia bukan perkara
moral, melainkan sudah bersifat struktural. Mengutus dan memilih politisi yang baik
tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Baiklah, mungkin kita senang
bahwa ada beberapa perubahan kebijakan yang lebih pro-rakyat. Namun seperti
sudah saya jelaskan, politik yang kita bangun saat ini berdiri di atas fondasi yang
sudah salah sedari awal.
Sekarang, apa alternatif politik yang memungkinkan?
Aristoteles, dalam buku pertama dari rangkaian karya Politica menjelaskan
bahwa manusia menurut kodratnya merupakan zoon politikon, makhluk yang hidup
dalam polis (kota). Polis, pada masa Yunani kuno adalah sebuah kota, dan aktivitas
untuk mengurusi polis adalah politik. Semua manusia, seharusnya mengurusi
kehidupan dan berorientasi komunitas bersama melalui politik. Politik bukanlah
ajang merebut kekuasaan seperti kita lihat pada negara-negara saat ini. Di dalam
polis-polis Yunani, semua lelaki dewasa terlibat langsung dalam pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan komunitas mereka secara konsensus dan tatap
muka (face to face). Makhkul politik dianggap sebagai sebuah sifat alamiah dalam
tujuan mengorganisasikan dan mengelola kehidupan komunitas mereka secara
bersama. Mereka tidak bisa sepenuhnya menjadi manusia kecuali mereka terjun
berpartisipasi dalam kehidupan komunitas yang berorganisasi. Mereka tidak harus
menjadi aktivis dan politikus untuk membuat perubahan. Mereka tetap bisa menjadi
pedagang dan sesekali datang dalam pertemuan warga untuk mengambil suatu
keputusan. Inilah yang dimaksud dengan demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan),
inilah bentuk kekuasaan rakyat yang sesungguhnya. Inilah demokrasi. Demokrasi
Yunani kuno memang tidak sempurna, karena masih terdapat perbudakan,
xenofobia dan patriarki. Budak-budak, perempuan dan orang asing sama sekali
tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Walau demikian, bentuk
demokrasi ini jauh lebih manusiawi dan rasional untuk menciptakan alternatif politik
desentralisasi radikal yang baik ketimbang politik negara yang tersentralisir. Pada
masa inilah kesenian, filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Warga sipil
Yunani bukanlah orang-orang bodoh apolitis yang tidak tahu menahu dengan apa
yang terjadi. Isu-isu politik didiskusikan di ruang-ruang publik dan keputusan ada di
tangan mereka sendiri. Dengan model politik ini Yunani mencapai bentuk
kebudayaan yang sangat maju di muka bumi pada zamannya, yang bahkan belum
dapat dilampaui oleh model-model politik saat ini.
Apakah demokrasi adalah peradaban barat? Tidak juga. Banyak kebudayaan
di dunia telah mengenal model yang sama namun dengan nama yang berbeda. Di
Indonesia, kita menyebut demokrasi sebagai musyawarah, dan menyebut
pengambilan keputusan konsensus sebagai mufakat. Demokrasi konsensus dan
musyawarah untuk mufakat adalah dua hal yang nyaris sama. Kampung-kampung
dan desa-desa di berbagai wilayah di nusantara telah mempraktikkan ini mungkin
sejak ratusan tahun yang lalu, dalam ukuran yang berbeda-beda. Sama seperti di
Yunani, bentuknya mungkin tidak sempurna. Ia bisa saja dimonopoli oleh segelintir
pemuka adat atau pemimpin desa, juga karena minimnya keterlibatan ibu-ibu, serta
dominasi oleh orang tua dengan seperangkat aturan tata-krama yang berlebihan
sehingga menekan orang-orang muda untuk patuh. Di satu sisi, otonomi politik desa
mungkin juga terhambat karena adanya kepatuhan terhadap otoritas kerajaan,
sehingga mereka kerap tidak dapat bebas dalam mengambil keputusan. Namun
perlu kita ingat, bahwa apa yang kita maksud demokrasi ternyata sangat dekat
dengan kultur kita, walau belum sempurna. Ini justru membantah mitos bahwa
Pancasila lahir dari rahim bangsa kita sendiri. Sila ke-4 dari Pancasila, yang berbunyi
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan
perwakilan” adalah komponen demokrasi perwakilan (alias oligarki) yang diserap
dari parlementerisme Eropa Barat modern. Bukannya mengenal sistem perwakilan
dalam budaya kita, kita justru mengenal sistem demokrasi langsung yang hidup
subur dalam otoritas monarki kerajaan nusantara.
Tapi perlu kita ingat, permasalahan utamanya tidak terletak pada partisipasi,
keterwakilan, dan keterbukaan, tapi pada kebebasan dan otonomi individu, dan
pada keadilan sosial. “Negara” adalah institusi politik yang bermasalah. Ia memang
lebih baik dan demokratis ketimbang kerajaan atau kekaisaran yang dimonopoli
oleh satu orang monarkis. Namun negara, bahkan walau dalam bentuk republik
sekalipun, tetap mempertahankan kekuasaan segelintir orang. Negara pada
hakikatnya, secara struktural dan profesional, terpisah dari khalayak umum. Ia
ditegakkan di atas orang-orang biasa, laki-laki dan perempuan. Ia menjalankan
kekuasaan atas rakyat dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan
mereka. Dengan sifatnya yang profesional, manipulatif dan imoral, sistem elit dan
massa yang berkedok demokrasi ini, menghina ideal demokrasi yang seringkali
mereka ikrarkan dalam seruan berkala kepada para ‘pemilih’. Jauh dari
memberdayakan rakyat sebagai warga, negara mensyaratkan pelucutan umum
kekuasaan warga. Sepanjang tahun, para ahli kenegaraan akan lebih senang jika
orang-orang cenderung lebih memusatkan perhatian pada urusan pribadi masing-
masing dan tak ambil pusing dengan aktivitas para “politisi.” Jika orang-orang
semakin aktif dan berminat aktif dalam kehidupan politik, mereka akan
menciptakan masalah bagi negara dengan mengusik-usik perkara ketidakcocokan
antara realitas sosial dengan retorika yang menyertainya.
Sekarang, bentuk demokrasi kita yang tidak sempurna tersebut (dan
sebenarnya bukanlah bentuk demokrasi), alih-alih bertambah baik, justru
bertambah buruk. Negara telah mencoba menghancurkannya melalui upaya yang
panjang dan melelahkan dan yang tersisa masih terus dihancurkan lagi. Negara
mengambil alih dan masih berupaya melumpuhkan partisipasi publik ini. Negara
juga memerintah tempat-tempat yang jauh untuk tunduk di bawah kontrolnya,
menghilangkan otonomi apapun yang sampai saat ini mereka nikmati.
Kita harus membuka kembali kehidupan sipil yang telah hilang dengan begitu
cepat dan mentransformasikannya ke ranah politik. Kita harus melahirkan warga
aktif yang keluar dari konstituen pasif dan memberikan mereka konteks politik
dimana mereka memiliki pilihan-pilihan yang lebih berarti dalam mengelola urusan
bersama. Kita harus menciptakan konteks ini dengan melembagakan kekuatannya
dalam majelis lingkungan (atau apapun namanya) dan rapat-rapat kota. Dalam
pengertian yang sangat radikal, kita harus kembali ke akar politik dengan
membangkitkan demokrasi langsung dan mengembangkannya, dengan nilai-nilai
rasional dan etis beserta praktik-praktik yang mendukungnya. Kebebasan harus
dijunjung tinggi sehingga tidak ada segelintir moralis yang masuk ke dalam
kehidupan pribadi kita dengan mengacak-acak kasur tempat kita tidur. Hal-hal ini
berarti menyaratkan dihancurkannya tatanan lama serta menciptakan yang baru di
atas puing-puing kehancuran dimana keadilan, kebebasan, kesetaraan dan
kesejahteraan diwujudkan dalam maknanya yang sangat literal, bukan doktrinal.
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20020)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12946)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)







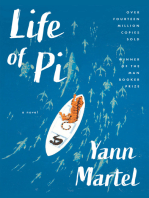
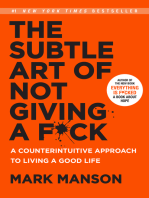





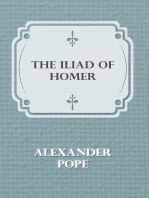





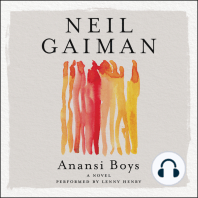

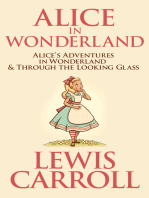




![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)