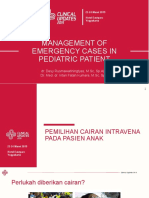PPK Dermatitis Kontak Alergi
PPK Dermatitis Kontak Alergi
Diunggah oleh
Tiara S Arum0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
6 tayangan3 halamanDka
Judul Asli
10. PPK DERMATITIS KONTAK ALERGI
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniDka
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
6 tayangan3 halamanPPK Dermatitis Kontak Alergi
PPK Dermatitis Kontak Alergi
Diunggah oleh
Tiara S ArumDka
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
PANDUAN PRAKTIK KLINIS
UPTD PUSKESMAS PERAWATAN
KARANG JOANG
DERMATITIS KONTAK ALERGI (DKA)
1. Pengertian (Definisi) Dermatisis kontak alergik (DKA) adalah reaksi
peradangan kulit imunologik karena reaksi
hipersensitivitas. Kerusakan kulit terjadi didahului oleh
proses sensitisasi berupa alergen (fase sensitisasi) yang
umumnya berlangsung 2-3 minggu. Bila terjadi pajanan
ulang dengan alergen yang sama atau serupa, p eriode
hingga terjadinya gejala klinis umumnya 24-48 jam (fase
elisitasi). Alergen paling sering berupa bahan kimia
dengan berat molekul kurang dari 500-1000 Da. DKA
terjadi dipengaruhi oleh adanya sensitisasi alergen,
derajat pajanan dan luasnya penetrasi di kulit.
2. Anamnesis ( Keluhan kelainan kulit berupa gatal. Kelainan kulit
Subjective) bergantung pada keparahan dermatitis. Keluhan dapat
disertai timbulnya bercak kemerahan.
Hal yang penting ditanyakan adalah riwayat kontak
dengan
Bahan-bahan yang berhubungan dengan riwayat
pekerjaan,
Hobi
Obat topikal yang pernah digunakan
Obat sistemik
Kosmetik
Bahan-bahan yang dapat menimbulkan alergi
Riwayat alergi di keluarga.
Faktor Predisposisi
Pekerjaan atau paparan seseorang terhadap suatu
bahan yang bersifat alergen
3. Pemeriksaan Fisik Tanda Patognomonis
( Objective)
Tanda yang dapat diobservasi sama seperti dermatitis
pada umumnya tergantung pada kondisi akut atau kronis.
Lokasi dan pola kelainan kulit penting diketahui untuk
mengidentifikasi kemungkinan penyebabnya, seperti di
ketiak oleh deodoran, di pergelangan tangan oleh jam
tangan.
4. Kriteria diagnosa Penegakkan diagnosis didasarkan atas anamesis,
pemeriksaan fisik dan penunjang
5. Diagnosis Kerja Arthritis Dermatitis kontak alergi
6. Kode Diagnosis No. ICPC-2 : S88 Dermatitis contact allergic
No. ICD-10 : L23 Allergic contact dermatitis
7. Assement Diagnosis ditegakkan berdasarkan gambaran klinis
8. Diagnosis Banding Dermatitis kontak iritan
9. Pemeriksaan -
Penunjang
10. Komplikasi Infeksi sekunder
11. Tatalaksana 1. Keluhan diberikan farmakoterapi berupa:
a. Topikal (2 kali sehari)
Pelembab krim hidrofilik urea 10%.
Kortikosteroid: Desonid krim 0,05% (catatan:
bila tidak tersedia dapat digunakan
Fluosinolon asetonid krim 0,025%).
Pada kasus dengan manifestasi klinis
likenifikasi dan hiperpigmentasi, dapat diberikan
golongan Betametason valerat krim 0,1% atau
Mometason furoat krim 0,1%).
Pada kasus infeksi sekunder, perlu
dipertimbangkan pemberian antibiotik topikal.
b. Oral sistemik
Antihistamin hidroksisin 2 x 25 mg per hari
selama maksimal 2 minggu, atau
Loratadin 1x10 mg per hari selama maksimal
2 minggu.
c. Pasien perlu mengidentifikasi faktor risiko,
menghindari bahan-bahan yang bersifat alergen,
baik yang bersifat kimia, mekanis, dan fisis,
memakai sabun dengan pH netral dan
mengandung pelembab serta memakai alat
pelindung diri untuk menghindari kontak alergen
saat bekerja.
12. Kriteria Rujukan 1. Apabila kelainan tidak membaik dengan
pengobatan topical standar.
2. Apabila diduga terdapat faktor penyulit lain,
misalnya focus infeksi pada organ lain, maka
konsultasi danatau disertai rujukankepada dokter
spesialis terkait (contoh: gigi mulut, THT, obgyn,
dan lain-lain) untuk penatalaksanaan fokus infeksi
tersebut.
13. Prognosis Prognosis pada umumnya bonam apabila kelainan ringan
tanpa penyulit, dapat sembuh tanpa komplikasi, namun
bila kelainan berat
dan dengan penyulit prognosis menjadi dubia ad bonam.
14. Penelaah Kritis Dokter Puskesmas
15. Kepustakaan 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
Anda mungkin juga menyukai
- Workshop 3. Pemilihan Cairan IVDokumen27 halamanWorkshop 3. Pemilihan Cairan IVTiara S ArumBelum ada peringkat
- Soal Yakin DermatovenerologiDokumen12 halamanSoal Yakin DermatovenerologiTiara S ArumBelum ada peringkat
- PSIKIATRI2Dokumen21 halamanPSIKIATRI2Tiara S ArumBelum ada peringkat
- PicoDokumen1 halamanPicoTiara S ArumBelum ada peringkat
- Aku Mencintaimu SuamikuDokumen26 halamanAku Mencintaimu SuamikuTiara S ArumBelum ada peringkat