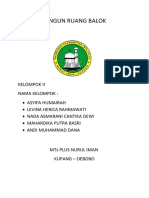ITS Undergraduate 7197 2702100009 Bab2 PDF
ITS Undergraduate 7197 2702100009 Bab2 PDF
Diunggah oleh
Hamdi Zae malikJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
ITS Undergraduate 7197 2702100009 Bab2 PDF
ITS Undergraduate 7197 2702100009 Bab2 PDF
Diunggah oleh
Hamdi Zae malikHak Cipta:
Format Tersedia
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Metalurgi Serbuk (Powder Metallurgy)
Metalurgi serbuk merupakan proses pembentukan benda
kerja komersial dari logam dimana logam dihancurkan dahulu
berupa tepung, kemudian tepung tersebut ditekan di dalam
cetakan (mold) dan dipanaskan di bawah temperatur leleh serbuk
sehingga terbentuk benda kerja. Sehingga partikel-partikel logam
memadu karena mekanisme transportasi massa akibat difusi atom
antar permukaan partikel. Metode metalurgi serbuk memberikan
kontrol yang teliti terhadap komposisi dan penggunaan campuran
yang tidak dapat difabrikasi dengan proses lain. Sebagai ukuran
ditentukan oleh cetakan dan penyelesaian akhir (finishing touch).
Langkah-langkah dasar pada powder metallurgy:
1. Pembuatan Serbuk.
2. Mixing.
3. Compaction.
4. Sintering.
5. Finishing.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 5
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Gambar 2.1: Langkah-langkah dasar powder metallurgy
2.1.1 Pembuatan serbuk
Ada beberapa cara dalam pembuatan serbuk antara lain:
decomposition, electrolytic deposition, atomization of liquid
metals, mechanical processing of solid materials.
1. Decomposition, terjadi pada material yang berisikan
elemen logam. Material akan menguraikan/memisahkan
elemen-elemennya jika dipanaskan pada temperature
yang cukup tinggi. Proses ini melibatkan dua reaktan,
yaitu senyawa metal dan reducing agent. Kedua reaktan
mungkin berwujud solid, liquid, atau gas.
2. Atomization of Liquid Metals, material cair dapat
dijadikan powder (serbuk) dengan cara menuangkan
material cair dilewatan pada nozzel yang dialiri air
bertekanan, sehingga terbentuk butiran kecil-kecil.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 6
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
3. Electrolytic Deposition, pembuatan serbuk dengan cara
proses elektrolisis yang biasanya menghasilkan serbuk
yang sangat reaktif dan brittle. Untuk itu material hasil
electrolytic deposition perlu diberikan perlakuan
annealing khusus. Bentuk butiran yang dihasilkan oleh
electolitic deposits berbentuk dendritik.
4. Mechanical Processing of Solid Materials, pembuatan
serbuk dengan cara menghancurkan material dengan ball
milling. Material yang dibuat dengan mechanical
processing harus material yang mudah retak seperti
logam murni, bismuth, antimony, paduan logam yang
relative keras dan britlle, dan keramik.
Dari sekian proses pembuatan serbuk, proses yang
banyak dipakai adalah proses atomisasi.
(a) (b) (c)
Gambar 2.2 : Proses Atomisasi
(a) Water or gas atomization; (b) Centrifugal atomization; (c) Rotating
electrode
Sifat-Sifat Khusus Serbuk Logam
1. Ukuran Partikel
Metoda untuk menentukan ukuran partikel antara lain
dengan pengayakan atau pengukuran mikroskopik. Kehalusan
berkaitan erat dengan ukuran butir, faktor ini berhubungan
dengan luas kontak antar permukaan, butir kecil mempunyai
porositas yang kecil dan luas kotak antar permukaan besar
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 7
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
sehingga difusi antar permukaan juga semakin besar dan
kompaktibilitas juga tinggi.
Tabel 2.1 Standart ukuran butir
2. Distribusi Ukuran Dan Mampu Alir
Dengan distribusi ukuran partikel ditentukan jumlah
partikel dari ukuran standar dalam serbuk tersebut. Pengaruh
distribusi terhadap mampu alir dan porositas produk cukup
besar Mampu alir merupakan karakteristik yang
menggambarkan alir serbuk dan kemampuan memenuhi
ruang cetak.
3. Sifat Kimia
Terutama menyangkut kemurnian serbuk, jumlah
oksida yang diperbolehkan dan kadar elemen lainnya. Pada
metalurgi serbuk diharapkan tidak terjadi reaksi kimia antara
matrik dan penguat.
4. Kompresibilitas
Kompresibilitas adalah perbandingan volum serbuk
dengan volum benda yang ditekan. Nilai ini berbeda-beda dan
dipengaruhi oleh distribusi ukuran dan bentuk butir, kekuatan
tekan tergantung pada kompresibilitas.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 8
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
5. Kemampuan sinter
Sinter adalah proses pengikatan partikel melalui proses
penekanan dengan cara dipanaskan 0.7-0.9 dari titik lelehnya.
Gambar 2.3 : Karakterisasi bentuk sistem partikel sederhana
2.1.2 Mixing (Pencampuran serbuk)
Pencampuran serbuk dapat dilakukan dengan
mencampurkan logam yang berbeda dan material-material lain
untuk memberikan sifat fisik dan mekanik yang lebih baik.
Pencampuran dapat dilakukan dengan proses kering (dry mixing)
dan proses basah (wet mixing). Pelumas (lubricant) mungkin
ditambahkan untuk meningkatkan sifat powders flow. Binders
ditambahkan untuk meningkatkan green strenghtnya seperti wax
atau polimer termoplastik
2.1.3 Compaction (Powder consolidation)
Compaction adalah salah satu cara untuk memadatkan
serbuk menjadi bentuk yang diinginkan. Terdapat beberapa
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 9
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
metode penekanan, diantaranya, penekanan dingin (cold
compaction) dan penekanan panas (hot compaction). Cold
compaction yaitu memadatkan serbuk pada tempetatur ruang
dengan 100-900 Mpa untuk menghasilkan green body.
Proses cold pressing terdapat beberapa macam antara
lain:
1. Die Pressing, yaitu penekanan yang dilakukan pada
cetakan yang berisi serbuk
2. Cold isotactic pressing, yaitu penekanan pada serbuk
pada temperature kamar yang memiliki tekanan yang
sama dari setiap arah.
3. Rolling, yaitu penekanan pada serbuk metal dengan
memakai rolling mill.
Gambar 2.4: Die Pressing
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 10
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Penekanan terhadap serbuk dilakukan agar serbuk dapat
menempel satu dengan lainnya sebelum ditingkatkan ikatannya
dengan proses sintering. Dalam proses pembuatan suatu paduan
dengan metode metalurgi serbuk, terikatnya serbuk sebagai akibat
adanya interlocking antar permukaan, interaksi adesi-kohesi, dan
difusi antar permukaan. Untuk yang terakhir ini (difusi) dapat
terjadi pada saat dilakukan proses sintering. Bentuk benda yang
dikeluarkan dari pressing disebut bahan kompak mentah, telah
menyerupai produk akhir, akan tetapi kekuatannya masih rendah.
Kekuatan akhir bahan diperoleh setelah proses sintering.
2.1.4 Sintering
Pemanasan kompak mentah sampai temperatur tinggi
disebut sinter. Pada proses sinter, benda padat terjadi karena
terbentuk ikatan-ikatan. Panas menyebabkan bersatunya partikel
dan efektivitas reaksi tegangan permukaan meningkat. Dengan
perkataan lain, proses sinter menyebabkan bersatunya partikel
sedemikian rupa sehingga kepadatan bertambah. Selama proses
ini terbentuklah batas-batas butir, yang merupakan tahap
rekristalisasi. Disamping itu gas yang ada menguap. Temperatur
sinter umumnya berada pada 0.7-0.9 dari temperatur cair serbuk
utama. Waktu pemanasan berbeda untuk jenis logam berlainan
dan tidak diperoleh manfaat tambahan dengan diperpanjangnya
waktu pemanasan. Lingkungan sangat berpengaruh karena bahan
mentah terdiri dari partikel kecil yang mempunyai daerah
permukaan yang luas. Oleh karena itu lingkungan harus terdiri
dari gas reduksi atau nitrogen untuk mencegah terbantuknya
lapisan oksida pada permukaan selama proses sinter.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 11
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Gambar 2.5: Proses Sintering
Penyusutan (shrinkage) selalu terjadi selama proses
sintering, rumusnya sebagai berikut:
Vsintered green
Vol _ shrinkage ........................ (2.1)
Vgreen sintered
1/ 3
........................ (2.2)
Linear _ shrinkage green
sintered
2.1.5 Finishing
Pada saat finishing porositas pada fully sintered masih
signifikan (4-15%). Untuk meningkatkan properties pada serbuk
diperlukan resintering, dan heat treatment. (Hirschhorn, 1969)
2.2 Serbuk Nikel (Nickel Powder)
Nikel ( 28 Ni ) adalah unsur logam dengan nomor atom 28
yang terdapat di bumi dalam bentuk bersama dengan unsur-unsur
lain. Nikel sering ditemukan di alam bersama denga unsur besi (
26 Fe ) dan Cobalt ( 27 Co ) karena berada dalam satu golongan
dan satu periode dalam susunan periode unsur kimia, yaitu
golongan VIII dan periode 4.
Nikel murni merupakan logam yang berkilauan dengan
ciri-ciri yang menarik antara lain:
1. Dapat dibentuk ( Malleability ).
2. Dapat dibentuk menjadi kawat.
3. Daya rentangnya tinggi (tensile strength)
4. Tahan karat (Rust Proof)
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 12
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Adapun spesifikasi dari logam Nikel adalah sebagai berikut :
Nama : Nikel
Rumus Atom : Ni
BA : 58,69
Spasific grafity : 8,90 (pada 20 oC)
Melting Point : 1452 0C
Bentuk : Padatan metal
Warna : Silver, metalik
Boiling Point : 2900 0C
Kegunaan logam nikel antara lain :
Pembuatan stainless steel, sering disebut baja putih yaitu :
suatu panduan nikel dan besi dengan unsur kimia lainnya.
Pembuatan logam campuran (alloy) untuk mendapatkan sifat
tertentu.
Untuk pelapisan logam lain (nikel Plating).
Bahan untuk industri kimia (sebagai katalis) untuk pemurnian
minyak.
Elektrik heating unit, dipakai pada unit pemanas listrik.
Bahan untuk industri peralatan rumah tangga.
Tahap-tahap utama dalam proses pengolahan adalah sebagai
berikut :
Pengeringan di Tanur Pengering.
Bertujuan untuk menurunkan kadar air bijih laterit yang
dipasok dari bagian tambang dan memisahkan bijih yang
berukuran +25 mm dan – 25 mm.
Kalsinasi dan Reduksi di Tanur Pereduksi.
Untuk menghilangkan kandungan air di dalam bijih,
mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam,
dan sulfidasi.
Peleburan di Tanur Listrik.
Untuk melebur kalsin hasil kalsinasi/reduksi sehingga
terbentuk fasa lelehan matte dan terak.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 13
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Pengkayaan di Tanur Pemurni.
Untuk menaikkan kadar Ni di dalam matte dari sekitar 27
persen menjadi di atas 75 persen.
Granulasi dan Pengemasan.
Untuk mengubah bentuk matte dari logam cair menjadi
butiran-butiran dengan ukuran +10 mesh sebanyak 0%,
+20 mesh sebanyak <10%, -100 mesh sebanyak <20%.
(PT. INCO, Tbk)
Gambar 2.6: Proses Pengolahan Nikel
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 14
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
2.3 Material Magnetik
Material magnetik merupakan suatu material yang dapat
menimbulkan gaya menarik material lain. Magnet terbaik
umumnya mengandung besi metalik. Namun ternyata bahwa
unsur lain pun menampilkan sifat magnetik. Dalam teknologi
modern kini digunakan magnet logam maupun magnet keramik.
Selain itu dimanfaatkan pula unsur lain untuk meningkatkan
kemampuan magnetik sehingga memenuhi persyaratan.
2.3.1 Histerisis magnet
Magnet biasanya dibagi atas dua kelompok: magnet
“lunak” dan magnet “keras”. Magnet keras dapat menarik bahan
lain yang bersifat magnet. Selain itu sifat kemagnetannya dapat
dianggap cukup kekal. Magnet lunak dapat bersifat magntik dan
dapat menarik magnet lainnya; namun, hanya memiliki sifat
magnet bila berada dalam medan magnet, kemagnetannya tidak
kekal.
Perbedaan antara magnet permanent atau magnet keras
dan magnet lunak dapat dilakukan dengan menggunakan lopp
histerisis
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 15
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
Gambar 2.7: Kurva Histerisis Magnet
H adalah medan magnetik yang diperlukan untuk
menginduksi medan berkekuatan B dalam material. Setelah
medan H ditiadakan, dalam spesimen tersisa magnetisme residual
B r , yang disebut residual remanen, dan diperlukan medan magnet
H c yang disebut gaya koersif, yang harus diterapkan dalam arah
berlawanan untuk meniadakannya. Magnet lunak mudah
dimagnetisasi serta mudah pula mengalami demagnetisasi, seperti
tampak pada gambar 2.7. Nilai H yang rendah sudah memadai
untuk menginduksi medan B yang kuat dalam logam, dan
diperlukan medan H c yang kecil untuk menghilangkannya.
Magnet keras adalah material yang sulit dimagnetisasi dan sulit
di-demagnetisasi.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 16
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
2.3.2 Momen magnetik
Akan diperoleh pengertian yang lebih baik mengenai
karakteristik magnetik dengan menelaah struktur intern bahan.
Tiap elektron atom memiliki momen magnetik, ρ m , yang
disebut spin elektron oleh ahli fisika. Momen magnetik, disebut
magneton bohr, dan sama dengan 9.27 x 10-27 A.m2. Elektron
biasanya berpasangan dalam orbit dan membentuk spin “atas” dan
“bawah” . Jadi, efek luar dari momen tersebut tidak ada. Atom
akan bersifat magnet bila ada ketidakseimbangan dalam spin
elektron. Oleh karena itu sekitar separuh elemen yang memiliki
karakteristik magnetik, tidak 50% dari elemen mempunyai jumlah
elektron valensi yang genap. Sama halnya dengan ion, kerena
kebanyakan ion melepaskan atau menerima elektron untuk
mengisi kulitnya dengan delapan elektron. Akhirnya, ikatan
kovalen selalu mempunyai pasangan elektron (dengan spin
berlawanan). Akibatnya, hanya beberapa atom memiliki spin
elektron yang tidak seimbang, dan dengan demikian memiliki
momen magnetik. Elemen yang memenuhi persyaratan adalah
unsur transisi dengan kulit subvalensi yang tak terisi (Tabel 2.2).
termasuk kelompok ini adalah besi, kobalt, dan nikel dan logam
tanah-langkah seperti gondolium (dengan kulit 4-f yang tak terisi)
dengan sifat magnet yang kuat.
Tabel 2.2: Distribusi Momen Magnetik dan Elektron
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 17
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
2.3.3 Domain
Tiap atom besi mempunyai empat magneton bohr, 2,2β.
Ini berarti, bahwa ada ketidakserasian sebanyak 2,2 spin tiap
atomnya (Tabel 2.2). Pada temperatur tinggi, agitasi termal
mencegah terbentuknya kopel magnet di antara atom. Karena tiap
magnet “atom” bekerja sendiri-sendiri, jumlah momen magnet per
satuan volume (=Σρ m /V, disebut magnetisasi, M) adalah nol.
Bahkan disebut paramagnetic, yaitu tidak ada pengaruh magnetik
yang saling memperkuat di antara atom-atom. Bahkan tidak ada
daya tarik magnetik.
Pada temperatur ruang, momen magnet dari atom besi
yang berdekatan bergabung. Orientasi yang terkoordinir yang
terjadi menghasilkan magnetisasi. Daerah kristal yang memiliki
orientasi magnetik yang sama disebut domain. Suatu butir kristal
mengandung sejumlah domain dan setiap bagian dari kristal
mempunyai orientasi yang berbeda. Domain, dengan orientasi
yang berbeda saling meniadakan magnetisasinya. Jadi, bila
volume domain dalam jumlah sama bersearah dengan berbagai
arah kristal tidak akan terjadi magnetisasi. Hal ini terjadi bila
bahan magnetik didinginkan dari temperatur paramagnetik (diatas
Temperature Curie, T c ) hingga rentang temperatur magnetik (di
bawah T c ) tanpa pengaruh medan magnet luar. (Djaprie, 1985)
Gambar 2.8: Struktur domain sederhana dalam material
feromagnetik. Tanda panah menunjukkan
arah magnetisasi dalam domain
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 18
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
2.3.4 Paduan Magnetik
Kerja yang dilakukan untuk memindahkan batas domain
bergantung pada energi batas, yang bergantung pula pada
anisotropi magnetik. Mudahnya magnetisasi juga bergantung
pada keadaan regangan internal dalam material dan keberadaan
pengotor. Dua faktor terakhir ini mempengaruhi “kekerasan”
magnetik melalui gejala penyusutan-magnet (magnetostriction),
yaitu konstanta kisi mengalami perubahan sedikit akibat
magnetisasi dari domain. Material dengan tegangan dalam sukar
dimagnetisasi atau didemagnetisasi, sedangkan material bebas
tegangan bersifat magnetisasi lunak. Oleh karena tegangan dalam
juga mempengaruhi kekerasan mekanik, prinsip yang mendasari
desain paduan magnetik adalah membuat material magnetik
permanent yang juga keras secara mekanik dan magnet lunak
yang secara mekanik juga selunak mungkin.
Material yang secara magnetis lunak digunakan sebagai
laminasi transformator dan jangkar magnet yang memerlukan
permeabilitas tinggi dan histerisis rendah; besi-silikon atau
paduan besi-nikel umum digunakan untuk keperluan ini. Pada
pengembangan material magnet lunak ditemukan bahwa elemen
yang membentuk larutan padat interstisi dengan besi adalah
elemen yang memperlebar loop histerisis dengan sangat baik.
Dengan alasan ini, maka pengotor seperti ini dikeluarkan dari besi
transformator melalui peleburan vakum atau anil hydrogen.
Namun demikian, proses ini mahal sehingga kerapkali digunakan
paduan untuk magnet “lunak”, khususnya besi-silikon dan paduan
besi-nikel.
Seri besi-nikel, Permalloys, adalah paduan yang sangat
menarik dan terutama digunakan dalam rekayasa komunikasi di
mana disyaratkan kondisi permeabilitas tinggi. Paduan dengan
rentang kandungan nikel 40-55% mempunyai karakteristik
permeabilitas tinggi pada kekuatan medan rendah dan mencapai
nilai 15000 dibanding dengan 500 untuk besi anil. Paduan 50%,
Hypernik, mempunyai permeabilitas mencapai nilai 70.000, tetapi
nilai awal tertinggi dan permeabilitas maksimum dijumpai pada
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 19
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
rentang komposisi superkisi FeNi 3 , asalkan gejala penataan
ditiadakan. Perkembangan menarik di bidang ini adalah perlakuan
panas paduan dalam medan magnet kuat. Dengan perlakuan ini
permeabilitas Permalloy 65 meningkat hingga sekitar 260.000.
Efek ini diperkirakan terjadi karena pada saat pengarahan domain,
terjadi deformasi plastis dan pelepasan regangan magnetostriktif.
(Smallman, 1999)
2.4 Pengujian Kekerasan Vickers
Prinsip dasar pengujian ini sama dengan pengujian
brinell, hanya saja di sini digunakan indentor intan yang
berbentuk pyramid beralas bujur sangkar dan sudut puncak antara
dua sisi berhadapan 136o. Tekannya tentu akan berbentuk bujur
sangkar, dan yang diukur adalah panjang kedua diagonalnya lalu
diambil rata-ratanya. Angka kekerasan Vickers dihitung dengan:
F
HV = 1.8544 ............................. (2.3)
d2
Dimana: HV = angka kekerasan Vickers (kgf/mm2)
F = beban yang diberikan (kgf)
d = diagonal identasi (mm2)
Hasil pengujian kekerasan Vickers ini tidak tergantung
pada besarnya gaya tekan (tidak seperti Brinell), dengan gaya
tekan yang berbeda akan menunjukan hasil yang sama untuk
bahan yang sama. Dengan demikian juga Vickers dapat mengukur
kekerasan bahan mulai dari yang sangat lunak (5 HV) sampai
yang amat keras (1500 HV) tanpa mengganti gaya tekan.
Besarnya gaya tekan yang digunakan dapat dipilih antara 1
sampai dengan 120 kg, tergantung pada kekerasan/ketebalan
bahan yang diuji agar diperoleh tapak tekan yang mudah diukur
dan tidak ada anvil effect (pada benda yang tipis). (Suherman,
1987)
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 20
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
2.5 Karakterisasi Material
2.5.1 Difraksi sinar-X
Analisa dengan difraksi sinar-x merupakan salah satu
metode terpenting dalam mengidentifikasi padatan, khususnya
padatan kristal. Dasar penggunaan dalam penelitian kristal adalah
adanya susunan yang sistematis dari atom-atom yang menyusun
padatan kristal atau ion-ion dalam bidang kristal dalam setiap
spesies kristal dicirikan oleh susunan atom yang spesifik yang
menciptakan suatu bidang atom sebagai penciri yang dapat
memantulkan sinar-x.
Sinar-x ini merupakan radiasi elektromagnetik dengan
panjang gelombang pendek, sesuai dengan jarak atom ataupun
bidang kristal. Pada tahun 1972, Laue adalah orang pertama yang
menunjukkan bahwa sinar x dapat dipantulkan oleh atom-atom
dalam bidang kristal yang menghasilkan pola-pola khas pada hasil
rekaman. Pola-pola difraksi inilah yang digunakan sebagai sidik
jari dalam identifikasi kristal (Day,1990).
Sinar-x ditimbulkan jika elektron berenergi tinggi
mengenai logam target (besi, tembaga dan lain-lain). Gelombang
sinar-x memiliki spektrum yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu
pita yang lebar untuk radiasi kontinu serta garis khas (K dan K )
komponen K 1 dan K 2 dipisahkan oleh jarak panjang gelombang
yang sangat kecil.
Garis K dan K seperti dipisahkan dengan filter
penyearah yang terbuat dari logam seperti zircon, nikel atau
mangan. Jumlah radiasi sinar-x yang diserap oleh cuplikan
ditentukan oleh koefisien absorsi zat sesuai panjang gelombang
sinar.
Apabila sinar monokromatik mengenai cuplikan, ada dua
hal yang terjadi :
a. Bila cuplikan memiliki struktur didaerah sekitar kristak
maka sinar x akan terhambur secara koheren, proses ini
dikenal sebagai efek difraksi sinar-x dan diukur secara
difraksi sinar sudut lebar.
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 21
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
b. Bila cuplikan memiliki struktur denagn daerah kristal dan
amorf maka sinar 2 akan terhambur secara tidak konkeren
(hamburan compton).proses ini terjadi dengan perubahan
panjang gelombang dan fase ini dikenal sebagai
hamburan sinar sudut sempit.
Permukaan suatu kristal dianggap suatu bidang yang
melalui permukaan atom dan oleh Miller diindekskan dengan
simbol d hkl . Melalui difraksi sinar x bidang kristal seperti
diketahui melalui persamaan bias :
n = 2d hkl sin............................. (2.4)
Dimana:
n = orde
= panjang gelombang
d hkl = jarak bidang antar kristal
Gambar 2.9: Berkas sinar-X pada Bidang kristal.
Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa panjang
lintasan DEF lebih besar daripada sinar ABC. Difraksi bidang-
bidang atom berjarak sama yang berturut-turut akan
menghasilkan difraksi maksimum.
2.5.2 Mikroskop optik
Mikroskop berasal dari bahasa yunani yaitu “micron” dan
“scopos”. Mikroskop adalah instrumen untuk mengamati objek
yang kecil dan tidak bias diamati dengan mata telanjang tanpa alat
bantu. Mikroskopi adalah ilmu tentang pengamatan objek kecil
menggunakan instrumen. Mikrografi adalah gambar hasil
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 22
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
pengamatan mikroskop. Bentuk sederhana dari mikroskop adalah
mikroskop optik yaitu instrumen optik yang terdiri dari satu lensa
atau lebih yang menghasilkan gambar dengan pembesaran
puluhan atau ratusan kali.
Mikroskop sistem optik objektif dibedakan berdasarkan
pada panjang fokus, numerical aperture, kemampuan pembesaran
lensa. Pembesaran mikroskop dirumuskan dengan
D.M 1 M 2
M ....................................... (2.5)
250
dimana M 1 : Pembesaran objektif,
M 2 : Pembesaran okuler, D: jarak proyeksi.
Resolusi = ....................................... (2.6)
NA
dimana λ : Panjang gelombang iluminasi
NA : Numerical Aperture objektif. (Hariyati, 2006)
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 23
FTI-ITS Surabaya
2007
Laporan Tugas Akhir Powder Metallurgy
(halaman ini sengaja dikosongkan)
Jurusan Teknik Material dan Metalurgi 24
FTI-ITS Surabaya
2007
Anda mungkin juga menyukai
- Kelas I Tema 1 BS PressDokumen168 halamanKelas I Tema 1 BS PressparicukBelum ada peringkat
- Bangun Ruang BalokDokumen8 halamanBangun Ruang BalokparicukBelum ada peringkat
- Makalah Penjas Cabang Olahraga Bola BesarDokumen29 halamanMakalah Penjas Cabang Olahraga Bola BesarparicukBelum ada peringkat
- Rumus Menghitung Sudut ElevasiDokumen1 halamanRumus Menghitung Sudut ElevasiVarran Kelautan50% (2)