Guru Monster PDF
Diunggah oleh
Rizaldy Trijulian0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
29 tayangan113 halamanJudul Asli
Guru Monster.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
29 tayangan113 halamanGuru Monster PDF
Diunggah oleh
Rizaldy TrijulianHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 113
PROLOG
KAUPIKIR kau sudah aman di tempat tidur.
Di luar jendela kamarmu, angin mendesing, menggetarkan kaca
jendela. Kau mendengar lolongan nyaring binatang dan suara cabang
pohon mengetuk-ngetuk tembok rumah.
Kau tidak peduli. Tempat tidurmu hangat dan empuk. Kautarik
selimutmu lebih tinggi dan kaubenamkan kepalamu di bantal.
Desing angin dan lolongan binatang itu terdengar jauh di luar.
Kau aman di sini, hangat dan nyaman.
Kau tidak melihat sulur-sulur hijau ramping yang menjulur naik
dari bawah tempat tidurmu. Mereka merayap ke atas, basah berkilat,
terus dan terus naik, seperti tanaman rambat.
Matamu terpejam dan bibirmu tersenyum.
Kau sedang memikirkan hal lucu yang kauucapkan pada
orangtuamu hingga mereka terpingkal-pingkal.
Kau tidak melihat sulur-sulur panjang itu melilitmu,
menggulungmu di dalam selimut, seperti ular-ular yang gemuk.
Kau tidak mendengar geraman makhluk di kolong tempat
tidurmu. Kaukira itu suara angin di luar. Kau tidak mendengar bahwa
geraman makhluk itu semakin keras sementara ia makin erat
melilitkan sulur-sulurnya yang panjang di tubuhmu.
Selimutmu begitu tebal, sampai-sampai kau tidak merasakan
belitan sulur-sulur itu... dan akhirnya sudah terlambat.
Sekarang kau tak bisa bergerak.
Makhluk itu menggeram dan menjepitmu. Lengan-lengannya
yang hijau panjang membelitmu lebih erat... lebih erat.
Kau serasa tenggelam, terus tenggelam ke dalam kegelapan
pekat.
Kau membuka mulut untuk menjerit, tapi tak ada suara yang
keluar.
Sulur-sulur hijau dan basah itu menjepitmu lebih erat. Di bawah
tempat tidur, makhluk itu menggeram dan terbatuk-batuk.
Kau megap-megap mencari napas. Akhirnya kau menjerit. Kau
membuka mulut, lalu menjerit dan terus menjerit.
Ketika berumur tiga dan empat tahun, aku sering mengalami
mimpi buruk seperti itu. Hampir setiap malam Mom dan Dad lari
masuk ke kamarku, menyalakan lampu, lalu duduk di tempat tidurku
sambil memegangi tanganku dan mengatakan bahwa semua itu hanya
mimpi.
"Monster itu tidak ada, Paul."
Begitulah selalu kata mereka.
Waktu masih kecil, aku percaya pada monster. Anak empat
tahun masih harus belajar banyak. Mereka tidak tahu mana kenyataan
mana khayalan.
Aku sering ketakutan. Aku percaya pada eksistensi hantu,
monster, dan makhluk-makhluk aneh lainnya.
Anak sebelah rumah mengatakan di bawah garasiku ada mumi,
dan aku percaya. Aku tidak pernah ke garasi sesudah gelap.
Aku tidak mau berenang di danau kalau kami pergi berlibur.
Mom dan Dad tak pernah bisa membujukku. Kubayangkan di dasar
danau itu ada makhluk-makhluk gelap dan lengket, menunggu dengan
cakar, taring, dan sengat mereka.
Oke, oke, kalian boleh bilang aku pengecut. Aku penakut.
Kuakui, memang begitulah aku. Mungkin itu sebabnya aku jadi
senang melucu. Aku melucu agar bisa mengatasi rasa takutku.
Dan cara itu memang ampuh.
Aku belajar membedakan mana yang nyata dan mana yang
tidak. Aku belajar menyadari kalau anak rumah sebelah sedang
menggodaku.
Sekarang umurku dua belas tahun dan aku tidak pernah
bermimpi buruk lagi. Aku tak perlu lagi melongok kolong ranjang
sebelum tidur. Desau angin tidak lagi kukira hantu, dan aku berani
pergi ke garasi siang atau malam.
Besok aku akan masuk ke sekolah baru. Untuk pertama kalinya
aku masuk sekolah asrama.
Aku tenang-tenang saja. Memang, tegang juga sih. Tapi aku
tidak takut.
Aku tahu kebanyakan manusia itu normal dan baik, ke mana
pun kita pergi.
Dunia ini normal dan biasa-biasa saja.
Tidak ada yang namanya monster.
Monster hanya untuk menakut-nakuti anak tiga tahun.
Iya kan?
Iya kan?
1
"ITU bukan salahku."
"Jangan membuat alasan lagi, Paul," Mom memperingatkan.
"Tapi itu bukan salahku. Itu salah Harold."
Mom dan Dad saling pandang, lalu menggeleng-geleng dengan
kesal.
Oke. Mungkin memang aku yang salah.
Akulah yang membawa Harold, si kakaktua, ke sekolah.
Aku juga yang mengajarinya mengucapkan, Jangan bikin PR.
Gurunya bloon.
Mana aku tahu dia akan mengucapkannya di tengah pelajaran?
Dan terus mengulanginya?
Aku sudah minta maaf pada Miss Hammett. Kukatakan Harold-
lah yang mengarang-ngarang ucapan itu.
Apa dia percaya?
Tidak lah yauw!
Ia menyeretku ke kantor KepSek. Tebak apa yang terjadi saat
kami ke sana?
Aku tak sengaja menjegal kakinya.
Ia jatuh di kakiku dan lututnya memar. Ia melolong kesakitan
sampai dua guru lain membantunya berdiri dan membawanya pergi.
Aku tidak sengaja. Swear! Aku memang payah. Kukatakan
pada Miss Hammett bahwa aku tidak sengaja. Ia tidak percaya.
Sesudah peristiwa itu, ia menyiksaku. Banyak PR ekstra, aku
selalu disuruh maju paling awal dan dibuat malu setiap ada
kesempatan.
Kucoba menarik simpatinya lagi. Kucoba membuat ia tertawa.
Begitulah caraku selalu untuk mengambil hati orang.
"Mr. Perez, coba eja kata MISSISSIPPI."
"Yang nama sungai atau negara bagian?"
Lucu juga kan leluconku?
Tapi Miss Hammett melotot marah padaku.
Kucoba lagi. Berkali-kali. Anak-anak lain tertawa, tapi Miss
Hammett tersenyum pun tidak.
"Miss Hammett benar-benar gawat. Dia benci padaku. Aku
tidak bakal dapat nilai bagus dari dia," aku mengeluh pada
orangtuaku.
Mom dan Dad sangat mementingkan nilai bagus. Mereka
berdua orang sukses.
Dad diangkat menjadi presiden di perusahaannya tahun lalu.
Mom seorang pengacara, tapi tidak buka praktek. Mom sering menulis
artikel panjang dan serius tentang hukum di semua jurnal hukum
bergengsi, juga tampil di TV untuk membahas semua pengadilan
penting.
Ngerti kan?
Orangtuaku adalah orang-orang serius. Aku tahu mereka sering
heran, kenapa mereka punya anak yang konyol seperti aku. Aku tahu
mereka kecewa padaku.
Begitu mendengar aku mendapat masalah di sekolah, mereka
langsung bicara pada Miss Hammett dan Kepala Sekolah. Minggu
berikutnya mereka memberitahuku bahwa mereka akan memberiku
kesempatan yang lebih baik.
"Kami sudah memilihkan sekolah asrama yang sangat bagus
untukmu," kata Dad.
"Sekolah itu biasanya hanya menerima murid-murid terbaik di
seluruh negara," kata Mom, "tapi ayahmu dan aku menelepon
beberapa orang dan menghubungi beberapa koneksi. Mereka akan
menerimamu sebagai murid percobaan."
"Aku dicoba?" seruku. "Maksudnya aku dicicipi enak atau
tidak?"
Lihat kan? Aku selalu melucu kalau sedang gugup.
"Mungkin aku bisa coba minta maaf lagi pada Miss Hammett,"
kataku. "Mungkin aku juga bisa menyuruh Harold minta maaf."
"Masalahnya bukan pada Miss Hammett," kata Dad. "Tapi pada
kelakuanmu, Paul. Kau perlu sekolah yang serius untuk menemukan
minat dan bakatmu yang sesungguhnya."
"Kau perlu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau bisa
mencapai cita-citamu," Mom menambahkan.
Nah, kan? Ini seriusnya benar-benar serius dengan S besar.
Aku berdebar-debar. Mendadak aku menggigil. Aku tidak mau
meninggalkan rumah. Tidak mau masuk sekolah yang asing bagiku,
dengan murid-murid yang serius dan selalu dapat A.
"Apa nama sekolah itu?" tanyaku.
"Caring Academy," sahut Dad. Ia menunjukkan sehelai brosur
dengan foto sebuah bangunan besar dari batu, terletak di puncak bukit.
Kelihatannya seperti puri Drakula.
"Caring Academy?" aku berseru nyaring. "Jelek amat namanya!
Kayak nama rumah sakit."
"Sekolah itu didirikan oleh keluarga Caring," kata Mom.
"Mereka keluarga New England lama dan mendirikan sekolah itu pada
tahun 1730."
"Terlalu tua," gerutuku. "Pasti toiletnya sudah rusak semua."
Aku bermaksud melucu, tapi mereka tidak tertawa.
"Ini kesempatan kedua yang sangat bagus bagimu, Paul," kata
Dad sambil meletakkan tangan di bahuku. "Sangat sulit meyakinkan
mereka agar menerimamu. Aku yakin kau akan berusaha sebaik
mungkin."
"Tapi kenapa sekolah asrama?" sanggahku. "Aku belum pernah
tinggal di sekolah. Pergi kemping saja tidak pernah."
Dad membimbingku ke ruang tamu. "Dunia di luar sana keras,
Paul," katanya pelan, seperti membisikkan suatu rahasia.
Ia mengerutkan kening. "Semakin lama dunia di luar itu
semakin keras. Kita memakan atau dimakan."
Aku melongo memandangnya, berusaha memahami ucapannya.
Memakan atau dimakan.
Memakan atau dimakan.
Waktu itu aku tidak mengerti sepenuhnya.
Tak kusangka ucapannya menjadi kenyataan.
2
CARING ACADEMY. Tulisan itu terpampang di gerbang besi
yang tinggi saat mobil kami memasukinya. "Apa ya nama tim sepak
bolanya? Mungkin Tim Cerdas. Atau Tim Cakep!"
Tidak terlalu lucu, sih, tapi aku tertawa juga pada leluconku
sendiri. Aku melompat-lompat seperti bayi di jok belakang mobil.
Aku tak bisa duduk diam.
"Ini sekolah yang sangat serius," kata Mom. "Di sini tidak ada
tim sepak bolanya, Paul."
Bangunan sekolah itu benar-benar seperti puri Drakula. Di
kedua ujungnya ada dua menara batu yang tinggi. "Kalau kau nakal,
kau dikurung di menara," seruku dengan suara diseram-seramkan.
Orangtuaku tidak mengacuhkan.
Awan tampak kelabu. Beberapa tetes besar air hujan
membasahi kaca depan mobil kami. Jalan sempit ini membawa kami
ke pekarangan yang gelap. Guntur membahana di atas menara gelap
itu. Suasananya benar-benar seperti di film horor.
"Kenapa sih sekolah ini dibangun di atas bukit begini?"
tanyaku. "Jauhnya minta ampun dari kota terdekat
"Mungkin karena pemandangannya bagus," sahut Dad.
Bercanda.
"Mungkin juga karena mereka butuh privasi," kata Mom.
Tak lama kemudian kami sudah berada di dalam gedung
sekolah itu. Ternyata di dalam terang benderang dan suasananya ceria.
Tembok-temboknya berwarna kuning hangat, dihiasi poster warna-
warni. Setiap pintu di lorong panjang ini diberi warna cat berbeda.
Seorang lelaki besar berbahu kekar dengan rambut kelabu tebal
dan kacamata berbingkai hitam datang bergegas di lorong yang ramai
itu untuk memperkenalkan diri. "Aku Mr. Klane, Wali Murid,"
katanya dengan suara berat. "Mari kubantu membawa koper-koper
itu."
Di balik sweater putihnya orang ini tampak berotot dan berdada
bidang. Seperti Superman. Ia mengangkat koperku yang berat dengan
satu tangan dan mengantar kami ke kamarku.
"Kamar-kamar ada di sayap ini," ia menjelaskan, "Ruang-ruang
kelas ada di ujung lain." Suaranya yang berat menggema di lorong
panjang itu. Ia mendekatkan tubuh padaku. "Ruang penyiksaan ada di
bawah," bisiknya.
Aku melongo.
Ia tertawa tergelak-gelak. "Hati-hati, Paul," ia mengingatkan.
"Teman-temanmu semuanya cerdas. Dan mereka senang sekali
mempermainkan anak baru."
Sambil berjalan, kuperhatikan anak-anak di sini. Semuanya
kelihatannya normal-normal saja. Pakai jeans dan T-shirt, sweater dan
pullover, dan rompi-rompi tanpa kancing. Tidak berbeda dengan anak-
anak di sekolahku yang lama.
Memangnya kaupikir mereka seperti apa, Paul? tanyaku pada
diri sendiri. Kaukira anak-anak di sini semuanya pakai kaus
bergambar Beethoven dan suka membaca ensiklopedi sambil jalan?
Kami belok ke sebuah lorong lain yang juga panjang. Mom dan
Dad mengikuti di belakang, membawakan perlengkapanku. Kami
melewati pintu bertuliskan KEPALA SEKOLAH CARING
ACADEMY. "Nanti kau akan bertemu dengan Kepala Sekolah," kata
Mr. Klane.
Anak-anak bergegas menyingkir memberi jalan. Mr. Klane
membawa koperku yang besar seperti membawa kotak makan siang
saja.
Seorang anak bertubuh pendek gempal dan agak aneh
menyingkir ketika kami lewat. Wajahnya bundar dan pucat, dengan
mata hitam yang kecil serta rambut hitam licin yang dibelah tengah. Ia
seperti tikus mondok. Itu lho, binatang gendut yang warnanya merah
muda dan hidup di bawah tanah.
"Kau sedang apa di sini, Marv?" bentak Mr. Klane padanya.
Sebelum anak itu sempat menjawab, Mr. Klane sudah mendorongnya.
"Pergi sana! Kau kan tahu, kau tidak boleh berada di sini."
Anak itu menggumamkan sesuatu, lalu menjauh. Cara
berjalannya aneh, agak diseret-seret. Bentuk anak ini seperti bola
boling berkaki.
Mr. Klane mengawasinya sampai ia menghilang di belokan, lalu
kami melanjutkan perjalanan. "Apa minat utamamu, Paul?" tanyanya.
"Hah? Minat apa?" Aku berusaha menyamai langkahnya.
"Minat utamamu dalam pelajaran," kata Mr. Klane.
"Makan siang?" gurauku.
Kulihat Mom dan Dad merengut sambil geleng-geleng kepala.
"Paul belum menemukan hasrat hatinya," kata Mom pada Mr. Klane.
Hasrat hati? Bleeh! Aku ingin muntah.
Mr. Klane mengangguk. "Murid-murid di sini sangat berbakat,
Paul," katanya. "Mereka hebat. Sayangnya, mereka semua belajar
terlalu keras."
Hebat, pikirku sinis. Tempat ini benar-benar cocok buatku.
Memang aku sial, atau aku memang sial?
"Ini kamarmu," kata Mr. Klane sambil membuka sebuah pintu
biru. Kami masuk. Kamar itu cerah, dengan dua tempat tidur, dua
lemari pakaian, dua meja, dan sebuah sofa kecil berwarna merah.
"Kau sekamar dengan Brad Caperton. Dia anak baik," kata Mr.
Klane. Ia menaruh koperku di ranjang yang kosong. "Brad sedang
latihan biola. Kalau sudah selesai, dia akan kemari."
"Kamar yang bagus," kata Mom sambil mengelilinginya. "Dan
kau punya teman sekamar, Paul. Asyik, kan?"
Aku menggeleng. "Aku pernah coba main harmonika, tapi
harmonikanya tertelan olehku."
Di luar jendela yang sempit, guntur menggelegar. Suaranya
mengguncangkan ruangan ini.
Mom dan Dad membongkar isi koperku. Mr. Klane
mengamatiku dari balik kacamatanya yang tebal dan berbingkai
hitam. "Tidak mudah masuk sekolah pada bulan November," katanya.
"Tapi kau pasti bisa mengikuti. Kalau kau belajar rajin."
"Paul memang ingin rajin belajar," kata Dad sambil
memandangiku dengan tegas.
"Aku mesti ke kantor sekarang," kata Mr. Klane sambil melihat
arlojinya. Ia berjabat tangan dengan Mom dan Dad. "Senang
berkenalan dengan Anda."
Ia berbalik ke arahku di ambang pintu. "Akan kusuruh dua
orang anak mengantarmu ke kelasmu. Semoga sukses, Paul." Lalu ia
pergi.ebukulawas.blogspot.com
Guntur kembali mengguncangkan ruangan ini. Lampu-lampu
berkeredap, tapi tidak mati.
Setengah jam berlalu. Selesai membongkar isi koper-koper,
kami saling mengucapkan selamat tinggal dan berpelukan.
Lalu Mom dan Dad pergi. Aku ditinggal di puri gelap di atas
bukit ini. Terperangkap di sebuah sekolah dengan anak-anak serius
yang rajin belajar.
Mendadak aku teringat Harold. Kakaktuaku yang malang,
sendirian di rumah tanpa ada yang mengajari mengucapkan kalimat-
kalimat lucu.
"Jangan bikin PR. Gurunya bloon!" Kucoba menirukan suara
Harold. Ternyata mirip sekali.
Kudengar suara tawa cekikikan. Aku menoleh dan melihat dua
cewek di ambang pintu.
"Aku... sedang meniru suara kakaktua," kataku. Wajahku merah
padam.
"Aku Celeste Majors," kata salah satu cewek itu. Ia bertubuh
pendek, dengan rambut ikal pirang dan wajah berbintik-bintik. Mata
hijaunya berbinar-binar di balik kacamata berbingkai kawat.
Celeste penggemar warna ungu. Sweater ungu, jeans ungu,
sepatu ungu.
Cewek satunya bernama Molly Bagby. Ia jangkung dan sangat
kurus, dengan rambut hitam lurus dan poni menutupi mata.
Molly juga mengenakan jeans—warna hitam, dengan kedua
lutut berlubang—dan sweatshirt merah dengan rompi kulit hitam. Di
satu telinganya menggantung tiga anting kecil dari perak.
"Mr. Klane meminta kami menunjukkan kelasmu," kata Molly.
"Kau siap?"
Aku mengangguk.
Dan hendak beranjak ke pintu.
Tapi kedua cewek itu bergegas masuk sambil menutup pintu
dengan keras.
Celeste menoleh ke belakangnya dengan tegang, lalu berpaling
ke Molly. "Ada yang melihat kita, tidak?"
"Ku... kurasa tidak," sahut Molly. "Dengar... Paul?"
Matanya menatapku tajam. "Kau mesti cepat-cepat," katanya
berbisik.
"Hah? Cepat-cepat?" Aku melongo memandang mereka.
Kenapa mereka kelihatannya begitu ketakutan?
"Dengarkan kami," bisik Celeste sambil menoleh lagi ke pintu.
"Pergilah dari sini."
"Apa?" tanyaku.
"Jangan tanya-tanya," kata Molly dengan mulut dirapatkan.
Dagunya gemetar. "Pokoknya pergilah dari sekolah ini, Paul. Selagi
masih bisa."
3
CELESTE mencengkeram lenganku dan mendorongku ke
pintu. "Mungkin orangtuamu belum pergi. Mungkin kau masih bisa
menyusul mereka."
"Tapi... tapi..." Aku tergagap-gagap.
"Cepat!" seru Molly.
Aku membuka pintu... dan bertumbukan dengan Mr. Klane.
Aku mundur, rasanya seperti tertabrak truk.
"Kalian masih di sini?" tanyanya pada Molly dan Celeste. "Ada
masalah?"
"Tidak, tidak ada masalah," sahut Celeste cepat-cepat sambil
menarik-narik lengan sweater-nya. "Kami cuma sedang menunjukkan
pada Paul..."
"Ya, menunjukkan letak tempat-tempat," sela Molly. "Ruang
olahraga, ruang makan siang."
"Bagus." Mr. Klane tersenyum padaku. "Tapi Paul tidak boleh
terlambat masuk kelas. Mrs.. Maaargh tidak akan suka."
Mrs. ... siapa?
Mr. Klane membuka pintu lebar-lebar. Kedua cewek itu
memimpin jalan ke lorong. Mr. Klane mengikuti sambil bersiul-siul
sendiri.
Kedua cewek itu tidak berbicara lagi sepanjang jalan.
Kami melewati jalan masuk depan, lalu masuk ke lorong tempat
ruang-ruang kelas berada. Anak-anak dengan ransel di punggung
bergegas masuk ke ruangan-ruangan di situ.
Mendadak aku tertawa. Aku baru menyadari apa yang
dilakukan Molly dan Celeste padaku tadi. Rupanya begitulah cara
mereka memberi ucapan selamat datang pada anak baru.
Mr. Klane sudah mengingatkanku untuk waspada. Katanya
anak-anak di sini senang mempermainkan anak baru.
Wow, aku benar-benar tertipu, pikirku. Tadi aku sempat
ketakutan.
Kulihat kedua cewek itu memandangiku sementara kami
berjalan. Mereka rupanya heran, kenapa aku tertawa. Aku diam saja.
Aku tidak sebodoh tampaknya, pikirku.
Kami masuk ke sebuah ruang kelas. Ruang 333. Mulanya
kukira kami terlambat. Kupikir pelajaran sudah dimulai, sebab
ruangan itu sunyi sekali.
Tapi tidak ada guru di depan kelas.
Beberapa anak asyik membaca buku. Dua anak sedang
mengetik dengan giat di komputer. Beberapa sedang menulis di buku
catatan.
Aku mengikuti Molly dan Celeste masuk. "Mrs. Maaargh
sebentar lagi datang," bisik Celeste sambil menyibakkan rambut
pirangnya yang ikal. "Jangan sampai kau membuat dia marah."
"Hati-hatilah...," Molly memperingatkan.
Tapi ucapannya terhenti oleh kehadiran seorang anak lelaki
berambut cokelat kaku seperti paku. Anak itu berjalan ke belakangnya
dan sengaja menabrakkan diri dengan bergurau. "Hentikan, Brad,"
bentak Molly.
"Hei, gimana?" tanya Brad padaku. "Aku teman sekamarmu.
Kau sudah lihat ruangan kita?"
"Yeah. Sudah," sahutku. "Tapi ruangannya terlalu sempit untuk
barang-barangku, jadi sebagian barangmu kulemparkan ke lorong."
Sejenak Brad melongo. Ketika tahu aku cuma bercanda, ia
tertawa. Molly dan Celeste tidak ikut tertawa. Mereka masih saja
menatap tegang ke pintu kelas.
"Sebaiknya kita duduk," bisik Molly. "Mrs. Maaargh senang
kalau kita duduk rapi di kursi masing-masing."
Aku menoleh... dan terkejut ketika melihat sepasang kaki
menjulur dari langit-langit. Aku menengadah dan melihat seorang
anak tergantung dengan tali.
Eh... bukan.
Bukan anak sungguhan.
Hanya boneka. Aku cepat-cepat menoleh, berharap Brad dan
kedua cewek itu tidak mendengar desah kagetku. Aku sangat malu
karena bisa dibodohi.
Pada pinggang boneka itu tergantung tulisan: JANGAN LUPA
PERTUNJUKAN BAKAT HARI JUMAT TANGGAL 18
NOVEMBER.
Brad melihatku memandangi boneka itu. "Apa bakatmu, Paul?"
tanyanya.
"Bakat? Eh... rasanya aku tidak punya," kataku mengakui.
Ketiga anak itu memandangiku. "Tidak punya bakat?" seru
Molly sambil menyibakkan poninya yang hitam. "Kau tidak mungkin
masuk ke sekolah ini tanpa bakat khusus."
Aku mesti bilang apa, ya? Aku tidak mau mengatakan bahwa
aku masuk ke sini karena pengaruh orangtuaku. "Apa bakatmu?"
tanyaku pada Molly, untuk mengalihkan perhatian mereka.
Molly mengernyit. "Aku punya masalah sedikit. Aku main
biola, begitu juga Brad."
"Kok itu kausebut masalah?" tanyaku.
Molly mengangguk. "Kata Mrs. Maaargh, hanya boleh ada satu
pemain biola dalam pertunjukan itu. Brad dan aku mesti bersaing.
Pemenangnya akan tampil dalam pertunjukan. Yang kalah mesti
menampilkan pertunjukan lain."
"Jangan khawatir," kata Brad pada Molly. "Kau kan jauh lebih
hebat daripada aku. Kau bisa menang dengan mudah."
Molly berseru pelan. "Coba kita bisa sama-sama menang, Brad.
Aku... aku takut sekali."
"Hei, ini kan cuma pertunjukan," aku menyela. "Iya kan?"
Tidak ada yang menyahut. Semua anak tekun membaca.
"Aku menyanyi," kata Celeste padaku. "Sejauh ini hanya ada
satu penyanyi, jadi aku aman. Kau tidak akan menyanyi, kan, Paul?"
"Tidak," kataku. "Kata ayahku, suaraku fals. Kenapa sih semua
orang cemas sekali tentang pertunjukan ini?"
Lagi-lagi tak ada yang menjawab. Ketiga anak itu menoleh ke
pintu. Belum ada guru yang datang.
"Kau mesti memutuskan akan menampilkan apa," kata Brad.
"Kalau tidak..." Ia tidak melanjutkan ucapannya.
Mereka cuma menakut-nakutiku, pikirku. Mereka sengaja
menggodaku.
"Aku punya bakat, kok!" seruku. "Aku bisa menari. Tarianku
hebat."
Aku mulai beraksi, menari dengan boneka yang tergantung dari
langit-langit itu. Aku menari dengan bersemangat sambil
bersenandung keras-keras.
Kukira seisi kelas akan tertawa. Kukira mereka akan berseru-
seru dan bertepuk tangan.
Di sekolahku yang lama, anak-anak pasti akan ribut bukan
main.
Tapi di sini tidak ada yang memperhatikanku. Mereka terus saja
membaca sambil menulis di buku.
Kupeluk boneka itu erat-erat dan kubawa berdansa tango.
Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berseru-seru. Brad,
Molly, dan Celeste melongo memandangiku dengan ekspresi
ketakutan.
Kenapa sih mereka ini? Ini kan lucu.
Aku berputar dengan gila-gilaan. "OOOPS!" Boneka itu
terlepas dari tanganku.
Aku meraihnya, dan terpeleset, lalu jatuh menimpa boneka itu.
Seisi kelas tetap bungkam.
Aku mengangkat kepala dan hendak bangkit dari atas boneka
itu.
Tapi aku berhenti karena di ambang pintu tampak sesosok
tubuh raksasa.
Mrs. Maaargh.
Aku ternganga memandanginya dalam posisi merangkak di
lantai. Ibu guru itu mengenakan gaun merah mengilat. Tubuhnya
begitu lebar, sampai-sampai memblokir cahaya dari lorong.
Ia menyipitkan mata cokelatnya yang berair padaku, lalu
menggeram, "Kau pasti Paul."
Sekarang semua anak memandangiku, termasuk anak-anak
yang tadi asyik mengetik di komputer.
Aku berdiri dari lantai. "Maaf," gumamku. Aku membungkuk
untuk mengambil boneka itu, tapi Mrs. Maaargh memberi isyarat
dengan tangannya yang besar agar aku membiarkan saja boneka itu di
lantai.
"Kemarilah, Paul." Suaranya serak, seperti ada kerikil di
kerongkongannya.
Aku ragu-ragu dan memandangi gaun merah cerahnya yang
memenuhi ambang pintu.
"Kemarilah, Paul," ulangnya. Matanya yang berair masih tetap
terarah padaku. Ia tidak mengerjap.
Wajahnya yang bundar sama sekali tanpa ekspresi.
"Kemarilah."
Aku melirik Molly dan Celeste. Wajah mereka tegang dan mata
mereka membelalak... ketakutan?
Kumasukkan kedua tanganku ke saku celana, lalu pelan-pelan
aku bergerak ke ambang pintu. "Aku cuma main-main dengan boneka
itu," kataku.
Mrs. Maaargh mengangguk. "Aku ingin mencobaimu," katanya
pelan.
Aku tertegun. Apa katanya?
"Kemarilah, Paul," ulangnya. "Aku ingin mencicipimu."
Kudengar Celeste terkesiap pelan di belakangku.
Tidak ada suara lain. Ruangan itu begitu sunyi, dan aku hanya
mendengar suara langkah kakiku di lantai kayu.
Aku mendekati Mrs. Maaargh dan tersenyum sangat manis.
"Hai," kataku.
Ia meraih lenganku dan menarik tanganku dari saku.
Lalu, sambil menggeram pelan, ia menundukkan kepala,
menjulurkan lidahnya yang gemuk basah dan berwarna merah muda,
seperti lidah sapi.
Dan ia menjilati lenganku, mulai dari pergelangan sampai ke
bahu.
4
KUDENGAR erangan muak dari anak-anak di belakangku, tapi
ketika aku menoleh, mereka semua menunduk, pura-pura tidak
melihat.
Iiihh!
Lenganku terasa geli, lengket, dan basah.
Mrs. Maaargh melepasku, lalu menyeringai. Tetes-tetes ludah
masih menempel di giginya.
"Enak." Rasanya itulah yang dikatakannya.
Aku ternganga kaget. Aku tak percaya. Benarkah tadi dia
menjilatiku?
Aku berdiri melongo.
Wanita itu benar-benar aneh. Kepalanya besar sekali. Rambut
cokelatnya yang tebal disanggul dan diberi pensil di puncaknya.
Ia balas menatapku dengan mata cokelatnya yang berair. Seperti
mata sapi. Kulitnya kuning pucat, seperti bulu anak ayam di
supermarket. Pipinya bergelambir dan bergoyang-goyang kalau ia
menyeringai. Seluruh wajahnya menggantung di atas bahunya, seperti
adonan kue yang masih mentah.
"Kau boleh duduk, Paul," katanya kemudian. "Duduklah di
dekat bagian belakang sana."
Aku senang sekali bisa menjauh darinya. Aku berjalan secepat
mungkin ke bagian belakang. "Kau melihat tidak? Dia menjilatku,"
bisikku pada Celeste ketika aku melewati kursinya.
Celeste pura-pura tidak mendengar. Ia mencengkeram
komputernya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih.
Ini cuma lelucon, pikirku.
Tak lama lagi kami semua akan tertawa ramai-ramai.
Tapi tak ada yang tersenyum.
Saat melangkah ke barisan belakang, kulihat serangkaian
kandang ditaruh di meja, dekat dinding. Di dalamnya ada seekor
kelinci putih, tupai kecil kelabu, guinea pig, dan seekor tikus putih.
Apa kelas ini tidak terlalu tua untuk mempelajari binatang-
binatang seperti itu? pikirku.
Dengan hati-hati aku melangkahi kaki seorang gadis berambut
merah, lalu duduk di depan seorang anak lelaki bertampang serius
yang sama sekali tidak mengangkat wajah dari bukunya.
Aku duduk dan meletakkan ranselku. Meja kayu ini sudah
retak-retak dan penuh goresan. Di salah satu sudutnya terukir dua
kata: TOLONG AKU.
Kugosok-gosokkan jariku di ukiran itu sambil memandang ke
depan kelas.
Mrs. Maaargh masih berdiri di ambang pintu. Ia belum
bergerak. Apa dia terlalu besar dan tidak bisa masuk? pikirku.
"Hari ini kita mulai dengan membahas PR tata bahasa,"
katanya. "Paul, kurasa salah seorang anak di sini akan bersedia
membantumu mengikuti pelajaran."
Sambil menggeram ia mendesak masuk melalui ambang pintu.
Gaun merahnya bergoyang-goyang ketika ia bergerak. Baru kali ini
aku melihat gaun sebesar tenda begitu.
Dagu Mrs. Maaargh bergerak-gerak, begitu juga sanggulnya
yang tinggi.
Saat ia berjalan ke mejanya terdengar suara SER SER.
Aku mencondongkan tubuh dan melongok ke bawah... dan
terperangah.
Mrs. Maaargh tidak mengenakan alas kaki.
Kakinya besar sekali. Besar dan gemuk, seperti bantal, dan
menimbulkan suara basah yang memuakkan di lantai kayu.
"Ohhhh!" Aku mengerang ketika melihat kakinya yang aneh.
Kakinya tidak berjari. Tidak berjari!
Yang ada adalah cakar-cakar hitam mengilap.
Aku merasa mual dan perutku bergolak.
Lalu suara ibu guru itu memecah kesunyian, "Kau memandangi
apa, Paul? Kau punya masalah?"
5
JANTUNGKU berdebar kencang. Aku menoleh ke Celeste, lalu
ke Molly. Apa mereka melihat kaki yang menjijikkan itu?
Kedua anak itu duduk sangat tegak dengan mata tertuju pada
wajah Mrs. Maaargh.
Aku melayangkan pandang, mencari-cari Brad, dan
menemukannya di barisan depan. Ia sedang mengetuk-ngetukkan
pensil di mejanya dengan santai, pura-pura tidak ada apa-apa.
Aku menoleh lagi ke Mrs. Maaargh. Kucoba tidak memandangi
kakinya, tapi tidak bisa.
"Apa yang kaupandangi?" Mrs. Maaargh bertanya lagi.
"Ha? Aku..." Keningku mulai berkeringat. "Aku.. tidak
memandangi apa-apa kok " Suaraku hanya berupa bisikan.
Mrs. Maaargh menggeleng-gelengkan kepalanya yang besar.
"Apa belum ada yang memberitahumu bahwa aku ini monster?"
Debar jantungku semakin kencang. "Ehm..."
Mrs. Maaargh beranjak ke sebuah tabel di depart kelas. Kakinya
menimbilkan bunyi basah di lantai, setiap kali a bergerak.
Ia mengambil sebuah tongkat penunjuk dan mengarahkannya ke
puncak tabel, ke kata-kata RANTAI MAKANAN.
"Ada yang bisa menjelaskan pada Paul tentang rantai
makanan?" tanyanya. Matanya yang besar bergerak memandang ke
seluruh ruangan. "Mary?"
Mary adalah gadis berambut merah di ujung barisanku. "Yang
besar memakan yang kecil," katanya takut-takut. "Maksudku, yang
kuat memakan yang lebih lemah."
Mrs. Maaargh mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke tabel itu
dengan tak sabar. "Kurang tepat," katanya. "Lebih tepat kalau
dikatakan bahwa spesies yang lebih tinggi memakan spesies yang
lebih rendah."
Brad mengangkat tangan. "Ikan-ikan kecil memakan plankton,"
katanya. "Ikan-ikan yang lebih besar memakan ikan-ikan kecil, dan
ikan-ikan yang lebih besar dimakan lagi oleh ikan-ikan yang paling
besar."
"Dan manusia memakan ikan yang paling besar," kata seorang
anak lelaki gemuk di dekat jendela.
"Dan monster memakan manusia," Mrs. Maaargh menggeram.
Wajahnya yang bergelambir bergoyang-goyang ketika ia membuka
mulutnya dan tertawa terbahak-bahak.
Tak ada yang ikut tertawa.
Aku memandangi tabel itu. Ada sekitar dua puluh sampai dua
puluh lima kartu putih disusun berurutan, masing-masing kartu ditulisi
nama setiap anak di kelas.
Apa ini semacam tabel prestasi? pikirku. Waktu di kelas dua
kami punya tabel semacam itu. Penilaian dilakukan dengan bintang
emas atau perak.
Agak kekanak-kanakan untuk anak kelas enam.
"Paul, kau tahu makhluk apa yang menjadi pemakan paling
bawah?" Mrs. Maaargh membuyarkan pikiranku dengan suaranya
yang serak.
Aku tercekat. "Eh... di danau atau lautan... pemakan paling
bawah adalah ikan yang berenang di dasar laut dan memakan
segalanya." Kuhapus keringat di keningku dengan punggung tangan.
"Benar." Mrs. Maaargh menyeringai. "Tidak enak berada di
dasar, bukan, anak-anak?"
Beberapa anak menggeleng, beberapa menggumam, "Tidak."
"Kalau kalian berada di dasar, kalian akan dimakan," kata Mrs.
Maaargh dengan bersemangat.
Kulihat Molly memegangi kepalanya, seperti sakit kepala. Di
sampingnya, Celeste menutupi mulutnya dengan dua tangan.
"Paul, di sekolah ini semua muridnya ingin berada di puncak,"
Mrs. Maaargh melanjutkan. Sambil bicara ia mengetuk-ngetukkan
tongkatnya pada tabel rantai makanan itu. "Dan di kelasku semua anak
berusaha keras untuk tetap berada di puncak."
Mrs. Maargh mencondongkan tubuh, dagunya bergoyang-
goyang, matanya yang berair tertuju padaku. "Karena apa, Paul?
Karena aku adalah pemakan yang paling bawah. Benar! Setelah
pertunjukan bakat berakhir, aku akan memeriksa rantai makanan ini.
Akan kulihat siapa yang berada paling bawah. Lain aku akan berpesta
pora memakannya."
Seluruh tubuhnya bergoyang ketika ia tertawa terbahak-bahak.
Ia terus tertawa sambil memukul-mukul lututnya, hingga gaunnya
berguncang-guncang seperti tenda penuh bola.
Aku ikut tertawa. Aku merasa semua ini lucu sekali.
Gurauannya benar-benar keterlaluan. Tapi sangat lucu. Anak
baru pasti ketakutan kalau tidak menyadari bahwa semua ini hanya
gurauan.
Tapi aku sendiri senang melucu. Ingat? Dan aku tidak bisa
dibohongi. Aku tahu apa yang terjadi.
"Bagus sekali!" seruku. "Lucu sekali! Aku tidak tahan nih!
Aduuh, aku tidak tahan!"
Mrs. Maaargh berhenti tertawa dan wajahnya berubah marah.
"Apa yang lucu?" ia menggeram.
"Semuanya," sahutku. "Maksudku, tabel itu dan semuanya."
"Apa ada lelucon yang tidak kupahami di sini?" tanya Mrs.
Maaargh sambil memandangi seisi kelas. "Coba, ada yang bisa
memberitahukan leluconnya padaku? Aku suka lelucon. Apa yang
lucu?"
Hening. Anak gemuk di sampingku terbatuk. Tidak ada yang
bersuara.
"Apa kau menertawakan aku, Paul?" tanya Mrs. Maaargh. "Apa
ada sesuatu yang lucu pada diriku?"
"Tidak!" seruku. "Tapi rantai makanan itu..."
"Ya? Kenapa rantai makanan itu?" Ia mengetukkan tongkatnya
begitu keras ke tabel itu, hingga tongkat itu patah. Ia melambaikan
patahannya padaku.
"Berenanglah secepat mungkin, Paul," geramnya. "Sebab
sesudah pertunjukan bakat tanggal delapan belas nanti, aku akan
melihat siapa yang berada paling bawah pada rantai makanan itu. Dan
aku akan memakannya, siapa pun dia."
"Bagus!" seruku sambil tertawa. "Nanti aku yang bawa saus
kecapnya."
Tidak ada yang tertawa. Kenapa sih anak-anak ini? Kan
ucapanku lucu.
Iya kan?
Celeste menempelkan satu jari di bibirnya dan memberi isyarat
agar aku tutup mulut.
Tapi aku tidak mau tertipu. Tidak usyah ya!
"Bisa kita makan buah sebagai hidangan penutup?" tanyaku.
Lagi-lagi tak ada yang tertawa. Tersenyum pun tidak.
Anak-anak ini benar-benar pintar pura-pura.
Mrs. Maaargh membungkuk di mejanya. Kulihat ia menuliskan
sesuatu. Tak lama kemudian, ia mengangkatnya. Sebuah kartu putih
bertuliskan namaku. PAUL PEREZ.
"Di balik kartu ini ada selotipnya, sehingga aku bisa mencabut
dan menempelkannya," katanya padaku. "Namamu kupasang di
puncak rantai makanan, Paul, sebab kau anak baru."
Dengan gerakan cepat ia memindahkan kartukartu lainnya agar
bisa memasang kartuku.
"Ini tidak adil," protes seorang gadis kurus dan pucat di dekat
pintu. "Aku sudah belajar keras supaya tetap di puncak. Kenapa
sekarang dia mengambil tempatku?"
"Tak usah cemas, Sharon," sahut Mrs. Maaargh. "Kurasa dia
tidak akan bertahan lama di tempat itu."
"Taruh dia di tempat paling bawah," teriak anak gemuk di
barisanku.
"Ya, taruh dia paling bawah. Paling bawah," beberapa anak
mulai berseru.
Wow, pikirku, mereka terlalu serius menanggapi lelucon ini.
Kenapa sih tidak disudahi saja? Sebab sekarang sudah tidak lucu lagi.
"Oke, anak-anak!" Mrs. Maaargh menepukkan tangannya satu
kali. Kedengarannya seperti bunyi kakinya di lantai. "Saat bersenang-
senang sudah usai. Sekarang saat belajar."
Aku menggeleng. Saat bersenang-senang?
Menakut-nakuti anak baru dianggapnya bersenang-senang?
"Seperti kataku, hari ini kita mulai dengan PR tata bahasa," kata
Mrs. Maaargh.
Ia berbalik ke papan tulis dan menuliskan: MAUKAH KAU
DATANG KE RUMAHKU? AKU AKAN SENANG SEKALI
MEMAKANMU!
"Siapa yang mau maju ke depan?" tanyanya.
Semua anak mengacungkan tangan. Wow! Malah ada yang
mengangkat dua tangan.
"Aku saja."
"Aku saja!"
Dasar penjilat semua!
"Paul, silakan maju ke depan," geram Mrs. Maaargh. "Kita
lihat, apa kau bisa membedakan antara subjek dan predikat."
Kenapa dia tidak memilih anak lain saja? Kan mereka ingin
maju semua. Kenapa mesti aku?
Aku ragu-ragu.
"Cepat!" Ia menghantam papan tulis dengan kepalannya yang
kekar. Bekas kepalannya meninggalkan noda bundar dan basah.
Pelan-pelan aku bangkit dan mulai maju ke depan.
Aku merasa semua mata memandangiku. Celeste
mengacungkan ibu jarinya yang dibalik ke bawah ketika aku melewati
mejanya.
"Kalau dia gagal, aku saja yang maju!" seru Brad.
"Baik" sekali teman sekamarku itu.
"Tidak, aku saja."
"Tidak, aku!"
Kenapa sih mereka ini? Rupanya anak-anak ini suka sekali
bersaing.
"Ini." Mrs. Maaargh memberiku sepotong kapur.
Aku maju selangkah lagi... dan mendengar bunyi BUSSSH.
Kakiku menginjak sesuatu yang lunak.
Aku tercekat dan memandang ke bawah. Dan berteriak,
"Tidaaaak! Oh, tidak!"
6
"OWWWW!" Mrs. Maaargh melolong kesakitan.
Rupanya aku menginjak kakinya.
Sepatuku melesak dalam ke dagingnya yang lunak. Aku harus
susah payah menarik kakiku kembali.
Aku terhuyung mundur dan akhirnya menabrak papan tulis.
Mrs. Maaargh mengempaskan tubuh ke kursinya dan
membungkuk untuk memeriksa kakinya. Sambil mengerang pelan ia
meraba kulitnya yang basah.
"Ma... maaf," kataku tergeragap. "Aku tidak sengaja. Sungguh.
Aku memang canggung."
Mrs. Maaaargh memandangiku dengan mata cokelatnya yang
berair. "Baru awalnya saja kau sudah payah," katanya. "Ingat
peringatanku tadi. Berenanglah secepat kau bisa."
Ia kembali menggosok-gosok kakinya, lalu mengambil sesuatu
dari lantai. "Owww, bisa berminggu-minggu untuk ini tumbuh lagi."
Aku terpekik ngeri ketika melihat apa yang dipegangnya.
Sepotong cakar hitam berkilat.
Ia mengamatinya di antara jemarinya.
Aku memandang kakinya. Empat cakar panjang tampak olehku.
Cakar kelima, yang tadi terinjak olehku, sekarang tinggal sepotong.
Dengan satu gerakan Mrs. Maaargh memotes sisa cakar itu,
memasukkannya ke mulut, dan... memakannya.
Aku terkesiap.
Mrs. Maaargh berdiri.
Ia terpincang-pincang melewatiku, menuju tabel rantai
makanan, dan menurunkan namaku dua baris.
Lalu ia kembali ke kursinya. Tapi, sebelum duduk, ia meremas
lenganku.
"Makan yang banyak, Paul," katanya. "Aku ingin kau cepat
gemuk, oke?"
**************
Ketika bel makan siang berbunyi, aku cepat-cepat keluar. Tapi
kulihat banyak anak berbaris di depan Mrs. Maaargh.
"Kelasnya asyik sekali tadi," kata si gadis berambut merah.
"Kelas ini yang terbaik," kata seorang gadis lain.
Mrs. Maaargh tersenyum lebar. Kelihatannya ia sangat senang.
Bleeeh! pikirku. Anak-anak ini bukan sekadar penjilat. Mereka
benar-benar memuakkan. Apa mereka begitu kepingin mendapat A,
sampai mesti menjilat-jilat begitu?
"Menurutku anak baru itu mestinya ditempatkan paling bawah,"
kudengar seorang gadis berkata.
"Ya, taruh dia paling bawah," seorang gadis lain menimpali.
Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Gurauan mereka tidak lucu
lagi, dan aku akan mengatakan ini pada Mrs. Maaargh sesudah makan
siang.
Di mana ruang makan siang? Aku benci hari-hari pertama di
sekolah baru. Semua mesti serba ditunjukkan.
Untung aku melihat Molly dan Celeste. Cepat-cepat aku
mendekati mereka.
"Tidak senang ya, tadi?" kata Celeste sambil menggelengkan
kepala.
"Memang," kataku. "Mrs. Maaargh aneh sekali. Menurutmu..."
"Kenapa justru kau yang mengeluh?" ratap Molly. "Apa kau
tidak lihat posisiku di rantai makanan tadi? Kedua dari bawah. Kalau
hari Minggu nanti permainan biolaku payah, habislah aku. Aku bakal
jadi makanan monster itu."
"Stop! Stop!" teriakku. "Bisa dihentikan tidak? Lelucon kalian
tidak lucu lagi."
"Lelucon?" Molly memiringkan kepala dan menatapku.
"Lelucon apa? Paul, kalau kaupikir dia cuma bercanda..."
Aku tidak mendengar sisa kalimatnya, sebab serombongan anak
lelaki melewati lorong sambil tertawa-tawa, sehingga ucapan Molly
tidak kedengaran.
Antrean anak yang hendak makan siang panjang sekali.
"Makanannya pasti enak," kataku. "Apa ada Kejutan Daging Misterius
di sini? Itu makanan kesukaanku."
Setelah mendapatkan jatah, kami tidak bisa duduk bertiga,
karena tidak ada meja dengan tiga kursi. Maka Molly dan Celeste
duduk berdua. Aku mencari tempat lain.
Aku melayangkan pandang di ruangan luas itu yang berisik itu
dan akhirnya menemukan tempat kosong di ujung.
"Hai," sapaku pada seorang anak gemuk berambut hitam licin
yang duduk di hadapanku. Ia sedang asyik menikmati makanannya,
wajahnya yang bundar hampir terbenam di piringnya.
Rasanya aku pernah melihat anak ini.
"Hei," sahutnya dengan mulut penuh spageti, matanya tetap
pada makanannya.
Aku menggigit sandwich-ku. "Namaku Paul," kataku padanya.
"Marv," gumamnya sambil mengangkat wajah dari
makanannya. Sepasang matanya hitam dan kecil dan hidungnya
bengkok.
Marv? Ini kan anak yang disuruh pergi oleh Mr. Klane kemarin,
ketika aku baru datang.
Marv dan aku makan bersama tanpa bicara selama beberapa
saat.
"Aku anak baru. Ini hari pertamaku di sini," kataku, mencoba
membuat percakapan.
Marv menyipitkan mata ke arahku. Kedua pipinya berlepotan
saus spageti. "Kau yakin mau duduk di sini?" tanyanya.
"Yeah," kataku. "Kenapa tidak?"
Ia angkat bahu. "Siapa gurumu?" Ia meminum susunya dengan
berisik.
"Mrs. Maaargh," kataku. "Dia benar-benar aneh." Aku
memelankan suara. "Dia bilang dia itu monster."
"Yang benar nih!" Marv tampak tak percaya.
"Dia pernah mengajar di kelasmu tidak?" tanyaku.
"Tidak." Marv mengambil sepotong bakso dan memasukkannya
ke mulutnya, menelannya tanpa dikunyah dulu. "Aku masuk kelas Mr.
Thomerson."
"Kau beruntung sekali!" seruku. "Mrs. Maaargh tidak pakai
sepatu, dan kakinya seram sekali."
Marv mengangguk.
"Kakinya menjijikkan," aku melanjutkan. "Kelihatannya seperti
balon isi air. Dan ada cakar-cakar hitam melengkung di ujungnya."
Kulihat Celeste melambai-lambai padaku dari seberang
ruangan.
Mungkin di sana sudah ada tempat kosong. Aku hendak
beranjak.
Lalu aku berubah pikiran. Aku ingin bicara dengan Marv, siapa
tahu dia tahu sesuatu tentang Mrs. Maaargh.
"Entah mana yang lebih parah... kakinya atau tabel rantai
makanannya," kataku.
"Dua-duanya parah," kata Marv. "Benar-benar parah."
Celeste masih melambai-lambai padaku dari seberang ruangan.
Aku mengangguk padanya, supaya ia tahu aku sudah melihatnya, tapi
aku terus bicara pada Marv.
"Kau tahu kan tentang tabel rantai makanan itu?" tanyaku.
Marv mengangguk.
"Itu cuma lelucon kan?"
Marv menggeleng.
"Yang benar saja," erangku. "Masa dia benar-benar akan
memakan seseorang sesudah pertunjukan bakat usai?"
"Mungkin saja," kata Marv dengan mulut penuh spageti.
"O ya?" Aku memutar-mutar bola mataku. "Apa dia makan
seseorang di sini tahun lalu?"
"Tidak," kata Marv. "Tahun lalu dia tidak makan siapa-siapa."
"Sip," kataku cepat. "Sebab semua itu cuma lelucon konyol
kan?"
"Tahun lalu dia tidak makan siapa-siapa karena tahun ini tahun
pertamanya di sekolah ini," kata Marv.
"Oh."
Celeste mulai melompat-lompat dan terus melambai-lambai
padaku. Molly juga.
Kenapa sih mereka? pikirku.
Marv mulai bercerita tentang gurunya. Katanya Mr. Thomerson
baik sekali. Aku menggigit sandwich-ku lagi... dan merasa pakaianku
ditarik-tarik dari belakang.
Ternyata Celeste.
Ia meraih lenganku dan menarikku menjauh dari meja.
"Kau gimana sih, Paul?" tanyanya. "Kenapa kau duduk semeja
dengan anak Mrs. Maaargh?"
7
HAH? Aku duduk dengan anak Mrs. Maargh? Dan aku
mengatakan padanya bahwa ibunya adalah monster?
Bagus sekali, Paul.
Kau bisa mendapat urutan atas di rantai makanan!
"Astaga, gimana nih?" erangku.
Aku sebenarnya tidak terlalu peduli tentang tantai makanan itu.
Toh itu cuma lelucon konyol. Tapi aku kan berada di sekolah ini
karena di sekolah yang lama aku punya masalah dengan guruku. Aku
tidak boleh sampai mendapat masalah dengan guru ini. Orangtuaku
bisa mengamuk.
"Aku mengatakan pada anak Mrs. Maaargh bahwa ibunya jelek
dan aneh!" seruku.
"Jangan khawatir," kata Celeste pelan. "Aku yakin Marv tidak
akan mengadu pada ibunya."
"Menurutmu bagaimana?" tanyaku pada Molly.
"Menurutku Celeste pembohong besar."
"Maksudmu..."
Molly menyibakkan poninya. "Marv sangat dekat dengan
ibunya. Mungkin saat ini dia sedang mengadukan ucapanmu
"Lalu aku mesti bagaimana dong?" ratapku.
Celeste menggigit bibir, lalu menggelengkan kepala. "Kau
dalam kesulitan besar. Aku sudah mencoba memperingatkanmu."
Molly angkat bahu. "Mungkin dia cuma akan memindahkan
urutanmu ke bawah sedikit. Jangan khawatir. Kau tidak akan merosot
sejauh aku." Ia mendesah cemas.
"Begini saja deh... aku akan menemui Mrs. Maaargh sekarang
juga," kataku. "Aku akan minta maaf padanya, sebelum Marv sempat
mengadukan ucapanku."
"Kau yakin itu gagasan bagus?" tanya Celeste. "Bagaimana
kalau..."
Aku tidak menunggu ucapannya selesai. Aku sudah melesat ke
lorong.
Aku mesti cepat-cepat ke ruang kelas, sebelum Marv sempat
bicara pada ibunya.
Apa yang akan kukatakan?
Nanti juga terpikir. Yang jelas aku mesti minta maaf.
Aku berhenti di depan pintu ruang kelas.
Aku menarik napas panjang untuk memberanikan diri.
Lalu aku masuk ke ruangan itu. "Mrs. Maaargh!" panggilku.
Kulihat ia ada di belakang ruangan, di dekat kandang-kandang
binatang. Ia sedang membungkuk di atas salah satu kandang sambil
bersenandung sendiri.
"Mrs. Maaargh?" Aku maju lebih dekat.
Sepertinya ia tidak mendengar. Ia sedang menggumam pelan
dan bersenandung.
Aku melihat sebuah piring di atas kandang tikus. Di piring itu
ada beberapa potong biskuit. Di bawahnya si tikus memandangi
sambil menggerak-gerakkan hidungnya yang runcing.
Aku maju lebih dekat.
Sedang apa dia?
Sekarang aku bisa mendengar ucapannya. "Ini dia si pemakan
paling bawah," katanya. "Siapa yang ada paling bawah sekarang?"
Dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, ia sudah
menangkap tikus putih itu.
Ia mengangkatnya dengan dua tangan, lalu membuka mulut
lebar-lebar... dan menggigit kepala tikus itu.
Kejadiannya begitu cepat, sampai si tikus tidak sempat lagi
mencicit.
Aku terpaku ngeri. Mrs. Maaargh mengeluarkan kepala tikus itu
dari mulutnya dan menaruhnya ke atas biskuit di piring.
Lalu ia mengambil biskuit itu dari piring.
Dan melihatku!
"Ohhhh!" Aku mengerang dan mundur.
"Paul!" seru Mrs. Maaargh. Ia mengangkat biskuit dengan
kepala tikus di atasnya. "Paul... mau coba?"
8
DIA benar-benar monster!
Baru saat itulah aku yakin. Aku tak perlu bukti apa pun lagi.
Tapi masih ada yang kulihat.
Kulihat ia memasukkan biskuit itu ke mulutnya, mengunyahnya
dengan nikmat, dan menelannya.
Perutku bergolak. Rasanya aku ingin memuntahkan lagi makan
siangku tadi.
Kututupi mulutku dengan tangan, lalu aku berbalik dan lari.
Aku bertabrakan dengan Marv di ambang pintu dan anak itu
hampir terjatuh.
"Hei!" panggilnya.
Tapi aku terus lari di lorong, menerobos anak-anak lainnya.
Dia benar-benar monster. Akhirnya aku percaya.
Dia monster, dan dia akan memakan salah satu dari kami.
Dia monster, dan belum apa-apa dia sudah tidak suka padaku.
Aku pernah menginjak kakinya dan mematahkan cakarnya.
Aku mengatakan pada anaknya bahwa dia aneh dan jelek.
Sial. Aku benar-benar sial, pikirku sambil lari dengan panik di
lorong-lorong panjang itu. Sial... kecuali aku bisa keluar dari sini.
Mom dan Dad.
Wajah mereka terlintas dalam benakku.
Kalau tahu bahwa guruku adalah monster, mereka akan
langsung datang.
Tidak, belum tentu.
Mereka tidak akan percaya. Mereka akan mengira aku mulai
berulah lagi.
Mereka akan mengatakan akulah yang bandel. Mereka sudah
mengingatkan agar aku menyesuaikan diri di sekolah ini.
Tapi mana bisa aku menyesuaikan diri dengan monster yang
ingin memakanku seperti dia memakan tikus itu?
Aku harus meyakinkan orangtuaku. Mereka mesti
mengeluarkan aku dari sini.
Aku memelankan langkah. Jantungku berdebar kencang.
Mulutku mendadak sangat kering dan aku tak bisa menelan.
Aku mencari-cari telepon umum. Apa saja.
Kenapa anak-anak lain tidak ada yang minta tolong? pikirku.
Molly, Celeste, Brad, dan anak-anak lainnya tahu ini masalah
serius. Kedua cewek itu sudah berusaha memperingatkanku.
Tapi kenapa mereka tidak menelepon orangtua masing-masing?
Kenapa mereka tidak mencoba meloloskan diri?
Aku berbelok dan berjalan ke arah asrama. Tidak ada telepon di
sini. Di lorong juga tidak ada.
Akhirnya aku melihat sebuah telepon umum tersembunyi di
suatu sudut gelap di ujung lorong.
Dengan terengah-engah aku mengangkatnya dan menekan
angka nol.
"Halo? Halo?" teriakku panik. "Halo? Operator?"
9
"OPERATOR? Halo?" teriakku dengan nyaring.
Terdengar suara dari mesin penjawab, "Harap menutup telepon.
Para murid hanya diperbolehkan menelepon keluar pada hari-hari
libur."
"Hah? Hari libur?" Aku terkesiap. "Aku tidak akan hidup
sampai hari libur berikutnya."
Aku akan menjadi kalkun santapan Mrs. Maaargh untuk hari
Thanksgiving.
Aku menutup telepon, lalu mengangkatnya lagi dan mencoba
mengubungi rumahku. Tapi lagi-lagi mesin itu yang menjawab.
Kutinggalkan telepon itu tanpa meletakkannya lagi di
tempatnya.
Apa yang harus kulakukan? Kucoba melenyapkan rasa panik
yang mencekik tenggorokanku dan membuat lututku gemetar.
Aku mesti keluar dari sekolah ini. Kami semua mesti pergi dari
sini.
Dengan berdebar-debar aku lari kembali ke ruang makan untuk
mencari teman-temanku. Kulihat Molly, Celeste, dan Brad berjalan
bersama-sama sambil berbicara.
"Hei!" panggilku terengah-engah. "Kita mesti pergi. Kita mesti
keluar dari sini."
Celeste melihat arlojinya. "Waktu istirahat masih ada sepuluh
menit," katanya.
"Bagaimana reaksi Mrs. Maaargh?" tanya Molly.
"Dia benar-benar monster!" teriakku. "Dia benar-benar akan
memakan salah satu dari kita."
"Itu sih kami sudah tahu!" seru Celeste. "Kan kami sudah
memperingatkanmu, Paul."
"Tapi... tapi... kenapa kita masih berdiri di sini? Ayo kita pergi
dari tempat ini!"
Celeste mendesah. "Tidak bisa. Tidak mungkin."
Brad juga menggeleng. "Kami pernah mencoba, berkali-kali.
Tidak ada jalan keluar dari sekolah ini."
"Kami sudah mencoba berbagai cara," Molly menimpali.
"Segala cara. Begitu tahu bahwa Mrs. Maargh itu monster, kami
mencoba menelepon orangtua kami, tapi anak-anak..."
"Hanya dibolehkan menelepon pada hari-hari libur. Aku sudah
tahu," erangku. "Aku tadi juga berusaha menelepon."
"Kami pernah menulis surat ke rumah," kata Brad, "tapi kurasa
pihak sekolah membuang surat kami. Orangtua kami tidak pernah
membalas."
"Kami juga pernah mencoba memberitahu Mr. Klane dan guru-
guru lainnya, tapi mereka tidak percaya," kata Celeste. "Mereka pikir
kami mengada-ada, cuma karena Mrs. Maaargh tampaknya aneh."
"Kita mesti bertindak," aku memohon. "Kita tidak bisa duduk-
duduk diam saja. AYOLAH!"
Molly mendesah. Ia menyibakkan poninya yang menutupi mata.
Kelihatannya ia sangat ketakutan. Matanya berkaca-kaca. "Satu-
satunya yang bisa kita lakukan adalah berusaha agar tidak berada
paling bawah pada rantai makanan," katanya pelan.
"Kita mesti berlatih untuk pertunjukan bakat itu," Brad
menimpali. "Mrs. Maaargh akan mengadakan audisi hari Minggu
sore."
"Minggu?" Aku tercekat. "Tapi aku tidak punya bakat.
Maksudku, aku tidak tahu..."
"Kami semua membuat laporan agar mendapat nilai tambahan,"
kata Celeste. "Kau mesti segera membuat laporan, Paul. Yang bagus."
"Laporan?" seruku. "Laporan tentang apa?"
"Dan proyek sains," kata Brad. "Kami semua membuat proyek
sains untuk mendapat nilai ekstra."
"Tapi aku masih baru di sini!" protesku. "Aku tidak tahu mesti
bagaimana."
Molly menatapku lekat-lekat. "Kalau kau tidak punya bakat dan
kau tidak membuat proyek tambahan..." Ia tidak menyelesaikan
kalimatnya.
Kami semua tahu kelanjutannya. Ia ingin mengatakan bahwa
kalau aku tidak cepat bertindak, aku akan menjadi yang dimangsa.
Aku memandangi yang lainnya. Bagaimana mungkin aku
bersaing dengan mereka? Mereka semua hebat-hebat dan berbakat.
"Ini sinting," kataku. "Aku tidak terima. Tidak! Aku akan
menemui Kepala Sekolah. Dia mesti menolong kita. Dia mesti
percaya pada kita."
"Jangan, Paul! Tunggu!" Molly berseru ketakutan.
"Tunggu!" Brad dan Celeste juga memanggil.
Tapi aku tidak menunggu. Aku langsung pergi.
Aku pasti bisa meyakinkan Kepala Sekolah bahwa Mrs.
Maaargh adalah monster, pikirku sambil menerobos kerumunan anak-
anak yang terkejut. Aku pasti bisa meyakinkannya.
Akan kubawa Kepala Sekolah ke ruang kelas Mrs. Maaargh.
Akan kuperlihatkan padanya tabel rantai makanan itu dan kandang-
kandang binatang yang kosong. Akan kuminta ia mendengarkan
pernyataan Celeste, Molly, Brad, dan anak-anak lainnya.
Mereka akan mengatakan pada Kepala Sekolah bahwa Mrs.
Maaargh adalah monster, dan Kepala Sekolah pasti percaya kalau
mendengar kesaksian kami semua.
Aku terbang ke kantornya. Aku belum pernah bertemu Kepala
Sekolah, tapi aku tahu letak kantornya. Aku melewatinya ketika aku
datang tadi pagi.
Kulihat arlojiku. Sebentar lagi lonceng tanda pelajaran dimulai
berbunyi. Masa bodoh. Urusanku lebih penting.
Aku berusaha menyelamatkan hidup kami semua.
Aku berhenti di depan pintu bertuliskan KEPALA SEKOLAH
CARING ACADEMY. Pintu itu terkunci.
Masih terengah-engah aku mengetuk.
Tak lama kemudian terdengar suara, "Masuk."
Dia ada di dalam. Syukurlah!
Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. "Anda mesti
menolongku," kataku.
"Menolongmu? Menolong bagaimana?" Kepala Sekolah
mengangkat wajah dari mejanya.
Dan aku berteriak ketakutan.
10
"Di…di mana Kepala Sekolah?" tanyaku terbata-bata. "Aku...
eh... perlu menanyakan sesuatu."
Mrs. Maaargh berdiri di belakang mejanya. "Paul, akulah
kepala sekolahnya," katanya, dagunya bergoyang-goyang di bawah
wajahnya yang lembek. "Apa tidak ada yang memberitahumu?"
"Tidak!" Tanganku gemetar, jadi kumasukkan ke saku
celanaku.
"Itu sebabnya aku ada di sini," si monster melanjutkan.
"Sekolah ini membutuhkan kepala sekolah baru. Tapi aku juga senang
mengajar. Aku tidak tahan jauh-jauh dari para murid. Mengajar anak-
anak sangat... memberikan kepuasan."
Ia keluar dari balik meja. Kakinya yang telanjang menimbulkan
suara basah di karpet. Ia mulai mengitariku, mata cokelatnya
mengawasiku dengan lapar.
Perutnya berkeruyuk. Keras sekali, sampai aku terlompat.
Bunyinya seperti bathtub yang sedang dikosongkan.
"Aku... aku ingin menelepon orangtuaku," kataku.
Mrs. Maaargh menggeleng. Pipinya bergoyang-goyang. "Ini
bukan hari libur," katanya.
"Ini tidak adil!" sentakku. "Ini tidak... manusiawi!"
Senyumnya semakin lebar. "Aku memang bukan manusia,"
katanya. "Aku ini monster."
"Tapi... Anda tidak boleh makan anak-anak," teriakku.
"Aku cuma makan satu anak," sahutnya.
Ia mengangkat daguku dengan satu tangannya. Kulitnya terasa
licin dan lembap. Ia mendekatkan wajah ke wajahku. Napasnya
berbau apa ya? Bau tikus?
"Kau agak kurus," bisiknya. "Apa kau cukup makan selama
ini?"
"Aku... aku..."
"Jangan tegang begitu, Paul," ia memarahiku. "Nanti kau tidak
enak dimakan kalau terlalu tegang."
"Tidak!" teriakku. "Lepaskan!"
Aku mencoba mundur, tapi ia mencengkeram tenggorokanku
dan menyipitkan matanya yang kecil padaku.
"Kenapa kau begitu yakin akan menjadi makananku?"
tanyanya.
"Tidak...!" jeritku. "Tidak... bukan aku!"
Ia melepaskan cengkeramannya dan kembali tersenyum.
"Belajarlah yang rajin, Paul," katanya. "Berusahalah sebaik mungkin.
Mungkin prestasimu bisa mengejutkanku."
Aku membalikkan tubuh darinya dengan berdebar-debar dan
tubuh gemetar.
"Mungkin prestasimu bisa mengejutkanku," ulangnya. "Tapi
kurasa tidak," tambahnya.
Aku terhuyung-huyung ke pintu, membukanya, dan melesat ke
lorong.
Lonceng sudah berbunyi. Lorong panjang itu sunyi dan kosong.
Ke mana aku harus pergi? Apa yang mesti kulakukan?
Cuma satu yang bisa kulakukan. Aku mesti membuktikan
bahwa dugaannya salah. Aku tidak akan menjadi mangsanya.
Aku tidak bisa masuk kelas, pikirku. Aku akan ke kamarku saja,
diam di sana dan berpikir, mencoba membuat rencana.
Aku berlari-lari kecil, berbelok... dan bertumbukan dengan
Marv.
Kami sama-sama berseru kaget.
"Hei," katanya. Ia mengangkat sebuah kantong kertas kecil
berwarna cokelat dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. "Ini
untukmu," katanya.
Ia mengulurkan tangannya padaku. Kue. Sepotong kue cokelat
besar. "Kau mau?" Ia mendekatkan kue itu ke wajahku.
Dia bersekongkol dengan ibunya, pikirku.
Dia mencoba membuatku gemuk.
"Tidak!" teriakku. Kudorong dia dan aku lari.
Ternyata aku salah besar!
11
SABTU pagi, sesudah sarapan, aku mengikuti Molly, Celeste,
dan Brad ke ruang musik. Mereka akan berlatih untuk audisi
pertunjukan bakat hari Minggu besok.
"Si Marv itu benar-benar nyebelin," keluh Brad.
Aku baru saja menceritakan bahwa Marv berusaha
menggemukkanku agar enak dimakan ibunya. "Apa dia memberimu
kue cokelat juga?" tanyaku pada Brad.
Brad menggeleng sambil membuka kotak biolanya. "Tidak,
kemarin, waktu aku sedang latihan biola, dia masuk kemari, ingin
mencoba biolaku."
Molly sudah mengangkat biolanya ke bahunya, untuk
menyelaraskannya. "Lalu bagaimana reaksimu?" tanyanya pada Brad.
"Kauizinkan dia mencoba?"
"Tidak akan!" kata Brad. "Kusuruh dia keluar."
"Dia cuma kesepian," sela Celeste. "Dia tidak cocok berada di
sekolah ini. Mestinya kau lebih ramah padanya, Brad."
"Tidak usyah ya!" kata Brad sambil menyelaraskan biolanya.
"Brad benar," kata Molly. "Marv juga monster. Jangan lupa itu.
Dia sangat dekat dengan ibunya, dan sekarang dia ikut menakut-nakuti
Paul."
"Aku tidak takut padanya," gerutu Brad. "Kalau dia
menggangguku lagi, tahu rasa dia."
Molly mendesah. Ia menurunkan biolanya dan berkata pada
Brad, "Aku... aku takut sekali, Brad. Masa kita mesti bersaing?
Kenapa Mrs. Maaargh tidak mengizinkan kita sama-sama bermain
biola dalam pertunjukan itu?"
"Tidak usah dipikirkan," sahut Brad. "Aku yakin kau bisa
menampilkan pertunjukan lain setelah aku memenangkan audisi
besok."
Molly memandangi Brad dengan terkejut.
Brad minta maaf. "Sori, cuma bercanda. Wow, semuanya
tegang amat sih!"
"Tentu saja kami tegang!" seru Celeste. "Salah satu dari kita
akan dimakan!"
Aku merasa sesuatu bergerak di jendela pintu ruang musik. Aku
menoleh dan melihat Marv. Ia memandangi kami dengan mata
bulatnya yang hitam. Memandang tanpa berkedip.
Aku merinding.
Marv menjauh.
Ketika aku menoleh kembali pada teman-temanku, mereka
sedang memandangiku. "Kau sendiri bagaimana?" tanya Celeste.
"Ya, apa yang akan kautampilkan, Paul?" tanya Molly.
Aku angkat bahu. "Entahlah. Aku sudah memikirkannya
semalaman."
"Dan...?" desak Brad sambil menggaruk-garuk rambutnya.
"Ehm... mungkin aku akan menceritakan lelucon," kataku.
"Gagasan buruk," komentar Celeste. "Kalau leluconmu tidak
membuat penonton tertawa, kau akan langsung dipindahkan ke tempat
paling bawah pada rantai makanan."
"Yeah, terlalu riskan," Brad sependapat.
"Lalu aku mesti bagaimana?" teriakku. "Aku tidak bisa nyanyi
seperti kau, Celeste. Aku tidak bisa memainkan alat musik. Dan..."
"Aku punya ide," sela Molly. "Agak aneh, tapi pokoknya ide."
Kami semua memandanginya. Ia meletakkan biolanya di
pangkuan. "Membuat binatang dari balon," katanya.
Aku mengernyit. "Apa?"
"Aku baru ingat, ibuku memasukkan sekotak balon di koperku,"
kata Molly. "Kau pasti bisa berlatih membuat binatang-binatang lucu
dari balon itu, dan sambil membuatnya kau bisa menceritakan
lelucon."
"Bagus juga idenya," kata Brad. "Bisa lucu."
"Yeah, lebih baik daripada cuma berdiri menceritakan lelucon,"
tambah Celeste.
"Yah..." Aku ragu-ragu. "Oke, akan kucoba. Trims, Molly."
"Kau mesti minta izin dulu pada Mrs. Maaargh," kata Brad.
"Benar, dia mesti memberikan persetujuannya dulu," kata
Celeste.
"Pergilah minta izin," kata Molly sambil memasukkan biolanya
ke dalam kotak. "Biasanya dia ada di ruang kelas pada pagi hari
Sabtu." Ia menutup kotaknya, lalu lekas-lekas keluar dari ruang musik.
Aku agak enggan menemui Mrs. Maaargh lagi, tapi aku tak
punya pilihan. Aku menyusuri lorong panjang menuju ruang kelas.
Setelah menarik napas dalam-dalam, aku melangkah ke ruang
kelas yang gelap.
"Mrs. Maaargh?"
Aku melayangkan pandang. Tidak ada siapa-siapa. Lampu-
lampu mati, kerai-kerai ditutup.
Aku menyalakan lampu. "Ada orang di sini?"
Kulihat tabel rantai makanan itu ada di depan kelas.
"Wah!" seruku. Namaku sudah diturunkan, ketiga dari bawah,
persis di atas Molly dan seorang anak bernama Peter Clarke.
Kenapa aku dipindahkan begitu rendah? Karena aku menolak
tawaran kue cokelat dari Marv? Atau karena aku berusaha menelepon
ke luar?
Atau karena Mrs. Maaargh tidak menyukaiku?
"Kau tidak akan bisa memakanku," kataku keras-keras. "Tidak
akan kubiarkan."
Aku berbalik hendak keluar, tapi sesuatu di bagian belakang
ruangan menarik perhatianku.
Kandang kelinci.
Pintunya terbuka lebar.
Ke mana kelincinya?
Aku maju beberapa langkah... dan terhenti. "Ohhhh!" Aku
mengerang mual ketika melihat benda di lantai.
Mulanya kukira itu bola kapas.
Setelah kupandangi, tahulah aku.
Sepotong ekor putih.
Ekor kelinci.
Kelincinya sudah tidak ada.
Dimakan. ËBÜKÜLÄWÄS.BLÖGSPÖT.CÖM
Mrs. Maaargh mulai beraksi mendaki rantai makanan.
12
MRS. MAAARGH mengadakan audisi di ruang kelas, sebab
auditorium sedang digunakan oleh kelompok lain. "Aku yakin acara
ini menyenangkan untuk kita semua," katanya bersemangat.
Ia mengenakan gaun kuning cerah yang membuatnya tampak
lebih besar daripada matahari. Rambutnya disanggul seperti gunungan
lumpur.
Hanya Mrs. Maaargh yang tersenyum di ruangan ini. Para
murid duduk tegang, termasuk aku sendiri.
Tidak ada yang bicara atau tertawa. Banyak yang berdeham dan
mengetuk-ngetukkan jari ke meja dengan gugup.
"Aku akan memanggil kalian secara acak," kata si monster.
"Ingat, ini hanya audisi, bukan pertunjukan sebenarnya. Tapi
berusahalah sebaik mungkin, sebab aku akan menentukan posisi
kalian pada rantai makanan hari ini."
Ia menatap langsung padaku ketika bicara tentang rantai
makanan itu dan menjilat bibirnya dengan lapar.
Celeste yang pertama dipanggil. Ia menyetel kaset berisi musik
untuk latar belakang, dan menyanyikan My Favourite Things dari The
Sound of Music. Suaranya bagus sekali.
Mrs. Maargh memindahkan Celeste ke posisi kedua di rantai
makanan.
Peter Clarke, yang berada pada urutan paling bawah, maju
berikutnya. Ia memperdengarkan nada-nada dengan bunyi-bunyian
dari mulut dan dengan memukul-mukul kepalanya, memainkan The
Star Spangled Banner. Kedengarannya lumayan.
Mrs. Maaargh menaikkan posisinya empat baris. Berarti Molly
berada pada urutan paling bawah.
Semalam aku menanyakan pada Molly, kenapa posisinya pada
rantai makanan bisa begitu rendah. Waktu itu habis makan malam dan
aku sedang berlatih membuat binatang dari balon, sementara Molly
berlatih biola.
"Mrs. Maaargh memergoki aku waktu aku mencoba kabur,"
kata Molly. "Waktu itu dua hari setelah sekolah dimulai. Aku sangat
ketakutan. Aku memanjat ke luar jendela dan mencoba lari turun
bukit."
Molly mendesah. "Tapi Mrs. Maaargh memasang kamera video
di seluruh gedung ini. Dia berhasil menangkapku waktu aku baru
setengah turun. Keesokan harinya dia menurunkan posisiku ke tempat
paling bawah."
Molly menggeleng. "Sejak itu dia selalu mengawasiku," gumam
Molly. "Karena itulah aku mesti tampil sebaik mungkin dalam audisi.
Kalau tidak..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya.
"Dia juga mengawasiku," kataku. Kuangkat binatang buatanku.
"Kau suka pudel ini?"
Molly memandangi hasil karyaku. "Pudel? Tadi kukira itu
kuda."
***********
Sekarang aku menatap Molly yang sedang mengetuk-ngetukkan
jemarinya di lengan kursi dengan gelisah, menunggu Mrs. Maargh
memanggilnya.
Tapi monster itu justru memanggil si gadis berambut merah,
yang menampilkan dansa modern. Penampilannya boleh juga, tapi
kemudian kakinya kram dan ia terpaksa berhenti.
Mrs. Maaargh menggeleng-geleng, tapi tidak memindahkan
posisi gadis itu. Ia tetap pada posisi tengah di rantai makanan.
Gadis itu senang sekali.
Berikutnya Molly.
Molly membawakan sepotong karya Bach. Mulanya ia gugup,
malah tongkat penggeseknya jatuh ketika ia baru mulai.
Tapi setelah mulai, penampilannya bagus sekali. Poninya ikut
bergerak sementara ia bergoyang mengikuti musik. Setelah ia selesai,
seisi kelas bertepuk tangan.
Molly membungkuk sedikit, lalu kembali ke kursinya. Kulihat
ia gemetar dan dahinya berkeringat.
"Bagus sekali, Molly," kata Mrs. Maaargh. "Ada satu violis lagi
yang mesti kita dengar, lalu aku akan memutuskan siapa yang berhak
tampil pada pertunjukan bakat."
"Tapi... tapi... " Molly terbata-bata, "apa posisiku tidak
dinaikkan?" Ia menunjuk namanya yang berada paling bawah.
"Tidak, kurasa tidak," kata Mrs. Maaargh.
"Kenapa tidak?" tuntut Molly.
"Tidak ada alasan," sahut sang guru monster sambil
menyilangkan lengannya yang lembek di depan gaun kuningnya.
"Tapi itu tidak adil!" teriak Molly, suaranya bergetar.
"Memang tidak adil," bentak Mrs. Maaargh. "Aku kan monster.
Ingat?"
Beberapa anak menggumamkan protes, tapi sebagian besar
hanya menatap diam ke depan. Kami semua tahu Molly diperlakukan
tidak adil, tapi tidak ada yang berani mengambil risiko menggantikan
tempatnya.
Berikutnya Mrs. Maaargh memanggil Brad. "Kita lihat, siapa
yang lebih bagus," katanya sambil menggosok-gosokkan kedua
tangannya. "Aku senang persaingan. Bisa membangkitkan seleraku."
Ia tertawa. Hanya dia yang bisa...
Kumasukkan kedua tanganku ke saku supaya tidak gemetar.
Mendadak mulutku terasa sangat kering. Aku benar-benar ketakutan
sekarang. Kalau Mrs. Maaargh tidak mau bersikap adil, habislah aku.
Dia benci padaku.
Kulihat Molly masih tetap gemetar di mejanya. Ia menutupi
wajahnya dengan dua tangan.
Brad pergi ke ruang musik untuk mengambil biolanya. Kami
semua menunggu dalam diam. Celeste mengacungkan ibu jarinya
pada Molly, berusaha menghibur anak itu, tapi Molly tidak melihat,
karena ia masih menutupi wajahnya.
Brad kembali dengan membawa kotak biolanya dan lembaran
notasi musik. Tangannya gemetar ketika ia menaruh kertas itu di
penyangga. Ia terus berdeham dam menghapus keringat di dagunya.
Tampaknya ia sangat ketakutan.
Ia membuka kotak biolanya dengan satu sentakan.
Ia hendak mengambil biolanya... lalu gerakannya terhenti.
Ia mundur, mengerang keras.
"Tidak! Oh, tidaaak!" ratapnya.
13
"OHHHH!" Anak-anak di dekat Brad ikut bersuara dan
mengernyit jijik.
"Bau sekali," seru seorang anak.
"Ya, baunya gawat!" kata seorang gadis.
Brad terhuyung mundur sambil menutupi mulut dan hidungnya.
Ia terbelalak kaget dan terus memandangi kotak biolanya.
"Wow!" teriakku ketika bau yang memuakkan itu melayang ke
bagian belakang ruangan. Baunya sangat tajam dan menyengat. Aku
menahan napas, mencoba tidak menghirup bau itu.
Beberapa anak melompat bangkit dan pindah ke dekat jendela.
Anak gemuk dari barisanku membuka jendela dan menjulurkan kepala
ke luar.
"Aku tidak bisa napas!"
"Aduh, baunya..."
"Keluarkan! Keluarkan! Aku mau muntah nih!"
Erangan dan omelan memenuhi seisi kelas.
Brad mundur ke papan tulis dengan tangan menutupi wajah.
Aku masih menahan napas, berharap bau memualkan ini segera
hilang.
Sambil geleng-geleng kepala Mrs. Maaargh menghampiri kotak
biola itu. Dengan menggeram ia membungkuk dan mengambil biola
dari dalam kotak, lalu mendekatkannya ke wajahnya.
Ia mendengus-dengus beberapa kali. "Seperti bau sigung,"
katanya. Lalu ia menaruh biola itu lagi di kotaknya. "Aku keluar
sebentar."
Ia berjalan ke pintu, gaun kuningnya yang besar bergerak-gerak
seperti balon gas.
Seisi kelas berusaha menahan rasa mual. Beberapa anak
mencoba mencari udara segar di luar jendela.
Brad meringkuk di tembok, memandangi biolanya dengan sedih
sambil menggeleng-geleng.
Tak lama kemudian Mrs. Maaargh kembali dengan membawa
sebuah botol cokelat kecil. Ia berhenti di depan pintu dan mengangkat
botol itu.
"Ini cairan bau sigung," katanya. "Diambil dari lab di atas.
Cairan bau sigung murni. Kutemukan di ruang musik."
"Tapi siapa...?" Brad hendak bertanya, namun ia tak bisa
menahan mual. Ia memencet hidungnya dan mencoba lagi, "Tapi siapa
yang menuangkan cairan sigung ke kotak biolaku?"
Mrs. Maaargh angkat bahu. "Mana aku tahu?" sahutnya. Lalu ia
mengangkat botol cairan itu ke bibirnya, menengadah sedikit, dan
menghabiskan isi botol itu.
Anak-anak berseru jijik. Lebih banyak lagi yang pergi ke
jendela.
"Yep, ini memang cairan sigung," kata Mrs. Maaargh sambil
menjilat bibirnya.
Brad mundur sampai ia berdiri di dekatku di bagian belakang
ruangan. Ia masih terus berusaha menahan mual.
"Biolaku...," gumamnya. "Aku tidak bisa menggunakannya
lagi."
Mendadak Mrs. Maaargh tampak marah. Dengan ketakutan
kulihat ia menunjukkan jarinya... ke arahku.
"Kau yang bertanggung jawab atas semua ini!" geramnya.
14
"HAH? Aku?" Aku terkesiap.
Aku hendak berdiri, tapi lalu kusadari bahwa yang ditunjuk
Mrs. Maargh ternyata Brad.
"Kau bertanggung jawab atas peralatanmu sendiri," katanya
pada Brad.
"Tapi... tapi...," Brad mencoba memprotes.
"Molly yang akan memainkan biola pada pertunjukan besok,"
kata si monster sambil menyeringai pada Brad. "Kau mesti
menampilkan pertunjukan lain."
Ia beranjak ke arah tabel rantai makanan, mengambil kartu
nama Brad dari bagian atas dan memindahkannya ke tempat paling
bawah.
Molly terisak-isak. "Aku ikut sedih, Brad," gumamnya. "Aku
tidak mau menang dengan cara begini."
Brad terenyak ke meja tempat kandang-kandang berada. Molly
bergegas mendekatinya sambil menggeleng-geleng dan merangkul
bahunya. "Kau pasti selamat," bisiknya. "Kau bisa menampilkan
pertunjukan lain."
Brad tertunduk, tidak menjawab.
Seisi kelas tidak tahan lagi dengan bau itu. Mereka minta
diizinkan keluar.
"Masih banyak yang akan melakukan audisi," kata Mrs.
Maaargh. "Kembali ke tempat duduk masing-masing."
Ia mengambil kotak biola tadi dan menyodorkannya pada Brad.
"Keluarkan ini. Mungkin baunya akan hilang dari sini."
Sambil menutup hidung Brad mengambil kotak itu dan
bergegas keluar.
"Berikutnya Paul," kata Mrs. Maaargh. "Duduk semuanya!
Duduk!"
Astaga, pikirku. Kenapa aku sial begini? Ruangan ini masih
bau. Tidak akan ada yang bisa menikmati pertunjukanku.
Lalu kulihat Mrs. Maaargh tersenyum lebar, dan tahulah aku
bahwa ia sengaja memilihku untuk maju berikutnya.
Aku meraih kotak balonku dari kolong tempat duduk. Tidak
ada. Rasa panik menjalari tubuhku. Lalu aku ingat di mana aku
menaruh kotak itu.
"Balonnya ada di kamarku," kataku pada Mrs. Maaargh. "Boleh
aku mengambilnya?"
Ia cuma angkat bahu.
Kuanggap itu isyarat mengizinkan, jadi aku melesat keluar,
menghirup udara sambil lari ke kamarku. Asyik, udara segar!
Bau sigung itu menempel pada pakaian dan kulitku. Entah bisa
hilang atau tidak. Aku ingin mandi sebenarnya, tapi tentu saja tak
mungkin.
Sudah waktunya beraksi. Aku sudah berlatih hampir sepanjang
malam. Pertunjukanku akan lumayan lucu.
Mungkin—cuma mungkin, lho—aku bisa menjaga agar tidak
berada paling bawah pada rantai makanan. Kalau Mrs. Maaargh
bersikap fair.
Aku masuk ke kamarku. Kulihat kertas-kertas musik Brad
bertebaran di mejanya. Kasihan dia, pikirku. Mrs. Maaargh tidak adil
terhadapnya.
Siapa yang menuang cairan bau sigung ke biolanya? Siapa yang
sampai hati berbuat begitu?
Aku melayangkan pandang dan melihat kotak balon itu di
tempat tidurku.
Aneh, pikirku. Aku yakin menaruhnya di atas lemari.
Kuambil kotak itu, lalu bergegas keluar, kembali ke kelas.
Semakin lama aku semakin ketakutan.
Apa Mrs. Maaargh akan menyukai pertunjukanku? Akankah dia
menganggapnya lucu? Akankah dia bertindak adil dan memberiku
kesempatan?
Sambil menarik napas panjang aku masuk ke kelas.
15
KUAMBIL sebuah balon merah. "Aku akan membuat pemakan
semut," kataku.
Beberapa anak berdecak. Masih ada yang menutupi hidung dan
mulut. Bau sigung itu masih sangat terasa.
"Mungkin kelihatannya seperti pudel," kataku, "tapi percayalah,
ini pemakan semut."
Aku meniup balon merah itu.
Tidak mengembang.
Tidak ada apa-apa. Udaranya keluar begitu saja.
"Ha ha, pasti balon ini bocor," kataku. Kubuang balon itu.
"Cuma bercanda. Memang kusengaja, supaya kelihatannya susah."
Beberapa anak berdecak.
Aku melirik Mrs. Maaargh. Ia sudah duduk di belakang
mejanya, memandangiku dengan galak sambil bertopang dagu.
"Oke, ini dia pemakan semut dari balon," kataku. Kuangkat
sebuah balon biru panjang ke mulutku dan kutiup.
"Hah?"
Balon ini juga tidak mengembang.
Kucoba lagi, meniup terus sekuat tenaga. Pelan-pelan balon itu
mulai mengembang. Aku hendak mengikat ujungnya, tapi ternyata
balon itu kempes lagi.
Beberapa anak tertawa. Mereka pasti mengira ini juga
disengaja.
Tapi mendadak aku merasa panik.
Kulemparkan balon itu dan kuambil balon lain. "Ini dia si
pemakan semut." Suaraku bergetar dan tanganku gemetar, sehingga
hampir-hampir aku tak bisa mengangkat balon itu ke mulutku.
Aku menarik napas panjang, berusaha mengusir rasa panik.
Lalu mulai meniup.
Dan gagal.
Beberapa anak tertawa.
"Tidak! Hentikan!" teriakku nyaring. "Ada yang tidak beres.
Aku akan membuat binatang yang paling susah saja. Lobster."
Kuambil sebuah balon merah panjang dari kotak dan
kurentangkan di kedua tanganku. "Lobster dari balon... dengan capit,"
kataku.
Dahiku mulai berkeringat. Lampu di langit-langit rasanya
terang sekali. Seluruh ruangan ini seolah terjungkit naik.
Kuangkat balon itu ke mulutku dan mulai meniup.
Tidak ada apa-apa.
Kuperiksa balon itu. "Ada apa sih ini? Masa semua balon ini
bocor?" seruku. ebukulawas.blogspot.com
Kulihat sebuah lubang kecil di ujung balon itu.
Aku mengambil sejumlah balon lain dan memeriksanya satu per
satu. Semuanya berlubang di ujung.
"Semuanya berlubang!" teriakku. "Ada yang menusuk..."
Mrs. Maaargh bangkit berdiri dengan berat, sambil mendesah.
"Kurasa aku sudah cukup melihat," geramnya.
"Tapi, Mrs. Maaargh...!" aku memohon, "aku tidak bisa
menampilkan pertunjukanku. Ada yang melubangi balon-balonku."
Ia berdecak-decak, lalu beranjak ke tabel.
Dengan suara keras ia menarik kartu namaku, lalu
memindahkannya ke bawah kartu Brad, posisi paling bawah pada
rantai makanan.
Kemudian ia menoleh padaku sambil menjilat bibir. "Jangan
lupa makan kue banyak-banyak, Paul," katanya. "Aku ingin kau enak
dan manis saat kumakan nanti."
16
"INI pasti ulah Marv," kata Molly ketika kami kembali ke
kamar. Pertunjukan-pertunjukan lainnya berlangsung sukses. Seorang
anak lelaki bernama Frank berhasil menduduki posisi paling atas
setelah membawakan puisi dari Hamlet.
Pada akhir audisi, aku masih tetap pada posisi paling bawah,
sesudah Brad. Aku berjalan dengan lesu sepanjang lorong. Aku serasa
lumpuh oleh rasa takut.
Aku tahu aku akan tetap berada paling bawah. Aku tahu akulah
yang akan dimangsa.
"Marv? Kenapa kau beranggapan begitu?" Brad bertanya pelan.
"Aku melihat dia berkeliaran di sekitar ruang musik pagi tadi,"
sahut Molly. "Aku yakin dialah yang menaruhkan cairan bau sigung
itu pada biolamu."
"Tapi apa alasannya?" tanya Brad. "Karena aku tidak
mengizinkan dia mencoba biolaku?"
Molly mengangguk dan berpaling padaku. "Aku juga
melihatnya di lorong depan kamarmu," katanya. "Aku yakin dialah
yang melubangi balon-balonmu."
"Mungkin," sahutku pelan. Aku tidak ingin membicarakan ini.
Tidak bisa. Aku merasa sangat marah dan takut.
"Apa yang akan kaulakukan, Brad?" tanya Molly. "Kau punya
bakat lain? Kau mesti ambil keputusan."
"Aku dulu bisa sulap dengan kartu, waktu masih kecil," kata
Brad dengan tercekat. "Mungkin aku masih bisa melakukannya
sekarang."
Kami tiba di kamar, berpisah dengan Molly, dan melangkah ke
dalam dengan lesu.
Tapi di ambang pintu aku terenyak.
Di mejaku ada sepotong besar kue cokelat, dialasi serbet kertas.
Jadi, memang Marv rupanya. Marv yang masuk ke kamarku
dan melubangi semua balonku.
Rupanya ia masih membantu ibunya untuk menggemukkanku.
"Berani-beraninya kau!" teriakku. "Awas kau!"
Kuambil kue itu dan kulemparkan ke luar jendela. Lalu aku
mengempaskan diri ke ranjang dan membenamkan wajah di bantal.
**********
Aku bertemu Molly dan Celeste di lab sesudah makan malam.
Mereka sedang membuat proyek ilmiah agar mendapat nilai ekstra.
Mereka sedang memasang bola-bola karet berwarna biru pada
sebuah rangka dari kawat dan kayu, sambil sesekali melihat tabel di
buku.
"Apa fungsi benda itu?" tanyaku. Perutku berkeruyuk. Aku
belum bisa makan, karena masih cemas dan takut.
"Tidak ada fungsinya," kata Celeste. Ia memasang sebuah
kawat keperakan mengitari sebuah kawat lain. "Ini model galaksi."
Aku mengangguk. "Bagus juga."
"Kau perlu membuat proyek, Paul," Molly mengingatkan.
"Segera."
"Benar," Celeste sependapat. "Kau berada paling bawah pada
rantai makanan itu."
"Kau tidak perlu mengingatkan aku," bentakku.
"Kan bukan salah kami!" seru Molly. "Jangan bentak-bentak
begitu dong! Kami cuma ingin membantu."
"Sori," kataku. "Aku salah paham." Aku mendesah pelan.
"Kau mesti berusaha lebih keras," desak Molly. "Kau mesti
membuat Mrs. Maaargh terkesan."
"Dia sudah terkesan padaku," erangku. "Aku dianggapnya akan
menjadi makanan enak."
Celeste berkata, "Kau mesti berusaha naik dari posisi paling
bawah, Paul. Usahakan sedapat mungkin."
"Buat proyek sains saja," desak Molly. "Semua anak melakukan
kegiatan ekstra. Kau juga mesti mencoba."
"Aku tidak seperti kalian," ratapku. "Aku tidak sesuai masuk
sekolah ini. Aku... aku..."
"Jangan pesimis dulu," Celeste memarahiku. Ia menyibakkan
rambut pirangnya. "Kau mesti berusaha, Paul. Jangan sampai kalah."
"Aku punya gagasan untukmu," kata Molly. Ia membolak-balik
halaman buku teksnya. "Ini. Lihatlah."
Aku melihat sebuah diagram di halaman itu. "Apa ini? Peta
New Jersey?"
Celeste tertawa. "Baguslah kau masih bisa bercanda," katanya.
"Aku selalu bercanda kalau sedang ketakutan," gumamku.
"Ini diagram molekul," Molly menjelaskan sambil
menelusurkan jari di halaman itu. "Ini susunan molekul paling rumit
yang pernah ditemukan."
Aku memutar-mutar bola mataku. "Hebat."
"Serius dong!" bentak Molly. "Mau dibantu, tidak?"
Aku minta maaf.
"Kau bisa membuat model susunan molekul ini," Molly
melanjutkan. "Mrs. Maaargh pasti terkesan.
Aku memandangi gambar itu. "Membuatnya? Bagaimana?"
Molly membuka laci. "Lihat. Ini ada bola-bola lunak dan kayu-
kayu. Kau bisa membuat susunan molekul dengan perlengkapan ini.
Pasti bagus jadinya
Celeste bergegas ke sudut lab, mengambil sebuah karton besar.
"Kau bisa menyimpannya di sini. Masukkan karyamu ke sini, lalu
tunjukkan pada Mis Maaargh."
Kupelajari diagram di buku itu. "Banyak sekali bagiannya,"
keluhku.
"Kau pasti bisa," kata Celeste.
"Kau mesti mencoba, Paul," Molly menambahkan.
Mereka benar. Aku tak boleh menyerah. Aku mesti
memindahkan posisiku dari urutan paling bawah.
Maka aku mulai bekerja. Aku mulai menyusun bola-bola itu
dan memasangnya ke kayu-kayu tersebut. Rasanya seperti permainan
ketika aku masih kecil. Hanya saja susunan molekul ini sangat rumit.
Kami mengerjakan proyek kami bersama-sama. Kalau saja
kegiatan ini dilakukan bukan karena panik, tentunya akan sangat
menyenangkan.
Molly dan Celeste kembali ke kamar mereka pukul setengah
sebelas malam, tapi aku masih terus bekerja. Aku ingin menyelesaikan
proyek ini secepat mungkin.
Menjelang tengah malam, aku tidak tahan lagi. Mataku berat
sekali. Aku tak bisa lagi membaca diagram di buku. Proyekku hampir
selesai, tapi aku terlalu lelah untuk meneruskan. Aku mesti tidur
sekarang.
Kuambil model itu dan dengan hati-hati kumasukkan ke dalam
kotak, lalu kotak itu kututup dan kusimpan di bagian belakang salah
satu lemari.
Sambil menguap kumatikan lampu ruang lab, lalu aku keluar ke
lorong dan menuju deretan kamar.
Sepatuku menimbulkan suara keras di lantai, bergema di
seluruh lorong. Semua anak sudah tidur rupanya. Atau sedang belajar
keras di kamar masing-masing.
Aku berbelok... dan terkejut ketika sesosok tubuh melompat
dari sebuah ambang pintu yang gelap.
"Marv!" teriakku.
Anak itu menatapku dengan sepasang matanya yang hitam.
Seulas senyum kejam tampak di wajahnya yang pucat dan bundar.
"Paul," bisiknya, "kau suka kue cokelatnya?"
17
"JANGAN ganggu aku!" teriakku dengan suara serak
ketakutan.
Kudorong dia dan aku lari ke kamarku. Di pintu aku menoleh
dan melihat Marv melotot padaku. Wajahnya merah padam dan
mengernyit marah.
Aku terhuyung-huyung masuk ke kamar dan mengunci pintu.
Napasku terengah-engah dan jantungku berdebar-debar.
Kenapa Marv jahat sekali padaku? pikirku. Aku kan tidak
pernah mengganggunya. Kenapa dia bersemangat sekali membantu
ibunya?
Kulihat Brad sedang duduk di tepi ranjangnya. Rambutnya
menutupi dahi dan matanya merah.
Ia mengangsurkan sekotak kartu padaku. "Paul, ambil satu,"
katanya. "Yang mana saja."
"Aku sedang tidak berminat main sulap," kataku, masih
berusaha mengatur napas. Aku menoleh ke jam dinding. "Sudah lewat
tengah malam, Brad. Aku..."
"Kau mesti menolongku," teriak Brad sambil bangkit berdiri.
"Aku sudah berjam-jam berlatih sulap ini. Sebelumnya aku mati-
matian belajar matematika agar mendapat nilai ekstra. Aku mesti
berhasil dengan sulapku."
Ia terisak ketakutan. "Aku... aku tidak mau di makan."
Aku merinding. "Aku juga tidak," gumamku. "Marv sudah
mencelakakan kita. Gara-gara dia, kesempatan kita hilang."
"Tapi kita masih bisa mencoba," kata Brad. "Kalau kita
berusaha keras, kita pasti bisa. Pasti!"
Ia mengangsurkan kartu-kartunya padaku. Aku mengambil satu
dan membantunya berlatih selama dua jam. Akhirnya aku tidak tahan
lagi. Mataku perih dan aku letih sekali, sampai tidak bisa
membedakan gambar-gambar di kartu lagi.
Sementara itu aku juga terus melirik kotak balonku. Mestinya
aku berlatih membuat binatang dari balon.
Besok malam saja aku latihan, pikirku. Aku akan belajar keras
dan melanjutkan proyek molekulku sambil membuat binatang dari
balon. Mungkin, mungkin, aku akan berhasil.
Sambil menguap kusetel alarm wekerku, lalu aku naik ke
tempat tidur dan langsung pulas.
***********
Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi sekali, sebelum
alarmku berbunyi. Kukenakan celana panjang dan sweatshirt-ku, lalu
aku bergegas ke mejaku.
Masih mengantuk aku menulis surat pada orangtuaku.
Kuberitahukan bahwa guruku adalah monster.
Kuminta mereka menyelamatkanku sebelum terlambat.
Molly dan Celeste sudah mengatakan bahwa surat mereka tak
pernah sampai, tapi aku masih ingin mencoba. Usaha terakhir.
Kotak surat ada di tembok sebelah luar kantor depan.
Dengan hati-hati aku menuliskan alamat dan menempelkan
prangko di amplop, lalu kumasukkan ke kotak surat. Tidak ada orang
di sekitarku.
Pintu kantor depan terbuka. Masih terlalu pagi, dan
kelihatannya tidak ada orang di dalam. Aku melongok... dan terkesiap.
Di bawah kotak surat itu ada tong sampah besar.
Pantas saja! Tidak akan ada surat yang sampai.
Dengan berdebar-debar aku melongok ke luar. Tidak ada siapa-
siapa.
Kuangkat telepon di meja depan dan kuhubungi nomor
rumahku.
Tapi yang menjawab adalah pesan yang sudah direkam itu.
Rupanya telepon kantor pun diblokir.
Aku tak bisa menghubungi orangtuaku.
Dengan lesu aku naik ke lab, melanjutkan proyek molekulku
sampai saat sarapan tiba.
Kuharap Mrs. Maaargh menyukai karyaku, pikirku putus asa.
Mudah-mudahan saja.
***********
Proyek itu selesai sesudah makan malam. Bentuknya rumit.
Aku memeriksanya dua kali, untuk memastikan hasilnya sempurna.
Lalu dengan hati-hati kumasukkan karyaku itu ke kotaknya dan
kututup rapat-rapat. Dalam perjalanan kembali ke kamarku aku
berpapasan dengan Molly dan Celeste. Aku mengacungkan jempol
pada mereka.
Apakah Mrs. Maaargh akan terkesan dengan hasil karyaku?
Bisakah karya ini menyelamatkan hidupku?
Hanya satu cara untuk mengetahuinya.
Keesokan paginya dengan hati-hati kubawa kotak itu ke ruang
kelas. Mrs. Maaargh sedang memeriksa kertas-kertas di mejanya. Ia
baru datang. Kelas baru dimulai seperempat jam lagi.
Ia pura-pura tidak melihatku, terus menunduk memeriksa
kertas-kertas itu sambil menggerutu sendiri.
Kuletakkan kotakku di meja di sampingnya. "Mrs. Maaargh?"
Akhirnya ia mengangkat wajah padaku. "Kau pagi sekali,"
gerutunya.
"Aku... aku tahu," aku terbata-bata, lalu menelan ludah.
Pernahkah aku segugup dan setakut ini dalam hidupku?
"Apa isi kotak itu?" ia memberi isyarat dengan kepalanya.
"Proyek sains," kataku. "Aku sudah berhari-hari
mengerjakannya. Model susunan molekul. Aku membuatnya untuk
mendapat nilai ekstra. Kuharap... Anda menyukainya. Aku..."
"Buka kotak itu dan perlihatkan isinya," bentak Mrs. Maaargh.
Aku ragu. "Ehm... kalau Anda sedang tidak berminat, aku
kembali lagi nanti. Maksudku..."
"Buka kotak itu!" bentaknya, seluruh wajahnya yang lembek
bergetar.
Aku terlompat. "Baiklah." Kubuka kedua sisi kotak itu. "Aku
bekerja keras menyelesaikannya. Ini karya yang sangat rumit," kataku.
Aku sangat ketakutan, sampai tidak sadar apa yang kukatakan.
Mrs. Maaargh mengetuk-ngetukkan jemarinya yang gemuk di
meja.
Dengan hati-hati kukeluarkan proyekku dari dalam kotak dan
kuletakkan di mejanya. "Anda suka, Mrs. Maaargh?"
Monster itu memandanginya. Matanya yang berair melotot, lalu
ia ternganga terkejut.
"Apa... ini... leluconmu?" geramnya.
Hah?
Aku memandangi proyekku. "Oh, tidak!" teriakku.
Seseorang telah mengubah hasilnya, memindahkan susunannya.
Ini bukan lagi hasil karyaku. Ini bukan susunan molekul.
Bola-bola dan tongkat-tongkat itu disusun membentuk dua kata:
KAU JELEK.
18
DENGAN geraman marah Mrs. Maaargh meraih proyek itu dan
meremukkannya. Bola-bola dan tongkat-tongkat itu hancur bertebaran
di lantai
"Aku... bukan aku... " kucoba menjelaskan.
"Leluconmu... tidak... lucu!" bentak monster ilu
Ia bangkit berdiri sambil menggeram marah, lalu berjalan ke
tabel rantai makanan.
"Mrs. Maaargh... jangan!" pintaku.
Ia merenggutkan kartu namaku dari bagian paling bawah dan
membuangnya ke lantai. "Kau tidak termasuk lagi dalam tabel itu,"
teriaknya.
"Tapi... tapi..."
"Kau berada lebih bawah lagi, Paul. Di lantai, teriaknya. "Kau
tidak berada di tabel itu lagi."
Aku ingin protes, tapi yang keluar hanya cicitan pelan.
Sementara aku berdiri gemetar, monster itu mendekatkan wajah
padaku. "Sekarang kau punya nama baru," katanya serak, napasnya
yang panas dan basah begitu dekat di wajahku. "Namamu bukan lagi
Paul, melainkan MAKANAN ENAK!"
Kakiku gemetar, juga seluruh tubuhku. Tapi aku berhasil
menjauh darinya dan bergerak lemah ke luar.
Aku berjalan di lorong dengan kepala pusing. Anak-anak mulai
keluar dari kelas masing-masing. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa.
Tidak ingin bicara dengan siapa-siapa.
Aku mesti kembali ke kamarku untuk berpikir. Aku mesti
merencanakan langkah selanjutnya.
Apa yang bisa kulakukan?
Aku berpapasan dengan segerombolan cewek, lalu aku
berbelok, dan melihat Marv.
Lagi-lagi ia tersenyum jahat padaku. Senyum penuh arti.
Ia ingin aku tahu bahwa ia sudah bertindak lagi.
Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi aku melewatinya,
menerobos sekelompok anak yang sedang menuju kelas.
"Paul... ada apa?"
Aku menoleh dan melihat Molly berlari mengejarku dengan
rupa cemas. "Ada apa, Paul?"
Aku tidak ingin bicara padanya. Aku tak sanggup
menghadapinya. Ia sudah mencoba menolongku, tapi ternyata sia-sia.
Ia dan Celeste melongo memandangiku sementara aku lari ke
kamarku, lalu membanting pintu. Kuempaskan diri ke ranjang, lalu
aku bangkit lagi dan mondar-mandir di dalam. Kemudian aku duduk,
tapi bangkit lagi.
Aku tidak tahu mesti melakukan apa.
"Kenapa akuuuuu?" teriakku sambil memukul mukul tembok
dengan tinjuku.
Mendadak aku tahu apa yang mesti kulakukan.
Melarikan diri.
Toh tak ada jalan lain untuk bertahan.
Sekarang namaku sudah MAKANAN ENAK. Begitulah kata
Mrs. Maaargh. Aku bahkan tidak berada pada rantai makanan lagi.
Lari. Itu satu-satunya kesempatanku.
Aku tahu Molly dan yang lainnya pernah mencoba, dan kata
Molly itu mustahil.
Tapi mungkin aku lebih beruntung. Mungkin aku bisa
menyelinap keluar, menuruni bukit, mencari seseorang, siapa saja,
yang mau mendengarkan ceritaku dan percaya padaku, lalu mau
datang ke sekolah untuk menyelamatkan anak-anak lainnya.
Aku menggosok-gosok tinjuku yang sakit terkena tembok. Tadi
aku tidak merasakannya.
Ya, aku mesti lari.
Toh tak ada cara lain lagi.
Aku tidak kembali ke kelas. Aku melapor sakit ke kantor
perawat.
Kutunggu sampai semua anak lain sudah berada di kelas, lalu
aku mulai menyelidiki bangunan ini.
Aku menyelinap dari pintu ke pintu, menghindari para guru dan
siapa pun yang berjalan di lorong. Aku menyusuri semua lorong,
sampai menemukan apa yang kucari.
Sebuah pintu kecil di samping lemari dapur di bagian belakang
sekolah. Pintu itu hanya digunakan oleh para petugas dapur untuk
membawa masuk bahan-bahan makanan.
Kalau aku membukanya, apakah akan ada alarm berbunyi?
Mesti dicoba. Aku menarik napas, lalu memutar tombol pintu,
dan menariknya.
Pintu yang berat itu membuka.
Tidak terdengar bunyi alarm.
Tidak terdengar apa-apa.
Bagus!
Aku melongok ke luar. Awan gelap menggantung di langit.
Udara sejuk dan lembap. Baru kali ini aku menghirup udara segar lagi.
Aku menjulurkan leher ke bawah bukit. Tidak ada pagar atau
sistem alarm apa pun di luar sana. Tak ada yang bisa menghalangiku
lari ke bawah.
Mungkin ada kamera video yang diarahkan ke pintu dan bagian
belakang gedung, tapi aku tidak melihatnya. Kalau aku lari cukup
cepat, mungkin aku bisa lolos.
Dan begitu berada di bawah bukit, kalau aku terus berjalan,
pasti akhirnya aku akan menemukan rumah, atau kota, atau orang.
Terdengar langkah kaki mendekat. Aku tercekat.
Cepat-cepat aku menutup pintu dan membalikkan tubuh. Dua
wanita berseragam putih mendatangiku.
"Sedang apa kau di sini?" tanya yang seorang.
"Aku... eh... tersesat," jawabku. "Aku mencari ruang makan."
"Ke arah sana," kata wanita itu, menunjukkan. "Tapi kau sudah
terlambat untuk sarapan, dan terlalu awal untuk makan siang."
"Oh, maaf," kataku, lalu berjalan pergi. Kurasakan mata mereka
terus mengawasiku ketika aku menjauh.
Tapi aku tidak peduli.
Aku mesti lari. Aku sudah tahu jalannya. Dan aku akan
mengambil risiko itu.
***********
Keesokan paginya hujan lebat turun. Guntur menggelegar.
Biar saja. Hujan akan membuat mereka lebih sulit mengejarku.
Aku sarapan bersama Brad. Kucoba bersikap biasa. Aku
melambaikan tangan pada Molly dan Celeste, berceloteh tentang
binatang dari balon pada Brad.
Sebenarnya aku ingin menceritakan rencanaku padanya, juga
pada Molly dan Celeste. Aku ingin mereka kabur bersamaku.
Tapi aku khawatir ada yang mencuri dengar.
Bagaimana kalau Marv ada di dekat-dekat sini?
Lagi pula lebih mudah satu orang yang kabur daripada dua atau
lebih.
Aku akan kembali membawa bantuan, pikirku. Akan
kuselamatkan mereka semua.
Di tengah sarapan aku beranjak ke toilet di bagian belakang.
Tapi begitu berada di luar ruang makan, aku berbalik.
Dan menyelinap ke pintu belakang yang kemarin kutemukan.
Aku tidak menunggu lagi. Tidak ragu-ragu lagi. Kubuka pintu
itu... dan aku melesat keluar, ke tengah hujan lebat.
19
"WAAAAH!" Aku berteriak ketika hujan lebat itu menerpaku.
Aku merunduk dan lari menembus tirai hujan.
Sepatuku terasa licin di jalan sempit yang keras itu. Genangan
air yang terinjak olehku muncrat membasahi kakiku.
Aku menuju rerumputan tinggi. Di depanku tampak bukit yang
menurun.
Tapi hujan ini begitu lebat, sampai-sampai aku tak bisa melihat
ke bawah bukit atau ke hutan lebat yang terbentang di baliknya.
Aku bahkan tak bisa melihat apa yang ada beberapa meter di
depanku.
Sering kali aku terpeleset dan harus memelankan laju lariku.
Pakaianku yang basah terasa menempel di kulit. Kucoba melindungi
mataku dengan satu tangan agar tidak kemasukan air yang menetes
turun dari dahiku.
Guntur menggelegar dekat di atasku, membahana di
sekelilingku.
Aku terus merunduk dan lari.
Biarlah hujan, pikirku. Hujan sederas mungkin. Aku akan
kabur! Kabur dari tempat mengerikan itu.
Aku tak bisa berhenti. Kutengadahkan kepala dan kubuka
mulutku, tertawa bahagia.
"Aku berhasil! Aku berhasil!"
"Hei!" Aku berteriak ketika kakiku tersandung sesuatu.
Aku mengangkat tangan, berusaha menjaga keseimbangan, tapi
tetap saja aku terpeleset.
Aku terjerembap telentang di rumput basah. Tubuhku melesak
di tanah yang lunak.
Hujan menerpaku dengan deras, gelombang demi gelombang
air sedingin es.
Aku berusaha bangkit. Mata kakiku sakit, tapi aku bisa
menggerakkannya. Tidak apa-apa.
Aku hendak berdiri, tapi kudengar seruan di belakangku.
Deru hujan begitu deras, sehingga aku tidak mendengar jelas
apa yang diteriakkan.
Aku berdiri gemetar sambil menyeka sejumput lumpur dari
pakaianku.
Kembali kudengar seruan itu. Lebih dekat.
"Paul! Paul! Stop!"
Aku ketahuan.
20
MELALUI tabir hujan yang deras kulihat sesosok tubuh berlari
ke arahku di tengah rerumputan sambil melambai-lambai liar.
Lagi terdengar seruan itu, "Paul... stop! Stop!"
Kilatan halilintar menerangi langit, dan dalam cahaya sekilas itu
kulihat Molly yang mendekat dengan wajah cemas dan mata nyalang,
sementara tangannya teracung melambai.
Aku ingin berbalik dan terus lari.
Tapi ia sudah berada di sampingku sebelum aku bisa bergerak.
Ia terengah-engah, membungkuk dan menekankan tangan ke jeans-
nya yang basah kuyup.
"Paul...," katanya. Poninya lekat ke dahi. "Kau mau..."
"Kita bisa kabur!" teriakku, mengatasi deru hujan. "Tidak ada
pagar di sini, Molly. Tidak ada yang bisa menghentikan kita!"
Aku menunjuk ke bawah bukit, tapi Molly meraih lenganku dan
menarikku kembali ke arah sekolah.
"Tidak tampak!" teriaknya.
"Hah?" Aku memandanginya melalui tirai hujan.
Molly menangkupkan tangan di depan mulutnya. "Pagarnya
tidak tampak! Dialiri listrik! Seperti untuk anjing. Supaya anjing tidak
keluar dari pekarangan!"
Aku mengangguk mengerti.
"Kau akan kesetrum!" teriak Molly. "Aku sudah tahu. Aku
pernah coba..." Sisa kalimatnya tenggelam oleh gelegar halilintar.
"Tapi, Molly, aku mesti mencoba," teriakku. "Aku tidak bisa
tetap di sini."
"Kau mesti kembali," desak Molly. Ia menarik lenganku lebih
keras, hampir-hampir membuatku jatuh.
"Lepaskan!" teriakku. "Aku tidak mau..."
"Kau mesti kembali!" ulangnya. "Orangtuamu ada di sini!"
21
AKU tercengang. "O ya?"
Molly mengangguk dan menarikku lagi.
Orangtuaku ada di sini? Bagaimana bisa? Bagaimana mereka
tahu aku perlu diselamatkan?
Molly dan aku lari berdampingan, melompati kubangan-
kubangan air hujan, terpeleset-peleset di rerumputan, terus mendaki
bukit.
Bangunan sekolah yang jelek dan gelap menjulang di hadapan
kami. Kilat berkeredap di antara sepasang menaranya yang hitam.
Kami masuk lewat pintu belakang, pakaian kami meneteskan
air di lantai. "Di mana mereka?" tanyaku. "Di mana?"
Molly menunjuk. "Kulihat mereka berdiri di depan. Dekat
ruang-ruang kelas." Ia mendorongku. "Cepatlah ganti pakaian."
Aku menggigil. "Tidak ada waktu. Aku..."
"Cepatlah," desak Molly. "Kalau mereka melihatmu seperti ini,
mereka tidak akan mau mendengarkanmu."
Benar juga.
Aku bergegas ke kamarku dengan terpeleset-peleset dan tubuh
terus meneteskan air. Kulemparkan pakaianku yang basah ke lantai
dan kukenakan pakaian kering.
Jantungku berdebar kencang. Aku tak sabar ingin bertemu
orangtuaku. Aku sangat bahagia. Sangat lega. Yakin akan selamat.
Aku lari di lorong secepat mungkin. Jantungku serasa akan
meledak.
Kulihat orangtuaku berada di luar sebuah ruang kelas. "Mom!
Dad!" teriakku terengah-engah sambil melambai-lambai senang.
Mereka menoleh dan balas melambai.
"Aku senang sekali!" kataku terharu. "Bagaimana Mom dan
Dad tahu..."
"Paul... tenanglah! Tenang!" kata Dad.
Mom mengernyit padaku. "Kata Mrs. Maaargh, kau punya
masalah, Paul. Kami sangat kecewa padamu."
"Dia itu monster!" teriakku. "Monster!''
Mrs. Maaargh melongok ke luar dari dalam kelas. "Nah, dengar
sendiri, kan?" katanya pada orangtuaku. "Mengerti maksud saya
sekarang?"
22
"TAPI... tapi... " aku tergagap-gagap.
"Mari ke ruang guru," kata Mrs. Maaargh dengan ramah. "Kita
bisa berbincang-bincang tanpa diganggu." Ia tersenyum memuakkan.
"Mom, dengar dulu...," pintaku.
Kaki telanjang Mrs. Maaargh menimbulkan bunyi basah di
lantai ketika ia berjalan di depan, menuju ruang guru.
"Paul, kau basah kuyup!" seru Mom. "Kenapa rambutmu basah
begitu?"
"Aku... aku..."
"Dia mencoba kabur tadi pagi," sela Mrs. Maaargh.
Orangtuaku terperanjat.
"Ya, benar," kata Mrs. Maaargh sambil menyalakan lampu.
"Sudah saya bilang dia kelihatannya bermasalah."
Kedua orangtuaku melotot marah padaku.
"Mari minum teh dan silakan cicipi kue kecilnya," kata Mrs.
Maaargh dengan manis. Ia membungkuk ke arahku dan menjilat
bibirnya. "Makanan kecil adalah pembuka hari yang nikmat."
Mom dan Dad duduk di dekat sebuah meja kayu. Aku dipaksa
ikut duduk. "Paul sulit menyesuaikan diri pada suasana baru di
sekolah," kata Mom pada Mrs. Maaargh.
"Saya merasa harus menghubungi Anda berdua," kata Mrs.
Maaargh sambil menuangkan teh.
"Hah?" seruku, melompat bangkit. "Anda yang menghubungi
mereka?"
"Saya pikir mungkin Anda ingin membawa Paul pulang," kata
Mrs. Maaargh sambil menyodorkan secangkir teh panas.
"Kelihatannya dia sangat tidak bahagia di sini."
"Ya!" aku berseru dengan tinju teracung. "Ya! Bawa aku
pulang! Bawa!"
"Kami tentunya tidak ingin membawa dia pulang," kata Dad
sambil merengut ke arahku. "Kami ingin Paul belajar menyesuaikan
diri."
"Kami harap Anda bersedia memberi kesempatan lagi
padanya," kata Mom. "Tolong jangan suruh dia pulang."
Monster itu mengangguk, dagunya terlipat di bagian depan
gaunnya. "Tak usah cemas," katanya manis. "Setelah bincang-bincang
kita hari ini, aku yakin Paul akan bisa mengatasi masalahnya."
Aku merinding dan melompat bangkit lagi. "Mom dan Dad
mesti membawaku pulang!" teriakku.
"Paul, duduk... sekarang!" bentak Dad.
"Tapi dia itu monster!" teriakku sambil menunjuk Mrs.
Maaargh. "Benar, aku tidak bohong!"
"Cukup!" teriak Mom. "Kenapa kau kekanak-kanakan begitu?"
"Mom mesti percaya," pintaku. "Dia monster. Lihat saja
kakinya. Lihatlah!"
Dad menggeleng dan Mom merah padam. "Kami minta maaf,"
kata Dad pada Mrs. Maaargh. "Kami minta maaf untuk Paul. Entah
kami mesti bilang apa."
"Tidak apa. Tidak apa." Mrs. Maaargh mengangkat satu
tangannya. "Anak-anak sering membicarakan kaki saya. Memang kaki
saya sangat bengkak."
Ia mundur, kakinya menimbulkan suara basah. Ia
memandanginya sambil menggeleng-geleng sedih
"Ini karena kelainan kelenjar," gumamnya. "Dokter-dokter
mengatakan belum pernah menemukan kasus separah ini. Saya sedang
berobat sekarang."
Mom berdecak-decak.
Mrs. Maaargh memotes sepotong sisik dari cakarnya yang
hitam.
"Kaki saya tidak muat dimasukkan ke sepatu," lanjutnya dengan
sedih. "Saya sangat malu karenanya."
"Anda tidak perlu malu," kata Mom. Ia menoleh padaku. "Paul
yang mestinya malu karena bersikap kasar."
"Mom tidak mengerti...," kataku.
Tapi Dad menyuruhku duduk dan tutup mulut.
"Saya cemas tentang Paul," kata Mrs. Maaargh sambil
menghirup tehnya dengan berisik. Lidahnya yang tebal bergerak-gerak
di dalam cangkit. "Sangat berbahaya mencoba kabur."
"Itu tidak akan terulang," kata Dad. "Saya janjikan itu."
"Tapi... tapi..." Susah payah aku berusaha menceritakan yang
sebenarnya, tapi orangtuaku terus saja menyuruhku diam.
"Hutan di dekat sini sangat berbahaya," Mrs. Maaargh
melanjutkan. "Kalau dia mencoba kabur lagi, dia bisa tersesat dan
hilang selamanya."
Oh, mendadak aku mengerti, mengapa Mrs. Maaargh meminta
orangtuaku datang ke sekolah.
Ia sedang merintis jalan agar aku menghilang.
Ia akan menjadikanku makan malam, lalu ia akan mengatakan
pada orangtuaku bahwa aku kabur lagi dan hilang di hutan.
Lalu dengan sangat sedih ia akan berkata, Sudah saya katakan
ini bisa terjadi. Saya sudah memperingatkan Paul agar tidak melarikan
diri.
Orangtuaku masih berbincang-bincang beberapa lama bersama
Mrs. Maaargh, lalu monster itu menghabiskan isi cangkirnya dan
bangkit berdiri.
"Senang sekali bertemu dengan Anda berdua," katanya dengan
senyum pura-puranya. "Sayang sekali saya harus segera mengajar."
"Terima kasih Anda mau menemui kami," kata Dad sambil
menjabat tangannya yang gemuk.
"Kami yakin mulai sekarang Paul akan belajar lebih rajin," kata
Mom dengan mata terarah padaku.
"Paul, kuharap kau menangkap pesan hari ini," kata Mrs.
Maaargh sambil nyengir memuakkan padaku. "Kau tahu?" Ia
membungkuk ke dekatku.
"Kau kuizinkan tampil pertama kali pada pertunjukan bakat
besok."
"Ada pertunjukan bakat?" seru Mom. "Bagus sekali. Sayangnya
kami tidak bisa hadir. Bagus sekali sekolah ini."
Mrs. Maaargh mengucapkan selamat jalan, lalu beranjak pergi.
Begitu ia tidak kelihatan lagi, aku melompat dan mencegat
orangtuaku. "Kenapa Mom dan Dad percaya padanya?" teriakku.
"Kenapa kalian tidak percaya padaku?"
"Kelihatannya dia baik," sahut Mom.
"Paul, kau ini kenapa sebenarnya?" tanya Dad.
"Dia itu monster!" teriakku. "Monster!"
Dad menggaruk-garuk kepalanya. "Dia memang agak aneh,"
katanya sambil mengernyit padaku. "Tapi kami mendidikmu untuk
tidak menilai orang dari penampilan luarnya. Ingat?"
"Penampilan luar bisa menipu," tambah Mom.
Mereka hendak beranjak ke pintu.
Aku meraih lengan kemeja Dad. "Tapi dia akan memakanku,"
teriakku. "Dia akan memakanku hidup-hidup."
Mom dan Dad tertawa. "Suruh dia menambahkan kecap
banyak-banyak," kata Dad.
"Dan minta dia sisakan tulang-tulangnya untukku," gurau Mom.
Bergurau?
Kami sudah berada di pintu depan. Mereka memelukku dan
memintaku belajar rajin, serta jangan membuat ulah lagi.
Lalu mereka pergi.
Mereka kesempatan terakhirku. Dan mereka pergi.
Aku berdiri terpaku di pintu depan.
Apa yang mesti kulakukan? Apa yang akan kalian lakukan
kalau kesempatan terakhir kalian sudah lenyap?
Masih adakah cara untuk menyelamatkan diri?
Sebuah sentuhan di bahuku membuatku menjerit.
Aku terlompat dan membalikkan tubuh dengan berdebar.
"Marv!"
Sepasang matanya yang kecil berbinar-binar di wajahnya yang
bundar. Ia nyengir lebar dan mengangsurkan sebuah kantong merah-
kuning. "Mau kue?" tanyanya.
23
MASIH ada satu kesempatan.
Situasinya sudah mendesak. Orangtuaku sudah diperingatkan
bahwa kalau aku kabur lagi, aku bisa hilang selamanya. Dan Mrs.
Maaargh sekarang memanggilku "Makanan Enak" di depan semua
anak.
Tapi selalu ada satu kesempatan paling akhir. Ya kan?
Aku berlatih sepanjang malam untuk perunjukan bakat itu.
Kupaksa Molly dan Celeste menontonku. Lalu kupaksa Brad
menontonku juga selama berjam-jam.
Binatang-binatang dari balon buatanku benar-benar jelek. Kata
mereka. Pokoknya jelek luar biasa.
Tapi aku menyertakan lelucon-lelucon yang sangat lucu untuk
setiap binatang yang kubuat.
Aku tidak tidur. Aku terlalu takut dan tegang.
Tapi semakin lama berlatih, aku semakin lebih yakin. Kalau
penampilanku bagus, mungkin aku bisa menaikkan posisiku pada
rantai makanan.
Pertunjukan bakat itu diadakan setelah sarapan. Aku duduk di
ruang makan, memandangi sarapanku.
Perutku kaku. Rasanya setiap otot di tubuhku melilit. Aku perlu
energi untuk bisa tampil baik, tapi aku tidak bisa makan.
"Paul?" Suara itu membuatku tersentak. Sekretaris kantor
berdiri di belakang mejaku. "Ada pesan untukmu," katanya. "Di
kantor depan."
Kuikuti ia ke luar ruang makan. Semua orang menatapku. Ia
membawaku ke kantor di dekat bagian depan sekolah.
"Itu," katanya menunjukkan, lalu bergegas mengangkat telepon
yang berdering.
Aku mengambil catatan yang ada di meja dan membacanya.
Mula-mula aku memperhatikan tanda tangannya. Pesan ini dari
Mrs. Maaargh. Ternyata tulisannya kecil-kecil dan rapi.
Waktunya tampil! Kau yang pertama pagi ini. Temui aku di
tengah panggung auditorium. Datanglah begitu kau menerima pesan
ini dan kita mulai pertunjukannya.
Mrs. Maaargh.
Aku tercekat. Mendadak mulutku kering sekali. Aku minum
banyak-banyak dari pancuran di luar kantor.
Lalu aku bergegas ke kamarku untuk mengambil balon.
Ini dia! pikirku. Ini kesempatanku yang paling akhir untuk
menyelamatkan diri.
Aku membuka pintu dan masuk. Aneh, auditorium luas ini
gelap gulita. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu sorot yang
membuat lingkaran cahaya di tengah panggung.
Pasti di situlah Mrs. Maaargh menghendaki aku menunggu,
pikirku.
Aku melayangkan pandang ke kursi-kursi, lalu ke panggung. Di
mana dia?
Kakiku lemas dan gemetar ketika aku naik ke panggung.
Kucengkeram kotak balonku erat-erat, seolah-olah benda itu adalah
ban penyelamat.
"Mrs. Maaargh?" panggilku sambil melihat ke bayang-bayang
di belakang panggung. "Mrs. Maaargh? Aku di sini!" Suaraku
bergema di antara barisan kursi kosong itu.
"Apa tidak sebaiknya lampu-lampu auditorium dinyalakan?"
seruku.
Tak ada jawaban. Tak ada siapa-siapa di sini.
Aku melangkah ke lingkaran cahaya itu, dan menunggu sampai
mataku bisa menyesuaikan diri.
"Halo?" panggilku. "Ada orang di sini? Halo?"
Kuangkat kotak balonku dan kuucapkan kalimat yang telah
kuhafalkan sebelumnya. "Halo, semuanya, aku ahli balon lokal yang
ramah "
Kubayangkah semua penonton di depanku tergelak-gelak,
sementara Mrs. Maaargh tersenyum lebar sambil berpikir, Ternyata si
Paul boleh juga. Mungkin dia akan kuberi kesempatan.
"Mrs. Maaargh?" panggilku. "Anda ada di sini?"
Aku mulai berkeringat di bawah lampu yang panas itu. Aku
merasa panas, lalu dingin. Tanganku basah dan dingin sekali.
Kesempatan terakhirku, pikirku. Ayo teruskan!
Di bagian belakang auditorium, sebuah pintu terbuka. Cahaya
masuk ke bagian belakang lorong. Seorang gadis melongok ke dalam.
Molly!
Aku menyipitkan mata ke seberang kursi-kursi. Molly
memandang ke arah panggung, masih memegangi pintu.
"Paul?" panggilnya. "Kau sedang apa di situ?"
"Menunggu Mrs. Maaargh," teriakku supaya ia bisa mendengar.
"Aku yang pertama tampil."
Molly ternganga. "Kau tidak tahu? Tadi diumumkan saat
sarapan."
"Apa yang diumumkan?" teriakku.
"Pertunjukan bakatnya ditunda."
24
MOLLY menghilang. Pintu menutup lagi, dan auditorium
kembali gelap.
Selama beberapa saat aku berdiri terkejut, terpaku dalam
kegelapan.
Ditunda? Ditunda?
Sambil mendesah panjang aku melangkah keluar dari lingkaran
cahaya.
Dan sebuah tangan mencengkeram tengkukku dengan kasar.
Aku terkesiap.
Tangan itu semakin erat mencengkeramku.
Aku membalikkan badan... dan melihat Mrs. Maaargh. Ia
mendekatkan kepalanya yang besar ke kepalaku dan membuka
mulutnya dalam suatu seringai lebar.
"Selamat pagi, SARAPANKU!" geramnya.
"T-tidak," aku tergeragap, lalu meronta-ronta.
Tapi ia terlalu kuat. Aku tak bisa melepaskan diri.
Aku menjerit kaget ketika lantai di bawah kakiku melesak.
Ada apa ini? Kenapa seluruh sekolah ini melesak ke bawah
tanah?
Tidak! Dengan ketakutan kulihat bahwa kami berdiri di sebuah
pintu bawah tanah yang tersembunyi di lantai panggung. Pintu itu
turun semakin cepat. ebukulawas.blogspot.com
"Kita akan ke mana?" teriakku. "Apa yang kaulakukan?"
Sebagai jawaban, ia menjilat bibirnya dengan lapar.
Aku mencoba mendorongnya dengan dua tangan.
Tapi cengkeramannya di leherku begitu erat.
Pintu bawah tanah ini turun ke bawah panggung. Sekarang yang
ada hanya kegelapan. Kakiku gemetar dan aku nyaris jatuh, tapi
monster itu mengangkatku dengan mencengkeram tengkukku.
"Kau... kau tidak sungguh-sungguh, kan?" tanyaku terbata-bata.
"Tentu aku sungguh-sungguh," geramnya.
Pintu yang kami injak turun semakin dalam... semakin dalam.
"Tapi... tapi kau pasti akan sangat menyesal," kataku.
"Tidak akan," sahut si monster. "Aku kan monster. Ingat?"
"Tapi ini tidak benar!" teriakku. "Kau tahu ini tidak benar."
"Aku tidak tahu mana yang benar mana yang salah," katanya.
"Aku cuma tahu aku lapar."
"Tapi... tapi... kau pasti tertangkap. Orang-orang akan tahu dan
akan menangkapmu. Mereka akan membunuhmu."
"Makanya aku selalu hati-hati," katanya, napasnya yang panas
dan asam meniup di wajahku. "Itu sebabnya aku cuma makan satu
anak setiap tahun."
Pintu yang kami injak berhenti turun. Di sekitarku hanya
kegelapan.
Mrs. Maaargh menarikku dengan kasar dari pintu, lalu pelan-
pelan pintu itu mulai terangkat kembali ke atas.
Aku terjebak di sini. Di mana kami sebenarnya?
Sambil menggeram pelan Mrs. Maaargh menyeretku di sebuah
lorong panjang dan gelap. Kami berbelok dan masuk ke terowongan
lain yang membuka ke sebuah ruang bawah tanah yang lebar dan
rendah. Di sepanjang tembok dan langit-langit tampak pipa-pipa
berselimut debu. Kudengar suara air menetes entah di mana. Mesin-
mesin berdengung. Di atas ada suara bergemuruh.
Monster itu menyalakan lampu bohlam dengan tangan satunya.
Cahaya lampu yang pucat menerangi ruangan yang kelabu dan
berdebu ini.
"Di mana kita?" tanyaku. "Untuk apa kita di sini?"
Ia menyeretku ke dinding, lalu membungkuk dan membuka
sebuah pintu besi yang besar.
Terdengar suara gemuruh. Lidah api menjilat-jilat di balik
pintu, berderak-derak dan melompat-lompat.
"Tempat pembakaran!" teriakku.
Mrs. Maaargh mendekatkan wajahnya padaku. "Aku bukan
binatang," katanya. "Aku tidak makan daging mentah. Santapanku
kumasak dulu."
Sambil memegangiku erat-erat ia membuka mulutnya lebar-
lebar. Gusinya mulai membesar. Empat baris gigi runcing mencuat
dan tetes-tetes besar air liur turun ke gigi-giginya yang jelek.
Ia mulai menggeram keras, dadanya turun-naik, lidahnya yang
gemuk berputar-putar di barisan giginya.
Ia mengangkatku dari lantai dengan dua tangan.
"Tidak, jangan!" pintaku. Aku melotot memandangi api yang
berkobar-kobar. "Tunggu!"
Ia mengatupkan mulutnya dengan lapar.
Lalu ia mengangkatku tinggi-tinggi di depannya... dan
melemparkanku ke api.
25
"TIIDAAAAK!" teriakku sambil meronta-ronta. Aku berhasil
menyambar pintu perapian raksasa itu. Sambil meliuk keras aku
menjauhkan diri dari api, dan berhasil berdiri di samping pintu
perapian yang terbuka.
Monster itu memiringkan kepala dan meraung marah. Ia hendak
menangkapku, tapi aku berhasil menghindar.
Kuambil sebatang pengorek berat dari besi, yang biasa
digunakan untuk mengorek perapian. Sambil menggerung kuangkat
pengorek itu dan kulemparkan sekuat tenaga ke arah monster tersebut.
Pengorek itu menghantam perutnya.
Si monster berseru kaget dan terjatuh.
Apakah dia terluka?
Aku tidak mau menunggu.
Aku lari ke terowongan dengan lengan terulur ke depan. Aku
lari sekuat tenaga, terengah-engah, tidak menoleh, tidak
mendengarkan, tidak melihat apa pun selain kegelapan lorong di
depan.
Aku berbelok dan lari di lorong berikutnya.
Di depan terdengar suara derum pelan. Lalu aku melihat
sepasang sepatu dan sepasang kaki dalam celana jeans.
Pintu bawah tanah! Seseorang turun kemari.
Aku berhenti lari. "Molly? Kau sedang... bagaimana kau..." Aku
tak bisa melanjutkan, napasku terlalu pendek-pendek..
"Paul, maafkan aku," seru Molly. "Cepat naik!"
"Maaf?" bisikku. "Apa maksudmu?"
"Maaf aku mencelakakanmu," katanya sambil terisak. "Tapi aku
takut sekali, Paul. Takut sekali. Aku tahu Mrs. Maaargh akan
memakanku. Dia benci padaku, karena aku mencoba kabur. Aku akan
menjadi mangsanya, Paul. Aku takut sekali. Lalu kau datang."
"Tapi... aku tidak mengerti," kataku.
"Aku tahu aku salah," lanjut Molly dengan gemetar. "Tapi
akulah yang melakukannya. Aku yang merusak biola Brad, sehingga
akulah yang tampil. Aku juga yang melubangi balon-balonmu dan
mengubah susunan molekulmu. Aku takut sekali. Aku tidak mau
dimakan."
"Tapi kemarin kau mengejarku dalam hujan. Kenapa?" tanyaku.
"Aku tidak mau kau kabur," kata Molly, terisak lagi. "Kalau kau
lari, akulah yang dimakan. Jadi, aku membujukmu untuk kembali.
Aku memang egois dan jahat, tapi itu kulakukan karena aku sangat
ketakutan."
Aku melongo memandanginya. Jadi, selama ini bukan Marv
yang jahat, tapi Molly.
"Tapi aku merasa sangat bersalah," kata Molly lagi. "Jadi, aku
datang untuk menyelamatkanmu."
Pintu itu berderum dan bergerak, mulai terangkat. "Cepat,
Paul." Molly mengulurkan tangan. "Lompat. Kita bisa kabur."
"Oke," teriakku. Pintu itu sudah naik hingga sebatas
pinggangku. Cepat sekali.
Aku melompat.
Tapi sesuatu menahanku.
"Kau mau ke mana, SARAPANKU?" Mrs. Maaargh
menggeram. Sepasang lengannya yang gemuk melingkari kakiku.
Aku mengulurkan tangan pada Molly. "Tunggu! Tunggu!"
pintaku.
Tapi pintu itu terangkat naik bersama Molly. "Sayang sekali,"
kata si monster. Senyum jahat menghiasi wajahnya. "Selamat tinggal,
pintu. Selamat tinggal, Paul."
"Tidak!" teriakku.
Aku meronta-ronta dan berhasil melepaskan diri. Aku bisa lari
lebih cepat daripada dia, pikirku. Dia besar dan lamban. Aku lebih
gesit.
Tapi ke mana aku bisa lari?
Monster itu bangkit dan siap-siap menjegalku. Aku menerobos
melewatinya dan lari.
Lari sekenanya di lorong itu. Adakah pintu di sini? Atau anak
tangga? Atau tempat bersembunyi yang bagus?
Aku menerobos ke dalam kegelapan.
Aku berbelok ke lorong lain, melewati ruang suplai yang penuh
sesak, masuk ke lorong lain lagi.
"Tidaaaak!" teriakku kaget saat aku bertumbukan dengan Marv.
26
"TOLONG... " pintaku. "Tolong jangan beritahu dia di mana
aku. Biarkan aku lolos."
Sepasang mata Marv yang kecil melebar heran. Ia mundur.
"Kau kan temanku," gumamnya.
Aku sudah hendak lari melewatinya, tapi lalu berhenti dan
menoleh. "Apa?"
"Kau temanku," katanya. "Kau mau duduk denganku di ruang
makan. Kau mau bicara denganku. Kau satu-satunya yang baik
padaku."
Aku tercekat. "Maksudmu..."
"Itu sebabnya aku membawakanmu kue," katanya. "Sebab kau
temanku."
"Kau bukannya ingin membantu ibumu?" tanyaku.
Ia menggeleng. "Aku akan membantumu," katanya.
Kudengar gemuruh langkah kaki di belakang kami semakin
keras. Mrs. Maaargh berhasil melacak jejakku.
"Bagaimana kau akan menolongku?" tanyaku. "Bisakah kau
mengeluarkan aku dari sini?"
Ia menggeleng. "Tidak ada jalan keluar," katanya.
"Lalu bagaimana kau bisa menolongku?" teriakku.
Langkah kaki si monster semakin dekat.
"Buatlah dia tertawa," kata Marv.
Aku menyipitkan mata. "Apa?"
"Buat dia tertawa, Paul. Dia hampir tidak pernah tertawa, tapi
kalau sudah tertawa, dia akan tidur panjang. Dia akan tertidur selama
enam bulan."
"Tapi bagaimana caranya?" tanyaku panik sambil
mencengkeram kemeja Marv. "Bagaimana aku bisa membuat dia
tertawa?"
Ia tidak menjawab. Matanya melotot dan ia melepaskan diri dari
cengkeramanku, lalu mundur ke dalam bayang-bayang.
Aku menoleh. Mrs. Maaargh berdiri di depanku, memblokir
lorong. Lengannya terentang. Ia merunduk dan menyeringai padaku,
siap-siap menyerangku lagi.
"Tak ada jalan untuk lari, Sarapan," katanya sambil menjilat
bibir dengan lapar. Ia membuka mulutnya, sekali lagi memamerkan
deretan giginya.
Aku memandanginya ketakutan. Bagaimana supaya dia
tertawa? pikirku. Apa yang mesti kukatakan atau kulakukan?
Aku berpikir keras. Kepalaku serasa akan meledak.
Apa aku mesti menceritakan lelucon padanya?
Tidak. Ia tidak pernah tertawa pada leluconku. Lagi pula aku
sedang sangat ketakutan dan tak ingat lelucon apa pun.
Kalau saja balon-balonku ada di sini, pikirku. Mungkin
binatang balon buatanku bisa membuatnya tertawa.
Apa lagi yang bisa kulakukan?
Menari? Menyanyi?
Tidak. Ia akan melahapku sebelum aku selesai. Sambil
menggeram pelan monster itu merunduk dan bersiap menyerang.
Mendadak aku mendapat gagasan.
27
MONSTER itu merunduk ke depan, kakinya yang besar
berdebum di lantai yang keras.
Aku berlutut.
"Kau mau apa?" tanyanya marah.
Aku membungkuk dan mengulurkan tangan.
Bisakah aku melakukannya? Bisakah aku menyentuh kaki
lembek yang menjijikkan itu?
Ia mengentakkan satu kakinya dengan tak sabar. SRET SRET.
Cakar-cakarnya yang tebal menyapu lantai.
Kuangkat tanganku di atas kaki itu.
Perutku bergolak. Aku merasa mual.
Aku tak sanggup menyentuhnya, pikirku. Terlalu menjijikkan.
"Bangun!" bentaknya.
Tak ada pilihan lain. Aku harus melakukannya.
Pelan-pelan kusentuhkan jemariku di kaki yang besar itu.
Rasanya sangat lembek dan lembap.
Dan aku mulai menggelitik.
Karena membungkuk, aku tak bisa melihat wajah monster itu,
tapi kudengar ia terkesiap.
Aku terus menggelitik kakinya, menggerakkan jemariku di
kulitnya yang lembek.
Iiih! pikirku. Ini memuakkan. Sangat memuakkan.
Aku tak percaya aku menyentuh kakinya.
Tapi Mrs. Maaargh mulai tertawa.
Aku menggelitik lebih lama.
Suara tawanya bergemuruh di seluruh lorong bawah tanah.
Kedengarannya lebih mirip salak anjing daripada suara tertawa.
Aku terus menggelitiknya.
Ia terus dan terus tertawa. Tersedak dan tertawa.
Lalu ia terduduk di lantai dan tertawa dengan kepala tengadah.
Sampai kemudian seluruh tubuhnya terdorong ke belakang dan
ia terbaring telentang di lantai.
Aku cepat-cepat berdiri dengan perut mual. Seluruh tubuhku
serasa gatal dan merinding.
Dada dan perut monster itu bergerak naik-turun. Napasnya
teratur, matanya tertutup dan mulutnya terbuka sedikit.
"Dia tidur," kata Marv pelan sambil melangkah keluar dari balik
bayang-bayang.
Aku memandangi monster itu, masih terlalu mual untuk bicara.
Masih terasa olehku kulitnya yang menjijikkan itu.
"Dia akan tidur berbulan-bulan," kata Marv. "Bisa juga
setahun."
Kupaksakan diri memalingkan wajah dari monster itu. "Kau
menyelamatkanku," kataku.
Marv tersenyum. Ia menarik-narik rambutnya. "Begitulah."
Aku merangkul bahunya. "Kau menyelamatkanku!" aku berseru
senang. "Tak percaya rasanya. Kau menyelamatkanku!"
Kami melangkah ke pintu bawah tanah. Lalu Marv berhenti
berjalan dan menoleh padaku. "Ada satu masalah, Paul."
"Apa?" tanyaku.
Mata Marv berkilat-kilat. "Semua keributan tadi membuatku
lapar sekali," katanya.
Aku terkesiap dan menjauh darinya. "Kau cuma bercanda kan?"
seruku.
"Kau bercanda kan?"
"Iya kan?"END
Anda mungkin juga menyukai
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5794)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Dari EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7770)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20020)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Alice in Wonderland: Down the Rabbit HoleDari EverandAlice in Wonderland: Down the Rabbit HolePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4609)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3275)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDari EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7086)
- The Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Dari EverandThe Illustrated Alice in Wonderland (The Golden Age of Illustration Series)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (4345)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12945)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2566)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (726)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6520)
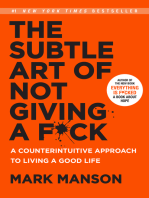













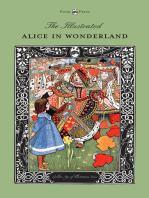

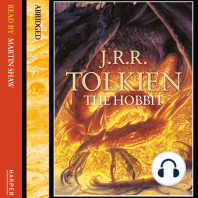

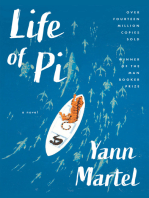


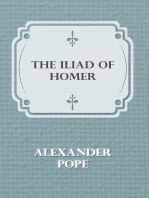


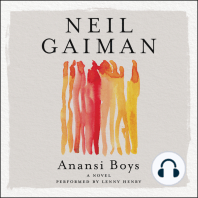



![Don Quixote: [Complete & Illustrated]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/264046221/149x198/541f56cceb/1617238192?v=1)