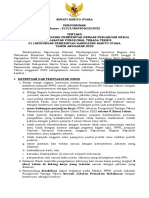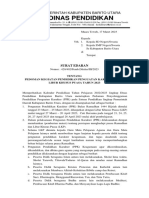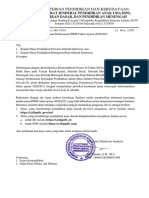119 212 1 SM
Diunggah oleh
MUHAMMAD HELMI GUNTARJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
119 212 1 SM
Diunggah oleh
MUHAMMAD HELMI GUNTARHak Cipta:
Format Tersedia
P-ISSN 2580-8338.
E-ISSN 2621-1564 Jurnal Lugas
20 Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 - 26
BUDAYA POLITIK DALAM MASYARAKAT
PRAGMATIS
Sumartono
Dosen Komunikasi FISIPOL
Universitas Ekasakti Padang
Email: rajoameh1999@yahoo.com
ARTICLE INFO ABSTRACT
General elections and regional head elections in Indonesia are conducted directly.
The pattern of community participation is changed. The emergence of pragmatism
or political pragmatism in society becomes an interesting political culture to study.
Practically, pragmatism means a condition that encourages people to get benefits
instantly. As a result, people take any actions to make it happen. In reality,
pragmatism not only affects the upper classes (those with a high level of education)
Keywords: but also ordinary people (lower class society or those with low levels of political
political culture, education). The development of money politics, cow trade politics, the sale of
political reality, votes, or the existence of political dowry is a sign that there has been a political
pragmatic society transaction becoming one of the indicators of pragmatism reality in society.
1. Pendahuluan
Secara aplikatif, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan
bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan
norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga
dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk
masyarakat seluruhnya.
Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih
khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan
kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang
dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya,
seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict
Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan
kelompok massa.
Kajian tentang budaya politik selalu menarik. Selain berkaitan dengan perkembangan politik
di suatu negara, budaya politik juga berhubungan dengan dinamika partisipasi politik masyarakat.
Artinya, perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya
yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat (dalam
konteks Indonesia) sangat memengaruhi perkembangan budaya politik di Indonesia yang memiliki
karakteristik berbeda pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perkembangan budaya politik
diwujudkan dengan terciptanya partai-partai politik. Partai politik selalu berusaha untuk merebut
simpati rakyat dalam kegiatan pemilu yang bertujuan untuk menempatkan orang-orang partainya
dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ideologi negara dan UUD 1945. Agar masyarakat
memiliki pandangan politik yang sesuai, sosialisasi politik dilakukan sesuai dengan kondisi dan
perkembangan lingkungan yang ada. Semakin stabil pemerintahan, semakin mudah untuk melakukan
sosialisasi politik. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang sempurna tetapi kita harus berusaha agar
perkembangan budaya politik terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai kepentingan
bersama, sehingga masyarakat yang memegang peranan penting dalam perkembangan budaya politik
suatu negara mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.
http://ojs.stiami.ac.id lugasjournal@gmail.com /lugasjournal@stiami.ac.id
P-ISSN 2580-8338 Jurnal Lugas 21
E-ISSN 2621-1564 Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 - 26
Berdasarkan pemahaman teoritikal, kita memahami bahwa budaya terbentuk dari sebuah
kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Demikian halnya dengan kebiasaan
yang ingin serba praktis dan instan, cepat serta mudah dalam menyelesaikan dan memenuhi segala
sesuatu kebutuhan. Kebiasaan tersebut berubah menjadi sebuah budaya pragmatis atau instan.
Budaya serba praktis dan instan di Indonesia kini telah menjadi kebudayaan secara nasional,
tidak hanya berjalan di suatu wilayah atau daerah tertentu, namun di seluruh Indonesia. Masyarakat
Indonesia cenderung menggemari sesuatu yang bersifat praktis, dimana masyarakat selalu
mementingkan segi kepraktisan dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat lebih memilih sesuatu
yang dapat diperoleh secara praktis dan instan, dimana tidak merepotkan masyarakat ketika
membutuhkan sesuatu. Contohny, mulai dari jenis makanan, pelayanan, mencapai sesuatu, pemenuhan
kebutuhan, sampai di hampir seluruh aspek kehidupan (termasuk politik) sudah dilingkupi oleh
budaya serba instan.
Mendiskursuskan tentang budaya politik menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konteks
kekinian di dalam masyarakat. Kecendrungan munculnya sikap pragmatis dalam kehidupan politik
menjadi sinyalemen bahwa realitas politik tidak hanya bicara merebut dan mempertahankan kekuasaan
tetapi bagaimana budaya politik yang berkembang di masyarakat disikapi dengan cara pragmatis.
2. Apa itu budaya politik ?
Almond dan Verba (dalam Alfian dan Sjamsuddin, 1991 : 21) mendefinisikan budaya politik
sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam
bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut. Dengan kata
lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat
bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri
mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.
Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam
sistem politik.
Berikut ini adalah beberapa pengertian budaya politik (yang dapat dijadikan sebagai pedoman:
(1). Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat,
tahayul, dan mitos. Semuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik
memberikan pemahaman rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain, (2).
Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada
isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Yang kedua (aspek generik)
menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau
tertutup, (3). Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar
yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan, dan (4). Bentuk
budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi
seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau
mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau men-
dorong mobilitas), prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).
Dari pengertian budaya politik yang telah diuraikan, nampaknya membawa kita pada suatu
pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu. Dengan
orientasi yang bersifat individual ini, tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya kita
menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme. Jauh dari anggapan yang
demikian, pandangan ini melihat aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan akan
adanya fenomena dalam masyarakat secara keseluruhan tidak dapat melepaskan diri dari orientasi
individual.
Menurut Ranney (dalam Ryass, 2000 : 64), terdapat dua komponen utama dari budaya politik,
yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations).
Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan
Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga
komponen obyek politik sebagai berikut: (1). Orientasi kognitif : yaitu berupa pengetahuan tentang
dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya, (2).
Orientasi afektif : yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya,
dan (3). Orientasi evaluatif : yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara
tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
22 Jurnal Lugas P-ISSN 2580-8338
Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 – 26 E-ISSN 2621-1564
3. Tipe-Tipe Budaya Politik
Berkaitan dengan tipe-tipe budaya politik, Gabriel A Almond (dalam Effendi, 1991 : 27)
membagi atas budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan.
3.1. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.
Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka
terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama
sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada
masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada
peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya
merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.
3.2. Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial
maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan
subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara
umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan
kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan
otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat
terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka.
Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem
politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
3.3. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat
tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Budaya politik
juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki
pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki
pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah
dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang
berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua
dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat
menerima atau menolak.
4. Pragmatisme Politik
Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma berarti perbuatan (action) atau tindakan
(practice). Isme berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti
ajaran/aliran/paham yang menekankan bahwa pemikiran itu mengikuti tindakan. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaraan atau nilai suatu ajaran
(paham/doktrin/gagasan/pernyataan/dsb) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia.
Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi
kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan); mengenai/bersangkutan dengan nilai-nilai praktis. Karena
itu, pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Suatu teori
atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar jika membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu
teori itu benar jika berfungsi. Jadi, pragmatisme dapat dikategorikan ke dalam pembahasan mengenai
teori kebenaran.
Kebenaran, menurut James dalam bukunya, The Meaning of Truth, adalah sesuatu yang terjadi
pada ide, yang sifatnya tidak pasti. Sebelum seseorang menemukan satu teori berfungsi maka tidak
diketahui kebenaran teori itu. Kebenaran akan selalu berubah sejalan dengan perkembangan
pengalaman. Sesuatu yang dikatakan benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena
itu, paham pragmatisme tidak mengenal adanya kebenaran mutlak. Kebenaran ditentukan oleh
kemanfaatan.
Ide pragmatisme keliru dari tiga sisi. Pertama, pragmatisme mencampuradukkan kriteria
kebenaran ide dan kegunaan praktisnya. Kebenaran ide adalah suatu hal, sedangkan kegunaan praktis
ide itu adalah hal lain. Kebenaran sebuah ide diukur dengan kesesuaian ide itu dengan realita atau
dengan standar-standar yang dibangun di atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan
realita. Kegunaan praktis suatu ide untuk memenuhi hajat manusia tidak diukur dari keberhasilan
penerapan ide itu sendiri. Jadi, kegunaan praktis ide tidak mengandung implikasi kebenaran ide, tetapi
hanya menunjukkan fakta terpuaskannya kebutuhan manusia. Kedua, pragmatisme menafikan peran
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
P-ISSN 2580-8338 Jurnal Lugas 23
E-ISSN 2621-1564 Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 - 26
akal manusia. Menetapkan kebenaran sebuah ide adalah aktivitas intelektual dengan menggunakan
standar-standar tertentu. Penetapan kepuasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah
identifikasi naluriah. Identifikasi naluriah dapat menjadi ukuran kepuasan manusia dalam memuaskan
hajatnya, tetapi tidak dapat menjadi ukuran kebenaran sebuah ide. Artinya, pragmatisme telah
menafikan aktivitas intektual dan menggantinya dengan identifikasi naluriah. Dengan kata lain,
pragmatisme telah menundukkan keputusan akal pada kesimpulan yang dihasilkan dari identifikasi
naluriah. Ketiga, pragmatisme menimbulkan relativitas dan kenisbian kebenaran sesuai dengan
perubahan subyek penilai ide --baik individu, kelompok, maupun masyarakat-- serta perubahan
konteks waktu dan tempat. Dengan kata lain, kebenaran hakiki pragmatisme baru dapat dibuktikan --
menurut pragmatisme itu sendiri-- setelah melalui pengujian kepada seluruh manusia dalam seluruh
waktu dan tempat. Ini jelas mustahil dan tidak akan pernah terjadi. Pragmatisme berarti telah
menjelaskan inkonsistensi internal yang dikandungnya dan menafikan dirinya sendiri.
5. Budaya Politik Dan Masyarakat Pragmatis Di Indonesia
Bila kita telaah lebih jauh lagi, maka kita dapat menggambarkan budaya politik di Indonesia
saat ini sebagai berikut: (1). Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak
sekompleks yang dihadapi oleh India misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama,
kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan, (2). Budaya politik Indonesia yang bersifat
Parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu sisi masih ketinggalan
dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin di sebabkan
oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial.
Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen
kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu; puritanisme
dan non puritanisme dan lain-lain. Kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih bersifat
paternalisme dan patrimonial, hal ini masih tercermin dengan berkembangnya fenomena bapakisme
atau sikap asal bapak senang, dan (3). Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala
konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.
Selain ketiga hal gambaran budaya politik di tanah air, kita juga dapat mendeskripsikan
realitas budaya politik masyarakat: (1). Hirarki yang tegar/ketat. Masyarakat Jawa, dan sebagian besar
masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini
tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa dengan rakyat kebanyakan (wong cilik). Masing-
masing terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tatacara sopan santun
diekspresikan sedemikian rupa sesuai dengan asal usul kelas masing-masing. Penguasa dapat
menggunakan bahasa 'kasar' kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan
diri kepada penguasa dalam bahasa 'halus'. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial
semacam itu antara lain tercemin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya, (2).
Kecendrungan Patronage. Pola hubungan Patronage merupakan salah satu budaya politik yang
menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya
budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih
mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya, dan (3). Kecendrungan Neo-
patrimonisalistik. Salah satu kecendrungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya
kecendrungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun
memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih
memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.
Laswell telah menanamkan pengertian yang paling pragmatis atas politik, siapa dapat apa,
kapan, dan bagaimana. Apa yang dilontarkannya itu sangat mudah dipahami, bahwa memang
demikianlah politik. Akar konfrontasi, dari kacamata Laswell, terjadi ketika definisi tersebut
diterapkan dan mengundang ketidakpuasan dari para pelaku kunci politik. Pengertian ”mendapatkan
sesuatu”, bukan berarti yang bersifat fisik, seperti uang atau materi lain, tetapi, tentu juga yang non-
material, seperti ideologi, kedudukan, harga diri, dan gengsi. Di dalam ”mendapatkan sesuatu”, semua
kekuatan politik saling bersaing di dalam suatu arena permainan politik.
”All my games,” Kata Indira Gandhi, Perdana Menteri perempuan India pada masanya.
Politisi mestinya sadar, sejak awal politik adalah juga merupakan suatu permainan, tak sekadar adu
ketangkasan, tetapi lebih dari itu adalah adu kekuatan. Pendekatannya, bisa secara keras (dominatif)
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
24 Jurnal Lugas P-ISSN 2580-8338
Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 – 26 E-ISSN 2621-1564
atau sebaliknya lembut (soft) atau hegemonik. Dalam menyerang dan bertahan secara politik, politisi
bisa bergaya seperti apakah Mohammad Ali ataukah Mike Tyson dalam bertinju.
Politik tidak semata-mata identik dengan adu kekuatan. Politik juga banyak dibahas dari sudut
pandang filsafatnya. Dari Aristoteles, misalnya, kita mengenal ungkapan zoon politicon, manusia pada
dasarnya merupakan ”seekor binatang politik”. Namun, Aristoteles tidak berpandangan negatif pada
politik, justru ia mendefinisikannya sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan
kebaikan bersama.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kebaikan bersama adalah pelaksanaan
pemilu langsung, yang pertama kali dilaksanakan masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno
Putri yang digelar “Orde Gotong Royong”. Pemilu langsung merupakan sejarah baru dalam
perpolitikan Indonesia dan terutama bagi para pemilih. Pasalnya, baru pertama kali dilaksanakan
dalam sistem pelaksanaan yang berbeda dengan sistem Pemilu-Pemilu sebelumnya. Yang selanjutnya
pelaksanaan pemilihan langsung untuk memilih pemimpin dilanjutkan pada pemilihan gubernur, wali
kota dan bupati karena sebelumnya gubernur, walikota dan bupati terpilih dengan sistem perwakilan
yang lebih banyak kelemahan dari pada kelebihannya, misalnya adanya politik dagang sapi dan
politik uang, pemimpin terpilih tidak memiliki legitimasi yang kuat karena kriterianya tidak sesuai
dengan keinginan masyarakat, pemimpin terpilih “berhutang budi” pada partai politik sehingga sistem
check and balance antara legislatif dan eksekutif tidak terjaga.
J.J.Rousseau mengungkapkan bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan, bukanlah
demokrasi sebenarnya, karena keinginan para wakil rakyat (Will of the few) bukanlah keinginan
rakyat. Peringatan Rousseau semakin memperkuat posisi suara rakyat yang selama ini lebih banyak
dijadikan sebagai pelengkap penderita.
Sejak tahun 2005 ketika pilkada langsung pertama kali dilakukan sampai sekarang, puluhan
kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) telah menjadi terpidana kasus korupsi. Melihat fenomena
ini, tidak mengherankan jika menghitung ongkos politik yang harus dikeluarkan pasangan calon
kepala daerah menjadi sangat tinggi. Selain harus membayar mahar kepada partai politik yang
mengusung dalam pilkada, mereka juga harus ”mengamankan suara” dan “mengamankan
kemenangan” dengan segala cara. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah mengatakan
bahwa besarnya jumlah dana yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi kepala daerah
(bupati/wali kota sekitar Rp 5 miliar, gubernur sekitar Rp 20 miliar). Dana sebesar itu agak mustahil
dapat diperoleh kembali dari gaji yang diterima, bahkan selama lima tahun karena Gaji bupati Rp 6,2
juta, sementara gubernur Rp 8,7 juta.
Masyarakat memandang Pilkada adalah sebagai sebuah proyek yang sangat menguntungkan
tanpa berpikir bagaimana kualitas dari proses dan hasil pilkada, sehingga yang terjadi saat ini
masyarakat kita sudah menjadi “mata duitan”. Namun, dengan melihat berbagai fenomena dalam
pelaksanaan pilkada di daerah tidak berarti sistem pemilihan harus dikembalikan ke sistem perwakilan
karena hal itu bukan solusi yang terbaik dan membuat kita semakin mundur. Descartes pada saat
melakukan rekonstruksi filsafat, langkah pertama yang dia lakukan secara teoritis adalah membuang
sikap skeptis. Yang dilakukan, ia mencari air mancur yang lebih alami dari prinsip-prinsip sejati, dan
menemukannya dalam pikiran manusia; Kesadaran diri untuk mendapatkan kebenaran dasar, dan
untuk memutuskan apa yang menyenangkan.
Mencermati pergeseran perilaku politik seseorang atau kelompok yang “suka duit” dapat
dilihat pada dua model analisis teori tentang perilaku pemilih, yang selama ini berkembang di
Indonesia. Pertama, Geertz yang melihat pola perilaku politik dengan orientasi sosio-religius santri
dan abangan. Kedua, model Jackson yang melihat faktor pola hubungan antara pemimpin dan pengikut
dalam perilaku politik.
Dengan demikian, tingkah laku politik tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan faktor-faktor
lain yang melekat dalam suatu sistem politik. Ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh.
Pertama, kekuasaan yakni cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain melalui sumber-
sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat itu. Kedua, kelompok yakni tujuan-tujuan
dikejar oleh perilaku-perilaku atau kelompok politik. Ketiga, kebijakan yakni hasil dari interaksi
antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan. Keempat budaya
politik yakni orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.
Terjadinya pergeseran dalam perilaku pemilih yang “suka duit” tidak semata-mata karena
persoalan pada sistem pemilihannya tetapi banyak faktor yang harus dibenahi terutama bagaimana
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
P-ISSN 2580-8338 Jurnal Lugas 25
E-ISSN 2621-1564 Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 - 26
memperbaki kualitas pendidikan politik masyarakat yang merupakan akar dari permasalahan
tersebut. Oleh sebab itu yang paling bertanggungjawab dalam hal tersebut adalah para pakar politik,
lembaga-lembaga masyarakat yang berfokus pada polling pendapat, partai-partai politik, organisasi
masyarakat dan pihak pemerintah. Mereka harus lebih intensif dalam menyosialisasikan tema
“Berpolitik Yang Beretika” apakah dalam bentuk seminar, panel diskusi, simposium, dialog interaktif
di TV, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori oleh pemerintah, agar nantinya masyarakat punya
bahan-bahan masukan yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam berdiskusi diantara mereka dan
bukan lagi didasari oleh rasa dendam dari prilaku-prilaku pemimpin sebelumnya dan saat ini, jadi
semuanya didasarkan atas pertimbangan yang ilmiah dan asas manfaat.
Merujuk pada realitas yang ada, budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini
adalah budaya politik yang lebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit
politik. Budaya seperti itu telah membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik.
Walaupun struktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satu
ke era selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya.
Menurut Karl D. Jackson (1978 : 23), budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar
dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia. Relasi antara pemimpin dan
pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien (bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi
individu yang berkembang untuk meraih kekuasaan dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan
elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Dwiyanto dkk (2002 : 71) mengenai kinerja
birokrasi di beberapa daerah, bahwa birokrasi publik masih mempersepsikan dirinya sebagai penguasa
daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
perilaku para pejabat dan elit politik yang lebih memperjuangkan kepentingan kelompoknya
dibandingkan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejar status
dibandingkan dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun1998 telah memberikan sumbangan bagi
berkembangnya budaya poltik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan
otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elit politik dan penyelenggara
pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai peduli dengan input-input politik,
akan tetapi tidak diimbangi dengan para elit politik karena mereka masih memiliki mentalitas budaya
politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik
subjek-partisipan.
Dalam pandangan Ignas Kleden, terdapat lima preposisi tentang perubahan politik dan budaya
politik yang berlangsung sejak reformasi 1998, antara lain: (1). Orientasi Terhadap kekuasaan,
Misalnya saja dalam partai politik, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai
politik telah membuat partai-partai politik era reformasi lebih bersifat pragmatis, (2). Politik mikro vs
politik makro, Politik Indonesia sebagian besar lebih berkutat pada politik mikro yang terbatas pada
hubungan-hubungan antara aktor-aktor politik, yang terbatas pada tukar-menukar kepentingan politik.
Sedangkan pada politik makro tidak terlalu diperhatikan dimana merupakan tempat terjadinya tukar-
menukar kekuatan-kekuatan sosial seperti negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil
society, dan sebagainya, (3). Kepentingan negara vs kepentingan masyarakat, Realitas politik
lebih berorientasi pada kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat, dan (4).
Desentralisasi politik, Pada kenyataannya yang terjadi bukanlah desentralisasi politik, melainkan
lebih pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan
demikian, budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorientasi pada kekuasaan
dan kekayaan, bersifat sangat paternalistik, dan pragmatis. Hal ini menurut Soetandyo Wignjosoebroto
karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya,
namun tidak pada budaya politik yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.
6. Simpulan
Budaya politik dalam masyarakat pragmatis telah menjadi realitas politik yang patut
dicermati. Aktivitas politik yang membutuhkan partisipasi masyarakat seakan mengalami benturan
manakala masyarakatnya bersifat pragmatis. Pola perilaku serba instan jelas mempengaruhi perilaku
politik baik di tingkat elit maupun masyarakat umumnya. Kemurnian dukungan dan lahirnya
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
26 Jurnal Lugas P-ISSN 2580-8338
Vol. 2, No. 1, Juni 2018, pp. 20 – 26 E-ISSN 2621-1564
pemimpin yang memiliki kepekaan sosial jelas sulit menjadi kenyataan manakala sindrom pragmatis
telah menjangkiti masyarakat secara keseluruhan.
Daftar Pustaka
1) Alfian. (1986). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama.
2) -------. (1991). Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama.
3) Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), (1991). Profil Budaya Politik Indonesia, Jakarta: PT
Pustaka Utama Grafiti.
4) Almond, Gabriel dan Sidney Verba, (1999). Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan
Demokrasi di Lima Negara, Penerjemah (Sahat Simamora), Jakarta : Bumi Aksara.
5) Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
6) Cangara, Hafied. (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
7) ------------------- (2011). Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta : Rajawali
Pers.
8) Dwiyanto, Agus, dkk, (2002). Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta : Pusat
Studi Kependudukan dan Kebijakan Yogyakarta.
9) Effendy, Onong Uchjana. (2003). Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya
Bakti.
10) Jackson, Karl D, 1978. The Political Implications of Structure and Culture in Indonesia,
California : University of California.
11) McNair, Brian. (2011). An Introduction to Political Communication, USA : Routledge.
12) Nimmo, Dan. (1982). Komunikasi Politik. Bandung : Remaja Rosda Karya.
13) Pabottinggi, Mochtar. (1993). Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik, Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
14) Rauf, Maswadi. (1993). Indonesia dan Komunikasi Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
15) Ryass, Muhammad, 2000. Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan,
Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya.
16) Siregar, Amir Efendi (ed.), 1991. Arus Pemikiran Ekonomi Politik : Esai-Esai Terpilih,
Yogyakarta : Tiara Wacana.
17) Surbakti, Ramlan. (2007). Memahami Ilmu Politik, Jakarta : PT Grasindo.
18) T. May Rudy. (2003). Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya,
Bandung : PT Refika Aditama.
19) Toha, Miftah. (2007). Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Sumartono (Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis)
Anda mungkin juga menyukai
- SK Pemenang Osn 2020Dokumen3 halamanSK Pemenang Osn 2020MUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Undangan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1444 H Masjid Baitul GhafurDokumen10 halamanUndangan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw 1444 H Masjid Baitul GhafurMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Undangan Lauching Dan Bimtek Srikandi Kabupaten Barito UtaraDokumen2 halamanUndangan Lauching Dan Bimtek Srikandi Kabupaten Barito UtaraMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- SE Bupati 2023 Tentang TNDDokumen10 halamanSE Bupati 2023 Tentang TNDMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- FPKD - Kab. BarutDokumen6 halamanFPKD - Kab. BarutMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Pengumuman CASN 2022 TEKNISDokumen17 halamanPengumuman CASN 2022 TEKNISMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Maulid Nabi Muhammad Saw 1444 H SMKN-1 Gunung TimangDokumen1 halamanMaulid Nabi Muhammad Saw 1444 H SMKN-1 Gunung TimangMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Surat Edaran PPK 2023Dokumen2 halamanSurat Edaran PPK 2023MUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Kalender Pendidikan 2019-2020Dokumen1 halamanKalender Pendidikan 2019-2020MUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Maulid Nabi Muhammad SawDokumen1 halamanMaulid Nabi Muhammad SawMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Nordiansyah, S.PDDokumen2 halamanNordiansyah, S.PDMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Surat Persiapan Pendataan Peserta UjianDokumen2 halamanSurat Persiapan Pendataan Peserta UjianMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Surat PersetujuanDokumen2 halamanSurat PersetujuanMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Undangan Roadmap Kab KotaDokumen4 halamanUndangan Roadmap Kab KotaMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- Surat Permohonan PengawasDokumen1 halamanSurat Permohonan PengawasMUHAMMAD HELMI GUNTAR100% (1)
- Praktek OtkpDokumen3 halamanPraktek OtkpMUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat
- ACC Sesditjen - 2020-05-05 PENGANTAR SES KE DINAS-v2Dokumen1 halamanACC Sesditjen - 2020-05-05 PENGANTAR SES KE DINAS-v2MUHAMMAD HELMI GUNTARBelum ada peringkat