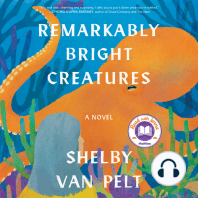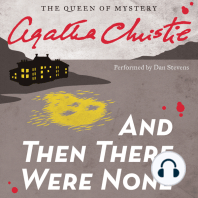Sumpah Pemuda Dan Taubat Literasi-Khairul Amin
Diunggah oleh
Nur Safitri0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
6 tayangan3 halamanJudul Asli
SUMPAH PEMUDA DAN TAUBAT LITERASI-KHAIRUL AMIN
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
6 tayangan3 halamanSumpah Pemuda Dan Taubat Literasi-Khairul Amin
Diunggah oleh
Nur SafitriHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
SUMPAH PEMUDA DAN TAUBAT LITERASI
Oleh
Khairul Amin*
Tepat 28 Oktober kemarin, kita merayakan peringatan 90 tahun Sumpah
Pemuda. Momen bersejarah tersebut merupakan tonggak persatuan pemuda secara
nasional. Diversitas secara simbolik disatukan dalam bingkai kebangsaan. Soal utama
lain ialah bahasa, sebab kesepakatan terhadap lingua franca dalam komunikasi suatu
masyarakat adalah tolak ukur yang asasi. Sejak 1928, masyarakat nusantara mulai
mengorbitkan dan menyiarkan seluas-luasnya penggunaan istilah Indonesia
menggantikan Hindia Belanda, seperti Perhimpunan Indonesia yang digagas oleh
Muhammad Hatta dan kawan seperjuangannya di Belanda.
Sejak itu muncul berbagai karya jurnalistik dalam bahasa Indonesia, utamanya
sejumlah surat kabar dan majalah (Fikiran Rakyat, Bintang Timur, Tjahaja,
Perantaraan, dan lainnya). Inisiatornya ialah gerakan pemuda terpelajar. Namun, tentu
saat itu tingkat literasi secara umum, belumlah mapan atau minimal terfasilitasi seperti
sekarang, sehingga kegiatan dan produk literasi tidak semasif hari ini. Disisi lain buta
huruf juga masih merajalela dan baca tulis masih menjadi kegiatan yang cukup langka.
Tidak mengherankan agenda besar pasca kemerdekaan adalah pemberantasan buta
huruf dan pengajaran tulis-menulis. Hal ini pula sejalan dengan amanat UUD 1945,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang secara substansial tidak jauh
berbeda, yaitu secara umum tingkat literasi rendah. Hal tersebut diindikasikan dengan
tingkat literasi rendah ditengah fasilitas yang sebenarnya cukup memadai. Perpustakaan
fisik maupun non-fisik telah tersedia secara luas. Namun tetap saja literasi kita
memprihatinkan, padahal kemajuan kegiatan literasi adalah bentuk kemajuan
peradaban, disamping ketangguhan militer dan stabilitas ekonomi, sebut Arnold J.
Toynbee dalam Mankind and Mother Earth : A Narrative History of The World .
Sebuah penelitian tingkat literasi oleh Central Connecticut State Univesity
bertemakan Most Littered Nation In the World, Indonesia menempati urutan ke 60 dari
61 negara dengan indeks hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia hanya satu
orang yang rajin membaca. Produktifitas karya literasi juga tidak jauh berbeda.
Indonesia rata-rata hanya mampu menghasilkan 18 ribu judul buku pertahun. Jepang
yang lebih sedikit populasinya, termasuk kuantitas generasi mudanya, ada diangka 40
ribu judul per tahun. Singkatnya, hasil penelitian ini menunjukkan mental literasi kita
bermasalah.
Walaupun zaman pra dan awal kemerdekaan tingkat literasi rendah secara
umum, sepatutnya kita harus berkaca dan merenung, lebihnya jika dikomparasikan
dengan keadaan hari ini. Pada keadaan fasilitas yang terbatas, perdebatan dan dialog
serta adu gagasan para pendiri bangsa berada level high-class. Apabila menyebut
Soekarno, Tan Malaka, Hatta, M.Natsir, Agus Salim, dan lainnya, maka kita akan dapati
narasi sejarah yang penuh dengan gagasan bernilai dan otentik. Pikiran bermutu hasil
dari tingkat literasi yang tinggi.
Melihat kondisi ini, maka taubat literasi wajib hukumnya, utamanya generasi
muda. Jika tidak, kemungkinan karamnya kapal bernama Indonesia akan terbuka atau
setidak-tidaknya akan menjadi objek bajakan bagi kapal lainnya. Jika Soekarno dan
angkatan awal sudah merintisnya dengan luarbiasa, maka tugas penerus adalah
mengembangkan dan mengokohkannya serta memastikannya agar mampu berlayar ke
arah yang benar. Pada kondisi ini, literasi ibarat sebagai alat bantu untuk mengetahui
cuaca, arah angin, kelembaban udara, gugusan bintang, dan sebagainya. Apabila literasi
kita gagal atau setidaknya rendah, tugas tersebut tidak akan berjalan dengan baik,
terlebih pada masa sekarang, yaitu masa revolusi informasi. Pada masa ini, peradaban
tuna literasi adalah peradaban yang akan takluk dan akan kalah bersaing.
Dalam The Third Wave, Alvin Toffler mengisyaratkan dunia akan menghadapi
gelombang ketiga. Karakteristik gelombang ini sangat berbeda dari 2 gelombang
sebelumnya. Jika gelombang pertama dan kedua bersifat fisik, touchtable (tersentuh),
serta predictable (terprediksi), maka gelombang ketiga bersifat non-fisik, untouchtable
(tidak tersentuh), dan random (acak). Singkatnya, revolusi informasi akan sangat
berbeda dari revolusi agraria dan industri, sebab penopang utamanya adalah revolusi
digital.
Revolusi digital meniscayakan arus informasi dengan sangat cepat, bahkan saat
informasi masih belum terjadi atau sedang terjadi (status quo) atau live. Perihal
demikian dapat mengubah cara pandang, sebab bagaimanapun, sumber informasi tidak
mesti didapat secara langsung baik sebagai pelaku, saksi, atau korban pertama, tetapi
melewati media sehingga rawan keluar dari konteks dan ter-framing. Hal ini
memunculkan peluang kegiatan provokasi, agitasi, distorsi, serta manipulasi dengan
probabilitas tinggi. Hasilnya sukar sekali menilai sebuah informasi. Hal ini pula
berakibat pada sulitnya mengambil tindakan secara tepat dan cepat, padahal disaat yang
sama dalam kondisi menekan untuk segera merespon. Sederhananya, jika dulu kita
mencari kebenaran dengan meniti sungai, maka hari ini kita harus menceburkan diri
untuk menemukannya.
Media (medium) memainkan posisi vital dalam revolusi informasi. Baik media
mainstream ataupun sosial, memberikan dampak yang luarbiasa pada status quo. Arah
implikasi nantinya bergantung pada pengguna media. Terkhusus media sosial, potensi
tantangannya akan lebih tidak terkendali. Secara umum media mainstream lebih
professional dalam menyajikan informasi, sebab berada di bawah kode etik jurnalistik,
lain halnya dengan sosial media. Sebagai media civil society, ia menjadi tempat
berekspresi individu-individu sipil, baik akun tersebut merupakan identitas
terkonfirmasi atau tidak. Maka, tidak heran perspektif atau framing lebih beragam
sekaligus liar dan tidak terkendali. Jika kita tidak siap dalam mengarungi samudera
revolusi informasi ini, maka kita akan menjadi korban ombak dan badainya.
Terkhusus generasi muda yang lahir periode 1990 an ke-atas (millenial), gagal
menghadapi revolusi informasi berarti rawan terhadap pada mis-konsepsi, mis-
interpretasi, sikap reaktif (sumbu pendek), dan ketidakmampuan menghadirkan solusi.
Sebagai contoh nyatanya adalah maraknya hoax dan ujaran kebencian di media sosial
hari ini. Sebagai perangkat menyuarakan suara di ruang publik, seharusnya yang keluar
adalah gagasan bermutu, bernilai, konstruktif, solutif, dan beradab. Namun sebab
literasi rendah, kejernihan logika dan legal reasoning tidak berjalan baik. Hasilnya
lahirlah masyarakat reaktif dan kagetan yang nir-solusi.
Sebagai penutup, sekali lagi kita harus muhasabah dan perlu segara taubat
literasi. Sudah terlalu banyak indikasi yang memperlihatkan bahwa kita tidak siap
menghadapi arus revolusi informasi ini. Sebelum benar-benar terlambat, kita harus
bertaubat, utamanya pemuda, lebih-lebih bagi pemuda pengguna perangkat elektronik
(gadget). Pikiran-pikiran pendiri bangsa kita lahir dari membaca, tetapi bukan sekedar
membaca WA, Facebook, ataupun Twitter. Kegiatan membaca serius meniscayakan
diskusi dan diskusi meniscayakan pertemuan gagasan, sedangkan pertemuan gagasan
adalah cikal bakal peradaban. Segera luangkan waktu untuk bercengkrama dengan
buku. Jadikanlah nongkrong (diskusi) di perpustakaan sebagai budaya. Buatlah status
yang bermanfaat jika ber-sosmed ria. Jika dulu Bung Hatta membawa 16 peti buku saat
diasingkan ke Banda Neira, kini apa yang para pemuda bawa? Jangan sampai hanya
sebatang gadget yang berisikan aplikasi sosial media dan selusin game yang
menghabiskan kuota. Bertaubatlah wahai generasi muda!. Tegakkanlah kembali
semangat ikrar sumpah pemuda, sebelum masa penyesalan tiba.
*Pegiat Literasi, Pengajar di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyyah Yogyakarta
Anda mungkin juga menyukai
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20025)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5795)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12947)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3278)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDari EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2507)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDari EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2499)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5509)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1108)












![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)