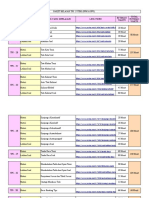Triratna - 12ipa5 - Bindo - Cerita Sejarah
Diunggah oleh
Jeollyfish0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan10 halamanCerita Sejarah: Rukmini Chaimin dan Pierre Tendean
Judul Asli
TRIRATNA_12IPA5_BINDO_CERITA SEJARAH
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniCerita Sejarah: Rukmini Chaimin dan Pierre Tendean
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan10 halamanTriratna - 12ipa5 - Bindo - Cerita Sejarah
Diunggah oleh
JeollyfishCerita Sejarah: Rukmini Chaimin dan Pierre Tendean
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 10
Sore ini aku kembali menyesap secangkir teh hangat
yang Ambar−putri sulungku−buat. Rasanya tidak lagi sama,
tidak akan pernah sama dan mau dikatakan apa pun lagi rasa
teh ini tidak akan pernah sama lagi. Di tengah rasa manis dan
hangat dari teh tubruk ini ditambah riuh dan gaduh sorai anak-
anak tetangga yang dititah Ibunya pulang ke rumah, Ambar
kembali menatapku dengan tatapan penuh isyarat tanda
tanya. Aku menyadari ada hal yang ingin dia tanyakan ke
padaku tapi tidak pernah aku selesaikan rasa penasarannya
barang satu kalimat pun.
“Ada yang mau kau tanyakan ke padaku Ambar?”
Kulihat Ambar seketika gelagapan menanggapi
pertanyaanku. “Tidak Bu, tidak ada.”
“Aku pernah mengandungmu sembilan bulan Nak,
membesarkanmu dengan kedua tanganku sendiri, aku dapat
melihat meski hanya dari sorot matamu saja ada sebuah hal
ganjil yang mengganjal betul?”
Ambar meletakkan cangkir tehnya ke meja dan
membuat postur tidak nyaman menghadapku. “Bu, ah tidak
lupakan saja. Ambar tidak jadi bertanya Bu maaf.”
Aku tersenyum, “Kau pasti mau tanyakan lagi soal dia
iya kan?”
“Dia?”
“Maafkan Ibu Mbar, Ibu tau kau sudah cukup dewasa
untuk mendengar kisah ini, tetapi Ibu tidak pernah sanggup
untuk mengingatnya lagi setelah sekian lama. Cukup hadir
Ayah dan saudara-saudaramu yang selama ini menjadi pelipur
lara, Ibu sebetulnya juga ingin melupakan dia Mbar tapi
belakangan ayahmu selalu mengungkit hal itu. Ayahmu
membuat luka-luka yang sudah kering di hati Ibu kembali
basah dan perih dan Ibu cukup tahu diri akan hal itu. Semua
memang salah Ibu sejak awal.”
“Tidak Bu. Tidak ada manusia yang bangkit hanya dari
kebenaran, harus ada salah supaya manusia bisa tumbuh
menjadi lebih baik. Itu adalah hal yang selalu Ibu katakan ke
pada Ambar.”
Kemudian, di sisa sore itu aku bercerita ke pada
Ambar tentang sosok yang bagai pasir ditelan ombak
laut−datang lalu pergi membawa separuh hatiku yang rapuh.
Tahun itu 1960, aku masih belia. Tamat menyelesaikan
pendidikan di sekolah menengah ketika di sore hari beranda
rumah gaduh oleh beberapa pria paruh baya yang kuyakini
adalah teman karib ayah. Ibu mengatakan padaku untuk
berias dengan sempurna dan segera menyambut beberapa
tamu di depan, katanya itu adalah kedatangan mendadak
tidak bisa salahkan siapa pun ketika aku merenggut sebal
dipaksa ini dan itu oleh Ibu.
Setelah selesai berias dan menggunakan baju yang
tentu saja Ibu pilihkan, aku dan Ibu akhirnya bergabung
bersama para tamu. Kau tahu? Rasanya tidak nyaman ketika
banyak orang melihatmu dengan tatapan yang bahkan tidak
bisa kau artikan, ketika teman-teman ayah bertanya ini dan itu
perihal diriku aku berani bersumpah rasanya tidak nyaman.
Sangat.
Lalu, seorang pria dengan tembakau di bilah bibirnya
kembali mengembuskan kepulan asap nikotin ke udara dan
berusaha membuat keadaan canggung di antara yang lain
menjadi lebih sedikit akrab, “Ruk pantas saja wajahmu itu
makin lama dipandang makin elok kelihatannya dengan begitu
aku tidak akan lagi heran mengapa banyak orang mengantre
untuk segera jadi pendampingmu.”
“Sembarangan, kau pikir sajalah memangnya anakku
ini jatah ransumtah? Kau sebut orang mengantre? Seharusnya
itu melamar wahai Pak Tua!” Ayahku meski melontarkan
kalimat dengan nada tinggi, aku tahu dia tidak benar-benar
marah justru senang dengan kenyataan yang pria itu bilang
tentang banyak orang yang mau jadi pendampingku.
Pria yang tidak aku ketahui namanya itu kemudian
balas tertawa remeh, “Kau tahu maksud aku yang sebenarnya
Chaimin dan itulah yang menjadi alasanku datang kemari sore-
sore.”
Aku tertegun. Jelas. Apa katanya? Alasan? Alasan apa
sebenarnya? Mengapa mendadak aku menjadi manusia paling
bodoh di tengah percakapan ini? Aku menatap Ibu meminta
penjelasan dibalik kedatangan para tamu tapi Ibu hanya balas
tersenyum ke padaku dan mengusap rambut belakangku
dengan lembut, tetapi aku tidak merasakan kehangatan
ataupun di balik lembutnya belaian Ibu melainkan rasa cemas
dan gemetar. Aku baru 18 dan aku tidak mau dijodohkan oleh
siapa pun. Sungguh.
Ayah kembali mengangkat cangkir tehnya
menyesapnya sebentar kemudian balas tertawa singkat, “Lalu
di mana keponakan yang katamu hendak diperkenalkan?”
“Hey tunggulah sebentar lagi, si Tendean itu
belakangan ini tengah menjadi orang sIbuk. Aku, pamannya
pun kadang heran apa saja yang dilakukannya seharian sampai
lupa menikah di usianya yang ke-28 ini.” Pria tua itu telah
kehabisan tembakaunya yang pertama dan kini bersiap untuk
membakar yang satunya lagi.
Aku benar-benar meremas samping Ibu menuntut
sebuah penjelasan dan berakhir dengan Ibu yang
membungkuk sopan di hadapan para tamu dan membawaku
masuk ke area rumah yang lebih dalam.
“Sebenarnya ada apa Bu? Kalau itu soal perjodohan
Ruk tidak mau dijodohkan dengan siapa pun, dari awal Ibu dan
Ayah pun sudah setuju untuk tidak melakukan hal semacam
itu dengan tanpa persetujuan Ruk. Lalu ini apa Bu?” Aku
bersungut-sungut sebal di hadapan Ibu, tidak habis pikir
tentang kejadian beberapa menit lalu. Memangnya semalam
aku mimpi apa? Aku tidak pernah bermimpi seorang pria yang
tidak pernah aku kenal sebelumnya mendadak jadi
pendampingku di sisa hidup yang terbatas ini, aku hanya
bermimpi untuk segera pergi ke Batavia merajut mimpi-mimpi
dan menjadi wanita yang hebat. Hal semacam ini tidak pernah
terlintas di benakku barang sedetik pun. Sungguh.
“Ibu akan ceritakan semuanya Ruk,”
“Tentu saja harus Ibu ceritakan. Semuanya!”
“Iya Ibu mengerti untuk itu anak gadis ibu yang baik
hatinya ini harus duduk dan menenangkan dirinya terlebih
dahulu baru Ibu siap menceritakannya untukmu.”
Aku mengatur napasku dan membuat bahu ini lebih
nyaman meski sebal dan marah masih bercampur-campur.
“Sudah Bu, sekarang ceritakan tolong.”
“Namanya Tendean. Kau sudah tahu umurnya 28
tahun dan Ibu kira itu tidak terlalu tua malah menjadi umur
yang pas untuk melengkapi sisi kekanak-kanakanmu itu.”
“Maksud Ibu apa sebenarnya?” Habis sudah
kesabaranku. Aku berdiri dan karena suaraku yang keras tadi
Ibu menarik pergelangan tanganku dan membuat isyarat
dengan telunjuknya untuk segera diam. Aku makin gusar.
“Ibu tahu kau tidak pernah suka dengan hal semacam
ini tapi untuk hal ini berbeda Ruk. Tendean sudah matang
usianya, bibit, bebet, dan bobotnya tidak perlu kau ragukan
lagi. Dia baik hati Ruk dan tidak gemar main-main dengan para
wanita. Ibu percaya kau akan bahagia jika dengannya.”
“Tapi Ibu dan Ayah sudah setuju untuk tidak
menjodohkanku dengan siapa pun. Ibu dan Ayah berjanji
untuk menyekolahkanku lebih tinggi ke Batavia, Ibu dan Ayah
setuju untuk membuatku menjadi wanita yang lebih
bermatabat. Lalu sekarang apa Bu? Mana janji itu?” Aku
merengek ke pada ibu disusul air mata yang tanpa permisi
mengalir bebas di pipiku.
Ibu memelukku membisikan berbagai macam kata
manis yang artinya tetap sama bagiku. Tidak apa-apa untuk
menikah dengan Tendean sekarang kau akan punya hidup
yang lebih baik. Sial. Aku benar-benar tidak mau menikah
sekarang.
“Tendean orang baik Nak, Ibu tidak mungkin tega
membiarkan anak gadisnya hidup bersama orang yang tidak
tepat. Kau akan segera menyukainya, dia akan sampai
beberapa jam lagi kau harus lihat dengan mata kepalamu
sendiri dan kau akan segera jatuh cinta padanya.”
Pukul empat di hari yang sama. Dia, Tendean pun
akhirnya datang. Ayah memanggil namaku dengan lantang
nada bicaranya kedengaran amat bahagia dan sekali lagi aku
benar-benar merasa dikhianati oleh kedua orangtuaku sendiri.
“Ruk cepat ke sini! Lihatlah siapa yang datang.”
Hal pertama yang membuat aku terkejut adalah
perawakan Tendean. Tubuhnya tidak seperti kebanyakan
pribumi yang mempunyai mata besar, hidung pesek, dan
tinggi rata-rata. Jauh dari bayanganku Tendean benar-benar
seorang pria yang menjadi khayalanku selama ini. Dia asing.
Tidak maksudku dia benar-benar orang asing tapi dia fasih
berbahasa Indonesia bagaimana bisa? Dia duduk di kursi yang
ada di seberangku, tersenyum simpul dan singkat sekali. Arah
matanya tidak pernah mengarah ke mataku, padahal netra ini
tidak bisa lepas dari rupanya. Untuk pertama kalinya dalam
hidupku aku diacuhkan oleh seorang pria bagaimana bisa?
“Apa kalian tidak akan berkenalan? Padahal sudah
sedekat ini apa tidak ada yang akan memulai terlebih dahulu?”
Itu suara Ayah dan aku sama sekali tidak berminat untuk
mengikuti usulannya.
Tanpa aku duga Tendean berdiri duluan dan membuat
postur tubuh khas orang yang ingin menjabat tangan. Mau
tidak mau aku membalasnya. Dia tersenyum. Aku masih kaget
ketika tangannya yang lembut tidak seperti kebanyakan lelaki
yang aku temui. Telapak tangannya yang lebar seolah-olah
membungkus tanganku yang tidak seberapa. Aku balas
tersenyum meski kaku dan dari sanalah untuk pertama kalinya
aku mengenal Tendean. Mata safir yang hingga kini berbayang
di benakku.
“Pierre Tendean. Kamu boleh memanggil saya
Tendean.”
“Rukmini.”
Hari demi hari. Aku tidak pernah membayangkan hal
ini sebelumnya. Tahun 1965, aku 23 tahun dan dia 33 tahun.
Aku pernah bermimpi untuk menjadi seseorang yang besar.
Kau tahu? Maksudku ketika impian untuk tinggal di kota besar
dan merayakan mimpi-mimpi yang berhasil itu menjadi
kenyataan, itu adalah hal yang luar biasa bukan? Namun,
seketika mimpimu hancur, sayap-sayapmu patah dan kau
berpikir hidupmu usai. Kenyataannya? Tidak. Tendean pernah
datang menghancurkan sayapku lalu dia membuat sayap yang
baru. Dengan warna dan rupa yang tidak pernah aku
bayangkan sebelumnya. Hadirnya adalah riuh ramai dalam
hati yang sepi ini dan aku cukup senang dengan fakta soal
Tendean yang tidak pernah main wanita. Ibu benar. Tendean
orang yang baik.
Tendean dikenal sebagai seorang tentara yang dingin
dan tidak banyak bicara. Bagiku Tendean sesuatu yang lain, dia
kaku dan tampak tidak bisa bersosialisasi dengan banyak
orang. Agak pemalu dan sikapnya yang hati-hati selalu
membuatku tersanjung sebab ia tidak pernah sekali pun
berkata atau melakukan hal-hal tanpa persetujuan kami
berdua. Kini aku 23 tahun, bukan lagi remaja tanggung yang
ceroboh. Mengenal Tendean sekali dalam hidupku tidak
pernah menjadi hal yang buruk. Sungguh. Kali ini aku
bersungguh-sungguh.
Kami menjalani hubungan yang sulit tapi karenanya
aku dapat bertahan bertahun-tahun lamanya. Kami menjalani
hubungan jarak jauh karena pekerjaannya. Mulanya aku
memang kesal. Kesal kalau ada perempuan lain yang berniat
menggait Tendean, kesal kalau aku harus berlama-lama
menunggu hanya untuk bersua dengannya, dan kesal-kesal
yang lainnya. Tetapi Tendean meyakinkanku untuk tetap
seperti biasa, berkirim surat dan jangan kesal-kesal lagi dan
selama itu aku selalu menyimpan apik surat-suratnya. Tidak
pernah aku lupa untuk berbalas pesan dengannya. Kadang aku
mendapat balasan tujuh hari setelah surat yang aku kirim
sampai padanya, kadang lebih lama dari itu dua hingga tiga
bulan lamanya. Ketika hari-hari yang kunanti tiba, saat
Tendean akhirnya singgah di rumahku dan mencium kedua
tangan orangtuaku, aku akan senantiasa berdiri di balik pintu
tersenyum melihat kehadirannya kemudian dia akan balas
tersenyum hangat. Tahun-tahun yang luar biasa.
Di pertemuan itu Tendean kembali mengajakku
berkeliling kampung dengan sepede ontel tuanya. Aku akan
bercerita banyak soal rasa bosan yang aku alami selama
tanpanya dan dia akan membalas gerutuanku dengan tawa.
Sebal tapi sayang. Sayang kalau dia akan pergi lagi, sayang
kalau hari ini akan segera berlalu, dan sayang-sayang lainnya.
“Ruk,” dia berhenti mengayuh sepeda, “ada beberapa
hal yang harus kusampaikan padamu.”
“Apa?” Aku balas bertanya ke padanya.
“Tidak di sini. Kupikir mengantarmu ke rumah adalah
langkah yang lebih bagus kita akan bicara di beranda.”
“Apa itu Tendean? Kau makin membuatku
penasaran.”
Tendean tersenyum. Senyum yang bagiku asing. Tidak
seperti biasa dan ganjil. Kami bicara di beranda rumahku. Aku
harusnya sadar ketika nada bicaranya yang rendah dan
senyum-senyum yang dia buat tidak lagi membuatku merasa
nyaman, ada sesuatu yang akan terjadi.
“Ruk aku akan pergi lagi kau tahu itu.”
“Aku tahu. Kini berapa lama? Satu bulan? Dua bulan?”
“Tidak kali ini lebih lama.”
“Kau pernah tidak membalas surat-suratku lebih dari
dua bulan Tendean, aku cukup sabar untuk menunggumu
kembali pulang.”
“Enam bulan.”
“Apa?”
“Aku akan pergi enam bulan Ruk dan kali ini akan lebih
sulit untuk berbalas pesan lewat surat denganmu. Keadaan di
sana sedang kacau. Kacau sekali.”
Aku terdiam menatap sendal yang tengah kugunakan
saat itu. Tendean menggenggam tanganku dan membawa
mata ini ke kedalaman matanya yang biru.
“Aku tahu ini tidak pernah mudah untukmu Ruk.
Tentu ini tidak pernah mudah untukku juga. Aku janji akan
rajin mengirimi surat,”
“Kau selalu berjanji hal-hal yang sama Tendean.
Nyatanya aku yang terus mengirimi lebih dulu.”
“Kali ini tidak Ruk. Di bulan ketujuh aku akan
membawa sanak saudara ke rumahmu.”
Ada guratan halus yang kuyakini singgah di dahiku.
“Maksudmu?”
“Ruk saya benar-benar telah jatuh. Jatuh hati ke
padamu maksud saya. Jadi di bulan ketujuh itu saya akan
datang kembali dan kita akan akan menggelar sebuah pesta
kecil, di mana saya dan kamu akan tersenyum ketika sama-
sama memasangkan cincin pernikahan.”
Sore hari selalu membawa kejutan di hidupku.
Tendean benar-benar melamarku di hari itu dan dia berjanji
untuk segera pulang di bulan ketujuh. Aku menangis. Haru dan
rasa bahagia yang membuncah membuatku tidak kuasa untuk
tidak mendekapnya. Kami akan segera menikah.
Di bulan kelima tidak lagi ada surat yang datang ke
rumah. Semakin jarang dan aku mulai cemas dengan hal-hal
yang belum pasti. Aku rajin mengiriminya surat setiap minggu
tapi Tendean tidak lagi membalas surat-suratku. Di bulan
keenam surat yang kukirim dua bulan belakangan tidak juga
mendapat balasan darinya. Tidak ada lagi makanan kesukaan
sebab semua makanan kini rasanya hambar. Tendean
mungkin lupa atau terlalu sibuk dengan kegiatannya di sana.
Berkali-kali aku berusaha untuk tidak meneteskan air mata di
sisa sore hari, berkali-kali itu pula Ibu selalu datang dan
memelukku dengan kalimat-kalimat yang sama. Tendean
orang baik.
Aku pernah dengar sebuah kalimat yang sering
dilontarkan nenekku sebelum ajal menjemputnya. Dia selalu
bilang kalau hadirnya seseorang dengan kebaikan hati yang
mulia akan lebih cepat dipanggil oleh Tuhan sebab Dia tahu
kalau dunia bukan lagi tempat yang cocok untuk manusia
sebaik dirinya. Tendean pergi. Tidak ada pernikahan di bulan
ketujuh. Sore itu ketika Ibu memanggil namaku keras-keras
dari beranda rumah, aku tahu kalau ada surat dari Tendean
yang dikirim oleh Pos. Ketika aku melihat surat yang dipegang
Ibu, aku tahu itu bukan surat yang biasa Tendean kirim.
Tendean tidak pernah mengirimkan surat yang ukurannya
lebih lebar dari telapak tanganku dan yang ini berbeda.
Suratnya lebih besar dilapisi oleh map cokelat yang asing.
Tidak ada bau harum ketika aku membacanya, tidak juga
tanda tangan milik Tendean di akhir surat. Surat asing itu
mengabariku perihal kematian Tendean beserta sembilan
orang prajurit lainnya. Surat itu bilang Tendean pergi dengan
meninggalkan jasa yang amat bagi negara ini. Persetan. Aku
tidak peduli. Sekarang aku hanya ingin Tendean kembali
pulang tidak bisakah? Meski habis air mataku nyatanya dia
tidak pernah kembali, di bulan-bulan kedelapan, kesembilan,
kesepuluh, dan bulan-bulan lainnya. Aku sadar kalau
percakapan kami yang di beranda itu adalah percakapan
terkahir kami. Tapi rasanya tidak pernah semenyakitkan ini.
Sungguh. Aku tidak pernah tahu.
“Lalu Ibu menikah dengan Ayah begitu? Bagaimana bisa?”
“Ayahmu yang terbaik Ambar. Ibu tidak pernah bisa
melupakan Tendean, tetapi ayahmu selalu sabar ketika Ibu
kembali menangis di sisa sore. Dia selalu merangkul Ibu.
Namun, belakangan Ibu sadar tak selamanya Ayahmu sanggup
menerima istri yang menatapnya sebagai orang lain,”
kemudian aku merengkuh anak gadisku, mencium wangi
rambutnya yang tidak pernah berubah dan ia balas
memelukku dekat.
“Ayah akan selalu sabar menunggu Ibu. Tentu Ibu harus balas
mencintainya sama seperti Ayah yang mencintai Ibu dengan
sepenuh hati ya?”
Aku mengangguk. Anggukan yang pasti.
Anda mungkin juga menyukai
- Paket Belajar TPS 2 Utbk (PBM & Ppu)Dokumen3 halamanPaket Belajar TPS 2 Utbk (PBM & Ppu)JeollyfishBelum ada peringkat
- Materi Utbk Soshum (Printable)Dokumen10 halamanMateri Utbk Soshum (Printable)JeollyfishBelum ada peringkat
- Triratna - 12ipa5 - Prakarya - Rencana Proses Produksi Dan K3Dokumen1 halamanTriratna - 12ipa5 - Prakarya - Rencana Proses Produksi Dan K3JeollyfishBelum ada peringkat
- Triratna - 12ipa5 - Prakarya - Laporan Praktik WirausahaDokumen6 halamanTriratna - 12ipa5 - Prakarya - Laporan Praktik WirausahaJeollyfishBelum ada peringkat