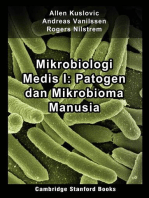Mauludina Zahroh - 2134008 - Essay Jiwa
Diunggah oleh
mauludina zahrrohJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Mauludina Zahroh - 2134008 - Essay Jiwa
Diunggah oleh
mauludina zahrrohHak Cipta:
Format Tersedia
ESSAY TENTANG DEPRESI DAN STIGMA NEGATIF PADA MASYARAKAT
YANG TERDIAGNOSA TUBERCULOSIS (TBC)
Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Keperawatan berbasis masyarakat pendekatan
keilmuan dasar dan komunitas dan jiwa
OLEH :
MAULUDINA ZAHROH
2134008
PROGRAM STUDI PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TAHUN 2021
ESSAY TENTANG DEPRESI DAN STIGMA NEGATIF PADA MASYARAKAT
YANG TERDIAGNOSA TUBERCULOSIS (TBC)
TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri penyebab TBC ini
umumnya menyerang paru-paru. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang
menempati urutan kedua di dunia sebagai penyakit infeksi dan jumlah individu yang sakit
akibat terinfeksi bakteri ini meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut menjadikan
tuberculosis sebagai masalah global dan menjadi salah satu agenda dari program Sustainable
Development Goals 2030, dengan target pada tahun 2030 dunia bebas dari penyakit ini.
Berdasarkan data dari WHO melalui Global Tuberculosis Report (2016) pada tahun 2015
terdapat 10,4 juta kasus tuberculosis diseluruh dunia. Jumlah tersebut meningkat dibanding
tahun 2014 dengan jumlah kasus 9.6 juta. Di Indonesia tuberkulosis paru merupakan
penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan, serta
menempati urutan pertama penyebab kematian untuk penyakit infeksi. Setiap tahunnya
ditemukan 61.000 kematian akibat penyakit ini (Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan data
Kemenkes RI (2015) tahun 2014 terdapat 460.000 kasus baru tuberkulosis paru pertahunnya,
dan jumlah ini meningkat ditahun 2015 menjadi satu juta kasus baru pertahunnya (kemenkes
RI, 2016). Kondisi ini menjadikan Indonesia berada di urutan kedua dengan jumlah kasus
tuberkulosis terbanyak setelah India, dan menyumbang 10% dari total kasus tuberkulosis di
dunia.
Penyakit TBC kerap dialami oleh mereka yang tinggal di lingkungan padat yang
seringkali terjadi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Sehingga sering muncul
anggapan bahwa TBC adalah penyakit orang dengan tingkat sosialekonomi rendah. Maka
lebih tepat dikatakan bahwa kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor yang mempermudah
penularan penyakit TBC. Sebab, kemiskinan menjadi hambatan bagi seseorang untuk bisa
membangun rumah yang sehat, yaitu dengan sanitasi air bersih yang cukup dan ventilasi serta
pencahayaan yang memadai. Meski demikian, tidak mudah mengubah stigma dan
diskriminasi terhadap pasien TBC karena pemahaman masyarakat mengenai penyakit ini
yang juga masih terbilang minim.
Secara spesifik, stigma terbagi menjadi stigma eksternal dan stigma internal atau biasa
dikenal dengan istilah stigma diri. Pasien TBC yang memiliki stigma diri cenderung memiliki
pikiran dan perasaan takut akan dihakimi oleh orang lain serta rasa malu dan bersalah
terhadap diri sendiri. Bila tidak diatasi, stigma diri dapat menyebabkan terisolasi dari
lingkungan sosial, ketidakpatuhan pasien untuk berobat, hingga tak jarang putus menjalani
pengobatan. Perlu dipahami bahwa TBC dapat disembuhkan melalui pengobatan rutin hingga
tuntas. Hanya saja, stigma dan diskriminasi pada pasien TBC dapat menjadi hambatan bagi
mereka untuk menjalani pengobatan. Maka, menjadi peran kita untuk mendukung mereka
yang terinfeksi, untuk dapat menjalani pengobatan hingga selesai tanpa ada stigma dan
diskriminasi.
Adaanya stigma negatif terhadap penyakit ini juga menambah depresi pasien.
Menurut Courthwright, dan Turner (2010) dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa
stigma negatif ini muncul karena adanya persepsi bahwa tuberkulosis adalah penyakit yang
sangat menular, berbahaya, kotor dan terkait dengan kemiskinan. Stigma negatif sangat
berpengaruh pada program pengobatan tuberkulosis paru.
Dalam jurnal yang berjudul The stigma of tuberculosis (Davis, & Juniati, 2010)
terdapat dua masalah utama dalam pengobatan tuberkulosis paru, yaitu keterlambatan dalam
pengobatan dan putus obat, salah satu penyebab dari masalah ini adalah adanya penghindaran
pasien tuberkulosis paru untuk berobat karena stigma negatif. Kondisi depresi akibat proses
penyakit tuberkulosis dan pengobatannya, serta stigma negatif terhadap penyakit tuberculosis
ini akan semakin memperberat kondisi pasien, baik fisik dan psikis. Kondisi fisik dan psikis
ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasien, karena keduanya merupakan domain
dari kualitas hidup (Nursalam, 2015), sehingga tidak jarang pasien dengan penyakit
tuberkulosis mempunyai nilai kualitas hidup yang rendah dikarenakan depresi yang dialami
pasien, serta diperberat denganstigma negatif terhadap penyakit. Kualitas hidup yang rendah
akibat adanya depresi dan sigma tentunya akan mempengaruhi bagaimana pasien tuberkulosis
paru menjalani proses penyakitnya serta proses pengobatannya yang secara keseluruhan akan
berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pengobatan.
Gangguan depresi pada penderita TB paru dapat timbul akibat berbagai faktor baik
internal maupun eksternal, seperti dukungan keluarga yang kurang, adanya halangan bagi
penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta halangan untuk berinteraksi dengan
masyarakat. Hal ini juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti adanya perasaan
menolak kenyataan mengenai penyakit TB paru dan akibat dari stigma masyarakat yang
negative mengenai tuberkulosis.
Pada beberapa orang yang mengalami atau menderita penyakit kronik seperti TBC
dan dengan pengobatan yang lama maka sangat mungkin penderita mengalami depresi maka
diperlukan pengobatan secara medis dan diperlukan dukungan social dari keluarga maupun
orang sekitar (Marselia, Wilson dan Pratiwi, 2017). Resiko depresi dapat diperburuk oleh
adanya masalah sosial ataupun hubungan dengan masyarakat dan buruknya tingkat kesehatan
yang dirasakan penderita. Depresi yang kebanyakan dialami oleh para penderita TBC
seringkali menyebabkan halangan dalam proses pengobatan. Salah satu penyebab terjadinya
depresi adalah karna banyaknya tiap obat yang dikonsumsi setiap hari serta terapi dalam
waktu lama dan kompleks, serta banyak stigma masyarakat menimbulkan potensi gejala
depresi (Muastaqin, Suryawati dan Priyanto, 2017). Pengobatan pada penyakit TBC
memerlukan waktu yang panjang. Pasien yang positif menderita TBC minimal harus
menjalani pengobatan selama enam bulan dan jika minum obat tidak teratur maka penyakit
TBC tidak akan sembuh bahkan menjadi lebih kuat (Putri, Kholis dan Ngestiningsih, 2018).
Beberapa program yang telah dikembangkan dan dilakukan oleh pemerintah belum
ada program yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikososial yang dihadapi penderita
TB paru, padahal dampak psikososial ini sangat besar pengaruhnya terhadap kepatuhan
berobat dan prognosa penyakit penderitanya. Dampak psikososial antara lain adalah adanya
masalah emosional berhubungan dengan penyakitnya seperti merasa bosan, kurang motivasi,
sampai kepada gangguan jiwa yang cukup serius seperti depresi berat. Masalah psikososial
lainnya adalah adanya stigma di masyarakat, merasa takut akan penyakitnya yang tidak dapat
disembuhkan, merasa dikucilkan dan tidak percaya diri, serta masalah ekonomi.
Bagi penderita yang mengalami depresi dan putus asa terhadap penyakitnya, mereka
tidak mau minum obat, resikonya adalah penderita tidak sembuh dan tentu akan menularkan
penyakit mereka pada orang lain disekitarnya. Pada penelitian kami sebelumnya sudah
ditemukan kebutuhan psikososial penderita TB paru (Suryani et al. 2014), sehingga
diperlukan upaya intervensi untuk mengatasinya. Psikoedukasi adalah pendidikan kesehatan
pada pasien baik yang mengalami penyakit fisik maupun gangguan jiwa yang bertujuan untuk
mengatasi masalah psikologis yang dialami mereka. Penyakit fisik disini bisa berupa
hipertensi, kanker, penyakit kulit, TBC dan sebagainya. Sedangkan gangguan jiwa bias
berupa depresi, kecemasan dan skizofrenia. Terapi psikoedukasi ini bisa berupa pasif
psikoedukasi seperti pemberian informasi dengan leaflet atau melalui email atau website dan
juga bias berupa aktif psikoedukasi berupa konseling atau pemberian pendidikan kesehatan
secara individu atau kelompok.
Stigma masyarakat memiliki sejumlah dampak negatif dan dapat merusak hubungan
sosial individu. Hal ini kemudian mendorong terjadinya isolasi sosial yang justru lebih
memungkinkan penyebaran virus/bakteri ketimbang upaya pencegahannya. Dikutip dari
panduan mencegah dan mengatasi stigma sosial oleh WHO, berikut tiga dampak stigma
sosial pada orang dengan penyakit menular:
1. Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakitnya untuk menghindari
diskriminasi
2. Mencegah orang segera mencari perawatan kesehatan
3. Mencegah mereka mengadopsi perilaku sehat
Dalam beberapa kasus, stigma masyarakat juga dapat menyebabkan orang dengan TBC
yang diusir dari rumah, komunitas, dan pekerjaan mereka, bahkan kehilangan rasa aman,
sistem pendukung, dan sarana pendapatan. Stigma tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga
mengikis komitmen petugas kesehatan untuk perawatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu,
pendekatan yang efektif harus melindungi hak setiap orang sebagai landasan perawatan yang
berpusat pada pasien.
Upaya mengatasi stigma masyarakat terbukti telah menghambat respon penanganan
epidemi maupun pandemi. Dalam kondisi tersebut perlu dilakukan upaya membangun
kepercayaan pada layanan dan sarana kesehatan yang terpercaya, mampu menunjukkan
empati kepada mereka yang terkena dampak, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
penyakit tersebut, serta mengambil langkah-langkah efektif untuk membantu menjaga diri
mereka dan orang di sekeliling agar tetap aman.
Adapun kemampuan kita mengkomunikasikan informasi mengenai penyakit TBC, Cara
mengkomunikasikan juga dapat mendukung mereka yang terdampak untuk dapat melawan
penyakit tersebut serta menghindari ketakutan dan stigma. Dalam panduan mencegah dan
mengatasi stigma sosial yang dirilis WHO, dirumuskan tiga hal yang perlu dilakukan untuk
mengatasi stigma:
1. Menggunakan kata-kata dan bahasa yang non-diskriminatif
Penggunaan kata dan Bahasa juga tidak jarang memicu sikap stigmatisasi, seperti
contohnya kasus suspek, isolasi, dll. Penggunaan kata-kata yang kurang tepat tidak jarang
dapat menguatkan stereotip atau asumsi negatif, memperkuat kaitan yang salah antara
penyakit dan faktor lain, seperti menciptakan ketakutan, atau merendahkan martabat orang
yang mengidap penyakit tersebut.
Penggunaan kata-kata atau bahasa yang kurang tepat justru dapat membuat orang
menghindari untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, dan karantina. Dalam panduan ini,
direkomendasikan untuk menggunakan bahasa yang fokus pada subyek dan memberdayakan
orang di semua kanal komunikasi, termasuk media.
2. Setiap orang memiliki peran untuk dapat menghapus stigmatisasi
Setiap orang memiliki peran yang sama dalam mencegah dan menghentikan stigma. Cara kita
berkomunikasi melalui media sosial maupun platform lain harus hati-hati dan bijaksana
dengan tidak fokus pada subyek namun lebih kepada informasi seputar penyakitnya.
Masyarakat dan petugas kesehatan untuk dapat membantu mencegah stigma:
Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien yang mencari perawatan kesehatan dan yang
mungkin menjadi bagian dari penyelidikan kontak apa pun.
Mengkomunikasikan dengan cepat risiko, atau kurangnya risiko, dari kontak dengan
produk, orang, dan tempat.
Memperbaiki bahasa negatif yang dapat menimbulkan stigma dengan membagikan
informasi akurat tentang bagaimana virus menyebar.
Menentang perilaku dan pernyataan negatif, termasuk yang ada di media sosial.
Memastikan bahwa gambar yang digunakan dalam komunikasi menunjukkan
komunitas yang beragam dan tidak memperkuat stereotip.
Menyarankan sumber daya virtual untuk kesehatan mental atau layanan dukungan
sosial lainnya bagi orang yang pernah mengalami stigma atau diskriminasi.
Komunikasi yang baik dan efektif
Stigma dapat berdampak negatif pada kesehatan emosional, mental, dan fisik kelompok
yang terstigma dan komunitas tempat mereka tinggal. Orang yang terstigma mungkin
mengalami isolasi, depresi, kecemasan, atau rasa malu di depan umum. Menghentikan stigma
penting untuk membuat semua komunitas dan anggota komunitas lebih aman dan sehat.
Setiap orang dapat membantu menghentikan stigma terkait TBC dengan mengetahui fakta
dan membagikannya kepada orang lain di komunitas mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Bagod Asturyno Wijaya, Joko Prasetyo, Shelfi Retnani Putri Santoso. (2021). Hubungan Tingkat
Kecemasan Dan Depresi Pada Pengobata Tuberculosis (TBC). Jurnal EDUNursing. 5(1). 10-22.
Debi Ariyanto, Muchlis Achsan Udji Sofro, Meidiana Dwidayani. (2020). Tingkat Depresi Pasien TB
MDR. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa. 3 (3), 277 – 290.
Devi alfiani. (2020). Hubungan Antara Pendampingan Patient Supporter Dengan Tingkat Depresi
Pada Pasien Tb-Mdr Di Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta : Universits Alma Ata.
Eli Kurniasih, Vina Jovitia Nurfajriani. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Tb Paru
Telaah Literatur. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. 21(1), 78-91.
Mustaqin, Suryawati, Heri Priyanto. (2017). Hubungan Tingkat Kepatuhan Minum Obat Anti
Tuberkulosis dengan Gejala Depresi pada Pasien TB Paru di RSUDZA Banda Aceh. Jurnal
Medisia. 2(2), 12-17.
Reni Marselia1, Wilson, Sari Eka Pratiwi. (2017). Hubungan antara Lama Terapi terhadap Tingkat
Gejala Depresi pada Pasien TB Paru di Unit pengobatan Penyakit Paru-Paru Pontianak. Jurnal
Cerebellum. 3(3), 831-841.
Rochman Basuki, Rihadini, Eko Budhiarti. (2020). Pengaruh Depresi Terhadap Kepatuhan Minum
OAT pada Penderita TB. Skripsi Semarang: Universitas Muhammaiyah.
Sulistiyani, Lamria Situmeang, Qoriah Nur. (2021). Psikologis Pasien Multi Drug Resistan
Tuberkulosis Selama Pengobatan Di Papua: Studi Fenomenologi. Jurnal Keperawatan Tropis
Papua. 4(1),11-21.
Suryani, Efri Widianti, Taty Hernawati, Aat Sriati. (2016). Psikoedukasi Menurunkan Tingkat
Depresi, Stres Dan Kecemasan Pada Pasien Tuberkulosis Paru. Jurnal Ners. 11(1), 128-133.
Verra Widhi Astuti, Astuti Yuni Nursasi, Sukihananto. (2019). Edukasi Kesehatan
Terstruktur Dan Stigma Masyarakat Pada Klien TB Paru. Jurnal Kesehatan Poltekkes
Palembang. 14(2),85-90.
Anda mungkin juga menyukai
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Jurnal Terapi PsikoedukasiDokumen9 halamanJurnal Terapi PsikoedukasiarenalestariBelum ada peringkat
- Stigma Dan Diskriminasi Penderita Tuberkulosis (TB) Multidrug ResistanceDokumen7 halamanStigma Dan Diskriminasi Penderita Tuberkulosis (TB) Multidrug ResistanceIsha McSmileBelum ada peringkat
- PEnanggulangan Penyakit TBDokumen13 halamanPEnanggulangan Penyakit TBHendrayadi PBelum ada peringkat
- Askep Komunitas Populasi Peny InfeksiDokumen23 halamanAskep Komunitas Populasi Peny InfeksiBudi Bakti WijayaBelum ada peringkat
- Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi 2016Dokumen7 halamanPencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi 2016Deni WahyudiBelum ada peringkat
- Bab 1 TB ParuDokumen4 halamanBab 1 TB ParuESWL haryotoBelum ada peringkat
- Bab I - 201801010Dokumen6 halamanBab I - 201801010icha nursyamBelum ada peringkat
- PENCEGAHAN PENULARAN TBCDokumen99 halamanPENCEGAHAN PENULARAN TBCFatiezt Puwnya'e BuwndaBelum ada peringkat
- TB Paru PendidikanDokumen7 halamanTB Paru Pendidikanjilyana adamBelum ada peringkat
- Bab 1-3Dokumen28 halamanBab 1-3Heni PuspitasariBelum ada peringkat
- Komunitas TB ParuDokumen39 halamanKomunitas TB ParuNoviriniBelum ada peringkat
- Pengalaman Keluarga Dalam Merawat Keluarga Yang TB ParuDokumen7 halamanPengalaman Keluarga Dalam Merawat Keluarga Yang TB ParuHeni PuspitasariBelum ada peringkat
- JurnalDokumen6 halamanJurnalmeldani653Belum ada peringkat
- Askep TB ParuDokumen43 halamanAskep TB ParuTry apriatnaBelum ada peringkat
- Kesehatan Jiwa TBDokumen16 halamanKesehatan Jiwa TBNurin nisaBelum ada peringkat
- STRES TBDokumen11 halamanSTRES TBEnggal PratamaBelum ada peringkat
- Askep KomunitasDokumen71 halamanAskep KomunitasFadil AshariBelum ada peringkat
- Test Askep Komunitas TB ParuDokumen41 halamanTest Askep Komunitas TB ParuFarid Arj100% (1)
- Tugas MetodologiDokumen10 halamanTugas MetodologiAULIA TOLIS CHANNELBelum ada peringkat
- Faktor TBDokumen8 halamanFaktor TBDella IzzaBelum ada peringkat
- Manuskrip Nurhidaya TerbaruDokumen13 halamanManuskrip Nurhidaya TerbaruOcep SaputraBelum ada peringkat
- Pender 2Dokumen10 halamanPender 2Tria JiraBelum ada peringkat
- PBL b2m2 Sken 1Dokumen9 halamanPBL b2m2 Sken 1diah savitri100% (1)
- Askep Komunitas TB ParuDokumen49 halamanAskep Komunitas TB ParuyanuarBelum ada peringkat
- Askep Komunitas TB ParuDokumen38 halamanAskep Komunitas TB ParuWhatyananda 0910Belum ada peringkat
- 5A - Keluarga - 1 - Pratiwi Ayuningtyas - BAB I-3 JADI FIXDokumen45 halaman5A - Keluarga - 1 - Pratiwi Ayuningtyas - BAB I-3 JADI FIXdark Coat19Belum ada peringkat
- Laporan Evaluasi Tahunan-TB-Paru TH 2020Dokumen15 halamanLaporan Evaluasi Tahunan-TB-Paru TH 2020Septian HermawanBelum ada peringkat
- TUGAS Kelompok I Determinan Sosial Kesehatan Berry, DKKDokumen9 halamanTUGAS Kelompok I Determinan Sosial Kesehatan Berry, DKKBerry Sanjaya KusumaBelum ada peringkat
- Makalah KLP 5 Askep Komunitas TBC Tugas Bu Widyo (3s & 3n)Dokumen36 halamanMakalah KLP 5 Askep Komunitas TBC Tugas Bu Widyo (3s & 3n)TyasBelum ada peringkat
- TB Paru dan Harga DiriDokumen32 halamanTB Paru dan Harga DiriYanti rosmiyantiBelum ada peringkat
- Skripsi HasilDokumen62 halamanSkripsi HasilAryoWibowoBelum ada peringkat
- Askep Komunitas TB ParuDokumen34 halamanAskep Komunitas TB ParuFitri MultazamBelum ada peringkat
- TB Paru dan Dampaknya di MasyarakatDokumen17 halamanTB Paru dan Dampaknya di MasyarakatIkhwan SahputraBelum ada peringkat
- Askep Komunitas TB ParuDokumen45 halamanAskep Komunitas TB ParuWahyu Brip005Belum ada peringkat
- TB PARUDokumen36 halamanTB PARUNeneng Sumyati IIBelum ada peringkat
- Askep Komunitas TB ParuDokumen46 halamanAskep Komunitas TB ParuSAIDA HELUTHBelum ada peringkat
- Bab1 3Dokumen93 halamanBab1 3Muhammad Bachiar SafrudinBelum ada peringkat
- Askep Komunitas TB ParuDokumen34 halamanAskep Komunitas TB Paru1907039 SINTASARI DEWI SETYANINGRUMBelum ada peringkat
- Tugas Komunitas TBDokumen12 halamanTugas Komunitas TBChenBelum ada peringkat
- Bdamanik,+55 +dachi+ (367-374)Dokumen8 halamanBdamanik,+55 +dachi+ (367-374)Hieronymus Kidung EnjangBelum ada peringkat
- SKRIPSIKUDokumen16 halamanSKRIPSIKUratnawul.oktBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan: 1.1 Latar BelakangDokumen11 halamanBab I Pendahuluan: 1.1 Latar BelakangCarien YesikaBelum ada peringkat
- Bab 1 Proposal Elan-1Dokumen25 halamanBab 1 Proposal Elan-1Marni adaBelum ada peringkat
- Hidayati 2015Dokumen7 halamanHidayati 2015Ivo TrisnaBelum ada peringkat
- ASUHAN TB PARUDokumen17 halamanASUHAN TB PARUAtika FadillaBelum ada peringkat
- PEDOMAN - PELAYANAN - TB - DOTS - Puskesmas Wuluhan - 2021Dokumen59 halamanPEDOMAN - PELAYANAN - TB - DOTS - Puskesmas Wuluhan - 2021ahmad hudaBelum ada peringkat
- Hubungan Tingkat Spiritual Denga Kualitas Hidup Pasien TB Di Puskesmas PunggurDokumen42 halamanHubungan Tingkat Spiritual Denga Kualitas Hidup Pasien TB Di Puskesmas PunggurAnton EffendiBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan KomunitasDokumen25 halamanAsuhan Keperawatan KomunitasOcing TanBelum ada peringkat
- Kebijakan Bu IfahDokumen17 halamanKebijakan Bu IfahSalsabilla KimikoBelum ada peringkat
- Liona Ayu Permata Kusuma - Ikm CDokumen4 halamanLiona Ayu Permata Kusuma - Ikm CLiona Ayu Permata Kusuma XII MIPA 5Belum ada peringkat
- GAMBARAN DEPRESIDokumen5 halamanGAMBARAN DEPRESImuhamad abiBelum ada peringkat
- Tugas Usulan Proposal Pemberdayaan MasyarakatDokumen12 halamanTugas Usulan Proposal Pemberdayaan MasyarakatAlfitrahrdaniBelum ada peringkat
- UAS METODOLOGI Lenora YaroserayDokumen17 halamanUAS METODOLOGI Lenora YaroserayMariana OrtumilenaBelum ada peringkat
- 15 Nurhidayah+Amir Stikes+Jayapura Clear+139-149Dokumen11 halaman15 Nurhidayah+Amir Stikes+Jayapura Clear+139-149Kadek Fina Aryani PutriBelum ada peringkat
- Artikel Raisa TuddinaDokumen7 halamanArtikel Raisa TuddinaKdrama IndoBelum ada peringkat
- H3 - Askep Komunitas Penyakit InfeksiDokumen22 halamanH3 - Askep Komunitas Penyakit InfeksiFaradila PutriBelum ada peringkat
- 53-Article Text-407-2-10-20220922Dokumen11 halaman53-Article Text-407-2-10-20220922Rulli SulaemanBelum ada peringkat
- Proposal HomeCare Irma DamayantiDokumen16 halamanProposal HomeCare Irma DamayantiIrma DamayantiBelum ada peringkat
- DDST II Anak 4 TahunDokumen6 halamanDDST II Anak 4 Tahunmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan StemiDokumen11 halamanLaporan Pendahuluan StemiRonay GokilBelum ada peringkat
- LP Dan Askep AsfiksiaDokumen24 halamanLP Dan Askep Asfiksiamauludina zahrrohBelum ada peringkat
- PJBL Respirasi IIDokumen10 halamanPJBL Respirasi IIAnonymous pdFngtkDMBelum ada peringkat
- Mauludina Zahroh - Studi KasusDokumen4 halamanMauludina Zahroh - Studi Kasusmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Hubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap PuskesmasDokumen12 halamanHubungan Komunikasi Terapeutik Dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap Puskesmasmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Contoh Promosi Kesehatan HipertensiDokumen35 halamanContoh Promosi Kesehatan Hipertensimauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Evaluasi Kegiatan (JIWA)Dokumen1 halamanEvaluasi Kegiatan (JIWA)mauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Mauludina - Zahroh - 2134008 - PBL - For MergeDokumen27 halamanMauludina - Zahroh - 2134008 - PBL - For Mergemauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Patway HivDokumen1 halamanPatway Hivmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Kel 2 Hiv Ibu MenyusuiDokumen5 halamanKel 2 Hiv Ibu Menyusuimauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Studi Kasus Keperawatan Berbasis MasyarakatDokumen4 halamanStudi Kasus Keperawatan Berbasis Masyarakatmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Roy Wijaya (STR 4B) LPDokumen20 halamanRoy Wijaya (STR 4B) LPmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Nurul Istiqomah (STR 4B) Lp.Dokumen13 halamanNurul Istiqomah (STR 4B) Lp.mauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Mauludina Zahroh (STR 4B) LPDokumen17 halamanMauludina Zahroh (STR 4B) LPmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Mauludina Zahroh 2134008Dokumen3 halamanMauludina Zahroh 2134008mauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Kesehatan Mental CovidDokumen6 halamanKesehatan Mental Covidmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Contoh Promosi Kesehatan HipertensiDokumen35 halamanContoh Promosi Kesehatan Hipertensimauludina zahrrohBelum ada peringkat
- MAULUDINA ZAHROH - 2134008 - Peng - KepDokumen6 halamanMAULUDINA ZAHROH - 2134008 - Peng - Kepmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Mauludina Zahroh STR 4B - Remidi Gadar KhususDokumen68 halamanMauludina Zahroh STR 4B - Remidi Gadar Khususmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Mauludina Z-2134008-ResumeDokumen6 halamanMauludina Z-2134008-Resumemauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Wawancara GiziDokumen2 halamanWawancara Gizimauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Contoh Promosi Kesehatan HipertensiDokumen35 halamanContoh Promosi Kesehatan Hipertensimauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Format PenugasanDokumen2 halamanFormat PenugasanDevira SiswoyoBelum ada peringkat
- Maternitas LP Nifas FixDokumen18 halamanMaternitas LP Nifas Fixmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Maternitas LP NifasDokumen17 halamanMaternitas LP Nifasmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Tugas B.ingDokumen2 halamanTugas B.ingmauludina zahrrohBelum ada peringkat
- Wawancara GiziDokumen2 halamanWawancara Gizimauludina zahrrohBelum ada peringkat