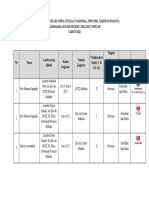Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air
Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air
Diunggah oleh
la alimudin saba0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan25 halamanJudul Asli
468. Panduan_pengendalian_dan_pemulihan_ekosistem_mata_air
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan25 halamanPanduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air
Panduan - Pengendalian - Dan - Pemulihan - Ekosistem - Mata - Air
Diunggah oleh
la alimudin sabaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 25
PANDUAN PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN.
OEM
Pusat Fengendatian Kerusakan Keanekaragaman Hayat!
BAPEDAU
200)
KATA CENGANTAR,
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas
perkenan-Nyalah, kami dapat menyelesaixan penyusunan buku “Panduan
Pengendalian Dan Pemulihan Ekosistem Mata Air”. Penyusunan buku ini
merupakan salah satu hasil kegiatan di Unit Kerja Pusat Pengendalian Kerusakan
Keanekaragaman Hayati - BAPEDAL.
Panduan Pengendalian Dan Pemulihan Ekosistem Mata Air ini diharapkan
dapat memberikan arahan dan panduan bagi pengelolaan mata air dan
Pengendalian kerusakan ekosistem mata untuk mewujudkan sistem pendayagunaan
mata air yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta dapat menjadi
bahan acuan bagi berbagai pihak dalam mengelola mata air di Indonesia.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
Penyusunan buku ini, terutama kepada Dr. Prastowo, Drs. Dibyo Sartono dan Dr.
Hamonangan Siregar, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu
per satu.
Akhimya, kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.
Jakarta, Desember 2001
Pusat Pengendalian Kerusakan
Keanekaragaman Hayati
BAPEDAL
eee .
‘Pundzan Pengendation dan Pemabban Uhoristem Mata fir "
Pusat Prugendelion Kmsakce Keasekero gre Hayati
Daftar isi
HALAMAN JUDUL .
KATA PENGANTAR
DAFTAR IST ...
DAFTAR LAMPIRAN
DAFTAR ISTILAH ...
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Sasaran
BABII PROFIL EKOSISTEM MATA AIR .
2.1 Definisi dan Pengertian
2.2 Karakteristik Mata Air
2.3 Manfaat dan Fungsi Mata Air ..
2.4 Kondisi dan Tingkat Kerusakan Mata Air ..
2.5 Pengelolaan Ekosistem Mata Air ....
BAB FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN
qr EKOSISTEM MATA AIR.
3.1 Faktor Alam ....
3.2 Faktor Sosial Ekonom
3.3 Faktor Sosial Budaya
BAB IV STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN MATA AIR
4.1 Aspek Pemanfaatan
4.2 Aspek Konservasi
4.3 Aspek Sosial ....
4.4 Aspek Legalitas
BABV PROGRAM AKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
KERUSAKAN MATA AIR,
5.1 Inventarisasi Potensi Mata Air .
5.2 Pendayagunaan Mata Air ..
5.3 Perijinan, Pengawasan dan Pemantauan
5.4 Konservasi Mata Air
Pandan Peagendilian dan Penubhan kosister Mata Air
Pusat Pengendalian Kprusaken Keanekgrogaman Hayat
FEO © O@NDAWW NNEm
Be ee
ao
ee
aOaaa
17
17
18
18
19
itt
BABI
PENDAHULUAN
ee
1.1. Latar Belakang
Air merupakan salah satu unsur kehidupan yang
Sangat penting, baik bagi manusia, flora, fauna,
dan makhluk hidup lainnya, Manusia
memeriukan air tidak hanya sebagai zat
makanan untuk mendukung metabolisme tubuh,
melainkan juga untuk kepentingan lainnya.
Penyediaan air untuk kehidupan di bumi
diatur/mengikuti suatu sikdus hidrologi, yaitu
suatu sikus yang menggambarkan sirkulasi air secara terus-menerus malalui
proses alami. Meialui sikius ini suplai air yang tersedia bagi manusia dan
Seeesenre: Rainy Capt peroies cet 2 sumber, yaitu air permukaan dan air
Sumberdaya air mempunyai manfaat yang tidak terhingga dalam menunjang
pembangunan nasional. Manfaat yang dapat dirasakan secara langsung
antara lain adalah untuk keperluan rumah tangga (domestik), industri dan
perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, pembangkit
listrik, dan pariwisata. Pemenuhan kebutuhan air untuk layanan tersebut
memeriukan upaya pengembangan sumberdaya air, salah satunya adalah
mata air. Pengembangan sumberdaya air (khususnya mata air) memeriukan
adanya konsepsi, perencanaan, perancangan, konstruksi, serta operasi dan
pemeliharaan fasilitas-fasilitasnya, sehingga dapat dimanfaatkan dan
dikendalikan dengan sebaik-baiknya.
Pada saat ini kondisi mata air diberbagai wilayah di Indonesia telah
mengalami perubahan/penurunan debit maupun kualitasnya. Hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah akibat penggundulan
hutan dan berubahnya fungsi daerah resapan. Sebagai akibatnya, air hujan
yang turun ke bumi sebagian besar mengalir sebagai aliran permukaan (/un-
of}, dan hanya sebagian kecil yang masuk ke dalam tanah untuk kemudian
mengalir sebagai aliran air tanah. Beberapa indikator kerusakan derah
resapan air maupun daerah tangkapan hujan diantaranya adalah banjir,
kekeringan, sedimentasi, tanah longsor, penurunan muka air tanah, rusaknya
Penden Jeagradaiion dan franiian tdpeniem Mata Me
Pusat Fregredaian Keraaten Kpamkeragoman Kirpan
keanekaragaman hayati, dan menurunnya debit mata air sebagai akibat
terganggunya fungsi penutupan lahan di daerah hulu.
Pemanfaatan mata air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara
bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun
generasi mendatang. Oleh karena itu pemanfaatan mata air dan pengendalian
ekosistemnya perlu diatur, agar diperoteh cara atau sistem Pemanfaatan yang
optimal bagi kepentingan kehidupan yang berkelanjutan.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan arahan
dan panduan pengelolaan mata air dan Pengendalian kerusakan ekosistem
mata air, untuk mewujudkan sistem pendayagunaan mata air yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
1,3. Sasaran
1. Memberikan gambaran tentang profil ekosistem mata air di Indonesia,
meliput! karakteristk, manfaat dan fungsi, kondisi dan tingkat kerusakan,
serta pengelolaan ekosistem mata air saat ini.
2. Identifikasi faktor-faktor yang menimbulkan kerusakan ekosistem mata
air, mencakup faktor alam, sosial-ekonomi, dan faktor sosial-budaya.
3, Merumuskan pendekatan, strategi, dan program aksi dalam pengelolaan
mata air dan pengendalian kerusakan ekosistem mata air.
Pandaan Cengendatian dan Pemultan € kgsistem Mata fir
Pusat Peapendalian Kerasaken Keanckerapaman Hayats
BAB IT
PROFIL EKOSISTEM MATA AIR
a i es ee Se
2.1, Definisi dan Pengertian
Ekosistem mata air merupakan salah satu
ekosistem lahan basah dan seringkali sebagai
Permulaan dari sebuah aliran sungai. Sumber
air ekosistem tersebut adalah aliran air tanah
yang muncul ke permukaan tanah secara
alami, yang disebabkan oleh terpotongnya
aliran air tanah oleh bentuk topografi setempat
dan kelvar dari batuan. Pada umumnya mata
air muncul di daerah kaki perbukitan atau
bagian lereng, lembah perbukitan, dan di daerah dataran.
Hampir semua air tanah berasal dari air hujan dan relatif sedikit dari sumber
lain. Berdasarkan jenis sumber air tersebut maka air tanah dikelompokkan
dalam 4 tipe yaitu :
1, Air meteorik ; Air ini berasal dari atmosfer dan mencapai zona saturasi
baik langsung atau tidak langsung yaitu dengan cara infiltrasi pada
permukaan tanah atau melalui kondensasi uap air. Sedangkan secara
tidak langsung melalui rembesan karena muta air tanah yang lebih rendah
dan air permukaan.
2. Alr Juvenil : Penambahan air ke zona saturasi dari bagian yang dalam
ari kulit burni yaitu air magma, vulkanik dan kosmik,
3. Air Rejuvenil : Air yang berasal dari siklus hidrologi dan digunakan
sementara untuk pelapukan atau lain proses dan kemudian kembali be
siklus dengan cara metamorfisme, kompaksi atau proses sejenis.
4. Air Konat : Air yang terdapat pada batuan sedimen dan wulkanik pada
Saat pembentukannya. Pada urmumnya air ini mengandung mineral yang
tinggi dan salinitas yang lebih besar dari air laut.
Air tanah mengalir dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah.
(aerah yang lebih tinggi merupakan daerah resepan atau recharge arez dan
Pinna Seared an Teele Ci geetom Masta the
Pusat Pngendadon Kermakon Kameterageman Hires
(yang saturated) menuju muka air tanah. Bila hal ini terjadi maka timbul mata
‘air atau spring dan rembesan atau seeps. Air dari spring atau seeps tersebut
tir ke badan air tawar misainya danau, sungai atau ke laut.
Diperkirakan sekitar 98% dari seluruh air tawar yang terdapat di bumi berada
di bawah permukaan, di dalam rongga-rongga batwan dan benda butiran.
Sedangkan sisanya 2% terdapat di danau, waduk dan sungal. Peranan mata
air dalam
ini,
E
hhidrolog! dapat dilinat dalam bagan alir pada gambar dibawah
2.2 Karakteristik Mata Air
Air di dalam tanah dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifat kesamaan umum
dan keadaan-keadaan spesifik. Penggolongan wilayah tersebut penting untuk
tujuan perbandingan dan pemerian dan dapat memberi pengarahan terhadap
kerangka eksplorasi meskipun terdapat variasi-variasi secara lokal. Dasar-dasar
Penggolongan air tanah ke dalam wilayah air tanah adalah kesamaan umum
dan karakteristik kejadian yang meliputi :
Paniasn Crediton da Sresien .fjeutom Mata ee
‘Eset Praendation Krenaen Kramctarngemen Hiatt
Morfologi
Dataran, pegunungan, kerucut gunung api, pantai dan sebagainya
4 Geologi
Macam batuan pengandung air, bentuk-bentuk —struktur yang
mengendalikan.
Beberapa contoh wilayah air tanah :
1. Wilayah aluvial pantai : medan datar, air tanah dangkal, dengan sistem
tekanan rendah kemungkinan penetrasi air asin, aquifer sering berbentuk
fensa dari kerikil-pasir lepas dengan sungai, misainya dataran pantai utara
pulau Jawa.
2. Wilayah kipas aluvial : medan miring melandai membentuk apex di hulu
dan melebar ke bawah, sistem tekanan sedang, aquifer/aquiclude miring
ke hilir dan membagi ke hulu, basement dangkal di hulu, aquifer dapat
sangat kasar dan permeabel, misalnya daerah kipas aluvial Bogor dan
Bandung Utara.
3. Wilayah cekungan gunung api : cekungan diantara gunung api, aquifer
dan aquicude hampir sama dengan kipas aluvial, terdiri dari produk
gunung api, tertransportasikan (lahar, kerikil, pasir, lempung), misainya
Cekungan Bandung, Garut, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Malang dan
Jember.
4. Wilayah pegunungan plateau : meadan terjat berlembah-lembah,
catchment area sempit, aquifer horizontal atau melipat lemah, air tanah
dalam dan umumnya sukar didapat, misalnya pegunungan setatan Jawa
Barat dan selatan Jawa Timur.
5. Wileyah pegunungan antikdinorium : medan bergelombang dengan bukit-
bukit memanjang, aquifer dalam batuan sedimen pervious, didasar sinklin
atau puncak antikiin, air termineralkan, air tanah sering dalam. Endapan di
bidang unconformity dapat berpotensi, misalnya zona Bogor, atau
pegunungan zona Rembang, zona Kendeng.
6. Wilayah pegunungan karst : medan berbukit-bukit kecil dengan dolina,
terdiri dari bukit-bukit gamping, banyak kekar, sungai-sungai bawah
permukaan, air tanah dalam, dikendalikan oleh adanya retakan dalam
gamping dan penyebaran lapisan aquiclude, misalnya pegunungan Seribu.
Secara ringkas komponen mata air terdiri atas 4 unsur, yaitu :
1. Wilayah/daerah resapan air (recharge area).
2. Proses resapan ke dalam bumi
3. Struktur lapisan dan patahan-patahan bumi
4. Wilayah keluarnya air tanah sebagai mata air (discharge area)
Pandvan Pengendabin dan Vemuban Ekgristem Mata fir
Paset Pengendabian Kerasakon Keanekaraqaman Hayat
2.3.
Dilihat dari lokasi pemunculan/penyebarannya, mata air yang umum dijumpai
di Indonesia berasal dari mandala airtanah gunungapi strato, mandala
airtanah perbukitan bergelombang, dan mandala airtanah dataran. Menurut
Jenisnya, mata air dapat dikelompokkan ke dalam 3 Jenis mata air, yaitu :
1. Mata air depresi (depresion springs) terbentuk karena aliran air tanah
memotong permukaan tanah.
2. Mata air rekahan/struktur sesar (fracture/fault springs) muncul dari
struktur rekahan atau jalur sesar.
3. Mata air kontak (contact springs) muncul pada kontak batuan
impermeable (batuan tersier) dan batuan permeable (batuan kuarter).
Kualitas mata air sangat dipengaruhi oleh jenis aliran airtanah sebagai sumber
mata air. Kualitas air mata air yang berasal dari aliran airtanah tertekan
(confined aquifer) relatif lebih baik dibanding dengan kualitas air mata air
yang berasal dari aliran airtanah bebas (unconfined aquifer).
Manfaat dan Fungsi Mata Air
Pemanfaatan mata air dapat dikelompokkan dalam 3 kategori :
1. Pemanfaatan dengan cara pengambilan, misalnya bagi peruntukan
domestik, irigasi dan industri
2, Pemanfeatan tanpa pengambilan, misalnya bagi peruntukan PLTA,
rekreasi, perlindungan satwa liar.
3. Tanpa pemanfaatan, misalnya penguapan air,
Mata air di Indonesia sebagian besar dimanfaatkan oleh penduduk setempat
secara langsung, baik untuk keperluan domestik mapun untuk
Pertanian/perikanan. Beberapa mata air dengan debit yang relatif besar telah
dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, sarana air bersih (PDAM), kolam
renang (wisata), dan industri air minum dalam kemasan.
Upaya pemanfaatan mata air yang umum dilakukan adatah dengan melakukan
Penurapan mata air, yaitu dengan cara membangun infrastruktur bangunan
Penangkap mata air (6ron capturing), jaringan (pipa) transmisi, dan bangunan
reservoir distribusi. Debit yang dimanfaatkan pada umumaya adalah debit
alamiah, yaitu debit mata air yang dapat ditangkap tanpa adanya rekayasa
teknik untuk menambah debit tersebut. Pada unit (pengguna mata air)
tertentu, selain penurapan atau penangkapan mata air, dilakukan pula
Pemboran/pemompaan tambahan untuk meningkatkan/memperbesar debit
air.
Candas Pengendalian dan Peruldian Ekgeittem Mata Air
Pusat Veapendalian Kerusakan Keanckeragaman Jiayati
2.4
Apabila dikaitkan dengan siklus hidrologi, upaya penurapan mata air yang
berwawesan jingkungan adalah penurapan mata air yang hanya
mengandalkan debit alamiah yang ada. Rekayasa teknik untuk menambah
debit meta air dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan antara debit
imbuhan (recharge) dan debit lepasan/pemanfaatan (discharge). Debit
pemanfaatan mata air yang melebihi debit imbuhan akan menyebabkan
terganggunya kelangsungan pemanfaatan mata air dimasa mendatang.
Kondisi dan Tingkat Kerusakan Mata Air
Masuknya air, yaitu : penetrasi air hujan ke dalam air tanah; perembesan
alamiah ke dalam tanah dari air danau, sungai dan sebagairya; perembesan
buatan ke dalam tanah dan air irigasi, waduk, sawah dan sebagainya;
pemasukan air tanah bebas dan artois dari daerah sekitarnya.
Keluarnya air, yaitu : rembesan keluar dan mata air dari air tanah bebas, run
off, evaporasi, transpirasi, dan dari drainase; keluarnya air dari mata air
melalui sesar pada air artois, rembesan melalui daerah baweh; keluarnya air
secara buatan dengan pemompaan; discharge bawah permukaan dari air
tanah bebas dan artois ke arah bawah.
Faktor-faktor geologi (jenis batuan, struktur geologi), morfologi, pelapukan,
iklim, vegetasi dan campur tangan manusia akan berpengaruh besar terhadap
kesetimbangan tersebut. Suatu daerah merupakan cekungan air tanah yang
baik bila ground water increment lebih besar dari ground water decrement.
Kondisi daerah resapan (recharge area) sangat berpengaruh terhadap debit
mata air dan kualitas aimya. Tata guna lahan Pada daerah ini berpengaruh
langsung terhadap bagian air hujan yang masuk ke dalam tanah sebagai
aliran airtanah (sumber mata Pada seat ini, beberapa daerah resapan
mata air (khususnya di P. Jawa) telah Mmengalami kerusakan yang
mengkhawatirkan. Beberapa mata air di daerah Bogor, Purwokerto, dan
Malang telah mengalami penurunan debit bila dibandingkan dengan kondisi
debit tahun 1970an. Apabila kondisi ini tidak diperhatikan, dalam arti tidak
ada upaya pengendalian kerusakan ekosistem mata air, maka dapat
dipastikan bahwa pemanfaatan mata air di masa mendatang akan terganggu.
Penurunar/hilangnya debit mata air juga berarti kerusakan ekosistem mata
air secara keseluruhan sebagai salah satu ekosistem lahan basah,
Pandvan Pengendalian dan Pemutiban Ckgsstem Mata Air
at aie
Keresakon Keanekaragaman Hayati
2.5. Pengelolaan Ekosistem Mata Air
Untuk kepentingan perlindungan mata air, maka pertu diketahui besarnya
pemanfaatan yang sesuai atau safe yield dengan pemompaan air tanah.
Untuk tujuan tersebut peru dilakukan beberapa hal sebagai berikut ;
1. Melakukan perhitungan neraca air untuk air tanah tersebut dan ditentukan
besarnya pemanfaatan yang sesuai dengan besarnya sirkulasi air tanah
berdasarkan hasil perhitungan neraca air tersebut. Juga diperkirakan
Pengaruh yang terjadi jika diadakan pemompaan lebih.
2. Di daerah pemanfaatan air tanah yang utama dipasang sistem
Pengamatan permukaan air tanah. Besarnya pemanfaatan air tanah itu
dibandingkan dengan hasil pengamatan air tanah. Jika terdapat keadaan
dimana permukaan air tanah itu menurun, maka harus diadakan
Peramalan mengenai penurunan permukaan air dan Pengeringan mata air
di kemudian hari berdasarkan kecepatan penurunan dan lain-lain sifat
aquifer.
Panduan Pengendalin dam Pemubhan Ekgrstem Mata fir
‘Pusat Pengendlalion Kerusaken Keanckaragrman Hayat
BAB IIT
FAKTOR- FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM
MATA AIR
wvewrmaon Keberadaan mata air sangat dipengaruhi oleh faktor-
faktor sekitarnya, baik yang bersifat “independen”
maupun yang “dependen”, baik yang bersifat
Positif/mendukung terhadap peningkatan —fungsi
ekosistem mata air maupun yang bersifat negatif atau
mengancam/merusak bahkan mematikan debit mata
air. Secara umum faktor-faktor tersebut dapat
dikategorikan sebagai berikut :
1. Faktor alam, yakni faktor yang merupakan proses alam balk karena
gerakan bumi maupun proses ekologis dan geologi lannya.
2. Faktor sosial ekonomi, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan
manusia dalam memperlakukan ekosistem mata air dalam rangka
memenuhi kebutuhan ekonominya.
3. Faktor sosial budaya, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan
manusia/masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budayanya
diwilayah ekosistem mata air.
Faktor-faktor diatas dapat bersifat positif kepada ekosistem mata air maupun
bersifat negatif sampai dengan hilangnya/keringnya mata air.
3.1. Faktor Alam
Gerakan evolusi bumi sangat berpengaruh kepada mata air, karena pada
dasarnya mata air terjadi karena adanya lapisan air pada struktur lapisan-
lapisan bumi yang karena adanya celah, patahan, atau retakan lapisan kedap
air yang melingkunginya, terjadilah mata air. Gerakan bumi ini dapat
mengakibatkan menurun atau hilangnya mata air, namun cepat pula
memunculkan mata air baru di tempat lain. Gerakan bumi ini bersifat
“independent” dan secara sadar manusia tidak dapat
mempengaruhi/mengendalikannya.
Salah satu upaya untuk dapat menata dan memprediksi keberadaan mata air
tersebut adalah dengan mempelajari struktur dan susunan tanah yang ada
disekitar mata air tersebut (ekosistem) sehingga dapat dilakukan prediksi
Puaduas Dragredabian Gon Pemasihan hosisiem Mate Ri °
‘Pusat Prnpendahian Kerasakes Keone gragemax Hayati
BAB IIT
FAKTOR- FAKTOR YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN EKOSISTEM
MATA AIR
ee ee
===eees MKeberadaan mata air sangat dipengaruhi oleh faktor-
F: . faktor sekitamya, balk yang bersifat “independen”
as maupun yang “dependen”, baik yang bersifat
positif/mendukung terhadap peningkatan fungsi
ekosistem mata air maupun yang bersifat negatif atau
mengancam/merusak bahkan mematikan debit mata
air, Secara umum faktor-faktor tersebut dapat
dikategorikan sebagai berikut :
1. Faktor alam, yakni faktor yang merupakan proses alam baik karena
gerakan bumi maupun proses ekologis dan geologi lannya.
2 Faktor sosial ekonomi, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan
3. Faktor sosial budaya, yakni faktor yang ada karena adanya gerakan
manusia/masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilal budayanya
diwilayah ekosistem mata air.
Faktor-faktor diatas dapat bersifat positif kepada ekosistem mata air maupun
bersfat negatif sampai dengan hilangnya/keringnya mata air.
3.1. Faktor Alam
Gerakan evolusi bumi sangat berpengaruh kepada mata air, karena pada
dasarnya mata air terjadi karena adanya lapisan air peda struktur lapisan-
lapisan bumi yang karena adanya celah, patahan, atau retakan lapisan kedap
air yang melingkunginya, terjadilah mata air, Gerakan bumi ini dapat
mengakibatkan menurun atau hilangnya mata air, mamun cepat pula
Memunculkan mata air baru di tempat lain. Gerakan bumi ini bersifat
“independent” dan secara sadar manusia tidak dapat
mempengaruhi/mengendalikannya.
Salah satu upaya untuk dapat menata dan memprediksi keberadaan mata air
tersebut adalah dengan mempelajari struktur dan susunan tanah yang ada
disekitar mata air tersebut (ekosistem) sehingga dapat dilakukan prediksi
Pandaan Pregradaiion din Premiiian ¢Eieelem Mata Me ,
(Puss Trmgemialion Kratos Keametaraguman drsati
3.2.
Pusat
mengenai masa keberadaannya (life time), kapasitasnya dan kualitasnya.
Dengan demikian perencanaan pemanfaatannya dapat didekati meskipun
dengan pengertian bahwa faktor alam adalah “independent”
Faktor alam lain yang sangat berpengaruh terhadap ekosistem mata air
adalah faktor iklim dan cuaca yakni pergiliran antara musim kemarau dan
musim hujan serta prakiraan cuaca hujan. Kalau terjadi pergeseran musim
kemarau lebih panjang daripada musim hujan dan adanya prakiraan bahwa
deras hujan lebih kecil dan biasanya maka dapat diprediksi bahwa mata air
akan mengecil. Faktor ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi daerah
tangkapannya termasuk pola pengelolaan atau pemanfaatan wilayah tersebut.
Faktor Sosial Ekonomi.
Faktor sosial ekonomi adalah faktor yang terjadi sebagai hasil perbuatan dan
pemikiran manusia/masyarakat dalam menyikapi dan memanfaatkan mata air
dan ekosistemnya. Kita sadari bahwa keberadaan mata air tidak lepas dari
alam sekelilingnya (ekosistem) dan terjadinya mata air adalah hasil dari suatu
rangkaian proses yang panjang yang tidak dapat dikendalikan manusia.
Kekurangan pengertian dan kesalahan dalam penafsiran yang mengakibatkan
kesalahan perlakuan terhadap mata air dan ekosistemnya sangat menentukan
keberadaan mata air itu sendiri. Adanya pemahaman yang salah dan adanya
tekanan kebutuhan ekonomi yeng mendesak sering melahirkan tindakan-
tindakan yang membahayakan, merusak bahkan menghilangkan mata air.
Beberapa tindakan masyarakat yang menonjol dalam hal ini antara lain :
1. Pemanfeatan Jahan yang tidak sesuai dengan fungsinya dimana
seharusnya daerah tersebut selalu tertutup hijauan, diubah menjadi
wilayah pertanian semusim, pemukian atau industri sehingga kemampuan
serap wilayah tersebut berkurang dan air hujan tidak masuk kedalam
tanah tetapi mengalir sebagai air permukaan yang disamping menjadikan
tidak terisinya akuifer-akuifer mata air juga dapat mengakibatkan
rusaknya daerah tersebut.
2. Perubahan bentang alam sehingga terjadi perubahan struktur tanah/bumi
yang mengakibatkan perubahan patahan lapisan bumi sehingga merusak
lapisan air dan kedap air yang dapat mematikan mata air.
3. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali sebagai akibat meningkatnya
kebutuhan air karena Perkembangan konsumsi atau industri. Pada
10
enclvan Congendatian dan Vomlian CKgsistem Mata fir
‘Cengendahian
Kerasakan Keanekaragaran Hyatt
dasarnya mata air akan aman bila jumlah yang dipergunakan adalah
sesuai atau di bawah kemampuan debit mata air namun sering terjadi
karena kebutuhan ekonomi, pengambilan dilakukan melebihi debit yang
ada, sehingga debit air dalam akuifer akan tersedct keluar secara paksa
dan tidak seimbang dengan jumlah pengisian akuifer, yang berakibat
mengecil/matinya mata air.
4. Mata air dapat pula rusak oleh kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan
Pencemaran baik diwilayah resepan maupun didaerah sekitar mata air,
sehingga meskipun debit tetap tidak berkurang nanum kualitas air akan
Menurun tercemar bahkan dapat menimbulkan wabah penyakit.
3.3 Faktor Sosial Budaya
Dalam masyarakat, sering terjadi adanya penilaian-penilaian sumberdaya
alam bukan hanya dari visi ekologis atau ekonomis saja, tetapi dapat pula
Mmemuat nilai-nilai religio magis, budaya, dan kebudayaan. Suatu mata air
dapat menjadi penting ecara social budaya hanya karena kepercayaan dapat
membuat awet muda, perkasa, atau hal-hal lain yang tidak logis. Pada
beberapa mata air karena komposisi kandungan mineralnya mempunyal daya
penyembuhan beberapa penyakit terutama penyakit kulit dapat seketika
menjadi terkena! dan banyak dikonsumsi masyarakat.
Adanya hal-hal ini walau dengan tidak sengaja melakukan perusakan terhadap
mata air dan ekosistemnya namun dapat menjurus kepada kecenderungan
perusakan karena :
1. Konsumen tidak hanya masyarakat sekitar namun datang dari luar daerah
sehingga bias terjadi pengambilan air yang melebihi debitnya.
2. Kedatangan konsumen dari luar daerah sering mengakibatkan keperluan
akomodasi, konsumsi makanan dan sebagainya yang dapat mendorong
terjadinya perubahan pemanfaatan ekosistemnya sehingga _ terjadi
degradasi yang berakibat kepada mata air itu sendiri.
3. Pengaturan yang kurang baik dengan adanya peningkatan pemanfaatan itu
dapat menimbulkan polusi yang tidak terkendali terhadap mata air itu
sendiri.
Kecuali faktor alam yang memang bersifat “independent” faktor sosial
ekonomi dan sosial budaya pada dasarnya lebih banyak bisa dikendalikan dan
diatur secara baik sehingga mata air akan berfungsi baik selama mungkin.
Pondean Ceagendaion dan Prmubihan kerictem Mata fir
Pusat Pengeadaian Kerusakon Kane groggman Hayati
Pusat
Mengingat bahwa pada dasarnya mata air adalah milik “publik” maka
sebaiknya pengelolaan mata air merupakan pengelolaan Partisipatif seluruh
“stakeholders' mulai di daerah tangkapan sampai dengan masyarakat
Pengguna hanya dengan cara ini, asal bukan karena faktor alam yang
‘independen” mata air dapat bermanfaat optimal bagi masyarakat.
Gancluon Vengeadatian dan Pemalian €Rgsister Mata Air R
Pengendabin
Kemsaken KeaneKeragaman Hiryati
BABIV
STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN
MATA AIR
4.1, Aspek Pemanfaatan
Penyusunan perencanaan pemanfaatan mata air untuk memenuhi kebutuhan
tertentu, dilakukan dengan mempertimbangkan :
@Kebutuhan mata air jangka panjang, berdasarkan kondisi
pemanfaatan yang telah ada dan rencana pengembangan mata air
di masa mendatang, sehingga dapat didayagunakan secara
berkelanjutan.
Debit mata air yang keluar secara alamiah, yang ditangkap dengan
teknis penurapan yang benar.
¢@Kemanfaatan untuk masyarakat, dengan pengertian bahwa selain
manfaat' ‘finansial, pemanfaatan mata alr juga herus tetap
memberikan manfaat sosial, khususnya masyarakat yang telah
memperoleh manfaat sebelum mata air dikembangkan.
@Konservasi daerah resapan, untuk menjamin keberlanjutan
pemanfaatan mata air.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air, maka urutan prioritas peruntukan pemanfaatan mata air
adalah sebagai berikut :
Air minum
. Air untuk rumah tangga
Air untuk peternakan dan pertanian sederhana
Air untuk industri
Air untuk irigasi
. Air untuk pertambangan
’.. Air untuk usaha perkotaan
. Air untuk kepentingan lainnya.
PNW AWE
an duan Pengeadalicn dan Pousiban Ulgeistom Mata Fie
Pusat Pengendatian Kerusakn Keenek erogamas Hisyati
Namun demikian prioritas peruntukan mata air ini dapat disesuaikan dengan
mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum serta kondisi spesifik
setempat.
Gamer, frmampungan Air
Aspek Konservasi
Upaya konservasi ekosistem mata air sangat
diperlukan untuk menjamin keberlanjutan
Pendayagunaan mata air serta mencegah dan
Menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan
akibat kegiatan eksploitasi mata air. Dengan
pemanfaatan secara bijaksana diharapkan
ketersediaan debit mata air mapun kyalitasnya
dapat terjamin, baik untuk masa kini maupun
untuk masa mendatang. Setiap pemegang Ijin
pengambilan mata air wajib melaksanakan konservasi mata air sesual dengan
fungsi kawasan yang ditetapkan sesuai tata ruang wilayah yang
bersangkutan.
Upaya konservasi mata air yang sangat penting untuk dilakukan adalah
rehabilitasi dan konservasi daerah resapan. Hal ini mengingat bahwa potensi
suatu mata air sangat ditentukan oleh kondisi bio-fisik daerah resapan, yang
Menjamin adanya aliran airtanah sebagai sumber utama dari mata air yang
bersangkutan. Apabila tata guna lahan pada daerah resapan tidak tertutup
leh vegetasi yang memadai, maka curah hujan yang turun pada daerah
resapan sebagian besar akan dialirkan sebagai limpasan (aliran permukaan|
Dengan demikian bagian hujan yang masuk ke dalam tanah yang mengisi
aliran air tanah yang akan muncul sebagai mata air, akan semakin berkurang.
Penchiee Pemgredalion dan rman Tlprwsre ate ar
‘Pusat Prnradatian Kerasahee Keeaekeragmmae Sirti
4.3.
Candivon Ceagendabion dau Comalian Ekgsisien Mata jit
Rehabilitasi dan konservasi daerah resapan harus dilakukan secara tepat,
yaitu pada wilayah yang harus dilindungi atau dikelola , yang telah ditentukan
berdasarkan delineasi daerah resapan. Salah satu kendala yang ada di
lapangan dalam upaya konservasi mata air adalah dalam hal status
pemilikan/pengelolaan lahan. Kepemilikan/pengelolaan daerah resapan
maupun daerah sekitar mata air biasanya mencakup areal yang relatif luas
dan melibatkan masyarakat banyak. Oleh karena itu, disamping pendekatan
teknis, dalam pelaksanaan konservasi mata air pertu dilakukan pendekatan
sosial, agar upaya konservasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan
efisien,
Aspek Sosial
Untuk mewujudkan agar pendayagunaan mata air dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya untuk masyarakat, maka perencanaan pemanfaatan mata
air harus dilakukan secara bijaksana, dengan mempertimbangkan faktor-
faktor teknis, finansial, sosial, dan pertimbangan lingkungan. Proses
penyusunan pemanfaatan mata air harus dilakukan dengan melibatkan :
1, Masyarakat dan atau pihak-pihak pengguna mata air sebelum mata air
yang bersangkutan dikembangkan.
2. Masyarakat di sekitar mata air (radius 200 meter), baik yang bermukim
maupun yang menggarap/mengelola lahan.
3. Masyarakat dan atau pihak-pihak di daerah resapan.
4. Pemerintahan Desa setempat, baik di sebelah hulu (up-stream) maupun di
sebelah hilir (down-stream) mata air.
Seperti_halnya proses penyusunan pemanfaatan mata air, penyusunan:
Program dan pelaksanaan konservasi mata air perlu dilakukan dengan mode!
Partisipastif, untuk membangun persepsi dan sikap kepedulian semua pihak
yang terkait terhadap pelestarian ekosistem mata air. Upaya pemanfaatan
mata air dan konservasi ekosistem mata air yang dilakukan dengan model
Partisipatif, selain memberikan manfaat finansial dan ekonomi, diharapakan
juga dapat memberikan manfaat sosiat kKhususnya bagi masyarakat sekitar.
Aspek Legalitas
Proses perijinan harus ditetapkan dan diikuti dengan mempertimbangkan hak-
hak kepemilikan lahan dan hak-hak pengelolaan mata air. Kegiatan penurapan
15
Pusat Pengendafan Kerusakan Keanekeragarsan Jayati
Pandan Pengendatian dan teealtian Ekosisiem Mata Air
Pusat
mata air dapat dilakukan setelah memperoleh ijin Penurapan mata air, dengan
mengikuti ketentuan bahwa_peruntukan pemanfaatan mata air untuk
keperluan air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama di atas
segala keperluan lain. Prioritas peruntukan Pemanfaatan mata air dapat
disesuaikan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat
Perijinan penurapan mata air selain sebagai perwujudan aspek legalitas, juga
dimaksudkan untuk mengendalikan pendayagunaan mata air dengan cara
mengikuti ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipatuhi serta daya dukung
ketersediaannya (debit mata air secara alami). Rencana penurapan mata air
dengan debit sama atau lebih besar dari 50 liter/detik harus dilengkapi
dengan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), sedangkan
Penurapan mata air dengan debit kurang dari 50 liter/detik harus dilengkapi
dengan dokumen UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya
Pemantauan Lingkungan),
‘Penagendallan Kerusatan Keanekeragaman Sayati
BABYV
PROGRAM AKSI
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN MATA AIR
TE SS cS
Program aksi pengelolaan mata air dan pengendalian kerusakan
ekosistem mata alr meliputi kegiatan-keglatan :
@ Inventarisasi potensi mata air
@ Pendayagunaan mata air
@ Perijinan, Pengawasan dan pemantauan
@ Konservasi mata alr
5.1. Inventarisasi Potensi Mata Air
Kegiatan inventarisasi potensi mata air meliputi_ kegiatan pemetaan,
penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi mata
air yang mencakup :sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akifer,
daerah resapan (recharge area) dan daerah lepasan/pemanfaatan (discharge
area, debit mata air dan kualitas air, debit penurapan mata air dan jenis
pemanfaatannya, serta data lain yang berkaitan dengan ekosistem mata air
1. Sebaran lokasi mata air mencakup data letak geografis, elevasi dan betak
administratif, sedangkan jenis mata air diidentifikasi berdasarkan lapisan
akifer, sehingga lokasi mata air dapat dengan mudah ditelusuri untuk
keperluan pendayagunaan maupun pengendalian kerusakannya.
2. Delineasi daerah resapan (recharge area) peru dilakukan untuk
mengetahui secara pasti batasan wilayah yang harus dilindungi atau
dikelola untuk mempertahankan debit dan kualitas mata air serta menjaga
keberlanjutan pendayagunaan mata air.
Candcan Pengendalion dan Prmafihan Ekpsicte Mata Sir "
Pusat Peapradation Kerasotes Keanekeragiman Hispati
3. Data debit penurapan mata air perlu dibandingkan dengan debit mata air
secara alamiah, sehingga diketahui efisiensi Ppemanfaatan mata air untuk
memenuhi kebutuhan air domestik, industri, PLTA, Pertanian/perikanan,
dan atau peruntukan lainnya.
4. Data lain yang berkaitan dengan ekosistem mata air antara lain meliputi
tata guna lahan dan keanekaragaman hayati di wilayah:
a. Sekitar (radius 200 meter) fokasi mata air,
b. Daerah resapan (recharge area).
¢. Daerah lepasan/pemanfaatan (discharge area),
5.2, Pendayagunaan Mata Air
Pendayagunaan mata air meliputi kegiatan perencanaan, desain teknis dan
konstruksi penurapan mata air. Setiap tahap kegiatan pendayagunaan mata
air ini harus dilakukan dengan mengikuti pecunjuk teknis penurapan mata air
yang ditetapkan oleh lembaga yang berkompeten (misainya : Departemen
Kimpraswil atau Instansi Teknis Pemerintah Daerah setempat).
1. Kegiatan perencanaan pemanfaatan mata air dilakukan sebagai dasar
untuk pendayagunaan mata air Pada suatu satuan wilayah sebaran mata
air tertentu, Perencanaan pemanfaatan ini hanus dibuat berdasarkan data
inventarisasi dan evaluasi potensi mata air.
N
Desain teknis dan konstruksi Penurapan mata air mencakup bangunan-
bangunan penangkap mata air (6ron_ capturing), jaringan transmisi,
reservoir distribusi, dan jaringan distribusi. Desain dan konstruksi ini harus
memperhitungkan debit aliran secara alamiah, dalam arti tidak dilakukan
dengan rekayasa teknik (misainya dengan melakukan pemompaan atau
Pemboran) untuk meningkatkan debit Penurapan dengan mengubah cara
pemunculannya.
Debit maksimum penurapan mata air ditentukan dengan pertimbangan ;
@. Tidak melebihi debit minimum mata air yang keluar secara alamiah
dikuranyi dengan debit pemanfaatan yang telah ada sebelumnya.
b. Menyediakan air kepada masyarakat (apabila diperlukan), maksimum
sebesar 10 % dari debit yang diijinkan untuk dieksploitasi.
5.3. Perijinan, Pengawasan dan Pemantauan
Kegiatan penurapan mata air dapat dilakukan setelah memperoleh ijin
Penurapan dari Instansi yang berwewenang sesuai dengan ketentuan yang
Gusdian Dengendlian da Qemuliban Clpsstem Mata ir 18
‘Pusat Ceapendafian Kerusafeu Keanekeragiman Hirt,
berlaku (KepMen Energi dan Sumberdaya Mineral No 1451 K/10/MEM/2000).
Selain sebagai perwujudan aspek legalitas, perijinan ini harus disikapi sebagai
upaya pengendalian, agar dilakukan pendayagunaan mata air yang
berkelanjutan. Prinsip-prinsip hak kepemilikan lahan harus dipisahkan dengan
hak pengelolaan atas mata air.
Keberlanjutan pendayagunaan mata air sangat tergantung pada efektivitas
yang perlu dilakukan meliputi :
1. Pengawasan pentaatan terhadap ketentuan teknis yang tercantum dalam
perijinan,
2. Pengawasan pentaatan terhadap ketentuan dalam UKL dan UPL atau
AMDAL,
3. Pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem mata
air.
Kegiatan pemantauan secara berkala dan kontinyu perlu dilakukan untuk
mendapatkan data fluktuasi atau kecenderungan perubahan debit mata air
dan kualitas airnya. Pengukuran dan pemantauan dilakukan minimal dalam
kurun waktu satu tahun, untuk mempercleh data fluktuasi debit sepanjang
tahun. Untuk selanjutnya pemantauan debit dan kualitas air dapat dilakukan
pada Musim Hujan dan Musim Kemarau. Kegiatan pengukuran dan
pemantauan dapat dilakukan oleh pihak pengguna mata air dan atau instansi
yang terkait dengan upaya pendayagunaan dan konservasi mata air. Adapun
kegiatan pemantauan yang peru dilakukan meliputi :
1. Pemantauan debit mata air dan kualitas airnya
2. Pemantauan perubahan penggunaan lahan di daerah resapan
3. Pemantauan perubahan penggunaan lahan di sekitar mata air
4. Pemantauan dampak lingkungan akibat pendayagunaan mata air.
5.4 Konservasi Mata Air
Kegiatan konservasi mata air diwajibkan
kepada setiap pemegang ijin penurapan
mata air. Pelaksanaan konservasi mata air
harus didasarkan pada hasil inventarisasi
potensi mata air, perencanaan pemanfaatan
mata air, perijinan, penentuan debit
penurapan mata air, serta laporan
pengawasan dan pemantauan. Hal ini periu
19
Pandas 0 ngpeilian dan Prmaiiian thynire Maca Ae
(Pt Drmarndation Arent Kecarksraaemae Tireatt
Pa Vegan dan Pian kgistow Mata ir
Pasat
diperhatikan agar setiap kegiatan konservasi dilakukan secara benar, baik
Mengenai ketepatan lokasi maupun teknik konservasinya. Upaya konservasi
mata air yang harus dilakukan meliputi :
1. Rehabilitasi dan konservasi daerah resapan untuk meningkatkan debit
imbuhan, Pada sebagian besar lokasi mata air, delineasi daerah resapan
belum dilakukan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti dimana lokasi
daerah resapan yang sudah kritis dan memerlukan rehabilitasi. Oleh
karena itu pemetaan daerah resapan merupakan langkah awal yang
sangat penting, sebagai dasar berpijak untuk penyusunan Program
maupun implementasi kegiatan rehabilitasi dan konservasi mata air.
Teknis budidaya kehutanan (sili kultur) pertu disesuaikan dengan kondisi
setempat, khususnya mengenai Jenis-jenis tanaman lokat yang potensial
untuk dikembangkan sebagai tanaman konservasi.
2. Pentaatan dan Penegakan ketentuan teknis penurapan mata air.
Ketentuan teknis ini mencakup bangunan Penangkap mata air, jaringan
transmisi, reservoir distribusi, dan Jaringan distribusi. Tata ietak dan
Pembangunan infrastruktur ini harus diupayakan sedemikian rupa
sehingga mampu menghindari konfllk sosial yang tidak diinginkan. Oleh
karena itu dalam Mengikuti ketentuan teknis Penurapan mata air, harus
Pula memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat,
misainya yang terkait dengan hak kepemilikan lahan pada lokesi
infrastruktur tersebut.
3. Perlindungan daerah sekitar mata air (radius 200 m). Pada saat ini kondisi
tata guna lahan sekitar mata air pada setiap daerah sangat beragam.
Beberapa lokasi mata air, daerah sekitarnya telah terdapat bangunan fisik
(pemukiman/industri). Pada lokasi mata air yang demikian maka yang
harus diperhatikan adalah menjaga agar sistem bangunan penangkap
mata air yang telah ada tidak diganggu, tetapi harus dipelihara dengan
baik, Namun demikian pada lokasi mata air yang masih bebas dari
bangunan fisik, maka fungsi lahan sekitar mata air sebagai kawasan
lindung harus dipertahankan,
20
‘ennendalian Kerusaken Keane groguman Hayoti
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, M. I. 2001, Analisa Sumber Mata Air di Kabupaten Banyumas. Kantor
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Purwokerto.
Budianta, E. 2001. Upaya Pemanfaatan Ekosistem Mata Air Berkelanjutan. Makalah
Disampaikan pada Workshop Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mata
Air.
Efendi, A.T. 1985. Peta Hidrologi Indonesia I : 250.000 Lembar Pekalongan
Gawa). Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Bandung.
Kolopaking, L.M., dkk. 2000. Konstruksi Pengembangan Aplikasi Inderaja untuk
Sumber Daya Air. Fakultas Pertanian-IPB dan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi. Bogor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2000. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman
Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air
Bawah Tanah. Jakarta.
Poespowardoyo, R.S. 1984. Peta Hidrogeologi Indonesia 1 : 250.000 Lembar
Kediri, Direktorat Geologi Tata Lingkungan. Bandung.
Prastowo. 2001. Pengendalian Kerusakan Mata Air. Makalah Disampaikan pada
Workshop Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mata Air, Bapedal Jakarta
tanggal 26 Nopember 2001. Bogor.
Sungkawa, W. 2000. Peta Hidrogeologi Indonesia I : 100.000, Catatan Penerangan
Lembar 1308-6, 1308-3 (purwokerto, Tegal). Direktorat Geologi Tata
Lingkungan. Bandung.
Suryaman. 1999. Peta Hidrogeologi Indonesia 1 : 100.000, Catatan Penerangan
Lembar 1608-1, Malang, Jawa Timur. Direktorat Geologi Tata Lingkungan.
Bandung
‘indus Geapadidcs dn mln Whgooiew Wu 21
Geegendalins din Pemba Ekgristem Mota fir
‘Psat Pengendalins Kprasakan Keane oraqam Diyas
Anda mungkin juga menyukai
- BetapaDokumen2 halamanBetapala alimudin sabaBelum ada peringkat
- Susunan Panitia Asesmen Madrasah Tapel 2023 - 2024Dokumen2 halamanSusunan Panitia Asesmen Madrasah Tapel 2023 - 2024la alimudin sabaBelum ada peringkat
- SalahutuDokumen2 halamanSalahutula alimudin sabaBelum ada peringkat
- 2 - Pembiasaan Siswa Dan Kegiatan Hari-Hari KeagamaanDokumen25 halaman2 - Pembiasaan Siswa Dan Kegiatan Hari-Hari Keagamaanla alimudin sabaBelum ada peringkat
- 7,8,9,16 - Prestasi SiswaDokumen20 halaman7,8,9,16 - Prestasi Siswala alimudin sabaBelum ada peringkat
- 1 - Tata Tertib Siswa - Man 1 Maluku TengahDokumen10 halaman1 - Tata Tertib Siswa - Man 1 Maluku Tengahla alimudin sabaBelum ada peringkat
- 30 - 3 - A - Format Penilaian Kinerja GuruDokumen1 halaman30 - 3 - A - Format Penilaian Kinerja Gurula alimudin sabaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen23 halamanBab Iila alimudin sabaBelum ada peringkat
- Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - Maluku Tengah 24 & 26 Oktober 2022Dokumen32 halamanPelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah - Maluku Tengah 24 & 26 Oktober 2022la alimudin sabaBelum ada peringkat
- Ekologi, Lingkungan Hidup, MC & Ekosistem, Dampak Pembangunan, Urbanisasi & LingkunganDokumen69 halamanEkologi, Lingkungan Hidup, MC & Ekosistem, Dampak Pembangunan, Urbanisasi & Lingkunganla alimudin saba100% (1)
- Islamic Political Economy of AccountingDokumen236 halamanIslamic Political Economy of Accountingla alimudin sabaBelum ada peringkat
- 3.5 Dinamika Kependudukan Di IndonesiaDokumen32 halaman3.5 Dinamika Kependudukan Di Indonesiala alimudin sabaBelum ada peringkat
- Pemanfaatan SumberdayaDokumen195 halamanPemanfaatan Sumberdayala alimudin sabaBelum ada peringkat
- Dinamika Kependudukan Di Indonesia-Part 4Dokumen7 halamanDinamika Kependudukan Di Indonesia-Part 4la alimudin sabaBelum ada peringkat
- Duniageo Com Un Geografi 2012Dokumen45 halamanDuniageo Com Un Geografi 2012la alimudin sabaBelum ada peringkat
- PetunjukDokumen4 halamanPetunjukla alimudin sabaBelum ada peringkat
- Penjelasan Soal Nomor 11-KSM-2015-geografi-provinsiDokumen2 halamanPenjelasan Soal Nomor 11-KSM-2015-geografi-provinsila alimudin sabaBelum ada peringkat
- Khutbah Jum'at - Tujuan Penciptaan Manusia PDFDokumen4 halamanKhutbah Jum'at - Tujuan Penciptaan Manusia PDFla alimudin sabaBelum ada peringkat
- Duniageo Com Un Geografi 2011Dokumen27 halamanDuniageo Com Un Geografi 2011la alimudin sabaBelum ada peringkat