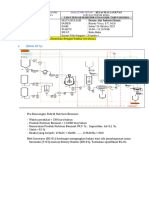BAB II Urea
BAB II Urea
Diunggah oleh
Syadila LutfiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II Urea
BAB II Urea
Diunggah oleh
Syadila LutfiHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.2 Urea
Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen,
oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Urea juga dikenal
dengan nama carbamide yang terutama digunakan di kawasan Eropa. Nama lain
yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide,
carbonyldiamine (Ernawanto, 2011). Urea merupakan pupuk nitrogen dengan
kandungan 46% yang memiliki karakter mudah larut dalam air dan tidak
mempunyai residu garam sesudah dipakai untuk tanaman (Demir, 2014).
Selain itu urea tidak bersifat mengionisir dalam larutan, sehingga mudah
mengalami pencucian karena tidak mudah terjerap oleh koloid tanah. Sehingga
untuk dapat diserap oleh akar tanaman, urea harus mengalami proses ammonifikasi
dan nitrifikasi lebih dahulu (Effendi, 2010). Cepat dan lambatnya perubahan
bentuk amide dari urea ke bentuk senyawa N yang dapat diserap oleh tanaman
sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu keadaan populasi, aktivitas
mikroorganisme, kadar air dari tanah, temperatur tanah dan banyaknya pupuk urea
yang diberikan bagi tanaman (Hardjowigeno, 2013). Unsur hara nitrogen yang
terkandung dalam pupuk urea memiliki kegunaannya bagi tanaman yaitu, membuat
daun lebih banyak mengandung klorofil (zat hijau daun), dapat mempercepat
pertumbuhan tanaman, dapat menambah kandungan protein tanaman dan dapat
dipakai untuk semua jenis tanaman (Al-Jabri et.al. 2011).
Disamping penggunaannya sebagai pupuk, urea juga digunakan sebagai
tambahan makanan protein untuk hewan pemamah biak, juga dalam produksi
melamin, dalam pembuatan resin, plastik, adhesif, bahan pelapis, tekstil, dan resin
perpindahan ion (Eko, 2013). Prinsip pembuatan urea pada umumnya yaitu dengan
5
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
mereaksikan antara amonia dan karbondioksida pada tekanan dan temperatur
tinggi didalam reaktor kontinyu untuk membentuk amonium karbamat (reaksi 1)
selanjutnya amonium karbamat yang terbentuk didehidrasi menjadi urea (reaksi 2).
Reaksi 1: 2 NH3 (g) + CO2 (g) NH2COONH4 (g)
Reaksi 2: NH2COONH4 (g) NH2CONH2 (g) + H2O (l)
Sintesis urea dilakukan dengan amonia yang berlebih agar kesetimbangan dapat
bergeser ke arah kanan sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih banyak.
(Muliawati, 2007). Berikut struktur urea yang ditunjukkan pada gambar II.1 serta
sifat fisika dan kimia urea:
➢ Sifat Fisika Urea
1. Rumus molekul : CO(NH2)2 atau CON2H4
2. Berat molekul : 60,06
3. Specific gravity : 1,335 (20oC/4oC)
4. Titik lebur : 132,7oC
5. Kelarutan : 100 (17oC dalam 100% air)
20 20oC dalam 100% alkohol)
6. Panas pembakaran : -91,02.105 J/kg
➢ Sifat Kimia Urea
1. Urea dibuat dari hidrolisis parsial cyanamide
H2N-CN + H2O H2N-CO-NH2
2. Urea dihasilkan dari reaksi antara ammonia dengan karbon dioksida
CO2 + NH3 H2N-CO-NH2 + H2O
3. Urea dapat bereaksi dengan formaldehid
NH2-CO-NH2 + HCHO NH2-CO-NH2 + CH2OH
4. Pemanasan ammonia sianat dapat terurai menjadi urea
NH4+OCN Heat H2NCONH2
6
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Gambar II.1 Struktur Urea
II.2 Adsorpsi
Adsorpsi adalah proses dimana molekul fluida menyentuh dan melekat pada
permukaan padatan dan akhirnya membentuk suatu film (lapisan tipis) pada
permukaan padat tersebut (Nasruddin, 2005). Dengan kata lain, proses adsorpsi
merupakan akumulasi adsorbat (zat yang teradsorpsi) pada permukaan adsorbent
(zat yang mengadsorpsi) dimana disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau
suatu akibat dari medan gaya pada permukaan padatan (adsorbent) yang menarik
molekul-molekul gas, uap maupun cairan (Oscik, 1982). Proses adsorpsi dapat
berlangsung jika suatu permukaan padatan dikotakan dengan molekul gas atau cair,
maka didalamnya terdapat gaya kohesif termasuk gaya hidrostatik dan gaya ikatan
hidrogen yang bekerja diantara molekul seluruh material. Gaya yang tidak
seimbang pada batas fasa tersebut menyebabkan perubahan konsentrasi molekul
pada interface solid/fluida (Ginting, 2008). Gaya tarik-menarik dari suatu padatan
dibedakan menjadi dua jenis yaitu gaya fisika dan gaya kimia yang masing-masing
menghasilkan adsorpsi fisika (physisorption) dan adsorpsi kimia (chemisorption).
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
1. Adsorpsi fisika adalah proses intertaksi antara adsorbent dengan adsorbat
yang melibatkan gaya antar molekul seperti gaya van der Waals. Molekul
teradsorpsi pada permukaan dengan ikatan lemah dan energi yang dilepaskan
relatif rendah (< 20 kJ/mol). Selain itu juga, adsorpsi fisik umumnya terjadi
pada temperatur rendah (bertambahnya temperatur jumlah adsorpsi
berkurang dengan signifikan) dan bersifat reversible (menurunkan tekanan
gas atau konsentrasi zat terlarut) (Castellan, 1983)
2. Adsorpsi kimia adalah proses intertaksi antara adsorbent dengan adsorbat
yang melibatkan ikatan koordinasi sebagai hasil penggunaan elektron
bersama. Proses ini umumnya menurunkan kapasitas dari adsorbent karena
gaya adhesinya yang kuat sehingga proses ini tidak reversibel dimana
memerlukan energi aktivasi dan nilai kalor relatif besar (100 kJ/mol) (Osick,
1983; Sukardjo, 1990)
Berikut beberapa faktor yang memengaruhi daya adsorpsi diantaranya yaitu
(Bambang, 2004):
1. Tekanan (P) adsorbat, kenaikan tekanan adsorbat dapat menaikan jumlah
yang diadsorpsi
2. Temperatur absolut (T) adsorbat, pelekatan adsorbat pada adsorbent terjadi
pembebasan sejumlah energi (eksotermis) dimana berkurangnya temperatur
akan menambah jumlah adsorbat yang teradsorpsi dan sebaliknya
3. PH larutan sangat berpengaruh terhadap kapasitas adsorpsi karena distribusi
muatan permukaan adsorbent dapat berubah (karena komposisi dari bahan
baku dan proses aktivasi) dengan demikian kapasitas adsorpsi bergantung
pada gugus fungsi dari adsorbat
4. Sifat adsorbat meliputi ukuran molekul serta kepolaran zat. Adsorpsi akan
bertambah besar jika diameter suatu molekul adsorbat lebih kecil atau sama
8
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
dengan diameter pori adsorbent. Sementara itu, molekul polar lebih kuat
diadsorpsi dibandingkan dengan molekul tidak polar
5. Sifat adsorbent meliputi kemurnian dan struktur pori. Kemurnian tinggi pada
adsorbent dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi. Sedangkan struktur
pori berkaitan dengan luas permukaan adsorbent dimana jumlah molekul
adsorbat yang teradsorp meningkat dengan bertambahnya luas permukaan
Sedangkan menurut weber dan Benefield (1982) mekanisme yang terjadi
pada proses adsorpsi ditunjukkan gambar II.2 dengan keterangan sebagai berikut:
yaitu:
1. Molekul-molekul adsorbent berpindah dari fase bagian terbesar larutan ke
permukaan interface, yaitu lapisan film yang melapisi permukaan adsorbent
atau eksernal
2. Molekul adsorbent dipindahkan dari permukaan ke permukaan luar dari
adsorbent (exterior surface)
3. Molekul-molekul adsorbat dipindahkan dari permukaan luar adsorbent
menyebar menuju pori-pori adsorbent. Fase ini disebut dengan difusi pori
4. Molekul adsorbat menempel pada permukaan pori-pori adsorbent
Gambar II.2 Proses Adsorpsi
9
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
II.1 Isotherm Adsorpsi
Isotherm adsorpsi adalah hubungan yang menunjukkan distribusi adsorbent
antara fase teradsorbsi permukaan adsorbent dengan fase curah yang berlangsung
pada temperatur tetap. Dari isoterm ini, akan diketahui kapasitas adsorpsi,
efisisensi suatu adsorbent (Castellan, 1982).
1. IUPAC b.) Donohue
Gambar II.3 Tipe Isoterm Adsorpsi
Bentuk isoterm adsorpsi yang diteliti secara garis besar diklasifikasikan
menjadi 6 (enam) tipe seperti disajikan pada Gambar II.3 (Balbuena, 1993). Tipe I
merupakan tipe Langmuir, terjadi pada adsorbent dengan pori mikro (< 2 nm). Tipe
II dan III, terjadi pada adsorbent non pori. Tipe II memiliki gaya tarik fluida dan
dinding pori (afinitas) yang kuat sedangkan pada tipe III, gaya tarik fluida dan
dinding bersifat lemah. Tipe IV dan V adalah isoterm untuk adsorbent dengan
mesopori (2 < dp < 50 nm) dan terjadi kondensasi kapiler. Tipe IV adalah sistem
adsorpsi dengan gaya tarik fluida dan dinding kuat, sedangkan tipe V, gaya tarik
dinding dan fluida bersifat lemah. Klasifikasi pertama oleh Brauner et al. (1940)
hanya menyampaikan 5 tipe (Balbuena, 1993). Tipe VI, merupakan tipe terbaru.
Isoterm seperti ini terjadi pada sistem adsorpsi dengan gaya tarik fluida dan dinding
relatif kuat dan biasanya terjadi pada temperatur mendekati titik leleh fluida.
10
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
1. Isotherm Adsorpsi Langmuir
Model isotherm adsorpsi Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas adsorpsi
maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal (monolayer) adsorbat di
permukaan adsorbent dan semua situs permukaannya bersifat homogen, karena
masing-masing situs aktif hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat.
Adsorpsi isotherm Langmuir didasarkan pada asumsi, yaitu (Oscik, 1982):
a) Pada permukaan adsorbent terdapat situs-situs aktif proporsional
dengan luas permukaan adsorbent. Pada setiap situs aktif hanya dapat
mengadsorpsi satu molekul saja, dengan demikian adsorpsi terbatas
pada pembentukan lapis tunggal (monolayer)
b) Pengikat adsorbat pada permukaan adsorbent dapat secara kimia atau
fisika, tetapi harus cukup kuat untuk mencegah perpindahan molekul
teradsorpsi pada permukaan (adsorpsi terlokalisasi)
c) Energi adsorpsi tidak tergantung pada penutupan permukaan
d) Laju adsorpsi akan bergantung pada faktor ukuran dan struktur
molekul adsorbat, sifat pelarut dan porositas adsorben, situs pada
permukaan yang homogen dan adsorpsi terjadi secara monolayer
Berikut bentuk persamaan isoterm adsorpsi Langmuir:
𝑥 𝑞𝑚 𝑏. 𝐶
=
𝑚 1 + 𝑏. 𝐶
Dimana:
x/m : Jumlah dari adsorbat yang teradsorpsi per unit berat adsorbent (mg/g)
C : Konsentrasi adsorbat dalam larutan pada saat kesetimbangan (mg/L)
b : Konstanta Langmuir (l/mg)
qm : Maksimum adsorbat yang dapat diserap (mg/g)
11
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
2. Isotherm Adsorpsi Freundlich
Model adsorpsi Freundlich digunakan jika diasumsikan bahwa terdapat lebih
dari satu lapisan permukaan (multilayer) dan site bersifat heterogen, yaitu adanya
perbedaan energi pengikatan pada tiap-tiap site (Schnoor, 1996). Berikut bentuk
persamaan model adsorpsi isotherm Freundlich:
𝑥
= 𝐾𝐶 1/𝑛
𝑚
Dimana:
x/m : Besarnya adsorbat yang teradsorpsi oleh adsorbent (mg/gr)
K : Konstanta Freundlich (mg/g) yang proporsional dengan rasio distribusi
konsentrasi adsorbat di solid-air
1/n : Menyatakan ketidaklinieran (tanpa satuan)
C : Konsentrasi adsorbat di air pada saat kesetimbangan
II.3 Zeolit Alam
Zeolit berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata zein yang berarti
membuih dan lithos yang berarti batu. Zeolit adalah mineral alam yang terbentuk
dari reaksi abu vulkanik dengan permukaan air atau ground water (Goenadi, 2004).
Terdapat pula pada lingkungan non-vulkanik selama interaksi antara partikel saline
soil dengan strong basic solution. Zeolit merupakan mineral alam yang terdiri dari
kristal aluminosilikat terhidrasi dimana mengandung kation alkali dan alkali tanah
dalam kerangka tiga dimensinya (Thirunavukkarasu, 2014). Perbedaan jenis zeolit
mempunyai daya serap (adsorption) molekul berbeda-beda secara selektif.
Keselektifan ini tergantung struktur masing-masing jenis zeolit, sehingga zeolit
dapat digunakan sebagai:
12
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
a) Penyaring ion, molekul atau sebagai katalis
Zeolit dapat menyaring ion, molekul, maupun atom karena mempunyai
saluran (channel) dan rongga (cavity) dalam struktur zeolit bila oxygen window
dari saluran atau rongga lebih kecil dari ion, molekul, atau atom. Zeolit mempunyai
pori sehingga juga dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi
dalam proses kimia.
b) Bahan penyerap
Bila zeolit dipanaskan pada suhu tinggi maka akan terjadi dehidrasi,
penguapan yang dikandungnya sehingga menyebabkan zeolit akan selektif dalam
menyerap molekul-molekul seperti He, N2, O2, CO2, SO2, Ar, dan Kr. Proses
penyerapan molekul oleh zeolit terjadi karena strukturnya juga mempunyai
polaritas yang tinggi. Kemampuan zeolit mengadsorpsi sangat bergantung pada
rasio Si/Al. Rasio Si/Al rendah, zeolit bersifat hydrophilic mempunyai afinitas
tinggi terhadap air dan senyawa polar lainnya. Sebaliknya jika rasio Si/Al tinggi,
maka zeolit bersifat hydrophobic dan mengadsorpsi senyawa non-polar
(Yuliusman, dkk., 2013).
c) Penukar ion
Pertukaran ion pada dasarnya terjadi dalam suatu cairan yang mengandung
anion, kation, dan molekul air dimana salah satu atau sebagian ion yang terikat
pada matriks mikropori berfase padat. Molekul air dapat berada dalam mikropori
bersama ion (kation, anion) dengan muatan yang berlawanan dengan ion matriks
sehingga terjadi kesetimbangan muatan untuk mencapai keadaan netral, sehingga
ion yang berada dalam cairan dapat bergerak bebas di dalam matriks mikropori
(Ginting, A., dkk., 2007). Sifat zeolit sebagai penukar ion khususnya kation
tergantung dari sifat kation, suhu, dan jenis kation. Penukar kation dapat
memengaruhi beberapa sifat zeolit diantaranya adalah stabilitas terhadap safat
panas, sifat adsorpsi dan aktifitas katalitis (Tri Widianti, 2006). Zeolit sebagai
13
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
penukar kation memiliki kation-kation pada rongga elektrolit yang berfungsi untuk
menjaga kenetralan zeolit. Keberadaan kation ini dapat ditukar dengan kation lain
yang memiliki selektivitas lebih besar. Kation dengan selektivitas lebih besar
semakin mudah mendorong terlepasnya kation yang terdapat pada zeolit dan
digantikan dengan kation yang memiliki selektivitas yang lebih besar. Urutan
selektivitas zeolit adalah Cs+ > Rb+ > K+ > NH4+ > Ba2+ > Sr2+ > Na+ > Ca2+ > Fe3+
> Al3+ > Mg2+ > Li2+ (Widianti, Tri. 2006).
Kekuatan zeolit sebagai penjerap, katalis, dan penukar ion sangat tergantung
dari perbandingan Al dan Si, sehingga dikelompokkan menjadi 3 yang ditunjukkan
pada table II.1 (Sutarti, 1994):
a) Zeolit dengan kadar Si rendah
Zeolit jenis ini banyak mengandung Al (kaya Al), berpori, mempunyai nilai
ekonomi tinggi karena efektif untuk pemisahan atau pemurnian dengan kapasitas
besar. Kadar maksimum Al dicapai jika perbandingan Si/Al mendekati 1 dan
keadaan ini mengakibatkan daya penukaran ion maksimum.
b) Zeolit dengan kadar Si sedang
Kerangka tetrahedral Al dari zeolit tidak stabil terhadap pengaruh asam dan
panas. Jenis zeolit mordenit mempunyai perbandingan Si/Al = 5 sangat stabil.
c) Zeolit dengan kadar Si tinggi
Mempunyai perbandingan Si/Al= 10-100 sehingga sifat permukaannya tidak
dapat diperkirakan lebih awal. Sangat higroskopis dan menyerap molekul non-
polar sehingga baik digunakan sebagai katalisator asam untuk hidrokarbon.
14
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Tabel II.1: Klasifikasi Zeolit Berdasarkan Rasio Si/Al (Ramoa, 1984)
Kenaikan rasio Si/Al memberikan pengaruh terhadap sifat-sifat zeolit seperti
berikut ini (Surtati, 1994):
1. Terjadinya perubahan medan magnet elektrostatik dalam zeolit, sehingga
mempengaruhi interaksi adsorpsi zeolit. Zeolit bersilika rendah bersifat
hidrofilik sementara zeolit bersilika tinggi bersifat hidrofobik (dan lipofilik).
2. Zeolit bersilika rendah (Zeolit A dan X) dapat stabil pada temperatur 800-
900 K, sedangkan zeolit bersilika tinggi (H-ZSM-5) stabil hingga temperatur
1300 K.
3. Zeolit bersilika rendah mudah rusak pada pH kurang dari 4, sedangkan zeolit
bersilika tinggi lebih stabil dalam lingkungan asam kuat
4. Kekuatan asam akan meningkat, sedangkan sisi Asam Bronsted akan
berkurang dengan naiknya rasio Si/Al. Kekuatan asam ini disebabkan oleh
posisi aluminium dalam kerangka yang lebih terisolasi. Menurut
Triantafillidis (2000), semakin banyak kandungan Al dalam framework
zeolit (rasio Si/Al menurun) akan menyebabkan kekuatan atau total situs
asam zeolit menurun. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan
15
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
bahwa dealuminasi akan menyebabkan peningkatan keasaman zeolit.
Keasaman yang dimaksud adalah kekuatan asam yang terdapat pada
permukaan zeolit atau banyaknya situs asam yang terdapat pada permukaan
zeolite
Zeolit mengandung beberapa unsur kimia seperti SiO2 sebesar 55-58%,
Al2O3 10-24% dan sisanyanya adalah CaO, MgO, Na2O dan K2O yang dapat
menutupi pori-pori dari zeolit sehingga untuk mendapatkaan zeolit sebagai
penukar kation, pengotor harus dihilangkan dengan cara diaktivasi (Rahayu dkk,
2008). Proses aktivasi dilakukan untuk meningkatkan nilai daya tukar kation yang
memiliki dua cara yaitu secara fisika dan kimia (Ramesh, 2011). Aktivasi secara
fisika dilakukan dengan cara pemanasan (300-400℃) dengan tujuan agar zeolit
mengalami dehidrasi yang mengakibatkan terbukanya pori-pori tau rongga utama
dan memperluas medan listrik rongga. Sedangkan aktivasi kimia dilakukan dengan
larutan aktivator seperti H2SO4, NaOH maupun NaCl dengan tujuan untuk
membersihkan permukaan pori-pori atau rongga, membuang senyawa pengotor,
mengatur kembali letak atom yang dapat dipertukarkan dan diharapkan dapat
meningkatkan daya tukar kation (Eko, 2013).
Rumus kimia zeolit secara umum dapat ditulis M2nO.Al2O3.xSiO2yH2O
dimana M adalah kation alkali dan alkali tanah; n adalah valensi logam alkali; x
adalah bilangan tertentu (2 s/d 10); y adalah bilangan tertentu (2 s/d 7). Zeolit
terdiri atas gugus alumina oksida dan gugus silika oksida yang berbentuk
tetrahedral dan saling dihubungkan oleh atom oksigen membentuk kerangka tiga
dimensi (Charlena dkk, 2008). Ikatan Al-O-Si membentuk struktur kristal
sedangkan logam alkali atau alkali tanah merupakan sumber kation yang dapat
dipertukarkan (Sutarti, M dkk, 1994). Struktur zeolit dapat dibedakan dalam tiga
komponen, yaitu rangka aluminosilikat, ruang kosong saling berhubungan yang
16
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
berisi kation logam, dan molekul air (Trenkel, 2010). Berikut contoh komposisi
Zeolit Alam (Sutarti, 1994) yang tersaji dalam tabel II.2 berikut:
Tabel II.2 Komposisi Zeolit Alam (Sutarti, 1994)
Struktur zeolite ditunjukkan pada gambar II.4, sedangkan karakteristiknya tersaji
pada table II.3 dengan keterangan sebagai berikut:
a) Sangat berpori, karena kristal zeolit merupakan kerangka yang
terbentuk dari jaring tetrahedral SiO4 dan AlO4.
b) Pori-porinya berukuran molekul karena pori zeolit terbentuk dari
tumpukan cincin beranggotakan 6, 8, 10, atau 12 tetrahedral.
c) Dapat menukarkan kation. Karena perbedaan muatan Al3+ dan Si4+
menjadikan atom Al dapat kerangka kristal bermuatan negatif dan
membutuhkan kation penetral bukan menjadi bagian kerangka ini
mudah diganti dengan kation lainnya.
d) Dapat dijadikan padatan yang bersifat asam. Karena penggantian
kation penetral dengan proton-proton menjadikan zeolit padatan
asam Bronsted.
e) Mudah dimodifikasi karena setiap tetrahedral dapat dikontakkan
dengan bahan-bahan pemodifikasi.
17
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Gambar II.4: Zeolit alam (Tri Widianti, 2006)
Sifat fisik dan kimia zeolit adalah sebagai berikut:
a) Hidrasi derajat tinggi
b) Ringan
c) Penukar ion yang tinggi
d) Ukuran saluran yang uniform
e) Menghantar listrik
f) Mengadsorpsi uap dan gas
g) Mempunyai sifat katalitik
Tabel II.3 Karakteristik Zeolit Alam (Sutarti, 1994)
Sifat zeolit sebagai penukar kation dapat dimanfaatkan dibeberapa bidang
sebagai berikut yaitu (Tan Yu Wea, 2018):
18
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
1. Bidang perikanan
Kualitas air dalam bidang perikanan ditentukan oleh suhu, salinitas, PH,
ammonia, senyawa nitrogen, H2S, CO, dan lainnya. Tingginya kadar ammonia
dalam air umumnya disebabkan adanya pembusukan sisa makanan, bangkai,
plankton, senyawa organik. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan
ikan dan udang dalam tambak. Oleh sebab itu zeolit digunakan untuk mengurangi
kadar ammonia.
2. Bidang pertanian
Pada bidang pertanian, zeolit dapat digunakan untuk memperbaiki sifat kimia
tanah, terutama tanah bersifat asam. Sifat lain yang menguntungkan dari zeolit
adalah untuk mengontrol pelepasan nutrisi tanaman seperti ammonia, kalium,
nitrogen dan lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan
kemampuan mengikat air tanah. Berikut syarat mutu zeolit untuk pembawa pupuk
urea (SNI 13-4696-1998):
Ukuran: -10+40 mesh
Kapasitas Tukar Kation (KTK): minimum 120 meq/100 gram
Kandungan mineral zeolitnya tidak kurang dari 50%
Berkadar air 8%
3. Bidang peternakan
Pada bidang peternakan, zeolit digunakan sebagai aditif makanan ternak.
Hewan yang mendapatkan makanan tercampur zeolit umumnya mempunyai
pertumbuhan berat badan yang cepat, kotoran tidak terlalu basah, dan abu kotoran
dapat terkontrol. Fungsi zeolit ini adalah mengatur keasaman dalam sistem
pencernaan, mengikat logam berat yang bersifat racun dan mengikat ammonia serta
NH4+ secara efektif. Berikut syarat mutu zeolit untuk makanan ternak ungags (SNI
13-4697-1998):
19
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Ukuran: -28+100 mesh
Kapasitas Tukar Kation (KTK): minimum 160 meq/100 gram
Bentuk tidak runcing dan PH 6,5-7,5
Berkadar air 5%
4. Bidang pengolahan air
Pada bidang pengolahan air, zeolit digunakan berdasarkan sifat penukar
kation dan adsorpsi yang dimiliki. Zeolit dapat digunakan untuk menurunkan
kandungan warna , NH4+, ion logam seperti Fe, Pb, Mn, Cr dan Ni
II.4 Gelombang
Halliday dan Resnick (1998), mendefinisikan gelombang sebagai sebuah
gangguan periodik dalam suatu medium atau ruang. Gelombang dapat diartikan
sebagai bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Dalam hal ini yang
merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. (Arifin, 2001).
Secara umum gelombang diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu gelombang
mekanik & gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang
yang memerlukan medium merambat, sedangkan gelombang elektromagnetik
tidak memerlukan medium untuk merambat (Trisnobudi, 2006).
Persamaan gelombang mekanik dapat diturunkan dari persamaan gerak
Newton, sedangkan persamaan gelombang elektromagnetik dapat diturunkan dari
persamaan Maxwell (Trisnobudi, 2006). Gelombang berdasar arah rambatannya
dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang
dikelompokkan menjadi gelombang trasnversal jika partikel-partikel mediumnya
bergetar ke atas dan ke bawah dalam arah tegak lurus terhadap gerak gelombang,
sedangkan dikatakan gelombang longitudinal jika arah getaran medium sejajar
dengan arah rambat gelombang (Lohat, 2008)
20
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
II.4.1 Gelombang Akustik
Gelombang akustik adalah sebuah gangguan mekanika yang terkoordinasi
yang melibatkan sejumlah banyak molekul, dimana molekul tersebut bergerak dan
bertumbukan ketika sebuah gangguan gelombang datang dan melewatinya (Kane
dan Sternheim, 1988). Gelombang akustik dapat merambat dalam fluida maupun
dalam padatan. Dalam fluida gelombang akustik merupakan gelombang
longitudinal, sedangkan padatan gelombang akustik dapat berupa gelombang
longitudinal dan gelombang transversal (Trisnobudi, 2006). Sifat gelombang
akustik bergantung pada sifat-sifat dari medium yang dilewatinya (Trisnobudi,
2006).
Kane dan Sternheim (1988) menjelaskan juga bahwa menurut frekuensinya,
gelombang akustik dikelompokan menjadi tiga jenis gelombang yaitu gelombang
infrasonik, gelombang sonik dan gelombang ultrasonik.
1. Gelombang Infrasonik
Gelombang infrasonik dalah gelombang akustik yang mempunyai frekuensi
sangat rendah sehingga tidak dapat didengar langsung oleh telinga manusia.
Gelombang infrasonik memiliki batasan frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh
gelombang infrasonik adalah suara ikan lumba-lumba.
2. Gelombang Sonik
Gelombang sonik adalah gelombang audio yang dapat didengar langsung
indera pendengaran manusia (audible range). Frekuensi gelombang ini berada
pada rentang antara 20 Hz sampai dengan 20 000 Hz. Contoh gelombang sonik
adalah suara manusia.
3. Gelombang Ultrasonik
Gelombang ultrasonik adalah gelombang akustik yang mempunyai frekuensi
diatas 20 000 Hz. Gelombang ini tidak dapat didengar langsung oleh telinga
manusia. Gelombang ultrasonik sudah banyak digunakan pada berbagai peralatan,
21
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
baik peralatan medis untuk pendeteksian bagian dalam tubuh, maupun peralatan
tambahan pada alat transportasi, baik transportasi darat, air, maupun udara
(Buchari, 2007). Prinsip yang digunakan pada peralatan tersebut adalah sama yaitu
dengan membangkitkan gelombang ultrasonik oleh audio generator,
memancarkannya ke obyek lewat transducer kemudian menunggu kapan
gelombang tersebut diterima oleh receiver. Gelombang yang diterima dikuatkan
kembali lewat rangkaian op-amp kemudian diteruskan ke oscilloscope agar
nilainya bisa diamati pada LCD (Satwiko, 2004).
Menurut Halliday dan Resnick (1998) dalam Deni (2007), gelombang bunyi
adalah gelombang mekanis longitudinal. Bunyi terjadi karena adanya kompresi dan
penipisan udara disekitarnya secara bergantian. Gelombang bunyi memerlukan
media perantara untuk perambatannya. Media perantara yang digunakan untuk
perambatan galombang tersebut dapat berupa media padat, cair maupun gas.
Pertikel-partikel media yang mentransmisikan sebuah gelombang seperti itu
berosilasi di dalam arah penjalaran gelombang itu sendiri. Penjalaran pada media
elastis terjadi karena adanya pergeseran dari bagian media elastis dari kedudukan
normalnya. Suatu gelombang mekanis dicirikan oleh pengangkutan tenaga melalui
materi gerak oleh gerak gangguan di dalam materi tersebut tanpa suatu gerak
menggumpal yang bersangkutan dari materi itu sendiri (Daud, 2002).
Analisis gelombang audio dilakukan dengan mentransmisikan gelombang
pada obyek dan mendeteksi gelombang pantulan dari obyek atau mendeteksi
gelombang yang ditransmisikan oleh obyek tersebut. Pengukuran amplitudo
gelombang audio pada alat peraga dilakukan dengan cara mengukur besarnya
simpangan terjauh gelombang dari sumbu kesetimbangan. Nilai amplitudo
pengukuran akan memiliki satuan besaran listrik, yaitu milivolt (mV). Perubahan
besaran fisik menjadi besaran listrik dilakukan receiver yang berperan sebagai
22
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
sensor penerima. Perubahan-perubahan pada amplitudo gelombang audio yang
terukur pada alat peraga digunakan untuk menganalisis tipe obyek yang ada.
II.4 Gelombang Ultrasonik
Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan
frekuensi di atas 20 kHz. Ultrasonik merupakan rambatan energi dan momentum
mekanik sehingga merambat sebagai interaksi dengan molekul dan sifat inersia
medium yang dilaluinya (Bueche, 1986). Karakteristik gelombang ultrasonik yang
melalui medium mengakibatkan getaran partikel dengan medium amplitudo sejajar
dengan arah rambat secara longitudinal. Sehingga menyebabkan partikel medium
membentuk rapatan (strain) & tegangan (stress). Proses kontinu selama gelombang
ultrasonik melaluinya menyebabkan terjadinya rapatan dan tegangan di dalam
medium disebabkan oleh getaran partikel secara periodik (Resnick dan Halliday,
1992).
Gelombang ultrasonik mempunyai sifat memantul, diteruskan dan diserap
oleh suatu medium atau jaringan. Apabila gelombang ultrasonik ini mengenai
permukaan medium, maka sebagian gelombang ultrasonik ini akan dipantulkan
dan sebagian lagi akan ditransmisikan. Getaran ultrasonik yang merambat ke dalam
jaringan atau zat cair akan mengalami efek kavitasi. Efek kavitasi terjadi karena
tekanan lokal pada gelombang ultrasonik menurun sampai harga yang cukup
rendah (Anies, 2005). Berikut evek kavitasi yang terjadi pada proses sonikasi
ditunjukkan pada gambar II.5
23
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Gambar II.5: Evek Kavitasi
Besar tekanan gelombang ultrasonik dinyatakan sebagai :
p = P – Po
dengan: p = tekanan gelombang ultrasonik (N/m2)
P = tekanan lokal/total sesaat (N/m2)
Po = tekanan lokal rata-rata/ keseimbangan (N/m2)
Intensitas gelombang ultrasonik yang merambat akan membawa energi pada
suatu luas permukaan per satuan waktu (Giancoli, 1998). Energi gelombang
ultrasonik tersebut melalui jaringan akan melepaskan energi kalor sehingga terjadi
pemanasan yang mengakibatkan suhu jaringan meningkat yang kemudian
menimbulkan efek kavitasi. Besarnya pemanasan tergantung pada variasi tekanan
gelombang ultrasonik dan kecepatan partikel terhadap energi yang diberikan
(Ackerman, et al., 1988).
Perambatan gelombang ultrasonik dalam suatu medium, maka partikel akan
mengalami perpindahan energi. Besarnya energi gelombang ultrasonik yang
dimiliki partikel medium adalah:
24
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
E = Ep+Ek
E = h.f.NA
Dengan:
Ep = Energi potensial
Ek = Energi kinetik
NA = Bilangan Avogadro
h = konstanta Planck
f = frekuensi
Perhitungan intensitas gelombang ultrasonik perlu mengetahui energi yang dibawa
oleh gelombang ultrasonik. Intensitas gelombang ultrasonik (I) adalah energi yang
melewati luas permukaan medium 1m2/s atau watt/m2 (Deni, 2007).
Efek penggunaan gelombang ultrasonik pada substrat dapat disebabkan
karena adanya efek termal, kavitasi dan mekanik. Efek termal adalah absorpsi
energi gelombang ultrasonik yang menyebabkan suhu atom/molekul meningkat.
Besar absorpsi energi gelombang tergantung pada viskositas, massa jenis dan
impedansi (Sari, 2009). Gelombang ultrasonik yang merambat melalui medium
mengalami pengurangan energi, karena sebagian energinya diabsorpsi medium.
Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu medium dimana tergantung pada besar
koefisien absorpsi & intensitas yang melaluinya (Trisnobudi, 2006). Efek kavitasi
merupakan terjadinya gelembung gas di dalam medium karena pemanasan lokal
dengan tekanan yang bervariasi, sehingga di dalam medium terbentuk gelembung
gas mikro. Gas di dalam medium dapat memuai jika diradiasi ultrasonik tinggi,
sehingga terjadi difusi gas yang tidak seimbang (Trisnobudi, 2006).
Efek mekanik ditimbulkan gelombang ultrasonik adalah getaran partikel di
dalam medium. Getaran terjadi pada semua intensitas, sehingga menyebabkan efek
mekanik. Efek mekanik akan menimbulkan percepatan partikel, getaran, tekanan
pancaran, gaya gesek (Sabbagha, 1980). Aplikasi gelombang ultrasonik pada
25
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
padat-cair atau suspensi cairan-kristal menghasilkan kecepatan tabrakan antar
partikel yang tinggi. Pengaruh yang ditimbulkan dapat mengubah morfologi
permukaan, komposisi, dan reaktivitas, sehingga ultrasonikasi dapat digunakan
sebagai deaglomerasi dan pengecilan material berukuran micrometer atau
nanometer serta untuk disintegrasi sel atau pencampuran pereaksi (Lohat, 2008).
26
Aktivasi Dan Karakterisasi..., Wancuh, Fakultas Teknik dan Sains, 2019
Anda mungkin juga menyukai
- Pertemuan 8 UTS Desain ALat Industri Kimia - SOAL B NIM GENAPDokumen2 halamanPertemuan 8 UTS Desain ALat Industri Kimia - SOAL B NIM GENAPSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Resume ATK 3 For UtSDokumen12 halamanResume ATK 3 For UtSSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Nomor 1. Soal PeraturanDokumen25 halamanNomor 1. Soal PeraturanSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Perancangan Proses Kimia UTSDokumen2 halamanPerancangan Proses Kimia UTSSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Invoice 3155309060Dokumen1 halamanInvoice 3155309060Syadila LutfiBelum ada peringkat
- Pakta Integritas Uts Ganjil 23-24Dokumen1 halamanPakta Integritas Uts Ganjil 23-24Syadila LutfiBelum ada peringkat
- NL FormDokumen2 halamanNL FormSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Harga Jual by CarajualanDokumen3 halamanHarga Jual by CarajualanSyadila LutfiBelum ada peringkat
- 3kontrk Kuliah Termodinamika TK IidocxDokumen6 halaman3kontrk Kuliah Termodinamika TK IidocxSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Limit SampleDokumen2 halamanLimit SampleSyadila LutfiBelum ada peringkat
- MekfluDokumen1 halamanMekfluSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Plastik Dan MasterbatchDokumen14 halamanPlastik Dan MasterbatchSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Cat Mhs Flow04 - Pemutaran KembaliDokumen6 halamanCat Mhs Flow04 - Pemutaran KembaliSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Pengumuman Surat Panggilan Tes Seleksi Calon Pegawai PT - Jakarta International Container Terminal (JICT)Dokumen4 halamanPengumuman Surat Panggilan Tes Seleksi Calon Pegawai PT - Jakarta International Container Terminal (JICT)Syadila LutfiBelum ada peringkat
- Pasien Undip PKMKDokumen30 halamanPasien Undip PKMKSyadila LutfiBelum ada peringkat
- CLAPR1035IN0116 Fasilitas Clariant Di Tangerang Mendapatkan Sertifikasi Halal Di IndonesiaDokumen3 halamanCLAPR1035IN0116 Fasilitas Clariant Di Tangerang Mendapatkan Sertifikasi Halal Di IndonesiaSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Contoh Soal Ujian Komprehensif Teknik Kimia Undip 2010Dokumen22 halamanContoh Soal Ujian Komprehensif Teknik Kimia Undip 2010Syadila LutfiBelum ada peringkat
- Lembar Jawaban Papi KostickDokumen1 halamanLembar Jawaban Papi KostickSyadila LutfiBelum ada peringkat
- Surat Pengajuan Pemotongan 50% UktDokumen1 halamanSurat Pengajuan Pemotongan 50% UktSyadila LutfiBelum ada peringkat