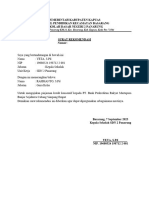Bab V RPK Kating
Bab V RPK Kating
Diunggah oleh
Fauzan MuttaqinJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab V RPK Kating
Bab V RPK Kating
Diunggah oleh
Fauzan MuttaqinHak Cipta:
Format Tersedia
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Asuhan keperawatan pada Ny. W dengan diagnosa medis Skizofrenia Tak
Terinci dilaksanakan di wisma Srikandi Rumah Sakit Jiwa Grhasia. Asuhan
keperawatan ini meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi,
implementasi dan evaluasi keperawatan yang berfokus pada masalah utama risiko
perilaku kekerasan dengan menerapkan terapi musik sebagai landasan Evidence
Based Nursing dalam proses keperawatan.
A. Pengkajian Keperawatan
Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan yang
diberikan pada Ny. W dan dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022.
Pengkajian ini dilakukan dengan metode wawancara, pemeriksaan fisik,
observasi, dan studi dokumentasi. Selama proses pengkajian, pengumpulan
data diperoleh dari beberapa sumber yaitu pasien, perawat dan rekam medis.
Dari hasil pengkajian didapatkan beberapa karakteristik pasien yang meliputi
jenis kelamin perempuan, status perkawinan sudah menikah, usia 33 tahun,
dan pendidikan terakhir SMK.
Karakteristik pasien dalam kasus ini dalah Ny. W berjenis kelamin
perempuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Livana dan Suerni
(2019), menyatakan bahwa sebanyak 65% responden berisiko mengalami
kekerasan mayoritas adalah laki-laki. Hal ini karena laki-laki cenderung
bersifat agresif dan memiliki tingkat emosional yang lebih tinggi daripada
55 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
56
wanita. Laki-laki cenderung tertutup ataupun malu untuk bercerita dan sering
memendam masalah ataupun stress psikologis sendirian sehingga jika tidak
mempunyai mekanisme koping yang kostruktif maka laki-laki memiliki
kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami gangguan jiwa dalam jangka
waktu tertentu. Selain itu laki-laki terutama yang sudah dewasa memiliki
tanggung jawab yang semakin meningkat sebagai tulang punggung keluarga
sehingga semakin mudah mengalami stress. Sedangkan Ny. W berjenis
kelamin perempuan karena tidak menutup kemungkinan seorang perempuan
juga bisa mengalami gangguan jiwa. Tentu saja hal ini bisa dipengaruhi oleh
banyak faktor yang menjadi masalah di kehidupannya. Selain itu asuhan
keperawatan ini dilakukan di wisma rawat inap putri sehingga yang ada hanya
pasien dengan jenis kelamin perempuan.
Ny. W memiliki status perkawinan sudah menikah dan sudah pisah
rumah dengan suaminya sejak 10 bulan sebelum masuk rumah sakit. Menurut
NANDA (2016) dalam Sutejo (2022) menyatakan bahwa salah satu faktor
risiko dari risiko perilaku kekerasan adalah status perkawinan. Berbagai
masalah yang terjadi dalam perkawinan dapat menjadi sumber stress bagi
seseorang dan merupakan salah satu penyebab umum terjadinya gangguan
jiwa. Masalah yang sering terjadi selama perkawinan misalnya adalah
pertengkaran, ketidaksetiaan, kematian salah satu pasangan, dan perceraian.
Usia Ny. W pada saat dilakukan pengkajian adalah 33 tahun yang
merupakan usia dewasa dan produktif. Pada usia ini dituntut untuk pencapaian
aktualisasi diri, mampu membina hubungan baik dengan masyarakat,
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
57
hubungan kerja, dan hubungan yang intim dengan orang lain. Jika seseorang
mengalami banyak gangguan pada masa sebelumnya, maka apabila seseorang
mengalami masalah pada masa dewasa ini akan menyulitkan pemenuhan
kebutuhan perkembangan dalam umur itu sehingga akan berisiko mengalami
gangguan jiwa (Yosep, 2011). Penelitian yang dilakukan Subagyo et al.,
(2018) menunjukkan hasil bahwa pasien dengan risiko perilaku kekerasan
terbanyak berada pada rentang usia 26-35 tahun yaitu 52,6 %. Sukmawati
(2010) dalam Subagyo et al., (2018) juga menyebutkan bahwa berdasarkan
data American Psychiatric Association (APA) penderita gangguan jiwa
terbanyak pada usia yang masih produktif. Ny. W mengalami kegagalan
dalam tahapan ini sehingga memiliki kecenderungan berbuat apa saja sesuka
hatinya termasuk menginginkan anak keduanya mati dan selalu merasa ingin
marah jika ada konflik. Tentu saja kegagalan ini terjadi karena beberapa
stressor yang dihadapinya seperti pernah bekerja sebagai SPG namun sekarang
sudah berhenti. Ny. W merasa tidak mampu menunjukkan kemandirian dan
tanggung jawab untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.
Karakteristik pendidikan Ny. W adalah SMK. Tingkat pendidikan sangat
berpengaruh terhadap cara seseorang berperilaku, membuat keputusan dan
memecahkan masalah, serta mempengaruhi cara penilaian seseorang terhadap
stresor. Notoatmodjo (2003) dalam Subagyo et al., (2018) menyebutkan
bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap pengetahuan yang akan menjadi stimulus terjadinya sikap yang
nantinya akan melandasi tindakan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
58
pendidikan seseorang maka akan semakin baik mekanisme koping dari orang
tersebut dalam menyikapi suatu hal yang terjadi dalam kehidupannya. Ny. W
memiliki tingkat pendidikan SMK yang termasuk dalam pendidikan
menengah atas, namun kemungkinan karena keterbatasan kemampuan untuk
berinteraksi dan mengelola stressor atau masalah baik dari diri sendiri dan
lingkungannya sehingga menyebabkan Ny.W mengalami gangguan jiwa. Hal
ini sejalan dengan penelitian Livana dan Suerni (2019) yang menunjukkan
hasil bahwa sebagian besar pasien memiliki pendidikan menengah sebanyak
61 %.
Alasan masuk Ny. W dirawat pada tanggal 22 Oktober 2022 adalah
mengamuk, marah-marah, mengancam anak dengan pisau, membawa pisau
kalau tidur, pasien tidak menghendaki anak dari kehamilannya yang kedua dan
menginginkan anaknya mati, mengancam ayah dan kakaknya, bicara sendiri
dan ngelantur. Keluarga pasien sudah berusaha untuk menenangkan pasien
namun tidak berhasil. Keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa ke
rumah sakit jiwa.
Perilaku agresif yang dilakukan Ny. W sudah sesuai dengan pendapat
Stuart (2016) bahwa perilaku yang berhubungan dengan agresi ditunjukkan
dengan penyimpangan pada agitasi motorik yaitu berjalan dengan cepat, tidak
bisa diam, mengepalkan atau memukulkan tangan, mengencangkan/
merapatkan rahang, pernapasan meningkat, catatonia. Pada kemampuan
verbal dijumpai adanya berbicara mengancam dengan obyek yang nyata atau
tidak nyata, meminta perhatian yang mengganggu, berbicara keras dan dengan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
59
penekanan, waham atau curiga. Perubahan afek menunjukkan marah,
bermusuhan, ansietas berat, mudah tersinggung, euphoria yang tidak wajar
atau berlebihan dan afek yang tidak stabil. Pada tingkat kesadaran dijumpai
perilaku bingung, perubahan status mental yang tiba-tiba, disorientasi,
kerusakan memori dan tidak bisa diarahkan.
Perilaku agresif yang ditunjukkan Ny. W juga didukung oleh penelitian
yang dilakukan oleh Suerni dan Livana (2019) dimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa mayoritas responden berespons kognitif berupa
perubahan isi pikir dan menyalahkan orang lain, respons afektif berupa
perasaan tidak nyaman, respons fisiolofis berupa pandangan tajam dan tangan
mengepal, respons perilaku berupa memukul benda/ orang dan agresif,
respons sosial berupa sering mengungkapkan keinginannya dengan nada
mengancam.
Pengkajian tanggal 31 Oktober 2022 ditemukan data bahwa perilaku
agresif pasien sudah tidak terjadi, namun pasien masih menunjukkan beberapa
tanda dan gejala yang berisiko perilaku kekerasan, antara lain nada bicara
pasien agak meninggi saat diajak berbicara tentang keluarganya, terkadang
ekspresi muka tampak tegang, afek masih labil dan asesmen risiko perilaku
kekerasan ada pada skor enam (risiko sedang). Hal ini mungkin disebabkan
karena pasien sudah mendapatkan terapi psikofarmaka dan terapi modalitas di
wisma maintenance sehingga pasien lebih mampu mengontrol perilaku
agresinya. Selain itu pasien juga jauh dari keluarga yang merupakan faktor
utama pemicu perilaku kekerasan yang dilakukan pasien.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
60
Faktor-faktor yang mendukung terjadinya perilaku kekerasan pada Ny.
W adalah pasien memiliki riwayat gangguan jiwa sudah lebih dari 10 tahun,
pernah dirawat karena mengamuk, riwayat minum obat tidak pernah teratur
dan putus obat. Pasien mengatakan neneknya yang dari ibu pernah mengalami
gangguan jiwa namun sudah meninggal. Pasien mempunyai pengalaman masa
lalu yang tidak menyenangkan seperti tertipu dan pisah rumah dengan suami.
Pasien merasa anggota keluarga yang lain tidak bisa mengerti apa yang pasien
inginkan dan pasien membenci anak keduanya karena merasa menambah
beban hidupnya.
Faktor-faktor yang mendasari perilaku agresi Ny. W sudah sesuai dengan
beberapa teori yang ada. Berdasarkan teori dari Yosep (2011), salah satu faktor
predisposisi penyebab pasien mengalami gangguan jiwa yaitu faktor genetik di
mana adanya faktor genetik yang diturunkan melalui orangtua menjadikan
potensi perilaku agresif. Individu yang memiliki hubungan sebagai keponakan
atau cucu kejadiannya 2-4 %, dalam hal ini diturunkan oleh nenek pasien dari
garis ibu. Berdasarkan Stuart (2013) dalam Sutejo (2022), teori agresif frustasi
menyatakan bahwa perilaku kekerasan dapat terjadi sebagai akibat dari
akumulasi frustasi yang terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai
sesuatu gagal atau terhambat. Pasien merasa anggota keluarga yang lain tidak
bisa mengerti apa yang pasien inginkan. Selain itu dari faktor internal pasien
merasa kehilangan rasa cinta terhadap anak keduanya dan kehilangan relasi
atau hubungan dengan orang yang dicintai karena pisah rumah dengan
suaminya.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
61
Faktor yang mendasari perilaku agresi Ny. W juga sesuai dengan
penelitian yang dilakukan Livana dan Suerni (2019) dimana hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pernah dirawat
sebelumnya dan ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Ny. W sudah pernah
dirawat karena mengamuk sehingga pasien sudah pernah mendapatkan
pembelajaran tentang cara mengontrol perilaku kekerasan baik secara individu
maupun kelompok. Akan tetapi, pasien belum mampu melaksanakannya
secara maksimal sehingga masih saja menunjukkan perilaku kekerasan pada
saat marah. Selain itu Ny. W mempunyai riwayat pengobatan tidak teratur
bahkan sampai putus obat karena pasien merasa tidak sakit sehingga tidak
perlu minum obat terus menerus.
Tinjuan teori dalam SDKI (2017) menyebutkan tanda dan gejala mayor
meliputi subyektif yaitu mengancam, mengumpat dengan kata-kata kasar,
suara keras dan bicara ketus. Obyektif yaitu menyerang orang lain, melukai
diri sendiri/orang lain, merusak lingkungan dan perilaku agresi/amuk. Tanda
dan gejala minor meliputi obyektif yaitu mata melotot atau pandangan tajam,
tangan mengepal, rahang mengatup, wajah memerah, dan postur tubuh kaku.
Tanda dan gejala perilaku kekerasan menurut hasil penelitian yang dilakukan
oleh Amimi et al., (2020) menguraikan bahwa tanda dan gejala pasien risiko
perilaku kekerasan yang sering muncul adalah mengepalkan tangan, bicara
kasar, suara tinggi, menjerit atau berteriak. Pada saat pengkajian, masih
didapatkan tanda dan gejala yang berisiko perilaku kekerasan yaitu nada
bicara pasien agak meninggi saat diajak berbicara tentang keluarganya,
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
62
terkadang ekspresi muka tampak tegang, afek masih labil dan asesmen risiko
perilaku kekerasan skor enam (risiko sedang). Sementara untuk tanda dan
gejala lainnya sudah tidak muncul. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien
sudah mendapatkan terapi psikofarmaka secara rutin selama sembilan hari dan
sudah mengikuti terapi modalitas di wisma maintenance sehingga pasien lebih
mampu mengontrol perilaku agresinya. Selain itu pasien juga jauh dari
keluarga yang merupakan faktor utama pemicu perilaku kekerasan yang
dilakukan pasien.
B. Diagnosa Keperawatan
Menurut SDKI (2017), diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian
klinik mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses
kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial.
Diagnosa keperawatan merupakan bagian vital dalam menentukan asuhan
keperawatan yang sesuai untuk membantu pasien mencapai kesehatan yang
optimal. Berdasarkan hasil dari pengkajian yang penulis lakukan, maka
ditegakkan tiga diagnosa keperawatan dimana yang utama yaitu risiko
perilaku kekerasan dibuktikan dengan riwayat atau ancaman kekerasan
(D.0146). Diagnosa keperawatan yang kedua adalah gangguan persepsi
sensori berhubungan dengan gangguan penglihatan dan pendengaran
dibuktikan dengan pasien mengatakan masih mendengar bisikan-bisikan yang
memberi tahu tentang sesuatu dan melihat bayangan binatang yang aneh-aneh
yang munculnya setiap saat yang membuat pasien ketakutan, pasien
mengatakan merasa gelisah dan memejamkan mata biar tidak melihatnya,
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
63
terkadang pasien tampak bicara sendiri dengan lirih, pasien banyak tiduran di
kamar, afek masih labil (D.0085). Diagnosa keperawatan yang ketiga adalah
ketidakpatuhan berhubungan dengan program terapi kompleks dan/atau lama
dibuktikan dengan pasien memiliki riwayat gangguan jiwa sudah lebih dari
10 tahun, pasien selama dirawat tidak pernah sembuh dan riwayat minum
obat tidak pernah teratur, pasien putus obat sejak 10 bulan yang lalu karena
pasien merasa tidak sakit sehingga tidak perlu minum obat terus menerus,
afek masih labil (D.0114).
Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Azizah et al., (2016),
diagnosa keperawatan yang muncul adalah perilaku kekerasan, risiko
mencederai diri sendiri orang lain dan lingkungan, perubahan persepsi sensori
: halusinasi, gangguan harga diri : harga diri rendah dan koping individu tidak
efektif. Berdasarkan data-data yang diperoleh pada pasien saat pengkajian,
maka penulis menetapkan diagnosa risiko perilaku kekerasan sebagai core
problem, perilaku kekerasan sebagai affect dan gangguan persepsi sensori
serta ketidakpatuhan sebagai cause. Diagnosa keperawatan tersebut memiliki
kesenjangan dengan teori yang dikemukakan oleh Azizah et al., (2016) yang
menetapkan bahwa perilaku kekerasan sebagai core problem, risiko
mencederai diri sebagai affect dan gangguan harga diri : harga diri rendah
sebagai cause.
Penulis menetapkan risiko perilaku kekerasan sebagai masalah utama
karena pada saat pengkajian pasien tidak menunjukkan perilaku agresifnya,
namun pasien memiliki riwayat melakukan perilaku kekerasan. Selain itu
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
64
pada pasien masih ditemukan tanda dan gejala yang berisiko memicu perilaku
kekerasan yaitu nada bicara pasien agak meninggi saat diajak berbicara
tentang keluarganya, terkadang ekspresi muka tampak tegang dan afek masih
labil. Pasien juga menunjukkan skor enam (risiko sedang) pada saat asesmen
risiko perilaku kekerasan. Jika tanda dan gejala yang masih muncul ini tidak
tertangani dengan baik maka dapat memicu munculnya perilaku kekerasan
baik pada diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan.
Penulis tidak menegakkan diagnosa keperawatan harga diri rendah
karena pada pasien tidak dijumpai adanya tanda dan gejala yang mengarah
pada masalah tersebut. Akan tetapi penulis menemukan tanda dan gejala yang
menunjukkan gangguan persepsi sensori yang kemudian ditetapkan sebagai
cause karena dapat memicu munculnya perilaku yang berisiko terhadap
perilaku kekerasan terutama jika pasien sudah masuk dalam tahap
conquering. Sedangkan diagnosa keperawatan ketidakpatuhan juga
ditambahkan dalam cause karena ada riwayat putus obat dan jika pasien tidak
mendapat penanganan yang tepat terkait masalah ini maka perilaku kekerasan
dapat terjadi.
Yosep (2011) menyatakan bahwa salah satu akar permasalahan dari
perilaku kekerasan adalah koping keluarga yang tidak efektif. Pengkajian dari
pasien memunculkan data terkait permasalahan dalam keluarganya, antara
lain pasien tidak menghendaki anak dari kehamilannya yang kedua,
menginginkan anaknya mati saja, pasien sering mencubit anak keduanya,
berbicara keras dengan anaknya, mengancam anaknya dengan pisau,
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
65
mengancam ayah dan kakaknya, pasien merasa keluarga tidak bisa mengerti
yang diinginkan pasien, pisah rumah dengan suaminya sudah 10 bulan,
riwayat sakit jiwa sudah 10 tahun dan riwayat putus obat selama 10 bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan dukungan dari keluarga terhadap
perawatan dan pengobatan pasien di rumah.
Penelitian Wardana et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan
anatara dukungan keluarga dengan tingkat kekambuhan pasien dengan risiko
perilaku kekerasan. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam
perawatan pasien selama di rumah, Namun penulis tidak menegakkan
diagnosa keperawatan terkait keluarga karena pada saaat pengkajian penulis
tidak bertemu dengan keluarga. Data yang didapat terkait hubungan dalam
keluarga didapatkan dari wawancara dengan pasien dan studi dokumentasi
pada rekam medis pasien. Selain itu pelaksanaan intervensi yang melibatkan
keluarga akan sulit dilakukan karena selama sembilan hari dirawat pasien
belum pernah dikunjungi oleh anggota keluarganya.
C. Perencanaan Keperawatan
Perencanaan atau intervensi keperawatan adalah segala bentuk
treatment yang dikerjakan perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan
penilaian klinis untuk mencapai outcome atau luaran yang diharapkan (SIKI,
2018). Intervensi keperawatan pada pasien ini difokuskan pada masalah
keperawatan utama yaitu risiko perilaku kekerasan. Namun bersamaan
dengan itu penulis juga melakukan intervensi terhadap diagnosa keperawatan
lainnya yaitu gangguan persepsi sensori dan ketidakpatuhan.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
66
Intervensi dari risiko perilaku kekerasan memiliki luaran utama (kontrol
diri) dan luaran tambahan (harga diri, orientasi kognitif, status orientasi)
(SLKI, 2018). Sesuai dengan kondisi pasien yang masih menunjukkan
perilaku yang berisiko munculnya perilaku kekerasan maka penulis
menetapkan luarannya adalah kontrol diri meningkat. Selain itu status
orientasi pasien juga masih baik.
Berdasarkan SIKI (2018), intervensi yang dilakukan penulis untuk
risiko perilaku kekerasan adalah intervensi utama yaitu pencegahan perilaku
kekerasan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ataupun tanda dan gejala yang
ditemukan pada pasien saat pengkajian. Sedangkan untuk intervensi
pendukung tidak dilakukan karena mengingat waktu yang terbatas dalam
pelaksanaan intervensi keperawatan. Intervensi dalam pencegahan perilaku
kekerasan meliputi monitor adanya benda yang berpotensi membahayakan
(mis.benda tajam, tali), monitor keamanan barang yang dibawa oleh
pengunjung, monitor selama penggunaan barang yang dapat membahayakan
(mis,pisau cukur), pertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin,
libatkan keluarga dalam perawatan, anjurkan pengunjung dan keluarga untuk
mendukung keselamatan pasien, latih cara mengungkapkan perasaan secara
asertif, dan latih mengurangi kemarahan secara verbal dan non verbal (mis.
relaksasi, bercerita, terapi musik) (SIKI, 2018).
Penulis memberikan intervensi kepada pasien sesuai dengan keadaan
dan tanda gejala yang ditemukan pada pasien sehingga tidak semua intervensi
utama pada pencegahan perilaku kekerasan diberikan kepada pasien. Adapun
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
67
intervensi yang tidak diberikan pada pasien adalah yang melibatkan
pengunjung dan keluarga. Hal ini disebabkan karena selama sembilan hari
dirawat pasien tidak pernah mendapat kunjungan dari anggota keluarganya
maupun orang lain di luar rumah sakit. Selain itu dalam kasus ini Ny.W
masih menunjukkan gejala yang mengarah pada risiko munculnya perilaku
kekerasan dimana keluarga menjadi pemicu konflik yang menyebabkan
pasien emosi.
Intervensi diagnosis risiko perilaku kekerasan berdasarkan Evidence
Based Nursing pada jurnal Ye et al., (2021) mengatakan bahwa menggunakan
intervensi berbasis musik tampaknya lebih manjur untuk mengurangi agresi
dan meningkatkan kontrol diri pada anak dan remaja. Hal inilah yang
mendorong penulis untuk menerapkan terapi musik sebagai salah satu
manajemen pengendalian marah, namun perlakuannya dilakukan pada pasien
usia dewasa yaitu 33 tahun. Selain itu didukung pula oleh hasil penelitian
Bensimon et al., (2018) yaitu musik relaksasi yang dipilih oleh pasien
memiliki efek positif pada keadaan emosi dan aktivitas perilaku mereka dan
oleh karena itu dapat berfungsi sebagai intervensi sensorik alternatif sebelum
pasien mencapai situasi kekerasan yang memerlukan pengekangan. Terapi ini
termasuk dalam intervensi latih mengurangi kemarahan secara verbal dan non
verbal (mis. relaksasi, bercerita) yang berfokus pada kegiatan relaksasi
dengan menggunakan musik (SIKI, 2018).
Intervensi yang dipilih untuk gangguan persepsi sensori berdasarkan
standar yang berlaku adalah manajemen halusinasi dimana kegiatannya
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
68
berfokus pada edukasi ke pasien tentang cara-cara mengontrol halusinasi
yang muncul. Sedangkan intervensi untuk ketidakpatuhan yang ditetapkan
adalah dukungan kepatuhan program pengobatan dimana pasien diberikan
pemahaman tentang pentingnya patuh minum obat.
D. Implementasi Keperawatan
Penulis melakukan tindakan keperawatan untuk risiko perilaku
kekerasan sesuai dengan intervensi yang telah disusun sebelumnya
berdasarkan standar keperawatan yang berlaku selama tiga hari dengan
penerapan terapi musik. Terapi musik ini diberikan sekali sehari setelah
pasien diberikan terapi generalis tentang cara-cara mengendalikan
marahnya. Terapi musik dilakukan selama 15 menit dimana pasien diminta
untuk mendengarkan musik klasik Mozart Classical Music For Relaxation
yang diputar melalui handphone dengan menggunakan earphone. Pasien
juga diminta mengatur pola pernafasan agar lebih rileks sehingga
diharapkan terjadi penurunan skor dalam asesmen risiko perilaku kekerasan
setelah dilakukan terapi musik.
Musik adalah salah satu terapi yang bersifat non verbal. Terapi dengan
bantuan musik pikiran pasien dibiarkan mengembara, baik untuk
mengenang hal-hal yang membahagiakan, membayangkan ketakutan-
ketakutan yang dirasakan, mengangankan hal-hal yang dicita-citakan, atau
langsung mencoba menguraikan permasalahan yang dihadapi (Djohan,
2015). Penerapan terapi musik dalam intervensi pencegahan perilaku
kekerasan ini didukung oleh penelitian dari Agnecia et al., (2021) yang
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
69
menunjukkan hasil terapi musik klasik memberi pengaruh terhadap pasien
risiko perilaku kekerasan dimana terjadi penurunan tanda dan gejala
perilaku kekerasan sebesar 58 %. Pelaksanaan terapi musik dalam penelitian
ini dilakukan sehari dua sesi yaitu pagi dan sore. Hal ini berarti juga terjadi
kesenjangan dalam proses pelaksanaan terapi musik pada pasien. Penulis
melakukan sekali sehari dengan pertimbangan bahwa pasien juga sudah
mendapatkan terapi modalitas yang lain di hari itu, misalnya terapi aktivitas
kelompok, terapi perilaku ataupun terapi generalis.
Penerapan terapi musik dalam intervensi pencegahan perilaku
kekerasan ini juga didukung oleh penelitian dari Vahurina dan Desi A.R
(2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa ada penurunan tanda dan
gejala resiko perilaku kekerasan setelah diberikan intervensi inovasi terapi
musik instrumental piano, dimana pada partisipan satu mengalami
penurunan tanda dan gejala dari angka tujuh turun menjadi empat dan pada
partisipan dua dari angka delapan menjadi tiga. Terapi dalam jurnal ini
dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan dalam waktu 10 menit. Hal ini
berarti juga terjadi kesenjangan karena penulis melakukan terapi musik
sebanyak tiga kali pertemuan selama 15 menit dengan harapan pasien lebih
bisa berkonsentrasi dalam mendengarkan musik yang diputar. Selain itu
dalam penelitian tersebut juga dilakukan tehnik relaksasi nafas dalam dan
tehnik pukul bantal terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi musik,
sedangkan penulis memberikan edukasi tentang manajemen marah secara
lebih lengkap meliputi cara fisik, patuh minum obat, cara verbal dan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
70
spiritual agar pasien paham tentang berbagai macam cara mengontrol marah
yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang dialaminya.
Pelaksanaan terapi musik dalam asuhan keperawatan ini juga
mempunyai kesenjangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gassner et
al., (2021). Penelitian tersebut menyatakan bahwa durasi intervensi dalam
terapi musik adalah mingguan hingga enam sesi per minggu (40-120 menit)
selama satu sampai enam bulan. Sementara terapi musik dalam asuhan
keperawatan ini hanya dilakukan satu sesi sehari selama tiga hari dengan
waktu 15 menit. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam pemberian
asuhan keperawatan.
Tahap implementasi untuk gangguan persepsi sensori dilakukan sesuai
dengan intervensi berdasarkan SIKI (2018) yaitu manajemen halusinasi. Di
sini pasien diberikan terapi generalis tentang cara-cara mengontrol
halusinasi yang muncul. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan
oleh Livana PH, dkk (2020) yang menyatakan bahwa ada peningkatan
kemampuan pasien halusinasi sebesar 64% sebelum dan sesudah diberikan
terapi generalis dengan cara melatih ingatan dan kemampuan pasien untuk
mengontrol halusinasinya.
Tahap implementasi untuk ketidakpatuhan dilakukan sesuai dengan
intervensi berdasarkan SIKI (2018) yaitu dukungan kepatuhan program
pengobatan. Di sini pasien diberikan edukasi tentang pentingnya kepatuhan
minum obat secara mandiri untuk mencegah kekambuhan baik selama
perawatan maupun setelah pulang ke rumah. Hal ini didukung oleh Nengsih
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
71
(2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh terapi Modeling Partisipan
terhadap kepatuhan minum obat pasien skizofrenia.
E. Evaluasi Keperawatan
Evaluasi adalah merupakan tahap akhir dari proses keperawatan.
Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi yang telah
dilaksanakan sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan atau tidak. Hal ini
dilakukan dengan cara membandingkan respon pasien sebelum dan sesudah
mendapatkan tindakan keperawatan.
Evaluasi yang didapat dari pasien Ny. W dengan diagnosa keperawatan
risiko perilaku kekerasan, setelah diberikan tindakan keperawatan selama tiga
hari sesuai dengan intervensi yang telah disusun dan ditambah dengan terapi
musik menunjukkan capaian kriteria hasil sesuai untuk masalah risiko
perilaku kekerasan teratasi sebagian. Pasien menunjukkan perkembangan
perilaku dalam kemampuan mengendalikan marah karena didapatkan data
subyektif pasien mengatakan sudah tenang dan jika pulang tidak ingin
berbuat masalah dengan keluarganya dan data obyektif pasien tampak tenang,
ekspresi wajah cerah, pasien mampu mengikuti kegiatan dengan baik, pasien
mampu mendengarkan musik dengan konsentrasi serta asesmen risiko
perilaku kekerasan skornya dua (risiko ringan). Hal ini berarti pasien sudah
cukup kooperatif dan mampu untuk memahami setiap perlakuan yang
diberikan sehingga mampu mengontrol emosi atau marahnya. Namun
intervensi masih tetap dilanjutkan dalam mempertahankan lingkungan bebas
dari bahaya secara rutin.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
72
Evaluasi keperawatan pada pasien Ny. W dengan diagnosa keperawatan
gangguan persepsi sensori, setelah diberikan tindakan keperawatan selama
tiga hari sesuai dengan intervensi yang telah disusun maka didapatkan
capaian kriteria hasil yang sesuai yaitu teratasi sebagian. Pasien menunjukkan
perkembangan dalam kemampuaan manajemen halusinasinya yang
dibuktikan dengan adanya data subyektif pasien mengatakan halusinasi sudah
berkurang, pasien mengatakan mengikuti kegiatan rehabilitasi mental di
bagian boga. Untuk data obyektif mencakup pasien kooperatif, pasien mau
duduk bersama temannya di ruang makan, pasien mau minum obat
Risperidone 2 mg 1 tablet, Trihexyphenidyl 2 mg ½ tablet dan Clozapine 25
mg ½ tablet. Hal ini berarti pasien cukup kooperatif selama dilakukan
tindakan keperawatan dan cukup mengerti dengan pendidikan kesehatan yang
diberikan dalam rangka mengontrol halusinasinya. Namun intervensi masih
tetap dilanjutkan dalam mempertahankan lingkungan yang aman dan
mengelola pemberian obat antipsikotik.
Evaluasi yang didapat dari pasien Ny. W dengan diagnosa keperawatan
ketidakpatuhan, setelah diberikan tindakan keperawatan selama tiga hari
sesuai dengan intervensi yang telah disusun maka didapatkan capaian kriteria
hasil yang sesuai yaitu teratasi sebagian. Pasien menunjukkan perkembangan
dalam kepatuhan mengikuti program pengobatan yang ditunjukkan melalui
data subyektif pasien mengatakan akan rajin kontrol dan minum obat teratur
jika sudah pulang biar tidak kambuh lagi dan data obyektif meliputi pasien
nampak tenang, pasien mengerti penjelasan perawat, obat oral Risperidone 2
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
73
mg 1 tablet masuk pukul 18.00 WIB, obat oral Trihexyphenidyl 2 mg ½ tablet
masuk pada pukul 18.00 WIB, obat oral Clozapine 25 mg ½ tablet masuk
pukul 18.00 WIB. Perkembangan ini dicapai pasien dengan baik karena
pasien sudah tenang dan cukup kooperatif selama diberikan tindakan
keperawatan untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan. Namun intervensi
tetap dilanjutkan dengan evaluasi komitmen dalam menjalani program
pengobatan dengan baik.
Dari ketiga diagnosis keperawatan yang ditegakkan semuanya
menunjukkan kalau masalah belum teratasi seluruhnya karena keterbatasan
waktu dan kesempatan penulis dalam melakukan asuhan keperawatan. Selain
itu, riwayat gangguan jiwa yang sudah lebih dari 10 tahun dengan pengobatan
yang belum pernah sembuh menunjukkan keseriusan masalah keperawatan
yang sulit untuk teratasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inayati
(2015) disebutkan bahwa rata-rata lama rawat pada pasien dengan masalah
keperawatan risiko perilaku kekerasan adalah selama 23 hari. Sedangkan
dalam proses asuhan keperawatan ini penulis hanya melakukan selama tiga
hari saja.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Anda mungkin juga menyukai
- Askep Jiwa - FauzanDokumen12 halamanAskep Jiwa - FauzanFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Surat RekomendasiDokumen1 halamanSurat RekomendasiFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Done-RisKep-Fauzan (AFM)Dokumen2 halamanDone-RisKep-Fauzan (AFM)Fauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Tugas Askep II DM Hari Ke-2 (AFM)Dokumen10 halamanTugas Askep II DM Hari Ke-2 (AFM)Fauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Tugas Resume-AfmDokumen8 halamanTugas Resume-AfmFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Tugas Askep II DM Hari Ke-2 (AFM)Dokumen10 halamanTugas Askep II DM Hari Ke-2 (AFM)Fauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Tugas Askep 2 DM (Ahmad Fauzan Muttaqin)Dokumen12 halamanTugas Askep 2 DM (Ahmad Fauzan Muttaqin)Fauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Skripsi FullDokumen205 halamanSkripsi FullFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Revisi - Tugas Askep II DM Hari Ke-1 (AFM)Dokumen9 halamanRevisi - Tugas Askep II DM Hari Ke-1 (AFM)Fauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Pertemuan IDokumen6 halamanPertemuan IFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Soal Kasus Askep Ii DM Pada LansiaDokumen1 halamanSoal Kasus Askep Ii DM Pada LansiaFauzan MuttaqinBelum ada peringkat
- Kasus Keperawatan Keluarga Hari IIDokumen2 halamanKasus Keperawatan Keluarga Hari IIFauzan MuttaqinBelum ada peringkat